|29| Obat Dua Hati
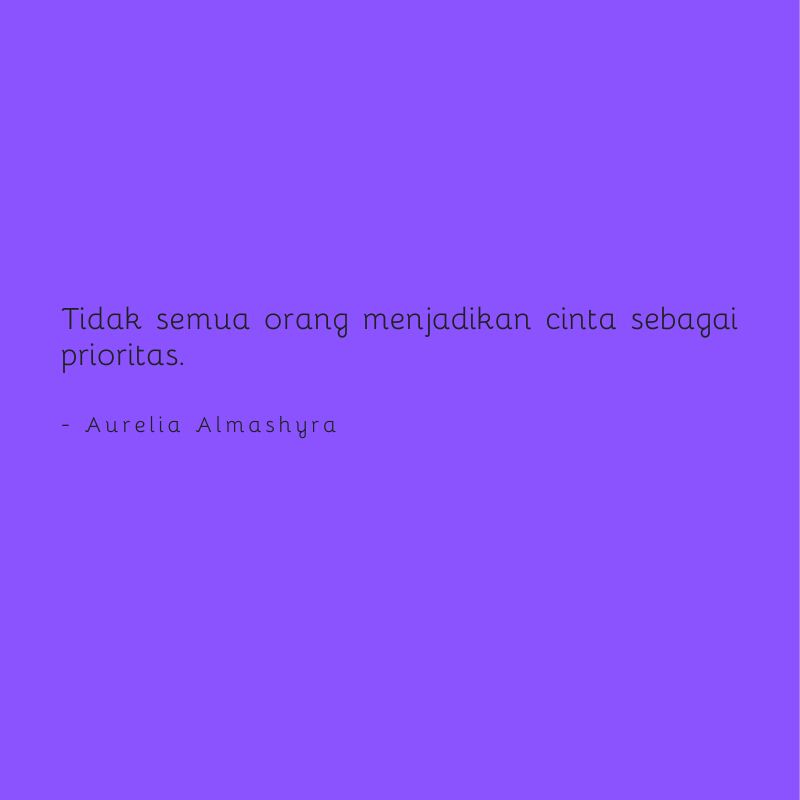
"Jadi pulkam lusa, Sha?"
"Iya, aku udah beli tiket." Kutanggapi pertanyaan Adiba tanpa menoleh ke arahnya.
Sore ini kami sedang membuat es buah guna persiapan takjil. LDK mengadakan buka puasa bersama bagi seluruh organisasi mahasiswa di kampus ini. Salah satu agenda besar selama bulan Ramadan.
"Enak banget yang bisa pulkam." Adiba mendesah pelan.
Aku mendongak, memandangnya sekilas. "Emang kamu nggak pulkam?"
Adiba menggeleng. "Kalau aku pulkam, siapa yang ngurusin agenda selama Ramadan?"
"Ada PJ-nya, kan?"
"Iya, tapi jalur koordinasi Ketum-Kabid Kemuslimahan tetap diperlukan sampai akhir acara. Di kampungku susah jaringan, Sha."
Aku menyengir. Risiko jadi Kabid Kemuslimahan. Rela berlama-lama di kampus, bahkan beberapa mantan Kabid bersedia lebaran di kampung orang demi menjalankan amanah dakwah. Aduh, mana mampu aku seperti itu?
"Melonnya dipotong kotak-kotak, Arisha. Bentuknya dadu, bukan persegi panjang." Aurel menyeletuk tiba-tiba. Aku cemberut ke arahnya.
"Syukurnya keluargaku di kampung mau lebaran di Malang tahun ini."
"Serius?"
"Yap. Kakaku nikah sama orang Malang. Ah, paling kami lebaran di rumah mertuanya."
Aku mengangguk-angguk. "Oh, kakakmu udah nikah? Kok kamu nggak ngundang-ngundang, sih?"
"Kenapa Adiba harus ngundang kita-kita? Yang nikah kakaknya, bukan dia." Aurel lagi-lagi menyahut.
Aku mendelik. Manusia satu ini tidak bisa diajak basa-basi. Tidak mungkin kami bekerja dalam situasi hening, bukan? Apa dia tidak bisa memahami usahaku untuk menghidupkan suasana?
Urusan kepanitiaan proker satu ini memang agak repot. Pasalnya, banyak anggota yang sudah pulang kampung. Sedikit sekali mahasiswa yang mau merayakan lebaran di tanah rantau.
"Kak, barusan aku udah ngecek gelas di lemari. Kurang dari seratus." Salah seorang junior menghampiri kami. Angkatan 2017. Dialah si PJ yang sempat kusinggung tadi.
"Beli lagi, Dek." Adiba menjawab cepat.
Gadis itu menyengir. "Ada yang bisa nemanin, Kak? Aku nggak berani bawa motor sendirian di tempat ramai."
"Rel, kamu bawa motor, kan?" Adiba beralih kepada Aurel. "Tolong kamu yang anter, ya?"
Aurel mengangguk tanpa banyak protes. Dia segera melepaskan pisaunya. Gadis itu bangkit menghampiri si PJ. "Ayo."
"Eh?" PJ mengerjap cepat. "Bareng Kakak?"
"Maumu aku sendiri yang pergi?" sahut Aurel sadis.
Aku geleng-geleng kepala. Tidak bisa membayangkan betapa kikuknya junior kami itu. "Kamu gantiin tugasku, Dek. Biar aku bareng Aurel."
"Eh, makasih, Kak!"
Aku terkekeh. Kami bergantian tugas. Aurel berjalan di sisiku. "Jangan pasang muka horor gitu, Rel. Orang-orang pada takut."
"Dari lahir mukaku udah gini," sahut Aurel acuh. Aku hanya mengedikkan bahu.
Kami berjalan santai menuju parkiran selatan masjid. Aurel diam saja. Aku melangkah sambil memikirkan percakapanku dengan Fauzan tiga hari lalu.
"Rel, gimana pendapatmu tentang nikah muda?" tanyaku penasaran.
"Pertanyaanmu aneh. Nggak jelas. Pendapatku dari sisi mana? Hukumnya kah? Pandanganku tentang orang-orang yang nikah muda kah? Atau yang seperti apa?"
"Aku ganti pertanyaanku. Kamu pengen nikah muda atau nggak?"
Kami saling melirik sekilas. "Aku penganut nikah di waktu yang tepat. Kalau ada yang ngelamar, ya nikah. Kalau enggak, ya udah."
Aku mendengus geli. "Ada gitu orang sesantai kamu ngomongin soal nikah?'
"Jarang, makanya jangan heran kalau bumi semakin banyak dihuni oleh manusia-manusia bucin."
"Ck. Dari jawabanmu, semakin membenarkan dugaanku kalau kamu belum pernah jatuh cinta." Aku menggeleng prihatin. "Aku penasaran, gimana dulu masa-masa sekolahmu, Rel."
Aurel mengedik. Dia berhenti, memandangku. "Lagian, kenapa tiba-tiba bahas nikah?"
"Aku mau cerita, tapi kamu jangan ketawa, ya?"
"Emang aku pernah ketawa dengar ceritamu?"
"Kejam, oi!" seruku sebal.
Aurel menyeringai. "Cerita aja lagi. Tumben banget kamu pakai konfirmasi segala."
Kami melanjutkan perjalanan. Tidak susah menemukan motor Aurel karena parkiran tampak lengang. Aku bergegas naik ke jok belakang.
Di atas motor, melawan desau angin, kuceritakan perihal lamaran. Tak luput rasa kalut kubagi juga padanya.
Aurel tidak menyela. Sesekali, dia hanya menyuruhku mengulang cerita saat bunyi motor mendistraksi suaraku.
Cukup lama kami berkendara, Aurel berhenti di toko plastik. Setelah mendapatkan gelas, kami pun segera kembali ke masjid kampus.
Kami turun di parkiran. Aurel menyuruhku menggotong kresek. Dia memandangku agak lama. "Ceritamu itu ... kisah nyata?"
Aku menekuk muka. "Buat apa aku ngarang, Aurel?"
"Maksudku, laki-laki yang kamu ceritakan benaran punya jalan hidup yang sama dengan kita?"
"Bukan cuma itu. Kata adikku, dia udah jadi musyrif di tempat pengajian. Tim media Organisasi Eksternal tingkat provinsi."
"Bentar, bentar, adikmu ini kok kayaknya tahu banget tentang dia?"
"Adikku keponya nggak ngira-ngira, Rel."
Aurel menyeringai. "Super sekali mantanmu. Aku nggak bakalan heran kalau kamu tiba-tiba kebelet nikah."
Aku membuang muka. Percuma menampik. Aurel tidak akan paham bagaimana rasanya. Dia kan belum pernah jatuh cinta.
"Arisha, perasaanmu itu ngaruh ke dakwah?"
Aku mendesah pelan sembari mengusap wajah. "Jangan ditanya, Rel. Tiga hari ini aku kepikiran terus. Apalagi menjelang tidur, parah. Aku baru bisa nyenyak di atas jam dua belas."
Aaurel menatapku lama. "Sampai segitunya? Emang kamu mikirin apaan?"
Mukaku sontak memerah. Aku membuang muka. "Ya, pokoknya ada, lah."
Aurel berdehem, "Kamu berfantasi aneh-aneh, ya?"
Pipiku panas. "Enak aja!"
Aurel menyeringai. "Saranku masih sama. Bicara dengan orang tuamu. Ajak ngomong baik-baik. Ingat materi awal-awal mentoring dulu, Arisha. Pembahasan tentang kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmani wajib dipenuhi. Kalau enggak terpenuhi, bisa sampai menyebabkan kepunahan. Misal, makan, minum, tidur. Lain cerita dengan naluri. Pemenuhannya nggak mutlak, kalau nggak dipenuhi, paling parah bikin gelisah. Lebih spesifik, kita merujuk ke masalahmu, naluri berkasih-sayang. Penampakannya berupa kecenderungan seksual terhadap lawan jenis. Itu normal, santai aja. Semua orang, apalagi kalau udah dewasa, pasti ngalamin hal serupa."
"Termasuk kamu? Kalau gitu, kenapa kamu nggak pernah jatuh cinta? Selain itu, pandanganmu tentang pernikahan juga kesannya kayak nggak peduli?" kejarku. Aku sungguh-sungguh kepo. Mumpung sedang dibahas, dia tidak akan berkelit.
"Kembali ke konsep kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmani muncul tanpa perlu rangsangan. Contoh, kalau tubuh udah kekurangan energi, ya otomatis perut bakalan lapar. Mau nggak mau harus makan. Beda lagi dengan naluri. Munculnya perlu rangsangan. Nah, kayak kasusmu itu. Udah tahu pacaran haram, masih aja coba-coba. Akibatnya, kalian nggak bisa move on, 'kan? Setelah hijrah, kalian berusaha menaati hukum Islam. Itulah mengapa dia datang ke rumahmu. Kalian sama-sama udah paham kalau nggak ada solusi untuk dua hati yang saling mencintai kecuali pernikahan.
"Sayangnya, Airsha, orang tuamu belum ngizinin. Karena memang, nggak semua orang nganggap naluri berkasih-sayang, khususnya kecenderungan seksual pada lawan jenis, sebagai prioritas utama. Aku contohnya. Karenanya, aku berusaha sekuat mungkin nggak nyari-nyari rangsangan untuk membangkitkan naluri itu tadi. Salah satu upayaku dengan jaga hati. Jauh-jauh dari makhluk berjenis kelamin laki-laki kalau nggak ada urusan penting dan mendesak. Gimana? Jawabanku muasin kekepoanmu?"
Aku mendebas. Ini bukan hanya memenuhi rasa ingin tahu, tetapi berhasil menginjak-injak harga diriku. Kata-kata Aurel terkesan merendahkan orang-orang yang dengan mudah mengumbar cinta pada lawan jenis. Rasa-rasanya, aku hina sekali karena termasuk di dalamnya. Ya, meski tidak dapat kumungkiri, semua itu benar adanya.
Tarik napas, embuskan. "Jadi, menurutmu, apa yang kurasakan salah besar?"
"Udah kubilang, cinta itu fitrah, terstruktur dalam naluri. Benar atau salah, tergantung gimana cara pemenuhannya. Tapi, secara pribadi, aku punya prioritas lain. Banyak mimpi-mimpi yang belum kugapai, ambisi-ambisiku masih harus dikejar. Dan urusan cinta, nggak masuk di dalamnya."
"Terus aku harus gimana?"
"Dibilangin dari tadi, ajak ngomong orang tuamu. Sebentar lagi kan lebaran. Nah, manfaatin momen itu buat bicara. Kalau-kalau ada kesalahan, siapa tahu kamu gengsi buat minta maaf di luar suasana hari raya."
"Kalau mau minta maaf, bisa kapan aja, Rel."
"Itu cuma misalnya, Arisha. Kalau nggak mau diambil, ya udah."
Aku tergelak. Aurel mendengus. Ponselku berdering. Adiba menelpon.
"Kalian di mana?! Lama sekali! Nunggu pesertanya pada datang?"
Mati. Kami keasyikan mengobrol di parkiran. "Buruan, Rel. Bahaya kalau kita diamuk masa."
Aurel menahan lenganku. "Bentar, Arisha. Solusiku tadi belum tuntas. Nah, kalau ternyata orang tuamu tetap nggak setuju, satu-satunya cara kamu harus ikhlas dan sabar. Lupakan aja si Dani-Dani itu."
Aku mendelik. "Mana bisa?"
"Harus bisa. Untuk memenuhi syarat bapakmu, minimal butuh 3 tahun." Aurel mendengus. "Yang benar aja, emang si Dani mau menanti selama itu?"
"Jangan ngehancurin ekspektasi orang dong, Rel," gumamku kesal.
"Realistis aja. Lagian, dibanding sibuk mikirin cara biar orang tuamu ngasih izin nikah pas kuliah, bukannya ada yang lebih mendesak buat dibicarain dengan mereka?"
Aku memandangnya heran.
"Asal-usulmu, Arisha."
Mulutku bungkam dalam sekejap.
Dasar Aurel berlidah tajam, manusia tega, si penghancur ekspektasi. Kenapa kata-katanya sering benar dan menohok?
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top