Chapter 12 [Berlian Melody]
Selamat datang di chapter 12
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena ia begitu tinggi mengangkat jiwa, di mana hukum-hukum kemanusiaan dan kenyataan alam tidak mampu menemukan jejaknya”
—Khalil Gibran
____________________________________________________
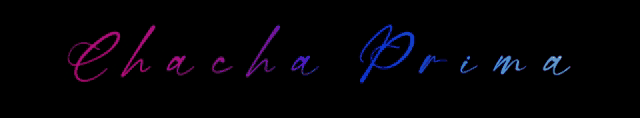
Jakarta, 27 Oktober
Pukul 11.40
“Saya pengin tiga lagi dokter spesialis jantung yang meriksa Papa saya,” lontar Jayden yang membuat seluruh penghuni ruang dokter kepala rumah sakit ini mendelik.
Aku mengerti kekhawatiran Jayden terhadap Papa. Namun, kurasa ini merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Kendati tahu akan sia-sia belaka, tetap saja aku berusaha menggenggam tangan Jayden yang duduk tegang di sebelahku guna mengingatkan, “Baby, kita udah minta empat pendapat dokter spesialis jantung. Semuanya kompak ngomong sama. Jadi, sebaiknya nggak usah. Kita fokus ke Papa aja.”
Sesekali aku melirik ke seluruh dokter yang duduk melingkar memenuhi sofa. Semuanya terlihat terintimidasi oleh suamiku. Banyak di antara mereka yang mengembuskan napas pasrah, juga geleng-geleng dengan murung.
“Terserah. Pokoknya harus ada tiga dokter lagi yang meriksa Papa. Kalau hasilnya sama, aku baru percaya.”
Melalui kata-kata tersebut yang dilemparkan padaku, wajah-wajah keriput para dokter yang menandakan begitu banyak pengalaman seakan-akan tidak dianggap kompeten bagi Jayden. Bila suamiku itu sudah berkehendak, entah bagaimana jadinya hal tersebut harus terlaksana. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tak terkecuali aku—terkadang, tergantung situasi.
Jayden beranjak pergi sambil menarik tanganku agar mengikutinya. Sembari tertatih, aku hanya bisa membungkukkan badan kepada para dokter sebagai tanda permohonan maaf atas tindakan suamiku.
Aku ingin membantah atau marah-marah kepada Jayden karena bertindak seenak jidatnya. Sayangnya, aku belum menemukan tempat atau kondisi yang tepat. Alasan lain yang membuatku menunda meluapkan emosi ialah aku takut Jayden akan bertambah murka.
Jayden itu seram sekali kalau marah. Auranya menggelap dengan wajah lebih mengintimidasi serta lebih menyeramkan berkali-kali lipat. Aku bisa mengatakan itu karena pernah melihatnya marah beberapa kali. Dalam keadaan itu, jangankan menatapnya atau membuka suara, bernapas pun aku tak berani.
Jadi, sehari setelah Jayden menurunkan mandat tersebut, pihak rumah sakit kalang kabut mendatangkan dokter-dokter terbaik di negeri ini untuk memeriksa Papa. Pada kesempatan yang tak diduga-duga, salah satu dokter spesialis jantung bermuka sinis yang menyampaikan kondisi Papa kepadaku—katanya aku lebih bisa diajak ngobrol logis—mengatakan, “Suami Anda ini keterlaluan. Kayak mafia aja main ngancam-ngancam bakal beli rumah sakit ini dan mecat kami kalau nggak nuruti perintahnya.”
“Maaf, Dok. Harap dimaklumi, suami saya baru pertama kali ngalamin hal ini.”
Dokter itu berkata lagi. “Saya heran. Kok, Anda mau dinikahi pria tempramen kayak suami Anda?”
Lagi-lagi, aku hanya bisa memaklumi kata-kata kejam dokter tersebut. Jayden memang bisa membeli rumah sakit ini lalu mewujudkan ancamannya untuk memecat orang-orang paling kompeten di bidangnya itu. Namun, aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Sebisa mungkin, aku akan mencegahnya. Mungkin itu luapan emosi suamiku. Jadi, aku pun akan menganggap angin lewat perkataan dokter tersebut.
Meski Jayden dianggap buruk bagi orang-orang, tetapi bagiku tidak. Bukan karena aku mencintai Jayden dan menurut orang-orang cinta itu buta, tak akan bisa melihat keburukan orang yang dicintainya, melainkan karena banyak bukti akan kebaikan Jayden. Contohnya, Jayden membantu Gibran dan Fani. Jayden juga memberi pekerjaan orang untuk dijadikan bagian keamanan serta staf-staf lain di rumah sakit kado ulang tahunku beberapa waktu lalu. Jayden juga membiayai pendidikan Dokter Fadli sampai lulus. Belum lagi calon wali kota itu—entah bantuan apa yang diberikan Jayden sebab tak pernah ada obrolan lagi soal itu. Mungkin Jayden tidak ingin sesumbar.
Itu baru yang terlihat olehku. Mungkin, masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang dilakukan Jayden tanpa ia perlu mengumbarnya.
Setelah tujuh dokter spesialis jantung yang ditugaskan Jayden memastikan kondisi Papa sudah membaik, Papa diperbolehkan pulang hari ini. Dengan catatan harus tetap memeriksa kesehatan secara berkala.
Sebagai seorang dokter, aku tentu merasa sangat khawatir. Pasalnya, penyakit jantung merupakan suatu penyakit yang penanganannya harus intens, telaten, dan rutin. Dengan obat-obat yang harus diperhatikan betul-betul kontra indikasinya. Terlebih, bila ada penyakit komplikasi. Penanganannya jauh lebih sulit daripada penyakit jantung tanpa komplikasi.
Ini merupakan pertama kalinya Papa mengalami serangan jantung. Bernasib mujur, malam itu Mbak Mar yang menyambut kepulangan Papa dan sopir taksi daring yang baru mengantar Papa pulang mengetahui kondisi Papa. Mereka lantas segera membawa Papa ke rumah sakit terdekat sehingga cepat mendapatkan penanganan dan tidak sampai memerlukan tindakan operasi.
Well, tujuh dokter itu sepakat mendiagnosis penyebab Papa mengalami serangan jantung ialah tekanan darah yang terlampau tinggi secara tiba-tiba dan aktivitas melebihi kapasitas kekuatan tubuh. Di usia yang sudah tidak muda lagi, fleksibilitas pembuluh darah tentu tidak begitu bisa maksimal sehingga rentan terhadap jejas. Terlebih bila itu berkaitan dengan makanan.
Kata Papa, belakang ini beliau mengkonsumsi gule kambing agak berlebihan. Pengolahan daging berlebihan minyak itulah yang berpotensi menaikkan tekanan darah dan juntrungannya ke serangan jantung.

Ketika awan terang menyelimuti Jakarta menunjukkan eksistensinya ditemani matahari yang mulai menyebar sengatan panas, kami tiba di mansion Papa.
Sebenarnya, aku heran dengan keadaanku sebab selalu tidak sempat melihat-lihat lebih saksama mansion bergaya Italia—khas Papa—ini. Aku hanya melewati kaskade di bagian fasad berhalaman luas dengan beberapa pohon palem besar di sekelilingnya tanpa bisa berlama-lama di sana. Padahal, aku ingin sekali sesekali bersantai dengan memberi makan ikan-ikan piaraan Papa di kaskade itu.
Aku juga hanya sempat ke kolam renang untuk acara-acara tertentu dan sarapan, bukan untuk berenang. Lalu ke kamar bermain Jayden. Yakni sebuah ruangan yang penuh mainannya sewaktu kecil. Dan tentu saja, aku lebih sering ke kamar Jayden yang kini menjadi kamar kami.
Ketimbang harus bolak-balik dari apartemen ke sini, Jayden mengusulkan tinggal di sini untuk sementara waktu sampai Papa benar-benar pulih. Kebetulan sekali letak kamar kami di mansion ini berseberangan dengan kamar Papa. Secara otomatis lebih memudahkan kami mengecek kondisi mertuaku itu.
Aku sungguh ingin membawa tubuhku berkeliling mansion. Sepertinya banyak hal menarik di sini. Terutama desainnya yang tidak umum di Indonesia. Atmosfernya pun nyaman. Membuat setiap orang yang kemari betah berlama-lama di sini. Rasanya, aku seolah-olah berpijak di negara Italia.
Papa berbaring di kasur. Dengan gaya ngotot ala orang tua, beliau mengusir Kak Jameka. “Udahlah, Jame. Papa baik-baik aja. Kamu pergi kerja aja sama Tito. Ada Jay sama Mel, Mbak Mar, dan lain-lain yang nungguin Papa.”
Kak Jameka membantah, “Tapi, Pa—”
“Udah beberapa hari kamu nggak masuk kerja gara-gara nungguin Papa. Hari ini juga jam kantor udah kelewat banyak. Heratl butuh kamu, Jame,” potong Papa.
Kak Jameka sontak membuang karbon dioksida secara brutal dan lama. Dengan wajah sangat kentara tidak ikhlas, ia dan Tito akhirnya berpamitan, “Ya udah. Aku berangkat dulu, ya, Pa.”
“Berangkat dulu, Om. Semoga lekas sembuh.”
Sambil membalas jabat tangan mereka, Papa bergumam, “Jame, Jay, Tito, maaf bikin kalian repot ngurus Heratl.”
“Apaan? Orang aku yang nawarin buat bantu-bantu, kok,” gerutu Jayden.
“Udah tugas negara kali, Pa,” gumam Kak Jameka.
Sedangkan Tito merespons, “Nggak apa-apa, Om Alle. Serahin aja ke kami.” Lalu ia mengajak Kak Jameka berangkat ke Heratl. Tinggallah aku dan Jayden yang menemani Papa. Kami pun menggeser sofa agar lebih dekat dengan kasur Papa.
“Ngapain malem-malem pergi sampai pagi buta baru pulang, Pa?” tanya Jayden sengit yang tampak sekali sudah ingin mengeluarkan pertanyaan itu dari kemarin-kemarin.
Suara rendah Jayden bak menjelma menjadi wartawan dadakan. Papa sebagai narasumber yang diwawancarai seolah-olah tidak ingin menunjukkan kepiawaiannya dalam merangkai kata membentuk kalimat jawaban. Malah, Papa tertawa geli lalu menyusun kalimat penyangkalan.
“Lagakmu udah kayak bapak-bapak nyeramahin anaknya yang bandel aja, Jay.” Papa kemudian mencondongkan tubuh ke arahku sambil menowel lenganku. “Kamu lagi isi, ya, Mel? Makanya suamimu jadi ceriwis macem emak-emak nawar cabe yang harganya lagi naik di pasar.”
Mendengar perkataan itu, aku sontak mengudarakan tawa sambil menutupi mulut menggunakan satu tangan. Meskipun sebenarnya jantungku kobat-kabit karena Papa menyinggung-nyinggung tentang kehamilan. Kemudian aku meringis kaku sambil melirik Jayden sebagai isyarat meminta bantuan.
Kalau boleh diutarakan dan seandainya Papa tidak sedang masa penyembuhan, aku ingin membagi pikiran tentang penundaan kehamilanku. Bukan dengan Papa saja, melainkan dengan keluargaku juga. Namun, tak bisa kupungkiri rasa takut seperti siap menyambut dan menenggelamkanku dalam nelangsa.
Bagaimana kalau orang-orang tidak sependapat dan kecewa? Mengingat biasanya keluarga—lebih-lebih para orang tua—selalu berharap cucu dari anak-anak mereka sesegera mungkin.
Teruntuk sementara ini, aku berusaha bersikap tenang dengan mengingat Kak Bella beberapa waktu lalu melahirkan bayi perempuan. Jadi, atensi orang tuaku beralih ke cucu pertama mereka. Tidak merongrongi aku dan Jayden perihal anak.
Yang tak kusangka, hal itu justru disinggung oleh mertuaku.
Aku tentu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, ini rumah tanggaku bersama Jayden. Kami-lah yang berhak menentukan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menikah lalu cepat-cepat mendapat momongan? Namun, bukankah setiap rumah tangga memiliki kisahnya sendiri?
Untungnya, Jayden sigap membaca situasi ini dan kembali mengusik Papa yang masih menunggu jawabku. “Pa, nggak perlu ngomong ngalor-ngidul. Jawab dulu pertanyaanku. Papa ngapain pergi malem-malem dan pulang pagi buta gitu?”
Papa menipiskan bibir lalu mengubahnya menjadi kerucut dan kelihatan mencari posisi ternyaman untuk berbaring. Secara berlebihan, Papa berakting mirip anak kecil merajuk. Fisik yang sungguh bertolak belakang dengan tingkah laku.
“Habisnya, Papa bosen di rumah terus. Daddy sama Maminya Mel sibuk sama cucu baru. Jameka sama kamu kemaren habis ke Kalimantan. Bentar doang jenguk Papa. Papa ngerti, kok. Anak-anak Papa udah pada dewasa dan pada sibuk. Tapi wajar, dong. Kalau Papa mau senang-senang. Kumpul sama temen-temen Papa yang lain sambil makan gule kambing.”
“Yang nggak wajar itu kalau tahu kondisinya lagi drop, tapi maksa keluyuran,” sarkas Jayden, “emang nggak bisa seneng-seneng di rumah aja, Pa? Emangnya nggak bisa pesen makanan selain gule kambing yang aman bagi tensi? Dari rumah, pakai aplikasi? Atau ngajak temen-temen Papa ke rumah aja?”
“Ya nggak serulah! Masa makan sendirian? Lagian kalau manggil temen-temen Papa ke sini, bakalan habis duit banyak. Kita, kan, lagi ekstra berhemat. Nah, kemaren itu gratis. Siapa yang nggak suka gratisan?”
“Papa tinggal bilang aku butuh duit berapa. Nggak usah khawatir soal itu. Aku yang bakal bayarin. Papa traktir temen-temen Papa juga boleh. Asal Papa jaga kesehatan. Toh, aku juga udah setuju Papa nggak mau tinggal sama Jameka atau aku. Aku juga yang biayain listrik dan segala macem mansion ini, kan? Semua ruangan sekarang nggak dipadamin listriknya.”
Papa makin ngedumel, “Lagakmu itu loh, Jay.”
“Aku—”
“Baby, stop, Baby. Kasihan, Papa belum sembuh total. Jangan dicerca kayak gitu,” selaku yang kulafalkan dalam bentuk bisik-bisik sambil menarik-narik lengan Jayden karena merasa suasana di kamar ini sudah tidak kondusif. Kendati sejujurnya aku juga kebingungan.
Jayden memang berkata dengan nada dan wajah datar. Namun, urat-urat yang muncul di pelipisnya sudah cukup membuatku paham bila suamiku sedang marah.
Beberapa bulan belakangan ini Jayden dan Papa baru memperbaiki hubungan setelah perang dingin bertahun-tahun. Aku tidak mau keduanya kembali menjadi asing satu sama lain. Sudah terlalu banyak luka batin yang ditimbun. Sudah terlalu banyak air mata yang mengalir karena kejadian tersebut. Yang pada akhirnya bisa berakhir dengan damai, bahagia, serta tidak ada kecanggungan di antar kedua pria ini. Jadi, sebaiknya tidak perlu ada yang menggali-gali luka lama lagi melalui perkara sekecil apa pun, yang bisa menyulut api masa lalu itu.
“Aku keluar dulu,” gumam Jayden yang lantas berdiri. Aku ingin mengikutinya, tetapi Papa mencegahku.
“Biarin dulu aja, Mel. Lagi emosional. Paling juga ngerokok.”
Mendadak aku digempur dilema; kenapa aku selalu dihadapkan dengan situasi semacam ini? Antara harus tinggal menemani Papa atau mengejar Jayden untuk menenangkannya. Keduanya sama-sama penting bagiku. Keduanya sama-sama harus ditangani dengan cara masing-masing. Dan keduanya sama-sama membuatku khawatir.
Papa perlu seseorang yang menemani, sedangkan Jayden perlu aku untuk menenangkannya—kalau bisa, semoga.
Akhirnya, dengan bimbang aku memilih tinggal untuk menemani Papa lantaran tahu, terkadang Jayden membutuhkan ruang untuk menenangkan diri tanpa gangguan. Ia pria normal. Ibaratnya selalu tinggal di gua apabila menghadapi tekanan berupa masalah. Bila sudah beres, barulah keluar dari persemayamannya itu.
“Maafin Jayden, ya, Pa. Papa tentu tahu maksudnya baik. Karena Jayden sayang Papa. Nggak cuma Jayden, aku juga, semua keluarga juga sayang Papa,” ucapku yang sudah gatal ingin menggigiti kuku. Seperti saat Jayden menginginkan tambahan tiga dokter spesialis jantung untuk menangani Papa.
Papa menolehku. Wajah itu kini murung. “Harusnya, Papa yang minta maaf atas nama Jayden ke kamu. Dia banyak bikin ulah. Papa ngerasa didikan Papa nggak begitu berhasil.”
“Papa jangan gitu, dong. Papa berhasil didik Jayden, Pa. Dia baik. Baik banget malahan.”
Tubuh tua yang masih tegap itu diikutsertakan menghadapku. “Tetep aja, Papa pengin minta maaf ke kamu, Mel. Tolong maafin kalau Jayden bikin salah.”
Jujur saja. Situasi ini menjadi makin aneh dan tak bisa kupahami sama sekali.
“Papa seneng kamu bisa jadi istrinya Jayden. Papa harap, pernikahan kalian bisa bertahan selamanya.”
“I hope so, Pa,” bisikku.
Papa diam dengan tatapan mengarah pada luar jendela kamar yang tirainya disibak. Sehingga cahaya matahari bisa masuk dan mengangkat kemuraman kamar ini. Bibir pucat Papa sedikit bergetar. Beliau seperti larut dalam pikirannya. Beberapa detik kemudian, Papa mengatakan, “Yang namanya berumah tangga itu pasti ada aja masalahnya ya, Mel.”
“Iya, Pa.”
“Kalau misalnya kalian lagi diuji sama masalah, entah itu masalah kecil atau masalah besar, Papa mohon banget sama kamu, Mel. Tetap bertahan sama Jayden,” ucap Papa sungguh-sungguh.
Perasaanku tidak enak lantaran Papa yang tiba-tiba seperti ini. Namun, aku berusaha mengabaikannya dan membalas Papa dengan anggukan. Bagaimanapun, orang sakit perlu ditenangkan agar psikisnya bisa menghasilkan hormon bahagia yang dapat mempengaruhi fisiologi tubuh. Istilahnya pendukung kesembuhan.
Setelah itu, Papa menarik selimut. “Ya udah, nyusul Jay sana, Mel. Papa mau boci.”
“Boci apaan, Pa?”
“Bobok cianglah. Masa gitu aja kamu nggak tahu, Mel.”
Demi Neptunus! Dari pembicaraan serius pangkat dua, aku sontak tertawa lebar. “Astaga, Papa. Ya udah, deh.” Aku pun berdiri. “Sofanya aku biarin di sini dulu, ya? Nggak kuat balikin ke tempatnya sendirian.”
“Iya, biarin situ aja.”
“Makasih, ya, Pa. Selamat istirahat. Cepet sembuh. Kalau perlu sesuatu bilang, ya?”
“Beres.”
Sebelum aku membuka pintu kamar Papa, mertuaku itu berkata, “Kalau lagi ngambek, Jay biasanya ngerokok di kolam. Kalau nggak ada coba cari aja ke ruang teater, Mel.”
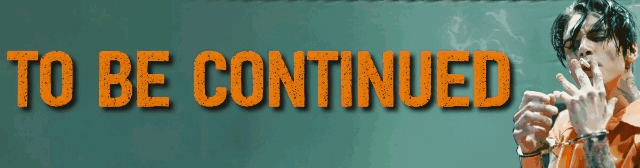
____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto My twin

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©®Chacha Nobili
👻👻👻
Sabtu, 6 Agustus 2022
Repost: Sabtu, 12 Oktober 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top