87. Kita Mengambil Langkah Berani I

Bundang adalah kota terdekat dengan Seoul.
Bundang merupakan salah satu kota terkaya di Korea Selatan. Sulit untuk sekadar membeli sepetak apartemen di sana kecuali kamu pengusaha, pialang saham, atau sebatang ranting yang berasal dari pohon keluarga kaya raya. Menurut koran langganan ayah Mark, harga hunian di Bundang bisa memicu sakit kepala, bahkan menandingi Seoul sendiri yang bangga pada Gangnam-nya. Hal itu karena kota yang dibangun pada tahun 1990-an itu menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari kota kebanyakan. Taman dan ruang hijau di Bundang konon sama umumnya dengan kedai kue beras.
Tapi itu dulu.
Berbagai bayangan tentang Bundang di masa kini berseliweran di kepala Mark keesokan paginya. Perasaannya terbagi dua antara lega dan khawatir ketika semalam semua anggota kelompoknya setuju mengganti Jeju dengan Bundang. Jeno mengaku pernah ke kota itu untuk sebuah turnamen sepak bola, Karina juga pernah mengunjunginya untuk liburan. Namun, tak ada yang benar-benar mengenal tetangga Seoul itu. Akan sangat mudah tersesat di sana. Bundang akan jadi tantangan baru mereka.
Itulah kenapa sejak pagi Mark sudah bersama Jeno di halaman, memilih dua mobil terbaik yang akan mereka tumpangi. Pilihan jatuh pada Mazda merah dan Mitsubishi putih. Kendaraan yang tereliminasi dikuras bensinnya. Mark menyelinap ke dalam saat jelas Jeno bisa mengurus semuanya, menuju kamar Grace, dan mengetuk pintunya. "Boleh aku masuk?"
Ketukan itu sejatinya hanya formalitas. Pintu kamar Grace terbuka. Gadis itu dan Karina sedang memeriksa pakaian sambil cekikikan. Karina melambai padanya. "Mark, sini, aku baru mau ngasih pujian buat selera fashion-mu. Ini BAGUS pakek huruf besar."
"Wah, aku emang layak dipuji, apalagi kalau inget perjuangan dapetinnya."
"Gara-gara kasir nggak ramah itu, ya?"
"Apa?"
"Kasir nggak ramah." Lirikan Karina menunjuk Grace yang segan menjalin kontak mata dengan Mark. "Itu sebutan Grace."
Mark tertawa singkat. "Bener." Lalu dia diam, berdiri canggung, dan dilanda semacam kekosongan yang akan melanda laki-laki mana pun di hadapan dua orang gadis yang salah satunya terang-terangan mengabaikannya.
Butuh setengah menit bagi Karina untuk menyadari adanya kekeliruan. Dia bergegas undur diri. "Aku, em, mendadak haus." Pintu tertutup di belakangnya.
Sepeninggal Karina, Mark bersandar di dinding dan memulai percakapan dengan cara yang payah. "Hai."
Grace menghela napas. "Pagi yang sibuk, Mark? Aku denger kamu dan Jeno ribut dari tadi."
"Kayaknya aku dan Jeno bukan satu-satunya yang sibuk. Kayaknya," Mark sengaja berpaling dari wajah Grace ke pakaian-pakaian di tempat tidur, "Kamu juga sibuk berkemas."
"Pengamatan yang brilian."
Kali ini tawa Mark lebih tulus. "Apa itu artinya kamu udah pertimbangin permintaanku?"
"Mungkin."
"Mungkin?"
Butuh dua kali melipat pakaian sebelum Grace bersedia menjawab. "Kenapa kamu peduli, Mark? Apa untungnya aku tinggal di sini atau nggak?"
"Aku peduli karena aku emang peduli," ujar Mark, sebab bagaimana lagi dia akan mengungkapkannya? Dia takkan pernah menemukan kata-kata yang tepat. "Lagian apa itu penting? Ah, Grace, sejak kapan hubungan kita jadi seburuk ini?"
Pertanyaan itu sepertinya membuat Grace terkesiap, meski dia cepat-cepat mengendalikan diri. "Dulu kita juga nggak akrab."
"Nggak akrab, tapi nggak sampai bermusuhan." Mark membetulkan. "Kamu pernah jadi temen sekelas yang dua kali nyumbang suara buat aku di pemilihan ketua kelas. Kamu juga yang sering jadi partner-ku ngelawan Jinho. Kita sering menang." Dia tidak bisa tidak tersenyum. "Kamu lihat, kita masih bisa mulai semuanya dari awal. Sebelum kekacauan ini, kita udah punya sesuatu di antara kita, Grace."
"Maksud kamu persahabatan?" Semakin Mark berusaha menjelaskan, semakin bingung Grace jadinya.
"Semacam ... Itu."
Grace membuka mulut, hendak mengajukan pertanyaan lain atau keberatan lain atau pertanyaan yang mengandung keberatan, tetapi Jeno mendahului. Dari luar, Jeno memanggil mereka. Grace menutup ritsleting tasnya. Momen itu musnah. "Ayo, kita bakal terlambat. Aku tinggal, Mark. Makasih buat tawaran dan penerimaan kamu."
Mark tidak berkomentar. Diam-diam dia tidak menyetujui ucapan Grace barusan. Menurutnya, waktu mereka masih banyak. Satu-satunya yang terlambat adalah pengakuannya, sehingga kini rasa yang dia miliki terpaksa dipendam selamanya. Seseorang yang lebih berani telah melangkahi Mark. Singkatnya, kamu tidak bisa menempatkan dua orang dalam satu hati yang sama.
Dulu, Mark terlalu pasif, jadi wajar Grace tidak menyadarinya.
Sekarang, dia terlambat bertindak, jadi wajar Grace memberikan mawar kuning* padanya.

Di kursi pengemudi Mazda, Jeno duduk, fokus ke depan, dan berjuang mengatasi panasnya cuaca.
Alat pendingin Mazda itu rusak, jadi Jeno membuka jendela yang justru menggiring hawa yang lebih panas lagi masuk ke kendaraan. Rasanya tidak terlalu buruk一hanya seperti direbus hidup-hidup. Jeno mengusap keringatnya. Teman seperjalanannya, Mark, bagai membangun tembok pemisah di sekelilingnya, jelas lebih suka ditemani pikirannya sendiri ketimbang diajak bercakap-cakap. Renjun menikmati camilan di kursi baris kedua, sedangkan Jaemin diam一mengaktifkan mode menghemat energi. Sisa anggota kelompoknya berkerumun di mobil kedua yang dikendalikan Karina tidak jauh di belakang.
Sama seperti Renjun, Karina mengaku belum lancar mengemudi (mereka ternyata seumuran), dan Sungchan menyarankan agar perjalanan ini Karina manfaatkan untuk latihan. Yah, Jeno berpikir seraya menengok keadaan sekitar, Sungchan benar. Jalanan tampak bagai loteng sebuah rumah yang dikunjungi setahun sekali; berdebu, kotor dan sepi. Mobil mereka adalah satu-satunya yang melintas. Bumi tengah terlelap, atau mungkin muak pada manusia. Telinga Jeno tidak menangkap suara apapun selain desir angin, dengung mesin, dan bunyi ban yang melindas aspal.
Barisan rumah berjajar tak ada habisnya. Ada yang besar, sederhana, dengan teras, dengan balkon, tanpa hiasan atau sangat meriah. Sesekali pemandangan itu disela oleh berbagai macam rambu lalu lintas. "DILARANG PARKIR", kata salah satunya. Yang lain berpesan, "BANYAK TIKUNGAN". Lalu tak berapa lama, muncul papan penunjuk jalan yang dinantikan, "BUNDANG 109 KM", disertai anak panah.
Mereka hampir sampai.

Seratus sembilan kilometer kemudian, Jeno menahan napas ketika mereka resmi memasuki Bundang. Dia merasa seperti baru saja mendengar peluit pertandingan ditiup dan berlari ke gawangnya, meski yang sesungguhnya dia lakukan tak lebih dari menurunkan kecepatan mobil hingga 50 km/jam. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Semuanya kelabu, rusak, berantakan. Namun satu-dua hal memang patut diamati.
Di kursinya, selesai bermuram durja, Mark celingukan. "Nggak banyak bedanya."
Jeno mengangguk, kecewa. Bukannya dia berharap akan disambut bak atlet yang memenangkan medali olimpiade一dia tidak mengharapkan taburan bunga atau hamparan karpet merah一Jeno hanya mengira Bundang akan lebih ... Membesarkan hati, bukannya menekan asa sampai semakin mengecil. Kenyataannya, dan ini menyedihkan, kota ini tidak jauh berbeda dengan kota yang mereka tinggalkan.
Beberapa unit mobil berserakan di bahu atau tengah jalan, seolah ada bayi raksasa yang memainkan lalu melemparkannya sembarangan setelah bosan. Motor dan sepeda lebih memilukan一penyok di sini dan di sana, hanya sedikit yang masih bisa berdiri tegak. Di atas salah satu jok motor, seekor kucing berbaring dengan kedamaian yang ganjil. Cakarnya terkulai. Jeno sempat mengira hewan itu mati. Namun perutnya naik-turun, menandakan dia bernapas dengan baik. Rasa ingin tahu Jeno pun tergugah一apa zombie makan daging hewan?
"Terus jalan," kata Mark, diselipi ketegangan. "Kita lihat apa yang nunggu kita di depan."
Jaemin menggosokkan tangannya seperti seorang dokter yang hendak memulai operasi. "Kalau一dan cuma kalau一ada shelter, lokasinya pasti bukan di tengah kota. Kita harus cari kawasan yang lebih sepi."
Hal itu lebih mudah dikatakan daripada dipraktikkan. Bila Seoul terlelap, maka Bundang praktis jatuh koma. Kota ini diselimuti keheningan yang begitu pekat sampai-sampai menyerupai kabut tebal. Mazda itu kembali terlonjak-lonjak menyusuri jalan. Semua penghuninya membuka mata lebar-lebar. Masing-masing mengantongi pistol yang terisi penuh beserta magasin cadangan. Pisau-pisau, yang bisa membunuh lebih senyap, berada dalam jangkauan.
Mereka melewati plang nama jalan yang tak bisa Jeno baca. Tiang yang menyangga plang itu ambruk dan plangnya tertimbun tumpukan sampah. Ini bukanlah kota yang Jeno kenal, dengan jalanan ramai yang kerap dilintasi mobil mewah dan lapangan yang rumput hijau zamrudnya terasa mantap saat dipijak. Ketika matanya tak sengaja tertumbuk pada bola kecil dari kain一bola balita一yang tergeletak di halaman rumah seseorang, Jeno tidak mau lagi membayangkan kondisi lapangan tempat dia dan timnya pernah memetik kemenangan telak.
Dalam setengah menit, Jeno sadar kunjungan sekali selama dua minggu ke sebuah kota tidak memberinya informasi yang cukup. Dia tidak menemui apapun yang akrab baginya, entah karena dia masuk melalui sisi kota yang salah atau yang lebih mungkin, dia lupa. Lagipula, di bus waktu itu, dia tertidur dan seandainya memiliki waktu luang, dia menghabiskannya dengan latihan tambahan. Jeno berakhir mengambil belokan secara acak.
Belokan itu menuntunnya ke sebuah rumah ibadah yang terabaikan, yang keadaannya bisa dimaklumi. Hari ketika segalanya berubah tidak terkendali adalah hari kerja, Jeno sangsi ada yang mau repot-repot mengunjunginya. Kantor, mall, dan berbagai tempat rekreasi lain pastilah lebih ramai. Seperti yang pernah Jeno baca di suatu buku: kita beriman saat sedang susah, dan menjadi ateis saat sedang senang.
Mazda itu belum lagi bergulir cukup jauh dari rumah ibadah tersebut manakala Jeno merasakan kecepatannya melambat. Dia bingung. Mobil yang telah dia periksa dengan seksama itu semestinya tidak bermasalah. Namun ketidakstabilannya mengkhawatirkan, dan dia dengan berat hati mengerem di pinggir jalan. "Semuanya turun. Ada yang salah sama mobil ini."
Mitsubishi ikut-ikutan berhenti sementara mereka mengerumuni kap mobil dan Jeno membukanya, menduga akan disembur asap tebal yang mengepul dari sana. Mobil yang mogok bisa dipicu berbagai hal; filter bahan bakar tersumbat, aki rusak, alternator yang performanya tidak optimal. Macam-macam. Yang mengherankan, dari pengamatan sekilas, Mazda itu baik-baik saja. Tidak ada asap, baut yang lepas, atau komponen yang salah tempat. Kerutan terbentuk di dahi Jeno. "Aneh."
"Kenapa?" tanya Haechan. Dia turut keluar dengan ekspresi sembunyi-sembunyi yang menyatakan setiap langkah merupakan siksaan baginya. Jeno menjelaskan duduk perkaranya dan Haechan menyimak. "Masalahnya bukan di mesinnya."
Suara Jeno memancarkan keraguan. "Dari mana kamu tahu?"
"Karena aku bisa lihat bannya dari sini dan ban itu penuh paku."
"Astaga." Bodohnya, Jeno tidak memeriksanya. Dia berjongkok dan memverifikasi kebenaran kalimat Haechan. Hasilnya, ban Mazda itu tertusuk begitu banyak paku bagai kulit durian. Ukurannya bervariasi dari paku kayu biasa hingga paku payung. Kehadiran paku-paku itu mengakibatkan mobil bekerja lebih keras, efek udara yang terbuang percuma. Parahnya, keempat ban tidak ada yang selamat.
Sungchan terperangah. "Apa-apaan ini?"
Karina mendekat membawa kabar buruk lainnya. "Mitsubishi juga kena."
Mark menoleh ke rute yang tadi mereka ambil. "Mobil-mobil ini nggak akan bertahan lama kan?"
"Kita perlu ganti kendaraan." Jeno sepakat. "Kerusakannya terlalu luas, dan kita nggak punya tire sealant."
Terjebak di antara pilihan sejenak menepi atau melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang tidak pasti, orang-orang yang mengenal Mark tahu apa keputusannya sebelum keputusan itu diumumkan. "Kalau gitu kita istirahat dulu semalam, sekalian makan. Tapi aku mau langsung cari kendaraan baru buat jaga-jaga."
"Rumah itu?" Grace memberi isyarat ke sebuah rumah yang tampilan luarnya mengungguli rumah-rumah mereka sebelumnya. Bergaya, luas, dan tersusun dari balok-balok kayu berkualitas yang menegaskan pemiliknya tidak memusingkan soal anggaran.
Mark tak menemukan alasan untuk tidak menyukai pilihannya. "Aku setuju." Anggota kelompoknya masuk ke rumah setelah yakin rumah itu bebas dari ancaman. Mark menganggapnya pertanda bagus karena sejauh ini mereka tak dihambat rintangan yang berat, lalu dia menghadap Jeno yang masih saja berjongkok, raut wajahnya heran. "Lupain aja."
"Pertanyaannya, kenapa? Buat apa?"
"Pertanyaan yang lebih penting adalah, di mana kita bisa dapet penggantinya?"
Ajakan tidak langsung itu membuat Jeno bangkit dan mengelap tangannya yang berupaya mencabut paku-paku itu ke celananya. "Kita jalan kaki?"
"Ya, biar mereka pindahin barang-barang di bagasi ke rumah."
Jeno tidak membantah. Kakinya yang pegal menginjak pedal gas bereaksi positif merespons usulan Mark. Keduanya berjalan ke utara menyusuri jalanan Bundang yang sempit dan kehilangan pesonanya, lebih lama dari yang direncanakan. Namun, sinar matahari menyuntik mereka dengan keberanian sembrono dan ilusi一bahwa tak apa-apa melanjutkan perburuan selama belum gelap.
Paling sedikit, mereka butuh dua mobil berkapasitas 5-6 penumpang. Sewaktu Jeno melihat Audi RS6 abu-abu yang teronggok tanpa penghuni, dia mengira tugas mereka berkurang setengahnya. Jeno berniat mencari kunci Audi itu saat Mark menggeleng. "Bannya."
Kerutan di dahi Jeno bertambah dalam. "Ini makin aneh." Ban Audi itu juga dipenuhi paku! Sesuatu mengusik benak Jeno laksana petir di siang bolong. Sesuatu yang berbisik bahwa tiga mobil yang dihiasi paku di area yang sama itu mencurigakan. Ini mengingatkannya pada kenangan yang telah berlalu ... Entah apa, Jeno lupa.
Mata Mark menyipit. "Kita coba jalan beberapa meter lagi, ayo."
Kecurigaan Jeno berperang melawan rasa penasarannya. Bagaimanapun, dia adalah kiper yang tidak sebatas menangkap, tapi terkadang ingin menendang bola terlepas dari apakah bola itu akan mendarat di kaki lawan atau kawan. Rasa penasarannya menang. Beberapa meter kemudian, mereka menjumpai pemandangan yang lebih aneh: dua mobil ditata berdampingan, dalam posisi horizontal, menutupi jalan. Mark dan Jeno saling tatap. Jeno yang lebih dulu bicara. "Bukan kebetulan." Mark mengangguk. Penataan mobil-mobil ini terlalu rapi. Seseorang sengaja mengaturnya agar menjadi penghalang dari ... Dari apa tepatnya?
Mark tersenyum masam. "Kalau ini shelter, tempatnya lumayan sepi."
"Kalau ini shelter," Jeno menirukannya, "Apa orang-orang yang tinggal di situ yang nebar paku di jalan?"
"Kita nggak akan tahu kecuali nanya atau ngintip kegiatan mereka."
"Bener." Jeno sudah melompati celah di bagian belakang salah satu mobil itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Lompatan itu bukan masalah baginya.
Menyaksikan Jeno ada di seberang, Mark membuntutinya semata-mata karena terpengaruh. Mirip saat temanmu bercerita roti merek A enak dan kamu tertarik membelinya. Dalam hitungan detik, Mark bergabung dengan Jeno. Mereka melangkah pelan-pelan, mencari tanda-tanda manusia hidup yang akan bersikap lebih ramah dari Aru. Sekali, mereka bengong mengamati seutas tali jemuran yang digantungi sehelai selimut dan beberapa potong pakaian. Semuanya belum dilapisi debu. Samar-samar tercium aroma pewangi yang belum memudar. Benar-benar ada manusia di sini, belum lama ini.
Mark menghitung cepat dalam hati. "Kalau satu orang cuma pakai dua pasang pakaian minus cardigan atau sweter, berarti seenggaknya ada 14 orang di sini."
"Dan bayi." Jeno menunjuk secarik pakaian kecil yang Mark sangka serbet makan atau lap piring. Jeno bergidik ngeri. "Ada bayi yang lahir di zaman kayak gini."
"Tapi di mana mereka?"
"Mungkin kita terlambat kenalan?"
"Kita sisir dulu daerah ini, nyari petunjuk tentang mereka atau makanan, senjata, dan lebih baik lagi, kendaraan peninggalan mereka." Mark menyarankan, memutar tumitnya, dan mendadak jatuh terduduk di atas lapisan semen yang padat. Terlampau asyik meneliti, dia menginjak kaleng soda kosong yang sontak berguling ke balik sebuah bangunan. Jeno melihatnya, membelalakkan mata, lantas melakukan apa yang akan dilakukan seorang sahabat一menertawakan Mark, sebelum menolongnya.
"Siku aman?"
Dengusan Mark meningkatkan kegaduhan. "Nggak patah. Cuma nyaris一"
Sesuatu menggelinding lemah beberapa meter di depan mereka.
Dari sudut bangunan yang sama.
Kaleng soda yang sama.
Celotehan Mark terpotong otomatis. Deretan pakaian terlupakan. Ada sesuatu yang menggesek-gesek aspal, seperti orang yang menyeret kakinya alih-alih berjalan secara wajar. Tubuh Mark berubah sekaku papan. Ketika sesuatu itu mewujud, mula-mula dia tidak dapat bergerak.
Yang pertama mereka lihat adalah seorang gadis cilik yang rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Mark dan Jeno bergeming. Menyaksikan seorang anak kecil berkeliaran di "zaman kayak gini" akan terkesan ... Janggal. Sedangkan anak itu, dari jarak sekian meter, justru tampak normal. Gabungan rambut dan bayangan gedung一toko perkakas?一mengaburkannya dengan sempurna. Lalu gadis itu keluar dari naungan bayang-bayang, mendongak, dan segalanya berubah. Gadis itu mendesis dengan cara yang tidak manusiawi. Sekonyong-konyong, ada lebih banyak orang yang menyusul. Mereka berbondong-bondong datang dalam jumlah besar. Sepuluh, lima belas, dua puluh ... Mark kehilangan hitungan!
Jeno mengulurkan tangan dan menarik Mark berdiri. "Kita beneran terlambat, Mark-hyung. Ayo pergi."
Mark tak perlu disuruh dua kali. Dengan memegangi sikunya yang nyeri, dia tersandung-sandung mengekori Jeno. Jeno, yang lebih atletis, gantian memimpin, kali ini tanpa kehati-hatian dan aksi pamer ketangkasan, tetapi masih mampu melompati celah di tengah-tengah antara dua mobil penghalang yang dianggapnya lebih lebar. Kesalahan fatal! Begitu jemari Jeno bertumpu di masing-masing kap, alarm mobil-mobil itu langsung meraung lantang!
Pintu rumah terdekat roboh, memuntahkan zombie lain yang mengepung mereka dari dua sisi.
Insting memerintahkan Jeno mencabut pistolnya dan itulah yang dia perbuat. Namun dia tahu tindakan itu hanya satu anak tangga di bawah sia-sia. Pistol dan magasinnya disiapkan untuk membereskan selusin, dua lusin zombie, bukan puluhan yang mendekati ratusan! Mark menepuk pundaknya, menuding ke kanan. "Sana!"
Mereka berlari, sementara alarm masih menjerit-jerit, mengabarkan posisi mereka pada telinga-telinga orang mati. Menyebarkan undangan makan siang dengan mereka sebagai menu utamanya. Sayangnya, perut kosong keduanya enggan bekerja sama dan tak lama, mereka tersengal-sengal kehabisan napas. Akhirnya, akhirnya Jeno tahu paku-paku itu mengingatkannya pada apa; tak lain dan tak bukan peliharaan Aru. Baik paku dan para peliharaan itu punya fungsi yang sama, yakni menyingkirkan orang-orang. Penghuni shelter itu pasti merupakan pelaku yang menebar paku, dan sama pastinya, usaha mereka gagal sebab kini mereka bergentayangan berburu daging mentah.
Mark di sebelahnya mengayunkan tungkainya dengan susah payah. Dia tidak ingin berhemat. Setiap kali seorang zombie menyebrangi jarak aman, dia akan melumpuhkannya dengan tembakan jitu ke kepala. Satu-dua tumbang, puluhan lainnya setia mengejar. Mark benci ini一kecerobohannya, angan-angan tentang shelter yang sirna, serta bagaimana dia dipaksa memerankan tokoh mangsa. Kemarahan mengalir di pembuluh darahnya. Tidak. Dia tidak jauh-jauh ke Bundang demi jadi kudapan mayat. Tidak sekarang. Tidak nanti. Mark menggertakkan gigi dan berlari lebih kencang.
Tanpa pikir panjang, dia menyambar peluang apapun yang tersedia. Saat dilihatnya sebuah gang sempit yang menguarkan bau busuk sampah, dia lekas mengajak Jeno memasukinya. Mereka berbelok ke gang itu bersama-sama. Jeno menendang sebuah tong sampah yang sukses menghantam kaki beberapa zombie. Itu tidak cukup. Mereka masih harus berlari. Keduanya lelah, lapar, dan haus. Namun ngotot meneruskan. Seandainya bisa, mereka akan terus berlari, kalau bukan karena keberadaan tembok dari batu bata yang menjulang tinggi, kokoh, dan menghalangi mereka beranjak. Mereka terjebak.
Mark menyerukan rentetan sumpah serapah dalam bahasa ibunya. "Setelah semua yang kita alami, apa kita bakal berakhir semengenaskan ini?"
Terulang lagi. Jeno meninju tembok itu seperti dia meninju pintu salah satu ruang kelas yang ditutup gurunya. "Sialan ...."
"Nggak ada gunanya."
Jeno menggeleng dan menggeleng. "Aku lebih baik mati daripada jadi kayak mereka. Aku manusia." Dia menelan ludah, teringat seorang gadis yang tewas di halaman Arena. "Aku manusia."
"Tolong, aku mohon, bantu aku supaya meninggal sebagai manusia."
Lantas, siapa yang akan membantunya sekarang?
Mark tertawa muram一jenis tawa ketika kamu tahu tak ada lagi yang bisa dilakukan. "Mati di gang kotor begini. Itu sesuatu yang nggak pernah aku bayangin."
Bahu Jeno merosot turun. "Tapi nggak tanpa perlawanan." Saat itu pun, meski tampangnya diselimuti awan mendung, dia mengangkat pistolnya, melanjutkan pertarungan yang dia mulai. Setengah lusin zombie menyerbu sekaligus. Jeno menembak. Jantungnya berdentam-dentam di balik tulang rusuknya. Kulitnya bergelenyar. Dia seperti bisa merasakan gigitan pertama, cakaran yang merobek dadanya ... Dia bertanya-tanya apa yang akan tersisa darinya usai gigitan dan cakaran dari zombie sebanyak itu?
Bahkan dengan dibantu Mark, Glock Jeno tidak bertahan lama. Dalam jeda semenit, Jeno merogoh sakunya mencari magasin cadangan. Tangannya gemetar hebat sehingga magasin itu meluncur ke kakinya. Yang terakhir. Tak satu pun dari Mark dan Jeno sudi mengakuinya, tetapi dia tahu, setelah magasin ini habis, maka habis pula harapan hidup mereka. Beranikah dia menekankan moncong pistol ke kepalanya sendiri? Beranikah?
Jeno berlutut meraihnya一dan tidak bangun lagi. Sebuah suara yang memancarkan otoritas dari luar gang memperingatkan mereka dengan ketegasan yang memaksa siapa saja yang mendengar agar mematuhinya.
"Tiarap, tiarap!"
Ledakan keras mengguncang tempat itu sejurus kemudian, diikuti api yang menjilat tong sampah dan menerbangkannya semeter ke udara. Tong sampah itu hancur, puing-puingnya yang terbuat dari plastik menghujani Mark dan Jeno yang berusaha melindungi kepala dan leher mereka sebisanya. Gelombang besar api menyapu para zombie yang berkerumun di mulut gang dari samping. Pakaian mereka menguap一tak ada cara lain menggambarkannya. Panasnya api bukanlah tandingan kain, begitu pula daging.

Tubuh-tubuh zombie memang tidak kontan lenyap, tapi dahsyatnya ledakan mencabik-cabik mereka layaknya hewan yang termutilasi di rumah jagal. Kaki melayang. Kepala terpenggal. Siku rantas. Segera saja, tanah dipenuhi potongan-potongan tubuh dari puluhan zombie yang mustahil disatukan kembali, bahkan meski seseorang berkonsentrasi seharian. Semuanya menghitam一seperti arang, seperti apa yang dibayangkan banyak orang sebagai warna kematian. Udara diracuni bau sangit daging yang terbakar. Api yang menyala menyumbang asap hitam yang menyesakkan pernapasan.
Jeno batuk-batuk, menyeka matanya yang berair. Karena tidak menunduk cukup sigap, pipinya kini dihiasi jelaga. "Apa itu tadi?"
Mark menyiasati situasi itu dengan bernapas lambat-lambat. "Granat, ya?"
"Bisa jadi. Ledakannya terlalu一"
"Mana bocah-bocah itu? Apa mereka betah di gang?" Suara seorang laki-laki, yang aksennya sulit dikenali, menimpali. Bukan suara yang sama yang menyuruh mereka tiarap.
Mark menggapai pistolnya tanpa niat menyembunyikan benda itu. Dia melangkah keluar dari gang dengan ketenangan yang tidak dia rasakan, sembari berhati-hati supaya tidak menginjak bagian tubuh siapapun yang tercecer di tanah. Seorang zombie, yang batok kepalanya masih utuh menggeliat ingin merenggut betisnya. Mark mundur, tepat waktu untuk mengindari sebilah belati yang ujungnya menembus kepala zombie itu dan seketika membunuhnya.
"Kalian nggak apa-apa?" tanya seorang perempuan, menggenggam belati kedua. "Ada yang luka?"
Laki-laki di sebelahnya tidak menunggu jawaban; dia mengobservasi Mark dan Jeno dengan tatapan menyeluruh dan tajam. Di bahunya, terdapat sebuah benda berbentuk tabung nan panjang yang tampaknya berat tetapi dipanggul laki-laki itu seolah tak lebih dari sehelai handuk. "Mereka jelas nggak apa-apa."
"Apa ... Itu?" Rasa penasaran Jeno tak terbendung.
Laki-laki bermata tajam itu paham. "Rocket launcher." Lalu dia menuntut timbal balik. "Giliran saya, apa yang kalian lakuin sampai jadi idola yang yang dikejar-kejar zombie?"
Rekannya, laki-laki yang aksennya unik itu, tergelak. Dia berambut panjang untuk ukuran laki-laki, yang diikat longgar. Tidak setinggi si pemegang rocket launcher dan tidak mengenakan kaus yang sama一sebuah kaus hitam lengan pendek yang di atas jantung bertuliskan "R.O.K.A". Republic of Korea Army. Sebaliknya, laki-laki itu memakai kaus biasa dilengkapi jaket lusuh yang bisa tampak bagus di badannya. Dibanding tentara, dia lebih mirip sindikat geng motor atau anggota mafia.
Mark hendak menjawab, tetapi dia tidak punya kesempatan. Sebuah mobil Mitsubishi yang dipaksa bekerja menepi beberapa langkah dari Mark. Sungchan yang menyetir. Satu per satu anggota kelompoknya meluber ke jalanan, mengibaskan udara di depan hidung atau memicingkan mata. Semua, kecuali Haechan, yang acuh tak acuh dan memandang rocket launcher dan senjata si tentara seperti seorang balita memandang semangkuk gula-gula. "MP-7 ...."
Seaaat tak ada yang menyahut. Mereka yang baru datang menyelisik kekacauan itu dan sadar hal yang lebih buruk baru saja dibatalkan. Namun memelototi mayat zombie dan wajah Mark dan Jeno yang kotor tidak cukup memberi penjelasan. Renjun berinisiatif memintanya. "Ada yang mau ngasih tahu aku apa yang terjadi?"
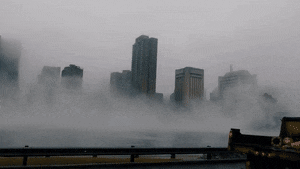
*Mawar kuning dalam bahasa bunga artinya persahabatan
Ini udah panjang banget ya, buat kompensasi update yang lama, jadi dilarang protes. Mending tebak2 aja, siapa 3 orang yang bantuin Mark sama Jeno? Yang bener kagak dapet hadiah ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top