68. Kita Merubahnya

34 JAM TANPA AIR
Jung Sungchan tertidur lagi.
Kini, tidur bukanlah kegiatan yang dia kerjakan semata-mata demi kebutuhan jasmani, melainkan metode melarikan diri yang dia nilai paling efektif. Dengan tidur, Sungchan akan lupa一pada kemalangan nasibnya, darah temannya yang tumpah, dan keluarga yang hilang. Hanya dalam mimpi lah dia aman, tempat segalanya menjadi mungkin, tak terkecuali angan-angan yang sejatinya sia-sia. Di menit-menit akhir sebelum dia pulas, Sungchan berdoa seluruh kekacauan ini akan menemukan jalannya kembali ke keadaan normal, namun dia selalu bangun mendapati Tuhan belum mengabulkan doanya.
Menurut perkiraan Sungchan, paling tidak satu setengah hari sudah terlewati, gejala dehidrasinya semakin menjadi-jadi. Dia tak lagi ingin buang air, kadar air di tubuhnya pasti menyusut drastis. Akibatnya, ginjal dipaksa bekerja keras, menghentikan sebagian tugasnya membersihkan aliran darah. Kulit kering dan mual adalah dua dari beberapa efek sampingnya. Lalu pada jam-jam berikutnya, tubuh akan lebih gencar memprotes, memohon air, air, air, agar bisa tetap berfungsi dengan baik.
Sambil menggigit bibir, Sungchan menyentuh kepalanya yang pening. Dia tak percaya berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk duduk dan menggapai kotak jus, tapi jusnya telah habis.
Patah semangat, dia melempar kotak tersebut sembarangan. Kemampuannya sebagai point guard membuat benda itu melayang terlalu jauh dan mengenai Karina, lantas menuruni punggungnya seperti perosotan. Gadis itu tidak menanggapi. Sesuatu yang terjadi pada Haechan mengambil alih fokusnya.
"Kenapa dia?"
Karina menatapnya dengan air mata menggenang. "Haechan. Dia nyaris nggak napas."
Sekujur tubuh Sungchan kontan membeku ketakutan. Dia mendongak pada Grace, namun Grace berdiri dua langkah darinya, bersandar santai tanpa memperlihatkan kepedulian. "Kamu yakin? Mungkin dia cuma ... Napas terlalu pelan."
"Ya, aku一" Karina berhenti sejenak dan menyeka pipinya. Dia menempatkan jarinya di bawah hidung Haechan selama beberapa detik, lalu ketika tak ada hasil, beralih memposisikan telinganya di dada pemuda itu. "Aku udah coba ngasih napas buatan. Berguna atau nggak, pokoknya aku harus ngelakuin sesuatu."
Haechan terkapar di lantai, diam tanpa pergerakan. Lehernya terkulai miring, seolah melambangkan peluang hidupnya yang menipis. Tepi-tepi luka di kakinya membengkak, sekarang tidak sekadar mengeluarkan darah. Kulitnya begitu pucat tak ubahnya selembar kertas yang gampang terbakar. Kemudian lenyap. Bibirnya, Sungchan perhatikan, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda dia bernapas.
"Karina?"
Karina, yang biasanya bersikap tenang, yang di Hari Itu menggandeng Giselle erat-erat tanpa menoleh ke belakang pada kumpulan monster yang mengejarnya, kini tak dapat menyembunyikan kepanikannya. "Haechan? Ayolah, Haechan."
Haechan belum sadar juga.
Bosan jadi penonton, Sungchan meraih pergelangan tangan Haechan. Dua jarinya, telunjuk dan tengah, diletakkan di jalur yang dia duga sudah benar. Jalur yang dilintasi pembuluh darah arteri, supaya dia bisa mengecek denyut nadi. Sungchan menekan dalam-dalam, sembari berupaya mengingat-ingat, berapa jumlah denyut nadi yang wajar bagi remaja menjelang dewasa?
"Biarin dia." Sebuah suara dingin menimpali, serak dan parau, barangkali karena dia terlalu lama bernyanyi.
"Kamu gila, ya?" Balas Karina. "Kamu mau Haechan meninggal?"
"Aku mau Haechan istirahat."
"Meninggal bukan solusinya."
Grace mengeluarkan tawa kasar yang lebih mirip jeritan. "Lebih baik daripada dia menderita."
Fokus pada tugasnya, Sungchan tidak tertarik meladeni mereka. Dia masih belum merasakan apa-apa, yang berarti entah jantung Haechan sudah berhenti berdetak atau dia salah menjalankan prosedurnya. Bagaimana? Bagaimana cara yang benar? Sungchan memindah-mindahkan jemarinya. Seandainya saja dia lebih menaruh perhatian di pelajaran olahraga!
"Mereka selalu pergi," ujar Grace lagi. Kata-katanya tersendat-sendat, mengindikasikan dia menangis. "Ayahku, sahabatku, Haechan." Di kata terakhir dia kehilangan pijakan dan terisak. "Aku ini kayak virus, jadi semua orang pergi ninggalin aku."
Itu dia! Ada. Sungchan yakin tadi dia mendeteksi denyut tersamar, hampir tidak kentara. Sangat pelan, sangat lambat一denyut nadi orang yang sekarat, namun setidaknya belum meninggal. Dia menekan lebih keras, dan dalam benaknya, memulai perhitungan. Tiga, empat, tujuh, sembilan...
"Seharusnya aku nggak bikin janji konyol itu ke Haechan. Itu janji yang nggak bisa aku tepati. Aku bukan dia. Aku b-bukan orang yang kuat."
Karina tiba-tiba bangkit dari duduknya. "Grace, mau apa kamu sama pistol itu?"
Suara pistol yang dikokang menyebar ibarat riak air di gudang.
"Turunin pistolnya!" Karina berteriak, lupa bahwa keberadaan pistol itu mestinya dirahasiakan, lupa bahwa walaupun sempit, gudang itu tidak kedap suara. "Jangan nekat. Ini bukan akhir, Grace. Selalu ada harapan."
Grace mundur, menepis baik tangan Karina atau kalimat motivasinya. "Apa gunanya nunda-nunda kematian?"
Bagai ilusi, dada Haechan mengembang lagi perlahan-lahan. Bagai keajaiban. Bagai sinar matahari pertama setelah musim dingin berkepanjangan.
Putus asa, Sungchan mengambil kotak jus Karina dan terkejut sebab kotak itu masih menyimpan beberapa tetes cairan. Dia segera merobeknya. Diangkatnya kepala Haechan lalu menuangkan sedikit demi sedikit jus itu ke bibirnya yang terbuka. Tidak ada reaksi. Sungchan menuang lebih banyak. "Minum!"
Seakan mendengarnya, Haechan menelan dengan susah payah.
Kabut tersingkap. Sungchan tersenyum, tak pernah merasa terlalu gembira untuk orang lain一dia bukan kepiting*. Meski bukan dia yang minum, sukacitanya murni dan tulus. "Grace, lihat."
Namun saat Sungchan berpaling, Grace mengangkat Glock setinggi kepala dan membidik dahinya sendiri.

Park Jisung kira dia tidak akan pernah bisa memandang jaket kulit dengan cara yang sama lagi.
Jaket hanyalah jaket, namun pasca temannya terbunuh oleh orang yang mengenakan jaket kulit yang juga dikenakannya sekarang, Jisung gagal mencegah dirinya mengernyit jijik. Bagaimana mungkin pria itu tertawa tanpa beban? Apa setelah mengambil nyawa seseorang dia melupakan mereka seperti barang bekas? Menganggap dirinya Tuhan, leluasa datang lalu membantai. Tak sadarkah dia tangannya kotor oleh noda darah yang selamanya takkan pudar?
Dasar iblis. Dada Jisung terasa sesak, riuh oleh ledakan amarah. Iblis yang terburuk一semua anggota kelompok Aru begitu. Yang bisa mereka lakukan hanya menebar teror ke tempat mana pun yang mereka tuju. Bajingan busuk! Berada sedekat ini dengan salah satunya, mendengar tawanya, membangkitkan sesuatu dalam diri Jisung yang dia pikir tidak dia punya; hasrat membalas dendam, untuk menyaksikan dan menimbulkan penderitaan.
Hasrat itu mendorongnya maju, menghalau rasa takutnya menjauh. Tangan-tangan tak kasat mata menekan punggungnya agar keluar dari tempat persembunyian, tapi Jaemin lebih sigap, dan dia menarik Jisung kembali dengan cara yang sama orang lain menangkap hewan buas. "Tenang. Berkorban bukan berarti kamu harus jadi korban."
"Itu dia," bisik Jisung rendah. "Itu orangnya. Dia yang bunuh Chenle."
Jaemin mengangguk. "Ya, aku inget dia, juga kemampuan menembaknya yang patut bikin kita waspada."
Seolah mendapat isyarat, si jaket kulit meletakkan senjatanya di atas atap mobil. Dia, bersama dua temannya, membetulkan posisi kotak-kotak kardus dan kantong plastik yang bertebaran tak teratur di kursi belakang. Sesekali mereka bergurau, rileks dan nyaman. Rasa aman yang melingkupi mereka barangkali ada hubungannya dengan senjata yang mereka bawa. Jisung mengenali Revolver dari film-film aksi yang dia tonton di rumah, berkat bentuk tabungnya yang khas. Kecuali si jaket kulit. Senjata miliknya adalah yang paling besar. Paling mengancam. Berbahaya.
Tatapan Jaemin turun ke pisaunya, benda tajam tipis yang berguna dalam pertarungan jarak dekat. Bila bersikeras menyerang mengandalkannya, kemungkinan mereka akan tewas dengan cepat. "Oke, jelas kita nggak bisa ngasih kejutan. Terlalu berisiko."
"Kalau gitu kita buntuti mereka? Kita harus tahu di mana mereka tinggal."
"Itu bakal jadi masalah lain."
"Apa?"
"Kamu nggak lihat fuel meter-nya?" Kalimat Jaemin meruntuhkan rumah kaca harapan Jisung dengan sebuah bola besi. "Bensin Subaru hampir habis. Mobil itu mustahil bertahan lebih dari lima blok."
"Habis?"
Saat itu, anak buah Aru menurunkan sebuah kardus tertentu. Mereka melepas segelnya, bersorak-sorai liar ketika meraih ke dalam dan mengeluarkan kaleng-kaleng bir murahan. Jaemin dan Jisung bisa saja berdiri di gang sempit itu seharian, mereka tidak akan memergoki keduanya. Mereka asyik beristirahat, merayakan kemenangan terlalu awal. Si jaket kulit menyesap kalengnya, mendesah puas pada tegukan pertama. Sementara Jisung setiap saat memikirkan kakaknya, di sinilah dia一mabuk kebahagiaan.
Tidak. Jisung menggeleng kuat-kuat. Tidak. Tak ada apapun di dunia ini seperti mobil yang kekurangan bensin yang boleh menghambatnya. Kali ini, hasratnya menolak dihentikan. Hasrat itu menuntut darah sebagai ganti darah teman-temannya. Untuk Chenle. Untuk Giselle. Haechan. Dan ... Grace. Park Jisung menentang. Ada determinasi di suaranya ketika dia berkata, "Jaemin-hyung, kita pertahanin yang pakek jaket kulit buat sandera. Yang lain kita singkirin. Setuju?"
"Kamu mau apa?" Tanya Jaemin tegang.
"Aku punya rencana." Tak menunggu Jaemin menyahut, Jisung berjalan ke pintu samping toserba. Pintu khusus pegawai. Tanpa tanda, hanya pintu biasa yang di sebelahnya terdapat tong sampah. "Aku mau masuk, tapi jangan susul aku dan cepet sembunyi sampai aku ngasih kode lewat inhaler."
Jaemin tidak terima. "Aku lebih suka kamu beberin dulu detail rencana itu."
"Nggak ada waktu. Aku harus udah di dalem sebelum mereka selesai minum-minum."
"Satu menit aja," pinta Jaemin. Jisung dibuat kaget karena kekhawatiran di matanya yang terlihat nyata. Padahal Jaemin tidak perlu lagi menjaganya. Utangnya pada Grace telah lunas. "Ini nggak aman. Jelasin ke aku dan biar aku gantiin kamu. Gimana pun, aku pilihan yang lebih masuk akal一jangan tersinggung."
Itu benar. Jisung tidak merasa disudutkan. Dia sudah sampai di tahap menerima dan berhenti bertanya-tanya mengapa dirinya tidak berguna. Tahap selanjutnya adalah mengambil lompatan besar, berubah dari pecundang menjadi pemenang, dan Jisung sangat siap. "Nggak bisa. Harus aku. Ini tugas yang cocok diserahin ke aku."
"Kenapa?"
"Karena mereka pasti ngira aku cuma bocah 15 tahun yang nggak bisa apa-apa."
Meski berat mengizinkan, Jaemin ragu-ragu sebab dia tak mampu mematahkan logika itu. Pegangannya pada lengan Jisung mengendur dan dia turun satu tingkat di anak tangga. "Apa keputusanmu udah bulat?"
Jisung malah naik semakin tinggi menghampiri pintu, menggarisbawahi tekadnya yang semakin kukuh. "Ya, ini mungkin kesempatan terbaik kita."
"Seenggaknya bawa ini." Jaemin menyodorkan pisaunya, gagang lebih dulu.
"Percuma, mereka bakal geledah aku."
"Kamu niat bikin dirimu tertangkap?!"
Waktu terus bergulir. Jisung seakan mendengar detik jam di kepalanya yang menyuruhnya bergegas. "Percaya sama aku. Buat kali ini aja, tolong."
Permohonan yang diucapkan dengan amat lirih itu akhirnya meruntuhkan keraguan Jaemin sepenuhnya. Ketika dia menepuk bahu Jisung lembut, Jisung tahu itu juga merupakan restu darinya. "Pergi sana, buktiin ke orang-orang yang ngeremehin kamu kalau mereka salah."
Setelahnya dia berlari ke bagasi, satu-satunya tempat yang layak dijadikan persembunyian. Tong sampah tak cukup besar, sedangkan bangunan lain tak bisa dicapai tanpa melewati mereka. Membuka bagasi tanpa suara memang sulit, namun melipat tubuh dan meringkuk di situ ternyata relatif mudah. Jaemin beruntung diberkahi tubuh yang ramping. Pisau masih dia genggam saat dia menutup pintu bagasi itu, menyisakan celah kecil supaya dia bisa bernapas.
Selang beberapa menit kemudian, ada benda yang jatuh membentur lantai dari bagian dalam toserba. Rak, kursi, atau meja. Suaranya begitu keras, sontak mengundang perhatian. Apapun rencana Jisung, dia mulai menjalankannya. Anak buah Aru memacu langkah memeriksanya, melupakan alkohol mereka.
Kena kalian.
"Sangyi, lihat! Ada orang di sini."
Orang yang mereka maksud menjerit-jerit. Tak terbatas pada suara, perlawanannya diikuti lebih banyak barang yang berjatuhan. "Lepasin aku. Lepasin aku!"
Tawa terkekeh yang membuat perut Jaemin mulas melayang di udara dan mengalir hingga ke bagasinya. "Oh, siapa ini? Si tikus rupanya. Apa kabar?"

Sekitar sejam sebelum Aru mengacak-acak keutuhan timnya, Sungchan dan keempat temannya duduk melingkar di ruang makan yang asing, saling merapat berbagi kehangatan.
Mereka hanya menyalakan satu lampu. Semua jendela ditutup, dan karena tak bisa menemukan kunci, pintu depan diganjal sebuah kursi kayu. Tak seorang pun berjaga-jaga mengawasi pekarangan atau kendaraan mencurigakan yang melintas. Sampai saat itu mereka belum pernah bertemu kelompok lain, sehingga mereka menjadi begitu bodoh dan lugu一gampang ditaklukkan tanpa persiapan. Ketika Sungchan sadar keberuntungan timnya sudah habis, Aru datang lalu mengajarinya definisi rasa takut yang sesungguhnya.
Kala itu, mereka makan daging gurita beku. Nasinya matang sempurna. Minumannya soda. Giselle-lah yang memasak, dan dia juga yang menatanya di atas meja. Karena terburu-buru, sendok nasi tergelincir dari tangannya, namun Karina dengan cekatan menangkap, mendahului Ryujin yang berniat sama.
Ryujin berdecak kagum. "Refleksmu bagus."
"Mungkin gara-gara taekwondo."
"Kamu bisa taekwondo?" Shotaro jatuh semakin dalam. Pesona Karina tak henti-hentinya menjeratnya.
Karina tersipu. "Itu yang kamu dapet kalau punya ayah yang posesif. Ayahku bilang cewek harus bisa ngelindungi dirinya sendiri, jangan nunggu pertolongan orang lain."
Sungchan bertanya, "Sabuk apa?"
"Sabuk hitam," kata Karina bangga. "Aku udah latihan bertahun-tahun, dan hasilnya lumayan. Aku tahu banyak teknik pukulan, bahkan cara ngerebut senjata dari orang kalau aku ditodong pisau atau benda-benda semacamnya." Dia angkat bahu. "Bukan berarti aku ngarepin itu, sih ..."
Namun Grace tidak mengetahuinya.
Grace juga tidak sempat menarik pelatuk. Karina menerjangnya bak elang menyambar tikus. Cengkeraman tangan kanannya memaksa lengan Grace yang menekuk mengarah ke atas. Grace memekik, "LEPAS!", tapi dia menangis, air mata memburamkan pandangannya dan dia terlambat mengantisipasi tendangan Karina yang mengincar lututnya. Grace pun jatuh berlutut. Bunyi tulang yang beradu dengan ubin keramik bergema lantang.
Terpojok, dia diam saja ketika Karina memelintir lengannya ke balik punggung. Satu pukulan keras terakhir dan Grace membuang pistolnya. Glock itu bergulir pada Sungchan dalam keadaan aktif, siap menembak. Senjata pembunuh hitam mengilap itu, tampak remeh dalam naungan kegelapan. Permukaannya terasa dingin. Air mata Grace-lah yang panas, berlinang membasahi pipinya menciptakan hujan deras kesedihan.
"Apa-apaan kamu?" Hardik Karina. "Kamu pikir ini semua bakal selesai dengan bunuh diri?"
Hujan yang mengisyaratkan bahwa bagi sebagian orang, akhir bahagia tak pernah benar-benar ada.
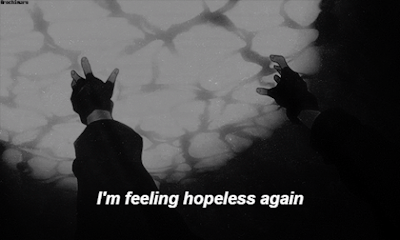
*Merujuk ke crab mentality, sebutan buat orang yang kagak demen sama kesuksesan orang lain
Fun fact = Karina beneran punya sabuk hitam taekwondo lho, jadi baik di dunia fiksi atau nyata, dia emang ciwi idaman 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top