66. Kita Bersiap
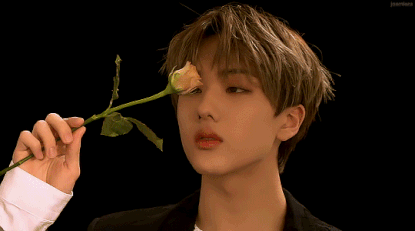
Pagi, fajar menyingsing.
Getaran yang menjalar dari ponselnya mengusik Park Jisung yang terlelap, dan dia bersyukur, sebab merasa sudah mencurangi mimpi buruk yang belakangan rutin menyambangi. Apa yang akan dia lakukan hari ini? Jisung duduk tegak, kebingungan. Dipandangnya ponselnya yang masih bergetar, lantas mematikannya. Itu adalah trik yang dia baca dari buku. Alarm bagi orang-orang tunarungu dirancang tanpa lagu, hanya getaran, agar bisa memancing mereka bangun tanpa mengganggu orang lain. Dan Jisung menirunya meski telinganya baik-baik saja.
Lalu dia ingat一apa yang terjadi, rencananya, alasannya.
Takut-takut, Jisung menengok ke bawah. Tempat tidur yang dia gunakan tidak besar, jadi rekan sekamarnya terpaksa beristirahat di lantai, namun Mark mengaku tidak keberatan. Mark mendengkur pelan, pulas. Untungnya. Jisung sempat cemas karena setahunya Mark tipe orang yang gampang terjaga. Kemarin saja dia bangun saat sedang tidur dalam posisi duduk dan kepalanya tidak sengaja terbentur dinding. Tak salah lagi, dia lelah, dan Jisung tidak menyalahkannya. Mark sudah bekerja keras.
Sambil berjinjit, Jisung melangkah mengitarinya. Gerakannya kikuk, dia tidak pernah harus mengendap-endap. Tunggu, apa Mark bergerak? Tidak, matanya masih terpejam. Jisung bergegas mempercepat langkahnya, melintasi kamar kakak-kakak kembar dan Renjun, juga Ryujin yang sendirian.
Tak ada waktu untuk mandi. Terlalu berisik. Jisung sekadar minum sebentar dan keluar. Di kursi teras, dia mendarat. Dirabanya kantong celananya. Inhaler? Ada. Gelang kakaknya? Ada. Kertas catatan? Ada. Kertas catatan inilah yang tidak dia ceritakan saat interogasi, dan memberikan penjelasan yang separuhnya dikarang-karang. Rasa bersalah menusuk hati Jisung, namun apa boleh buat? Pilihannya amat terbatas.
Di kertas itu, tertulis dalam tulisan tangannya versi berantakan, terdapat delapan alamat tempat-tempat yang menjual makanan.
Dia mencarinya sendiri kemarin, tanpa bantuan siapa-siapa, dan dia bangga, kendati itu tak berguna kalau dia tidak bertindak. Bertindak, seperti kata Haechan. Dia pasti bisa. Haechan telah mengajarinya banyak pelajaran berharga. Berbekal pisau dari dapur, Jisung berangkat mencari kendaraan. Embun pagi itu masih kalah dingin dari ekspresinya.
Terlampau fokus pada misi, Jisung tidak sadar, seseorang mengawasinya dari dalam rumah dan mengikutinya diam-diam.

20 JAM TANPA AIR
Buka, tutup. Buka ... Tutup.
Lama-lama ini membosankan. Jung Sungchan yang berusia 16 tahun mungkin punya wajah tipikal aktor terkenal, namun dia tak bisa berakting atau berpura-pura一atau entah apa lagi istilahnya一bahwa menjentikkan butterfly knife sama asyiknya dengan memainkan bola basket. Pisau itu memang keren, benar, hanya saja setelah memelototinya berjam-jam pisau yang sama cenderung membuatnya jenuh karena tidak cukup menghibur. Pisau ya pisau, fungsinya terbatas pada memotong atau menyakiti, bukan untuk menyenangkan hati.
Di lantai yang dingin Sungchan merebahkan diri. Kotornya lantai itu diabaikan karena sudah beberapa hari ini dia tak peduli pada higienitas. Sungchan terdiam menatap langit-langit gudang, pikirannya berkelana ke suatu tempat yang lebih hangat. Bunyi napas lembut Karina yang tertidur ikut andil membawanya ke masa lalu yang damai. Masa yang, Sungchan khawatirkan, tidak akan pernah terulang.
Darimana semua ini bermula?
Sungchan ingat, pagi itu dia sarapan seperti biasa dengan keluarganya. Ibunya yang menyukai kegiatan memasak menyiapkan menu beragam; ayam goreng renyah, telur gulung, sandwich tuna, dan hm, susu cokelat. Sungchan keluar dari rumah dengan sisa sedikit waktu yang mepet untuk mengejar bis, sementara kakaknya一tampan, lincah, satu telinganya ditindik sembunyi-sembunyi一bersiul santai menghampiri motornya. Sekolah mereka yang berbeda mengakibatkan Sungchan gagal mendapat tumpangan gratisan.
"Shotaro!" Sehari-harinya, hanya ada Sungchan dan bis, dan tentu Shotaro, tetangga sekaligus temannya sejak kecil. Shotaro setahun lebih tua darinya, meski jika menengok postur tubuh mereka, jarang ada yang percaya. "Sepeda belum bener?"
Osaki Shotaro, pemuda keturunan Jepang, menoleh. Dia lebih mirip berang-berang daripada manusia. Wajahnya seukuran telapak tangan, dan dia tak pernah bicara lebih keras dari dering ponsel yang volumenya dikecilkan setengahnya. Akhir-akhir ini, ada yang aneh, Shotaro mencampakkan sepedanya, dia lebih memilih menemani Sungchan dengan dalih peduli lingkungan, walaupun Sungchan tak bodoh untuk menyadari itu bukan satu-satunya alasan. "Iya, belum beli rantai baru."
Sungchan terkekeh. "Apa Korea sekarang kehabisan rantai sepeda?"
"Kayaknya harus nyari ke Jepang dulu." Shotaro menjawab asal, matanya menjelajah ke luar jendela. Ketika sopir bis hendak menutup pintu, dia menunjukkan reaksi berlebihan. "Paman, tunggu! Masih ada yang mau naik."
"Siapa?" Leher Sungchan terjulur tegang.
"Seseorang..." Suara Shotaro memudar, dan Sungchan tak perlu bertanya-tanya lebih lama sebab dari seberang jalan, seorang gadis tinggi semampai berlari sambil menggamit lengan temannya. Kedua gadis itu sama-sama berambut panjang, sama moleknya, tapi hanya satu orang yang presensinya membuat senyum Shotaro mengembang.
"Aduh," komentar Sungchan, mencoba menirukan siulan kakaknya. "Mestinya aku tahu. Yoo Karina?"
"Sssttt!"
"Pantes aja, dia cantik."
Dan itu merupakan pujian yang tepat, karena gadis-gadis itu, yang mengenakan seragam serupa dengannya, memang cantik. Mereka adalah nutrisi yang baik bagi mata pria, terutama Karina. Karina yang saat berjalan di koridor mengundang perhatian siswa-siswa, yang tahi lalat di dagunya terlihat seksi, dan kini, sepertinya, menggiring temannya ke perangkap berbahaya bernama jatuh cinta.
"Ayo, Giselle." Usai mengucapkan terima kasih pada sopir, Karina mengajak temannya, Giselle, mencari tempat yang masih tersedia. Parfum mereka menyebar dan mengubah bis menjadi taman bunga. Shotaro nyaris tak berkedip menatapnya, namun Karina malah sama sekali tidak meliriknya saat lewat.
Sungchan terbahak-bahak一sepelan dan sesopan yang dia bisa tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. "Dicuekin sama dia."
Bahu Shotaro terkulai lesu. "Mungkin besok."
Dua gadis itu duduk, dua kursi dari mereka, di belakang wanita pekerja kantoran yang hak sepatu runcingnya bukan mustahil digunakan untuk menikam penjahat. Tak sampai sedetik, Karina dan Giselle sudah sibuk membicarakan topik mengenai planet cewek-cewek, yang artinya berkisar pada drama, grup idola, atau nail art.
Siku Sungchan mendarat di perut Shotaro. "Udah, minta aja ID Kakao-nya. Pasti dikasih, tenang!"
"Caranya?" Shotaro, si murid teladan, ahli di pelajaran bahasa dan rapornya hampir selalu cemerlang, mengerjap lugu mendengar sarannya.
Sungchan mengerang, menepuk dahinya gemas. Ketika remaja, dia tumbuh jadi pemuda yang menganggap biasa bicara dengan wanita, lain halnya Shotaro, yang pertumbuhannya agak kacau dan sering malu-malu bila berhadapan dengan lawan jenisnya. Gawat, ini sih bencana besar! "Samperin, tepuk bahunya."
"Ntar dikira copet gimana?"
"Nggak lah, ngawur!" Mulut Sungchan sekarang hampir berbusa-busa menjelaskan tipsnya. "Makanya sapa sambil senyum, pasang ekspresi ramah, terus bilang, 'Halo, Karina, boleh aku minta ID Kakao kamu?'. Tuh, gampang!"
Shotaro bimbang. "Masa iya segampang itu?"
Berlagak bagai pakar cinta berpengalaman, Sungchan mengacungkan jempolnya. "Percaya sama bro-mu ini. Kalau cewek itu nolak, dia yang rugi."
Kata-kata Sungchan yang sok yakin justru menambah kadar keraguan Shotaro. Dia mengernyit, baru hendak membantahnya saat tiba-tiba bis mengerem mendadak dan melontarkan tubuh penumpang tanpa aba-aba. Semua orang terkesiap. Dahi Sungchan menabrak kursi lain, poninya acak-acakan. Bis itu berguncang sebentar selagi lajunya berkurang, lalu melambat, dan berhenti total dengan suara decit ban yang membahana.
Beberapa penumpang yang juga kena sial mengeluh, sedangkan si wanita pekerja kantoran membentak kasar, "Paman? Hei, paman! Apa paman udah kehilangan akal? Hati-hati nyetirnya!"
Protes itu dihadapi si sopir dengan tenang. "Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ada masalah di luar sana一"
"Macet?" Wanita itu tidak senang. "Kok tumben?"
Dengung percakapan mereda. Lampu di plafon bis berkedip-kedip. Hidup-mati, hidup-mati. Mungkin efek samping guncangan tadi. Pria berkemeja biru yang sebelumnya asyik mendengarkan musik mencopot earphone-nya. Wanita di sebelahnya menyimpan ponsel ke sakunya. Dalam keadaan bingung luar biasa, tanpa sadar semua penumpang bergabung dalam satu kesatuan yang kompak, mereka berdiri, enggan hanya duduk terpaku di kursi.
Hal pertama yang dilihat Sungchan adalah belasan kendaraan yang turut menepi. Roda empat, roda dua, semuanya. Posisi parkir mereka yang tak teratur memblokir satu sama lain. Helm-helm dilepas, kaca-kaca di buka. Seluruh pengguna jalan mengerutkan kening, gelisah dan heran, manakala terdengar jeritan yang bersumber dari rumah sakit pusat yang tak sampai 50 meter jauhnya. Itu salah satu rumah sakit terbesar di Seoul, mampu menampung ratusan pasien, dan setiap harinya kerap mengirim pasien-pasien mereka pulang一entah ke rumah atau ke pangkuan Tuhan.
"Karina, ada apa?" Suara Giselle sarat kecemasan.
Karina menggeleng, anting-anting mungilnya bergoyang mengikuti gerakannya. "Apapun itu, bukan pertanda bagus."
Ketegangan meningkat. Bis dan kendaraan di sekitarnya bergeming. Parade warna kuda-kuda besi menutupi aspal yang berwarna hitam. Bahkan jika ingin berputar balik, sudah terlambat. Mereka terkurung di jalanan yang penuh sesak itu bersama-sama sementara jeritan-jeritan misterius semakin dekat, semakin jelas一
Sungchan terlonjak. Ponsel si wanita pekerja kantoran berbunyi lantang.
"Mama?" Wanita itu mengangkatnya usai mengecek identitas penelpon. "Mama? Halo?" Dia mengaktifkan fitur loudspeaker. "Mama?"
Suara si penelpon bergemerisik. "Hwamin? Hwa ... Min?" Sinyal terganggu, suara itu terputus-putus.
Wanita yang dipanggil Hwamin menggigiti kukunya. "Aku nggak bisa denger suara Mama."
"Hwamin, di mana kamu?"
"Apa maksud Mama aku di mana? Aku di perjalanan ke kantor."
Puluhan orang berlarian dari rumah sakit. Pria dan wanita. Anak-anak yang pipinya dihiasi lelehan air mata. Ibu muda yang menggendong bayinya. Raut muka mereka menampakkan ketakutan seolah telah menyaksikan isi neraka. Tubuh mereka kotor bermandikan keringat dan ... Darah?
Shotaro menyambar ranselnya. "Sungchan, ayo kita keluar. Kalau jalan kaki pasti kita bisa."
Sungchan menelan ludah. "Atau lari."
Ibu Hwamin kembali bicara. "Lupain kerja. Pulang, Nak. Lekas pulang. Seoul itu daerah rawan. Kamu harus ke Bundang!"
"Bundang? Apa yang Mama omongin?"
"Dengerin Mama, Hwamin, Bundang masih bertahan. Bundang mungkin tempat teraman di negara ini, karena kita lebih ... Siap一"
Panggilan itu berakhir secara sepihak.
Orang-orang yang berlari mulai menggedor bis, atau pintu-pintu mobil. Sebagian yang nekat menggulingkan pengendara motor dan merebut kendaraan mereka. Yang tidak kuat ditinggalkan, dan tewas terinjak-injak. Keributan pun tak terelakkan. Kegemparan pecah. Seumur hidup, itulah pemandangan paling mengerikan bagi Sungchan, dan dia terjebak di tengah-tengahnya.
"Tolong!"
"Bawa anak Saya!"
"Jangan dorong, jangan dorong一"
Rekan satu sekolah lain yang tidak Sungchan kenal menyenggolnya. "Ya Tuhan," ujarnya, dia seorang gadis berambut merah terang yang tasnya lebih cocok disandang laki-laki. Tangan gadis itu melayang ke bibirnya. "Ya Tuhan ...."
Kemudian dari belakang, muncullah makhluk-makhluk ganas dan liar yang hanya Sungchan jumpai dalam mimpi buruknya. Atau video game一sesuatu yang tidak dia bayangkan akan jadi nyata.

Sisa perjalanan hari itu terlalu panjang untuk diceritakan.
Sungchan mengusap sudut matanya yang basah. Ini terjadi lagi. Dia menangis demi teman yang sudah pergi mendahuluinya. Dan bagian teburuknya adalah, pembunuh Shotaro masih berkeliaran. Aru hidup, Shotaro tidak. Kebencian melenyapkan ketenangan Sungchan, namun apa yang bisa dia lakukan? Dia terkurung di sini, di peti mati berupa gudang penuh rongsokan, bersenjatakan sebilah pisau yang namanya di ambil dari nama hewan.
Sia-sia saja.
Sungchan berbalik, memiringkan tubuh dan memakai lengannya sebagai bantal. Dia tidak ingin berpikir, tidak ingin merasakan apa-apa. Jadi dia menutup matanya rapat-rapat.
Di luar, bulan purnama bersinar, indah dan sempurna, memantulkan cahaya matahari ke bumi dan melakukannya terus semalaman. Tanpa lelah, tanpa perlu dihadiahi pujian. Dialah setitik piringan perak di langit luas yang gelap.

Garasi yang sama, waktu yang berbeda.
Park Jisung membelai setang sepeda baru di tempat dia menemukan sepeda lamanya. Untuk berjaga-jaga, dia telah memeriksa ruangan lain di rumah itu, karena siapa tahu, ada zombie yang masuk selagi dia tertidur. Rupanya tidak ada. Kemarin, ketika Renjun memergokinya di toserba, Jisung sangat terkejut sampai melupakan sepeda yang dibawanya. Padahal, sumpah, dia tidak membuat banyak suara di sana, namun Renjun tetap bisa menemukannya. Mungkin karena kebetulan. Mungkin juga ketelitian.
Pokoknya, lain kali Jisung akan menutup pintunya.
Persis di sebelah sepeda, terdapat sebuah mobil. Volvo biru, sudah cukup tua dari penampilannya, tapi jelas akan lebih berguna andai dia bisa mengemudikannya. Dalam hal ini, Jisung mirip Grace; mereka sama-sama payah di bidang mengoperasikan kendaraan selain sepeda. Sebagian salah ayahnya, yang melarangnya dekat-dekat motor atau mobil sebelum mencapai usia legal. Mau bagaimana lagi. Jisung pasrah, dia berjalan ke pintu garasi dan membukanya.
"Halo, Jisung."
Begitu pintu itu terbuka dan menggulung ke atas, dia dikagetkan oleh suara berat khas laki-laki yang mendengarnya menimbulkan efek seolah-olah dia jatuh menimpa kaktus berduri. Jisung mundur selangkah, mulai bicara terbata-bata sesuai kebiasaannya saat gugup melanda. Lalu dia melihat siapa pemilik suara itu dan menghentikan racauannya.
"Jaemin-hyung?"
Itu Jaemin dengan muka bantalnya.

Acieee Shotaro jadi cameo di part ini ehehehehehehe, maap yak dia kagak bisa tampil lama2 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top