51. Kita Tegar

Hujan sudah berubah menjadi rintik-rintik. Apa yang tadi terkesan bak lolongan histeris langit telah berganti jadi isakan-isakan pelan yang memudar. Seperti seseorang yang merelakan, melepas sesuatu tak ditakdirkan jadi miliknya. Hanya ada angin yang bertiup membisikkan rahasia-rahasia alam, berduet dengan petir yang sesekali menyambangi tanah. Bersama, keduanya menciptakan gelap dan terang yang bercampur dalam cawan kekacauan. Suasananya dingin membekukan, seluruh warna ibarat terisap menuju ketiadaan.
Inilah gambaran yang paling mendekati mimpi buruk Mark Lee, yang terburuk dari segalanya, sebab ia tahu ia takkan bisa mencubit pipinya dan berharap bangun lantas kembali ke rutinitasnya yang biasa.
Ini sungguhan. Ini nyata. Dan Mark terjebak di dalamnya.
"Maaf, Jisung."
Terhitung sudah 3 kali Mark melontarkan kalimat itu. 2 kata, 10 huruf, amat sering ia eja sampai-sampai kehilangan maknanya. Maaf untuk ini, maaf untuk itu. Terlalu memuakkan untuk diingat alasannya.
"Aku gagal..."
Dia mengakhiri penuturannya dengan menyerahkan seuntai gelang. Setengah lusin ceri mungil yang menyebar teratur di tiap permukaannya berwarna merah, matang karena darah.
Jisung menerimanya, gelang tanpa tuan yang pernah melingkari pergelangan kakaknya. Mark menyaksikan jakunnya naik turun, menelan ludah, dan mungkin juga tangisan. Dia mengatupkan tangannya ke sekeliling gelang itu rapat-rapat, sementara harapan di matanya retak, lalu jatuh berguguran. "Apa dia meninggal?"
Mark tidak sanggup menjawab.
Si kembar berdiri. Jeno duluan, Jaemin menyusulnya. Gerakan mereka memang selalu selaras. Namun Jeno-lah yang meletakkan tangan di bahu Jisung dan berusaha menyeretnya mundur. "Kasih ruang Mark-hyung buat napas dulu. Seenggaknya sekedar ganti baju."
Tidak digubris, Jisung justru menepis upaya Jeno menenangkannya. "Apa dia meninggal?"
"Jisung."
"Mark-hyung, tolong jawab aku, apa kakakku meninggal? Aku berhak tahu soal ini."
Bola mata Mark bagai tersaput awan kelabu. "Sulit buat narik kesimpulan. Aku sendiri nggak tahu pasti. Kamu inget asap merah yang muncul nggak lama setelah Aru pergi?"
Jisung mengangguk dengan wajah kaku. Dia seperti pemuda yang berdiri di pinggir tebing dan tidak yakin apakah Mark hendak mendorong atau menolongnya.
Masalahnya adalah, entah ingin atau tidak, Mark tidak mampu mencegahnya. Ini一dan banyak hal lain一berada di luar kendalinya. Mark bukan penyihir sakti dengan tongkat ajaib, dia tak lebih dari manusia biasa, yang kini berpendapat dirinya tidak berguna. "Hujan bikin asap itu memudar, tapi berkat beberapa suara tembakan aku bisa ngikutin mereka ke Shinsa-dong. Sayangnya waktu sampek di sana, aku nggak ketemu siapa-siapa. Jisung, aku terlambat."
"Grace Noona dan Haechan-hyung...?"
"Dua-duanya lenyap. Tempat itu sunyi senyap. Gelang Grace dan koin-koin Haechan tergeletak di genangan darah yang nggak jelas asalnya. Cuma itu yang tersisa, selain pecahan kaca dan potongan-potongan motor Ducati mereka."
"Tapi dia一nggak ada mayat?" Tenggorokan Jisung tercekat.
Untuk amannya Mark menggeleng. Dia pengecut, tidak berani menyuplai harapan lain tak peduli sekecil apapun. Terhitung saat ini ia takkan pernah bisa mempercayai mulutnya untuk bersumpah, berjanji, atau berkata keadaan akan terkendali lagi. Yang terbaik bagi mereka adalah saling jujur mengenai segalanya. Jangan ada pisau dibalik manisan apel. Tak perlu juga ada yang disembunyikan. Apa yang terjadi, terjadilah.
"Aku bener-bener minta maaf, Jisung." Dia menunduk.
Semua perkara mengenai permintaan maaf ini rupanya membantu Jaemin kembali menemukan suaranya. Dia menggaruk pucuk hidungnya dengan canggung. "Ayo kita masuk ke rumah. Hawanya dingin bukan main."
"Ya, ide bagus." Jeno mendukungnya. "Aku bisa nyeduh teh supaya kita ngerasa lebih ... Hangat."
Terbatasnya pilihan membuat Mark mematuhinya. Baru dia sadari bahwa dia menggigil, ujung-ujung jarinya berkerut persis orang yang terlalu lama mencuci piring. Tawaran apa saja yang menyangkut sesuatu yang hangat akan ia terima dengan senang hati. Mark ingin mengusir rasa dingin ini, sebab sukar rasanya bernapas saat di dadamu seolah ada lubang selebar ngarai.
Lebih lambat selangkah dan lebih enggan, Renjun membuntutinya tanpa menoleh ke belakang. Dia menutup pintu, mengurung atmosfer mengerikan ini di ruang duduk. Kegelisahan mewarnai wajahnya. Dia tak ubahnya burung yang kakinya terikat dan tak sabar ingin terbang. Jika punya sayap, ia pasti akan melayang dari sini sejauh-jauhnya, mungkin ke China, atau tempat mana pun dimana maut tidak berkuasa begitu perkasa.
"Mana ya, kotak musikku?" Ia beralasan, mencari-cari kotak musik yang ia mainkan ketika Ryujin bercerita mengenai teman-temannya. "Apa ketinggalan?" Menggunakan alasan itu Renjun menyingkir ke sebuah lorong yang karena penerangannya padam jadi menyerupai jalan masuk ke gua.
Rahang Jaemin terbuka memandangnya. Bunga ketidakpercayaan mekar, namun ia sudah lebih pandai menahan diri dari mengungkapkan hal-hal yang sebaiknya disimpan saja. Renjun kabur一itu pilihannya. Renjun tidak mau menanti keajaiban dan memutuskan untuk menumbuhkan sayapnya sendiri. Tidak penting apakah sayap itu kuat atau tidak, realita bisa menjelma jadi apapun yang kita inginkan一kadang-kadang.
Selain Jaemin, sosok berparas ayu yang ikut betah bersikap diam adalah Ryujin. Layaknya memahat di atas air, kata-kata Ryujin melebur dan tak pernah lolos dari bibir. Mereka melakukan kontak. Cukup lama mata amber Mark terpaku pada mata cokelat terang gadis itu. Dan tanpa bisa dijelaskan, ia merasakan moment paling ganjil saat ia duga Ryujin memahaminya bahkan sebelum ia berbicara.
Paham bahwa Mark, bodohnya, pulang dengan tangan hampa.
"Biar aku obatin tanganmu, Mark-hyung." Calon dokter Na Jaemin dengan cekatan mempersiapkan alat-alat perangnya. Bungkusan obat yang diperoleh Renjun didampingi Grace, Grace yang tak berhasil Mark jaga, ia keluarkan. "Ada banyak pecahan kaca di lenganmu. Kita mungkin butuh pinset一"
"Nanti."
"Apa?" Ketenangan Jaemin terganggu. Dia melemparkan tatapan menegur. "Nanti? Kenapa nanti? Luka kayak gitu harus buru-buru diurus kalau nggak mau infeksi."
"Santai." Mark berharap bisa merangkai kalimat yang lebih panjang, lebih meyakinkan, tapi tersenyum saja mendadak terasa sangat susah. "Aku harus ke kamar mandi sebentar. Di mana?"
Dari posisinya yang tengah mengisi air ke teko, Jeno menunjuk arah berlawanan dari yang dituju Renjun. "Di situ. Tas pakaian ada di kamar sebelahnya."
Mark melambai ringan. Perkara remeh seperti pakaian ganti saat ini berada di dasar prioritasnya. Dengan langkah tersaruk-saruk dan punggung membungkuk, dia bergegas ke tujuannya, secepat yang ia bisa, meninggalkan tetes-tetes air di tempat kakinya berpijak.
Sesampainya di dalam, Mark mendapati dia berada di ruangan yang didominasi wanita. Jubah mandi tergantung di balik pintu, warnanya pink. Bersanding dengan obat kumur di lemari, terdapat 2 sikat gigi, alat cukur beserta krimnya, deodoran, sabun wajah, dan produk-produk perawatan rambut. Pasangan yang baru menikah, tebaknya, atau barangkali 2 sejoli yang telah lama tinggal seatap. Cermin besar seukuran kepala hingga dada terpasang di atas wastafel keramik, menempel rapat di dinding. Mark berjalan menghampiri cermin itu dan meneliti penampilannya.
Dia tidak menyukai apa yang dia lihat.
Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Cermin ini dari luar memang terlihat baik-baik saja dan normal, tapi mana mungkin cermin yang normal merefleksikan sesuatu yang tidak nyata? Cermin ini pasti rusak, jadi bayangannya terdistorsi sedemikian parah.
Dulu sekali, saat ia masih kecil, Mark bercita-cita sebagai penulis. Sekarang pun masih. Setiap kali ditanya atau diminta melengkapi data diri untuk buku tahunan sekolahnya, ia konsisten selalu mengisi "author" di kolom cita-cita. Sekian lama, tak pernah berubah, meski untuk tiba pada titik menerbitkan buku yang tercantum namanya di bagian sampul depan akan jadi perjalanan yang melelahkan. Ia tak peduli, sebab menulis memberinya kebahagiaan.
Mark memiringkan kepalanya, mencoba membandingkan anak penuh semangat di benaknya dengan sosok asing yang terjebak dalam kaca. Mereka berbeda. Sosok itu lemah dan patah. Matanya cekung, dengan tatapan suram khas orang yang kenyang mencicipi kejamnya dunia. Bahunya merosot turun. Di bawah kulitnya yang pucat dan hampir-hampir transparan, tak ada apapun selain keletihan.
Siapa kamu? Mark penasaran, dan mengusap-usap cermin itu berharap pantulannya akan berubah, namun kini, lebih buruk, ia justru mendapati bayangan wajah-wajah Chenle dan Giselle menjelang akhir riwayat hidup mereka. Dia mengingat jelas bagaimana mereka terjatuh, berdarah, meninggal. Malah, terlalu jelas. Kenangan itu membakar kewarasannya. Ia turut mendengar suara tawa Aru sekarang, mengejek ketidakberdayaannya.
Air mata mengalir di pipinya. Tanpa suara, hanya sedu sedan teredam yang disusupi kata 'maaf'. Dia berpegangan di wastafel rumah tak dikenal itu, takut-takut duka akan membuatnya ambruk. Pahitnya penyesalan menikamnya. Mark kira dia sudah tahu apa itu benci, tapi tak pernah ada kebencian sebesar ini, pada dirinya sendiri, yang sebatas jadi penonton selagi teman-temannya satu-persatu dihabisi.
Mark mulai menangis.

Park Jisung hanya berjarak 48 jam dari ulang tahunnya yang ke-6, sedangkan Grace berusia sembilan tahun ketika mereka berjumpa untuk kedua kalinya.
Ini kejadian langka, dan yang dimaksud dengan langka adalah amat kecil kemungkinannya terulang. Ayahnya mestinya tidak ke rumah Grace pada tanggal 3 februari. Jadwalnya mengunjungi anak perempuannya masih berbulan-bulan lagi, namun dia sudah muak mendengar Jisung merengek minta diantar menemui kakak yang di pertemuan pertama lebih sering mengabaikannya.
Setelah perkenalan yang janggal itu, Grace mengamatinya layaknya mengamati alien yang mendarat ke bumi. Kebanyakan saudara tak perlu menunggu bertahun-tahun untuk saling mengenal, jadi Jisung menerima sikapnya yang dingin. Mama bilang itu karena mereka belum dekat, maka dari itu Jisung berinsiatif mengundangnya ke pestanya supaya mereka bisa perlahan-lahan mengakrabkan diri.
Tentu saja, Grace terkejut, dan seandainya Jisung pandai mengartikan ekspresi orang lain, ia akan tahu bahwa Grace sangat tidak senang. Terpaksa, Grace mengizinkan Jisung masuk ke kamarnya.
"Hamster." Nyaris Jisung lupa, Grace memanggilnya hamster karena bentuk matanya. "Ngapain kamu ke sini?"
Kamar Grace tidak mirip kamarnya, atau kamar teman-temannya. Sejak dulu Grace selalu tampil seperti miniatur orang dewasa. Tak ada mainan yang berserakan di sana, buku-buku dongeng menggantikan boneka. Banyak sekali, semuanya bertumpuk rapi di atas meja belajar. Tabel perkalian dipajang di tembok, dan di bawahnya, adalah kertas hasil ujian yang disatukan dengan penjepit hitam. Sekilas lirik, Jisung menemukan angka "93" di pelajaran matematika.
"Aku bukan hamster, Noona." Ia protes. "Namaku Jisung."
"Ya ya, terserah. Kamu mau apa?"
"Nganter undangan."
"Undangan?" Grace menghempaskan dirinya di ranjang. Dia bersin, kemudian batuk-batuk sambil menutupi mulut. Hidungnya berair. Ia tampak menderita dan tak menginginkan apa-apa kecuali tidur siang.
Mata hamster Jisung memperhatikannya dengan cemas. "Noona sakit?" Tanyanya, dan menyerahkan undangannya.
"Flu berat." Suara Grace serak. Dia bergeser sedikit ketika Jisung duduk di sampingnya. "Jangan deket-deket, nanti kamu ketularan." Lalu usai menepiskan kepangan rambutnya ke punggungnya, dia membaca kertas yang Jisung sodorkan. "Oh, kamu ulang tahun?"
"Iya! Yang ke-6. Aku udah gede."
Grace mendengus. "Gede apaan, bocah."
"Kata mama gitu." Jisung membantah keras kepala. "Tahun ini aku nambah tinggi 5 senti lho!"
"Ssstt!" Grace menuntut ketenangan. Dia terhanyut dalam jalinan kata demi kata yang ia telusuri bersama gerakan jari telunjuknya. Hingga di bagian, "Kutunggu kedatanganmu ya", tepatnya di baris dimana Jisung menulis, "Grace Park" dengan bimbingan ayah, dia berhenti. "Jisung."
Raut itu. Raut muka terganggu itu. Grace semakin tidak senang. Entah sebab apa, agaknya Jisung telah merusak harinya. "Ada yang salah?"
"Tulisanmu yang salah." Grace menuding namanya. "Margaku Moon, bukan Park."
"Moon? Kenapa Moon?"
"Apa ayah nggak cerita?" Dengan jemari lentiknya dan pena, Grace mengoreksi apa yang ia anggap tidak benar. "Aku pakek marga mama dari bayi. Kita beda."
"Aneh." Jisung tidak pernah mendengar sesuatu semacam itu. Setahunya, saudara seharusnya mempunyai marga yang sama. Itu menandakan mereka berasal dari 1 pohon keluarga. Mereka terhubung melalui ikatan darah. Jika dari segi fisik dan nama saja berbeda, apa mereka masih bisa disebut adik-kakak? "Tapi, Noona." Dia menarik-narik sweter Grace agar menghadapnya. "Walaupun beda kita tetep saudara kan? Iya kan?"
Grace hanya menatapnya dan tidak menjawab. Dia bahkan absen di ulang tahun Jisung yang ke-6, dan ulang tahun selanjutnya saat Jisung tumbuh tinggi lagi 15 senti, 25 senti, sampai akhirnya keunggulan postur mereka berbalik.
Grace tidak pernah menjawabnya.
Di usia 15 tahun, dengan tinggi yang sudah mencapai 5'3", Park Jisung berkonsentrasi mencongkel noda darah yang mengering di perhiasan kakaknya. Grace, dan koleksi gelangnya yang beraneka ragam. Ini salah 1 kesayangannya. Lebih cocok dipakai anak-anak, sebenarnya, daripada gadis remaja. Mengingat banyaknya makanan yang ia santap, Jisung terheran-heran mengapa perawakan Grace semungil anak cheetah.
"Mark-hyung belum keluar juga?" Jaemin mondar-mandir khawatir.
Ryujin berdiri dengan tenang. "Biar aku yang ngecek dia."
Mark. Mark bilang tidak ada mayat. Oke, dia memang tidak mengucapkannya melalui lisan, namun Jisung memilih mempercayai apa yang ia mau. Yang artinya, masih ada harapan. Di suatu tempat, kakaknya bisa saja masih bernapas. Hanya ada 1 hal yang perlu dilakukan; menemukannya. Seperti dulu, Jisung-lah yang harus mendatanginya.
Bila dirinya adalah Aru, ketua dari kelompok dengan begitu banyak anggota, kemana ia akan membawa para sandera?
Diawali dengan bersua Ryujin dan Giselle. Lalu Aru muncul dan membuntuti mereka dari minimarket. Apa inti kedua peristiwa itu? Benarkah Aru menargetkan mereka secara acak? Entah kenapa Jisung merasa ini tidak sesederhana kelihatannya. Jisung mungkin lemah dari segi fisik, tapi Grace bukan satu-satunya anak ayah yang cerdas. Pasti ada benang merahnya. Pasti. Kamu butuh kode yang tepat untuk membuka suatu brangkas.
Park Jisung menutup matanya, berpikir, menganalisis...
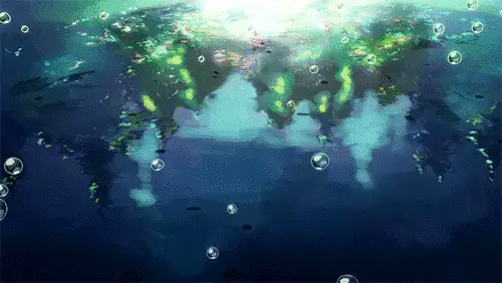
Hiii sorry banget baru update my prenz 🤧 sesungguhnya otak w lagi buntu akhir2 ini, idenya nyangkut ntahlah, ke genteng tetangga kayaknya. Masih ada yang nunggu pan? Jangan kabur dulu euyy, soalnya besok Haechan udah nongol lagi ☹️👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top