38. Kita Berteman I
Di sudut malam yang remang-remang
Pemuda berbaju lusuh itu duduk sendirian
Deraan sepi mendorongnya berdendang menghibur diri
Hingga tak sadar di ujung terowongan ada seberkas sinar yang menanti
"Apa itu?" Dia bertanya, lirih dan pelan
Terlalu lama dalam gelap membuat dia tak mengenali cahaya
Terlalu lama seorang diri membuat dia lupa bagaimana rasanya punya teman.
Lee Haechan takkan bilang dia punya jiwa seorang pujangga, tapi saat itu, di atas jok motor Ducati yang telah dikeringkan, ia mendapati dirinya merangkai sajak-sajak sederhana yang entah bisa disebut puisi atau bukan. Ia dan buku sejujurnya jarang akrab. Buku jelas lebih cocok berteman dengan pemuda-pemuda seperti Mark Lee yang memenuhi kriteria cowok culun dari A sampai Z atau Park Jisung.
Hanya saja, ampun deh, kalau ia memiliki buku di tangannya, ia pasti sudah tamat membacanya 2 kali saking lamanya Grace berdandan. Hal ini memberitahunya bahwa terlepas dari perilaku Grace yang bisa sangat sadis, dia tetaplah gadis yang amat feminin.
"Udah belom?"
"Sebentar." Sahutan samar terdengar dari dalam rumah. "Aku lagi nyari iket rambut."
"Lammmaaah."
"Jangan cerewet ya, cebol!"
Heran sekali Haechan. Bibir Grace agaknya bekerja lebih sigap dari matanya. Diminta bersiap-siap dia lambat, diminta meledek dia jagonya. Namun Haechan tak menyahut sebab sadar diri, di sanalah letak kesamaan mereka berada. Duduk manis macam murid yang rajin, Haechan menarik napas panjang. Aroma tanah basah yang bercampur dengan semerbak wangi bunga memenuhi paru-parunya. Hujan paling deras atau badai paling dahsyat pun pada akhirnya menyisakan pelangi paling cerah.
Sayangnya, dasar Haechan, dia memang tidak terkenal karena kesabarannya. "Serius, Grace, kamu nyari iket rambut sambil ngitung bubuk kopi, ya?"
Parahnya, Grace baru keluar 5 menit kemudian dengan wajah berseri-seri tak berdosa. "Nyantai dong jadi orang!"
Terlanjur kesal, Haechan terpikir sebuah rencana jahat. Saat gadis berkepang satu yang disampirkan di bahu kanannya itu lewat, dia sengaja menjulurkan kaki di jalurnya. Tapi Grace tak termakan jebakan itu. Grace malah melompati kaki Haechan dan balik menendang betisnya. "Aduh!"
"Rasain," ujarnya tanpa belas kasihan. "Yuk, berangkat."
Si pemuda cemberut, sempat membetulkan posisi tas senjatanya sebelum tancap gas. Ducati melaju mulus di sepanjang permukaan garis putih putus-putus yang membelah jalanan menjadi dua. Daun-daun berterbangan terhempas angin yang mereka timbulkan. Setengah tangki bensin dari Lexus di garasi rumahnya masih sanggup mengantar keduanya ke titik X pertama yang tercantum dalam peta.
Ini dia, minimarket terpencil di Joongyi-dong.
Membangun bisnis di daerah ini sejatinya tidak terlalu menguntungkan, namun setiap tahun, minimarket itu mampu selamat dari ancaman kebangkrutan. Bagi penduduk sekitar, tempat ini adalah tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bagi Haechan, tempat ini adalah penyelamat kala ia jalan-jalan terlalu jauh dan tersesat. Kali ini, dia menghitung, 3 pegawai minimarket termasuk kasir ramah yang pernah mengajaknya bercakap-cakap telah berubah.
Mengaduk-aduk tasnya, Haechan menarik keluar sebuah Glock 18 yang terisi penuh dan menyerahkannya pada rekannya. "Kamu yang urus."
Karena pistol itu merupakan pistol yang sudah ia kenali cara penggunaannya, Grace bisa memakainya dengan mudah. 3 kepala sukses ia hancur leburkan tanpa melenceng dari sasaran. "Gimana?" Dia terdengar sangat bangga pada dirinya sendiri.
Haechan tidak tahan untuk tidak tersenyum. "Bagus, Moon. Kamu nggak perlu diajari. Mungkin ntar kita bisa langsung latihan beladiri?"
"Nggak masalah. Apa kamu belajar semua itu dari penjara, Haechan?"
Sang mantan narapidana tertawa. "Kalau kamu nanya tentang keahlian nembak, jawabannya nggak. Aku dulu ikut kursus."
"Jadi kamu bohong ke Mark?"
"Mark Lee nanya pakek nada nuduh, aku nggak suka itu."
Grace semakin penasaran. "Dan soal beladirinya?"
Sebuah ingatan menyambar benak Haechan ketika membahasnya. Berkata berkelahi itu bakat alaminya akan terdengar arogan, saat faktanya ia memperoleh keahlian itu berkat keadaan yang memaksanya terbiasa. "Waktu aku di Juvie," katanya sembari mendorong pintu kaca. "Ada penghuni senior yang numpahin makanannya ke bajuku."
"Kenapa?"
"Dia bilang aku duduk di kursinya, dan aku nggak mau pindah."
"Pinter." Grace gantian memuji. Kemiripan karakter membuat ia tahu bahwa mengalah di situasi yang tidak tepat sama saja dengan mendeklarasikan diri sebagai jongos yang gampang ditindas.
"Dia marah, aku marah. Kebetulan penjaga nggak ada. Dia mukul aku duluan, dan aku bales mukul dia. Seru situasinya."
"Akhirnya?"
"Aku disuruh bersihin tempat pembakaran sampah. Seandainya bukan anak baru, masa hukumanku pasti ditambah."
Bagian dalam minimarket rupanya cukup lengkap. Keberadaan 3 zombie di luar barangkali efektif mengusir penjarah yang berniat menguras habis tempat ini. Rak-rak camilan, permen, alat cukur, pelembut pakaian, pembalut, dan aneka kebutuhan pokok lainnya belum rusak, meski sebagian besar isinya telah berkurang. Sisi positif dari pandemi yang baru masuk hitungan hari, tidak ada barang-barang yang melewati batas kelayakan konsumsi. Grace meraih plastik belanja dan berkomentar, "Sial banget kalau gitu."
"Oh, nggak." Ralat Haechan ringan. "Aku nggak akan nyebut itu sial. Bukan aku yang pingsan dan harus dapet perawatan, Grace."
"Sinting. Kamu bikin dia pingsan?"
"Jenius." Dengan jari telunjuk Haechan mengetuk-ngetuk sisi samping kepalanya. "Sejak itu nggak banyak orang tolol yang ganggu aku."
Grace mengukir senyum simpul一paduan yang pas antara kecantikan dan sikap liar. "Aku mau tutorialnya nanti."
"Siapa yang sinting sekarang?"
"Ini gara-gara kelamaan kumpul sama kamu."
Ketika Haechan berancang-ancang melemparnya dengan sebungkus roti cokelat, Grace buru-buru minggat. Jadi mereka berpencar, mengawali penjelajahan dari titik yang berbeda. Grace menjemput kacang karamel tersayangnya, sementara Haechan lebih berminat memeriksa deretan minuman. Mengambil kesempatan saat tak ada orang yang meminta kartu identitasnya, sekaligus melengkapi rapor merah moralnya, dia menggapai sebotol soju yang tutupnya masih tersegel utuh.
Mengangkatnya sejajar dengan mata, Haechan mengguncang dan membuat cairan di dalamnya teraduk-aduk seperti ombak di pulau asalnya. Hanya dengan sekali putaran ke kanan, tutup botol itu terlepas. Ia lalu menurunkannya. Bibirnya menyentuh bagian luar soju tersebut dan sudah akan menenggaknya manakala mendadak Grace berseru lantang. "Haechan, coba ke sini!"
"Apa?"
"Ke sini, aku ada di rak deterjen!"
Berhubung Haechan menyayangi telinganya dan enggan telinga itu dibombardir bertubi-tubi teriakan, dia menyerah. Dihampirinya gadis itu untuk melihat apa gerangan yang ingin dibaginya bersama.
Ternyata itu sebuah dinding, berwarna putih yang mengingatkannya pada rumah sakit. Atau dulunya putih, dan kini berganti kusam digerus oleh kerasnya perubahan. Kian memperparah, seseorang yang tulisan tangannya buruk telah mencorat-coret dinding itu dengan cat pilox merah darah dan menuangkan rasa frustasinya dalam sebaris kalimat singkat,
"TUHAN MEMBENCI KITA."
Begitulah bunyinya.
Keduanya memandangi guratan-guratan kasar huruf itu bagai dihipnotis, terpaku seakan menyaksikan kehancuran dunia一yang tidak sepenuhnya salah一sekaligus runtuhnya kepercayaan manusia pada sang pencipta.
Sepertinya saat sedang berada dalam belenggu kesulitan, mudah sekali bagi kita untuk melakukan lompatan besar dengan menyalahkan Tuhan, tanpa berpikir 2 kali adakah makna tersembunyi di balik cobaan yang Dia beri. Kita seumpama berkaca pada cermin yang retak, sehingga tak benar-benar bisa berintrospeksi diri.
Kita menuding Tuhan, padahal kitalah yang salah. Kita mengutuk takdir atas semua yang terjadi, padahal kitalah penyebabnya. Kita lupa, lebih dari sering, bahwa benih yang bermutu rendah mustahil menghasilkan buah yang berkualitas. Ini sebab-akibat, bukan dadu kehidupan, melainkan hal yang tak terbantahkan bahwa Tuhan selalu memberi balasan yang setimpal. Tidak sepatutnya kita menuduh-Nya jahat, saat melalui bencana Dia justru memperingatkan kita agar tak meneruskan perbuatan tercela.
Manusia terlalu mudah lupa, mudah abai, mudah tersesat.
Grace berdecak karenanya. "Kamu percaya Tuhan, Haechan?"
"Siapa aku sampek nggak percaya?" Pertanyaan retoris itu tak perlu dijawab. "Alam semesta ini terlalu luar biasa buat dibilang ada dengan sendirinya."
"Katanya, kita harus menghormati kepercayaan masing-masing, terus orang yang nggak punya kepercayaan gini enaknya diapain?"
"Jangan ditemenin."
Sudut bibir Grace melengkung ke atas dan ia tertawa. Dia membungkuk, memungut kaleng cat yang tidak dibawa oleh si pelaku vandalisme dan menimpa kata-katanya dengan kalimat baru yang lebih bijaksana.
Tak mau kalah, Haechan meniru tingkahnya dan menambahkan sesuatu yang menandai jejak mereka. "Beres." Ia bergumam puas. "Ayo cepet selesaiin ini dan pergi."
Setengah jam berikutnya mereka habiskan dengan berkeliling, mengangkut apapun yang bisa diangkut dan menaruhnya di plastik sampai penuh. Selain makanan, Haechan juga merenggut senter, baterai, obat-obatan, rokok, novel-novel di rak yang berdebu (untuk Grace) serta segenggam koin dari mesin kasir.
"Udah?"
Grace mengangguk. "Ya. Jangan lupa tas senjatanya."
"Siap." Haechan menepuk-nepuk tas yang dikhawatirkan, yang ia kaitkan di bahunya. "Kamu tahu, ada satu senjata yang paling aku pengen, tapi bukan pistol."
"Apa itu? Granat?"
"Salah. Pernah denger rocket launcher?"
Mereka pun keluar, kembali ke dunia yang menantang, meninggalkan pesan一warisan sederhana一bagi siapa saja yang mungkin memahami artinya.
"TUHAN ̷M̷E̷M̷B̷E̷N̷C̷I̷ KITA
TUHAN MENGUJI KITA."
LH & GM WAS HERE.
Grace tak pernah tahu bahwa selisih beberapa menit usai ia berlalu, 2 kelompok yang berbeda mendatangi tempat itu, salah satunya Mark ... Dan adiknya.

Rumah ketiga kelompok Mark Lee adalah rumah pertama yang bisa ia buka di dekat jembatan.
Bangunan itu berbentuk memanjang, beratap rendah, dan lebih cocok ditempati oleh keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan 1 anak, dibanding tim yang berjumlah 8 orang.
Pekarangannya sempit, hanya muat dimasuki 1 unit mobil. Puluhan batu warna-warni tersebar untuk mengantisipasi tanah becek di musim hujan, sekaligus menambah nilai estetika. Pagar-pagar kayu yang di ukir menyerupai anak panah berbaris rapi mengelilinginya dalam jarak tak lebih dari 10 senti dari satu sama lain. Saat disentuh, catnya mengelupas, membekas di tangan, namun setidaknya rumah itu memiliki atap yang bisa melindungi mereka dari tangisan langit yang kian deras.
Mark enggan berjudi dengan takdir. Adanya tambahan 2 nyawa semakin memotivasinya untuk meminimalisir resiko apapun yang bisa berujung pada kejadian naas seseorang terkapar kesakitan. Dia rela berdesak-desakan di ruang tamu bila itu artinya semua anggota aman, bersama Renjun, Giselle, dan Ryujin.
"Jadi ... Ryujin kan?"
"Shin Ryujin." Gadis yang pundaknya terbalut selimut tebal usai ia mandi itu mengangkat dagunya dalam isyarat berani.
Si penanya, Mark, menganggukkan kepalanya. "Dari sekolah mana?"
"Apa ini interogasi?" Giselle menyikut lutut Ryujin, tapi gadis itu berpura-pura ia tidak pernah disela. "Atau bayaran atas bantuan kalian?"
Mark tersenyum. "Cuma tanya jawab biasa."
"Kalau gitu biar aku yang mulai duluan. Karena ... Kamu sadar kan, kita belum kenalan? Pertanyaan pertama, nama kalian?"
Di sebelah kiri Mark, Renjun yang bermain-main dengan kotak musik yang ia temukan di kamar bayi rumah itu mengacungkan tangannya. "Panggil aku Renjun."
"Mark Lee." Mark menunjuk dadanya, bicara dalam aksen Canada yang kental. "Yang barusan keluar itu Jisung, maknae kita. Yang masak di dapur Jaemin dan Chenle. Kalau yang lagi mandi kakaknya Jaemin, Jeno."
"Yang suka kopi itu Jaemin?"
Dua laki-laki itu tergelak. Pertama kali memasuki rumah, Jaemin sudah sibuk mencari kopi sementara yang lain mengatur giliran mandi. Dalam 30 menit, dia telah menghabiskan 1 gelas dan tengah beralih ke gelas kedua, meski tidak ada yang berani mencicipi kopi buatannya setelah Jeno memperingatkan; kopi Jaemin itu berpotensi membuat perut melilit. "Ya, itu Jaemin."
Ryujin menelaah banjir informasi itu sejenak. "Sekolahku dan Giselle jauh dari sini, Midspa."
Renjun bersiul. "Itu bukan cuma jauh, tapi terlalu jauh."
Giselle menimpali, "Kita sering pindah-pindah lokasi karena nggak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Nggak aman."
"Apalagi buat pulang." Ryujin menunduk memainkan jari-jarinya. Perbedaan gadis-gadis baru itu terlihat sangat jelas karena nada naik-turun dan intonasi yang Giselle pakai lebih lembut dari temannya. "Ke manapun aku belok, kayaknya aku selalu ketemu monster. Kalian beruntung."
"Uhm, aku harus bilang itu nggak bener." Memamerkan lengannya, Renjun memperlihatkan perban yang melingkar di sana dan belum boleh dilepas oleh dokter pribadinya. "Kita semua punya kisah yang nggak kita angkat ke permukaan."
Bila diperhatikan, 2 orang yang berinisial sama itu tampak seperti gambaran yang berbeda dari 1 objek tunggal. Renjun si matahari terbit, dan Ryujin si matahari terbenam yang menyanggah, "Seenggaknya kalian punya senjata bagus di sini一"
Renjun terbatuk. "Senjata-senjata itu di dapet dari polisi yang gagal evakuasi sekolahku."
"Dan." Ryujin hanya setengah menyimak perkataan si pirang. "Jumlah kalian lebih banyak. 6 lebih baik daripada 2."
"Tapi dulunya," cicit Giselle pelan. "Kita nggak berdua. Sebelumnya kelompokku terdiri 5 orang, 3 di antaranya Karina, Sungchan, dan Shotaro."
Wajah Ryujin tertekuk sedih. "Udah berapa lama kalian ada situasi tanpa rumah? Apa kalian udah tahu kalau bukan cuma monster yang wajib kita waspadai?"
Mark dan Renjun bertukar pandang. "Kurang lebih."
"Dunia ini gila. Kata pepatah, sifat asli seseorang bisa dilihat waktu dia ada di kondisi terdesak, dan itu bener. Banyak orang yang ngelakuin apa aja buat makanan dan kekuasaan. Aku udah ketemu salah satunya, namanya Aru."
"Si一siapa?" Nama itu membuat Renjun gelagapan.
"Aru." Ryujin menegaskan sekali lagi. "Kim Aru. Kenapa? Kamu kenal?"

Catatan sj ya kawand2, alamat2 di sini kagak sesuai sama alamat Seoul yang asli, karena seringnya gua cuma asal nyatet dari drama yang gua tonton xixixixixi 😳
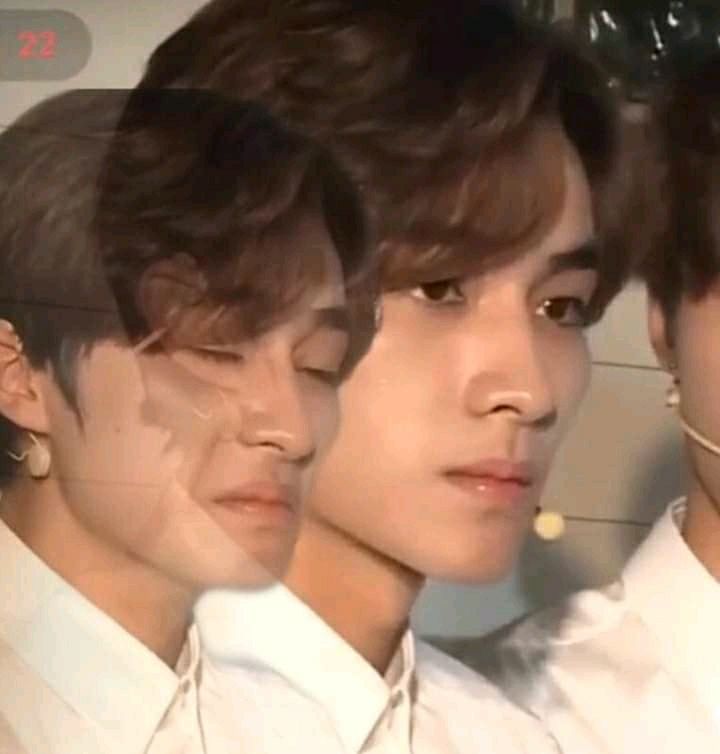
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top