|30| Inilah Jalan Kita
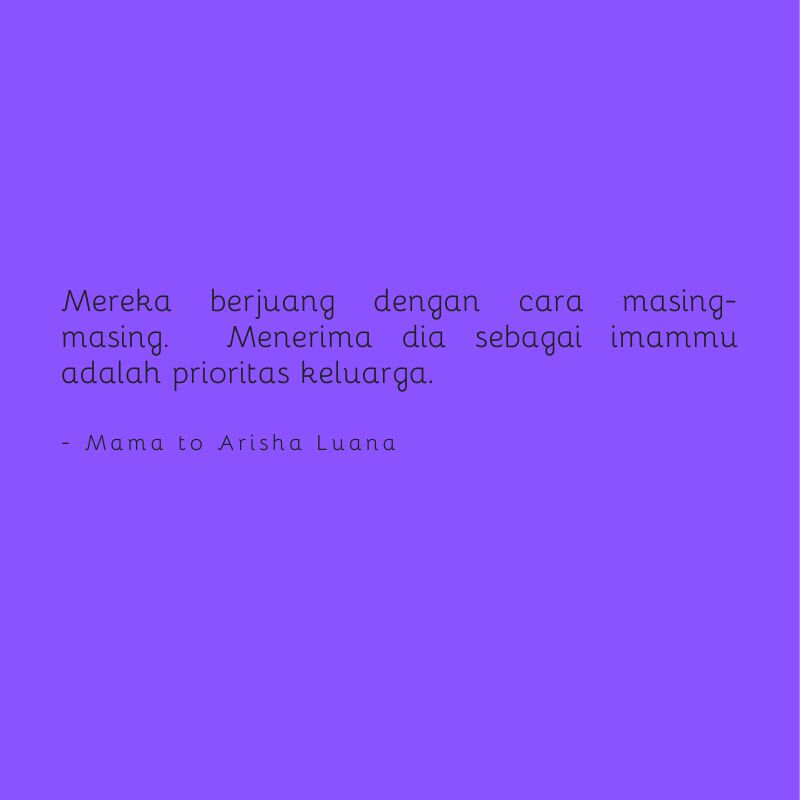
(Petunjuk: Baca pelan-pelan. Banyak informasi penting ada di chapter ini.)
*
Buton, Sulawesi Tenggara, Juni 2019.
Semarak perayaan hari besar agama Islam menggema di seluruh desa. Jalan-jalan padat oleh rombongan keluarga yang saling mengunjungi guna menyambung silaturahim. Rumah kami tak kalah meriah. Silih berganti tamu berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah rekan atau siswa Bapak.
Aku sibuk membantu Mama di dapur. Beliau tengah memasak gulai daging, akulah yang bertugas menyuguhkan minuman kepada tamu.
Fauzan entah pergi ke mana. Mungkin dia tengah keluyuran bersama kawan-kawannya.
Aku mengantarkan nampan dengan hati-hati. Gelas berisi es buah berjejer di atasnya. Aku berdehem singkat untuk membunuh rasa kikuk. Terasa aneh ketika kulihat Rafid mengisi salah satu kursi.
Kurasakan semua mata tertuju padaku. Ada empat orang termasuk bapak. Mereka mantan siswa beliau.
Aku meletakkan nampan hati-hati. Dari sudut mata, kulihat Rafid tengah menunduk. Benar kata Fauzan, penampilan Rafid berubah drastis.
"Maaf, ya. Ini si Rafid sejak kamu datang kerjaannya menunduk. Takut hafalannya buyar," cetus salah seorang kawan Rafid.
Mukaku sontak memerah, derai gelak ringan memenuhi ruang tamu. Aku buru-buru undur diri.
Aduh, lelucon semacam itu sangat rentan bagi hati yang lemah.
Aku merasa agak canggung berjumpa lagi dengan pemuda itu. Kemungkinan dia pun begitu. Senyumnya tampak kikuk saat kami tak sengaja berpapasan di jalan, tipis dan bola matanya bergerak ke sembarang arah. Aku tahu karena pernah sekali memperhatikannya.
"Siapa yang datang?" Mama bertanya begitu aku tiba di dapur.
"Rafid sama teman-temannya."
"Lho, kenapa dia sudah datang?"
Aku mengernyit samar. "Maksud Mama?"
"Ah, bukan apa-apa. Es buahnya masih banyak?"
Aku mengedikkan bahu. "Tinggal sedikit."
"Aduh, kita kehabisan stock sirup. Coba kamu cek warung di depan, sudah bukan atau belum."
"Mana ada warung yang buka lebaran begini, Mama?"
"Cek saja. Siapa tahu tamu si pemilik warung disuruh ke sana, kan?" perintah Mama. Kuembuskan napas pelan. "Oi, lewat situ, jangan ke ruang tamu." Mama menunjuk pintu dapur menggunakan dagu.
Aku bergegas tanpa berkata-kata lagi.
Hah! Aku juga pengen main ke rumah teman-temanku sewaktu sekolah. Hari raya, dan aku malah terjebak di dapur.
Ah, ya sudahlah. Aku bisa pergi di lain hari.
Oh, mungkinkah kalian bertanya-tanya tentang kelanjutan lamaran Dani tempo hari?
Aku akan mengikuti saran Aurel. Memastikan perihal asal-usulku terlebih dahulu, barulah membahas soal pernikahan. Aku juga belum mengklarifikasi perkataan Fauzan kepada orang tua kami.
Rencananya, aku akan berbicara dengan mama secara personal. Sayangnya, belum ada waktu yang tepat. Mama terlalu sibuk akhir-akhir ini.
Hah! Sudah dua kali aku mendesah lelah dalam rentang waktu tak cukup 30 menit.
Aku balik badan. Sudah kuduga warungnya tutup. Mama ada-ada saja.
Kubuka pintu dapur tanpa permisi. "Nggak ada, Ma."
Mama melirikku. "Kalau begitu, jerang air buat bikin teh."
"Siapa yang mau minum teh cuaca panas begini, Mama?"
"Ya, tinggal ditambahkan es batu, toh, Arisha."
Aku mendengus dalam hati. Risiko jadi anak sulung. Dasar si Fauzan, ke mana perginya saat-saat seperti ini?
"Habis itu kasih tahu bapakmu. Suruh pindah ke ruang tengah itu bujang-bujang. Ajak makan."
Aku membeliak. Oi, yang benar saja! Mereka akan mempersulit akses ke kamarku kalau begitu. Aku ingin istirahat sebentar. "Eh, buat apa kasih makan mereka?"
"Tenang saja, Arisha. Tidak akan habis ini gulai."
"Tidak usah, Ma. Mereka pasti masih kenyang."
"Tidak boleh pelit. Sudah, sana susun piring di meja. Kalau mau, kamu juga boleh ikutan makan."
Ogah. Makan di meja yang sama dengan Rafid? Aduh, bisa-bisa hilang selera saking canggungnya.
"Cepat, Arisha!"
Hah!
Saat itu, aku mendekam di dapur. Makan sendirian sambil memandangi air laut dari jendela. Tertahan hingga rombongan Rafid pergi.
Nasib.
*
Aku mengetok kepala Fauzan gemas. Dia baru muncul ketika bayang-bayang mulai samar, saturasi sinar jingga semakin tajam menghiasi langit. "Dari mana saja, hah?"
Fauzan cengengesan. "Di mana bapak, Kak? Jangan marah-marah, lah. Baru juga selesai puasa, sudah nambah dosa lagi."
Aku menggeram. Fauzan menyalami tanganku cepat-cepat, mencium takzim. "Mohon maaf lahir dan batin, Kak."
"Telat, oi!"
"Tak apa, daripada tidak sama sekali." Fauzan menjawab santai. "Di mana bapak?"
"Ada di kamar sama mama."
"Mereka bikin apa?"
"Mana aku tahu, Fauzan?"
Fauzan tergelak sambil berlalu. Aku mengekor di belakangnya. Fauzan mengetuk pintu kamar orang tua kami tanpa ragu. Bapak keluar, disusul oleh Mama.
"Sudah siap?"
Fauzan mengacungkan jempol. "Berangkat sekarang?"
Bapak mengangguk. Tanpa banyak bicara, beliau menuju pintu keluar.
"Mau ke mana, Pak?" tanyaku penasaran.
"Rumahnya Pak Dosen."
"Buat apa?"
Bapak memandangiku sejenak, lalu menarik napas seraya berkata, "Coba-coba cari link biar Fauzan ada peluang lulus jalur mandiri di Universitas K. Jaga-jaga kalau tertolak SBMPTN."
Aku mendelik ke arah Fauzan. Dia pura-pura tak melihatku. Sebetulnya, aku ikut sedih waktu dia tertolak di SNMPTN, bahkan sudah gagal dalam pemeringkatan nilai tingkat sekolah. Namun, itu konsekuensi yang harus dia terima atas seluruh tindak-tanduknya.
"Semoga berhasil, Ozan," kataku tulus, tapi Fauzan malah memandangku curiga.
"Ya sudah. Kami pergi. Balik setelah Isya. Sekalian mau salat di masjid."
Sepeninggal mereka, aku melirik mama diam-diam. Kutelan ludah susah payah. Ini kesempatanku. "Mama sibuk?"
"Tidak kecuali kalau ada tamu lagi."
Aku berdehem. Tenggorokan mendadak gatal. "Aku mau ngobrol-ngobrol, boleh?"
"Boleh, mau ngobrol apa?"
Aku bersorak dalam hati, menyemangati diri sendiri. "Di kamarku saja, Ma. Biar lebih enak ngobrolnya."
Kami jalan beriringan. Kututup pintu kamar. Duduk di tepi ranjang. Aku harus mulai dari mana?
Mama menatapku heran. "Kenapa mukamu pucat? Kamu sakit?"
Aku menggeleng kuat-kuat. Berdehem sekali lagi, "Ma," panggilku, "Fauzan itu adik kandungku kah?"
Mama kelihatan kaget, tetapi dengan cepat menutupinya. "Ngomong apa kamu, Arisha?"
Aku menjilat bibir. "Setelah kupikir-pikir, mukaku kok beda sendiri, ya, Ma? Mirip Mama sedikit, tapi tak ada mirip-miripnya sama Ozan, apalagi Bapak."
"Memangnya satu keluarga harus mirip semua?"
Napasku mulai berat, bola mataku memanas. "Ma, aku ... udah tahu ra-rahasia pernikahan kalian."
Mama memicing. Aku bergerak gelisah. Ini berat, tetapi harus kukatakan. "A-aku ... peduli setan sama bapak bilogisku. Dia tidak penting. Tak ada gunanya aku tahu siapa dia. Demi Allah, aku bahagia tinggal sama Mama-Bapak, ta-tapi, Ma, a-apa benar ... aku bukan anak Bapak?"
Belum sempurna kalimat terucap, Mama sudah meringsek ke arahku. Kedua pundakku dicengkeram kuat. "Ngomong apa kamu, Arisha?!" sergahnya cepat.
Aku meringis pelan. Mataku sudah basah. Kaget melihat raut muka Mama. Beliau menggeram, bola matanya melotot. Pertama kali kusaksikan ekspresi demikian. "Sa-sakit, Ma."
"Tahu dari mana kamu masalah itu?!" Mama mengguncang bahuku. "Jawab, Arisha!"
Aku tergugu. Mama yang kukenal bukan begini. Beliau sering mengomel, tetapi tak pernah dengan raut bengis. "Jadi, benar, ya? Oma yang bilang. Beliau dengar Mama-Bapak berbincang sewaktu awal menikah dulu."
Hatiku rasanya perih. Aneh, padahal aku sudah tahu, tetapi masih saja sesakit ini.
Mama kelihatan linglung. Cengkeraman di bahuku lepas. Beliau mundur pelan-pelan, jatuh terduduk di atas kasur.
Aku menggigit bibir demi mengurangi sesak. Jantungku berdenyut-denyut. Rasanya dingin, jari-jariku gemetar. "Kenapa ... a-aku berhak tahu tentang asal-usulku. Ini berpengaruh buat masa depanku, Ma. A-aku ... tak ingin ketahuan saat mau menikah."
Mama masih diam, tertunduk dalam. Ribuan pertanyaan bermain-main di kepalaku, berisik. "Dari kecil aku selalu bertanya-tanya, kenapa Bapak galak, dan Mama lebih banyak diam. Ternyata ... aku," isakkanku menghiasi seluruh ruangan, "bukan anak beliau. Wa-wajar kalau beliau cuma sayang Fauzan."
Air mataku berurai. Aku tersedu-sedu. Seperti ada tangan gaib yang meremas jantungku. "Ugh."
Aku tak tahu mengapa Mama tiba-tiba memelukku. Beliau menggeleng kuat. Aku mendengar tangisnya. Perasaanku semakin tak keruan. Kupegang erat-erat ujung bajunya.
"Jangan bicara begitu, Arisha. Rasa sayang bapakmu luar biasa buat kita. Lihat dirimu, Nak. Pernah merasa kebutuhanmu terabaikan? Kamu disekolahkan tinggi-tinggi. Bapakmu berharap kamu jadi contoh buat Fauzan.
"Mama yang salah, Arisha. Maaf, maaf karena punya mama model begini. Kamu harus lebih baik, jangan jadi kayak Mama. Tidak bisa memberi contoh yang baik, bahkan tidak pantas punya suami sebaik bapakmu."
Aku meraung. Dekapan Mama semakin kencang. Pedih sekali mendengar beliau bicara seperti itu. Luka di hati Mama jauh lebih banyak. Aku merasa berdosa karena mengungkit-ungkit masa lalunya.
"Maaf, maaf, bukan begitu maksudku. Mama dan Bapak orang tua paling baik. Aku sayang kalian. Maaf karena udah lahir ke dunia dan bikin susah."
"Ya Allah, Arisha! Ngomong apa kamu, hah? Kamu tidak bersalah. Jangan pernah merasa minder. Kami membesarkanmu dengan kasih sayang." Mama menjauhkan tubuhku.
Takut-takut, kupandangi wajah beliau. "Mari kita lupakan saja masalah ini, oke? Mama mohon jangan ungkit soal ini di hadapan bapakmu, Nak. Jangan sekali-kali."
Aku tergugu. "Ma, ta-tapi cepat atau lambat aku pengen menikah. Bapak tidak mungkin jadi waliku. Orang-orang akan tahu dengan sendirinya."
Mama menggeleng tegas sambil mengusap rambutku. "Iya, biar kami yang menyelesaikan. Ini urusan orang tua."
Aku menunduk dalam-dalam. "Maaf."
Mama mencium dahiku. Rasanya hangat. Kapan terakhir kali kami sedekat ini?
"Kamu tenang saja. Tidak perlu pusing. Sudah kami pikirkan solusinya." Mama menangkup pipiku. "Nah, mending sekarang kamu mandi. Dandan yang cantik. Nanti malam Rafid sama orang tuanya mau ke sini."
Aku menyorot bingung. "Buat apa, Ma?"
Mama tersenyum lembut. "Ya, sudah jelas, 'kan? Buat apa lagi laki-laki bawa-bawa orang tuanya ke rumah perempuan?"
Aku berkata ragu, "Tidak mungkin kayak yang aku pikirkan, Ma?"
"Kalau yang kamu pikirkan lamaran, memang sudah itu tujuannya."
Aku menganga. Shock berat. "Mana bisa begitu?!" seruku tanpa sadar.
"Lho, memang kenapa?"
"Seorang laki-laki tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya, sampai dia menikahi atau meninggalkannya."
Mama memandangku bingung. Mengerjap pelan. Aku membuang muka, agak malu. "Dengar-dengar, Dani main ke sini?"
"Ah, maksudmu laki-laki itu? Fauzan yang cerita sama kamu?"
Aku mengangguk cepat. Mama geleng kepala. "Pantasan rajin sekali dia tanya-tanya soal lamaran si Dani. Namun," ujar Mama, "apa hubungannya dengan lamaran Rafid?"
"Eh, itu ... ya, lamaran dia masih ditangguhkan. Belum ada kepastian. Entah jawaban Bapak, maupun keputusan dari Dani. Aku baru dibolehkan nikah setelah lulus magister, kan?"
"Tidak percis begitu. Fauzan mana paham cara bicara orang dewasa. Kamu sudah mengerti, bapakmu bukan wali sah secara agama. Beliau tidak bisa dengan tegas menerima atau menolak. Lagi pula, si Dani sepertinya langsung paham. Dia bilang sendiri, meski sudah datang melamar, tapi sama sekali tidak ada ikatan. Paham maksudnya? Kamu boleh menikah dengan orang lain, begitu pula dengan dia. Kalian bebas. Jadi, keraguanmu itu tidak berlaku.
"Beda kasus dengan Rafid. Sekarang kamu ada di rumah. Bisa langsung menjawab secara tegas. Kamu siap?"
Aku menggeleng. Ini gila. Aku tidak mau menikah dengan laki-laki selain Dani. "Ma, mereka belum tahu asal-usulku. Mama yakin Rafid dan keluarganya mau punya menantu sepertiku?" tukasku sengaja mengungkit perihal ini. Aku tengah mencari-cari alasan untuk menolak.
"Kemungkinan itu juga berlaku buat Dani, Nak. Salah satu alasan kami, aku dan bapakmu, kurang sreg sama dia. Lalu soal keluarga Rafid, kamu salah perhitungan."
"Maksud Mama?"
"Dulu sekali, waktu hamil kamu, Mama diasingkan. Menurutmu, apa orang-orang desa tidak akan bertanya-tanya? Sederhananya, mereka yang sejak dulu sudah tinggal di desa kita, tentulah tahu masalah Mama.
"Asal kamu tahu, Arisha. Mama pernah dicibir warga satu kampung, tapi lama-kelamaan mereka mulai lupa dan menerima, sebagaimana kehidupan kita detik ini. Kejadian itu sudah lebih dari dua puluh tahun, mereka sudah tidak peduli, meski beberapa mungkin masih belum menerima baik.
"Dengan kata lain, keluarga Rafid tidak keberatan, Arisha. Begitu pula si Rafid. Fakta kalau kamu bukan darah daging bapakmu, biarlah itu jadi rahasia. Orang-orang tidak akan berpikir sampai ke sana. Sebisa mungkin aib harus ditutup, Nak. Oma perlu diajak kerjasama."
"Ma, kemungkinan itu juga berlaku buat Dani dan keluarganya.
Mama menggeleng tegas. "Sama sekali tidak. Mereka bukan warga sini. Mana tahu persoalan kampung kita?"
Aku menggigit bibir bawah. Mencari argumen-argumen lain. "Mama sama Bapak bukannya membenci Rafid? Aku pernah dimarahi waktu pacaran sama dia, kan?"
"Itu dulu, tapi sekarang dia sudah berubah. Daripada dikatakan marah, kami sebenarnya khawatir. Kalian terlalu dekat. Kami takut kalian tergelincir."
"Ta-tapi, aku tidak dimarahi saat pacaran dengan Dani?"
"Kalian pernah pacaran? Mama pikir cuma akal-akalan Ozan buat ganggu kamu."
Aku menggerutu dalam hati. Memang cuma sekali Dani mengantarku sampai di depan rumah, di pertemuan pertama kami. Selanjutnya, kami selalu janjian di luar. Entah di jembatan penghubung, atau di sudut lain desa. Intinya, jauh dari pengawasan orang tua. Aku mengusulkan itu gara-gara kapok kena marah sewaktu pacaran dengan Rafid. Pasalnya, bersama Rafid, mungkin karena kami tetangga, sering terlihat berduaan di sekitaran rumah.
Aduh, aku harus bagaimana lagi?
"Em, aku ... sukanya Dani," cicitku malu. Sudah Tidak ada pilihan lain.
Mama menatapku penuh perhatian. Rambutku dielus berkali-kali. "Coba kamu pikirkan lagi, ya? Tak banyak keluarga laki-laki yang mau menerima perempuan apa adanya. Selain itu, Nak, apa kamu mau masa lalu itu terus diungkit-ungkit?"
Aku bungkam seketika. Kehabisan kata-kata. Tak punya argumen lain. Karena memang, aku sadar betul, perkataan Mama tak terbantahkan.
"Arisha, perlu kamu tahu, Rafid benar-benar serius sama kamu. Mamanya sempat menolak keinginan untuk menikahimu, bahkan sampai menjelaskan borok keluarga kita, dia tetap kukuh. Mamanya dibuat luluh. Jauh sebelum Dani menemui bapakmu, Rafid sudah lebih dulu berjuang, meski dengan cara berbeda.
"Jika Dani gagah berani menemui bapakmu sendirian, maka Rafid cerdik dengan meminta bantuan orang tuanya untuk mendekati orang tuamu, sembari dia memperbaiki diri. Ini bukan soal balas budi, tapi prioritas, Arisha. Dani boleh jadi mau menerimamu, kamu pun mencintai dia, tapi keluarganya belum tentu begitu. Sementara Rafid, meski hatimu bukan untuknya, tapi keluarganya rida jika kalian menikah. Mengubah hatimu lebih mudah daripada mengubah hati keluarga Dani, bukan?"
Tidak, ini tidak benar. Seharusnya aku dapat membantah kata-kata Mama, tetapi kenapa bibirku kelu?
"Nah, Arisha, maukah kamu mempertimbangkan Rafid sebagai calon imammu? Mama harap, jawabanmu iya. Kalian bisa melangsungkan ijab kabul secara tertutup untuk menjaga nama baik keluarga. Asal rukun nikah terpenuhi. Urusan resepsi, bisa menyusul belakangan."
Aku menekan gejolak di dada kuat-kuat. Mama benar, jika calon mempelai pria dan kekuarganya sudah menerima kami, ijab kabul dapat dilakukan secara tertutup, sehingga tidak akan mengundang omongan orang bila mendengar namaku disebut tanpa menyertakan nama Bapak. Tak kusangka orang tuaku merancang sejauh ini demi kebaikan keluarga kami.
Tarik napas, embuskan.
Mungkin beginilah jalan kami, aku dan Dani. Hijrah dan dakwah. Kami terpisah karenanya, dan kuharap kami pun disatukan di atas bahtera yang sama.
Akan tetapi, kini biarlah takdir memainkan perannya untuk kami.
~Original Story by Umul Amalia~
Next, epilogue.
Cek suara, yuk.
Pilih Dani atau Rafid sebagai pasangan Arisha?
Btw, gantung, ya? Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top