|27| Romansa Anak Kuliah
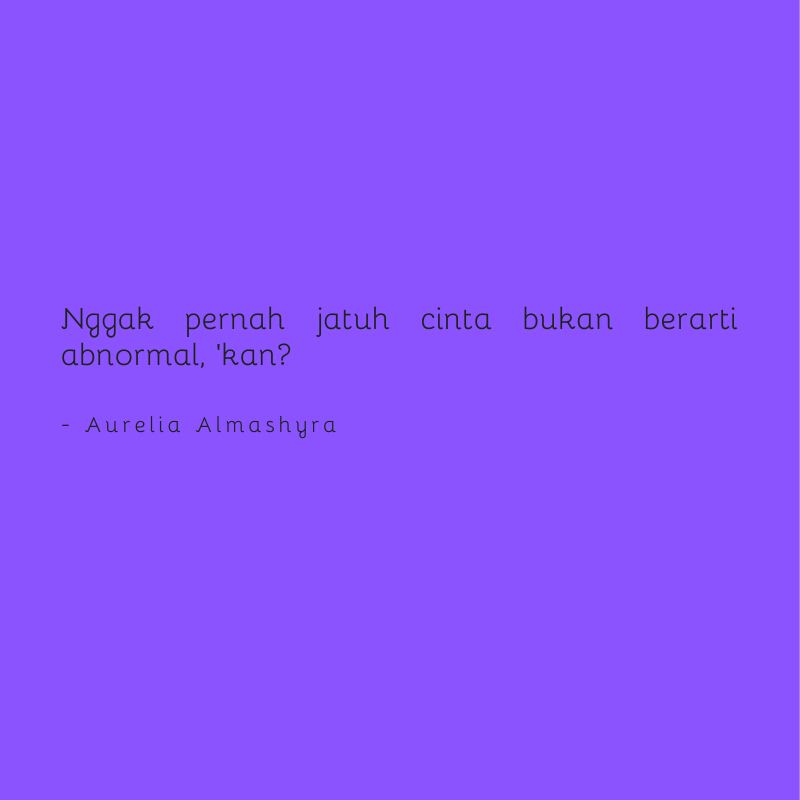
"Kupikir kamu sudah menikah, makanya nggak pernah masuk!"
Gelak tawa menyambutku ketika menginjakkan kaki di dalam kelas. Azel si ketua kelas menjadi provokator olok-olok pagi itu, sedangkan yang lain semangat menyoraki.
"Gimana liburanmu, asyik? Udah ada yang melamar ceritanya ini?" komentar salah seorang kawan.
Aku menggeleng. "Apaan, sih! Lamar, lamar! Kita masih semester 6, heh!"
"Ya, nggak pa-pa kali, Sha! Semester 6 itu udah pantas! Berarti ada peningkatan topik. Daripada si Azel, dari maba sampai sekarang kerjaannya PDKT mulu, kode-kode, nggak pernah dianggap."
"Kenapa aku ikut kena, hah?" Azel menyahut sewot.
Seluruh ruangan riuh lagi. Dosen belum datang. Aktivitas saling ledek ini tampaknya masih akan berlanjut.
"Maksudmu, Azel PDKT sama siapa? Eza?" Aurel bahkan tertarik menimpali.
"Siapa lagi?"
"Kamu salah perhitungan kalau gitu. Azel itu udah naksir Eza sejak kecil."
"Oi, Aurel, kenapa tiba-tiba bahas masa kecil?" Azel menggebrak meja. Kami terbahak, sedangkan Eza hanya cengar-cengir saja.
"Seriusan, Rel? Kasihan sekali kalau gitu ketua kelas kita ini," sahut teman-teman Azel sesama cowok. Aurel mengacungkan jempol.
Seru-seruan itu semakin jadi sampai dosen masuk. Kegiatan semacam ini sudah sering dilakukan sejak tiga tahun lalu usai kami saling mengakrabkan diri.
Rasa-rasanya, semua orang kena kecuali Aurel. Gadis ini memang sudah menunjukkan perbedaan sejak pertama kali masuk. Susah sekali menemukan cacat Aurel selain kata-katanya yang terlampau pedas, apalagi untuk urusan percintaan.
Selama tiga tahun ini, belum pernah kudengar Aurel menyinggung-nyinggung masalah lawan jenis. Bahkan, ketika kemunculan Pak Alvarendra menghebohkan nyaris seluruh mahasiswi, Aurel cuek saja. Aku jadi penasaran, apakah Aurel pernah jatuh cinta?
Seringaiku mengembang. Kutanyakan saja hal itu padanya. "Rel," bisikku sambil tetap awas mengamati dosen. Aurel bergumam. "Kamu pernah jatuh cinta?"
Aurel menoleh. Dahinya berkerut samar. Memandangku agak lama. "Menurutmu, aku nggak normal?"
Aku menyengir bodoh. Redaksiku salah. Kugaruk pipi pelan. Aurel sudah kembali fokus mendengarkan perkataan dosen. Aku kehilangan momentum. Tekadku bulat. Lain kali aku harus berhasil mengorek kisah romantisme Aurel. Anggap saja sebagai amunisi bila dia mulai mencecarku dengan argumen-argumennya, pengalih perhatian. Sayang, Aurel terlalu ahli dalam mengabaikan orang, aku belum berhasil mengulik-ulik kisah cintanya.
*
Pagi memelesat cepat, siang menjelang, begitu pula sore berganti malam. Kesibukan tiada terkira membunuh waktu. Tanggung jawab akademik kian berat. Seluruh mahasiswa semester 6 diwajibkan mengambil mata kuliah Seminar Proposal.
Asal-usulku masih melekat dalam benak. Luka itu tetap ada, menjadi bagian dari diriku. Hubunganku dengan Mama kembali seperti semula. Sehari setelah nasihat Aurel waktu itu, aku menelpon Mama. Beliau mencecarku dengan banyak pertanyaan. Aku yang sulit dihubungi, membuat khawatir keluarga. Kujadikan kesibukan sebagai alasan. Sibuk meratap, maksudku. Tentu aku tidak menjelaskan secara detail kepada beliau.
Bapak tetap sebagaimana dirinya. Hubungan kami masih begitu-begitu saja. Menelepon ketika ada keperluan, misal, akhir bulan. Namun, sesekali, Mama mengatakan kalau Bapak bertanya kabarku padanya. Hal itu sudah membuatku senang. Setelah tahu asal-usulku, aku tak boleh banyak menuntut, bukan?
Fauzan tidak jauh berbeda. Kami masih sering berselisih. Saling ledek, saling tengkar. Hanya saja, anak itu menunjukkan gelagat aneh akhir-akhir ini. Ketika kami sedang bercakap lewat telepon, tanpa komando, tiba-tiba dia mengungkit masalah pernikahan. Seperti saat ini, misalnya.
Malam kesekian sejak aku tahu rahasia Mama-Bapak. Hari-hariku berjalan normal. Bimbingan seminggu dua kali, memegang tiga adik binaan, kerja kelompok, tugas-tugas individu, dan masih banyak lagi.
"Arisha, jawab pertanyaanku!"
Tangan Mama hinggap di kuping Fauzan. "Kamu sudah besar, yang sopan sama kakakmu!"
Wajah cemberut Fauzan memenuhi layar ponselku. Aku terkekeh puas. Panggilan video tengah berlangsung.
"Ma, si Ozan suruh nikah aja. Kayaknya dia nggak mau sekolah lagi. Kerjaannya bahas-bahas pernikahan." Aku memprovokasi. Fauzan mendelik sebal.
"Kakakmu benar, Ozan. Kamu masih kelas tiga SMA, buat apa singgung-singgung masalah pernikahan?"
"Aduh, Mama, aku cuma nanya, kalau ada laki-laki yang pengen datang lamar Arisha, maksudku, Kak Airsha, boleh apa nggak?"
Mama tergelak pelan. "Siapalah yang bisa larang anak orang datang melamar? Kamu ini ada-ada aja, Ozan."
Fauzan menyengir, aku menyorot curiga. Inilah pertanyaan yang menjadi obsesi Fauzan akhir-akhir ini. Aku tidak pernah meresponnya. Lagi pula, buat apa dia memusingkan perihal itu?
"Kalau orang lamaran, ada pestanya atau nggak, Ma?" Fauzan masih penasaran.
"Aduh, kamu ini, Ozan. Tergantunglah jenis lamarannya. Kalau si laki-laki datang sendirian, kita sebut lamaran secara pribadi, buat apa pakai pesta segala? Lain cerita kalau pihak keluarga sudah sepakat, kita sebut lamaran resmi, ah, itu baru pakai acara." Mama bersungut-sungut menjelaskan. "Memangnya anak gadis siapa yang mau kamu lamar?"
Fauzan tertawa bagaikan orang bodoh. Aku agak-agak khawatir dengan kondisi mental adikku itu. Apa tekanan siswa kelas tiga SMA zaman sekarang terlalu berat hingga otaknya jadi bermasalah?
"Ngomong-ngomong tentang pesta, Mama ada kabar baik buat kamu, Arisha."
Aku memusatkan perhatian kepada Mama. "Kabar apa, Ma?"
"Tadi Mama si Rafid datang ke sini. Bulan depan ada acara syukuran di rumah mereka. Mama diminta bantu persiapan."
Kerutan di dahiku muncul. "Apa urusannya sama Kak Arisha, Ma?" Fauzan menyambar. Kali ini aku tidak akan kesal.
"Tentu saja ada urusannya. Acara itu dalam rangka pulangnya si Rafid."
"Sudah lulus dan jadi hafiz berarti dia, Ma?" Fauzan masih menyela. Lagi-lagi aku tidak keberatan. Kami sepemikiran saat ini.
"Luar biasa memang. Percaya sama Mama, acara ini bakalan jadi ajang promosi anak gadis ibu-ibu sedesa. Nah, Arisha, kamu mau juga Mama promosikan?"
Aku melotot, Mama tergelak. "Oh, Mama lupa, kamu tidak perlu promosi. Kalian sudah pernah pacaran, bukan? Peluangmu lebih banyak, Nak."
Astaga. Kenapa Mama jadi terlihat menggilai Rafid?
"Nggak boleh gitu, Ma. Mereka 'kan sudah lama putus. Pacar terakhirnya Arisha itu Bang Dani." Fauzan menimpali semangat.
Oi, oi, ini kenapa mendadak mereka membahasa masa laluku? Sejak kapan pula Fauzan memanggil Dani dengan akrab begitu?
"Siapa itu Dani?"
"Mantannya Arisha, Ma. Tinggal di kampung tetangga. Kuliah di Kendari. Itu, lho, Ma, cowok yang bikin anak orang galau waktu masa-masa SMA awal." Fauzan melirikku.
Aku menepuk dahi. Malu sendiri saat teringat masa lalu. "Stop, stop! Kenapa bahas topik ginian? Aku matikan kalau gitu."
Fauzan dan Mama kompak tertawa mengejek. Tarik napas, embuskan. Ini bukan apa-apa. Tidak ada maksud tersembunyi. Mereka hanya kekurangan bahan lelucon. Ya, pasti begitu.
"Malu kakakmu, Ozan. Mari kita ganti topik saja."
Malam itu, kami mengobrol banyak hal. Fauzan menceritakan tentang rencana kuliahnya. Mama meninggalkan kami begitu Bapak pulang dari rumah temannya.
Tidak ada kecurigaan apa pun. Fauzan berhenti menyinggung masalah pernikahan. Setiap ada waktu mengobrol berdua begini, aku menyempatkan diri menyampaikan tentang Islam kepada Fauzan. Pelan-pelan, berharap dia pun mau berubah. Bukankah keluarga merupakan prioritas utama dalam dakwah?
Fauzan manggut-manggut saja. Terlihat paham betul. Tak banyak protes, hanya mendengarkan.
Tanpa terasa, waktu bergulir, bulan terpangkas, untuk kesekian kali ujian akhir semester manyapa. Dibandingkan kampus lain, kampus kami terbilang cepat libur. Seminggu usai UAS, masa-masa merepotkan bagi mahasiswa tahun ketiga berlangsung, jadwal pelaksanaan sidang proposal. Syukurlah segalanya berjalan lancar.
Pertengahan Mei. Usiaku sudah 21 tahun kala itu. Aku bukanlah mahasiswa dengan manajemen waktu secanggih Adiba, apalagi segigih Aurel untuk urusan akademik. Impianku sederhana, tidak muluk-muluk. Yudisium tepat empat tahun dengan IPK rata-rata— minimal lulus seleksi berkas CPNS. Cukup, itu saja.
Akan tetapi, ketika aku seusia itu, satu kabar mengejutkan datang dari rumah. Informasi yang mendadak membuatku ingin cepat-cepat lulus.
Aku ingat betul hari itu. Bulan puasa telah tiba, kepulanganku tertunda karena masih ada kegiatan organisasi. Selepas salat tarawih di masjid kampus, aku bergegas balik ke kost.
Badanku lelah, aku butuh istirahat agar mampu menjalani puasa esok hari. Mataku mulai terpejam, tetapi sial sekali, tiba-tiba ponselku berdering nyaring, buru-buru kuangkat. Fauzan menelepon. Tidak biasanya selarut ini.
"Halo, Zan, kenapa?"
"Halo, sebenarnya aku pengen ngomong dari sore, tapi sibuk bantuin Mama bawa takjil ke masjid, terus lanjut salat tarawih. Jam setengah sembilan udah selesai, mau nelepon, tapi baru ingat kalau di Malang beda satu jam. Kemungkinan kamu pun masih di masjid."
"Bentar, bentar, kamu mau ngomong apa, sih?" Aku langsung memotongnya. Terlalu bertele-tele.
Kudengar Fauzan cengengesan di ujung sana. "Aku punya kabar baik buat kamu."
"Apaan? Cepatan ngomong, aku ngantuk."
"Sabar dong, Arisha. Kamu siapin hati dulu."
"Astaga, aku matiin kalau kamu nggak ngomong dalam tiga puluh detik!"
Fauzan tertawa renyah. "Aku jamin malam ini kamu nggak bakaln bisa tidur."
"Oi! Jadi ngomong atau nggak?"
Fauzan berdecak. "Kak, tadi ada yang datang nemuin Bapak buat ngelamar kamu."
"Hah?"
"Dia datang sendirian. Hm, sebenarnya aku yang bantuin. Kamu harus berterima kasih sama aku. Jangan lupa oleh-oleh kalau pulkam."
"Ngomong apa, sih, kamu, Fauzan?"
Fauzan bercerita, aku mendengarkan dengan saksama. Dan benar saja, sesuai dugaannya, semalaman aku nyaris tidak bisa menutup mata. Terlalu sibuk mengurus degup jantung yang menggila.
Detik itu juga aku berambisi lulus semester tujuh.
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top