|24| Titik Nadir
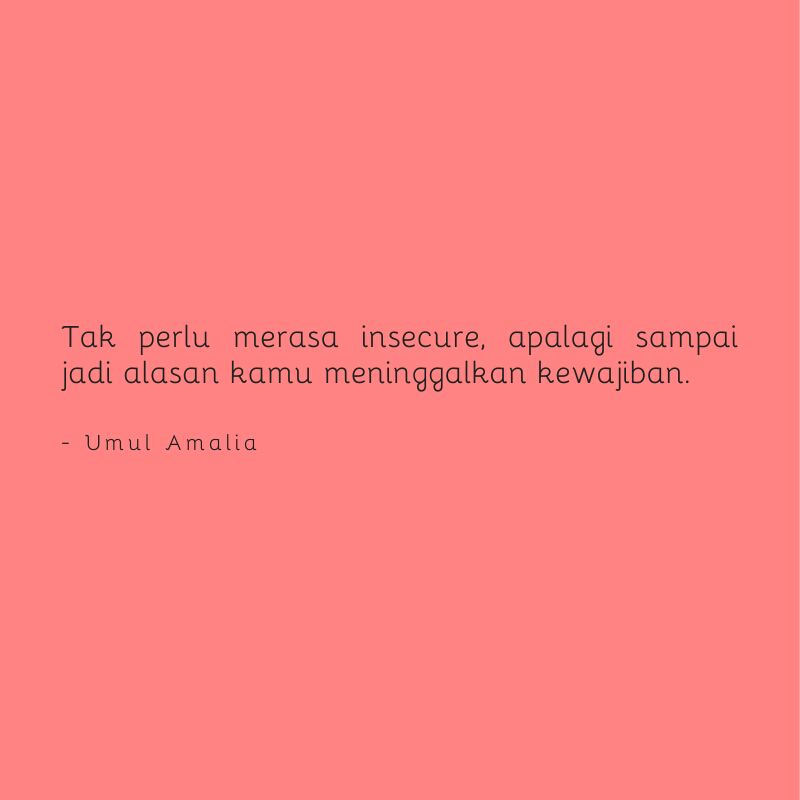
Akhir Januari 2019.
Sebulan berlalu sangat cepat. Besok perkuliahan semester genap dimulai. Tiga tahun sudah aku menyandang status sebagai mahasiswa.
Dua hari yang lalu aku balik ke Malang. Meninggalkan setumpuk kesedihan dari kampung halaman. Perasaanku masih belum membaik. Aku terlalu shock akan kebenaran yang disodorkan di depan mukaku.
Kuusap air mataku kasar. Rasanya bagaikan mimpi. Kupeluk diriku erat-erat. Aku tergugu. Sesak luar biasa.
Pertanyaanku selama ini terjawab sudah. Bapak yang bersikap dingin, Mama yang diam saja. Tak kusangka hidupku akan begini menyedihkan.
Di saat aku sudah bertekad untuk meniti jalan dakwah, kenyataan pahit justru menyambutku. Aku kehilangan rasa percaya diri. Tak pantas orang sepertiku menjadi aktivis.
Aku terus menangis. Menyesali keputusanku pulang kampung. Seandainya aku tetap di Malang, mungkin hatiku takkan sesakit ini. Aku akan terus hidup dengan baik. Tidak akan ada yang berubah.
Kini, segalanya terasa serba salah. Aku ingin mengutuk apa pun. Menyalahkan siapa saja yang membuat perasaanku kacau balau. Aku terisak. Lagi dan lagi.
Malam itu, entah berapa lama aku meratap, mengais-ngais impian di tengah kenyataan, berharap semua yang kudengar salah.
Akan tetapi, berapa lama pun aku berharap, sejauh apa pun aku berusaha ingkar, bahkan meski air mataku mengering, dadaku sedemikian sesak, di dalam mimpi sekalipun, takkan ada yang berubah. Fakta tetaplah fakta.
Hari-hari selanjutnya kujalani tanpa semangat. Aku hanya terbaring di atas kasur. Beranjak ketika lapar, ingin ke kamar mandi, atau melaksanakan salat.
Kuliah kutinggalkan, amanah kulupakan, dering ponsel tak sedikit pun menarik perhatianku.
Semua terasa percuma. Aku jijik pada diri sendiri. Kebanggaan yang kumiliki lenyap tak bersisa.
Aku berguling di atas kasur. Telentang. Suram. Nyaris tidak ada cahaya yang masuk ke dalam kamar.
Ah, sudah berapa lama aku seperti ini? Tanggal berapa sekarang? Kuraih ponselku sekilas. Genap seminggu.
Apakah belum waktunya untuk mati? Aku kehilangan makna. Tak ada gunanya. Segalanya kini terasa salah.
Aku mengerjap. Bola mataku bergulir. Ah, siapa yang datang mengunjungiku?
Kupejamkan mata. Tak peduli meski pintu kamarku terus diketok. Semakin lama gedoran di pintu semakin brutal. Biarkan saja.
"Aku tahu kamu ada di dalam! Buka pintunya, Arisha!"
Suara itu tidak asing. Siapa pun dia, aku ingin menemuinya. Perasaan ini terlalu berat kutanggung sendirian. Sayang, aku tak punya cukup keberanian. Jika terhadap diri sendiri saja aku jijik, apatah lagi orang lain.
Lengang. Gedoran di pintu berhenti. Kudengar bisik-bisik dari luar. Ah, ternyata lebih dari satu orang.
Kutarik napas berat. Pandanganku nanar tertuju ke arah langit-langit. Cairan bening menetes tanpa bisa kucegah. Kilasan masa kecil bermain-main di benak.
Tak banyak yang bisa kuingat. Hanya sepenggal memori menyakitkan. Usiaku sekitar tiga tahun saat Fauzan lahir. Aku benar-benar senang saat itu.
Akan tetapi, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika Fauzan semakin tumbuh, dia merebut segalanya dariku. Perhatian Mama, juga kepedulian Bapak.
Aku ingat betul saat usiaku tujuh tahun. Mama-Bapak meninggalkanku sendirian di rumah. Mereka terlalu khawatir akan kondisi Fauzan. Malam-malam, hujan di luar begitu deras. Mereka ke Puskesmas. Aku menangis ketakutan di rumah. Untunglah saat itu Paman—adik mamaku—segera muncul. Mungkin Mama yang memintanya untuk menjagaku. Beliau menenangkanku, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Sejauh yang kuingat, dari sanalah segalanya bermula. Fauzan selalu jadi yang utama bagi mereka. Fauzan yang bertingkah, aku yang disalahkan. Aku anak pertama, begitu yang senantiasa Mama ucapkan. Sampai sebulan yang lalu, pandanganku berubah. Ah, teryata Fauzan pun merasakan kecemburuan serupa. Biasa terjadi dalam hubungan saudara sedarah.
Kupikir segalanya berangsur-angsur membaik. Sikap Bapak memang tidak bersahabat, tetapi beliau menyayangiku. Mungkin Bapak tipikal orang yang susah mengekspresikan perasaannya. Bukankah laki-laki sering begitu?
Hatiku menghangat, kerinduanku akan kampung halaman semakin kuat. Kuputuskan untuk pulang.
Sayang, kebahagiaan mungkin memang bukan milikku. Belum lama aku rela terhadap perlakuan yang kuterima selama ini, kenyataan pahit justru muncul menghancurkan segala ekspektasi.
Alasan sikap Bapak, kediaman Mama, bukanlah karena aku anak pertama, atau Bapak susah mengekspresikan rasa, ada yang lebih besar, lebih kelam dari itu semua.
Brak!
Aku menoleh lemah. Aurel menatapku nyalang, Eza mematung di belakangnya.
Air mataku belum kering. Dadaku kian sesak. Alasan yang sesungguhnya, rahasia kelam yang diam-diam disembunyikan orang tuaku, meski hatiku berdarah-darah, harus kuterima dengan lapang dada.
Karena memang, aku menjijikkan. Anak haram sepertiku tidak pantas bahagia.
Aku tersenyum pahit. Lelah.
Laki-laki yang kupanggil "Bapak", yang kusayangi dengan sepenuh hati, bukanlah ayahku. Itulah alasan logis dibalik semua sikap dinginnya.
"Ya Allah, Arisha, kamu kenapa, hei?!" Aurel menepuk-nepuk pipiku. Eza bergegas menyingkap gorden.
Aku bangkit. Aurel membantuku minum. Kuterima tanpa perlawanan. Tidak, aku tidak sakit. Kondisi fisikku baik-baik saja. Seratus persen sehat. Batinku yang terluka, psikisku mungkin cedera.
Aurel mengembalikan gelas ke tempat semula. Aku duduk dalam diam. Dia menarik kursi plastik ke tepi ranjang. Kami berhadap-hadapan.
"Za, makasih, ya?" Aurel menoleh kepada Eza. Gadis itu memandangi kami saling bergantian. Mungkin dia bingung. "Bisa minta tolong kembalikan kuncinya ke pemilik kost? Aku yang bakalan bicara sama Arisha."
Eza mengangguk. "Cepat sembuh, Sha," tukasnya sebelum berlalu. Eza menjauh. Pintu tertutup. Tinggallah aku dan Aurel di dalam kamar.
"Makan." Aurel menyodorkan roti. Lagi-lagi kuterima tanpa banyak protes. "Kamu ke mana aja? Orang-orang pada nyariin. Nggak di kelas, nggak di organisasi, semua nanyain kamu."
Bergeming. Kukunyah roti lambat-lambat. Enggan menjawab.
"Aku nggak tahu apa masalahmu, tapi kayaknya berat. Kamu sampai nggak masuk satu minggu." Aurel mengeluarkan buku dari dalam tasnya. "Mungkin karena kita udah semester enam, dosen-dosen nggak terlalu repot sama urusan kontrak perkuliahan. Beberapa bahkan langsung ngasih tugas. Kamu bisa lihat instruksinya di catatanku."
Aku menerimanya. Aurel tetap seperti dirinya yang biasa. Sangat peduli akan urusan akademik.
"Kupikir kamu masih di kampung. Lupa balik karena terlalu betah. Untung ada Eza yang sekost denganmu. Dia yang pertama heboh di kelas. Kamu mirip robot, ditegur diam saja, begitu katanya. Cuma kelihatan sesekali pas waktunya makan siang."
Aku memalingkan muka. Setahun yang lalu Eza pindah ke indekos ini. Dia ada di lantai satu, sedangkan aku di lantai tiga.
"Sebenarnya aku agak malas ke sini, tapi Adiba yang maksa. Oh, roti yang kamu makan dia yang beli. Salam dari Adiba. Cepat sembuh, begitu katanya. Dia belum sempat datang. Maklum, dia kabid rangkap mentor. Di tempat pengajian, dia juga udah jadi musyrifah. Banyak urusannya."
Aku memberengut. Lama-lama kesal juga mendengar tutur katanya. "Jadi, kamu nggak ikhlas datang ke sini? Pulang aja, sana!"
"Aku bakalan pulang setelah tahu apa masalahmu. Kamu paham sendiri kondisi LDK saat ini. Angkatan 2015 udah keluar. Pembinaan agak keteteran. Kita butuh mentor tambahan untuk mengurus semua anggota. Kalau kamu kayak gini, gimana nasib dakwah kita? Ah, seharusnya Adiba yang menyampaikan ini, tapi karena kamu nggak respon, jadi terhambat. Coba cek WhatsApp-mu. Aku yakin dia udah ngajak kamu ketemuan."
"Tahu dari mana?"
"Adiba yang bilang. Jangan bikin dia tambah pusing. Mari sama-sama berusaha, yang lain udah nunggu."
"Menurutmu, aku cuma jadi beban?" tanyaku langsung tanpa rasa sungkan.
"Aku nggak ngomong gitu."
"Jelas-jelas barusan kamu ngomong gitu. Fine, kalau emang cuma jadi beban, aku bakal keluar dari organisasi!"
Aurel menatapku lama. "Apa masalahmu? Kenapa tiba-tiba gini?"
"Apa pun masalahku, kamu nggak akan ngerti!" seruku emosional.
"Aku emang nggak ngerti, mungkin juga nggak bakal paham gimana perasaanmu, tapi aku bersedia mendengarkan."
Ada yang mendengarkan, itu yang kubutuhkan. Aku tahu Aurel hanya peduli pada organisasi. Dia merasa terganggu akan ulahku seminggu belakangan. Namun, segampang itu aku dibuat terenyuh. Bukan hal mudah mendengarkan cerita orang lain tatkala hati tak sedikit pun peduli.
Aku menarik napas dalam-dalam. "Mungkin kamu akan jijik setelah ini, tapi makasih karena bersedia dengerin. Ini adalah aib, nggak seharusnya kuceritakan. Aku cuma nggak sanggup mendam sendirian. Di masa depan, kalau kita bertengkar, tolong jangan bocorkan ceritaku kepada siapa pun."
"Cerita aja, udah. Panjang banget pembukaanmu."
Aku berdecak. Manusia satu ini rupanya tidak tahu cara bersimpati. Sial, di kala aku butuh sesuatu, kenapa dia sering jadi orang pertama yang muncul?
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top