|23| Kabar dari Rumah (b)
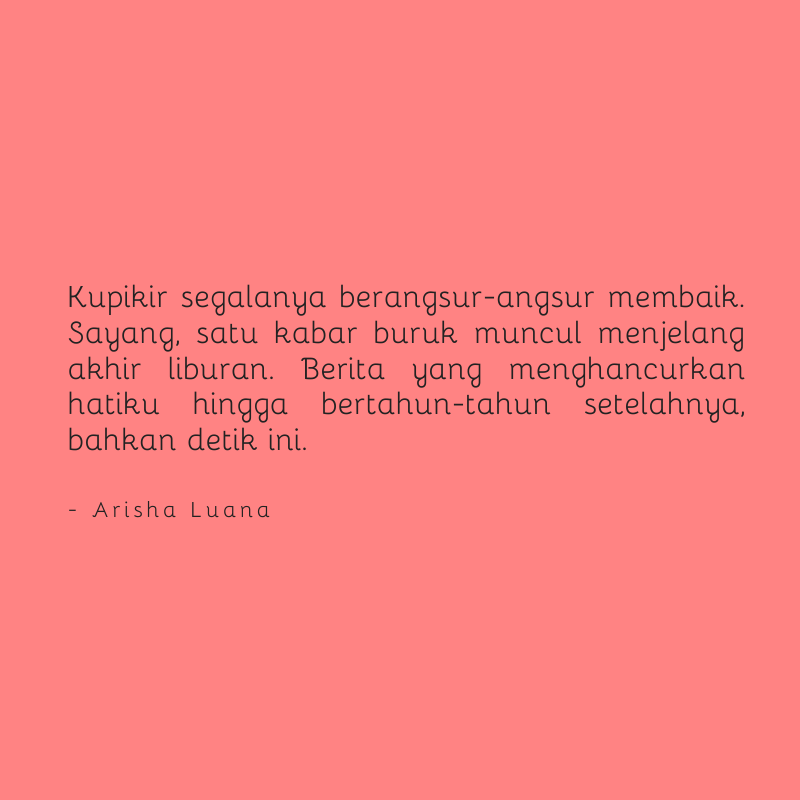
Mama menelponku lagi keesokan harinya. Fauzan sudah pulang. Mama sengaja memasak makanan kesukaan anak itu. Bapak tidak banyak berkomentar. Kata Mama, suasana rumah berubah jadi canggung. Hampir tidak ada yang saling bicara di meja makan. Aku menenangkan beliau dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Mereka hanya butuh waktu untuk mengurai segala emosi negatif.
Sudah empat hari terlewati. Aku masih saja sibuk dengan tugas-tugas kampus dan kegiatan organisasi. LDK akan mengadakan bazar di awal September. Program tahunan yang digelar untuk umum.
Siang itu, kami tidak jadi kuliah. Dosen berhalangan hadir. Ada tugas di luar kota, begitu yang disampaikan Azel si ketua kelas. Oleh karena itu, aku dan Aurel memutuskan main ke sekretariat Kemuslimahan LDK. Kebetulan beberapa panitia sedang berkumpul untuk mendesain isi stand Bidang Kemuslimahan. Ada sekitar 7 orang termasuk kami.
Dalam organisasi yang kuikuti, laki-laki dan perempuan memang dipisahkan sedemikian rupa. Pemimpin tertinggi adalah Ketua Umum, dibantu Sekertaris Umum dan Bendahara Umum, serta lima Bidang penunjang. Salah satunya Bidang Kemuslimahan, tempat semua anggota perempuan berkumpul.
Selain struktur organisasi yang seolah terpisah, kantor kesekretariatan berbeda, jalur koordinasi juga dijaga sedemikian ketat. Antara laki-laki dan perempuan, hanya Ketua Umum dan Kepala Bidang Kemuslimahan yang boleh berkomunikasi. Lewat handphone, tentunya.
Di Bidang Kemuslimahan sendiri ada tiga departemen, Infokom, Kreativitas, dan Pembinaan. Aku dan Aurel ada di Kreativitas. Itulah kenapa urusan kami tidak jauh-jauh dari membuat konten.
"Ada yang punya lampu tumblr?" Kak Faira bertanya.
"Coba tanya ikhwan, Kak? Mungkin mereka punya?" Adiba menyahut santai. Gadis itu sedang menggunting huruf-huruf dari kertas.
"Alah, mana ada? Biasanya kalau agenda bareng, mereka selalu nyuruh kita yang nyari aksesori gini!"
Semua yang ada di sana tertawa pelan. Kak Faira adalah Kepala Bidang Kemuslimahan periode 2018. Tahun lalu menjabat sebagai Kepala Departemen Pembinaan. Aku menatap ganjil. Kak Faira sering terlihat kesal saat ada yang menyinggung-nyinggung ikhwan. Kabid Kemuslimahan 2017 tidak begitu. Kurasa ada sesuatu yang salah.
Aku hanya menduga-duga, Ketua Umum 2018 mungkin terlalu menyebalkan. Betapa perempuan lembut seperti Kak Faira berhasil dibuat sebal.
Tahun berikutnya aku baru menemukan jawaban. Angkatan 2015 sudah muktamar. Adiba terpilih jadi Kabid Kemuslimahan 2019. Benar saja, gadis sekalem dan seceria Adiba ikut uring-uringan. Sebagai teman dekatnya, aku tentu berani bertanya. Ternyata memang, dalam setiap koordinasi ikhwan-akhwat, tak selamanya berjalan mulus. Banyak perbedaan pendapat. Terlebih, media yang dipakai berkomunikasi kebanyakan lewat chatting. Bisa dibayangkan betapa rentan muncul kesalahpahaman.
Ah, tetapi itu hanya informasi selingan. Kembali ke saat ini, aku mengedikkan bahu. Fokus menempelkan huruf-huruf kertas ke atas karton. Ini akan jadi latar stand kami. Saat sedang asyik-asyiknya bekerja, tiba-tiba ponselku berdering. Sangat nyaring. Semua mata tertuju ke arahku.
Aku menyengir. Buru-buru keluar dari ruangan. Mama menelpon. Segera kuangkat. "Iya, Ma?"
"Kamu di mana, Nak?"
"Masjid. Ada apa, Ma?"
Kudengar beliau menarik napas. "Bagaimana ini, Arisha? Adik sama bapakmu belum akur. Sudah lebih dari tiga hari diam-diaman."
Aku ikut menarik napas. "Sudah Mama bujuk si Ozan? Suruh dia minta maaf duluan."
"Sudah. Dasarnya memang keras kepala. Percuma, Arisha. Saya kasihan lihat bapakmu. Beliau sering melamun akhir-akhir ini. Sepertinya emosi beliau sudah mencapai puncaknya."
Aku mengernyit dalam. "Kenapa Mama bilang emosi Bapak sudah mencapai puncak? Bukannya bagus kalau Bapak diam? Tidak ada keributan di rumah."
"Ngomong apa kamu, Arisha?" Mama menyahut tegas. "Marahnya orang tua itu ada tiga tahap. Tegur baik-baik, kesalahan anak masih ringan. Dikerasi, tandanya anak mulai melunjak. Terakhir, diam. Asal kamu tahu, Arisha, diamnya orang tua berarti kecewa. Paham maksudnya? Anak harus berhenti bertingkah. Jangan sampai orang tua hilang kepedulian."
Dibanding mereka, aku lebih khawatir pada Mama. Pasti berat berada di tengah-tengah orang yang sedang perang dingin. "Mama sudah makan?"
"Belum, Nak. Masih nunggu bapakmu. Sebentar lagi paling pulang dari sekolah."
"Gimana sekolahnya Ozan?"
"Ya, pagi-pagi dia ke sekolah. Sejauh ini belum ada laporan bolos lagi."
"Syukurlah kalau begitu. Nanti aku yang coba bicara sama dia. Mending Mama istrahat dulu. Aku tutup telponnya?"
"Iya. Jaga diri baik-baik di sana. Tidak usah terlalu banyak yang diurus. Fokus saja sama kuliahmu. Kurang-kurangi itu kegiatan organisasimu."
Aku meringis. Teringat kejadian setahun silam. Saat aku pulang dalam kondisi sudah berpakaian syar'i. Jilbab, kerudung, dilengkapi kaos kaki. Hampir seharian Mama-Bapak menginterogasiku. Khawatir anaknya terpapar paham ekstrem. Saat itu aku tertunduk malu. Bukan, bukan malu pada pakaianku, melainkan teringat akan masa lalu. Tentang kekhawatiranku terhadap perubahan Dani. Jika diingat-ingat lagi, kini kenangan itu terasa lucu.
Ah, ngomong-ngomong tentang Dani, mungkin kalian bertanya-tenya bagaimana perasaanku padanya kini?
Jawabannya, sama saja. Rasa ini masih untuknya, meski tak sebesar dulu lagi. Aku terkena virus gagal move on, memang.
"Arisha?"
"Y-ya? Mama bilang apa?" Aku terlalu lama melamun.
"Jangan terlalu sibuk sama organisasi."
"Iya, Mama."
"Mama tutup." Sambungan terputus.
Aku kembali ke kantor sekretariat. Aurel mengambil alih pekerjaanku. "Geser, Rel," pintaku. Aurel menatapku sekilas, lalu mengangguk kaku.
Kutempelkan huruf-huruf itu sembari berpikir. Merancang cara agar Fauzan dan Bapak berdamai. Masalah ini harus segera dituntaskan.
"Sha, hurufnya terbalik, lho!" Adiba berseru.
Aku sontak menunduk. Huruf A malah jadi seperti V. Cengiranku muncul. Adiba geleng-geleng. "Mikirin apa, sih?"
Apa sebaiknya aku minta saran pada mereka? Mungkin mereka pernah mengalami hal serupa. Namun, bagaimana caranya agar tidak terkesan mengumbar aib keluarga?
"Em, kamu punya adik laki-laki nggak, Dib?"
Adiba menggeleng. "Adanya kakak laki-laki. Eh, tapi dia udah punya calon istri."
Aku melotot. "Oi, apa tujuanmu ngomong gitu, heh?"
Adiba tergelak. "Kali aja gitu, Sha. Lagian, buat apa kamu nanyain adik laki-laki orang lain?"
Aku memutar bola mata. Memilih tidak menjawab. Percuma kujelaskan. Adiba takkan mengerti. Aku menoleh ke arah Kak Faira. "Kakak punya adik laki-laki?"
Kak Faira menatapku, tersenyum simpul. "Adanya perempuan, Dek."
Kuberalih kepada yang lain. Tiga orang teman seangkatan Kak Faira. "Kakak-kakak punya adik laki-laki?"
"Aku anak tunggal, Dek."
"Kami bersaudara perempuan semua, Dek."
"Sama kayak Adiba. Adanya kakak laki-laki. Dia belum punya calon, sih, tapi kayaknya bukan tipemu, Dek." Kak Titania menimpali. Dia mentor pertama Aurel sekaligus Kepala Departemen Pembinaan.
Mereka lagi-lagi tertawa. Aku memberenggut. Tentu saja bukan tipeku. Suami idaman yang kuinginkan itu macam Daniyal Alhusain!
Hah? Mikir apa aku barusan?
"Mungkin Aurel punya, Dek?" Kak Faira bersuara lagi.
Aku segera menoleh ke arah Aurel. Menatapnya ragu. Aurel membalas tatapanku, mengangguk. "Heh, kenapa nggak ngomong dari tadi?" tukasku sewot.
"Kamu nggak nanya."
Hah! Risiko punya teman model begini. "Jadi, kamu punya adik laki-laki?"
"Iya, tapi mereka masih sekolah, SMA dan SMP. Belum diizinkan nikah."
Lagi-lagi mereka menertawaiku. Aku mendengus tipis. Astaga. Memang siapa yang cari calon suami?
"Udah, udah. Muka Arisha mulai cemberut, tuh." Kak Faira berkata menggoda. Sisa-sisa tawa mereka belum hilang. Aurel satu-satunya yang berwajah datar sedari tadi. Ya, wajar. Selera humor gadis ini agak-agak menyedihkan.
"Bapakmu pernah bertengkar sama adikmu nggak, Rel?"
Aurel memandangiku aneh. "Tadi adikku, sekarang bapakku. Maumu apa?"
Aku ingin menjedotkan kepala ke dinding. Oi, tampaknya aku salah memilih tempat bertanya.
Ada yang berdehem. Aku menoleh, Adiba. "Adikmu diajak bicara baik-baik coba. Em, mungkin bisa dimulai dengan kabulkan keinginannya. Hal-hal kecil saja. Belikan pekat data, misal?"
Aku mengerjap. "Eh, kamu tahu?"
"Ya, nggak mungkin kamu nanyain adik kita-kita benaran buat nyari calon suami, kan? Lebih-lebih nanya soal bapaknya Aurel." Adiba tersenyum geli.
Aku menahan kedut di bibir. Mau tidak mau, tawaku lepas juga.
"Setiap keluarga kayaknya pernah berantem, Dek. Ada satu-dua cekcok. Adik-kakak, ibu-bapak, anak-orang tua. Mungkin persoalannya terletak di komunikasi kali, ya." Kak Titania menambahkan tanpa terkesan menghakimi.
"Benar, Dek. Lakukan pendekatan melalui adik. Bagaimanapun, orang tua punya keyakinan tahu mana yang terbaik buat anaknya. Adikmu yang harus mengalah."
"Ah, satu lagi, rumahmu jauh, kan? Ngomongnya lewat panggilan, jangan chatting. Bahasa tulisan terlalu rentan muncul salah paham." Kak Faira menambahkan.
"Kayak kamu sama ketum, ya, Fai?" goda Kak Titania.
"Hah?!"
Kami tertawa sekali lagi. Perasaanku jadi lebih baik. Tidak sia-sia aku bertanya pada mereka.
"Kalau masih belum selesai, mending kamu pulang kampung. Sebaik-baik pembicaraan dilakukan secara langsung." Aurel menutup obrolan kami siang itu.
Selepas merapikan barang-barang, kami membubarkan diri. Sepuluh menit lagi azan Ashar akan berkumandang. Pekerjaan ini masih dapat dilanjutkan esok. Usai melaksanakan salat, aku dan Aurel berpamitan. Kami masih ada kuliah sore ini. Sepanjang perjalanan menuju ke kelas, otakku menyusun pelbagai rencana demi mendamaikan Fauzan dan Bapak.
Aku pun memikirkan saran Aurel. Selama kuliah aku baru pulang kampung sebanyak dua kali. Setiap libur semester genap, saat bulan Ramadan telah tiba. Biaya ke sana cukup mahal.
Tiba-tiba aku teringat perkataan Fauzan. Mungkin memang akulah yang menghabiskan uang Mama-Bapak. Perasaan bersalah terbit detik itu juga. Segera kutepis. Sudah telanjur. Balasan terbaik yang bisa kuberikan dengan kuliah sebaik-baiknya, serta jadi anak berbakti.
Tekadku sudah bulat. Liburan semester ini aku mesti pulang kampung. Agar biaya terasa ringan, aku akan menghemat pengeluaran. Desember masih lama. Aku bisa menyisihkan jatah kiriman uang setiap bulannya.
Sepulang dari kuliah, tanpa membuang-buang waktu, aku kembali menghubungi Fauzan. Semula dia menolak, tetapi kupaksa lewat SMS dengan iming-iming gratis paket data. Benar saja apa kata Adiba, Fauzan bersedia tanpa banyak kata.
Aku mendengus geli. "Begini kalau ditelepon kakakmu, heh?"
Fauzan ikut tertawa di ujung sana. "Ya, siapa yang bisa nolak gratisan, sih?"
"Ck. Gimana kondisi rumah, aman?"
"Aman. Bapak jarang marah. Telingaku jadi tenteram."
"Jangankan marah, bicara sama kamu aja, Bapak enggan. Kamu senang, Zan, lihat Bapak kayak gitu? Kamu lega dicuekkin Bapak berhari-hari?"
"Bukan Bapak yang cuek, tapi aku," sahutnya santai.
"Yakin sekali kamu, Fauzan? Setelah pulang ke rumah, pernah lihat Bapak negur kamu? Kita ini cuma anak kecil, nggak pantas bertingkah gitu di hadapan orang tua. Bukan kamu yang cuek, tapi Bapak udah nggak peduli. Ah, kamu nggak percaya? Sekarang Bapak lagi di rumah, bukan? Nah, coba kamu dekati, tanya-tanya, kalau kamu ditanggapi, baru boleh bertingkah."
Fauzan diam. Aku setia menunggu. Karena terlalu lama, aku jadi gemas. "Tahap marahnya orang tua itu macam-macam, Fauzan. Kesalahan ringan, kita ditegur baik-baik. Melunjak, kita dikerasi. Kalau orang tua sudah diam, itu tandanya beliau kecewa. Paham maksudnya? Jangan sampai Bapak hilang kepedualian sama kamu." Aku menyalin ucapan Mama siang tadi, meski tak benar-benar paham.
"Jangan bilang begitu dong, Arisha."
Aku tersenyum geli. Oi, anak mana yang tidak khawatir diabaikan orang tuanya? "Ya, makanya minta maaf, sana. Kalau kamu belum percaya, buktikan aja perkataanku tadi. Kalau Bapak udah nggak peduli, Ozan, bisa-bisa uang jajanmu lenyap, barang-barangmu disita. Mau jadi gelandangan, hah?"
Fauzan diam saja sepanjang sisa perbincangan kami. Aku terus menasihatinya. Besok-besok, jika kejadian serupa terulang, akan kujewer telinga anak itu.
Hari-hari selanjutnya kuhabiskan dengan semangat. Kondisi rumah sudah membaik. Fauzan minta maaf, entah karena merasa bersalah, atau malah khawatir jadi gelandangan. Apa pun itu, kuharap keluarga kami tetap harmonis.
Aku tak sabar menanti liburan. Waktu melesat dengan cepat. Ujian akhir selesai, liburan telah tiba, tantangan semester berikutnya siap menghadang. Rumah masa kecilku sudah menunggu.
Aku masih ingat betul hari itu. Kakiku berpijak di depan pintu. Mereka menyambutku. Mama memelukku, Bapak tetap cool seperti biasa, Fauzan menagih buah tangan.
Kupikir segalanya berangsur-angsur membaik. Sayang, satu kabar buruk muncul menjelang akhir liburan. Berita yang menghancurkan hatiku hingga bertahun-tahun setelahnya, bahkan detik ini.
To be continue ...
Ya, lagi-lagi aku mempercepat alur kalau udah dekat ending 😂
Btw, kayaknya ini cerita paling ringan di work-ku, ya? Santai gitu bacanya, minim konflik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top