|22| Kabar dari Rumah (a)
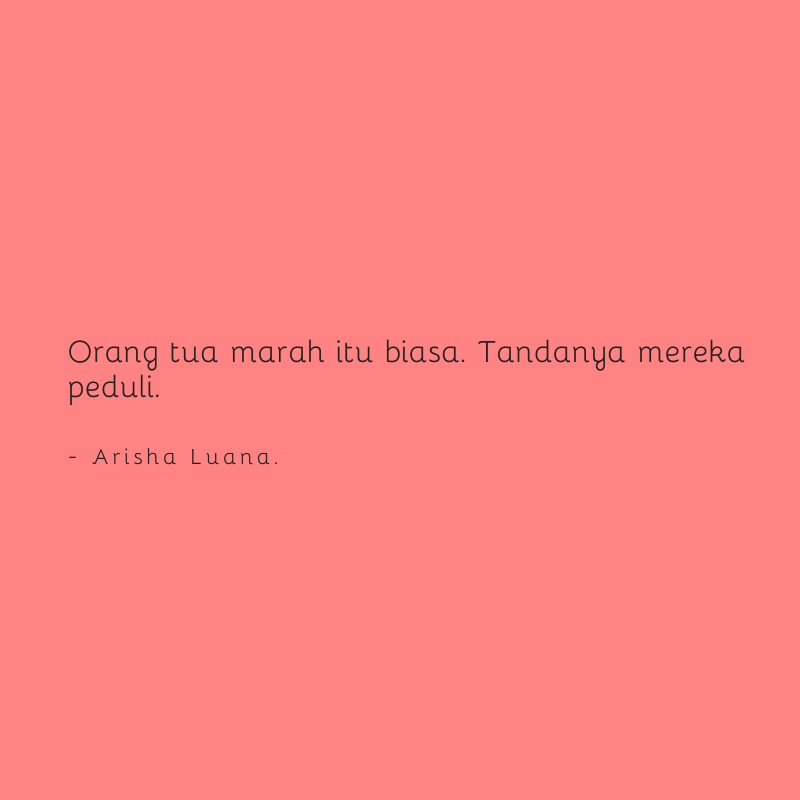
Sudah kuduga ini tidak akan mudah. Dakwah menuntut banyak hal dari para pengembannya. Waktu, harta, tenaga, dan lain sebagainya. Bahkan, jika berkaca pada sejarah, generasi Islam terdahulu sampai mengorbankan nyawa.
Satu hal yang paling terasa setelah aku memutuskan menumpang di atas kereta dakwah. Aku jadi malu bermaksiat, baik secara sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan. Bukan, aku tidak sedang mengklaim diri sebagai orang alim, suci dari dosa. Perkara mubah atau sia-sia mungkin masih sering kulakukan. Membuka media sosial hingga lupa waktu, misalnya. Hanya saja, aku lebih berhati-hati dalam bertindak.
Kupikir, jika aku menjadi pengemban dakwah, menyerukan kebaikan kepada sesama, akan sangat berdosa bila perkataanku tidak sejalan dengan tindakan. Aku teringat ayat-ayat Allah yang mencela orang demikian.
"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?" (QS. Al-Baqarah: 44).
"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. Ash Shaff: 2-3).
Aku merenggangkan otot-otot badan. Ini hari Minggu, tetapi kerjaan tidak ada habisnya. Sejak pagi aku sudah berkutat dengan pakaian kotor. Beginilah aktivitas anak kost.
Selepas menjemur pakaian, aku beralih pada tugas lain. Merapikan kamar yang sudah dua hari terbengkalai. Berhubung aku hanya tinggal sendiri, tidak ada orang lain yang membantu.
Ketika aku sedang merapikan tumpukan kertas dan buku yang berserakan, ponselku berdering. Jarang-jarang ada yang menghubungi secara langsung. Kuraih bendah pipih yang terselip di antara kertas. Mama menelpon.
"Assalamu'alaikum, Ma."
"Wa'alaikumussalam, Sha. Kamu lagi ngapain?"
"Baru selesai nyuci. Ini lagi beres-beres."
"Jam segini baru beres-beres?" Mama menyahut heran.
"Hehe, iya, tadi cucianku banyak sekali."
"Haduh, jangan bilang kamu numpuk-numpuk pakaian kotor lagi? Apa susahnya dicuci setiap mau mandi, Sha? Kamu itu sudah dewasa. Masa dari kecil kebiasaannya belum berubah?"
Aku meringis. Seharusnya aku tidak membahas topik ini. "Banyak tugas dari dosen, Ma. Nggak sempat."
"Halah, bilang saja kamu malas. Jadi perempuan itu harus pembersih, rajin, cekatan. Jangan nunda-nunda pekerjaan. Kalau kamu masih keteteran ngurus diri sendiri begini, bagaimana nanti pas sudah menikah?"
Astaga. Ini tidak akan berakhir sebelum aku mengaku salah. "Iya, iya, Mama sayang. Arisha emang malas, makanya pakaian kotornya menumpuk."
Kudengar Mama menarik napas. Ah, apa aku membuatnya marah? "Kamu sudah makan?"
"Sudah, Ma."
"Makan apa?"
"Hehe, mie instan."
"Ya Allah, sudah berapa kali Mama bilang? Jangan makan mie terus! Sekarang mungkin belum terasa, tapi lama-lama bahaya. Kemarin ada yang mati dari kampung tetangga karena penyakit lambung. Setelah diselidiki, selama kuliah, hampir setiap hari makan mie."
Astaga. Salah melulu. "Iya, iya. Arisha bakalan makan empat sehat lima sempurna. Jadi, uang bulanannya ditambah biar bisa beli makanan begituan."
"Itu akal-akalanmu saja!"
Aku tertawa. Ya, lumayan kalau dapat tambahan jatah bulanan, bukan?
"Mama sudah makan?"
"Sudah, barusan sama bapakmu. Bagaimana kuliahmu, Nak?"
"Lancar, alhamdulillah. Arisha punya teman-teman yang baik selama di sini. Mama sama Bapak sehat-sehat?"
"Alhamdulillah sehat. Bapakmu semakin banyak pekerjaannya. Sekolah lagi sibuk persiapan akreditasi. Hampir setiap hari teman-teman bapakmu datang ke rumah."
Ah, tiba-tiba aku merindukan mereka. Omelan Mama, sikap Bapak yang tidak bersahabat, tingkah menyebalkan Fauzan. Aku menarik napas dalam-dalam, sesak. "Ya, semoga urusan Bapak dilancarkan. Oh, iya, Ozan di mana? Sudah lama nggak dengar suara anak itu."
Lengang. Aku melirik layar ponsel. Masih terhubung. "Mama?"
"Ozan pergi dari rumah sejak kemarin."
"Apa?"
"Bapak marah karena adikmu susah diatur. Berantem di sekolah, merokok, bolos pas pelajaran."
Aku mengusap wajah. Sudah tahu tentang kenakalan Fauzan. Mama sering mengeluhkan hal itu. Hanya saja, tidak kusangka kondisinya separah ini. Kabur dari rumah? Konyol sekali. Bagaimana dia akan hidup di luar sana?
"Jadi, dia tinggal di mana?"
"Belum tahu. Teleponnya tidak diangkat. Mungkin di rumah temannya."
Aku menarik napas. "Biar aku yang hubungi. Semoga saja direspon. Mungkin Mama sama Bapak bisa nanya ke teman-temannya di kampung."
"Adikmu beda sekali sama kamu, Nak. Dia suka bertindak seenaknya. Susah dinasihati. Kerjaannya main terus, jarang belajar."
Aku diam saja. Bingung harus merespon seperti apa.
"Ya sudah, kamu jaga diri baik-baik. Jangan terlalu dipikirkan masalah adikmu. Mama tutup."
Aku mendebas. Bagaimana tidak kepikiran jika mereka sering mengadu padaku?
Inilah salah satu alasanku merasa berat untuk mengambil jalan dakwah. Keluargaku bermasalah. Setelah masuk SMA, kenakalan Fauzan sudah tidak terkondisikan
Tarik napas, embuskan. Aku pasti bisa mendamaikan mereka. Semoga.
Kuselesaikan sisa pekerjaan terlebih dahulu. Setelah segalanya rapi, kucoba menghubungi Fauzan. Nada tunggu terdengar. Tak lama, dia mengangkat panggilanku.
"Ozan?"
"Kenapa?" sahutnya jutek. Astaga. Apa-apaan anak ini!
Tarik napas, embuskan. Aku harus tenang. Sebaiknya basa-basi dulu. "Sudah makan?"
"Repot-repot nelpon cuma mau nanya itu?"
"Gimana kondisimu, baik?"
"Mama ngomong apa?"
"Kenapa kabur dari rumah, Ozan?"
"Siapa yang kabur? Aku cuma menginap di rumah teman."
"Pergi tanpa izin, apa namanya kalau bukan kabur? Pulang, Ozan. Dicari Mama sama Bapak."
Kudengar ia mendecih. Aku mengerutkan dahi dalam-dalam. "Malas. Dimarahi terus. Sedikit-sedikit disuruh belajar!"
"Ya, itu memang tugasmu sebagai siswa. Kamu sudah kelas tiga. Mau jadi apa kalau malas belajar begitu? Kampus mana yang mau terima pemalas?"
"Cih. Bukan urusan kalian!"
"Fauzan!" pekikku kesal. "Kamu kenapa, hah? Makan, main, belajar, tidur. Itu saja urusanmu. Tidak perlu memasak, cuci piring, cuci baju, kerja kayak pembantu. Susah sekali diatur. Kamu pikir Mama sama Bapak tidak capek, hah?"
"Kamu ngomong begitu karena jadi anak kesayangan! Saya juga pusing dibanding-bandingkan terus. Apa-apa kamu. Minta beli sepatu baru tidak bisa, dipakai buat biaya kuliahmu! Minta tambahan uang jajan tidak boleh, dikirim buat kamu! Semua-muanya untuk kamu! Memang cuma kamu anak mereka, hah?"
Aku mengerjap. Astaga. "Ngomong apa kamu, Fuzan?"
"Nilaiku rendah, dibilang contoh kakakmu. Saya ribut di kelas, dikatain beda sama kamu! Tidak orang tua, tidak guru-guru, semuanya mau saya jadi macam kamu. Memang cuma kamu yang jadi kesayangan. Saya salah terus!"
Aku bersandar pada tembok. Shock. Bicara apa anak ini? Urusan di sekolah, aku akan percaya. Karena memang, aku masuk kategori siswa berprestasi. Tapi orang tua? Mana mungkin mereka begitu, apalagi Bapak. Jelas-jelas beliau selalu menunjukkan sikap tidak bersahabat padaku sejak kecil. Fauzan tentu anak kesayangan mereka.
"Jangan cari-cari alasan, Fauzan. Dari kecil kamu selalu diajak Bapak ke mana-mana, memancing, ke hutan, kadang dibawa ke sekolah. Keinginanmu sering dituruti. Kamu yang salah, saya yang dimarahi. Mama tidak pernah suruh kamu kerja di dapur. Jelas-jelas kamu anak kesayangan mereka!"
Fauzan tertawa. Begitu sinis. "Omong kosong! Kamu tahu apa yang selalu mereka katakan? "Nak, jadi seperti kakakmu. Jangan nakal. Nurut sama orang tua. Belajar yang rajin biar pintar." Sampai kapan pun kamu selalu jadi kebanggaan mereka."
Dadaku sesak. Tak menyangka. Ini informasi mengejutkan. Bertahun-tahun aku selalu menganggap orang tua kami lebih mengutamakan Fauzan. Aku bahkan berpikir kalau Bapak membenciku. Aku sudah salah paham selama ini.
Jika memang Bapak begitu bangga padaku, lantas kenapa sikapnya tidak bersahabat? Dalam pandanganku, beliau senantiasa lemah-lembut kepada Fauzan. Berbeda dengan Mama, meski sering mengomel, beliau cenderung diam ketika Bapak mulai marah-marah padaku.
Ada yang salah dengan hidupku. Seharusnya tidak begini. Aku sudah telanjur menerima segala kekerasan Bapak padaku. Kenapa Fauzan mengatakan hal-hal aneh?
"Ozan, kamu tidak mengarang cerita?" tanyaku lamat-lamat.
"Hah? Buat apa? Sudahlah, kamu pasti senang jadi anak kesayangan."
Aku bungkam. Terpaku. Tidak dapat menghindar. Kata-kata Fauzan benar sekali. Meski sempat terkejut, tetapi tidak dapat dimungkiri ada kebahagiaan yang muncul di hati. Astaga. Tidak seharusnya aku senang di atas penderitaan adikku.
"Begini saja, Ozan. Coba kamu pulang dulu. Mama-Bapak khawatir sama kamu. Jangan tambah beban pikiran mereka dengan pergi dari rumah. Bicarakan baik-baik apa masalahmu."
"Terus apa? Lagi-lagi dibandingkan sama kamu, begitu? Enak saja!"
Aku menarik napas kuat-kuat. Memang tidak enak dibandingkan dengan orang lain. Itu menyebalkan. "Bukan begitu. Coba kamu pikir baik-baik, mau sampai kapan menginap di rumah temanmu? Sehari, dua hari, mungkin boleh-boleh saja. Kalau sudah sebulan, bagaimana? Kamu pikir orang tua temanmu mau menampung selama itu? Mereka juga punya masalah keluarga sendiri."
Lengang. Kuyakin Fauzan sedang berpikir. Aku menanti khawatir. Bagaimana bila dia kukuh pergi dari rumah? Aduh, aku tidak bisa membayangkan adikku terlunta-lunta di jalanan.
"Tahu, dah. Lihat saja nanti!" sahut Fauzan sambil berdesis.
Aku tersenyum, menghela napas lega. Dia pasti pulang. Kami bisa tenang sekarang. "Jangan lama-lama kalau mikir. Diusir betulan dari rumah, tahu rasa! Jaga dirimu, Ozan. Belajar yang baik biar lulus di kampus negeri kayak kakakmu ini."
"Oi!"
Aku tertawa. Senang menggodanya. Ah, dia kambali. "Ya sudah, saya tutup. Bye, adikku tercinta."
"Saya tidak cinta sama kamu!" geramnya, lantas memutus sambungan. Aku terkikik sambil memandangi layar ponsel.
Hah! Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang.
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top