|21| Bicara Tentang Dakwah
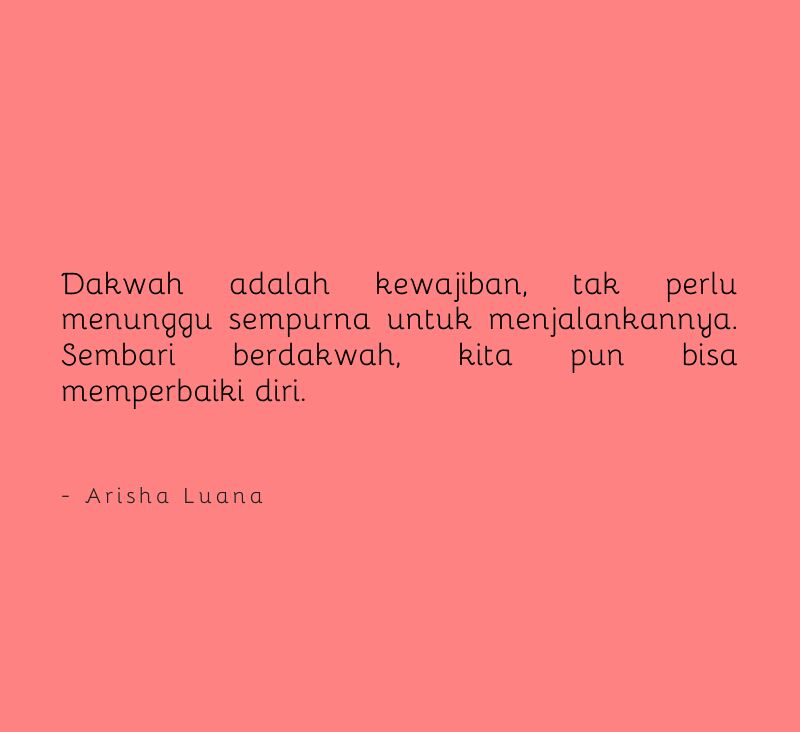
Agustus 2018.
Genap dua tahun aku menempuh pendidikan di kota ini. Banyak hal yang berubah. Tidak mudah memang, tetapi aku mampu bertahan sampai sejauh ini. Kulangkahkan kaki dengan riang. Tahun ajaran baru senantiasa memberi kesan berbeda.
Mahasiswa berseragam hitam-putih lalu-lalang di sepanjang jalan kampus. Mahasiswa baru yang belum tersentuh beratnya kehidupan kuliah. Aku selalu suka melihat sorot ingin tahu dari mata mereka.
Langkahku semakin cepat setelah memasuki gedung jurusan. Lantai tiga menjadi tujuan. Biar kutebak, dosen pasti belum datang. Mereka biasanya terlambat 10 menit. Berhubung sudah tahu betapa pentingnya disiplin dalam pandangan Islam, kuputuskan untuk hadir tepat waktu.
Kulirik jam tanganku. Tinggal 5 menit lagi. Pintu ruangan 305 sudah di depan mata. Langkahku sedikit melambat saat melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu sambil menatap kertas pengumuman. Sepertinya dia tengah memastikan jadwal.
Aku tidak mengenalinya. Mungkinkah dia mahasiswa dari kelas lain? Mengingat kelas pagi ini adalah mata kuliah pilihan. Besar kemungkinan gabungan dari setiap kelas.
"Maaf, permisi, Mas. Saya mau lewat," tukasku agak sungkan setelah berdiri di sampingnya. Dia menghalangi jalan masuk.
Lelaki itu menoleh. Pandangan kami bertemu. Senyumnya merekah. Aku buru-buru mennggerakkan bola mata ke arah lain. Gila. Bolehkah aku sedikit berkomentar? Kurasa dia benar-benar tampan.
Aku menepuk jidat. Apa yang kupikirkan? Ah, salah satu kelemahanku muncul lagi. Masih susah mengendalikan hati. Bukan berarti aku langsung jatuh cinta pada laki-laki asing ini.
"Ini kelas Asesmen Formatif, ya?" tanya laki-laki itu.
"Iya, Mas," sahutku cepat. Dia tersenyum geli. Aku mengerjap. Apa yang salah?
"Terima kasih informasinya. Silakan masuk duluan," tukasnya sambil bergeser, memberiku jalan. Tanpa membuang waktu, aku langsung mengambil kesempatan.
Sesampainya di dalam kelas, kupilih bangku paling depan. Setelah ditegur Pak Revan beberapa tahun lalu, aku kapok tidur di dalam kelas. Terlebih, aku belum tahu bagaimana ketentuan dosen pengampu mata kuliah ini.
Seperti biasa, Aurel sudah mendiami posisi favoritnya. Tepat di hadapan meja dosen. Ah, gadis itu memang agak-agak ambisius dengan nilai. Kurasa IPK-nya pasti di atas rata-rata. Entahlah.
Aku sengaja duduk di dekat Aurel. Besar kemungkinan kami akan jadi partner lagi jika ada pembentukan kelompok. Terlepas dari sikap menyebalkan, dan lisannya yang super tajam, Aurel sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya.
"Kamu udah nulis artikel opini?" bisikku kepada Aurel. Kami jadi tim media di organisasi. Sungguh mengherankan. Tidak di kelas, tidak di organisasi, kami hampir selalu bersama. Mau tidak mau, aku berlatih membiasakan diri dengan sikapnya.
"Udah," sahutnya tanpa menoleh ke arahku.
"Tentang apa? Aku lagi nggak ada inspirasi, nih," keluhku.
Artikel itu nantinya akan dikirimkan ke redaksi koran lokal sebagai tulisan opini. Jika ditolak, biasanya berakhir di website milik LDK. Kami juga mempunyai program pembuatan buletin setiap dua minggu sekali. Salah satu cara untuk memperluas opini di kalangan civitas akademika. Seluruh anggota bertugas menyebarkan buletin tersebut kepada para mahasiswa.
"Dosennya udah masuk," gumam Aurel.
Aku buru-buru merapikan posisi. Jarang-jarang ada dosen yang tepat waktu begini. Pandanganku tertuju ke depan. Rasa-rasanya, mataku nyaris meloncat keluar saat dosen itu menapatku sekilas. Oi, laki-laki tadi bukan mahasiswa, beliau dosen! Good. Mau ditaruh di mana mukaku?!
Alvarendra Pratama. Umur 23 tahun. Dosen muda yang membuat geger para mahasiswi. Keberadaan beliau menggeser posisi Revan Hardian sebagai dosen paling tampan.
*
"Rel, tunggu!"
Kami bergegas meninggalkan kelas usai dosen mengakhiri kuliah pagi itu. Aku mengejar Aurel. Gadis itu tampak buru-buru.
"Kenapa?"
"Kamu mau ke mana, sih? Kelas berikutnya dimulai setelah salat Zuhur."
"Aku ada mentoring."
"Ah, gitu?" Aku mengangguk-angguk.
"Aku duluan!"
"Eh, bentar!" Aku menahan lengan Aurel.
"Apa lagi?"
"Artikelmu tentang apa? Bantuin dong."
Kulihat dia menarik napas. "Jadwalku padat siang ini. Kalau mau, kamu ke kosku pas malam. Sekalian ngerjain tugas barusan."
Aku memutar bola mata. "Ngerjain tugasnya kapan-kapan aja, ya?"
"Kalau bisa secepatnya, kenapa harus ditunda?" sahut Aurel santai sambil menatapku lamat-lamat.
Aku mendengkus sebal. "Iya, deh! Aku ke kosmu habis Magrib."
"Oke. Udah, kan? Aku duluan. Assalamu'alaikum," tukasnya sambil mengulurkan tangan. Kami bersalaman. Aurel menghilang dari pandanganku tak lama kemudian.
Aku melanjutkan perjalanan. Kuputuskan untuk ke musala prodi. Aku malas balik ke kost. Capek jalan kaki.
Sesampainya di pintu masuk musala, aku dikagetkan dengan keberadaan Adiba. Gadis itu sontak menyapaku ramah. "Arisha!"
"Eh, Dib, kamu ngapain di sini?"
Adiba tertawa pelan. "Yang pasti bukan tidur. Kamu nggak ada kuliah?"
"Baru aja selesai. Kamu?"
"Ini mau lanjut kuliah. Tadi kelas apa?"
"Asesmen Formatif."
Adiba tersenyum misterius. "Dosennya masih muda banget, ya?"
"Tahu dari mana? Bukannya beliau masuk perdana di kelasku, ya?"
"Emang. Dosen baru, kok. Kami pernah ketemu." Adiba mengedipkan mata.
"Minggir. Jangan ngobrol di depan pintu. Kamu menginjak sepatuku." Gadis lain menyela percakapan kami. Aku sontak menoleh ke arahnya. Abelyn, teman sekelas Adiba.
"Bel, jangan gitu," bisik Adiba kepada temannya. Sayang, Abelyn hanya menunjukkan raut tak peduli.
Satu lagi orang menyebalkan lainnya. Sifat Abelyn mirip-mirip Aurel. Kami pernah sekelas beberapa kali. Sedikit mengherankan karena gadis ini menjadi teman dekat Adiba. Mereka sering ke mana-mana bersama. Eh, apa jangan-jangan, aku dan Aurel terlihat seperti mereka?
"Sha, kami pergi dulu, ya!" Adiba pamit sambil menggeret tangan Abelyn. Aku tersenyum geli melihat tingkah mereka.
Setelah salat duha, aku tidur-tiduran di lantai musala. Jam begini sepi pengunjung. Hampir semua mahasiswa sedang ada kuliah. Pikiranku melayang ke mana-mana.
Belakangan, ada perasaan ganjil menyusup ke dalam hatiku. Terasa aneh setiap kali menyaksikan kondisi di LDK. Betapa kekurangan kader tampak jelas di angkatan 2016. Di antara 12 anggota, baru 2 orang yang menjadi mentor. Adiba dan Aurel. Padahal, tidak lama lagi angkatan 2015 akan jadi alumni. Lantas, bagaimana ke depannya nasib organisasi?
Besar kemungkinan Adiba akan jadi Kepala Bidang Kemuslimahan selanjutnya. Bagaimana dengan perangkat pengurus yang lain? Mungkinkah akan diambil alih oleh angkatan 2017?
Lebih jauh, apa kabar nasib pembinaan anggota? Bagaimana mungkin orang seperti Aurel menjadi mentor? Maksudku, aku mengenal pribadinya. Dia tak selemah lembut Kak Faira. Tentu saja kalimatnya masih sering menyakiti hati. Kasihan sekali yang jadi adik binaannya.
Terus terang, sampai detik ini aku belum mau komitmen di dalam dakwah. Fokusku masih tahap memperbaiki diri. Ketakutan-ketakutan silih berganti menghantui. Lagi pula, aku merasa belum pantas mendedikasikan diri sebagai aktivis dakwah.
Akan tetapi, jika dipikir-pikir kembali, kenapa aku merasa minder? Bukankah orang seperti Aurel saja mendapat amanah sebagai mentor? Dia dan segala sikap kasarnya tidaklah dipermasalahkan. Apa pertimbangan Kepala Departemen Pembinaan saat memilih Aurel?
Kuusap wajahku kasar. Segera mengucap istigfar. Perasaan ini ... benar-benar menyesatkan. Jangan sampai aku bertahan di dalam organisasi hanya karena mengharapkan eksistensi.
Astaghfirullah.
Astaghfirullah.
Astaghfirullah.
Betapa hati masih terlalu kotor. Begitu mudah niat ternoda. Ah, siapalah aku yang mempertanyakan kebijakan para pengurus? Lagi pula, mungkin saja, tanpa aku ketahui, ada sesuatu yang dimiliki Aurel hingga dia laik menerima amanah sebagai pembina. Bukankah Allah memberikan amanah sesuai porsinya?
Aku bangkit. Mungkin sebaiknya mencari kesibukan lain. Tidak ada salahnya melanjutkan artikel yang belum seberapa. Kukeluarkan laptop dari dalam tas. Kala itu kuhabiskan waktu dengan mencari referensi hingga beberapa paragraf muncul di lembar kerjaku. Ketika siang menjelang, usai melaksanakan salat, aku mulai berkutat dengan kuliah lagi.
Tanpa terasa, malam telah tiba. Kuputuskan untuk segera bertandang ke indekos Aurel. Kami masih tinggal di kawasan yang sama. Hanya butuh waktu 10 menit, aku sudah berdiri di depan gadis itu.
*
Aurel menyingkir, membiarkan aku masuk. Kamar Aurel bernuansa biru cerah. Luasnya sekitar 3 x 4 meter. Ada sebuah ranjang, lemari, juga rak buku. Tidak ada meja dan kursi. Kami lesehan di lantai.
Bukan pertama kali aku datang ke sini. Selama dua tahun ini, sudah beberapa kali kami bergantian saling menyambangi indekos. Entah kepentingan kuliah, maupun organisasi.
Kami menjadikan tepi ranjang sebagai pengganti meja. Aurel menyodorkan buku tebal. Benda itu berguna sebagai alas. Beginilah kehidupan anak kost dengan segala keterbatasan.
"Bantu aku nulis artikel dulu, ya? Udah mepet deadline. Tugas kuliah masih lama, bisa diselesaikan kapan-kapan."
Aurel hanya mengangguk. Dia menoleh ke kanan, kubalas tatapannya. "Sudah punya ide?" tanyanya.
"Hm, tapi agak ragu. Kamu nulis tentang apa?"
"Kemerdekaan."
"Kemerdekaan?"
"Iya, memanfaatkan momentum."
"Ah, ini bulan Agustus, ya? Kamu bahas dari sisi mana?"
"Makna kemerdekaan."
Aku mengangguk-angguk. "Kenapa ngambil tema itu? Ada hal lain yang bisa dibahas, bukan? Rasa-rasanya, sudah terlalu banyak artikel yang membahas topik serupa."
"Selama kita belum merdeka sepenuhnya, nggak ada salahnya terus dibahas. Semoga ada satu-dua orang pembaca yang tersentuh hatinya."
Aku menatap Aurel serius. Tertarik mendengarkan lebih jauh. Aurel dapat berperan sebagai teman diskusi yang asyik dalam situasi tertentu. Dia mendengarkan saat orang lain berbicara, bersuara ketika diminta.
"Seperti apa makna kemerdekaan yang ada dalam tulisanmu?"
"Sebelum itu, apa arti merdeka menurutmu?"
Aku mencibir. Khas mentor sekali. Hobi melempar balik pertanyaan. "Kenapa mentor-mentor di LDK hobi sekali nanya balik?" gerutuku.
"Biar adik binaannya mikir. Prinsip mentoring adalah membina, mengubah pola pikir dan pola sikap, bukan sekadar transfer ilmu."
"Iya, dah."
Aurel menyeringai tipis. "Jadi, apa arti merdeka menurutmu?"
"Ya, ketika kita udah nggak terjajah, baik secara fisik, maupun aspek lain. Ekonomi, misalnya."
"Kalau begitu defenisinya, berarti saat ini kita masih terjajah?"
"Tentu. Mungkin bangsa kita nggak terjajah secara fisik. Peperangan udah dihapuskan. Sayang, dari aspek lain, kita juga belum bisa dikatakan mandiri. Utang negara membengkak, kesenjangan sosial kian melebar, jaminan belajar nyatanya cuma bualan."
Aurel berdehem. Tatapannya berubah serius. "Aku sepakat. Kurang lebih begitu isi artikelku. Pertanyaanku, hal-hal yang barusan kamu paparkan, apa sudah disadari oleh semua orang?"
Aku mengedikkan bahu. "Bisa jadi. Siapa sih yang enggak sadar dengan kesulitan hidup hari ini? Hanya saja, sebagian besar memilih masa bodoh, sedangkan sebagian lainnya pasrah. Sedikit sekali yang mau peduli, bukankah begitu, Kak Mentor?"
Aurel menahan senyum. Tentu saja aku tahu arti senyuman itu. Dia pasti senang karena topik-topik mentoring selama ini tertancap dalam benak kami, para adik binaan.
Sudah kubilang, bukan? Siapa yang akan lupa jika hampir di setiap kesempatan selalu dijejalkan persoalan serupa?
"Kamu benar. Terlepas dari banyaknya persoalan hidup hari ini, ada di mana posisi kita?"
"Maksudmu?"
"Masa bodoh, pasrah, atau memilih peduli?"
Aku bungkam seketika. Pukulan telak. Pertanyaan berulang. Akhir dari percakapan ini adalah ajakan untuk berdakwah. Selalu begitu. Seperti yang sudah-sudah. Bukan pertama kali aku menerima pertanyaan serupa. Redaksinya boleh berbeda, tetapi maknanya sama saja.
Agaknya para mentor memang sangat berniat merekrut orang-orang di sekitanya untuk menjadi aktivis dakwah. Adik binaan, teman, keluarga, selagi ada peluang, tentu akan dimanfaatkan. Bukan hanya Kak Faira dan Aurel, Adiba bahkan dalam banyak kesempatan senantiasa menyinggung-nyinggung tentang perjuangan dan pergerakkan.
Bagaikan bola salju, menggumpal, menggelinding, semakin besar, pertanyaan yang terpendam di benakku saling menumpuk tak tertahankan.
Hijrah dan dakwah. Dua kata yang mengantarkanku berada di titik ini. Kuputuskan berhijrah saat menyadari hakikat hidupku sebagai seorang manusia. Aku adalah hamba Allah. Tugasku untuk beribadah. Persoalan hijrah selesai.
Kupikir segalanya berhenti sampai di situ. Nyatanya, aku keliru. Ada tahap selanjutnya, dakwah. Apakah setiap yang berhijrah harus berdakwah? Kenapa pula kita diminta mengurusi hidup orang lain tatkala diri sendiri saja sulit dikondisikan?
Aku menarik napas keras. Rasa penasaraan ini sudah tidak dapat dibendung. "Kenapa ... kalian, maksudku, para mentor, ngotot banget ngajak adik binaannya berdakwah?"
Aurel mengangkat alis, lantas tertawa geli. "Lucu. Kamu nanya itu setelah dua tahun ada di LDK? Waktu daftar dulu, emang kamu nggak baca visi-misi lembaga?"
Aku merapatkan bibir. Terdengar merendahkan. Aurel mode sadis muncul lagi. Sayang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Nyatanya, niatku dahulu memang keliru.
"Ah, nggak usah ngomongin visi-misi, deh. Terlalu berat. Cukup melihat arti singkatan LDK, harusnya kamu sudah mengerti ke mana arah organisasi ini bermuara. Lembaga Dakwah Kampus. Wajar dong kalau seluruh anggotanya dituntut untuk berdakwah?" tukas Aurel dengan senyum menyebalkan yang belum terhapus dari bibirnya.
Ah, bodoh sekali aku menanyakan hal ini padanya. Egoku terluka. Aku tidak bisa diam begini. "Oh, berarti tuntutan organisasi? Setelah jadi alumni, kamu bakalan berhenti berdakwah, gitu?"
Aurel mengibaskan tangan. Badannya menghadap sempurna padaku. Lupakan saja tugas, abaikan tenggat waktu. Detik ini juga kami harus menuntaskan pembicaraan. Kurang lebih begitu arti gerak tubuh Aurel.
"Lepaskan dulu status sebagai mahasiswa. Abaikan keberadaan organisasi. Terlepas dari itu semua, kita adalah hamba Allah, benar?" Aurel menatapku. Tak pernah bisa kupahami arti sorot matanya. Di lain waktu, ia terlihat kosong, di kesempatan berikutnya, terlalu dalam untuk diselami.
Aku mengangguk kaku. Cara bicaranya seolah memaksaku untuk mendengarkan baik-baik. Jangan hilang fokus.
Aurel menyentuh dadanya seraya berkata, "Karena kita adalah hamba Allah, maka dakwah menjadi kewajiban. Apa artinya? Berpahala saat dilaksanakan, berdosa bila ditinggalkan. Itu alasan yang pertama."
Aku mengigit bibir. Sudah dari dulu aku tahu perihal itu. Entahlah. Hanya saja, belum ada panggilan hati untuk benar-benar komitmen meniti jalan dakwah. Aku belum menemukan alasan terkuat. Sesuatu yang akan mengunciku, menjadi landasan untuk tetap tinggal, bertahan walau seberat apa pun.
"Seperti yang kamu paparkan tadi. Hari ini kita dicengkeram oleh beban hidup yang demikian besar. Bernapas saja rasanya susah. Aturan-aturan silih berganti direvisi. Sayang, enggak pernah ada yang menyejahterakan rakyat. Alasannya sederhana, peraturan hidup diciptakan oleh manusia. Serba lemah, serba terbatas.
"Aturan Allah dicampakkan, kitab suci dinistakan, keberadaan Rasulullah dianggap tokoh fiktif. Kita butuh solusi tuntas atas seluruh persoalan ini. Perubahan mendasar dan menyeluruh, bukan parsial. Allah yang paling tahu tentang ciptaan-Nya. Kitab suci ada sebagai pedoman. Rasulullah diutus untuk jadi teladan. Lengkap sudah. Kalau bukan Islam, lalu apa?"
Aku membasahi bibir. Itu benar. Tidak akan kubantah. "Iya, aku sepakat Islam jadi solusi. Itu jelas. Pertanyaanku, kenapa harus dakwah? Maksudku, lawan kita adalah para pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Mereka punya segalanya. Minimal, kalau memang mau menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, harus adalah senjata super. Menjadi pemegang kekuasaan, misalnya. Dakwah modalnya cuma ngomong. Apa iya perubahan akan muncul hanya karena kita berkoar-koar?"
Aurel tertawa lagi. Mendengus, terdengar sarkas. "Masalahnya bukan ada pada penguasa secara personal, tetapi landasan yang digunakan untuk menjalankan roda kekuasaan. Aturan yang dipakai, prinsip-prinsip yang berlaku, dan masih banyak lagi. Ini persoalan sistem, bukan semata kesalahan manusianya. Sistem hidup hari ini melegalkan adanya tindakan kecurangan asalkan kepentingan tercapai. Boleh menipu, yang penting nggak ketahuan. Asal bermanfaat, nggak akan jadi persoalan. Apa pun jadi selama ada uang.
"Nggak bakal ada gunanya berjuang lewat parlemen. Jangankan membuat peraturan berbau Islam, masyarakat biasa aja, bila terindikasi menyebarkan Islam, getol menyuarakan solusi, dilabeli radikal atau teroris. Ulama yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan, nggak ragu dipersekusi. Kalau sudah begitu, apa yang bisa diharapkan? Masih mau percaya dengan sistem hari ini?"
Aku bungkam. Merenung lamat-lamat. Semua terasa masuk akal.
Aurel menarik napas. Senyumnya mengembang. "Dakwah memang modalnya ngomong doang. Tetapi, dengan dakwah, masyarakat bisa dipahamkan. Mereka boleh jadi belum sadar di mana letak akar permasalahannya. Sebagian masa bodoh, pasrah tanpa tahu apa-apa. Adapun yang peduli masih keliru memberi solusi. Berkutat pada perbaikan individu, pemecahan secara parsial, padahal sumber persoalannya jauh lebih besar.
"Kita nggak ngomongin Surga atau Neraka. Apakah yang sibuk mengusahakan perbaikan individu masuk Surga? Itu hak prerogatif Allah. Fokus kita adalah persatuan umat. Membangkitkan pemikiran kaum muslimin yang sedang mengalami kemunduran. Dakwah pemikiran, tanpa kekerasan, secara politis (non parlemen), berjalan dalam jamaah, itulah karakter dakwah Rasulullah. Dengan begitu, kebangkitan Islam menjadi suatu keniscayaan. Jadi, kalau bukan dakwah, lalu apa?"
Lengang. Penuturan Aurel menancap dalam-dalam. Benteng yang selama ini kubangun, runtuh malam itu. Kebenaran dijejalkan di depan mataku. Tak ada lagi pelarian, lenyap semua pembenaran. Aku kalah telak.
Terpaku untuk waktu yang cukup lama. Perkataan Dani beberapa tahun silam perlahan kupahami. Alasan kami berpisah. Keinginannya untuk menempuh jalan hijrah, aktivitasnya dalam berdakwah. Aku yang semula datang dengan niat keliru, kini berbalik arah. Mulai detik itu kudedikasikan hidupku untuk dakwah. Semoga Allah menguatkan langkahku.
Malam itu, aku pun mengerti alasan Aurel menjadi mentor. Dia memang punya kapasitas. Kata-katanya boleh jadi kasar, menyakiti hati, tetapi sekali berargumen, hujahnya kuat. Membungkam pendengar.
Bukan, aku bukan membenarkan karakter Aurel. Kata-kata kasar dilarang dalam Islam. Terlebih bagi aktivits dakwah, itu jelas tidak pantas. Begitulah, karena dakwah adalah kewajiban, tak perlu menunggu sempurna untuk menjalankannya. Sembari berdakwah, kita pun bisa memperbaiki diri.
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top