Chapter - 33: Patah Dan Lenyap
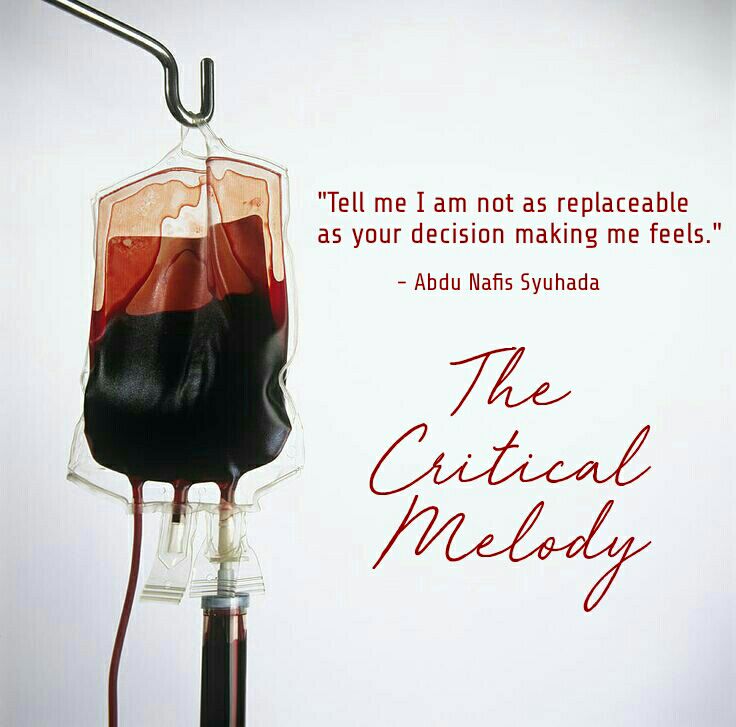
🎸Nafis🎸
Rea duduk di seberang meja. Seporsi roti isi sudah terhidang di hadapannya tanpa disentuh. Dia seolah menyesal sudah memperlihatkan air matanya di depan gue. Gue tahu, cara dia mengelak dengan bentakan adalah luapan perasaannya yang terdalam. Kalau pun itu tak benar gue akan tetap mempercayainya. Bukan, gue memilih percaya.
“Kamu nggak perlu menebak-nebak. Dan aku pun nggak ingin pura-pura lagi.”
Rea berani menatap mata gue. Masih jelas terlihat kilatan-kilatan yang sulit diterjemahkan.
“Banyak yang bilang aku sudah keren. Dalam artian yang sudah kita ketahui masing-masing, Re.”
Tetap hening tanpa jawaban.
“Aku tahu aku salah. Aku ngebiarin kamu lepas gitu aja waktu itu. Aku yang dulu menolak kita balik lagi. Iya, mungkin menurutmu ini obrolan basi dan nggak lebih dari gombalan tengik cowok yang masih cinta sama mantannya. Tapi kamu harus tahu alasan yang sebenarnya dari itu semua.”
“Nggak ada yang perlu dijelasin,” tegasnya dingin. Kalimat pasaran dari seorang cewek. Sesuatu seperti amarah yang dia salurkan ke udara mendarat di benak gue. Aneh, itu malah membangkitkan tekad gue untuk terus mendorong egonya. “Kamu itu emang basi ya.” Kita masih bertatapan. “Tengik. Pengecut.” Napasnya seolah ngos-ngosan. “Persis seperti yang sudah kamu akui.”
“Kalau gitu aku satu-satunya tengik basi dan pengecut yang terbang jauh-jauh sampai ke sini untuk tujuannya. Pengecut yang cukup nekat selama ini nahan kangen ... nahan emosi ... nahan betapa aku pengin lihat wajah kamu,” gue nyaris terbawa emosi juga.
“Playing victim.”
“Aku nggak playing victim, Rea. Itu kenyataannya. Kalau pun kamu juga ngerasain hal yang sama, nggak perlu disembunyikan.”
“Kelewatan kamu, Fis.”
“Nggak akan seperti ini kalau kamu bisa mereda ngadepinnya. Seenggaknya kalau memang aku nggak ada kesempatan apapun, atau barangkali dalam hatimu udah nggak ada akunya, kamu harus mau membicarakan ini dengan tenang. Aku datang baik-baik.”
Dia hendak menjawab tapi langsung gue tangkis.
“Sekarang aku ingin kita ganti cara bicaranya. Kamu bertanya dan aku jawab. Aku bertanya dan kamu jawab pula.”
Sepertinya dia setuju meski ekspresinya enggan.
Gue menyandarkan pundak di kursi. Menguyup minuman dingin. Dan berusaha untuk tidak kalap. Ini momennya. “Rea yang bertanya dulu.”
Awalnya dia ingin tetap bungkan. Tetapi ketika gue hendak bicara, dia menyambar.
“Mau apa kamu datang ke sini?” masih tetap dingin.
“Karena aku udah siap dan ingin menepati omonganku dulu. Mana kala aku sudah siap segalanya, aku akan mengajak kamu balikan dan menjalani semuanya dengan serius,” gue menjawab cepat tanpa basi-basi lagi. “Karena dulu kamu juga mengiyakan keputusanku ini.”
“Dengan cara kamu yang nekat gini nggak akan merubah apa yang sudah ada.”
“Tenang. Aku nggak datang untuk merubah apapun. Asal terbuka. Aku sudah punya pengalaman dengan rasa sakit diputusin kamu. Jadi kalau pun kamu melakukannya untuk kedua kalinya, mungkin sakitnya akan beda. Cukup beri alasan yang kuat apakah aku harus tinggal atau pergi.”
Rea bungkam sesaat. “Dia orang yang baik. Selalu ada dan nggak pernah menyerah ke aku,” oke, gue yakin ini tentang Jullian. Seperti getir. Tapi ada ketulusan yang tersirat dari kalimatnya. Dan itu membuat perasaan gue terbentur. Seolah gue telah kehilangannya lagi. Entah seberapa kuat gue mengaku bisa tanpa dia, kenyataannya ini masih memberatkan ketika mendengarnya membicarakan sosok lain di antara kita berdua. “Dia ada kapan saja aku perlu. Dia memperjuangkan aku dengan caranya. Dia nggak pernah berusaha buat ngelepasin aku.”
“Terdengar sempurna.” Gue mendadak diserang putus asa.
Dan Rea malah terdengar seperti ingin terus mengalahkan dan mematahkan gue pada saat yang sama.
“Jullian nggak pernah satu kali pun ngecewain aku.”
Tangkai pertama dari pohon perasaan itu telah gugur daun-daunnya.
Gue tetap meluruskan pandangan ke wajahnya. Tanpa berkedip dan ekspresi.
“Jujur ya Fis, aku-” setelah itu dia menggigit bibir atasnya. Menunduk sebentar seraya jatuhnya sebening air yang dia seka cepat-cepat. “aku mikirnya ini udah nggak perlu diobrolin lagi. Aku nangis bukan karena aku ketemu kamu setelah sekian lama. O-oke, dulu kata ‘keren’ itu ada. Dan memang hanya muncul dari mulutmu saja kan. Aku mengiyakan karena menaruh harapan besar. Harapan pada saat itu kamu akan berubah pikiran. Aku nyadar kok waktu itu salah banget. Aku nyadar kamu juga lagi sakit-sakitnya waktu itu. Asal kamu tahu aku udah melepas diri dari semua itu.”
“Gimana kamu akan bahagia setelah ini?” itu pertanyaan pertama yang gue ajukan. Mulai merasa percuma. Seperti ada spiral yang berkemelut di jarak beberapa senti dari dahi.
“Aku akan bahagia.”
“Itu pertanyaan pertama yang harus kamu jawab sepanjang aku tadi. Jawaban yang aku perlu bukan sekadar ‘aku akan bahagia’. Tapi bagaimana caranya. Sementara kamu akan bisa bahagia, aku pun tidak ingin tidak bahagia pada saat yang sama. Aku cuma ingin tahu bahagia yang seperti apa yang kamu upayakan setelah ini. Setelah aku pulang dan habisnya pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan kamu.”
Lagi-lagi bibirnya gemetar. Membuat gue ingin menggigitnya dengan kesal. Sial!
“Setelah aku nikah sama Jullian aku akan bahagia. Kami akan punya anak-anak yang manis.”
Dia benar-benar tidak tahu bahagia yang sebenarnya.
Rahang gue mengetat. Tidak ingin menyangkal pendapatnya tentang mendefinisikan bahagia caranya. Dia sedang kacau. “Bagus. Itu juga rencanaku,” gue ragu-ragu, tapi entah kenapa gue perlu mengakui ini ke Rea. Dan barangkali ini adalah satu-satunya alasan paling kuat kenapa gue nekat terbang ke Chicago untuk nyari kejelasan, “Namanya Hasna. Ayah memperkenalkannya padaku sebulan yang lalu,” gue mengatakan ini sembari mengarahkan tatapan tetap pada wajahnya. Agar dia tahu dan tidak perlu susah mencari-cari kejujuran di mata gue. Kartu as. “Dia putri seorang Kiai. Kerabat Ayah. Aku belum pernah menemuinya secara langsung. Hanya sebuah foto yang ditunjukan oleh Bunda.”
Ada sesuatu yang goyah di tatapan Rea. Dia tak yakin menyesap minumannya.
“Dia cantik. Katanya sangat menjaga diri. Dokter spesialis yang memegang klinik gigi dan mulut di puskesmas kecamatan.”
“Terdengar sempurna,” Rea melempar kembali komentar yang pernah gue katakan beberapa saat yang lalu.
“Ayah kenal baik dengannya semenjak sudah tidak aktif di Jakarta dan fokus mengelola yayasan. Cewek itu dua tahun di bawahku. Bunda sangat menyukainya, pun ayah. Meskipun orang tuaku tidak mengatakan ini sebagai perjodohan. Tapi aku bisa menangkap kilatan harapan di mata mereka.”
“Harusnya kamu nggak perlu datang ke sini kalau sudah ada seseorang.”
“Aku belum pernah punya seseorang sejak kamu yang terakhir. Jika pun iya, aku pengin kita selesai dengan cara yang sangat adil. Tidak ada aku yang mendahuluimu, atau kamu bahagia terlebih dulu sementara aku tidak tahu apa-apa. Ini caraku yang sedang berusaha bersikap bijak, Rea. Bahkan sampai kebahagiaanku pun aku masih ingat untuk bersikap adil entah apa saja reaksi yang kamu berikan.”
Dia menatapku, “Kamu suka sama cewek itu?”
Gue menggeleng, “Aku belum memutuskan bereaksi apa-apa padanya. Belum merencanakan apapun selama kita jelas.”
“Sekarang sudah jelas kan?”
“Kalau itu memang yang kamu mau dan putuskan.”
Gilanya, di hadapan gue ini Rea sedang berusaha merajut senyum. Lalu tiba-tibat tangannya mengulurkan sebuah jabata tangan.
“Untuk apa?”
“Kemerdekaan masing-masing untuk kita,” katanya tampak diusahakan setegar mungkin. “Sudah tidak ada lagi yang perlu dimaafkan. Tidak ada yang perlu dibincangkan soal apapun itu yang kamu bawa jauh-jauh ke sini.”
Gue memandagi tangan itu beberapa saat lebih lama. Sampai akhirnya gue sadar sudah tidak ada lagi Nafis di hati Rea.
Tangan gue masih berkeringat saat menyambut salaman itu. Kugenggam erat tangan itu karena sekarang telapak tanganku lebih besar dari tangan rea. Gue mengangguk, “But, tell me I am not as replaceable as your decision making me feels. Aku ingin memastikan ini untuk yang terakhir-akhir-akhir-akhir kalinya padamu, Re. Kalau kamu menerima kedatanganku ke sini bersama semua maksudnya, maka aku akan memperjuangkannya. Tapi kalau kamu sudah yakin dengan keputusan itu, dan yakin akan mengejar bahagia dengan caramu bersama Jullian. Setelah ini aku akan langsung pulang tanpa pernah menoleh satu kali pun.”
Gue kecewa melihat bibir itu tersenyum, “You’re not as replaceable as you think,” katanya mengejutkan, “But it’s enough for us.” Dan kembali meremukkan.
“Copy.”
Kita selesai. Dengan begini meskipun remuknya redam sekali, sudah pasti bahwa tidak ada kesempatan yang bisa gue ambil celahnya, dan akan menjadi adil kalau pada akhirnya gue mencari pembahagia yang lain.
Gue tidak menyelesaikan makan bersamanya. Angin menderu memasuki kafe seraya menerbangkan sebuah rasa terbiasa. Membuat sosok di depan gue seolah perlahan-lahan terasa asing. Perjuangan gue berakhir.
Gue mengambil jaket di sandaran kursi. Menyampirkannya di lengan dan tanpa sepatah kata lagi mengambil langkah panjang keluar dari sana. Benar-benar meninggalkan dia dengan cara seperti itu. Pulang. Waktu memperjuangkannya benar-benar usai sebelum tengah hari. Gue tidak akan pernah memaksa lagi. Berkemas.
***
💡Rea💡
***
Angin yang melintas bersama langkah kakinya yang pergi meninggalkanku, mengirim gigil yang teramat kepada ulu hati. Seolah aku baru saja ditinggalkan sendirian di planet ini oleh seluruh penghuninya. Seolah segalanya menjadi gelap.
Aku mengerang meninju meja. Aku berdiri kemudian. Lalu berlari mengejarnya keluar kafe. Dan seakan kutukan itu mulai bekerja. Tidak akan pernah ada kesempatan baru lagi. Dia menjauh bersama taksi yang melaju kencang.
Aku meraung di trotoar. Kenapa aku bahkan tidak bisa membahasakan apa inginku sendiri? Kenapa aku melepaskan mimpi yang setiap malam datang menghampiri tidurku? Kenapa aku membiakan detak jantung itu memelan?
Dan kenapa aku harus jatuh cinta denga orang yang sempurna seperti Jullian?
Kuusap-usap layar ponsel. Kucoba menelepon nomornya yang dia kasih saat tadi. Tidak diangkat. Kenapa aku harus membuatnya berjalan sejauh ini tanpa hasil? Aku mengerang ketika bahkan tak ada satu taksi pun yang lewat setelah itu. Dan baru datang belasan menit kemudian. Nafis menginap di flat seberang. Harusnya masih bisa kukejar jika dia harus mengemasi barang-barangnya dulu.
Dan kutukan itu terus berjalan. Aku tidak bisa mengejarnya di flat. Dia benar-benar pergi.
Sudah. Aku menahan kakiku untuk tidak melakukan pengejaran lagi. Aku menangis di kamar. Aku merasa benar-benar gila.
Tetapi aku harus kembali berpura-pura baik saat Mami menelepon.
“Rea, kamu tidak dengar apa kata Mami?”
“Ada apa, Mi?”
“Tadi Jullian menelepon. Dia cuma ingin kasih kabar kalau kamu sedang berada di Chicago.”
“Iya.”
“Berapa kali Mami bilang? Mami tidak pernah setuju kalau kamu masih dekat dengan Jullian. Ini bukan masalah karir kamu atau apa, Sayang. Tapi Jullian bilang kalau dia ingin membuat pertemuan dengan Mami dan Papi untuk mendiskusikan pernikahan kalian. Tanpa Mami atau Papi tahu. Tidak pernah ada pernikahan selama Mami tidak merestui! Dan kamu tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan laki-laki yang seiman.”
Dan lunaslah himpitanku saat itu juga.
-----------------------------------------------
***
🍁Zaryn Geraldi🍁
***
"Nafis belum tahu soal ini?" kata Andin saat dia mengaitkan kancing kemeja atas saya di kamar. "Yakin tidak perlu memberitahu dia?"
"Belum saatnya," saya beranjak ke depan cermin mengambil sisir dan menata rambut yang telah ditumbuhi beberapa helai uban. "Ini hanya obrolan antara saya dan Kiai Abimana mengenai pendirian pesantren putri. Tidak ada kaitannya dengan Hasna atau Nafis."
"Tapi tetap saja. Pembicaraan tentang itu pasti akan terselip."
"Percayakan sama Mas."
"Mereka sudah menunggu di ruang tamu. Kiai Abimana saja yang datang. Tidak dengan istrinya. Omong-omong Bunda kangen lho kita Kamisan di sana." (Kamisan = Pengajian Hari Kamis)
"Kamu palingan cuma kangen sama botok ikan mangutnya Bu Nyai doang."
Dia mendekat dan mencubit pinggang saya, "Perasaan yang suka botok ikan mangut itu Sampean."
Saya terkekeh, "Dan kamu yang hobinya nyamain selera akhirnya doyan juga to."
"Ya doyan, tapi kan Bunda kangen sama ngajinya. Lihat ustaz-ustaz muda yang ganteng. Santri-santri yang cakep."
"Tuh, tuh. Segera istighfar sebelum suamimu cemburu."
"Lho, memandang wajah guru dengan penuh kekaguman itu berbuah pahala. Besar keutamaannya."
"Iya, tapi kan itu membuat uban-uban di kepala ini semakin perlu disamarkan. Yang muda memang menawan, tapi siapa sosok peyot yang masih membersamaimu sampai sekarang ini punya setia yang tiada tanding."
"Elehh. Sudah ah, Kiai Abimana sudah nunggu di ruang tamu. Jangan lupa pakai minyak wangi."
"Kamu yang pakaikan. Lagi sibuk sisiran."
"Sibuk sisiran?"
Sudah tahu ada tamu tapi kami masih saja sibuk bergurau di kamar. Maklum, Kiai Abimana datang ketika saya sedang tidur setelah sholat jumat tadi. Makanya perlu sedikit waktu untuk bersiap. Kami sambangi beliau kemudian.
"Ahlan wasahlan, Kiai," sambut saya. "Waduh malu sekali ini. Ada tamu agung tapi kepergok sedang nyenyak."
Kami berpelukan sebentar.
"Ah, ane yang tidak enak. Ganggu waktu istitahat orang saja."
Kami berkelakar di sana.
"Oh iya, bagaimana kabar keluarga?"
"Alhamdulillah, insya Allah baik-baik saja. Ane tadi habis sowan ke Pekalongan, sekalian aja mampir ke rumah antum."
"Jumatan di sana berarti?" tanya saya sembari membuka toples berisi kacang.
"Iya. Tadinya mau lusa saja mampirnya. Tapi keluarga yang di Pamijahan telepon katanya keponakan ane mau ijab. Ada yang khitbah kemarin dan mau langsung disahkan besok lusa. Makanya lagi pontang-panting lawatan ke sana-sini."
"Masya Allah, insya Allah berkah."
"Dan kedatangan ane ke mari hanya ingin ... ya barangkali saja keluarga antum mau ikut silaturahmi ke Pamijahan. Saya ingat waktu itu Bu Andin pengin lihat Goa Safar Wadi. Sekalian aja ayo ke sana. Ziarah ke makam ke makam Syekh Muhyi."
Saya kira mau membicarakan pasal pesantren. Tapi tidak apa-apa, ini juga tak kalah menarik.
"Wah, itu harus saya omongin dulu ke istri. Kayaknya sih mau. Orang nagih-nagih terus pengin main."
"Coba saja dibicarakan. Kalau setuju, besok subuh kita berangkat bareng-bareng."
Saya minta diri sebentar ke kamar. Andin kembali ke kamar tadi setelah mengantar suguhan.
"Itu Kiai Abim ngajak-. Kamu kenapa?" saya mendapati Andin sedang duduk termangu di pinggiran tempat tidur. Tatapannya fokus ke layar televisi. Tangannya dia letakkan di dada.
Saya lalu ikut menoleh ke televisi yang sedang menayangkan berita terkini tentang pesawat rute penerbangan Chicago - Kuala Lumpur yang terjatuh di pegunungan.
"Innalillahi wainnailaihi rojiun," ucap saya spontan. "Kapan kejadiannya?"
"Hilang kontak kemarin malam. Bunda kok lemes ya kalau lihat berita musibah seperti ini."
"Ada penumpang WNI?"
"Katanya ada, tapi masih simpang siur beritanya."
"Oh, ya sudah. Kita temui Kiai dulu yuk. Ada obrolan penting."
Andin menoleh, "Tentang Hasna sama Nafis?"
"Bukan."
****
Yup, rencananya ini adalah chapter terakhir yang akan saya unggah di wattpad karena endingnya hanya akan ada di versi buku. Dan bukunya masih akan keluar di bulan Mei 2019 😥
Tapi, saya masih bisa merubah rencana itu kalau ada minimal 100 orang/akun yang berkomentar isinya alasan kenapa harus saya lanjutkan sampai tamat di wattpad.
Kenapa harus dalam bentuk komentar? Karena saya anggap itu sebagai petisi dari kalian.
Jadi kalau masih mau saya lanjutkan, silakan komentar. ☺
Sebenarnya ini bukan hal berat bagi saya untuk menamatkannya di wattpad. Saya cuma takut akan menambah daftar cerita tergalau di wattpad saja.
Banyak kejutan ya di bab ini?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top