Chapter - 28: Reasons Why
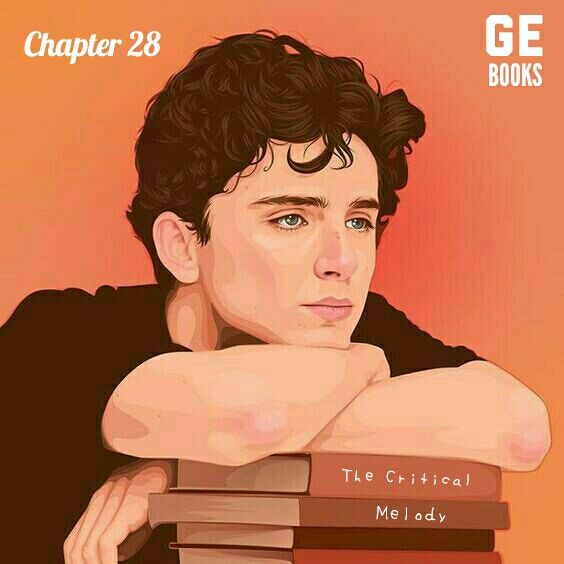
Alo, maaf saya baru unggah lagi karena sedang lumayan padat urusan kampusnya. Dan mungkin saya akan makin padat lagi ketika Agustus. Ada kegiatan KKN yang jelasnya mempersempit ruang waktu saya.
Biar saya punya jeda juga buat istirahat, saya naikin deh. Chapter 29 akan diunggah kalau chapter 28 udah 260 votes. Saya serius, ini supaya ada jeda buat sayanya saja. ☺ Semoga kalian bisa memahami. Lagian saya yakin ko kalian bisa patungan ngumpulin 260 votes dalam waktu kurang dari seminggu. Kalian mah keren. Kesayangan saya. Minta doanya ya supaya urusan saya bisa terselesaikan dengan lancar. 🙌
Selamat membaca ☺
*tidak perlu komentar tentang typo. Nanti saya akan patroli sendiri. ☺
***
🎻Louisa🎻
***
*Budayakan vote sebelum baca. Sementara kamu dibahagiakan oleh yang bikin cerita dengan unggahan chapter baru, caramu membahagiakan sudah cukup dengan ngasih bintang. Karena kamu tidak tahu apa yang sudah dikorbankan oleh kami untuk bisa mengunggah chapter baru. ☺
10 Tahun Kemudian
"Kamu kapan pulangnya?" tanyaku. Ini kali ketiga aku meneleponnya.
Setelah menikah dan sekarang sedang hamil anak pertama, jujur aku merasa sangat perlu berada di sisinya setiap saat. Bahkan seperti lebih baik dia nggak usah kerja, di rumah saja, atau kerja dari rumah kalau bisa. Tapi dia juga punya tingkat kepanikan yang berlebih semenjak aku hamil. Dia semakin sigap mengangkat panggilan teleponku setiap saat.
"Aku udah di gerbang komplek. Kamu nggak lagi ngerasain sesuatu atau tanda-tanda mau lahiran, kan?"
"Emang acaranya udah selesai?" padahal aku hamilnya baru lima bulan. Mana ada lahiran.
"Kamu gimana sih?" keluhnya, "Tadi minta aku buru-buru pulang, giliran aku udah pulang kamunya malah bersikap seolah khawatir sama pekerjaanku. Kamu itu nggak tahu, ya? Telepon dari kamu itu bisa mengguncang jantungku dalam hitungan detik. Takut kamu lagi ngangkang di lantai mau lahiran, nggak ada orang, dan aku jadi calon ayah yang nggak bertanggung jawab gara-gara istrinya lahiran tanpa pendamping. Ya Allah, ngebayangin aja udah horor banget."
Aku tergelitik mendengar ocehannya, "Nggak, ih. Bawa apa?"
"Bawa apa?"
"Ih, kan aku pingin gulai yang di perempatan itu. Nggak jauh dari kantor kamu malahan, ihhh."
"Astaghfirullah!"
"Oke, pasti lupa! Aku nggak mau buka pintu. Tidur di luar, titik, pakai tanda seru!"
"Galak amat istriku."
"Ya kamunya sih, ih!" aku mulai manja, ya ampun. "masa, aku cuma pengin itu aja. Tiga hari ini aku belum minta yang nggak ada di kulkas tau."
"Ya itu bagus kan."
"Bagus apanya? Bagus karena kamu nggak perlu repot-repot nyari, iya?Oh, bagus karena kamu nggak perlu ngeluarin duit lima puluh ribu buat istri kamu sendiri, iya? Yang di perut aku itu anak kamu tau."
Dia tertawa terbahak-bahak. "Santai dong, Nyonya. Ini aku beliin gulainya. Sekalian sama lontong bakar yang dibungkus daun pisang."
"Awas kalau bohong. Aku aduin ke Mama mertua. Biar kamu diomelin sampai abis."
Dia masih tergelak. Suara deru mobil berhenti di gerbang rumah tak lama kemudian. Aku segera berlari ke sisi jendela. Menyingkap tirai dan memastikan kalau itu memang mobilnya. Dia keluar dari mobil dan membuka sendiri gerbang depan, lalu menggemboknya lagi setelah berhasil memasukkan mobil ke halaman depan di bawah kanopi.
"Ini aku udah di depan pintu. Bukain dong."
"Kamu bawa nggak?"
"Iya bawa."
"Awas ya kalau bohong."
"Buka dulu pintunya, nanti kamu lihat apa yang aku bawa."
Aku menuruni tangga pelan-pelan. Membuka pintu dan mendapati dia sedang menempelkan ponsel ke telinga, masih berpakaian rapi dalam kemejanya. Lalu memasukkan ponselnya ke saku. Tapi dia nggak bawa apa-apa.
"Oke, fix. Kamu tidur di luar."
"Lebih penting aku atau gulai sama lontong itu?"
"Ya gulai sama lontong, lah."
"Ya ampun."
Dia akhirnya menyerah. Tubuhnya memutar balik ke mobil dan mengambil sesuatu di jok belakang. Itu yang aku pesan tadi!
Aku menggigit kedua bibirku menahan tawa, menang.
"Ini pesanan Anda, Nyonya Louisa."
Lalu aku melebarkan lengan dan menangkapnya dalam pelukanku. Dia memeluk sampai membuat tubuhku terangkat. Aku mencium setiap inci wajahnya yang kelelahan. Tapi aku tahu dia tidak akan lelah kalau mendapat sambutan seperti ini. Dia memperlakukan hal serupa padaku.
"Plis, jangan bikin aku pengin itu di ruang tamu," katanya berlagak kalah.
"Apaan sih!"
"Hehe."
Lalu dia melakukan ritual khususnya setiap mau pergi atau pulang. Yaitu berlutut dan mencium perutku, "Ayah pulang, Nak. Kamu nggak rewel, kan? Nggak bikin Momi kerepotan, kan? Momi memang galak, jadi kamu jangan bikin dia marah-marah, ya?" dia menciumnya sekali lagi setelah mendapat jeweran dariku.
"Huh, capek banget," dia duduk membelesak di sofa ruang tengah. Tangannya meraih remot dan menyalakan acara komedi yang masih tayang di pukul setengah sebelas malam.
Setelah aku mengambil peralatan makan. Dia membantuku menuangkan dua bungkus gulai yang udah nggak terlalu panas itu. Aku mengiris lontong bakar kesukaanku ke dua piring yang berbeda. Sesekali dia tertawa melihat adegan konyol di tv. Aku tak menghiraukannya, biarkan dia menghibur diri setelah seharian ini berlelah-lelah mencari nafkah.
Kami sama-sama sibuk setiap harinya. Aku dari pukul sebelas siang sampai empat sore berada di sanggar. Ngajar tiga kelas biola tanpa jeda. Apalagi tiga anak didikku ada yang berencana mau ikutan audisi Indonesian Got Talents tahun ini, jadi aku ekstra keras membantu mereka bikin improvisasi lagu.
Sebenernya aku kasihan sama suami. Tiap hari harus ngurusin kerjaan di dua tempat yang berbeda. Aku tahu nggak bisa bantu banyak. Mungkin cuma bisa ngasih perhatian selayaknya aku sebagai istri ke suami, ngasih dukungan ke dia, jadi teman sekamar yang betahin, bikin masakan yang enak apalagi dia doyan makan banget, dan jadi orang yang bahagia. Katanya sih aku nggak perlu ngasih apa-apa selain berbahagia dan jangan berhenti bersikap manja. Terdengar sempurna banget ya dia? Eh, nggak! Aku cuma nggak mau ngomongin kekurangannya aja. Banyak dong mestinya. Ya aku juga sama banyak kurangnya, tapi biarin aja, aku mau ngomongin baik-baiknya dia aja. Tapi tapi tapi, ada satu hal deng yang perlu diketahui siapa saja biar nggak ribut kalau lagi bareng suami aku, yaitu jangan sampai buang gas di dekat dia! Demi menjaga batas itu, dia sampai rela pergi ke toilet cuma buat buang gas. Serius.
Pernah, kita lagi ngambek-ngembekan gitu. Aku sih yang salah. Dan dia itu lagi susah-susahnya diajak baikan. Karena aku udah jengkel banget, yang ibaratnya kayak udah ngusahain ini itu tapi dia tetep kayak anak kecil ngambeknya, gilak. Dia yang lagi main game di kamar, serius, aku kentutin di depannya sambil lewat.
"Sayang!" teriaknya sambil menjatuhkan ponselnya di kasur. Wajahnya kayak yang 'plis deh nggak perlu kentut juga'.
"Noh, rasain. Awas ya kalau kamu masih ngambek kayak gitu lagi. Aku abis beli ubi di pasar dan mau makan telor asin yang banyak, ngunci kamu di kamar, dan kentut sepuasnya."
"Ih, mainnya gitu lah," dia menggelung badan di tempat tidur sambil nutupin bantal di atas kepalanya. Seolah-olah aku baru saja melepaskan gas mematikan di kamar kita, "Soalnya, nih ... kamu kan udah janji mau nonton dvd itu bareng aku, kan?" katanya lagi masih di bawah bantal, "terus kamunya diem-diem nonton duluan kan nggak asik. Kamu itu orangnya spoiler parah."
"Iya, iya, aku janji nggak akan ngulangi lagi, Ya Allah."
Dia nggak bergerak hampir semenit penuh sampai kukira pingsan. "Masih bau nggak kamar ini?" katanya tiba-tiba.
"UDAH ENGGAK."
"Serius? Demi apa?"
"Ya ampun! Demi suami aku."
Lalu dia mengangkat bantal. Bergegas ke kamar mandi. Ngapain coba? Cuci muka, gosok gigi, kumur-kumur entah berapa kali. Aku bener-bener nggak ngerti imajinasi dia seperti apa tiap kali denger suara kentut dan mencium baunya. Keluar dari kamar mandi dia masih punya tatapan dendam di matanya, tapi aku yakin emosinya udah hilang.
"Aku udah boleh peluk nggak nih?" tanyaku.
"Iya." Dia mengangguk.
Lalu aku berjingkat ke arahnya dan memeluk. "Maafin aku ya, udah bikin kita ngambek-ngambekan seharian ini."
"Iya, aku juga."
Udah baikan gitu kan, tiba-tiba entah hidung dia yang setajem apa, dia nyeletuk, "Ko masih bau sih?" padahal dari awal bom itu meledak juga nggak ada bau apa-apa, sumpah!
Langsung deh, aku ambil parfumnya dia di meja, aku semprotin ke tempat di mana aku buang gas, sampai aku semprotin ke wajahnya. Well, dia nggak marah, cuman ya gitu, akunya yang jadi kesel.
Tapi ya ginilah pasangan. Kalau udah klop sama dia pasti sampai enggan beranjak darinya entah senyebelin kayak apa kekurangan yang dia punya. Setidaknya begitu, dan kita berdua udah belajar menerima satu sama lain secara serius sejak beberapa bulan sebelum kita menikah. Yang kumaksudkan serius itu sejak dia resmi melamar aku, ya.
"Abisin dong," ucapnya ketika gulai di piringnya udah kosong.
"Pasti abis. Aku mah makannya pelan-pelan, nggak kayak kamu."
"Aku laper banget asli."
"Salah sendiri nggak sekalian makan di sana."
"Sekarang iya bilang gitu," dia memainkan tusuk gigi di mulutnya, "kalau aku beneran makan di luar pasti kamunya yang uring-uringan."
Aku menyeringai padanya.
Kita di depan tivi cuma sampai acara komedi itu selesai. Aku membereskan semuanya, sebelum narik-narik dia supaya sikat gigi bareng. Lalu ke tempat tidur deh. Dia selalu memasang posisi tidur kesukaannya hampir setiap malam, yaitu telentang dengan kaki kanan ditekuk. Lengan kirinya membentang di bantalku supaya aku bisa meletakkan kepalaku di atas bisepnya yang berukuran biasa-biasa saja. Dia nggak berotot memang, tapi tetap menarik untuk terus bersamanya.
"Ada kejadian apa hari ini?" aku bertanya.
"Nggak ada apa-apa. Sama seperti hari senin yang biasanya terjadi."
"Oh."
Dia memiringkan tubuhnya ke hadapanku, "sayang."
"Mm?" aku memegang pipinya yang baru minggu pagi kemarin aku cukur.
"Pendapatmu gimana kalau kita punya pembantu?"
"Kenapa kamu merasa kita perlu?"
"Aku cuma mikirin aja, misal nanti anak kita semakin membuat perutmu membesar. Kamu udah ambil cuti ngajar, kan bakal kerepotan banget kamunya," dia bilang begitu.
"Tahu nggak?" ucapku.
"Apa?"
"Mama ngebesarin aku itu nggak perlu yang namanya pembantu. Malah nenek aku yang di Makassar nggak lantas dibawa ke sini buat ikut ngurus. Aku juga ingin kayak gitu. Ya maksudnya cuma aku sama kamu aja."
"Kamu yakin nggak nih?"
"Jangan nanya aku deh. Coba pertanyaannya aku puter balik, kamu siap nggak ngedampingin aku buat membesarkan anak kita?"
"Aku sih yakin banget."
"Nah, ya udah. Lagian kalau kita bisa ngelakuinnya bareng-bareng kenapa harus susah-susah ngeluarin duit buat mempekerjakan orang?"
"Bukan gitu. Aku cuma khawatir aja beneran. Tabungan kita lebih dari cukup untuk sampai persalinan nanti dan kayaknya aku juga nggak keberatan kalau harus jadwalin gaji buat pembantu gitu."
"Beneran, aku bisa."
"Ya udah, kita bakal bareng-bareng deh."
Dia menggelempangkan tubuhnya sampai memelukku. "Kamu kalau mandi jangan kesorean. Mending abis asaran aja."
"Lah kenapa?"
"Kan aku udah bilang, aku lebih suka aroma kamu yang tanpa tambahan parfum. Kalau mandinya telat kan aroma kamu masih wangi."
"Dikit aja tadiii."
"Kamu kalau bisa beli parfum yang waktu kuliah dulu kamu pakai dong."
"Kuliah?"
"Iya. Aku kalau mencium aromamu waktu itu, makin jatuh cinta. Dan jatuh cintanya seperti ke jurang yang dalam, nggak sampai-sampai ke dasar."
Aku mencubit dadanya sampai membuat dia menjingkut. "Bokis banget."
"Ye, nggak apa-apa lagi."
"Jujur aku lebih suka parfum kamu pas SMA dulu. Aromanya misterius. Seperti ada timbunan rahasia sebelum aku benar-benar semakin sangat ngenalin kamu."
"Oh, jadi kamu dulu naksir banget ya sama aku? Pasti sekarang merasa beruntung banget ya sama aku nikahnya."
"Ihh pede banget sih. Nggak juga."
Dia menggelitik tulang igaku sambil terus mendesak, "Ayolah. Ngaku deh."
Apa yang dibutuhkan kebanyakan perempuan adalah seorang laki-laki yang tak hanya pantas dijadikan suami, tapi juga bisa menjadi teman hidup yang benar-benar seperti sahabat. Mungkin aku sama dia termasuk pasangan yang rajin banget ketawa bareng. Satu hal yang menarik lagi, kita jarang membicarakan masa lalu. Meski, sepertinya itu masih tetap jadi permen karet paling awet untuk dikunyah dalam kepala kita. Tidak membicarakan bukan berarti tidak memikirkan. Itu sih menurutku.
Aku nggak tahu gimana harus menceritakan bagian di mana aku mulai menyadari, bahwa orang yang sekarang terlelap memelukku adalah apa yang sebenarnya aku butuhkan. Orang yang sebenarnya sudah digariskan untuk harus ada di sisi lain tempat tidurku, menitipkan anaknya di dalam perutku, dan, ya, yang disebut jodoh itu kadang emang nggak jauh-jauh dari kehidupan. Kita cuma perlu dihampiri momen yang tepat untuk menyadari dan memutuskan.
Sebentar lagi aku akan menjadi ibu. Aku bahagia ketika mendapati aku bisa hamil. Aku tahu, aku pasti akan merasa sangat bersalah jika tidak bisa memberi suami keturunan. Itu yang aku takutkan sebelum menikah. Cuman aku udah yakin bakal bisa bahagia bareng dia. Dan akunya aja yang lumayan kepikiran banget takut nggak bisa bikin dia bahagia. Tapi pada akhirnya, ya, kita bisa membahagiakan masing-masing. Meskipun ... mm, kan, ... mulai lagi. Aku masih sempet kepikiran seseorang yang lain. Bukan! Ini bukan seperti aku yang diam-diam berempati pada laki-laki lain. Hanya saja kudengar sampai sekarang dia masih lajang.
***
10 Tahun Yang Lalu
Di satu sisi aku juga merasakan kekecewaan yang lain. Mama benar-benar tidak ingin aku terlibat dalam pembicaraan mengenai Papa. Jadi obrolan mereka tertutup hanya untuk keluarga. Bahkan Om Zaryn tidak bisa ada di tengah pembicaraan. Mereka pamit tak lama setelah memastikan akan ada pertemuan kembali grup pertemanan yang dulu.
"Aku yakin masalah ini akan terselesaikan," Alex optimis sekali mengatakan itu padaku.
"Tapi sama saja bohong kalau aku nggak dikasih tahu apa-apa. Mama bahkan nggak ngebolehin aku ada di pembicaraan itu."
"Aku pikir memang sebaiknya kamu jangan dulu ikut berbicara. Biarkan mereka selesaikan masalah ini dulu. Yang penting kamu jangan sampai kalap sama emosi."
"Sebelum datang masalah ini aku juga merasa ada banyak rahasia yang coba Mama sembunyikan dariku, Alex. Seperti aku hidup di antara kepura-puraan yang tersamarkan dengan sempurna."
"Aku nggak bisa ngasih petunjuk apa-apa. Karena aku tidak tahu menahu soal urusan itu. Dan apa kaitannya dengan ayahnya Nafis?"
Alex meraih jaket parka berlogo jurusan kuliahnya di sandaran kursi. "Pakai ini," katanya pelan.
"Aku udah pakai sweater, Alex."
"Iya, tapi itu punya Nafis."
"Kita udah ngobrolin ini. Kamu jangan mulai bikin aku kesel lagi, deh."
"Ini supaya aku bisa lebih tenang aja. Aku merasa gagal berkali-kali kalau kamu terus-terusan merasa hangat dari sweater milik orang lain, oke? Pakai punya aku."
Aku menatapnya tidak habis pikir. Tapi dari pada memulai sitegang lagi, dan aku memang melihat garis-garis khawatir di wajahnya, maka aku menuruti. Aku melepas sweater hingga hanya berkaos, lalu menggantinya dengan parka itu.
"Puas?" tanyaku. Dia tersenyum geli. Mencubit pipiku sekali saja.
"Aku yang salah, bukan kamu."
"Ya memang kamu."
"Nafis sudah mencoba ngasih tahu aku kalau kamu sedang sangat tidak baik dan butuh aku. Itu sebabnya sehabis dia telepon, aku langsung minta dipesankan Uber. Aku dipaksa sama trainer supaya tetap tinggal, tapi diri aku sendiri juga memaksa untuk pergi. Hujan gede, kan. Ya udah aku pergi, terus lihat kamu sama Nafis lagi di halte, terus kalian boncengan sampai ke rumah gede itu."
"Kamu tahu kenapa aku ngikutin dia?"
Alex mengangkat bahu.
"Ada yang coba Nafis kasih tahu tentang Mama aku."
"Apa hubungannya dengan dia?" dia benar-benar bertanya.
"Sebenarnya bukan Nafis. Tapi ayahnya."
Alex mengangguk-angguk.
"Ayahnya Nafis dan mama punya persahabatan yang kuat waktu kuliah. Mereka punya semacam kelompok pertemanan. Tapi Mama memisahkan diri dari mereka."
"Kenapa?"
"Itu dia. Om Zaryn nggak ngasih tahu ke aku, dia cuma terlihat sangat bahagia waktu tadi tahu aku ini anaknya Mama. Tentu dia mengenali. Dan katanya memang saat pertama ketemu aku, beliau udah mulai menaruh curiga. Atau menduga-duga."
"Waw," dia berwaw dengan suara yang berat.
"Kamu tahu nggak? Kisah hidup mereka itu dibukukan. Sebenarnya itu porosnya di Om Zaryn."
"Maksud kamu dibukukan?"
"Ya, ada novelnya."
"Beliau nulis sendiri?"
"Bukan, Sahlil Ge yang nulis."
"APA??"
"Ya."
"Masa sih? Aku koleksi semua buku-bukunya dia. Dan nggak ada deh bukunya yang berkisah tentang karakter yang benama Zaryn atau ibu kamu."
"Alex, itu dia. Buku itu nggak dipublikasi secara masiv. Memang cuma orang-orang tertentu saja yang punya."
Dia berusaha berdiri tapi kesusahan.
"Kamu mau ke mana?"
"Ambil buku-bukunya Ge. Aku mau periksa sekali lagi."
"Biar aku yang ambilkan."
Aku berjalan ke rak lemari buku yang sudah berjubel. Dan ternyata Alex meletakkan bukunya Kak Ge di satu lot, berjejeran. Dan totalnya ada belasan. Aku malah nggak pernah tahu kalau Alex salah satu pembacanya Kak Ge. Aku tidak terlalu rajin membaca, bahkan buku yang waktu itu dikasih secara langsung sama beliau belum aku baca.
Aku memeriksa satu persatu dan nggak ada satu pun yang berjudul dua buku itu. Aku menggeleng padanya, "Nggak ada, Alex."
"Berarti bener buku itu memang tidak dipublikasi luas."
Saat itu sebuah gagasan melintas di kepalaku. Kalau tidak salah aku pernah mendengar obrolan Mama dan Kak Ge bahwa mereka berdua yang paling tahu cerita sebenarnya bahkan ketika Oranje berjauhan.
"Alex, aku mungkin nggak bisa dapat informasi dari Mama. Tapi mungkin aku bisa mendapatkannya dari Kak Ge."
"Ya, itu mungkin saja."
"Bukan mungkin lagi."
"Kirimi saja email ke beliau. Aku pernah hadir di bedah bukunya, beliau bilang cukup responsif kalau ada pembacanya yang kirim email."
"Kenapa harus email kalau aku bisa membuat janji temu sama dia."
"Kamu nggak bakal bisa, Lou. Sibuk pasti. Lagian kamu harus nyari jadwal bedah bukunya yang terdekat."
"Bukan itu, aku punya kontak WA-nya."
Mata Alex melebar, "Asli?"
"Waktu main ke rumah, Kak Ge ngasih kontaknya ke aku, katanya-."
"Sahlil Ge main ke rumah kamu???"
"Ya."
"Kapan?" tanyanya sambil serius memegangi lenganku.
"Waktu awal aku masuk SMA."
Alex tertegun, "Dan menurutmu beliau masih mau kalau kamu mengajak janji temu?"
"Aku coba dulu."
Alex meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya sendiri, "Kamu punya kontaknya Sahlil Ge dan bisa membuat janji temu? Kenapa aku baru tahu?"
Aku baru bisa sedikit tersenyum kali ini, "kamu suka baca buku-bukunya?"
Tangannya mengibas, "persis waktu aku masih di RS," dia ngomongnya serius sekali, "beiau diundang anak Sastra UI buat bedah buku, tapi akunya nggak bisa datang. Padahal ada lima buku yang belum dapat tanda tangannya."
"Terus kalau ternyata beliau menyanggupi janji temu sama aku gimana?"
Alex menggeleng-geleng, "Aku harus ikut."
Aku lantas mengetik pesan dengan sangat santun untuk beliau. Aku menceritakan semua informasi sebanyak yang aku tahu dan bisa membuatnya mempertimbangkan untuk bertemu denganku.
"Bagaimana?" Alex benar-benar menunggu.
"Belum dibalas. Tapi sudah terkirim."
Alex meminta ponselku untuk melihat foto profilnya.
"Itu foto anaknya," kataku.
"Kamu udah pernah ketemu anaknya juga?"
"Sama istrinya juga kan main ke rumah."
"ISTRINYA JUGA?"
"Serius Alex, jangan berlebihan."
"Nggak, Lou. Aku itu bener-bener minat sama beliau." Wajahnya antusias sekali.
"Kamu sudah baca semuanya?"
"Aku sudah baca semuanya. Pertama yang kubaca Imam Masa Depan. Cerita itu terlihat seperti realsitis, seolah tokoh Abimana adalah Sahlil Ge itu sendiri. Tapi nggak mungkin. Dan buku keduanya, Tasbih Sang Kiai. Aku belum bisa menerima kejadian tragis tiga karakter penting di buku kedua itu. Aku sampai sekarang masih tidak habis pikir kenapa ada musibah sebanyak itu dalam satu buku. Dan yang dikorbankan harus mereka-mereka yang aku pikir akan sangat baik. Bahkan sampai adegan tembak-tembakan pistol ada dikemas dalam buku religi. Sahlil Ge itu pencerita yang kejam tapi nggak bisa bikin aku berhenti baca kekejamannya. Kamu harus baca kedua buku itu, Lou."
Aku mendengarkan Alex bicara dengan cermat. Karena tidak biasanya dia menceritakan hal-hal seperti itu. Kukira selama ini mainannya hanya piano. Ternyata dia cukup baik memahami bacaan.
Ponselku membunyikan sebuah notifikasi pesan.
"Alex," kataku.
Dia sedang meraih kruk-nya. "Hum?"
"Lusa."
"Apanya?"
Aku menunjukkan balasan dari Kak Ge.
***
Hari pertemuan dengan Kak Ge, aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya akan mengarahkan pembicaraan ke topik yang informatif buatku. Alex sudah bisa hanya menggunakan satu tongkat saat turun dari mobil pesanan kami. Dia juga sudah sanggup berdiri dan melangkah tanpa tongkat sebenarnya. Tapi masih terlalu berbahaya kalau dia memaksakan diri tanpa tongkat.
Kulihat Kak Ge sedang sendirian di sebuah kursi restauran. Di mejanya sudah ada dua gelas minuman dingin dan satu teh milik beliau, kurasa. Tangannya melambai begitu melihatku.
"Kamu nanti kenalin aku, ya?" Alex berbisik saat kami berjalan pelan.
Aku memutar bola mata, "Iya."
Aku menyalaminya dengan sopan. "Silakan duduk," pintanya ramah. "Naik motor?"
"Uber, Kak," jawabku.
Alex benar-benar terlihat gugup. Tidak banyak bicara. Saat dia mulai berdeham, aku tahu ketidaksabarannya sudah mempengaruhi kenyamanannya.
"Um, Kak, ini Alex." Mereka berdua bersalaman.
"Oh, pacarnya Louisa itu? Gimana keadaannya, sehat?"
Aku sedikit tersipu. Alex terkejut mendengar Kak Ge yang seolah tahu tentang dirinya. Garis-garis wajah Alex mengisyaratkan dia sedang terkesan. Itu bukan karena Kak Ge mencari tahu, tapi Mama yang pasti memberitakan tentangku. Mereka berkawan cukup baik, kan.
"Ya," jawab Alex. Napas di dadanya terhela seolah baru dia tahan beberapa saat. "Saya pacaranya Louisa," dia mengatakan dengan bangga. "Dan saya cukup sehat untuk datang ke sini."
"Syukurlah, Mamanya Louie pernah cerita tentang kalian. Karenanya saya sedikit tahu."
Aku menahan Alex saat tangannya hendak membuka zipper tas. Dia pasti tidak sabar ingin menunjukkan buku-buku itu. Tapi itu bisa nanti!
"Um, saya pesankan minuman itu. Silakan, diminum. Mumpung lagi santai sayanya."
"Nggak lagi sibuk nulis, Mas?"
Alex! Aku ingin mencubitnya.
"Tidak. Lagi ada penyelarasan naskah film. Jadi diistirahatkan dulu nulisnya."
Alex mengangguk pelan. Aku segera mengambil alih pembicaraan sebelum Alex semakin ingin bertanya.
"Jadi, Kak," aku berkata. Dan beliau mengangkat kedua alisnya. "Saya udah bilang sebelumnya di pesan. Ini tentang Mama dan Oranje."
"Saya udah bisa menalar masalahnya," beliau menjawab. "Ini cukup bisa saya pahami. Kamu sudah besar dan, ya, wajar kamu ingin tahu."
Aku dan Alex menyimak. Rasanya tak berani menyela kalau beliau sudah berbicara.
"Jadi apa yang ingin Lou tahu dari saya?"
"Mungkin, saya ingin tahu kenapa Mama begitu menjaga jarak dari teman-temannya. Itu aja dulu, Kak."
"Tunggu, Om Zaryn udah ketemu Mama kamu, kan?"
"Iya. Kemarin malah Mama udah ke rumahnya, ada reuni kan sama temen-temen kuliahnya dulu. Saya sih nggak tahu gimana acaranya karena harus ke sekolah."
"Oranje kumpul lagi?"
"Iya. Kakak nggak tahu?"
"Belum."
"Jadi bagaimana?"
Kak Ge berdeham, "Saya juga tidak tahu banyak. Tapi kalau Lou ingin tahu, ada beberapa informasi. Mama kamu tidak melarang saya untuk bercerita ke kamu, dia cuma melarang memberi tahu ke Oranje saja."
Dan akhirnya, Kak Ge menceritakan banyak informasi. Satu-satunya masalah yang membelit hanya ada di Mama. Sejak dulu waktu Mama masih bekerja di ekspor-impor, Kak Ge bilang bahwa Papa melamar Mama. Tapi, setelah lama cincin itu ada di jari Mama, restu dari keluarga Makassar belum juga diberikan. Akhirnya mereka berdua rela untuk menahan diri sampai mendapat restu. Begitu direstui kedua belah pihak, mereka menikah. Tahu tidak? Restu itu diberikan setelah Mama mendonorkan satu ginjalnya untuk adik laki-lakinya yang pesakitan. Aku tidak tahu entah itu sebuah pengorbanan atau apa. Tapi, demi apa saja aku masih belum menyangka tentang itu. Kalian boleh tidak percaya kalau mau, karena aku juga berusaha tidak mempercayai kalau selama ini mama hidup dengan satu ginjal saja. Namun, kalian atau pun aku, pasti akan susah menyangkal jika informasi ini dikaitkan dengan Mama yang sakit-sakitan. Dan ini masalah kedua yang membuat mama menghilang dari teman-temannya.
Lalu apa masalah pertamanya?
Sebelum Mama mengandungku. Masalah serupa yang dialami Papa muncul untuk yang pertama kalinya. Sebagian besar keuangan mereka dientas habis untuk menebus kecelakaan finansial itu. Berita tentang Papa semena-mena tersebar kotor di banyak media. Dan itu alasan pertama kenapa Mama perlahan menghilang. Dia merasa malu dengan teman-temannya. Malu karena pesakitan dan malu karena kasus Papa. Mungkin lebih karena Mama tidak ingin teman-temannya berempati. Kalian tahu kan? Mama orangnya sangat independen. Saking begitunya dia tidak begitu mengharapkan banyak belas kasih dari orang terdekatnya.
Perlahan semuanya berlangsung membaik. Tapi naasnya beberapa tahun kemudian ketika keuangan kami sudah kembali sehat dan sangat sejahtera, kecelakaan serupa terjadi lagi. Dengan biaya denda yang lebih besar bahkan itu yang membuat Ayah nekat melesat ke Brunei untuk mendapatkan pundi-pundi nafkah yang lebih. Om Irfan juga membantu banyak di sini. Ya, wajar, Papa adalah adik kandung Om Irfan.
Kepalaku masih pening. Aku tidak berpikir kalau informasi yang akan kudengar akan serumit itu.
Alex berhaslil mendapatkan selfi kebanggannya dengan Kak Ge, juga autograf khusus di lima bukunya. Setelah itu kami berpamitan.
Aku mungkin saja bisa mendapatkan informasi yang lebih dari ini, tapi aku menahan, aku belum terlalu siap untuk mengetahui semuanya.
Tepat saat perjalanan pulang, ada satu pesan masuk dari Kak Ge. Kurasa dia masih belum beranjak dari tempat duduknya tadi.
"Ada alasan lain yang perlu Lou tahu. Oranje pernah bercita-cita kalau di antara mereka harus ada yang berbesan. Dan yang mencetuskan cita-cita itu adalah Mama kamu. Itu wajar, banyak pertemanan yang berharap bisa begitu. Dan sepertinya Mama kamu juga merasa tak enak hati karena ada masalah soal Papa kamu. Sebab, sebelumnya Om Iqbal dan Mama kamu istilahnya ingin berbesan. Kaka bilang ini supaya kamu tahu, seandainya memang Lou ingin tetap sama Alex. Buatlah jawaban yang kuat supaya ketika Lou ketemu dengan Mas Febri anaknya Om Iqbal bisa baik-baik saja."
Mas Febri siapa? Jantungku berdebar kencang. Alex benar-benar tidak boleh tahu soal ini.
Aku membalas, "Ka, :( . Kalau itu benar, sepertinya Mama pun nggak akan melanjutkan cita-citanya."
"Semoga begitu. Tapi siapa tahu? Oranje sudah berkumpul kembali. Pasti obrolan itu akan kembali menghangat." Balasnya lagi.
***
Jadi, sebenernya siapa yang bikin suasana kacau? 😆
Sampai jumpa di chapter 29. ☺
Jangan lupa kasih bintang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top