Chapter - 27: Sorrow
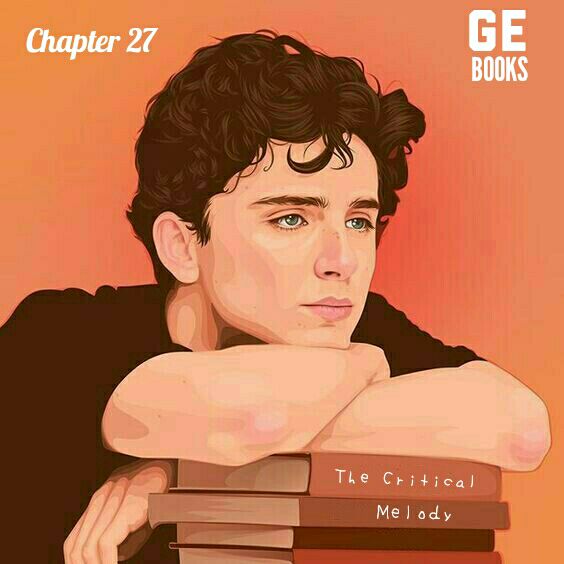
***
Sebelum kalian membaca saya ingin menunjukkan ini dulu. Akan ada judul baru yang siap menggantikan The Critical Melody setelah tamat nanti.
Dan mulai chapter 27 ini sampai tamat saya akan menampilkan klu yang bisa kalian jadikan sebagai petunjuk untuk menebak judul atau membayangkam ceritanya akan jadi seperti apa. Pastinya ini sebuah Fiksi Remaja yang saya kemas dengan beberapa komponen, yaitu Classical, Historical, Riddle, Mistery, Crime, Romance dan Fantasy.
Ini tiga gambar pertama yang ingin saya tunjukkan, silakan berandai-andai:



***
Chapter 28 akan saya unggah kalau Chapter ini sudah mencapai 210 Vote. Kenapa naik? Karena biar kalian gereget nungguinnya. Dan ada jeda supaya tidak terlalu sering. Biar kangen juga.
***
***

***
🎸Nafis🎸
***
Demi karang yang tak pernah mengaduh ketika digempur ombak,
Awang yang tak pernah menjerit ketika dipecut kilat,
Kemarau yang tak akan merintih untuk dikecup hujan,
Senar yang tak penat berdenting melagukan,
Dan Kepada hati yang tak bergeming ketika rindu menikam,
Aku ingin bicara pada sepi;
'Tetaplah kau diam, rahasiakan dari hatinya tentang dia yang terpenjara di kepalaku sekian lama,'
Sepi janganlah kau berbisik,
Biarkan ini jadi kedap,
Biarkan laki-laki ini tak perlu memaksa diri untuk hidup seperti mati,
Kiranya cukup untuk aku menggeligis di ceruk kalbu dan meratapi.
...
10 Tahun Kemudian.
Jarum panjang di dinding sudah bertolak sejauh tujuh titik dari angka sembilan. Gue mengambil jas di kursi untuk disampirkannya pada lengan kiri, mengemasi berkas ke dalam tas sling sebelum menyantelkannya di pundak, dan menyesap genangan teh terakhir yang sudah mendingin. Gedung perkantoran ini kian sepi dari geliat pegawai-pegawai. Hanya ada suara gerak OB yang sedang menyapu lantai, mengumpulkan timbunan abu tembakau di asbak, merapikan kertas-kertas, dan salah satu dari mereka terkejut saat melihat gue yang baru keluar dari ruang kerja gue sendiri.
"Loh, Pak Nafis belum pulang?" pemuda tanggung itu bertanya.
"Datang lebih awal, pulang paling akhir," jawab gue memberi senyum.
"Ada yang perlu saya lakukan di ruangan Bapak?"
"Seperti biasa, jangan sentuh kertas apapun kalau itu masih ada yang tergeletak di meja kerja saya. Memang sengaja tidak saya bereskan semua karena ada peta konsep yang dibiarkan terbuka. Cukup sapu lantai saja sama ganti hordeng. Karpet sama sofa bisa divakum?" pemuda itu mengangguk, "Besok ada tamu dari vendor. Jadi ruangan saya harus lebih rapi. Dan jangan ganti pengharum ruangannya, tetap yang aroma melon. Sori, Gus, ngerepotin."
Dia bersikap sangat hormat mendengar instruksi gue. "Siap, Pak. Malam ini juga kami kerjakan."
"Kerja yang bener, ya," gue menepuk pundak kecilnya sambil berlalu.
Jakarta malam sedang menggigil dikepung angin kemarau. Air tak pernah sebeku kali ini jika disentuh. Gue melajukan mobil di jalanan yang tak begitu padat. Menyetel lagu-lagu akustik di pemutar yang ada di dasbor. Satu tangan fokus pada kemudi, satunya lagi berupaya melepas dasi dan satu biji kancing atas kemeja.
"Lima belas menit lagi saya sampai di sana," kata gue ke Vira lewat telepon. Dia orang yang gue pekerjakan untuk memegang kafe selagi gue sibuk sama kerjaan inti.
"Tamunya udah banyakan?"
"Oke, Pak. Um, udah banyakan, sih, tapi ketolong sama anak-anak SMA itu. Mereka bagus juga penampilannya. Nggak salah Pak Nafis ngambil mereka dari almamater. Bagus!"
"Iya, bagus deh," gue bilang juga apa. Anak-anak akustik dari klub gue dulu memang selalu berbakat.
"Oh, iya, nanti sekalian saya mau ngasih laporan keuangan bulan ini. Kabar baiknya kita nggak ada defisit, kabar buruknya kasir kita resign."
"Nilam resign? Kenapa?"
"Dia kan keterima kuliah di Bandung, jadi ya, katanya sih besok udah harus berangkat ke sana. Nggak di sini lagi."
"Oh, kalau alasannya gitu ya saya dukung aja. Tapi dikasih gaji nggak sama kamu?"
"Tadi dia buru-buru pulang, rencana besok saya ke rumahnya atau mau buat janji temu untuk ngasih gaji."
"Oh, gitu. Vir, kasih dia tiga kali gaji, deh."
"Maksudnya?"
"Kasihan, dia udah lama kerja bareng kita. Saya juga senang denger dia udah mau kuliah. Itu catat aja sebagai balas jasa dari saya. Kira-kira ada nggak kasnya?"
"Ada sih, Pak."
"Kalau nggak nanti saya yang transfer ke rekening dia. Kamu nanti kirimin nomor rekeningnya Nilam aja ke saya."
"Eh ada kok, Pak, beneran. Masa harus pake uang Pak Nafis."
"Ya kan sama saja."
"Ada kok, berarti tiga kali gaji ya?"
"Iya. Sampaikan terimakasih dari saya, katakan untuk semangat terus kuliahnya, dan kamu mewakili kafe kita ya, Vir, minta maaf kalau ... kamu pahamlah."
"Siap."
Tak berselang lama setelah gue memutuskan panggilan itu, panggilan yang lain pun datang. Tapi kali ini dari seseorang yang sangat penting.
"Halo, ada apa, sayang?"
"Pulang jam berapa?"
"Mungkin jam sebelas malam aku baru pulang. Mau dibelikan sesuatu? Jangan minta mangga lagi, lho. Nanti mag-nya kambuh. Walaupun kamu ingin, coba alihkan ke yang lain kepinginnya, biar aku nurutinnya juga enteng. Oke?"
"Nggak, tadi ada orang yang main ke rumah. Nyari kamu gitu."
"Siapa?"
"Kurang tahu, tapi katanya pernah satu SMA bareng. Aku kasih alamat kafe kamu deh akhirnya."
"Jadi mereka mau ke sini?"
"Nggak yakin."
"Oh."
"Jangan kemalaman ya pulangnya."
"Iya, tapi jangan ngambek kalau jadinya malah kemalaman," gue meledeknya, "karena ini kan giliran aku yang tampil. Pekan spesial tiap akhir bulan. Meraki bakal ramai kalau aku ambil giliran."
"Ish. Ya sudah," gue tersenyum mendengar reaksinya.
Parkiran kafe sudah berdesakan, untungnya ada satu lot kosong yang selalu disediakan untuk mobil gue.
Tiga tahun berjalan kafe yang gue namai 'Meraki' ini sudah sangat menjanjikan. Dua kali tayang di acara tv yang membahas keunikan desain interior membuat Meraki semakin tersohor. Bersyukur, karena siapa yang menduga bahwa selama ini gue yang selalu labil milih jurusan kuliah malah sukses jadi wisudawan terbaik untuk jurusan Desain Interior di ITB. Dan gue butuh waktu jeda satu tahun saat itu untuk lanjut mengambil Arsitektur Lanskap tingkat master. Sampai akhirnya kedua jenjang pendidikan itu selesai, dan gue bisa fokus kerja.
Kalau membahas tentang jurusan dan apapun itu yang kaitannya tentang akademik, selalu ada hempasan akal yang tak ayal mengingatkan gue padanya. Dia yang telah pergi begitu lama. Meninggalkan hati yang begitu sepi, dan selama itu pula rindu belum sempat melipat jarak untuk bertatap. Ah, kau malam, janganlah berbintang untuk malam ini, kau tak boleh jadi lebih indah untuk laki-laki ini.
Meski gue sudah terjun pada dunia desain, tapi musik tetap menjadi hasrat lain yang alirannya sungguh kuat di pembuluh nadi. Pada awalnya mungkin ayah ragu, tapi kau hanya perlu memberi sebuah bukti dan pandangan jauh untuk sebuah itikad yang baik. Hanya perlu itu kalau ingin meluluhkan ayah. Akhirnya gue dikasih modal untuk pendirian kafe, bahkan hampir delapan puluh persen ide Meraki baik konsep maupun sistemnya adalah dari gue sendiri.
Setahun bareng Meraki, gue yang juga ambil posisi di perusahaan ayah akhirnya bisa beli rumah buat sendiri. Meski masih nyicil, tapi setidaknya bisa kami berdua tinggali untuk menyongsong masa depan bersama. Setidaknya untuk beberapa tahun yang akan datang.
Gue juga nggak mau jadi kacang yang lupa kulit. Setiap akhir pekan Meraki selalu mengundang anak-anak dari klub akustik di SMA untuk tampil di Meraki, udah rutin sih ini. Gue ingin mereka juga merasakan bagaimana bahagianya waktu gue tampil di kafe saat dulu. Dan khusus pekan tiap akhir bulan, gue selalu dapat giliran tampil. Kadang The Couple Goals juga ikutan datang. Yap, Yusuf sama Bre nikah akhirnya. Malah udah punya anak dua masih kecil-kecil.
Gue meminta Vira untuk menunda pembahasan laporan keuangan karena gue ingin mencoba fokus pada penampilan malam ini. Biar cepet beres, kasihan yang di rumah sudah nungguin. Belakangan gue nggak punya banyak waktu buat dia, gue tahu banyak yang harus kami berdua bicarakan.
"Thanks buat kalian semua yang udah pada hadir," sapa gue. Duduk di kursi berpenampang bundar tanpa sandaran tepat di panggung mini. Masih tetap kasual dengan kemeja yang tadi dipakai buat kerja, lengan disingsingkan sampi siku, dan bersikap santai di depan mereka. Gue nggak mau menghibur puluhan orang ini dengan penampilan yang kaku, karena gue tahu, Jakarta punya banyak orang kelelahan yang perlu dihibur hatinya. Apalagi di hari-hari terakhir tiap bulan. Untuk itulah Meraki hadir dan menghibur mereka yang akan menyongsong tanggal gajian.
Mereka bertepuk tangan.
"Selamat datang gue ucapkan. Kita bisa berjumpa lagi di hari-hari yang menjepit ini. Mari lemesin otot, karena bentar lagi gajian," gue membuat mereka berkelakar dan tergelak.
Di tengah tawa yang tak terlalu riuh itu tiba-tiba pintu depan terbuka. Gue biasanya nggak pernah fokus sama siapa saja yang keluar masuk melewati pintu itu. Tapi mungkin tidak untuk kali ini. Gue yang duduk di bawah sorot lampu ini terperanjat melihat sepasang manusia yang baru saja melewati pintu. Yang laki-laki berdiri satu langkah di belakang yang perempuan. Gue tidak tahu laki-laki itu siapa sebab dia berdiri di bawah bayang-bayang. Sementara perempuan itu ... dia berdiri di sana dan membuat napas gue sedikit terhisap entah ke mana.
Tapi gue harus tetap fokus meski hati gue sudah nggak karuan dan pikirannya sudah ingin menghampiri sosok itu.
"Terimakasih sudah datang," gue berkata melalui mikropon sehingga itu terkesan kepada semua hadirin.
Gue terdiam beberapa saat sembari memangku gitar. Sorot lampu yang jatuh melingkari gue seolah harus sekali menjadikan gue sebagai pusat dari segala perhatian. Dan hingga akhirnya jemari gue memetik nada pertama dari lagu The Critical Melody, memori gue seolah terhisap kembali dan diterbangkan hingga sampai ke masa itu. Sebuah masa lalu yang mengajari gue sebuah rasa tersayat-sayat dari tragedi putus cinta pertama kali.
***
10 Tahun Sebelumnya...
Saat malam itu,
Gue nggak ingin mengelak, tapi ternyata diputuskan dan menjadi patah hati itu rasanya sesakit ini.
Sebisa apa, demi Tuhan gue ingin banget nggak sampai nangis gara-gara diputuskan Rea. Karena gue sendiri yang pernah bilang ke Pian waktu dia agak mau nangis karena awal-awalnya dia ditolak sama Hanum; 'Cowok jangan sampai nangis kalau lagi patah hati.' Gue menenangkan begitu. Ternyata saat itu gue bukanlah lagi menguatkan Pian, tapi sedang menginjak-injak harga dirinya sebagai laki-laki yang sedang terluka.
Tepat saat gue udah nggak karuan banget rasanya isi kepala dan hati, gue mematikan laptop dan menggulung badan di bawah selimut. Gue membenamkan kepala di bawah bantal, air mata sialan itu keluar kayak disuruh aja. Rasanya diputuskan dengan alasan 'meski masih sayang' itu bener-bener malah mengundang marah. Nggak berlogika. Tapi gue juga nggak tahu! Ini marah atau kecewa atau luka yang pedihnya udah menyatu sama darah barangkali. Ya Tuhan, gue nggak boleh mulai lebay. Gue harus jadi lakik dengan tidak ber-, tapi rasanya sakit sangat lho. Dan nggak tahu kenapa gue mulai meninju-ninju kasur.
Kenapa Rea sampai mengambil keputusan itu? Kenapa harus diakhiri? Seolah setelah gue ditempatkan di dasar jurang lalu jurang itu diurug pakai timbunan tanah.
Sesaat gue mulai marah sama diri sendiri juga. Gue menyesal karena tadi sempat seperti marahin Rea. Tapi gue nggak bermaksud begitu. Gue cuma ingin Rea lihat apa yang harus gue alami untuk sampai pada titik lapang dada dan merelakan agar Rea di sana untuk berobat. Apa bisa dikata kalau dia malah melengkapi rencana gue dengan pernyataannya yang harus gue telan paksa. Getir. Masih nggak habis pikir.
Gue juga merutuk. Oke, gue memang PERNAH ada rasa sama Lou. Tapi... itu sangat dulu dan jauh sebelum gue benar-benar jatuh dan tenggelam ke dalam roman picisan gue bersama Rea. Tapi, ya, lagi-lagi mungkin gue memang salah. Gue memang berusaha bersikap baik ke banyak orang. Atau ... sveavicbalwefbe!
***
Gue tertidur tanpa menyadari labas sampai pukul sembilan siang dan bergegas keluar ingin ke kamar mandi. Saat melewati ruang keluarga, gue mendengar sayup-sayup seperti suara ayah. Tapi ini kan sudah siang? Kenapa dia nggak pergi ke kantor?
"Ayah tidak ke kantor atau mengajar?"
Dia menoleh dari sofa dengan wajah terkejut karena mendengar suara gue yang tiba-tiba, "Eh, Nak," tukasnya. "Ini Nafis udah bangun," gumamnya pada seseorang di panggilan, "Bundamu mau ngomong," katanya lagi sambil berjalan mendekati gue yang di dekat pintu. Ayah menyerahkan ponsel seolah benda itu adalah sesuatu yang sangat panas dan supaya segera beralih ke tangan gue.
"Iya, Bun," sapa gue.
Sambil berlalu melewati, tangan ayah seperti disengajakan memegang kening gue sebelum berjalan menuruni tangga. "Masih anget," gumamnya lirih.
"Fis, Bunda mau ke sana nanti sore."
"Ke mana?" gue bertanya.
"Ke Jakarta. Bunda nggak sampai hati dengar kamu yang demam-demam terus. Kamu harus disuntik imun sama Bunda."
"Bunda, nggak usah," gue serak, tenggorokan terasa perih.
"Suara kamu juga begitu. Nanti malah jadi radang, Nak. Kamu tidak usah banyak omong, Bunda tadi habis marahin ayah kamu. Dia lupa nggak beli sirop yang Bunda resepkan," oh, ini.
"Di sini banyak dokter juga. Nanti malah Bunda yang capek bolak-balik." Sebenarnya, ini lebih karena gue nggak ingin berurusan sama jarum.
"Udah, kamu diam saja. Bunda tahu kamu sakitnya di mana tanpa kamu bilang. Bunda sudah jadi dokter kamu sebelum kamu lahir." sakitnya di hati, Bunda, nggak mungkin tahu.
"Adek ikut?"
"Sama Simbah di rumah. Kalau ikut nanti malah minta main ke mana-mana. Kamu istirahat saja! ayah sudah telepon ke sekolah. Pokoknya Bunda khawatir. Kamu tidak perlu mengajari Bunda soal ini-itu, Bunda lebih tahu."
Gue nyerah kalau frekuensi bicara Bunda udah seperti ini.
"Ya sudah."
Lalu terdengar napasnya mengehela panjang, "sarapan dulu sana. Ayah kamu kalau Bunda marahin cuma diam sambil 'iya, iya' saja, padahal Bunda serius kalau minta ayahmu beli obat," sedikit dan hanya sangat sedikit gue ingin tertawa. Tapi cuma berakhir dengan sebuah eseman.
"Nanti kalau Bunda di sini, tidur sama saya, ya?"
"Iya, mau tidur bertiga pun terserah. Yang penting Bunda ingin lihat kamu saja."
"Maksudnya, Bunda tidur sama saya, itu sebagai hukuman buat ayah."
"Nak!"
Akhirnya gue benar-benar bisa melebarkan senyum. Meski untuk sesaat gue teringat apa yang membuat hari ini dimulai dengan hal yang tidak baik sama sekali. Bunda orang yang paling bisa gue andalkan untuk diajak bicara. Tapi apa iya, semisal gue harus membicarakan masalah gue ini sama Bunda? Itu nggak lakik namanya. Tapi kan Bunda dokter, barangkali gue bisa tahu sesuatu tentang parkinson.
***
Abis zuhur ayah pergi ke kampus karena ada urusan sampai asar. Tapi ternyata ayah belum pergi ke mana-mana. Saat gue keluar mau ketemu Mas Indra buat minta tolong dibeliin sesuatu, gue melihat ayah yang lagi ngobrol sama Pian di sana, deket pos satpam. Gue bahkan nggak tahu kalau Pian datang.
Mereka menatap gue. Baru setelah itu ayah pergi meninggalkan gue sama Pian. Gue tahu ayah ingin membicarakan sesuatu ke gue saat itu juga. Tapi dia mengurungkan dan melanjutkan mobilnya.
"Yan," gue menyapanya. Melupakan pertikaian kita yang semalam setelah gue pulang dari ruma Louisa.
"Fis, aku-."
"Masuk aja ke dalam. Jangan di sini," suara gue hampir hilang. Tenggorokan terasa garing dan nggak nyaman banget.
Gue mengajak Pian ke kamar. Karena gue keluar sebentar pun rasanya udah dingin banget padahal siang benderang.
"Aku minta maaf buat yang semalam," ucapnya dari kursi panjang dekat jendela.
Gue memakai jaket yang seperti jubah sebelum bergabung sama Pian di sana.
"Kamu ngomongin apa sama ayahku tadi?"
"Tadinya aku mau ngomong sama kamu dulu. Tapi aku pikir juga bagus kalau aku minta maaf sama ayahmu."
"Untuk apa?"
"Ya intinya aku merasa perlu."
"Dia bilang apa?"
"Ya biasalah orang tua. Tapi ayahmu nggak aku kasih tahu apa-apa mengenai yang sebenarnya terjadi."
Gue mengangguk. "Aku juga minta maaf kalau kelewatan."
"Aku izin pas istirahat kedua begitu tahu kamu nggak masuk karena ada izin sakit. Aku cuma khawatir, takut semisal gara-gara aku kamu sampai nggak sehat."
"Nggak, aku memang lagi ringkih akhir-akhir ini."
"Oke."
"Aku udahan sama Rea."
Mata Pian melebar begitu gue mengatakan itu, "Maksudnya?"
"Rea punya keputusan yang sepihak saja."
"Aku nggak ngerti, maksudnya kalian udahan itu ... putus?"
Dengan ragu gue mengangguk.
"Asli??"
"Kamu bisa tanya aja ke dia. Coba tanya kenapa dia nggak begitu masuk akal."
"Ng, Fis, t-tapi bagaimana awalnya?"
"Nggak tahu, aku sempat mengira itu gara-gara aku seperti marah ke dia. Tapi ternyata dia punya alasan lain."
"Apa alasannya?"
"Ya dia semacam cemburu gitu, mungkin."
"Cemburu?"
"Ke banyak orang."
Pian belum menjawab.
"Aku cuma lagi bingung sama jalan pikir orang-orang akhir ini. Nggak Rea, nggak kalian, aneh. Aku kecewa sih, Yan, ke kalian. Coba aja aku dikasih tahu dari awal, atau kalian nggak main rahasia-rahasiaan ke aku, pasti bakal ada obrolan yang enak antara gue sama Rea."
"Maaf."
"Maaf dari kalian udah nggak penting buatku. Maksudnya, tolong lain kali lebih koopereatif satu sama lain."
"Aku cuma waktu itu marah."
"Marah dengan alasan yang nggak masuk akal itu bakal jadi kayak gini ujungnya. Ada yang dilukai. Sekarang kamu bayangin aja deh. Rea lagi sakit, aku sama dia kacau gara-gara ada komunikasi yang nggak lancar, lalu dengan alasan yang menurut gue masih sangat tabu dia mutusin gue. Katanya biar dia fokus sama pengobatannyaa. Terus kalau dia sehat dia toh tetap akan di Liverpool buat melanjutkan semuanya. Apa itu nggak aneh?"
"Aku sih jujur nggak tahu banyak soal keluarga Rea. Tapi setahuku memang Rea pun ingin ke sana sebelum daftar ke sekolah kita. Itu dulu, sebelum akhirnya aku tahu kamu jadi alasan kenapa Rea betah di sini."
"Menurutmu aku harus gimana?" gue bertanya setelah lengang.
"Ada informasi lain yang bisa jadi petunjuk buat aku ngasih saran?"
"Rea bakal pulang bulan depan. Dan itu pun cuma sebentar karena mau ngurusin pindahan."
"Aku malah nggak tahu. Tapi kalau itu benar, aku pikir itu bisa jadi satu kesempatan untuk memperbaiki keadaan."
Gue mendesah.
"Itu tergantung kamu, Fis. Apakah mau balikan lagi sama Rea atau nggak."
"Ya maulah."
"Dan Rea sendiri menurutmu gimana?"
"Aku lumayan mengerti tentang Rea, Yan. Aku cuma perlu waktu bicara lebih lama dan ngeyakinin dia aja."
"Kalau itu yang kamu bicarakan ya aku cuma bisa mendukung saja."
"Dengan cara apa?"
"Membuat rencana."
"Ini kamu sedang dalam mode bisa dipercaya nggak?"
"Sangat, bro. Nggak adil aja kalau aku diam saja sementara kamu punya jasa besar untuk hubungan aku sama Hanum."
Gue tersenyum dengan sebelah bibir.
"Yan."
"Apa?"
"Menurutmu kisah cinta yang diukir sejak remaja bisa bertahan sampai selamanya tidak?"
Pian berdiri sebelum berjalan ke meja gue yang ada deretan action figure KungFu Panda. Dia mengambil karakter Po dan berbalik ke gue dengan menyandarkan belakang tubuhnya ke meja. "It's a possibility. Because being forever is not that simple."
"Harus melewati banyak aral."
Pian mengedikkan bahu.
"Kamu sendiri apa harapannya sama Hanum?"
Dia meringis, "aku nggak yakin kalau cerita soal aku sama Hanum itu tepat untuk diobrolin di depan orang yang lagi patah hati."
Gue berdecap, "tinggal bilang aja kali."
"Nggak tahu sih ini bener atau nggak, tapi aku harapannya mau pacaran sampai usia dua lima saja."
"Kok gitu?"
"Setelah itu kita menikah, hehe."
Entah kenapa seketika gue ketawa. "Nikah? Masih remaja gini udah mikirin nikah? Yang bener aja lu."
"Iya. Kenapa kamu ketawa? Itu rencana jangka panjang."
"Serius kalian berencana mau sampai nikah?"
"Kenapa tidak? Karena kita ingin sampai selamanya. Memangnya kamu nggak pernah kepikiran untuk sampai selamanya sama Rea?"
Itu membuat gue terdiam. Iya, ya. Kenapa gue atau Rea nggak pernah membicarakan ini ketika bersama? Apa ada yang salah dari cara kami melakukannya? Apa ini letak kesalahannya?
Setiap lagi bareng, kita cuma belajar, paling makan di luar, dan yang dibicarakan adalah masa depan kita untuk karir; kuliah di mana dan mau jadi apa. Apa itu bukan yang seharusnya dilakukan saat punya 'pacar'? Kita seperti ... atau, gue yang memang nggak pernah berusaha mengarahkan pembicaraan ke topik tentang hubungan kita. Apa cara gue yang garing ini ternyata melukai Rea tanpa gue tahu? Apa ini tidak malah membuat gue sama Rea hanya seperti 'sahabat dekat' alih-alih 'pacar'?
"Apa sepenting itu kita mengandaikan 'selamanya'?"
"Penting, itu kalau kamu ingin bersama seseorang selamanya."
"Bisa kamu jelasin?"
Pian menelengkan kepalanya, "serius?"
Gue mengangkat bahu, "yeah."
"Komitmen itu apa yang disepakati dan diusahakan untuk diwujudkan. Komitmen akan jadi pengingat ketika ego sedang tidak bercuaca baik."
"Seperti cita-cita?"
"Semacam itu, kayaknya."
"Kamu udah ngomongin yang kayak gituan sama Hanum?"
"Mm, belum. Tapi sudah ada di kepalaku."
Ada satu hal yang gue kalah dari Pian. Dia bisa mengerti ceweknya dengan sangat baik, dia bisa menjalani apa itu sebuah hubungan dengan perasaan.
Saat ini gue selalu memenangkan apa yang disebut logika. Seolah sedikit sekali gue melibatkan perasaan ke Rea. Ini jelas salah gue. Gue jarang mengatakan kata-kata yang manis, dan begitu pun Rea tidak melakukannya mungkin karena dia nungguin gue mengatakannya lebih dulu. Mungkin dari sinilah Rea berpikir gue nggak sayang sama dia bahkan sampai ada sebuah curiga bahwa dia bukanlah satu-satunya.
Kok gue bisa sebodoh ini ya dalam mencintai? Gue terlalu banyak mengerem dan menahan diri. Terlalu pakem. Sementara yang dipikirkan atau yang diharapkan Rea mungkin adalah sebuah kisah yang manis. Bukan yang tragis seperti ini. Yang ujung-ujungnya gue malah kebawa emosi karena gue nggak tahu apa-apa.
Malam itu, Rea beberapa kali berkata 'Nggak tahu!'. Itu barangkali adalah sebuah protes dari hati seorang cewek supaya cowok mengerti. Sekarang gue tahu kenapa cewek banyak menyalahkan logika laki-laki yang terlalu dominan dan mengkerdilkan kepekaannya. Tapi gue rasa cewek juga harus mengerti, bahwa cowok berlogika terlalu sering karena kami ingin memastikan segalanya bisa berjalan sesuai seharusnya. Seperti gue sendiri, bahkan belum pernah memeluk Rea hanya karena gue takut. Sistem di kepala gue masih digerakkan oleh sebuah protokol bahwa moral harus jadi nomor satu. Tapi mungkin bagi Rea yang cewek, nggak ada pelukan sama dengan nggak ada romantis. Ini hanya analogi dari gue sendiri. Karena beberapa kali Rea sering melingkarkan lengannya di leher gue ketika gue duduk di lantai dan Rea di atas sofa.
Kesimpulannya hanya satu, gue GAGAL peka. Dan berhulu dari sini akhirnya gue sama rea berhilir di sebuah keputusan berakhir.
Sekarang gue bener-bener merasa kehilangan.
Gue memahami sesuatu lagi. Bahwa ada hal yang tidak akan manusia pahami betapa berharganya itu sampai dia benar-benar menghilangkannya sendiri; cinta yang tak teranggap, sayang yang terabaikan, dan keberadaan yang tak nampak. Dan ketiga hal ini termanifestasikan pada satu wujud kehadiran 'seorang manusia'.
Gue merasakan sakit yang tak terperi ketika menyadari bahwa gue telah ditinggalkan oleh Rea. Gue nggak akan menyalahkan dia lagi. Jika ada seseorang yang sampai memutuskan untuk meninggalkan gue, padahal ada cara lain yang bisa dibicarakan, itu berarti di dalam benak keputusannya ada celah yang menjadi kemungkinan bahwa gue adalah orang yang memang layak untuk ditinggalkan. Dan gagasan itu membuat gue sedih. Gue layak untuk ditinggalkan?
"Kamu nangis, Fis?" kata Pian yang sedari tadi sedang memperhatikan gue merenung.
Gue menggeleng, "Kelilipan."
"Oh."
Gue mendongakkan kepala padanya, "Yan, bantu aku supaya bisa balikan sama Rea. Kamu cuma perlu membuat rencana supaya aku bisa ketemu sama Rea. Ada kesempatan ketika Rea pulang nanti. Mungkin kalau aku yang ngajak ketemu langsung, dia nggak bakal mau. Aku nggak akan memaafkan diri sendiri selama belum bisa mengembalikan semuanya menjadi baik-baik saja dan sebelum dia melihat aku berusaha memperbaikinya."
Pian yang sedang berdiri tak jauh dari gue tertegun. Lalu pelan sekali kepalanya mengangguk.
---o0o---
Sampai jumpa di chapter 28 kalau chapter ini sudah mencapai 210 votes. So, let's vote. Cepet vote, cepet tamat, cepet ganti cerita.
Jangan sungkan untuk berkomentar.
☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top