Chapter - 26: The Fundamental Of Loving
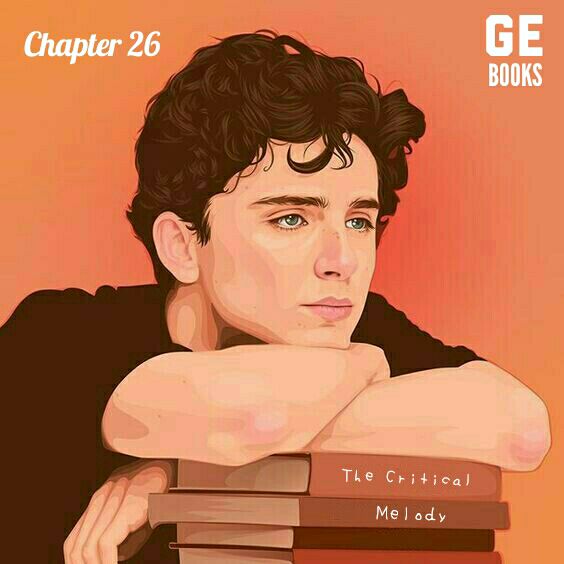
*Kalian curang sih, vote nya cepet banget sampe 150 saya jadi buru-buru ngeditnya. 😬 Yaudah, chapter 27 akan saya unggah kalau udah sampai 200 votes. Tapi kayaknya kalian bakal lebih ngegas setelah baca chapter ini. Dimohon untuk mempersiapkan apa saja yang bisa digunakan untuk mengelap pipi.
***
💡Rea💡
***
Note #447
Mood: Ew!
Aku tidak percaya, hari ini untuk pertama kalinya aku pergi ke salon. Ew! Kau tak perlu mencibirku, Lucas! Karena kau tak pernah membantu sama sekali. Kau hanya pendengar berbentuk lembaran kertas yang cukup berbaik hati mau menerima goresan pulpenku. But I’m grateful for belonging you as my 20th diary. Thanks, Lucas.
Aku tidak pernah berpikir bahwa SMA baik untukku. Aku bisa berangkat ke Liverpool hari ini juga kalau Mami tidak mendaftarkanku di SMA itu. Lucas, kau tahu, kan. Aku sudah menceritakannya padamu berlembar-lembar. Aku membayangkan hari-hariku di Liverpool; aku akan menemui sepupuku Josephine dan Liam, memakan es krim vanila sambil begadang semalaman dengan Netflix, sepertinya ide yang bagus kalau aku membawakan mereka satu ember es krim durian. Kau tahu di sana tak ada durian. And maybe I’ll find new romance there. Imagine! A calm boy who has a cute lip, a talented person, smart. I wish someone with lionheart in his teddy face will come close to me. LOL. Juga, Papi sudah merestuiku untuk memperjuangkan Julliard. Hmm, okay okay, I know, Lucas. Aku baru beberapa bulan ini bergabung dengan sanggar. Dan aku tahu itu hanya terapi. Tapi aku seolah tersadarkan. I found my trully days at least.
Seseorang di Quora mengatakan agar aku merubah gaya rambut, body lenguage, kontrol bicara, dan ... hmm. Lucas, apa kau pikir aku terlalu menyedihkan sampai harus melakukan itu? Tapi aku sudah terlanjur mengikuti tes masuknya. Aku ingin melupakan semua yang terjadi di SMP.
#Note450
Mood: Grateful
Coba tebak, aku mendapat peringkat pertama di sekolah itu. Nilaiku yang terbaik, seperti kata Mami, doanya selalu seperti itu.
Lucas, sekolah itu sangat keren. Mereka punya fasilitas yang lengkap. Sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sistemnya kurasa sangat menakjubkan.
Ada satu yang perlu kau tahu, Lucas. Aku satu kelas dengan Louisa. Seseorang yang tak bisa kuhindari. Salah satu yang ingin kudekati, tapi rasanya akan semakin keliru kalau aku mendekatinya. Aku tak bisa, tapi aku ingin.
Satu lagi, aku duduk sebangku dengan seorang cowok, dan hanya kami yang duduk berpasangan beda gender. Tapi aku tidak khawatir padanya, sebab kupikir seseorang yang bernama Nafis itu sangat kompeten. Dia punya attitude yang baik. Dari sepuluh besar peraih nilai terbaik, dia satu-satunya laki-laki di deretan nama-nama itu. Mungkin, bisa dikatakan laki-laki terbaik dari angkatan kami secara akadaemik, kurasa.
Aku harap kami bisa berteman.
Pian juga satu kelas dengan aku, Lucas. Aku tahu dia sedang berpura-pura sepertiku.
#Note455
Mood: Impressed
Aku tidak bermaksud membicarakan tentang seorang cowok padamu, tapi, kau perlu tahu tentang Nafis, Lucas. Iya, teman sebangku yang pernah kuceritakan padamu tempo hari.
Dia ... menarik. Aku belum pernah menemukan seseorang yang berkarakter seperti dia. Terlepas dari akademiknya yang mengagumkan, sebenarnya, dia biasa-biasa. Tidak berlebihan dan bisa menempatkan diri dengan pas. Impianku pada sosok populer seperti Bjork sudah tidak akan terjadi lagi. Biarlah masa SMP menjadi kesalahan yang tak boleh terulang.
Nafis kalau ke sekolah bawa gitar akustik. Gitar itu kadang seperti terlalu besar untuk tubuhnya, tapi aku belum tahu bagaimana permainannya.
Aku benar-benar bisa berubah, Lucas. Aku terbiasa dengan semua orang. Meski tetap saja aku hanya terbuka padamu. Apa yang salah ketika kita berbaur dengan banyak orang tapi kita mengatakan isi kepala dan hati kita hanya pada satu tempat saja? Makanya aku tidak akan lelah berterimakasih karena kau, Lucas, sudah menjadi diary-ku yang setia, tak kalah setia dengan sembilan belas lainnnya. Tapi kau tinggal beberapa lembar lagi, aku akan mencari yang baru dan membiarkanmu beristirahat dengan teman-teman lainya.
#Note460
Mood: Amazed
Hei, Luc. Um, coba tebak?
Aku rasa Nafis adalah sosok yang kukira hanya ada dalam imajinasiku saja. Aku selalu mengandaikan sosok yang menyukai lagu-lagunya Ryan O’Neal.
Tadi aku tidak sengaja melihat Nafis memainkan ‘Two’. Bahkan aku melihatnya dari petikan pertama. Kau ingat lagu itu? Yang kubilang jadi salah satu favoritku?
Oke, dia benar-benar seolah mengatakan lirik lagunya padaku.
‘Sweet heart, you look a little tired. When did you last eat?’
Aku kesal! Karena dari semua orang yang sedang memperhatikannya berlatih di auditorium, mereka seperti tidak ada yang tahu lagu itu! Tak ada yang tersenyum atau tersipu sepertiku saat lirik sederhana dan manis itu dinyanyikan. Oh, aku tidak yakin mereka musisi sejati. Tapi setidaknya aku tahu Nafis mengenal lagu itu. Hm, ya, seperti yang pernah kubilang. Aku dan Nafis belum cukup mengenal satu sama lain meski kami satu bangku. Mungkin karena dia malu, dan aku juga lebih memilih untuk memanipulasi ekspresi dengan lebih dekat pada orang lain.
‘Come in and make yourself right at home. Stay as long as you need.’
Dan masih tak ada yang tersipu. Mungkin hanya aku sosok di dekat pintu yang melihatnya dari jauh.
Oke, aku akan menulis liriknya lagi agar kau ingat atau setidaknya aku bisa membayangkan lagu itu dinyanyikan olehnya. Kita akan membayangkannya bersama-sama.
‘Tell me, is something wrong? If something wrong you can count on me.
You know I’ll take my heart clean apart, if it helps yours beat.
It’s okay if you can’t find the words, let me take your coat and this weight off of your shoulders.’
Aku benar-benar masih seperti mimpi ada orang yang menyanyikan lagu itu di depan mataku meski dia tidak memaksudkannya untukku. Dia sedang berlatih, kudengar ada ajang khusus di klub ini.
‘Like a force to be reckoned with, a mighty ocean or a gentle kiss. I will love you with every single thing I have.
Like a tidall wave, I’ll make a mess or calm waters if that serves you best. I will love you without any strings attached,’
Kau tahu, Ryan tak seperti musisi folk lainnya. Dia tidak menyanyikan lirik, tapi dia menyanyikan sebuah puisi. Dan itu yang tadi Nafis lakukan.
‘It’s okay if you can’t catch your breath, you can take the oxygen straight out of my own chest,'
Cukup, tanganku mulai gemetar dan kecepatan menulisku semakin melambat. Parkinson mulai menggangguku lagi, Lucas. Aku benci ini.
Nafis has an angelic voice, I own it, only by once heard.
***
Setitik air mata jatuh membasahi sampul Lucas saat aku menutupnya. Aku membawa Lucas, Ken, Holmes, dan Yashmina ke Liverpool. Hanya ingin membacanya dan mengenang beberapa hal yang pernah aku alami dengan Nafis.
Dia adalah lembaran baru dari semua kisah-kisah yang telah lalu. Dia memberi warna pada hidupku yang monokromatik pada kenyataannya. Dia yang mengurungkanku untuk jadi aku yang baru. Alih-alih dia mempertahankanku pada sosok diriku yang apa adanya, tepatnya sebelum aku datang ke salon saat dulu.
Aku menyukai setiap orang, tapi yang kusimpan dalam hati hanya satu. Dia senang padaku, dan aku senang padanya. Dia pintar, manis, dan tipeku sepenuhnya. Kau pernah melihat cowok yang berwajah daun muda, segar, tapi kadang bertingkah ‘seolah’ dewasa? Kalau begitu, mungkin dia seperti Nafis.
Aku suka wajahnya yang menyenangkan. Aku suka dia yang kadang pura-pura sebal. Aku suka cara dia mengatakan hal-hal yang jernih. Dia bukan sosok yang berpemikiran dewasa sebenarnya, itu kenapa aku suka saat dia berusaha mendewasakan cara bicaranya. Itu pendapatku.
Galileo Galilei pernah berkata, “we cannot teach people anything, we can only help them discover it within themselves.” Barangkali itu yang aku lakukan sekarang pada Nafis. Aku tidak tahu, tapi aku lebih senang mengarahkan seseorang untuk memahami sebuah hakikat alih-alih mengatakannya secara langsung untuk pembenaran. Setiap orang punya ruang luas sendiri di dalam kepala dan dadanya. Dan aku tahu Nafis punya kapasitas yang memadai untuk memahami hidupnya sendiri.
Pernah tidak, ketika kau menjalin hubungan selama lebih dari dua belas bulan, tapi malah kehampaan yang ada. Sesuatu seperti segalanya tidak benar-benar baik-baik saja.
Kami memulainya dengan sangat sederhana. Tapi bagiku itu begitu istimewa. Hari-hari yang terlewati begitu manis, sehat, aman, dan kooperatif. Maaf kalau aku tidak bisa mendeskripsikan bagaimana hubungan kami persisnya.
Tapi tetap saja ... maksudku.
Maaf aku harus mengelap air di pipiku berkali-kali ketika menyampaikan ini pada siapapun kamu.
Tempat mana pun tak akan jadi lebih baik selama di sana tidak ada kamunya, Fis. Keputusanku berangkat dan merahasiakannya sama sekali tak menimbang dari seberapa mungkin kamu akan mencari. Satu tahun, Fis, bahkan melewati itu aku nyaris nggak bisa lagi main rahasia soal keraguanku. Nyaman di awal, tapi hambar perlahan.
Kita sering bareng, tapi pikiranmu seolah tidak benar-benar ada di sana, melainkan di tempat lain, atau orang lain. Diam-diam aku menyimpannya sendiri. Iya, ini soal alasanku menjaga jarak perlahan. Sebab bagaimana aku akan jujur tentang sakitku, jika bahagiaku saja kamu sama sekali nggak bisa merasakan. Aku tahu kamu kerap mengatakan tentang ‘kita’, tapi aku ragu itu hanya lanturanmu saja, atau upaya tak jujur agar aku senang. Jika tak ingin mencari, aku sangat bisa menerima kalau kamu ingin tetap di sana. Toh seberapa sering, sih, kamu menyengajakan uluran tangan supaya aku meraih?
Tapi kalau kamu ingin mencari dan berusaha mengembalikan semuanya agar seindah seharusnya. Aku akan pastikan kamulah satu-satunya orang yang memiliki setiap detik sisa hidupku. Kamu selalu punya semua kesempatan yang kamu perlukan. Karena seberapa sengit aku kadang membenci ini, aku tetap tidak ingin kehilanganmu atau harus menggantikannya dengan orang lain. Aku tidak ingin mengganti apalagi tergantikan.
*sebuah catatanku di dalam Yashmina.
***
Belasan panggilan tak terjawab menumpuk di notifikasi. Semuanya dari Nafis. Aku menutup Lucas dan menahan diri untuk tidak membaca catatan tentang malam di mana aku jadian dengan Nafis.
Tanganku gemetar saat membawa buku harian itu ke sebuah meja. Ini bukan karena aku kelelahan atau apa, tapi karena parkinson dalam kepalaku sudah mulai membuat kendali saraf gerakku semakin melemah. Di Liverpool sedang memasuki pukul sembilan malam. Itu artinya di Jakarta sedang pukul tiga pagi. Aku mencoba menelepon Nafis meski tidak mengharapkan dia akan mengangkatnya sebab kurasa dia sedang tidur. Tapi dugaanku salah. Aku mulai berdebar dan mempersiapkan diri untuk semuanya.
“Hei,” kataku saat dia menjawab panggilanku, “kenapa diangkat?”
“Aku nggak bisa tidur. Dan kebetulan kamu menelepon. Barangkali salah satu alasan kenapa aku masih terjaga adalah ini,” suaranya serak. Aku tahu sebenarnya dia mengantuk.
“Mm.”
“Sudah minum obat?”
“Mau menunggu beberapa menit?”
“Kenapa?”
“Aku mau minum obat.”
Dia tidak menjawab seketika, “bagaimana kalau panggilan video? Aku kangen wajah kamu, ngomong-ngomong.”
“Kamu nggak terganggu?”
“Sama sekali nggak. Kayaknya agak demam lagi.”
Aku memikirkan tawarannya sebentar.
“Aku tutup teleponnya dulu. Nanti aku siapkan skype.”
“Oke, skype ide bagus.”
Setelah panggilan terputus aku lalu menyiapkan laptop di meja dan mengaktifkan skype. Beberapa saat menunggu akhirnya akun Nafis sedang daring.
Tak lama kemudian kami sudah berhadapan dengan wajah masing-masing. Aku duduk di kursi, sedangkan dia seperti masih di atas tempat tidur dan bersandar pada bantal.
“Udah diminum obatnya?” katanya.
Aku menggeleng, rasanya ingin menjadi cengeng saat melihat wajahnya dan suaranya yang perhatian itu. Sering kali aku berusaha meyakinkan bahwa apa yang kuduga itu salah, barangkali hanya prasangkaku saja, Nafis tidak mungkin menggantikanku dengan siapapun. Aku takut hanya karena parkinson lantas gejala keresahan ikut merenggut antara aku dan dia.
“Diminum sekarang, aku tungguin.”
Dia benar-benar menunggu di depan monitor. Dan aku pun meminum semua pil-pil itu sesuai dosis dalam pengawasannya.
“Aku perlu melakukan ini setiap kamu mau minum obat, nggak?”
“Pengin, sih.”
“Oke, aku akan mengatur pengingat biar bisa. Aku nggak bisa janji akan tepat waktu, tapi aku bakal sangat berusaha.”
Aku mengangguk, “kamu demam lagi?”
“Tadi kehujanan.”
“Salah kamu, kan?”
“Iya.”
“Kabar Pian sama Louisa gimana?”
Dia memandang lensa lekat-lekat yang membuatnya seolah sedang menyelami mataku. “Mereka bikin jengkel. Louisa marah-marah karena aku nggak bisa mengenalimu lebih baik. Tadi malam aku ketemu Pian, kita bertengkar, aku ditonjok.”
“Apa?” aku mencondongkan diri ke monitor.
“Iya.”
“Pian nonjok kamu?”
“Kenapa? Itu salahku.”
Aku terkejut mendengar aduannya. Apa yang terjadi? “Kenapa kamu salah?”
“Aku mendorongnya lebih dulu. Karena aku marah dia menyembunyikan informasi sebanyak itu tentang kamu. Kita bertengkar, aku tidak sabaran, dan dia melakukannya. Itu tidak sakit. Karena ada yang lebih sakit dari itu sekarang.”
“Kamu nggak boleh kayak gitu, Fis.”
“Aku nggak tahu harus bagaimana. Akal dan hatiku kacau. Aku nggak bisa berpikir jernih, kamu tahu? Oh, mungkin tidak.”
Perasaanku tak tega melihat wajahnya yang memang benar-benar terlihat kacau itu. Sedikit marah.
“Aku boleh nanya nggak, Re?”
“Hm? Ya.”
“Apa alasan kamu melakukan hal yang sangat tega seperti ini ke aku?” suaranya seperti dia sedang menahan sesuatu yang menyakitkan. Aku tidak tahu kenapa pertanyaan itu seolah sangat menyulitkanku. “apa aku punya salah yang nggak aku ketahui? ... apa aku melukaimu tanpa aku tahu? ... apa aku punya kekurangan yang tidak bisa kamu terima? ... apa mungkin karena aku tidak terlalu sering mengaku kalau aku sayang banget sama kamu. Cinta sama kamu. Dan nggak ingin kehilangan kamu?”
Aku menahan sesuatu yang begitu pilu. Bibirku mulai berkedut ingin menangis.
“Aku benar-benar nggak tahu apa salahku sampai seolah-olah aku begitu pantas diposisikan di jurang seperti ini oleh kamu,” katanya lagi.
Aku menggeleng, “nggak,” lalu nangis.
“Jangan bohong. Coba eja satu-satu, apa kesalahanku? Meskipun aku pacar kamu, tapi bukan berarti aku ini malaikat yang harus bisa baca semua unek-unek di hati kamu, Rea.”
“Fis,” aku menggeleng menutupi wajah.
“Hubungan kita nggak akan jadi lebih baik sampai kamu mengatakan apa yang harus aku perbaiki. Kita udah sebulan lebih nggak punya komunikasi yang sehat.”
“Aku nggak tahu.”
“Tapi kenapa Louisa sama Pian seolah marah karena mereka tahu apa yang seharusnya aku tahu dari kamu?” dia seperti menahan amarah. “Itu yang bikin aku stres sampai mau gilak sepertinya.”
“Nafis, aku pergi ke sini murni karena aku sakit!” aku benar-benar tidak punya ide untuk menjelaskannya. Pernyataan Nafis yang tadi membuatku merasa sangat bersalah. Dan tidak perlu dia menjelaskannya lagi dengan panjang lebar pun aku seolah tahu bahwa, ya, aku salah, mungkin ini hanya efek parkinson yang membuatku resah.
“Sampai harus membohongi semua orang, Re? Pertukaran pelajar? Kamu bohong soal SALJU di Sapporo,” gaya bicaranya!
“Aku cuma ngerasa kadang seolah aku bukan satu-satunya!” aku tidak menyangka itu keluar dari mulutku.
“Haah?” lalu dia mengusap kepalanya sendiri sampai wajahnya.
“Apa aku lagi dituduh punya orang lain?”
Aku menangis.
“Coba kamu tanya sama Pian SEPUPU kamu yang jadi mata-mata itu, atau tanya Louisa yang TEMAN DEKAT kamu. Tanya apa aku kelihatan pacaran sama orang lain?” aku bisa melihat wajahnya yang paling kacau, dan itu baru pertama kali aku melihatnya. Dia masih berusaha untuk tidak marah meski kemarahannya sangat mudah aku baca. “Demi Tuhan aku nggak punya siapa-siapa di belakang kita. Aku menikmati setiap detik sama kamu. Aku nggak pernah jadi orang lain saat sama kamu.”
“Tapi kamu bersikap baik sama Louisa!”
Kali ini alisnya menyudut, monitor di pangkuannya sedikit bergoyang. “Kamu cemburu sama Louisa?”
“Kamu juga begitu sama Hanum! Sama Risa anak akustik juga. Lalu anak olimpiade sains yang nggak aku tahu namanya,” aku benar-benar merasa bodoh dan nggak tahu kenapa semakin aku mengatakannya, semakin tidak masuk akal juga alasan yang aku lontarkan. Aku mulai menyalahan parkinson jika memang semua kecemasan ini datangnya dari sana.
“Rea, aku selalu berusaha bersikap baik sama semua orang,” dia tetap mencoba sabar padaku.
“Tapi aku kadang merasa sudah kehilangan kamu.”
“Hilang seperti apa?”
“Aku nggak tahu!”
“Tuh kan,” dia seperti lelah, “kamu nggak masuk akal.”
Tak ada pertengkaran lagi untuk sesaat. Apa tadi kami baru saja bertengkar? Aku menangis sesenggukan di depan lensa laptop. Aku menutupi wajah. Aku ingin marah pada diri sendiri. Aku merasa bersalah karena sesuatu yang begitu bodoh.
“Maaf sudah bikin kamu nangis,” katanya kemudian. “aku cuma nggak tahu apa yang sedang kamu persoalkan. Intinya apapun praduga burukmu tentang aku, Re, aku bisa pastikan itu nggak benar.”
Aku sesenggukan. Entah kenapa rasanya aku malu jika tidak punya alasan yang tepat.
“Aku salah, Fis.”
“Bukan, mungkin memang aku yang salah. Sisi lainnya memang aku bahkan nggak bisa tahu kalau kamu lagi sakit.”
Aku menggeleng, “Itu karena aku nggak mau kamu tahu. Penyakitku kayak nenek-nenek, Fis.”
“Tapi selama ini kamu terlihat baik-baik saja! kenapa aku bisa nggak tahu?”
“Karena aku menyembunyikanya!”
“Dari aku pacar kamu sendiri, ha? Tolonglah. Bicarakan apa saja. Kamu bahkan sudah tahu semua tentangku. Tapi aku malah seperti nggak benar-benar dibiarkan masuk ke kehidupan kamu, tahu nggak. Bersikap terbuka adalah hal yang paling mendasar dari mencintai satu sama lain. Itu sebuah fundamental. Aku yakin nggak akan kejadian seperti ini, kita bertengkar di waktu yang nggak tepat sama sekali, kalau kamu bisa lebih terbuka sama aku.”
Aku pun mulai merasa kacau. Tanganku gemetar lagi. Kendali gerakku sedikit terdistrak. Tapi berusaha aku sembunyikan.
Lihat? Aku bahkan masih tidak berani bersikap terbuka ketika Nafis baru saja mengatakan itu. Aku pasti akan banyak merepotkan Nafis jika hubungan ini berlanjut. Aku sayang dia, tapi pesakitan sepertiku hanya akan membuatnya malu.
“Coba terbuka sama aku, Rea,” katanya lagi.
“Aku akan pulang bulan depan. Tapi hanya untuk mengurus surat pindahanku dan lain-lain. Setelah itu aku akan ke sini lagi dan mungkin nggak akan balik ke Indonesia,” kataku menangis.
Dia tertegun.
“Pengobatanku perlu berbulan-bulan, Fis. Ada serangkaian terapi yang sudah terjadwal. Aku tidak bisa kembali untuk jangka waktu yang nggak bisa ditentukan. Papi juga sudah merencanakan agar aku melanjutkan sekolah di sini.”
Kulihat cairan bening merembas di pipinya. Tapi dia masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun.
“Aku tahu ini salah dan sangat jahat, Fis, tapi aku nggak bisa berbuat banyak. Aku juga malu dengan sakitku ini. Aku akan banyak merepotkan kamu.” Aku berusaha membuat senyum di sela-sela tangis meski pasti terlihat jelek. “Semuanya sangat mendadak. Tapi ini memang sudah direncanakan oleh kedua orang tuaku.”
“Bukan ini yang ingin aku dengar, Rea.” Sekarang dia benar-benar menangis, tapi sangat terkendali.
“Tapi ini memang kenyataan yang aku sendiri terima.”
“Ini nggak masuk akal. Dan sampai kapan kamu akan terus nggak masuk akal seperti ini, sih?”
“Aku tahu.”
Aku mengumpulkan tenaga dan nyaliku di dada. Aku sangat yakin ini bukanlah hal yang aku dan Nafis inginkan. Tapi jika aku dan Nafis berlanjut, maka konsentrasiku pada pengobatan akan terpecah. Jarak jauh ini nggak akan pernah berhasil.
“Aku berpikir kalau kita selesai sampai di sini saja,” kataku pura-pura tegar. “aku nggak yakin semuanya akan berjalan lebih baik. Ini bukan karena prasangka burukku yang tadi atau apa. Tapi karena sekarang keadaannya sudah berubah. Aku terlalu banyak nggak adil sama kamu-.”
“Bisa nggak jangan mikirin itu? Demi Tuhan aku bisa nerima semuanya tentang kamu. Putus bukan jalan keluar yang baik kecuali kalau kamu memang nggak pernah sayang sama aku. Kita bisa melewati ini, Re.”
“Bukan kita, Fis. Mungkin kamu bisa, tapi aku nggak bisa. Ini terlalu berat buatku ada di sini.”
“Kamu nggak masuk akal sih.”
“Coba jangan pakai akal, Fis. Ini tentang perasaan.”
Aku melihat Nafis sudah enggan menatap ke lensa. Dia sudah nggak bisa fokus. Dia seperti marah dan aku yakin dia juga sangat kecewa. Aku tahu ini benar-benar jahat, tapi aku sudah tidak bisa kuat dengan posisi ini.
“Maaf,” kataku, “maaf sudah ngecewain. Maaf jika aku terlalu jahat. Tapi aku harap kamu bisa mengerti. Rea sayang Nafis, tapi belum nemu alasan apakah ini akan lebih baik kalau diteruskan. Aku sudah memikirkan ini belakangan. Mungkin dengan putus, aku bisa lebih fokus ke diri sendiri tanpa perlu khawatir berlebihan ke kamu.”
Lalu kulihat Nafis mendongakkan kepala, tidak menatap lensa lagi, tapi pipinya basah. Dia menggigit bibir bawahnya. Tangannya seperti melakukan sesuatu pada keyboard, lalu koneksi kami benar-benar terputus.
Saat itulah aku menutup laptop keras-keras. Dan menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Kau ingin tahu apa yang kulakukan selanjutnya? Kalau kau adalah seseorang yang pernah mengalami unconditionally break, harusnya kamu tahu bagaimana keras sakitnya, seberapa banyak dan lama tangisannya.
***
Oke, silakan berkomentar sebebas emosi kalian.
Semoga kalian siap untuk kelanjutannya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Chapter 27 akan saya unggah kalau chapter ini sudah sampai 200 votes.
So, silakan patungan votes biar cepet tamat.
Karena cerita ini sudah saya ketik sampai tamat dan tinggal editing saja.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top