Chapter - 24: Rindu Yang Salah
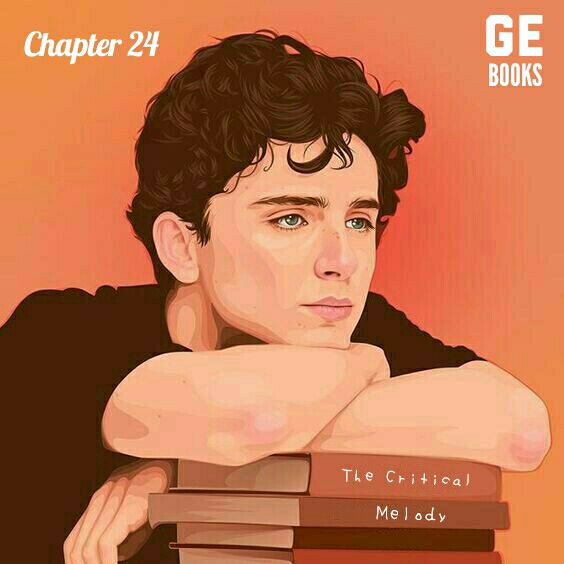
***
🎸Nafis🎸
***
Di dalam rumah itu seperti ada perbincangan yang kurang mengenakkan antara Louisa dan Papanya. Gue berteduh di bawah atap warung makan. Dan sama sekali nggak mendengar dengan jelas perbincangan apapun di dalam sana kecuali seperti suara tangisannya Louie, atau kalimat samar Papanya yang seperti sedang menjelaskan sesuatu.
Gue menelepon Alex kemudian, “Alex?”
“Fis? Tumben. Ada apa?”
“Aku ganggu, nggak? Ada hal penting yang mau aku kasih tahu, jadi kalau lagi sibuk tolong sempetin bentar.”
“No, nggak apa-apa, aku sekarang di tempat gym. Baru beres pelatihan buat kaki.”
“Oh, bagus.”
“Kamu mau ngomongin apa?” dia bertanya.
“Umm, ini aku lagi berteduh di warung makannya Louisa.”
“Iya, terus?”
“Karena hujan dan Louisa tadi minta tolong untuk diantar.”
“Oh, makasih udah mau nganter.”
“Ya, itu cuma hal kecil, santai saja. Alasan kenapa Louisa minta diantar karena Papanya pulang.”
Terdengar suara gemeresak dari ponsel, “Serius?” dia mendadak antusias sekali.
“Ya, beliau pulang.”
“Oke, makasih udah ngasih tahu.”
“Tapi ada satu hal lagi.”
“Apa?”
“Aku nggak yakin dengan ini, tapi sepertinya ada yang nggak beres sama mereka.”
“Maksudmu?”
“Y-ya. Um,” gue menghela napas, “tadi pas baru nyampe, kami langsung disambut dengan adegan yang kurang menyenangkan. Mamanya Louisa keluar rumah sambil bawa ransel, dan ... beliau menangis.”
“Nangis?”
“Y-ya,” gue sediki gagap karena nggak yakin.
“Lalu?”
“Aku nggak terlalu yakin, tapi sepertinya alasan kenapa di sana terlihat kacau karena ada anak kecil yang dibawa sama Papanya Louisa.”
“Anak kecil?”
“Ya, anak kecil. Sebenernya di dalam seperti ada perdebatan antara Louisa dan Papanya. A-aku nggak nguping, cuman samar-samar terdengar.”
Alex terdiam di sana.
“Lex, kamu memikirkan apa yang aku pikirkan?”
“Tentang?”
“Ya ini. Aku nggak bermaksud ikut campur, tapi sepertinya setelah ini Louisa sangat butuh keberadaan kamu.”
“Aku tidak memungkinkan.”
“Bentar, bentar.”
Gue memutuskan panggilan saat melihat Lou keluar rumahnya. Masih pakai seragam dan wajahnya kacau sekali. Dia lari menerobos hujan. Papanya hendak mengejar tapi tertahan di bibir teras karena ada suara anak kecil yang menangis di dalam.
“Louisa! Dengarkan Papa!”
Tapi Lou tak menggubris sama sekali. Langkahnya cepat menuju jalan raya. Dia menoleh kanan-kiri mencari arah yang akan dia tuju selanjutnya. Entah apa pertimbangannya, tapi dia memilih berbelok ke kanan.
Gue bingung. Ingin mengejar tapi fisik gue lagi rentan banget sama hujan. Tapi karena gue khawatir dan tidak bisa mengharapkan kehadiran Alex, akhirnya gue mengejar. Sebelumnya, gue sempat bertatapan dengan Papanya Lou. Beliau kehilangan ekspresinya untuk menyapa atau sekadar memberi sedikit keramahan. Sekilas padahal gue bisa menilai beliau memiliki tampang wajah yang bersahabat. Namun untuk alasan keseluruhannya gue sulit memahami situasi ini.
Anehnya setetes hujan yang mengenai badan itu seperti punya setruman buat gue. Dinginnya terasa lain, bikin merinding keterlaluan.
“Lou!” seru gue ketika berhasil berjalan cepat di sebelahnya. “Kamu mau ke mana?”
Dia tidak menjawab melainkan nangis.
“Naik motor aja kalau mau ngejar Mama kamu,” gue berusaha memahami.
“Fis! Aku mau ngejar ke mana?! Arah Mama pergi pun aku nggak tahu!” dia marah-marah.
“Ya makanya kamu jangan panik begini!” entah kenapa gue juga membentak. “Tenangkan dulu lah! Lagian Mama kamu tadi udah bilang akan ngasih tahu kamu secepatnya. Dan ini baru beberapa menit.”
“Beberapa menit katamu? Fis! Beberapa menit di Jakarta kalau naik kendaraan itu udah lenyap, jauh!”
“Iya, makanya aku minta supaya kamu nggak usah maksain lepas kendali kayak gini! Ayo, aku mau nganter ke mana aja tempat yang kamu curigai ada Mama kamu. Dan kalau kamu tidak keberatan, coba jelaskan situasinya lagi seperti apa.”
“Kamu nggak usah ikut campur sama kehidupan keluarga aku, ya, Fis!”
“Aku nggak ikut campur! Sama sekali nggak ingin, Lou. Tapi sekarang lihat keadaan kamu kayak gimana! Oke, kalau kamu penginnya aku pergi, nggak masalah. Yang jelas tadi aku udah ngabarin Alex, dan dia lagi nggak memungkin ada di sini. Kamu mau minta bantu ke siapa? Coba singkirkan sejenak apapun pikiranmu tentang keberadaanku di sini. Ini nggak lebih dari teman yang membantu temannya. Atau bukan juga orang yang nggak ada kerjaan ikut campur urusan orang lain.”
Dia malah nambah nangis, lalu mengejutkannya dia memukul dada kanan gue. Di sini gue nggak menganggap pukulan itu sebagai pertanda kalau dia membenci gue, tapi lebih ke betapa dia sudah muak dengan problemanya. “Dengan kamu ngasih tahu ke Alex, itu ikut campur namanya!”
“Aku cuma ingin dia tahu situasinya, Lou! Karena aku curiga yang kayak gini bakal terjadi. Maksudku kamu yang lepas kendali begini.”
“Kamu itu nambahin beban pikiran Alex. Dia lagi pelatihan tadi bilang. Dengan kamu ngasih tahu soal ini, dia bakal khawatir banget, Fis!”
“Entah kenapa seolah alasan marahmu sekarang itu karena aku. Dan asal kamu tahu, itu udah jadi keharusan Alex untuk khawatir sama pacarnya. Dia laki-laki.”
Mulut Louisa menganga sebentar, “Nggak usah ngajarin apa itu khawatir ke Alex. Sementara kamu sendiri bahkan nggak pernah tahu kalau pacarmu lagi sekarat!”
Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba Louisa menyeret persoalan gue sama Rea.
“Loh, kenapa kamu seret-seret soal aku sama Rea? Ini jelas nggak ada hubungannya sama sekali.”
“Dan Alex juga nggak ada hubungannya dengan urusanku saat ini!”
“Alex jelas ada hubungannya! Dia pacarmu dan kamu butuh dia sekarang. Aku cuma ingin ngasih sedikit bantuan yang aku bisa. Kenapa kamu malah kesannya mempersulit niat baikku?”
“Aku nggak mempersulit!!” emosinya meledak bersama bentakannya. Apa yang dia katakan percuma, pasti berujung kacau sebab dia sudah dalam kendali amarah. Dan nggak heran kalau tiba-tiba dia menyeret topik yang nggak ada kaitannya sama sekali. Lalu dia duduk jongkok di aspal dan menutupi wajahnya, menangis.
Sekarang gue baiknya gimana? Ninggalin dia di sini jelas bukan ide yang baik. Dan tetap di sana dengan semua ledakan emosi Louisa pun pasti nggak akan membawa arah yang jelas. Tapi ada satu yang gue mengerti soal situasi seperti ini, Louisa perlu gue kasih penegasan.
Gue berlari cepat ke rumahnya untuk mengambil motor. Setelah itu gue menyodorkan helm ke Louisa, helm gue, karena gue nggak tahu dia naroh helmnya tadi di mana.
“Ayo kita cari Mama kamu sekarang,” kata gue. Dan beruntungnya Lou nggak mencoba mendebat tawaran gue ini. Bahkan dia seolah nggak nyadar kalau yang dia pakai itu helm gue, dan gue nggak pakai helm.
Gue tahu pencarian ini akan sulit. Jelas-jelas tadi gue lihat Mamanya naik taksi ke arah yang lain. Gue nggak tahu mau ke mana.
Yang menyedihkan dari pencarian ini, Louisa hanya punya satu referensi tempat yang dicurigai ada Mamanya. Dan itu bukan rumah atau alamat seseorang, melainkan stasiun kereta. Bisa ditebak hasilnya nggak ada. Louisa nggak punya referensi rumah saudara Mamanya di sini. Katanya nggak mungkin juga Mamanya pergi ke rumah Alex yang notabene bakal gampang didatangi Papanya sendiri.
Setelah kita muter-muter lebih lama lagi, akhirnya dia menyerah. Dia meminta gue untuk mengantarnya kembali ke rumah. Gue mengiyakan secepatnya karena badan gue mulai greges dan jujur nggak sanggup kalau dibawa hujan-hujanan lebih lama lagi.
Saat di belokan dekat rumahnya, tepat di halte sana dia meminta gue berhenti, berteduh.
Hari mulai sore. Angin dan suhu tak seramah sebelum-sebelumnya. Rasa panik dan kegelisahan Louisa dalam sekejap sudah menyalur ke gue. Ini bukan apa-apa, hanya saja gue bisa paham banget apa yang harus dia perangi di batinnya karena ini. Ya mungkin gue juga bakal panik kalau lihat orang tua gue sendiri berantem di rumah dan salah satunya kabur. Dan sekarang gue nggak tahu Louisa mau diem di halte yang sepi ini sampai kapan.
Di bagasi motor gue punya mantel yang belum dipakai. Sementara ada juga jaket yang tersimpan di tas, aman nggak kebasahan karena gue sempet pasang mantel parasut untuk tasnya. Gue nggak sempet mengenakan jaket atau pun mantel hujan buat gue, makanya tadi keliling pun cuma pakai seragam sekolah. Beruntung nggak ada hambatan dari polisi, dan jarak stasiun dari rumahnya Lou pun tidak terlalu jauh. Kami banyak melewati rute tikus.
Louisa duduk di sisi lain kursi halte, sementara gue nekat menyingkirkan rasa malu melepas baju gue dan segera menggantinya dengan jaket. Berusaha kuat nyembunyiin geligis dingin yang udah nyerang gue sedari tadi. Ya, itu jelas membuat Louisa memalingkan muka seketika.
Setelah itu gue duduk di sebelahnya, mungkin berjarak dua meter. Halte, hujan, angin, dingin, dan koneksi yang belum bisa dikatakan baik-baik saja antara gue dan Louisa.
Gue mengulurkan mantel ke Louisa, “Rangkap baju kamu pakai ini.”
Dia menoleh ragu, lalu menerimanya dan dengan segera memakai rangkap mantel itu.
Awkward, that’s a good word to describe this situation.
“Maaf,” ucapnya lirih.
Gue nggak lantas menjawabnya, karena memang sudah seharusnya dia minta maaf.
“Aku tadi lagi marah, Fis.”
“Iya, aku tahu. Lupain aja,” gue memasukkan tangan ke saku jaket.
Tak lama kemudian terdengar dia mulai nangis lagi. Dan gue cuma bisa menahan napas karena rasanya aneh berada di dekat seseorang yang sedang menangis sementara gue nggak bisa berbuat apa-apa semisal mengelap air matanya atau menepuk pundaknya atau memegangi tangannya, no, gue nggak bisa.
“Aku tidak yakin akan bilang mencintai seseorang sampai selamanya, sementara ada kesetiaan bodoh yang dipertontonkan Papaku sendiri.”
Gue takut berkomentar.
“Laki-laki itu menjijikan. Mereka hanya peduli dengan kesenangannya sendiri.”
“Kenapa kamu bilang begitu?” ini sih udah nggak bener.
Dia menggeleng, “Rasanya sakit banget,” dia berkata. “rasanya seperti aku diselingkuhi ayah sendiri,” dia terisak, “seolah rindu yang selama ini aku pupuk bareng sama Mama itu salah. Nggak ada bedanya seperti menanti kotak harta karun yang kosong.”
“Maaf, aku nggak mengerti situasinya seperti apa.”
“Dengan bodohnya Papa mengenalkanku pada anak kecil yang tanpa pernah kutahu dan memang nggak mungkin kalau itu adikku. Yang entah hasil cintanya dengan siapa.”
Gue sangat terkejut dengan pernyataannya itu. Tak bergeming saat menoleh ke arahnya.
“Dia sudah menjelaskan tentang itu?” gue bertanya hati-hati.
“Mungkin maksudnya Papa ingin menjelaskan, tapi aku enggan mendengarkan.”
“Kamu harus mendengarkan alasan seseorang berbuat sesuatu.”
“Ngomong memang gampang, Fis.”
“Maaf,” gue mengangguk, “kalau boleh tahu Papamu baru pulang dari mana?”
Dia menceritakannya selama hampir seperempat jam, sampai gue akhirnya bener-bener tahu situasinya seperti apa. Tapi ada satu hal yang mengganjal di telinga gue saat Louisa menyebut nama ibunya, ‘Mirwana’. Itu nama yang tak asing. Lalu gue teringat buku itu. Tapi, mana mungkin?
“Lou, nama ayahmu siapa?” gue bertanya.
“Kenapa kamu perlu tahu?”
“Cuma penasaran.”
Dia menghela napas, “Iyus.”
***
🎹 Alex 🎹
***
Namanya Mas Adit, dia instruktur yang membantu pelatihan untuk penyembuhan kaki saya. Semenjak itu ada banyak perubahan yang signifikan. Setidaknya saya jarang merasa kesakitan di bagian kaki dan sedikitnya bisa saya usahakan untuk berjalan, meski masih perlu bantuan kruk.
“Grab pesananmu sudah di bawah. Yakin mau pergi? Ini masih hujan deres, bro,” katanya yang habis memastikan mobil yang saya pesan sudah datang.
“Ada keperluan mendesak.”
“Nanti kalau Pak Irfan marahin saya gimana? Sudah perjanjian kalau saya harus antar kamu pulang juga. Kalau mau menunggu dua jam lagi pasti saya antar seperti biasanya.”
“Nggak apa-apa, Mas lanjutin urusannya saja. Aku bisa balik lagi ke sini kalau sudah selesai, ini cuma perlu memastikan sesuatu saja.”
“Kamu serius?”
“Ya, ini cuma sebentar.”
Kelemahan saya terletak pada rasa khawatir ketika mendengar bahwa Louisa sedang dalam kesulitan. Itu benar-benar selalu berhasil membuat saya melanggar banyak aturan dan menerabas hambatan.
Dari yang Nafis kabarkan tadi, saya merasa perlu berada di sana. Atau nanti malah orang lain yang menenangkan Louisa dan bukannya saya.
Beberapa kali saya pergi keluar atau ke kampus dengan bantuan jasa moda transportasi daring. Bahkan pergi ke gym pun saya dengan itu. Makanya tadi yang saya lakukan begitu Nafis menutup panggilan adalah memesan Grab car. Entah apa yang sedang terjadi sama Louisa, intinya saya perlu ada di sana memastikan situasi apa yang sedang terjadi.
Mobil melaju cepat. Saya nggak peduli hujan yang turun semakin deras. Setelah beberapa menit kemudian mobil berderap di belokan sekitar rumah Louisa. Namun apa yang saya dapati adalah sesuatu yang tak pernah saya harapkan. Seolah apa yang saya usahakan untuk sampai di sana hanyalah sia-sia.
Saat mobil melintasi sebuah halte, dengan jelas saya melihat Louisa yang sedang mengobrol berdua dengan Nafis.
Perempuan saya sedang menangis di dekat cowok lain. Seharusnya saya yang ada di sana untuk jadi teman berkeluhnya.
Saya menyuruh sopir menghentikan mobil itu tak jauh dari halte. Hanya untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan selanjutnya.
Dia Nafis, saya tahu dia tidak akan menjadi halangan buat saya. Dan dia sedang dalam keadaan yang rumit dengan Rea.
Semakin lama saya memperhatikan, cara mereka mengobrol semakin serius. Tangan keduanya ikut bergerak sembari bicara. Saya nggak suka ketika Louisa yang bahkan mulai merasa enteng menumpahkan air matanya di depan Nafis. Itu nggak boleh! Meski dia adalah Nafis!
Sejurus kemudian saat hujan berubah menjadi rintik kecil, mereka berdua berdiri. Louisa memakai mantel hujan yang mungkin itu adalah kepunyaan Nafis. Saya tahu Lou nggak punya mantel semacam itu. Lalu yang terjadi selanjutnya mereka berdua berboncengan. Di situlah, ada sayatan kecil yang saya rasakan. Samar, tapi terasa menyakitkan melihat mereka berdua berboncengan.
Saat motor itu melintasi mobil, saya menyuruh sopir untuk mengikuti motor itu. Jarak laju yang semakin jauh seperti membuat rekahan sengit di dada saya. Padahal saya pernah berjanji nggak akan mencemburui Louisa dalam situasi apapun. Namun rupanya hati saya tak bisa searah. Dia cemburu, dia kesakitan, dia curiga.
Tak lama kemudian motor itu berhenti di depan sebuah minimarket. Louisa turun dan menunggui di dekat motor Nafis. Saya merutuki kaki saya yang saat ini nggak mungkin digunakan untuk lari ke sana dan membawa kabur Louisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencengkeram pinggiran jok, dan terkapar pada suhu panas dari kecemburuan yang sejak sekian lama baru kali ini saya rasakan.
Nafis keluar dari minimarket dengan plastik belanjaan. Dia mengulurkan sekotak tisu kecil pada Louisa sebelum melajukan motornya kembali.
Saya tidak tahu pasti, tapi akhirnya motor itu menikung masuk melewati gerbang utama sebuah rumah besar. Apa itu rumah Nafis? Saya tidak begitu yakin.
Perlahan saya merasakan sayatan itu semakin melukai. Ada yang tidak saya ketahui di sini. Kenapa mereka melakukan ini? Jangan bilang hanya karena pacar mereka sedang dalam keadaan tak sempurna lagi lantas mereka saling jatuh cinta.
Dengan gugup saya menekan nomor Louisa di ponsel. Meneleponnya untuk memastikan. Namun berkali-kali saya mengulang tidak ada jawaban darinya.
Saya membanting ponsel di jok sampai terjatuh ke bawah, sedikit gaduh.
"Ada apa Masnya?" tanya sopir itu.
"Putar balik, Pak."
"Ke mana? Nanti tarifnya nambah lho."
"Putar balik saja, akan saya bayar berapa pun juga."
***
Fyuuh.
How do you feel? just comment here.
Jangan lupa kasih bintang 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top