Chapter - 19: Accidental Spot
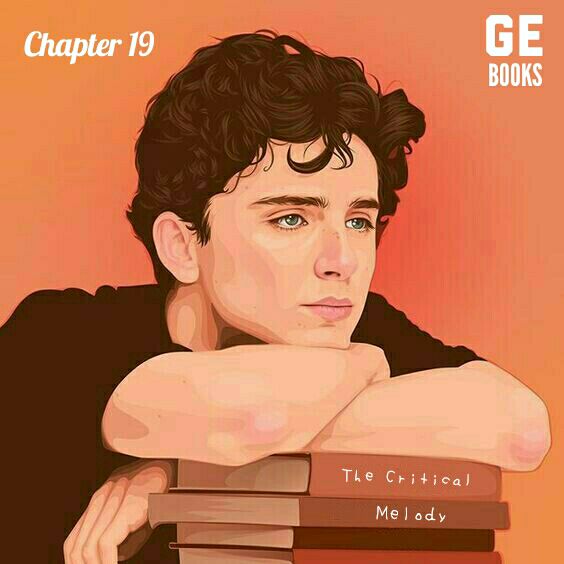
***
🎻Louisa🎻
***
Hasil pemungutan suara jelas-jelas sangat sulit untuk disangkal. Aku hanya tak ingin memiliki kesibukan di organisasi lebih banyak dari pada meluangkan waktu untuk Alex. Tapi sebagian besar forum tidak menyutujui penolakanku untuk menjadi Pradana Putri terpilih.
"Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi sepertinya saya tidak bisa mengemban amanah ini untuk kedepannya," kataku yang setengah membungkuk di depan forum demokrasi. Tatapan mereka masih fokus ke arahku dengan lamat.
"Kalau kamu bisa memberi alasan yang lebih jelas, mungkin akan sedikit bisa diterima akal. Saat ini kamu cuma memberi alasan yang begitu ringan, bahwa, kamu hanya beropini akan tidak bisa mengemban tanggungjawab ini," salah seorang Purna berkata demikian. Aku tahu sebagian besar dari mereka adalah yang mengisi suara terbanyak untuk memilihku. Karena mereka sangat semangat untuk mengusung aku sebagi kandidat terpilih. "Sangat tidak masuk akal bukan? Kamu kan selama ini tidak pernah absen setiap latihan pramuka. Jam terbangmu juga sangat bagus, Lou. Dan, empat puluh persen dominasi suara yang kamu dapat pasti percaya kamu bisa. Kandidat yang lain juga sama-sama layak, tapi angka yang memutuskan," tambahnya.
Aku sekuat tenaga untuk tidak mengutarakan bahwa Alex adalah alasannya. Ini sangat egois memang, tapi kejadian mengerikan yang menimpanya itu membuat aku tidak siap melepaskan Alex dari jangkauan pengawasanku lama-lama, atau, aku harap tidak akan pernah ada hal menakutkan serupa yang akan terjadi.
Saat mendengar Nafis berkata, "Umm," yang aku yakini sekali dia akan berbicara soal urusan pribadiku sebagai alasan agar aku mau. Ya, dia terpilih dengan suara mayoritas dan sangat semangat untuk mengemban amanah itu. Dia berdiri tak jauh dari meja karena menunggu giliranku sebelum dia yang maju. Aku langsung menyela dengan cepat.
"Baiklah. Sebenarnya saya punya urusan pribadi yang amat, sangat mempengaruhi keputusan saya. Tapi," aku membuat gap cukup lama di sini. Sedang mengingat-ingat Alex pasti akan marah kalau tahu aku menelantarkan keyakinan banyak orang. Alex sangat mendukungku untuk aktif di organisasi ini, dan sudah berkali-kali memperingatkan agar aku tidak terlalu banyak memikirkannya. Dia mengatakan dukungannya beberapa hari sebelum kejadian mengerikan itu. Aku menegakkan punggung dan menghadap ke depan. Sekali lagi membayangkan wajah Mama yang juga pasti akan mengomel kalau Alex mengadukan sikapku yang jika menolak ini. "Saya akan mencoba. Mohon bantuan semuanya."
Gaung salam pramuka akhirnya membesarkan keyakinanku bahwa ego harus ditahan dengan sebaik mungkin. Seseorang pernah berkata bahwa musuh terbesar cinta adalah ego. Dan bagiku, itu memang benar. Aku dipenjarakan oleh sebuah ego untuk tetap menjadi pencinta yang setia, bahkan jika harus mengorbankan sebuah kedudukan seperti di organisasi. Aku memang sangat mencintai pramuka. Tapi tak ada ambisi untuk berada di sebuah posisi.
Upacara pelantikan dilakukan tak lama setelah Nafis resmi menerima jabatannya sebagai Pradana Putra melalui pidato singkatnya. Dia jauh lebih bersemangat dari dugaanku. Memang sangat layak. Kalau boleh jujur, aku juga tadi mempercayakan suaraku kepadanya. Dan sepertinya dia akan jadi rekan yang baik, asalkan ... um, lupakan. Aku hanya berpikir semua orang tidak akan mungkin sama.
***
Pukul empat sore di hari ketiga perkemahan ini, kami sudah berkemas untuk pulang. Karena aku punya tanggung jawab baru, sudah berkewajiban bagiku, Nafis, dan rekan panitia yang lain untuk memastikan semua adik tingkat pramuka mendapat tempat duduk di bus untuk pulang. Sementara aku dan rekan yang lain akan menunggu bus berikutnya sambil bergotong-royong mengangkat benda-benda penting ke truk pengangkut.
Saat langit menggelap, semuaya sudah bersiap ke bus. Aku keluar dari tenda kesekretariatan sambil menggendong ransel gendut. Tenda ini milik pengelola bumi perkemahan, jadi bukan kami yang akan memberesi. Lagipula keesokan harinya di tempat ini akan ada perkemahan lagi. Aku baru saja memastikan sudah tidak ada lagi anak yang ketinggalan. Untungnya tidak ada.
Aku membiarkan Fina pergi duluan saat kulihat Nafis sedang mengikat tali sepatunya di sisi tenda.
"Ayo buruan," kataku membuatnya mendongak.
"Kamu duluan saja, rekan," wajahnya masih terlihat puas sekali. Dia pasti merasa menang dua kali lipat. Pertama karena berhasil mendapat suara terbanyak, dan yang kedua akhirnya aku menyerah untuk menerima jabatan itu. "Aku nggak pulang bareng kalian."
Aku menahan diri untuk pergi, "Maksudnya? Mau jalan kaki?"
"Ayahku mau jemput ke sini."
"Ha? Dijemput?"
"Bukan aku yang minta. Ibu tadi nelepon katanya Ayah bakal ke sini buat jemput. Dan pesannya, aku nggak boleh nolak."
Dia pasti tahu aku pengin banget menertawakan ini. Dia kayak anak kecil banget coba masih dijemput-jemput gitu.
"Silakan aja kalau mau diketawain."
"Ya itu hak ayahmu mau jemput," aku memutuskan untuk merahasiakan ejekanku. "Lagian biar langsung ke rumah."
Setelah bilang gitu, aku melenggang pergi. Tapi buru-buru langkahnya mengejar. "Pulang bareng aku aja, yuk?"
Nafis berjalan di sebelahku.
"Ngapain pulang sama kamu? Aku niatnya mau nginep di rumahya Fina."
"Pasti gara-gara nanti sampai sekolahnya malam dan udah susah kendaraan, kan?"
"Ya, kan Alex nggak mungkin jemput aku."
"Makanya, mending pulang bareng aku. Bisa tidur nyaman selagi ayah aku yang nyetir. Itu juga kalau dia nggak cerewet tanya-tanya."
Aku tidak akan menerima tawaran baik itu. Karena ini berbahaya untuk persahabatan aku dan Rea yang baru saja membaik. Apa jadinya kalau ada anak lain yang lihat aku masuk ke mobil itu dan ada gosip aneh nantinya.
"Aku udah janji sama Fina. Lagian nggak enak lah sama anak yang lain."
"Tuh, aku juga mikirnya gitu misal dijemput. Nggak enak sama yang lainnya."
"Kamu sih nggak apa-apa. Toh pekerjaanku memata-matai kamu di sini udah beres. Tinggal laporan," aku tertawa melihat ekspresinya yang seperti kesal sekali.
"Kamu perlu disogok nggak sih biar nggak bilang ini-itu ke pacarku?" ucapnya bangga.
"Uu, sebenernya kalau kamu nggak terlalu semangat nyudutin aku biar mau ambil posisi ini, aku bakal mempertimbangkan soal pekerjaan mata-mataku," sekali lagi aku tergelak.
Tapi Nafis sudah tidak mendengarkanku rupanya. Sikapnya berubah teduh saat dia menatap mobil yang nggak jauh dari bus pengangkut rombongan panitia. Kalau tidak salah, itu mobil ayahnya.
"Ya sudah, aku duluan, ya?" ucapnya tanpa menolehku sambil mempercepat langkah. Sikapnya itu seperti sebuah pertanda dari hubungan ayah dan anak laki-laki yang kurang harmonis. Pikirku.
***
Menginap di rumah Fina adalah ide yang bagus. Aku tidur pulas sekali meski harus bangun setelah subuh dan segera pulang. Ya pastinya Fina dan Ibunya menahan aku agar pulang setelah sarapan di sana. Tapi, mungkin karena aku mendapatkan senyum kerennya Alex dalam mimpi yang sangat membuatku seterkesan ini, makanya aku dengan sopan pamit saja.
Sampai dirumah aku yakin sudah punya cukup tenaga untuk bergerak cepat mengganti pakaian yang rapi dan menuju ke rumah sakit. Di rumah tidak ada siapa-siapa, sedangkan di warung cuma ada Mba Atin yang jaga. Aku titip pesan ke dia untuk disampaikan ke Mama soal aku yang pergi ke rumah sakit. Mama pasti pulangnya agak siang kalau urusannya dengan pengepul ikan di pasar. Setahuku Mama juga akan memulai bisnis baru yang berkaitan dengan ini. Dia punya kehebatan untuk urusan bisnis.
Sesampai di ruangan Alex, coba tebak, dia sedang membaca buku sambil bersandar di bantal. Ada seorang suster yang baru saja keluar mengecek kesehatn Alex. Tubuhku serasa seringan kapas ketika senyum yang semalam kulihat dalam mimpi kini menjadi sangat nyata di depanku. Meski wajahnya masih sedikit pias, tapi dia seolah akan jadi jauh lebih baik kalau melihatku.
"Om Irfan atau Tante Ratih, mana?" tanyaku begitu menyadari ruangan itu sepi.
"Mereka pulang begitu tahu kamu mau datang. Katanya mumpung ada perawatku yang ini," yang dia maksud itu aku, "Ada kolega ayah yang datang dari jauh. Paling abis zuhur mereka balik lagi."
Aku memberengut bukan hanya karena tahu Alex dari tadi sendirian, tapi karena suaranya yang masih serak dan saat aku meremas jemarinya rasanya hangat tidak wajar, seperti demam. Aku menatapnya dengan hati yang teriris. Kepalanya masih dibebat, kakinya juga ditopang bantal, meski ada kabar baik bahwa sakit di tangannya mulai mereda.
"Sakit banget, ya?" kataku pelan. Menahan rasa ingin mengomel karena kecerobohannya yang bikin seluruh keluarga kalangkabut.
Jemarinya menyambut baik sentuhanku "Semuanya akan lebih baik lagi."
Aku menghela napas sukar, menggerakkan ibu jari untuk mengusap jemarinya.
"Kenapa kamu nggak sekolah?"
"Masih capek."
"Tapi nggak cukup capek buat pergi ke sini?"
"Ini semester baru, Alex. Nggak bakal ada pelajaran di kelas. Lagian aku nggak mau kalau ketemu anak-anak dan mereka pada ngerubung cuma buat ngucapin selamat atas jabatan yang nggak aku inginkan sama sekali."
Alis Alex terangkat, "Well, apa kubilang. Kamu pasti mendapat posisi itu. Selamaaat!"
"Tapi aku nggak suka!" proteskku.
"Kamu suka!" tampik Alex dengan intonasi yang meniru suara cewek. Bukan lain niatnya pasti mau bikin aku semakin kesal, dan tetap begitu, "Kamu cuma sedang bikin alasan. Dan kalau alasannya adalah aku," kepalanya menggeleng dengan ekspresi, "aku nggak setuju."
"Aku tahu kamu bakal bilang begitu. Geez," kataku sambil mencubitnya.
Dia meringis, "Dan Pradana Putranya adalah?"
"Kamu pasti tahu siapa," aku pasti sedang merajuk. Di dekatnya, aku ingin merajuk seperti ini. Cuma ingin lihat bagaimana Alex akan bersikap manis untuk merebut hatiku lagi.
"Bagus dong. Nafis, kan? Dia anaknya kapabel buat jadi Pradana. Lagi pula kalian kan temenan, jadi nanti bisa lebih gampang kalau mau buat program kerja satuan."
"Iya sih," aku sedikit lesu.
"Kenapa? Kamu takut aku cemburu?"
Sekarang aku ingin memukul perban di kepalanya, "Ya iyalah aku takut kamu cemburu! Secara kan nanti aku bakal sering rapat sama dia. Ya, sama yang lain juga. Kalau kamu mencemburuiku dengan semua curigamu, aku merasa direndahkan komitmen setianya."
Mendengar pembelaanku Alex malah tertawa lebar. "Kamu pikir aku cemburu?" tanyanya masih dengan sisa-sisa tawa. "Lou, aku menang hompimpa sama malaikat maut dan diganjar dengan satu kesempatan hidup lagi. Mana mungkin aku akan menghabiskan ganjaran ini buat mencemburuimu. Dan seandainya kamu pikir aku cemburu, berarti, kamu juga meremehkan kesetiaan dan kepercayaanku ke kamu."
Itu menyentuh bagian terdalam dari hatiku. "Nah, sebelum kita berpotensi saling meremehkan. Aku mau memastikan kalau kamu nggak perlu khawatir akan kehilangan aku."
"Lagian dengan adanya Rea yang mulai akur lagi sama kamu, pasti dia juga nggak akan membiarkan kejadian memalukan di masa lalu kalian itu terulang kembali. Rea akan sangat menjaga Nafis."
"Nah, kan, kamu nggak perlu khawatir," kataku. Aku tahu Alex masih belum puas ingin menertawakanku.
Alex meremas jemariku untuk menunjukkan kepercayaannya padaku. Dan kehangatan yang menenangkan dari suhu demamnya cukup membuatku bergerak meletakkan kepalaku di bagian samping tempat tidurnya. Posisi dudukku sudah nyaman, dan suasana hatiku memasuki dimensi baru dari ketenangan. Alex meletakkan bukunya di nakas dan mengelus kepalaku.
"Kamu sudah minum obat demam? Badanmu agak panas," kataku lirih yang mulai terasa ngantuk. Mungkin terlelap dalam posisi duduk dan menopang kepala di kasur seperti ini tidak apa-apa.
"Suster yang tadi baru saja ngasih obat demam."
"Mm," gumamku, "Kamu kuliahnya gimana?"
"Tidak masalah, ada toleransi untuk ini. Kamu tahu kan, pihak kampus ikut cemas. Mereka datang ke sini dan memastikan kalau keadaanku nggak akan berimbas lebih buruk ke kuliahku, selain ketinggalan materi."
"Jangankan pihak luar yang pada khawatir, kamu sudah terlebih dulu membuatku mati rasa lebih dari apa yang mereka khawatirkan ke kamu," kataku, "mati rasa di dalam," sebagai penekanan.
Aku mendengar senyum Alex, dan tangannya masih mengelus, "Lou," katanya.
"Mm," mataku mulai terasa berat. Kantuk menyerang perlahan.
"Bagaimana kalau saat itu aku mati?"
Jantungku mencelos saat Alex megatakan itu. Dia tidak tahu betapa aku sudah bertikai sengit dengan gagasan mengerikan itu dalam kepalaku. Dan berusaha sekeras apa untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi malah dia yang mengatakannya. Itu sangat menakutkan. "Ide yang buruk kalau kamu mau membahas itu, Alex."
"Aku serius, apa yang terjadi ketika, apabila di kehidupan ini nggak ada Alexnya lagi?"
"Aku tamat," jawabku singkat karena sama sekali nggak ingin membahas ini.
"Seenggknya aku mencintaimu sampai mati."
"Alex! Aku pergi sekarang kalau kamu masih mau ngomongin ini. Membayangkannya saja sudah membuatku mati rasa, apalagi sekarang kamu malah membicarakannya."
"Iya, iya," aku harap dia benar-benar akan berhenti mengungkit topik itu.
"Harusnya aku nggak pernah kasih kamu izin pergi naik gunung!" kataku kembali merebahkan kepala setelah tadi menegakkan badan.
"Sudah terjadi."
Kantuk yang sempat menggelayut entah pergi ke mana sekarang. "Aku juga masih ingin tahu kenapa kamu bisa sangat ceroboh. Karena kamu bilang ke Om Irfan begini, dan bilang ke akunya lain lagi."
Alex masih mengunci mulutnya.
"Sekarang coba ceritakan kenapa?"
"Sebenarnya aku masih terguncang karena kepergian dua sahabatku itu. Jadi, aku nggak tahu apakah menjelaskan detailnya saat ini adalah ide yang baik atau sebaliknya."
Aku semakin memegangi tangannya, "Mumpung tidak ada siapa-siapa selain aku. Mungkin kamu bisa mengatakan apa yang tidak ingin orang lain tahu. Itu kalau menurutmu keterbukaan masih diperhitungkan di hubungan ini."
Alex mendesah, "Aku nggak yakin kamu akan menyukai cerita ini kalau aku jujur, Lou."
"Justru aku akan semakin bertanya-tanya kalau kamu masih nggak mau menceritakannya," aku menatapnya dengan tatapan kepercayaan. Berharap Alex bisa tahu kesiapanku menyimak apa saja.
Bibir bawahnya tiba-tiba gemetar, dia semakin ragu untuk menceritakannya. Ada kilauan seperti air mata yang menahan di pelupuknya. "Anna dan Nirwan semakin nggak akrab sejak aku hanya mau difoto sendirian. Kamu pasti tahu foto yang aku unggah di facebook itu?"
Aku mengangguk tulus supaya Alex tetap nyaman mau bercerita.
"Anna tidak mau berbicara ke siapapun semenjak aku menolak foto bareng dia."
Aku tidak berani menduga-duga. Bibir Alex masih bergetar setiap kali hendak mulai berbicara, "Dia menyukaiku. Nirwan menyukainya. Dan aku nggak menaruh hati ke siapapun selain kamu."
"Lalu?" aku menelan ludah berusaha tidak menunjukkan betapa buyarnya perasaanku mendegar itu.
"Ada pertengkaran kecil antara mereka berdua," dia memejamkan matanya sesekali untuk mengingat. "Nirwan minta bantuan ke aku supaya mau ikut foto-foto bertiga. Karena dia pikir dengan aku mau foto itu bisa bikin Anna lebih baik sikapnya. Cewek itu memang agak tempramental, makanya lumayan susah buat bikin dia tenang. Mereka berdua pergi terlalu jauh dari kelompok. Aku tahu ini salah banget dalam aturan pendakian. Nirwan agak sok tahu jalan padahal setahuku dia baru pertama kali ke sana. Dia pikir jalur jejak yang dia ambil itu untuk pendakian. Ternyata, atau mungkin bisa jadi itu cuma jejak pemburu atau warga setempat yang selain untuk pendakian. Semakin jauh dan jauh, sampai aku mulai khawatir." Dia jeda sebentar, "aku nggak tahu bagaimana persisnya. Ketika aku sedang fokus membidik hummingbird dengan kamera ... tiba-tiba saja terdengar jeritan dari dua orang itu."
Aku nggak berani menyela untuk menanyakan apapun. Intinya aku ketakutan.
"Itu tebing yang cukup tinggi dan berbatu," kata Alex getir. "Saat itu aku bodoh memang. Harusnya langsung pergi mencari bantuan, bukannya sok jagoan atau karena aku terlalu panik untuk melongok ke jurang."
"Gimana kamu bisa ikutan berada di bawah sana?" tanyaku ragu.
"Batu yang aku injak tidak berada di posisi yang tepat."
"Terpeleset?"
"Batu itu yang membawaku ke jurang dan dihantam apa saja. Aku menggelundung di kemiringan tebing, bukan terjun bebas."
Aku memejam penuh kesakitan membayangkan Alex harus menggelundung seperti ceritanya itu.
"K-kamu, kamu yakin tidak ada unsur bunuh diri di sana?"
Alex menggeleng, "Aku nggak yakin. Meski aku tahu belakangan Anna lagi punya depresi karena orang tuanya bercerai. Tapi, aku nggak ingin menduga karena itu lantas dia memutuskan untuk, ya."
"Atau hanya karena kamu yang nggak mau foto sama dia?"
"Lou, itu kemungkinan kecil. Tempat yang kami datanig bertiga itu memang rawan."
"Kamu nggak sebodoh itu buat terus ngintilin mereka ke tempat rawan yang harusnya kamu tahu itu, kan?" tanyaku kesal.
"Kan aku niatnya bikin mereka baikan makanya aku nurutin saja."
Aku mendesah dengan denyutan pening di kepala. "Lalu sejak kapan Anna menyukaimu sampai akhirnya kamu tahu?"
"Belum lama ini."
"Beneran?"
"Dia bilang ke aku tepat setelah malamnya Nirwan nembak dia. Anna nggak tahu kalau aku sudah punya seseorang, makanya dia ... aku bingung."
"Kamu suka dia?"
"Seratus persen nggak," jawabnya cepat-cepat. "Aku baru tahu mereka meninggal ketika Ayah bercerita dengan hati-hati. Dan itu baru dua hari kemarin."
Aku mengusap pundaknya, "Aku nggak tahu harus mengomentari apa lagi." Tubuhku mendekat sampai memeluknya yang bersandar di bantal itu. "Yang terpenting, kamu baik-baik saja."
Suara isakan lirih terdengar dari Alex.
"Kesalahan memang kadang perlu terjadi, Alex."
"Apa aku berdosa, Lou?"
Aku menggeleng cepat-cepat, "kamu tidak melakukan hal yang salah. Sayangnya kamu harus terlibat pada takdir dua orang itu. Dia temen baikmu, kan?" kataku sambil menepuknya pelan.
Aku tahu betapa sulit bagi Alex jika harus menceritakan semua detilnya ke banyak orang. Dan sepertinya informasi yang disebarkan oleh media pun murni hanya tentang kesalahan pendaki, meski banyak komentar miring soal itu. Tapi itu nggak terlalu berimbas buruk untuk nama Alex.
Aku sampai di rumah menjelang sore, masih lesu karena ketiduran di bus selama perjalanan pulang. Mama sedang kedatangan tamu rekan bisnisnya di rumah. Jadi lebih baik aku segera ke kamar dan merebahkan tubuh sebentar. Hampir saja aku terlelap jika ponselku tidak berdering karena Rea meneleponku dan membuatku harus cepat-cepat mengangkatnya.
"Hai, Lou."
"Rea, ada apa?"
***
***
🎸Nafis🎸
***
"Tempat ini asik banget loh, Nak," kata Bunda saat kami berempat sedang di dalam lift menuju rooftop sebuah hotel. Kami akan merayakan tujuh belas tahunku dengan makan malam santai di rooftop ini.
"Kamu pasti belum pernah ke sini," Ayah menambahkan. Dia berdiri di sebelah gue sambil menggamit tangan Nasywa. "Pemandangan malam Jakarta itu ide yang bagus buat orang yang mau ulang tahun ke tujuh belas."
"Terakhir ke sini, kapan ya, Yah?" Bunda bertanya.
"Kapan ya?" mereka cekikikan.
Gue diam saja, karena gue pikir ini lebih berkesan seperti malamnya mereka berdua alih-alih malam spesialnya gue. Tentu ide ke sini dari mereka. Gue mana mungkin kepikiran buat ke tempat ginian.
Saat Ayah dan Bunda masih bercakap-cakap sambil sesekali menjawab pertanyaan anehnya Nasywa, gue mengetik pesan ke Rea dengan usaha agar tidak terlalu menarik perhatian Ayah. Rea nggak bisa hadir di sini kan. Tapi katanya Pian akan datang. Ayah memang nyuruh gue buat ngajak beberapa teman buat ikutan makan malam ini. Dan gue cuma percaya sama Pian karena agak malas kalau Ayah jadi punya lebih banyak ketemu teman gue yang bisa dia tanya-tanya.
Begitu nyampai di atas, gue meminta agar Ayah sama Bunda duluan. Karena Pian menelepon yang katanya baru sampai di depan meja resepsionis.
"Aku nunggu kamu di depan lift teratas, nih," kata gue.
"Lift-nya yang mana?"
"Tanya aja ke resepsionis, nanti diarahin kok. Tadi aku udah bilang ke mereka kalau ada orang yang namanya Pian mau ke rooftop."
"Lantai berapa?"
Begitu aku menyebutkan dia langsung menutup panggilan.
Gue menunggu di sana hampir sepuluh menit. Entah karena Pian nyasar atau karena dia nggak tahu cara memakai lift.
Tak lama setelah itu, pintu lift di depan gue terbuka, dan di sana ada Pian yang membawa kado berbentuk kubus kecil dengan warna hitam dan berpita emas. Pakaiannya terlalu formal. Tapi yang membuat gue terpana bukanlah kehadirannya semata. Melainkan seseorang yang ikut di sebelahnya, mengenakan dress santai berwarna merah marun. Bibirku melengkung otomatis.
"Kalian nggak nyasar kan?" tanya gue.
"Pian kebelet ke toilet dulu tadi, itu yang bikin lama," jawab Louisa dengan ekspresi wajah yang sebal ke Pian.
"It's Okay," gue berkata, "Orang tuaku sudah ada di sana. Barangkali kalian perlu kenalan dulu." tambah gue sambil berpikir kenapa Louisa bisa ikut datang ke sini. Tapi itu bagus.
***
***
Terimakasih sudah setia membaca kisah ini. Jangan sungkan untuk berkomentar.
*Chapter 20 akan saya unggah kalau chapter ini sudah mencapai 85 votes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top