Chapter - 10: The Day Before
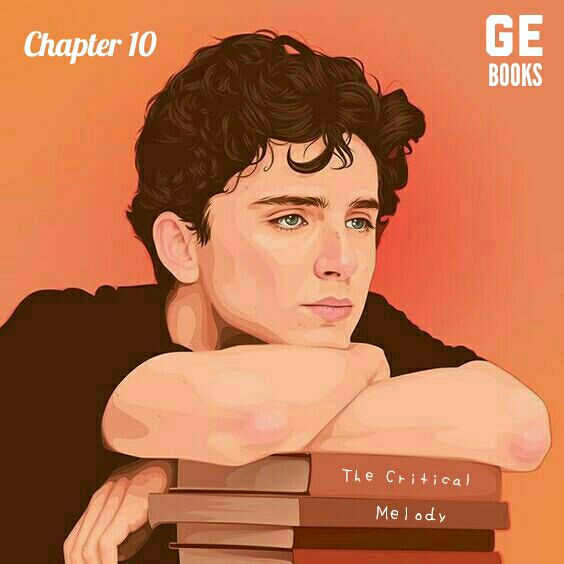
1
Yang gue suka dari Rea bahkan setelah setahun kita pacaran adalah bagaimana dia membuat gue merasa sangat dia butuhkan. Komitmen picisan yang kita berdua buat waktu itu telah kami genggam rapat-rapat sampai sekarang. Pian atau siapapun nggak ada yang tahu kalau gue dan seorang Milly Reason menjalin hubungan spesial.
Bayangkan saja, selama itu kita berhasil bikin tak ada seorang pun yang curiga. Ini bukan soal gue yang memberi penekanan supaya Rea tetap mengunci, bahkan gue tak pernah memberi penekanan apapun. Dia ataupun gue sama-sama melepas tali ikatan ketika di depan orang-orang. Tapi jangan tanya ketika kami lagi ada kesempatan berdua. Seolah kalian semua harus membayar bulanan selama tinggal di planetnya gue sama Rea ini. Oke, mungkin itu berlebihan. Tidak, kami hanya merasa bahagia kalau lagi bareng.
Gue bangga sama Rea yang selama tiga semester ini berhasil menempati posisi pertama dari sekian banyak anak seangkatan. Diikuti Louisa pada posisi kedua. Dan pacarnya Rea tepat di posisi ketiga. Jadi soal kartu ajaib itu memang sebuah pertaruhan besar untuk siapapun yang bisa memenggal posisi yang ada. Jujur persaingannya begitu menakutkan.
Apalagi gue sama Rea yang kerjaannya pacaran. Maksudnya gini, memanfaatkan kedekatan untuk hal-hal baik. Sepertinya cuma gue sama Rea yang ketika hubungannya makin kuat, semakin bagus juga prestasi akademiknya. Iyalah, kita belajarnya bareng, gue yang main ke rumahnya Rea. Kakaknya Rea juga sudah akrab sekali sama gue, namanya Mas Abam (Abraham Reason), dia sudah kerja di kounter gadget bareng Maminya Rea.
Semenjak kita pacaran, gue jadi lebih tahu kalau selama ini Rea sebenarnya nggak punya teman yang benar-benar bisa selalu ada. Gue nggak ngerti alasannya apa, tapi ada sesuatu yang coba Mas Abam ceritakan ke gue. Cuman Rea selalu saja punya alasan untuk menghentikannya. Tak apa.
"Jadi akhir pekan ini kamu harus berangkat kemah?" Rea sedang membaca katalog kampus-kampus populer. Sementara tadi gue lihat Mas Abam masuk ke dalam kamarnya. Televisi yang sedang menyala pun dibiarkan menayangkan iklan alat kebugaran tanpa ditonton.
"Tahun ini aku punya firasat bakal dicalonin jadi ketua pramuka untuk masa bakti yang akan datang. Aku harus berangkat dong, Re. Lagian kenapa kamu nggak ikutan aktif di pramuka? Kan bisa misalkan akhirnya kita nanti berangkat bareng."
"Nggak apa-apa sih."
"Sih?"
"Aku udah terperangkap sama klub mata pelajaran."
"Risiko kan?"
"Ya."
"Kalau nanti yang jadi ketua putrinya Louisa gimana?"
Dia seperti pura-pura tidak mendengar. "Baiklah, ini bukan bahasan yang kamu harapkan," kata gue lagi.
Ada tawa yang terdengar santai, dia memeluk leher gue dari belakang. Posisinya dia lagi baringan di sofa, sementara guenya lagi main legonya Mas Abam di karpet bawah sambil bersandar pada sofa yang sama. "Jangan gitu, nanti Mas Abam lihat."
"Biarin."
"Ini mau apa? Aku nggak boleh ikutan pramuka kalau dia yang nanti jadi ketua putrinya?"
"Siapa yang bilang gitu?"
"Nebak aja."
"Kamu bawa jaket ya nanti."
Gue meringis mendengar nadanya yang menutup ego, "Nggak mau bawa ah."
"Ya udah."
"Ya udah?"
"Kenapa?"
"Kamu nggak peduli neh misal aku abis dikroyok nyamuk?"
"Yaudah bawa!"
"Hehe."
Dia melepas tangannya dari leher gue, pasti meninggalkan bekas. "Semua orang udah yakin kalau kamu sama Lou yang nanti dicalonin."
"Dan?"
"Masalahnya aku nggak mungkin bisa mencegah keinginan ratusan orang sementara aku cuma sendirian misal menentang."
"Oke, aku tahu kamu ragu."
"Terus kalau aku menghalangi, apa kamu akan berhenti juga? Kayaknya nggak, wee. Aku tahu seperti apa kamu suka banget sama pramuka."
"Rea."
"Santai aja, Fis."
"Santai, gimana aku bisa santai kalau kamu ragu gini."
"Nggak ragu kok. Cuman ya-."
"Apa?"
Mas Abam menuruni tangga sudah berpakaian rapi dengan tas sling di pundak. "Kalian jangan macem-macem ya. Gue mau ke plaza sekarang."
"Tenang aja," jawab gue. "Kita mau ke sanggar kok."
"Ya udah, jangan lupa pintu dikunci, oke? Atau kasih aja kuncinya ke bibi di dalem."
"Iya, Mas," jawab Rea tanpa menoleh.
Tak lama kemudian terdengar mobil keluar dari pekarangan.
"Aku nggak mau ke sanggar," Rea mengganti saluran televisi.
"Kenapa? Libur? Kalau alasannya malas, itu bukan kamu banget."
"Bukan malas. Cuma ingin ngobrol sama kamu saja."
"Kan bisa nanti di perjalanan."
"Di sini aja. Aku mau ngomongin sesuatu."
Dahi gue mengkerut. "Ngomongin apa?"
Sambil menunggu jawaban, gue beringsut naik ke sofa. Kalau ini sesuatu yang penting, gue harus berkesan serius dengerinnya.
"Fis."
"Katakan."
"Setelah lulus kamu mau ke mana?"
"Jadi karena kamu baru baca katalog universitas terus kamu nanya ini?"
"Jawab dulu."
"Kemungkinan besar kuliah. Kamu tahu."
"Di?"
"Belum tahu."
"Loh? Kita itu udah kelas sebelas, wajar kalau kita mikirin soal ini biar pas tahun terakhir nanti nggak pusing. Kamu juga pasti udah punya angan mau jadi apa kan?"
"Masih tabu," kata gue. Tiba-tiba Rea menyentuh samping kepala gue. Mungkin maksudnya adalah cafune. Gue jadi merasa sedang dimanja. Apa yang terjadi kalau Ayah sampai lihat ini? "Intinya aku nggak ingin punya profesi yang bikin aku jauh dari rumah."
"Kenapa? Bukannya cowok kebanyakan suka merantau?"
"Bukan gitu."
"Kebebasan itu salah satu unsur yang mengalir pada darah cowok, terutama kamu. Meskipun kamu tadi bilang gitu, tapi dengan sikap kamu yang bahkan nggak suka diatur itu sudah cukup menjelaskan. Kamu nggak ingin kerja di kantor Ayahmu? Jadi penerus barang kali."
"Yah. Mungkin itu yang Ayah mau. Tapi benar kata kamu, aku pengin bebas. Aku ingin membuat lajur baru biar di keluarga nggak melulu isinya orang serius. Siapa tahu kelak Nashwa adikku bisa jago ekonomi supaya bisa jadi penerus."
"Iya, kamu ingin profesi yang kayak gimana? Tentukan! Ini di katalog ada macam-macam universtias yang bisa kamu kulik. Siapa tahu bisa klik."
Gue merenung untuk sesaat.
"Kenapa nggak menekuni belajar musik?" tanya Rea.
"Tidak mungkin. Ini cuma hobi."
"Hobi yang bahkan sekarang kamu rajin manggung di kafe setiap malam minggu. Itu udah layak buat diseriusin, Fis."
"Mungkin, tapi aku nggak ingin."
Sedikit menyerah lalu Rea membuka laptopnya dan mulai mengetik di pencarian 'jurusan kuliah yang asik untuk laki-laki'. Sambil memikirkan, gue lalu balik nanya ke Rea.
"Terus, kamu sendiri gimana? Pada akhirnya aku perlu tahu juga kan?"
Tanpa menoleh dari monitor dia menjawab, "Hanya ada dua kemungkinan. Menyusul ayah ke Liverpool atau New York."
"Ha?" gue agak bingung. "Tunggu, kalau kamu jawab Liverpool menurutku wajar. Tapi New York?"
"Juilliard."
"Serius??" disini gue sedikit bangga dengan jawabannya. Tapi ada satu yang mengganjal ketika dia memilih kampus seni pertunjukan terbesar dan terbaik di dunia itu. "Yakin?"
"Kamu tahu kan aku sudah berlatih rutin tiap minggu biar tarianku sempurna."
"Iyap, jelas. Tapi kenapa Juilliard? Kamu bahkan punya kemampuan tak lazim di ilmu sains. Kenapa bukan kedokteran? Atau aktuaria? Sejenisnya mungkin?"
"Aku kebalikanmu. Belajar itu hobi, Fis. Yang serius bagiku itu menari."
"Bercanda?"
Dia tersenyum percaya diri. "Apa wajahku meragukan?"
"Tidak sama sekali. Tapi, itu artinya kita akan berpisah selama itu?"
"Iya, kecuali kita kuliah di kota yang sama. Atau setidaknya kamu ada di negara yang bisa dijangkau kalau kita ingin bertemu." Seolah dia yakin hubungan cinta kita akan langgeng. Gue juga yakin.
"Aku nggak mungkin bisa masuk ke Juilliard, Rea. Dan nggak ingin." gue terkekeh kecil. "Kalau kamu yang daftar itu mungkin saja. Kemampuan gitarku belum layak ditandingkan di kancah sekeren itu. Beda sama kamu yang udah koleksi ratusan medali dari kompetisi menari."
"Terus kamu sendiri yang serius belajar kenapa sampai saat ini belum nemu tujuan?"
"Aku cuma-. Mungkin sesuatu yang berbau pertanian, konservasi hutan, dan semacamnya. Atau sedikit seni. Dulu memang pengin sih ke perminyakan atau pertambangan tapi-."
"No! Aku nggak setuju kalau kamu di perminyakan. Itu nggak sesuai sama angan kamu yang nggak mau jauh dari rumah."
"Iya aku tahu. Bagaimana dengan yang pertama?"
"Bagus juga. Tapi apa tujuanmu pilih itu?"
"Menurutku itu sesutu yang menarik."
"Ada Jepang, Korea, Belanda dan Kanada yang punya sekolah pertanian yang bagus. Tapi menurutku pilih Jepang dan Belanda."
"Tidak."
"Tuh," Rea memutar bola mata. "Kamu maunya apa?"
"IPB mungkin?"
"Beres. Aku yakin kamu bisa masuk ke sana dengan nilai rapor kamu. Tapi kalau kamu ingin sesuatu yang lebih menantang, ya, keluar negeri. Merantau jauh lalu balik lagi ke tanah air dengan ilmu yang kamu ambil di negara orang. Terapkan di negara sendiri."
"Tapi tunggu dulu."
"Apa lagi?"
"Menurutmu arsitek kerjaannya jauh dari rumah nggak?"
Meski terlihat kesal tapi dia berusaha sekali buat menyembunyikannya dari gue. "Yang jelas nggak lebih sibuk dari pekerjaan Ayah kamu. Tapi penuh tantangan."
"Aku tertarik juga ke sana. Atau teknik sipil?"
"Fis! Jangan plin-plan. Kamu punya passion di sesuatu yang berbau keindahan. Misal kamu pilih arsitek itu masuk akal. Ingat pas kita ada tugas bikin maket hasil pengerjaanmu keren banget?"
"Lumayan."
"Jadi mau yang mana nih?"
Tapi rasanya kalau gue nentuinnya sekarang malah jadi terasa aneh. Karena apa yang gue tentuin kali ini bisa jadi akan berubah ketika pada masanya gue memilih jurusan nanti.
Gue menatap Rea dengan sorotan yang berbeda. Membicarakan persoalan ini malah bikin gue mikir apa yang akan terjadi nanti seandainya gue sama Rea terpisah.
"Aku belum pernah memikirkan ini sejauh yang kamu lakukan, Re. Kamu selalu semangat ngomongin kuliah ke luar negeri. Kamu suka bahas bagaimana hidupmu nanti misal udah masa kuliah. Tapi aku sendiri malah begini. Liverpool, atau bahkan soal Juilliard, itu sangat keren."
"Kamu baik-baik saja?"
"Iya, seenggaknya sampai kamu bilang soal kuliah ke luar negeri."
Rea terdiam.
"Apa aku harus melakukannya juga? Bagaimana kita akhirnya nanti? ... selesai?" kataku sedikit getir.
Rea menggeleng cepat. Wajahnya menunjukkan penolakan dari ucapanku. "Nggak pernah dalam pikiranku ada gagasan selesai."
"LDR itu omong kosong, Re."
"Ini masih setahun lagi, Fis."
"Setahun lagi, dan beberapa menit yang lalu kamu bilang harus mulai memikirkan ini dari sekarang. Artinya, sekarang pun aku udah harus mulai memikirkan apa jadinya kalau kita jauhan."
"Fis, kenapa arahnya jadi ke sini?"
"Karena pada akhirnya, kita mentok pada pembahasan ini. Jakarta akan lain cerita kalau aku nggak pacaran sama kamu, dan tanah yang aku pijak nanti juga nggak yakin bakal ada grafitasinya kalau kamu jauh."
"Jangan lebay deh," dia berusaha bersikap biasa.
"Aku nggak lagi lebay. Ini cuma pikiran seorang cowok yang sadar bahwa hari perpisahan jarak dengan pacarnya itu udah kelihatan meski itu setahun lagi."
"Aku juga nggak ingin kita jauhan."
"Terus? Kenapa harus banget nyusul ayahmu? Kenapa nggak tetep kuliah di Indonesia?"
Bahkan dia tidak menjawab. Aku bisa membaca jelas ada yang tak bisa dia ceritakan kali ini.
---o0o---
Bab ini sengaja pendek, karena mulai memasuki feel yang berbeda. Maksudnya, proses pendewasaan sudah dimulai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top