8. Jangan Percaya Butiran Debu di Kaki Langit
Tidak ada pemaksaan dalam hal perdebatan kemarin malam. Berulangkali Pak Kusno meminta maaf atas ketidakjelasan yang menyebabkan terjadinya perpecahan pendapat itu. Segera setelah semua disetujui, pagi harinya, rombongan yang memutuskan untuk meninggalkan Desa Tirtanan, telah bersiap dengan segala barang bawaan mereka.
Hanya aku, Profesor Abram, Alesya, Annelies, dan Pak Witno—sopir bus kami—, serta Bekti yang terlihat tidak membereskan barang bawaan. Enam orang akan tetap tinggal di Desa Tirtanan. Entah mengapa. Al memberi tahu kalau desas-desus yang disebarkan Des sudah membuat muak dirinya. Dia menjelaskan bahwa Des Masnafi telah menyebarkan kebohongan, kalau orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang tidak mau repot kembali dengan terjebak di dalam hutan. Annelies tampak bersedih, ketika ia harus berpisah dangan temannya, Gita, yang memutuskan untuk ikut dengan rombongan yang pergi.
"Kami memutuskan ... untuk mengirim tim ekspedisi bersama kalian ...," ujar Pak Kusno. Tim ekspedisi dipimpin oleh Pak Trikarliek dan Pak Basuki. Ekspedisi yang menjadi ekspedisi keluar warga Desa Tirtanan adalah yang ke empat, setelah percobaan sebelumnya juga tidak membuahkan hasil.
"Aku tahu, kecil kemungkinan kalian bisa keluar. Namun, kami akan mencoba sekali lagi. Toh ... kalian punya barang-barang yang tentunya bisa membantu, bukan?" ujar Pak Basuki.
"Pak Tri adalah ketua ekspedisi sebelumnya. Dia dan beberapa orang yang akan membantu kalian, sudah hapal dengan beberapa rute yang ada di dalam hutan," jelas Pak Kusno seraya memperkenalkan Pak Tri. Ekspedisi mengirimkan sekitar dua belas orang yang akan 'mengawal' kelompok pergi, untuk keluar, setidaknya sampai menemukan jalan raya atau semacamnya.
"Untuk pengawalan ... bukankah ini cukup besar?" Prof. Abram bertanya seraya melirik barang bawaan tim ekspedisi yang berada di tiga buah tandu, dua kereta dorong, dan dua kuda.
"Kalau kalian berhasil menemukan jalan keluar, bukankah itu adalah suatu pencapaian besar, Pak Abram? Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita." ujar Pak Kusno.
"Apa mereka akan baik-baik saja?" celetuk An yang masih khawatir.
"Tenang ... mereka dibantu orang-orang ahli dan kenal daratan ini ...," sahutku datar.
"Yah ... kuharap mereka tidak buat kehebohan," sambung Bekti.
Pagi itu, sekitar pukul sembilan pagi, rombongan ekspedisi berangkat meninggalkan desa Tirtanan. Sontak desa itu menjadi sedikit lebih sepi daripada biasanya. Kami yang tinggal hanya dapat berharap, mereka dapat menemukan apa yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mencari ini.
****
Sehari setelahnya.
Aku dan Bekti duduk terlongong-longong di teras rumah kami menginap sementara di Tirtanan. Matahari yang terik kadang-kadang terselimuti awan, sehingga rasanya tidak terlalu panas. Angin semilir khas pedesaan juga sesekali melintas.
Sepi.
Tenang.
Burung-burung berkicauan, lalu lalang angsa berbaris, kerbau melenguh yang menarik pedati, dan suara belalang mengerik siang itu melintas di kuping kami berdua.
Al yang kebetulan lewat di depan rumah kami, memandang kami dengan sengit.
"Jadi ... kalian memutuskan untuk tinggal di sini, lalu jadi pengangguran? Sampah kalian!" ejeknya.
"Terjebak di dalam sebuah komunitas tanpa adanya alat dari peradaban masa kini yang memadai, membuat kami serasa kebingungan dengan hidup kami sekarang," celetuk Bekti.
"Bukankah kalian bersikeras untuk tinggal dan lanjutkan praktik kerja nyata kalian!? Kerjakan apa yang harus kalian lakukan, sialan!" protes Al sengit.
"Aku akan memikirkan topiknya sembari menikmati hari-hari awal di desa Tirtanan. Menjauhkan diri dari hegemoni perkotaan rasanya lumayan nyaman," ujarku.
"Tidak usah beralasan klasik, Rendra!" Al menatapku kecut.
Lalu, datanglah Annelies. Ia menyapa kami dengan ramah senyum polosnya. Tipikal bocah. Sepertinya ada kemungkinan ia juga menikmati hari-harinya di desa isolasi ini.
"Wah, sepertinya kalian sedang berkumpul di sini, ya!" ujar Annelies
"Ann, dari mana saja kamu?" tanya Al penasaran. Yang ditanya malah menguap.
"Huah ... bangun tidur ...," jawab An enteng.
"Ba-bangun tidur!?" Al terkejut.
"Ja-jangan begitu ... kamu ini perempuan lho, An! Setidaknya cari hal yang menyenangkan, selagi kita di sini." Rupa-rupanya Al sedikit mengkhawatirkan tingkah An yang khasnya sedikit 'lambat' ini.
"Jadi ... habis ini kaumau melakukan apa?" tanyaku pada Ann. Tidak menjawab, Ann malah duduk di sampingku sembari leyeh-leyeh.
"Aku akan memikirkan topik yang akan jadi laporan PKN-ku nanti."
Bekti tertawa, Al menepuk muka seraya meraupkan tangannya, dan aku tertegun—setelah kami mendengar jawaban Ann.
Satu lagi produk gagal!
"Kau sendiri terlihat santai, gitu? Apa jangan-jangan kamu juga menganggur?" sungut Bekti sembari memperhatikan Al. Al yang sedikit disinggung, langsung tersenyum licik.
"Maaf ya, tapi aku sudah dapat topik, sekaligus subjek pendukung!" ujarnya dengan sok sombong.
"Cepatnya!" sahutku kaget.
"Tadi pagi aku bersama salah satu penduduk desa pergi ke Balai Pos Dagang. Lalu, aku menemukan banyak hal menarik. Akhirnya aku menemukan beberapa penduduk peranakan Belanda yang tinggal di dekat bukit tenggara desa," jelas Al bercerita.
"Balai Pos Dagang? Masih ada yang seperti itu? Kupikir hanya ada di zaman baheula dan koloni Amerika Utara saja," komentarku.
"Jadi ... apa saja yang dijual di sana? Kulit beruang? Bulu terwelu?" celetuk Bekti. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan, kira-kira seumuran Ann, memakai sebuah setelan kebaya berwarna putih krem, dengan kain batik motif Parang sebagai pakaian kemben—kain yang dililit untuk menutupi dada.
"Kenalkan, namanya Ningsih. Penduduk yang tadi mengajakku untuk ke Balai Pos Dagang," ujar Al memperkenalkan perempuan itu.

"Sugeng siang. Asma kulo Ningsih Soekarliek," ujar gadis itu sembari membungkuk sejenak memperkenalkan diri.
"Ah ... Anu ...." Aku gelagapan menjawab.
Dua puluh tahun kamu gagal sebagai peranakan Jawa tulen, Rendra! Demi seluruh leluhur Jawa dan kemahsyuran keturunan Surbakti, mana identitasmu!
"Sugeng siyang. Asma kulo nipun Bekti! Rencang kulo ingkang niki asmanipun Rendra lan Annelies." Untunglah Bekti dengan sigap memperkenalkan diri. Sepertinya aku menangkap ada maksud lain di balik keramahannya yang cekatan. Biasanya dia lebih lemot dari Ann.
"Ah, Ningsih. Beberapa tidak bisa bahasa Jawa. Jadi, pakai bahasa Indonesia saja," kata Al menambahkan. Seketika kata-kata Al serasa menusuk jantungku.
Harga dirimu sebagai Jawa tulen, dipreteli oleh seorang wanita modern, Rendra!
"Ah ... maaf," ujar Ningsih—dengan suara yang cukup pelan dan lembut sehingga seketika bulu kuduk kami berdua seakan berdiri—sembari mengangguk takzim.
"Ningsih memang cenderung pendiam dan malu-malu. Apalagi ketika bertemu dengan pendatang seperti kita," ujar Al.
"Omong-omong, di mana rumahmu?" tanya Bekti, berusaha untuk memberikan simpati lebih, tetapi sepertinya gelagatnya untuk 'mendekati' Ningsih kelihatan.
"Umm ... di seberang jalan di dekat kebun tebu milik warga sini. Di sebelah tenggara. Rumah biasa semi permanen dengan gudang besar di dalamnya," jelas Ningsih seraya menunjuk ke arah tenggara.
"Hmm ... sepertinya kita mendapat pemandu kita. Bisa tunjukkan tempat yang menyenangkan di daerah sini?" Aku yang bangkit dari duduk—sembari sesekali meliukkan tubuh yang pegal—menginterupsi pembicaraan.
"Ah, aku tidak begitu tahu beberapa tempat yang menurut kalian bagus. Namun, dulu aku sering bermain di padang rumput yang ada di Selatan," ujar Ningsih.
"Benarkah? Di mana tepatnya?" tanyaku mengejar.
"Setelah melewati jalan besar di Balai Pos Dagang, pergilah ke Barat Daya dan keluar dari jalan besar. Di sana langsung ada padang rumput ...."
"Ah, terdengar menarik. Bekti, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar?" tanyaku pada Bekti.
"Tentu saja!" jawab Bekti tanpa banyak berpikir.
"Aku juga ikut!" seru Ann. Kami bersiap untuk berangkat ketika Ningsih seperti mencegah kami untuk pergi.
"Ja-jangan ke sana terlalu jauh atau pulang terlalu malam ...," ujarnya sedikit ragu. Sempat terdengar nada kecemasan dari perkataannya.
"Sebaiknya kita harus ke sana dengan pendamping ...," celetuk Al ragu.
"Tenanglah, kita bukan anak kecil yang harus selalu didikte dan diatur untuk tidak berlarian ke mana-mana ...," elakku.
"Huh, terserah." Al hanya pasrah mengikuti kami bertiga pergi. Sempat kami berpamitan dengan Ningsih, yang raut mukanya—demi Tuhan, sepasang mata berkilau dengan rambut sebahu yang tergerai angin dan bibir kecil itu membuatku menggila!—mengatakan kecemasan yang cukup jelas.
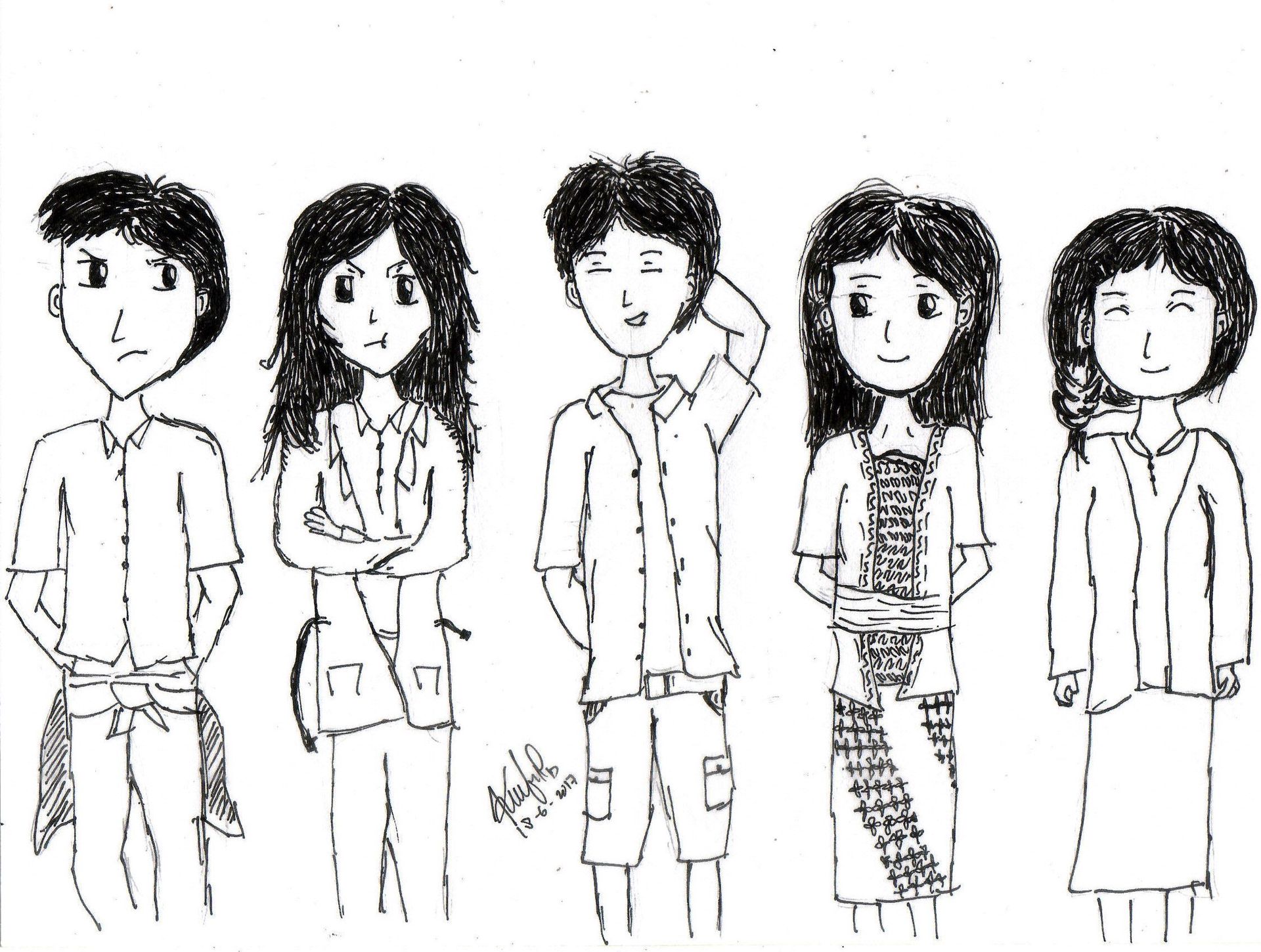
****
"Aku kini mulai mengerti apa yang dikhawatirkan Ningsih. Apa kita harus berjalan lebih jauh lagi? Pos Dagang juga sudah sepi serta banyak lapak yang sudah tutup," ujarku sembari terus berkontribusi dalam menyumbangkan suara ngos-ngosan sedari tadi. Kurang lebih aku memperkirakan kami berempat telah berjalan sejauh empat kilometer. Sempat tadi kita istirahat sebentar ketika aku sampai di Pos Dagang. Nyatanya, Pos Dagang tidak ubahnya seperti pasar biasa yang cukup besar dan terbuka, dengan banyak lapak-lapak berjejeran. Malah, lebih seperti lapak orang jual makanan di penghujung senja waktu bulan puasa meski lapaknya juga lebih besar.
Setelah melalui Pos Dagang, kami melewati jalan besar di mana kiri dan kanan adalah ladang jagung yang terhampar sepanjang jalan yang lurus. Sebenarnya tidak hanya ladang jagung saja. Ada singkong, kentang, dan kebun sayur. Namun, kelelahan kami terbayar sudah ketika kami dapat melihat hamparan tanah hijau yang cukup luas, tidak terlalu jauh dari ladang. Terlihat panorama yang kontras antara ladang dengan tanah hijau yang tampak seperti rerumputan dan ilalang. Kami menemukan titik ujung dari ladang warga, yang langsung bersenggolan dengan tanah berumput.
Padang rumput dan ilalang, sesekali tanah yang membukit terhampar luas di depan mata. Di ujung pandangan, di sebelah barat, barisan pepohonan lebat berjajar rapi. Sesekali pepohonan tersebut terlihat membukit cukup tinggi, lebih jauh jika meluaskan pandangan lebih jauh ke barat. Mungkin, bagi orang-orang yang tinggal di daerah urban, melihat luasnya padang rumput seperti ini adalah hal yang baru dan mengagumkan. Ketika para kaum urban telah keki dengan hutan beton dan lantai aspal, melihat hal sedekat dengan alam ini, rasanya adalah sebuah keajaiban tersendiri.
"Terlepas dari betapa terpencil dan tersembunyinya daerah ini ... demi Tuhan, aku belum pernah melihat hal sehebat ini," ujarku lepas.
"Well, tidak ada salahnya aku tetap tinggal di sini. Jauh lebih baik daripada harus berkutat di kemacetan sore hari selepas kuliah, dengan bising klakson kendaraan bersahutan ...," tambah Al.
"Bah! Bahkan di desa lihatnya hanya sawah dan kebun melulu! Ini pemandangan yang ... sepadan lah dengan jatuh bangun kita kesasar di tempat ini." Bekti melepas kehebohannya. Bahkan ia berteriak-teriak ketika angin sore menerpa dengan cukup kencang. Ketika tidak ada benda yang menahan laju angin, apalagi di tengah tempat terbuka seperti ini, angin berkecepatan biasa pun terasa jadi lebih kuat.
"Hei, apa di sana ada laut?" tanya Al, seraya menunjuk horizon di selatan yang sesekali terlihat memendarkan berkas cahaya kelap-kelip.
"Dilihat dari kelap-kelip yang terpantul dan kontur tanah yang semakin mendatar. Kemungkinan besar iya. Sayang sekali Bethlehem tidak ada di sini," ujarku.
"Oi, Rendra," panggil Al.
"Hmm?"
"Apa kau tidak menyesali ketika kaupilih untuk tinggal di sini? Menukar segala kemewahan hidup di luar sana?" tanya Al. Bekti dan Annelies sudah berlari-larian sendiri. Bekti berguling-guling di tanah, sementara Ann mengejar-ngejar keluarga kelinci yang kebetulan muncul dari balik lubang-lubang di padang rumput.
"Jujur ... pasti Ibu akan cemas ketika menyadari anaknya hilang. Semoga saja media di luar sana tidak keburu jadi keran bocor dulu. Ah, terlepas dari segala ketertinggalan ini ...."
"Woy ...," gerutu Al.
"Aku menikmati ini," lanjutku. Kami berempat sudah berpetualang menuju ke tengah padang rumput. Cahaya surya sore hari mulai melukis serat-serat jingga di atas langit. Hanya ada suara embusan angin, burung berkicau—aku dengar ada elang berkaok—yang terbang, sesekali suara kerikan belalang.
"Hah ... tempat yang indah untuk dua hal," ujar Al. Aku menoleh memandangnya yang sedang menatap lurus ke arah cakrawala selatan.
"Apa?"
"Bulan madu dan mengasingkan diri dari hegemoni peradaban."
"Wah, aku pilih yang kedua. Aku bertaruh mantan-mantanmu akan cepat bosan bila harus bertapa di sini, Alesya," ledekku.
"Oi! Apa aku terlihat seperti perempuan yang berusaha mendekati jomblo mengenaskan sepertimu? Juga, memanggilku dengan nama penuh terdengar menggelikan ketika kamu yang bilang!"
"Heh! Aku tidak akan terjebak tipuan wanita sepertimu, dasar wanita aristokrat berkedok postmodernisme!" ejekku. Alesya tertawa. Baru kali ini aku mendengar dan melihat dia tertawa lepas.
"Haha ... jangan gengsi dulu, pria ansos!"
"Oi! Ayo ke sini!" teriak Ann seraya melambai-lambaikan tangannya ke arah kami. Karena kami berdua tidak segera ke sana, Ann dan Bekti-lah yang akhirnya mendatangi kami. Aku dan Alesya hanya tertegun melihat sebuah berkas titik-titik, kemudian membesar membentuk bentuk yang lebih jelas dari cakrawala di belakang mereka.
"Hoi, Rendra, jangan kebanyakan bengong," sahut Bekti. Aku masih tertegun melihat sesuatu dari kejauhan yang lama-lama ... semakin mendekat.
"Umm ... apa itu?" tanyaku sembari menunjuk arah di antara Bekti dan Ann. Mereka berdua menoleh ke belakang, menyusuri arah telunjukku.
Bekti memicingkan mata, lalu bergumam tidak jelas.
"Hmm ... sesuatu? Ada yang mendekat?"
"Kuda?" celetuk Ann.
"Kuda? Ah ... sepertinya iya," ujarku sembari ikut memicingkan mata. Sesuatu itu tampak makin jelas. Memang tampak seperti kuda yang sedang menuju ke arah kami. Lebih tepatnya segerombolan kuda, karena aku tidak hanya melihat satu kuda saja.
"Wah, tempat ini keren ...."
"Bekti, diam sebentar," tukasku. Kami berempat memperhatikan gerombolan kuda—atau apalah itu—yang menuju ke arah kami. Makin lama gerombolan—yang ternyata benar-benar kuda—itu makin mendekat. Juga, ada sosok orang yang seperti menunggangi kuda-kuda tersebut.
Jarak Satu kilometer.
Satu, tiga ... dua belas ... empat belas. Empat belas kuda dan orang yang menungganginya. Mereka berpakaian seperti sarung yang dililitkan ke tubuh mereka.
Jarak 750 meter.
Mereka makin mendekat. Oh! Jumlah mereka ternyata lebih dari empat belas orang. Sepertinya ada penduduk—mungkin para koboi—yang ingin memperkenalkan diri. Kami berempat masih berdiri melihat mereka dengan tercengang. Suara gemuruh dari derap kuda yang makin lama makin terdengar jelas.
Jarak 500 meter.
Ah ... mereka terlihat cepat dan sepertinya tidak akan mengerem. Pakaian mereka dapat dideskripsikan sebagai para penunggang kuda berselimut sarung dan terlilit menutupi kepala dan muka mereka. Bagian wajah yang tidak tertutup hanya bagian sekitar mata saja.
Jarak 150 meter.
"An ...." Aku berkata lepas, tidak hendak memanggil Annelies, karena yang kupanggil juga tidak menoleh.
Aku melihat jelas apa yang mereka bawa sambil mereka tunggangi kuda-kuda mereka.
"... cuuk!!"
Senjata.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top