12. Eksodus Masa Lalu
Kami kembali menuju desa dengan perasaan yang masih mengganjal. Terlepas dari rombongan kelompok yang meninggalkan Tirtanan dapat kembali dengan selamat, tetapi dua hal masih membuat kami—kelompok KKN Integrasi—menjadi sedikit gundah gulana.
Pertama, kami belum menemukan dua gadis dari kelompok kami. Auriga dan Gita. Mereka menghilang ketika kekacauan yang diakibatkan kabut tebal turun secara tiba-tiba di daerah hutan. Berarti, pencarianku dan empat orang lainnya tadi belum dapat dikatakan sukses. Entah nyawa mereka selamat atau tidak, itu juga yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Para dosen, Annelies yang teman dekat, hingga Adrian sebagai ketua kelompok.
Kedua, adalah sebuah pernyataan mengejutkan dari seorang pria 35-tahunan berdarah asli Jepang bernama Yamaguchi Maeda. Dia tiba-tiba saja datang padaku, lalu menanyakan putrinya yang hilang di hutan belantara Tirtanan lima tahun lalu, Yamaguchi Kaaya. Namun, sebelum kami mengupas lebih jauh tentang peristiwa hilangnya putri keluarga Yamaguchi, kami membutuhkan satu hal. Penjelasan mengenai generasi Jepang yang beranak-pinak di Tirtanan.
Perjalanan pun dimulai kembali. Segera setelah rombongan kembali ke desa, beberapa orang perangkat desa, semua dosen pembimbing KKN, aku dan beberapa orang lainnya ikut dengan Yamaguchi-san—begitulah aku menyebutnya kemudian—menuju ke tempat tinggalnya. Aku agak terkejut, ketika mengetahui sebuah peradaban lain tumbuh di daerah antah-berantah ini. Lebih tepat itu disebut sebagai "Kampung Jepang", sebagaimana Kampung Pecinan di beberapa kota besar.
Kurang lebih aku menemui sekitar 42 struktur bangunan seperti rumah. Perbandingan atap jerami yang dipadatkan dengan atap genteng, sekitar tiga banding satu. Terlihat jauh lebih sederhana daripada rumah-rumah penduduk Tirtanan yang kebanyakan memakai genteng. Kebanyakan rumah yang ada di kawasan kampung Jepang lebih terlihat besar daripada bangunan rumah di desa Tirtanan. Tidak seperti dibuat besar-besar, melainkan ada penyatuan dari dua rumah, yang beberapa terlihat mencolok dari struktur bangunannya. Di mana ada beberapa lorong panjang seperti menghubungkan dua rumah.
Aku kurang mengerti tentang adat di sini, tetapi Yamaguchi-san menjelaskan kalau memang seperti itu budaya yang dibawa. Kebanyakan pasangan yang telah menikah, lebih memilih tinggal bersama keluarganya. Pun bila memungkinkan, kedua keluarga pasangan dijadikan tinggal serumah atau tinggal bersebelahan. Biasanya antara 'rumah orang tua' dengan bagian 'rumah keluarga baru' dipisahkan dengan lorong atau semacamnya.
Pak Baek sempat menjelaskan kalau ada tujuh belas bagian bangunan rumah yang menjadi khas bagi rumah-rumah bergaya Jepang, terutama yang tradisional. Beberapa di antaranya adalah shoji—dinding yang terbuat dari panel kayu dan kertas transparan, engawa—koridor luar yang mengelilingi rumah, tatami—lantai yang terbuat dari jerami, dan wagoya—pertemuan dua kisi-kisi kayu rumah, di mana notabene orang Jepang tidak memerlukan paku dalam membangun rumah. Hampir semuanya terbuat dari kayu, kecuali atap dan pondasi yang menggunakan tanah liat atau batu.
Kediaman Yamaguchi-san cukup besar dengan ruang tamu yang seluas setengah dari pendopo Desa Tirtanan. Ini pertama kalinya aku duduk di atas tatami, yang asli. Setelah disambut oleh keluarga—dengan panganan yang bahkan aku sendiri belum pernah tahu itu makanan apa—Yamaguchi-san mulai bercerita. Mula-mula ia bercerita tentang penduduk di desa ini yang cukup damai dalam tahun-tahun terakhir. Penduduknya makmur, damai dengan semua orang, terikat dengan kebiasaan tanah air mereka.
Generasi mereka datang jauh sebelum mereka dilahirkan. Generasi pertama membangun tempat ini penuh dengan perjuangan, bahkan tidak jalan pertumpahan darah menjadi jalan demi mempertahankan eksistensi. Entah berapa generasi yang telah dilahirkan. Yamaguchi-san dilahirkan sekitar 1960-an, Kalender Masehi. Generasi sebelumnya sepertinya telah membuat kedamaian pihak mereka dengan pihak luar. Jepang Tirtanan agaknya menjadi julukan mereka selanjutnya.
"Keturunan kami sudah memiliki banyak generasi di sini, sejak dahulu kala," ujar Yamaguchi-san di dalam ceritanya.
"Kapan?" tanyaku sebagai salah satu 'tamu' di sana.
"Sejak Shimabara tumbang oleh Shogun ...," jawab Yamaguchi-san dengan sedikit berat, seolah-olah itu masa lalu yang tidak ingin diungkit lagi.
"Shimabara ... Shogun? Eh, 1638!?" celetukku setelah menemukan pencerahan.
"He!? Mustahil!?" Bekti yang kaget dengan tahun yang kusebutkan langsung ikut bereaksi.
"Pasca-pertempuran di Shimabara dan Shiiro Amakusa ditangkap, Shogun mulai melancarkan perburuan pada kami, warga desa yang memberontak," ujar Yamaguchi-san melanjutkan cerita.
"Eh, Pertempuran?" tanya Bekti seraya melirik kepadaku, berharap aku memberikan jawaban seputar 'Sejarah Jepang'. Namun, malah keluar jawaban dari mulut seorang Bethlehem.
"Pemberontakan Shimabara. Beberapa orang yang memeluk Katholik mendapatkan represivitas dari Shogun Tokugawa, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Namun, pemberontakan itu berhasil dipatahkan oleh Keshogunan Tokugawa."
"Katholik?" celetuk Bekti mengerutkan kening.
Bethlehem mengangguk, seraya berkata, "Iya. Para misionaris dari Portugis yang menyebarkannya. Mereka mendapatkan represivitas dari Shogun atau dari orang asing lain, seperti Belanda yang Protestan."
"Kalau begitu, anda Katholik?" tanyaku seraya memandang ke arah Yamaguchi-san.
Yamaguchi-san mengangguk, lalu menjawab, "I-iya. Mayoritas dari kami Katholik, tetapi beberapa keluarga di sini ada juga yang memeluk kepercayaan lama mereka,Shinto."
"Menarik ... kenapa di Shimabara pecah pemberontakan, tetapi di sini baik-baik saja?" ujarku penasaran. Yamaguchi-san mendehem seolah ia ingin menegaskan apa yang selanjutnya akan ia katakan.
"Kami sudah muak dengan perang konyol atas nama agama. Pada akhirnya, para pengikutlah yang jadi bola sepak para Shogun dan Daimyo. Agama yang mulanya dianggap suci, malah digunakan kesuciannya untuk mengejar kepentingan duniawi. Bukankah itu suatu yang hampir selalu menimbulkan pertumpahan darah. Di mana pun? Moyang kami berulang kali bercerita kalau mereka bahkan kehilangan bayi mereka akibat perang konyol itu," ujar Yamaguchi-san.
"Wah ... andai saja kedamaian seperti ini terjadi di Negeri ini sekarang ...," celetuk Bekti sembari mengelus dagu. Percakapan pun lama-lama bercerita tentang keluarga Yamaguchi-san, hingga pada akhirnya, ia menceritakan tentang Kaaya.
"Lalu, putri Anda? Bagaimana?" Kini giliran Profesor Abram yang menanyakan.
"Kejadiannya berlangsung lima tahun lalu. Waktu itu, Kaaya masih berusia sekitar 5 tahunan. Dia sedang bermain di dekat hutan. Lalu setelah malam menjelang, dia tidak kunjung pulang," jelas Yamaguchi-san.
"Lalu?" kejar Prof. Abram.
"Seisi kampung, bahkan dengan bantuan warga dari Kusno-san, telah berusaha mencarinya, terlebih kami dari seluruh Klan Yamaguchi. Namun, hasilnya nihil. Orang-orang bersarung yang bermukim di padang rumput itu berkata, putriku telah melintas jauh menuju Hutan Keputusasaan," lanjut Yamaguchi-san menjelaskan.
"Hutan Keputusasaan?" Aku—hampir diikuti dengan seluruh tamu—terkejut sembari mengulangi kata terakhir Yamaguchi-san.
"Hutan di mana berbagai roh, baik jahat mau pun baik tinggal. Sangat sulit kemungkinan untuk kembali dari sana, kecuali satu hal." Tiba-tiba suara dari luar—karena waktu itu pintu shoji dibiarkan terbuka untuk para tamu yang membeludak—terdengar. Nai dan Tetua Adat Nenek Naode.
"Ah, Nai! Nenek Tetua!" panggilku sembari melambaikan tangan ke arah mereka.
"Satu hal?" tanya Yamaguchi-san dan Prof. Abram berbarengan.
"Hari ini tidak hujan. Kalau dari malam ini sampai malam besok tidak hujan, juga awan tidak terus-menerus menghalangi matahari, ada kemungkinan mereka dapat ditemukan," ujar Nai, setelah mendapat bisikan dari Nenek Tetua.
"Benarkah? Benarkah itu!?" Sontak, Yamaguchi-san berdiri dari duduknya.
Nai dan Nenek Tetua mengangguk.
*****
Terhitung hari ke-enam semenjak kami berangkat menuju tanah antah-berantah ini. Lelah yang masih memuncak, memaksa ekspedisi penyelamatan menjadi sedikit lebih lambat. Tidak, aku dan teman-teman sudah bertekad untuk membawa kembali Auriga dan Gita selamat. Pun juga tekad itu telah ditunjukkan oleh Yamaguchi-san, dengan mengerahkan hampir satu klan untuk mencari putrinya, Kaaya Yamaguchi, yang hilang lima tahun lalu di Hutan Keputusasaan.
Seperti yang diharapkan oleh semua orang. Pagi hari yang cerah, tidak ada hujan, awan bergerak menipis tertiup angin secara perlahan. Langit fajar tanpa ada gumpalan awan yang bergerombol di atasnya. Cuaca hari ini cerah seperti yang disyaratkan oleh Nenek Tetua. Semalam juga tidak turun hujan. Matahari pagi bangkit menuju langit tanpa ada halangan dari awan.
Kami berangkat dengan rombongan besar. Rombongan berisi sekitar sepuluh hingga lima belas orang, dengan peralatan ekspedisi seadanya. Seluruh rombongan KKN-Integrasi juga ikut dalam ekspedisi pencarian ini. Terlepas dari kemarin malam, mereka merasakan dahsyatnya teror mengenai hutan yang tidak dapat tertembus, setidaknya mereka masih bisa menemukan kolega mereka di dalam hutan yang ... masih dapat dijamah.
Kemungkinan untuk bertemu binatang buas juga tinggi, tentu saja senjata sudah dipersiapkan. Entah, kenapa aku terpikir tentang warga Tirtanan yang selalu bergantung pada senjata, tiap kali melakukan ekspedisi. Aku hanya menemui ular besar sewaktu kami terjebak dulu. Tidak ada singa, tidak ada macan, tidak ada beruang, atau tidak ada serigala yang berkeliaran di hutan ini. Aku lebih mengkhawatirkan, bahwa apa yang selama ini aku dan orang-orang lain jelajahi, masih belum apa-apanya. Tentu saja, warga desa sudah tahu seluk-beluk tempat ini. Namun, akhirnya pengetahuan yang terbatas itu membuat mereka harus terjebak di sini. Mungkinkah ada sesuatu yang lain, lebih berbahaya dari binatang buas? Entahlah, aku tidak tahu dan tidak mau tahu dahulu.
"Tapi ... kenapa harus ada syarat itu?" Sempat Bekti berceletuk penasaran mengenai syarat yang diberikan oleh Nenek Tetua.
Aku mengelus dagu, seraya berkata, "Hmm ... aku menduga, jika hujan turun di daerah ini, itu akan memperlambat jalannya pencarian. Selain itu, ini daerah dengan tingkat kelembapan tinggi. Sering terjadi pembentukan kabut tebal di tengah malam, di tengah-tengah hutan seperti di sana. Itu pun jika kabut hari ini sudah hilang."
"Lalu, apa kabut yang ada di hutan itu tidak bisa hilang?" Septian mengejar pertanyaan.
"Entahlah. Mestinya saat kemarau, jumlah pembentukan fenomena kabut akan jauh berkurang, karena kelembapan rendah. Namun, sekali lagi. Tempat ini aneh. Banyak terjadi anomali di tempat ini," ujarku melanjutkan.
"Begitu. Cukup cerdik juga, seorang Rendra ini," gurau Adrian.
"Jangan membual, Adrian," timpalku.
Aku sampai pada akhir cerita bagian ini, di mana pada akhirnya, setelah tiga jam ekspedisi melakukan pencarian ke Hutan Keputusasaan yang masih berkabut—walau tidak terlalu parah—kami menemukan Gita dan Auriga. Mereka selamat, juga yang lebih mengejutkannya lagi, mereka bertahan hidup di Hutan Keputusasaan selama kurang lebih dua belas jam, berkat bantuan seorang gadis kecil yang kira-kira berusia sepuluh tahunan.
Itu adalah gadis yang aku dan Annelies temui sewaktu tersesat di hutan, kemarin malam. Ternyata memang benar-benar seorang anak manusia. Setelah diamati baik-baik, ciri-ciri yang sama dengan apa yang diutarakan Yamaguchi-san, gadis itu adalah Kaaya, yang menghilang lima tahun lalu di hutan. Kiranya, aku dapat menggambarkan tangis bahagia Yamaguchi-san ketika menemukan putri kecilnya yang sempat menghilang. Sebuah keluarga yang kembali lengkap, hadir di orang-orang keturunan pelarian. Pelarian dari kebrutalan penguasa zaman dahulu kala.
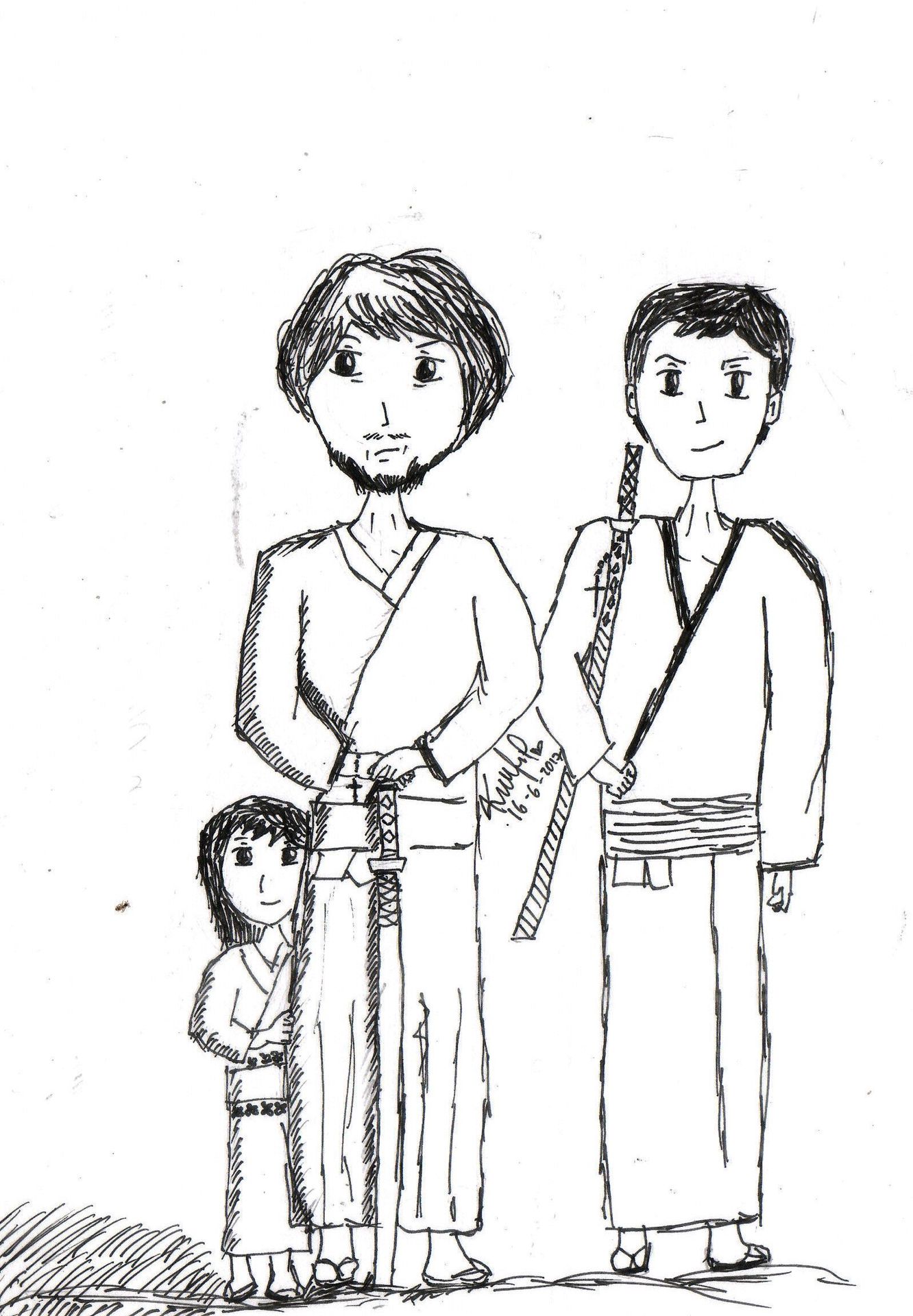
Setidaknya enam hari aku di Tirtanan, sudah banyak hal yang membuatku dapat bercerita sebanyak ini. Namun, ini masih belum apa-apanya. Aku yakinkan hal itu. Aku melirik Nenek Tetua, beliau sempat terlihat cemas akan sesuatu sebelum akhirnya ikut bersuka cita atas bertemunya kembali Kaaya dengan keluarganya. Hal lain akan terjadi.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top