1. Kautahu, Pekenalan Tidak Selalu Menyenangkan
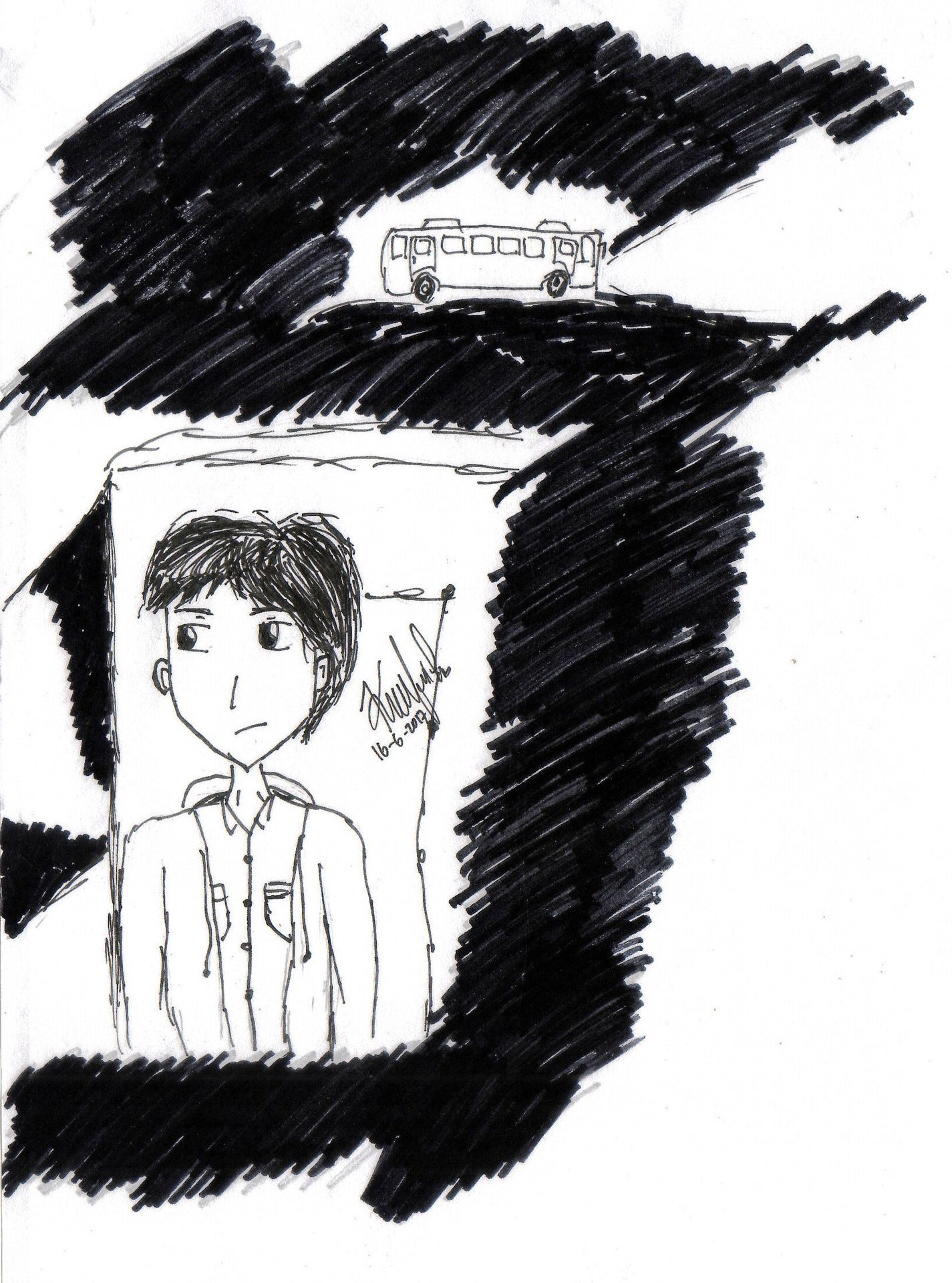
Semua dimulai ketika cakrawala senja sudah memudar. Malam pun mulai menampakkan kuasanya, ketika bus kami melaju dengan kecepatan sedang melewati daerah Bondowoso. Aku mencoba membaur dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Jangan salah sangka, aku gunakan ini sebagai sikap oportunis. Siapa tahu mereka berguna sewaktu kerja nyata nanti. Relasi pertemanan bisa dibentuk dari hal seperti ini, 'kan? Tidak salah.
"Jadi ... bagaimana denganmu, Rendra? Apa kau sudah kenal dengan teman-temanmu di bus ini? Mereka akan jadi orang yang dekat saat praktik lapangan nanti, lho!" celetuk Adrian, mahasiswa Teknik Elektro yang jadi ketua rombongan KKN kelompok tiga. Yah, ketika dia memperkenalkan diri, bisa dibilang dia cukup ahli dalam seni berbicara. Dia adalah ketua BEM di fakultasnya. Agak kaget saja, ketika dia ikut KKN-Integrasi. Orang-orang semacamnya seharusnya cukup pintar dalam memanajemen kegiatan, kecuali dia memang sedikit berbenturan dengan akademiknya.
"Beberapa orang saja. Huh, cara bicaramu seperti ibu-ibu yang mengingatkan anaknya di hari pertamanya sekolah ...," timpalku. Adrian tertawa renyah.
"Kau ini terlalu berlebihan, Rendra. Yah, aku bertanggung jawab atas kelompok ini dan orang-orangnya. Aku akan sangat sedih bila kau tidak bisa mengikuti KKN-Integrasi ini dengan gembira ...," ungkapnya seraya memasang senyum terbaik untuk meninggalkan kesan, seolah dia adalah ketua ramah yang siap bertanggungjawab.
"Aku akan lebih sedih, bila kau terlalu ramah daripada ibuku," candaku. Adrian kembali tertawa.
"Wah ... itu menarik, dong. Dengan begitu, kita bisa jadi teman akrab," ujarnya sembari menepuk-nepuk—mengelus-elus lebih tepatnya—bahuku.
"Ih, jijiik!" sahutku. Adrian kembali hanya tertawa pelan, lalu menuju ke bangku lain. Sepertinya ia adalah orang yang ingin sekali kenal—atau dikenal—orang lain yang memiliki kepentingan yang sama dengannya. Dalam hal ini, kelompok kuliah kerja nyata. Yah, sungguh niat baik dari Pak Kepala. Sayangnya, energiku pasti tidak akan cukup, bila menemui satu per satu orang di bus ini, lalu berbincang sembari mengakrabkan diri. Seringkali aku heran sendiri, mengapa ada orang yang begitu senang mengobrol—berekspresi riang gembira—dengan orang yang baru dikenalnya 73 menit yang lalu?
"Sepertinya ia ingin terkenal ...," bisik Bekti padaku seraya melirik Adrian.
"Yah ... orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ingin dapat perhatian lebih," celetukku.
"Namun, untuk apa? Hei, kaubisa menebak Adrian itu orang yang seperti apa?" Bekti menggaruk kepalanya. Aku menghela napas panjang. Aku sudah sedikit sakit hati mendengar pertanyaan sejenis.
Gawat, dia sama seperti orang awam dimakan psikologi pasaran!?
"Aku tidak bisa yang seperti itu. Bahkan anak SD saja tahu kalau dia lagi cari perhatian. Yah, mungkin supaya dia terkenal lah, atau ingin punya banyak relasi lah!?" bisikku sengit.
"Yah ... mana aku tahu," sungut Bekti. Kemudian, ia melemparkan badannya ke arah kursinya dan memandang ke luar jendela. Aku tidak begitu mengerti tentang orang kebanyakan. Mungkin aku cukup dekat dengan Bekti beberapa jam yang lalu, tetapi kenapa hal itu terasa ... sedikit membuat telinga terasa panas. Mengapa orang-orang psikologi masih dianggap seperti penyihir terbang? Rasanya aku ingin mengambil mikrofon yang ada di dekat sopir, sembari berteriak, "Aku bukan penyihir terbang!"
Yah, kita kesampingkan masalah penyihir terbang. Aku sekarang malah tertarik dengan orang yang duduk di bangku seberangku dan Bekti. Tidak, posisinya sekarang agak menyilang, satu bangku di depan tempat duduk kami. Dari tadi dia memperhatikan sebuah benda yang mirip ponsel, tetapi lebih besar dan tebal. Juga, benda itu punya antena yang bisa di panjang-pendekkan. Aku mengira itu radio, tetapi benda itu tidak memunculkan suara. Kuhampiri tempat duduknya.
"Anu ... itu apa?" tanyaku penasaran kepada laki-laki yang asyik dengan mainannya.
"Oh, ini? Ini GPS militer." Lelaki itu menoleh lalu menjelaskan dengan singkat benda yang dibawanya.
"GPS militer? Bagaimana kaubisa dapat barang sehebat itu?" Aku sedikit tercengang dengan benda sakti itu.
"Oh, ini? Aku meminjamnya dari cowok tambun berjenggot tebal yang ada di sana. Yah ... sepertinya kita memang benar-benar masuk pedalaman ...," ujar lelaki itu seraya kembali memperhatikan layar GPS. Aku menyusuri arah tunjukan jari lelaki itu, mengarah ke tiga bangku di depan, di mana cowok yang disebut sedang berbincang dengan rekan yang ada di sebelahnya.
"Uh-oh, apakah kita benar-benar akan masuk pedalaman?" tanya lelaki yang memegang GPS tadi.
"Umm ..., kurasa iya ...."
"Apa kau pernah ke pedalaman sebelumnya? Apa di sana ada hewan buas? Apa di sana ada makhuk halus!?" Aku diberondong beberapa pertanyaan panik dari si lelaki. Aku sedikit gelagapan menjawabnya.
"Ah, soal itu ... aku memang pernah ke beberapa desa pelosok, tetapi tidak sampai ada hal-hal yang seperti itu ...," jelasku, yang langsung disambut oleh kicauan si lelaki.
"Ya! Iya! Semoga tidak ada hal-hal yang seperti itu!?"
"Eh ... kupikir tidak sampai segitunya ...." Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal.
"Oh, namamu Narendra Su ...,"
"Surbakti," pintaku.
"Aha, iya! Narendra Surbakti. Panggil saja namaku dengan Wili, salam kenal!" ujar si Lelaki GPS memperkenalkan diri.
"Ah, panggil saja dengan nama Rendra, tetapi ... hampir semua orang tadi memanggilmu Beth?" ujarku penasaran. Si Wili—alias Beth—langsung memasang muka bebek.
"Arrgh! Kenapa semua orang suka memanggil nama depanku? Bahkan tidak ada yang pernah memanggilku Wili. Ibuku juga! Demi Bapa yang Mulia, mengapa Engkau jadikan namaku ambigu!?" racau si Wili—alias Beth—sembari mengusap muka. Satu lagi produk aneh KKN-Integrasi kelompok tiga.
"Eh ... namamu ...," geruhku.
"Bethlehem Wiliardo ...," ucap si Will—alias Beth—seraya tertunduk lesu.
"Baik, aku akan panggil kamu Beth," pintaku.
"Lho! Dipanggil juga! Demi Bapa Yesus ...." Beth—mulai sekarang kupanggil dia Beth—langsung menepuk jidat.
"Baiklah, Beth. Sedari tadi aku melihatmu sedang membuka banyak peta. Apa kausuka dengan peta?" tanyaku sembari menuding beberapa tumpukan peta di pangkuannya.
"Ah, bisa dibilang begitu. Aku mahasiswa Kartografi, Fakultas Geografi dan Geofisika. Aku mencintai peta semenjak sekolah dasar dan peta adalah hal yang membuatku senang!" Bethlehem langsung semringah.
"Huh, Kartografi?" Aku mengerutkan kening.
"Iya ... program studi dengan mahasiswa yang bisa dihitung semua jempol manusia. Kami masih dalam satu Jurusan dengan Geografi ...." Beth kembali menunduk lesu.
"Berarti kaukenali daerah yang kita sedang lalui?" tanyaku. Beth mengangguk.
"Iya. Terkadang beberapa daerah pelosok tidak dapat terjangkau GPS biasa. Biasanya hanya digambarkan daerah dengan warna sama seperti warna tanah atau wilayah. Karena itu, aku meminjam GPS militer kepunyaan Ronny. Lebih akurat," jelas Beth.
"Tunggu ... jangan-jangan kauikut kelompok ini ...," dugaku sembari memegang dagu.
"Iya, menggambar peta, apa lagi?" timpal Beth.
"Itu aku juga tahu! Maksudku, apa kau akan menggambar peta daerah yang ada di sana nanti?" tanyaku.
"Untuk tujuannya, iya. Ketika sekarang kau lebih mengandalkan satelit untuk merekam segalanya dari atas. Yang manual membutuhkan perjalanan menyusuri wilayah yang akan dipetakan terasa sukar, serta butuh waktu," jelas Beth. Cukup merepotkan bagi seorang kartografer manual dalam menjalankan pekerjaannya. Yang jelas, berjalan naik-turun gunung atau menyusuri pantai akan sangat capek.
Aku sangat menikmati pembicaraan hingga aku hampir tidak sadar, bahwa sedari tadi ada yang memperhatikanku. Aku melirik di bangku yang ada di belakang Bethlehem. Seorang perempuan tampak menatapku. Lebih tepatnya, kami bertatap muka sekarang. Lantas, perempuan itu hanya memberikan senyum lebar yang saking lebarnya, kedua mata perempuan itu malah seperti merem. Aku menghampiri perempuan yang menatapku tadi. Entah apa yang akan kukatakan untuk memulai percakapan, tetapi dengan gobloknya, aku malah kembali ke tempat dudukku.
*****
Hari telah berangkat di permulaan malam, jalanan mulai gelap. Aktivitas yang ada di dalam bus ini jauh lebih berkurang. Kebanyakan penumpangnya tidur untuk menghemat energi, setelah tadi heboh dengan berbagai percakapan yang tiada habisnya. Aku sendiri tidak bisa tidur dengan cepat kalau berada di kendaraan seperti ini. Namun, baru beberapa saat aku menyusun posisiku dengan enaknya di tempat duduk sembari menatap ke arah jendela, tiba-tiba bahuku ditowel oleh Bekti.
Aku menoleh, "Apa, Bek?"
"Kamu dipanggil ... eh, siapa namamu tadi? Hap ... aish! Kau dipanggil si Hap-Hap?" ujarnya seraya menunjuk perempuan di bangku seberang yang tadi menatapku. Ia melambaikan tangannya padaku. Perempuan yang ada di sebelahnya terlihat menahan tawa. Apakah namanya memang 'Hap-Hap'? Aku sangsi dengan kata-kata Bekti yang sudah kukenal beberapa jam yang lalu sebagai seorang pelawak ulung. Aku meminta Bekti untuk berganti tempat duduk, agar aku dapat berbicara dengan perempuan—yang dipanggil Hap-Hap—tadi dengan lebih jelas dan nyaman.
"Uh ... hai," ucapku singkat sembari menggaruk kepalaku yang tidak gatal.
"Hai ...," ucap perempuan itu setengah berbisik. Aku hendak menjawabnya, tetapi dia kembali mengucapkan 'hai' sebanyak dua kali. Detik itu aku sedikit curiga, jangan-jangan perempuan ini juga punya bakat lawak.
"Hai-nya cukup sekali saja ...," sungutku. Lantas, dia tertawa pelan.
"Namaku Annelies!"
"Aku Rendra. Salam kenal, Annelies," jawabku sedikit masygul.
"Nama Annelies kepanjangan, panggil saja dengan sebutan Ann!" ujarnya.
"Ah ... kurasa itu kependekkan," komentarku. Satu detik kemudian aku menyesal telah bertemu dengan Septian Bekti. Mendadak sesuatu yang gawat terlintas di pikiranku. Kebegoan lawakannya menular kepadaku. Annelies hanya tertawa meresponku.
"Kuharap, kita bisa bekerja sama saat KKN! Mohon bantuannya!" ujar Annelies riang. Tampaknya dia adalah orang yang ramah. Alangkah bahagianya aku dapat menemukan sebuah relasi sosial yang begitu friendly denganku. Bekti, Adrian, Bethlehem, dan Annelies. Kurasa aku tidak akan dapat masalah yang macam-macam saat kerja nyata. Aku sendiri juga belum terlalu kenal dengan anggota kelompok kerja nyata yang lain.
Situasi di bus saat ini jauh lebih tenang daripada saat sore hari tadi. Air Conditioner bus dinyalakan, entah kenapa hawanya membuatku malah tambah kedinginan. Saat aku melirik ke jendela, rupanya sedang hujan. Jalanan semakin lama semakin sepi dari lalu-lalang kendaraan. Itu berarti kami sudah melewati tapal batas peradaban lalu-lintas padat, alias masuk ke daerah pedesaan. Di sepanjang kanan-kiri jalan hanya terdapat barisan sawah, kebun, rumah warga yang berjarak sangat renggang, barisan pohon bambu, dan sebagainya. Deru mesin bus terdengar cukup jelas, saking tenangnya bus ini. Sesekali kasak-kusuk dari beberapa penumpang yang masih melek juga sesekali terdengar.
Bekti masih sibuk bermain dengan ponselnya. Entah mengapa aku menyesal bertukar tempat duduk dengan dia. Posisi enak yang sangat dijanjikan oleh semua kendaraan umum adalah di dekat jendela. Dengan enaknya Bekti menikmatinya, bersender di tepi jendela bus sambil mengutak-atik ponselnya. Sepertinya ia sedang bermain game dan tampaknya ia tidak mau diganggu.
"Hei ... hei ... hei." Suara di seberang bangku memanggilku pelan. Sikuku ditowel-towel. Aku melirik, mendapati Annelies memanggilku. Perempuan dengan rambut sebahu yang terlihat melebar seperti singa serta dikuncir kuda—tidak, lebih tepatnya dkepang dan diikal satu sisi—yang baru kukenal beberapa saat yang lalu. Sialnya, aku tidak tahu harus memulai pembicaraan yang seperti apa! Aku jarang sebagai orang memulai pembicaraan dalam suatu percakapan. Pun memulai, aku akan malu sendiri telah memulai topik pembicaraan. Terlebih lagi yang kuajak bicara sekarang perempuan. Aku tidak tahu apakah status jomblo ngenes dua puluh satu tahun ini adalah kutukan yang tidak pernah dicabut? Aku harus mencoba berkenalan!
"Hmm ... i-iya?" tanyaku sedikit canggung.
"Kudengar kamu anak psikologi, ya?" tanya Annelies balik. Prasangka langsung bereaksi dengan cepat. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan hal yang seperti ini, terkadang akan berujung dengan pertanyaan awam yang cenderung ... membuat setiap akademisi psikologi menangis dan menjerit dalam hati.
"Ah ... iya," jawabku ragu.
"Pasti capek ya, berkutat dengan alat tes dan wawancara ...," kata Annelies. Aku terkesima, saking terkesimanya, aku langsung menyalami Annelies kuat-kuat sembari mengangguk-angguk takzim.
Akhirnya ada yang bisa diajak omong psikologi dengan benar!
"Huh, he? Kenapa? Ada apa?" tanya Annelies bingung.
"Ah, tidak, Ann! Aku hanya senang bahwa kau tidak seperti kebanyakan orang ...," ucapku lepas.
"Huh? Aku mengetahuinya dari Bekti, katanya anak psikologi itu selalu berkutat dengan mengamati orang, mengetes orang, mewawancara orang ...." Aku menoleh sengit ke arah bekti yang rupanya mencuri dengan pembicaraan. Ia menahan tawa.
Sialan, kau mencuri start, Bek!
"Hah ... begitulah. Namun, tidak selalu seperti itu. Kau sendiri, anak mana?" tanyaku berusaha mengalihkan topik pembicaraan.
"Oh, anak Kesehatan Masyarakat, seperti temanku yang di sebelah ini," ujar Annelies.
"Wah ... enaknya punya teman satu jurusan ...," gerauku.
Tiba-tiba bus yang kami tumpangi bergoyang cukup hebat. Sepertinya jalanan yang kami lalui sudah mulai bergelombang tidak beraturan. Menandakan, kami sudah masuk pedalaman desa. Namun, sejurus kemudian Bethlehem bangkit dari duduknya. Wajahnya terlihat panik dan pucat, ia bergegas menuju ke depan, sepertinya ke arah sopir.
"Bethlehem, kamu kenapa, mabuk?" tanyaku.
"Bu-bukan! Kita harus ke Pak sopir!" cicitnya dengan gigi bergemeletuk. Aku merasakan ada yang tidak enak dari perkataan Bethlehem. Ia bergegas menuju ke depan, tetapi ia terhuyung-huyung karena jalan yang dilalui bus bergelombang parah.
"Beth, ke mana?!" Aku akhirnya berteriak. Beberapa orang tampak terbangun dari tidurnya.
Bethlehem terlihat menarik napas panjang sebentar, sebelum akhirnya ia berteriak, "Pak Sopir, berhenti! Di depan ada jurang!"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top