[Tidak] Normal
Rekomendasi lagu: Young & Sad oleh Noah Cyrus

"Kau baik-baik saja, Ren?" tanya Pak Soni dengan nada lembut.
Aku ingin menjawab, 'Menurutmu bagaimana, Pak? Saya baru saja ditampar oleh seorang guru. Apa saya baik-baik saja?' Kubayangkan diriku memutar bola mata. Kubayangkan. Aku tidak benar-benar melakukannya.
"Tolong maafin Bu Neila ya," pinta Pak Soni dengan memelas, "Dia ... sedang melalui banyak hal."
Aku melirik Pak Soni. Aku sudah menduga mengenai 'hal' yang sedang dilalui oleh Bu Neila. Dan aku memang sudah siap untuk memaafkan Bu Neila. Lagi-lagi kubayangkan diriku menghembuskan napas. Sementara kujaga ekspresiku tetap netral.
"Semua orang juga sedang melalui banyak hal," kata Nana dengan nada ketus, "Bukan berarti itu jadi alasan untuk nampar orang, kan?"
Perkataan Nana membuatku tertegun. Aku yakin Nana tidak mengetahui keadaan Bu Neila yang sebenarnya. Dia pintar secara textbook tetapi tidak secara street smart. Namun perkataannya....
Aku selalu diajarkan bahwa semua orang memiliki ceritanya masing-masing. Terutama mereka yang bersembunyi di balik tindakan yang vulgar atau kasar. Mereka sebenarnya memiliki hati yang paling terluka.
Kata Ayah dan Ibu, sebagai psikiater dan terapis, adalah tugas kita untuk mendengarkan. Mereka, para pasien, memutuskan untuk pergi ke ahli profesional karena sudah tidak dapat mengatasi diri mereka sendiri. "Kita harus menampung semua rasa sakit mereka," kata Ayah ketika aku berumur sepuluh tahun. "Ada beberapa orang yang self-defense mechanism mereka adalah projecting. Yaitu mereka harus memproyeksikan rasa sakit mereka pada orang lain. Mereka akan mencari orang lain sebagai tumbal dari rasa malu ataupun amarah mereka, seolah-olah orang lain itu yang salah."
"Ketika menemui orang seperti itu, jangan marah balik. Biarkan rasa sakit mereka mengalir padamu tapi jangan kamu ambil rasa sakit itu." Ayah duduk di sisi ranjangku. Ia mengalungkan lengannya padaku.
Hari itu aku berpikir betapa anehnya ayahku. Ketika ayah orang lain membacakan dongeng untuk mengantar anak tidur, ayahku malah mengajariku dasar psikologi.
"Gimana caranya mengalirkan rasa sakit, Yah? Aku ga ngerti," tanyaku waktu itu.
"Ketika kamu mengerti penderitaan mereka, kamu akan bisa menoleransi tindakan mereka. Itu artinya 'mengalirkan' rasa sakit itu. Biarkan mereka mengeluarkan unek-unek mereka dan kamu menjadi perantara untuk keluarnya rasa sakit itu. Beritahu mereka dengan tindakanmu bahwa kamu mengerti. Entah dengan ucapan atau ekspresimu."
"Tapi gimana kalo aku ga bisa mengerti?"
Kuingat Ayah waktu itu mengeratkan pelukannya padaku. Ia mendekatkan wajahnya pada telingaku kemudian berbisik, "Itulah mengapa psikolog dan psikiater terbaik adalah mereka yang dapat berakting."
Aku ingat aku begitu terkejutnya dengan kata-kata Ayah hingga rahangku terbuka lebar. Mataku membulat menatap sepasang mata Ayah yang penuh kejahilan.
"Bukan berarti kita harus berpura-pura setiap saat," lanjut Ayah, "hanya berpura-pura cukup untuk membuat mereka merasa didengarkan."
"Ren, mereka tidak datang untuk mendapatkan solusi. Mereka datang untuk didengarkan... dan untuk mendengar kata-kata yang mereka ingin dengar. Itu adalah sebuah seni tersendiri. Dan profesi seperti Ayah mempelajari seni itu."
Saat itu aku tidak mengerti maksud Ayah. Namun setelah memasuki SMP kemudian SMA, perlahan aku mulai mengerti. Kata-kata yang semua orang ingin dengar....
'Semua akan baik-baik saja,'
'Itu bukan salahmu,'
'Tidak apa-apa,'
Aku sudah mengerti maksud Ayah. Kita harus selalu menjadi orang berhati lebih besar. Harus selalu menoleransi dan mengerti tindakan orang lain. Dan ketika orang seperti Bu Neila dan Jon melakukan apa yang mereka lakukan padaku... aku harus mengatakan apa yang ingin mereka dengar.
'Aku mengerti.'
Jadi ketika Nana bertanya dengan nada kesal, aku tertegun.
Nana dapat merasa kesal karena dia tidak tahu cerita sepenuhnya. Dia tidak mengerti rasa sakit orang lain di balik tindakan mereka. Namun aku, yang sudah mengetahui permasalahan Bu Neila ... apa aku tidak berhak untuk merasa kesal pula?
Kubayangkan diriku menghembuskan napas kembali.
Ignorance is bliss. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan.
Karena begitu kau tahu cerita orang yang sepenuhnya, kau terpaksa menjadi pihak yang 'menoleransi.' Kau terpaksa merelakan kemarahanmu sendiri.
"Saya mengerti kok, Pak." Aku memberikan senyuman kecil pada Pak Soni. Beliau terlihat lebih tenang meski sorot matanya masih terlihat khawatir. Maka kuyakinkan beliau, "Tenang. Saya juga tidak akan memberitahu orang tua saya. Anggap saja ini saya nabrak pintu." Aku terkekeh dengan jawabanku sendiri meski pipiku terasa sedikit sakit ketika aku tertawa.
Pak Soni menepuk pundakku. Tatapannya tulus ketika ia berkata, "Kamu orang yang baik."
"Apa?" seru Nana di balik Pak Soni, "Lu bakal maafin Bu Neila? Dia nampar lu di siang bolong padahal dia orang dewasa–"
"Lalu?" tanyaku pada Nana. Gadis itu menatapku seolah akulah yang gila. "Orang dewasa juga manusia. Tidak ada yang sempurna."
Nana memicingkan matanya padaku. Bisa kulihat gadis itu sedang memutar otak pintarnya. Mungkin dia sedang mencoba membaca pikiranku. Kuberikan dirinya senyumanku yang mampu meluluhkan semua orang dewasa.
Senyuman itu sepertinya tidak mempan untuk Nana. Ya... aku tidak begitu peduli juga.
"Lu beneran gapapa, Ren?" tanya Milo. Aku menoleh pada pria itu dan masih memasang senyuman yang sama.
"Yup," jawabku ringan.
"Ehem. Ehem." Pak Soni pura-pura membersihkan tenggorokannya untuk menarik perhatian kami. Ketika puas telah mendapatkan perhatian ketiga murid yang terkena detensi itu, Pak Soni memasang kacamata bacanya.
"Milo, kamu kan sudah sering kena detensi...," sementara Pak Soni berkata, kulihat Milo mulai menegang kembali. Mungkin pemuda itu takut bila Pak Soni akan berkata hal yang sama dengan Bu Neila.
"Apa ada yang ingin kamu beritahu pada saya?" tanya Pak Soni dengan lembut.
Ini adalah kesempatan untuk Milo mencurahkan kegundahannya. Namun bukannya bercerita, Milo justru menggeleng pelan.
"Kamu yakin?" tanya Pak Soni sekali lagi.
"I– iya, Pak. Saya ga punya... alasan...."
Jujur aku tidak begitu tahu mengapa manusia seringkali memilih waktu dan situasi tidak tepat untuk mencurahkan hati mereka. Lalu ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka merasa rendah diri dan lebih menutup diri dari sebelumnya. Bahkan ketika kesempatan yang sempurna datang pun, mereka sudah terlanjur mengurungkan niat untuk mengeluarkan kegundahan mereka.
Aku seharusnya membantu Milo, tidakkah kau pikir begitu?
Bila Milo tidak mulai menceritakan pengalamannya dirundung oleh Bimo pada Pak Soni, ia kehilangan kesempatan untuk bercerita sama sekali.
Namun, mengapa aku harus membantunya?
Kulirik ke sebelah kiriku. Nana sedang menggigiti bibirnya. Bila kutebak, sepertinya Nana berpikir untuk menceritakan perundungan Milo pada Pak Soni. Namun kuyakin ia tidak akan melakukannya. Gadis itu baru saja mendengarnya dari Milo tadi mengenai alasan pemuda itu sering terkena kelas detensi. Sebagai seorang kutu buku akut yang tidak begitu memerhatikan pergaulan sosial, kupikir Nana belum mendengar desas-desus yang beredar mengenai Milo di sekolah ini. Maka, gadis itu pasti merasa ia tidak punya bukti cukup untuk menceritakan apapun.
"Baiklah kalau begitu," kata Pak Soni sembari mengangguk. Pria usia tengah baya itu menoleh pada Nana. "Saya rasa ini pertama kalinya kamu kena kelas detensi benar kan, Na?"
"Uh... I– iya, Pak." Nana menundukkan kepalanya. Kutebak ia malu berada di dalam kelas detensi. Seorang yang memiliki rekor nilai dan performa sempurna di sekolah tiba-tiba mengikuti kelas detensi. Jujur, aku sedikit penasaran.
"Ada yang ingin kamu ceritakan pada saya, Na?"
Nana menggeleng singkat, tatapannya masih menuju meja.
Pak Soni menghela napas panjang. "Kalau begitu, langsung saja saya akan beritahu tugas kalian untuk detensi kali ini–"
"Pak," Nana memotong kalimat Pak Soni, "Bapak belum nanya sama Renald."
Ah, perempuan ini....
Sebelum Pak Soni berkata apapun, kuputuskan untuk menceritakan sendiri alasan aku mengikuti kelas detensi. "Gue merokok di sekolah. Pak Soni nemuin gue di atap."
Lagi-lagi Nana seakan tidak puas dengan jawabanku.
Lagi-lagi, aku memberikan senyuman manis pada Nana. Meski aku tahu senyuman itu hanya akan membuatnya jengkel.
Suara Pak Soni membersihkan tenggorokannya kembali membawa perhatian kami padanya. "Intinya kalian bertiga di sini karena sudah melanggar peraturan sekolah. Sekarang, tugas kalian adalah untuk membuat sebuah proyek bersama."
"Sebenarnya saya cukup bingung mau menugaskan apa pada kalian. Apalagi kalian bertiga sangat berbeda satu sama lain. Namun sepertinya ada satu tema yang bisa kalian usut."
Aku menaikkan satu alisku, penasaran dengan perkataan Pak Soni.
"Tema proyek kalian adalah 'Identitas.' Buat sebuah proyek yang memiliki dampak pada masyarakat dan berlangsung selama minimal satu minggu."
"Pak!" seru Nana sembari mengangkat tangannya. "Saya ada lomba olimpiade tiga bulan lagi."
Pak Soni memberikan tatapan agar Nana mengelaborasi pernyataannya. Namun gadis itu ternyata sudah selesai berbicara.
Aku mendecak dalam hati. Gadis ini tidak begitu pandai dalam membaca gestur tubuh.
"Seperti yang kamu bilang, olimpiade itu dalam tiga bulan dan sebelum kamu protes lagi," lanjut Pak Soni sebelum Nana sempat melayangkan protesnya kembali, "Bila proyek ini gagal, sekolah akan memberhentikan partisipasimu dalam perlombaan apapun."
Nana yang terkejut berkedip dua kali. "Apa?"
Pak Soni mengangguk mantap. "Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik untuk proyek ini."
"Ta– tapi–"
"Nana, ini adalah konsekuensi dari melanggar peraturan sekolah," Pak Soni memotong Nana kembali, "Lagipula kalau proyek ini berhasil, bisa kamu daftarkan untuk lomba pula. Pikirkan hal itu untuk resume kuliahmu."
Wow. Dengan kata-kata itu, Nana langsung menurut dan menutup mulutnya.
Kemudian Pak Soni memberikan sebuah senyuman yang lebar. "Kalian bertiga bekerja sama dengan baik yaa... Selama seminggu setiap pulang sekolah kalian akan menghabiskan satu jam di kelas ini untuk membicarakan proyek kalian. Minggu depan saya sudah mau melihat proposal proyek kalian."
"Apa ada pertanyaan?"
Melihat tidak ada yang mengangkat tangan, Pak Soni akhirnya berkata, "Baik kalau begitu kelas detensi hari ini saya akhiri lebih cepat. Besok di jam yang sama kalian bisa mulai diskusi untuk proyek kalian."
Pak Soni akhirnya membuka pintu kelas seakan mengusir kami bertiga. Aku memanggul kembali tasku. Kulihat Nana masih sibuk untuk merapikan alat tulisnya sementara Milo sudah lebih dulu keluar dari ruangan.
Milo berhenti di depan pintu secara canggung. Ia melirik aku dan Nana. Kemudian masih secara canggung, ia melangkah pergi.
Aku mengikuti sosok Milo, keluar dari ruangan itu. Meski pikiranku seakan masih terjebak dalam ruangan itu.
Identitas, huh? Kenapa Pak Soni memilih tema itu untuk kita? Mengapa 'Identitas' adalah hal yang sama untuk kita bertiga?
Aku, Milo, dan Nana tentu sangat berbeda dari satu sama lain....
–Bersambung–
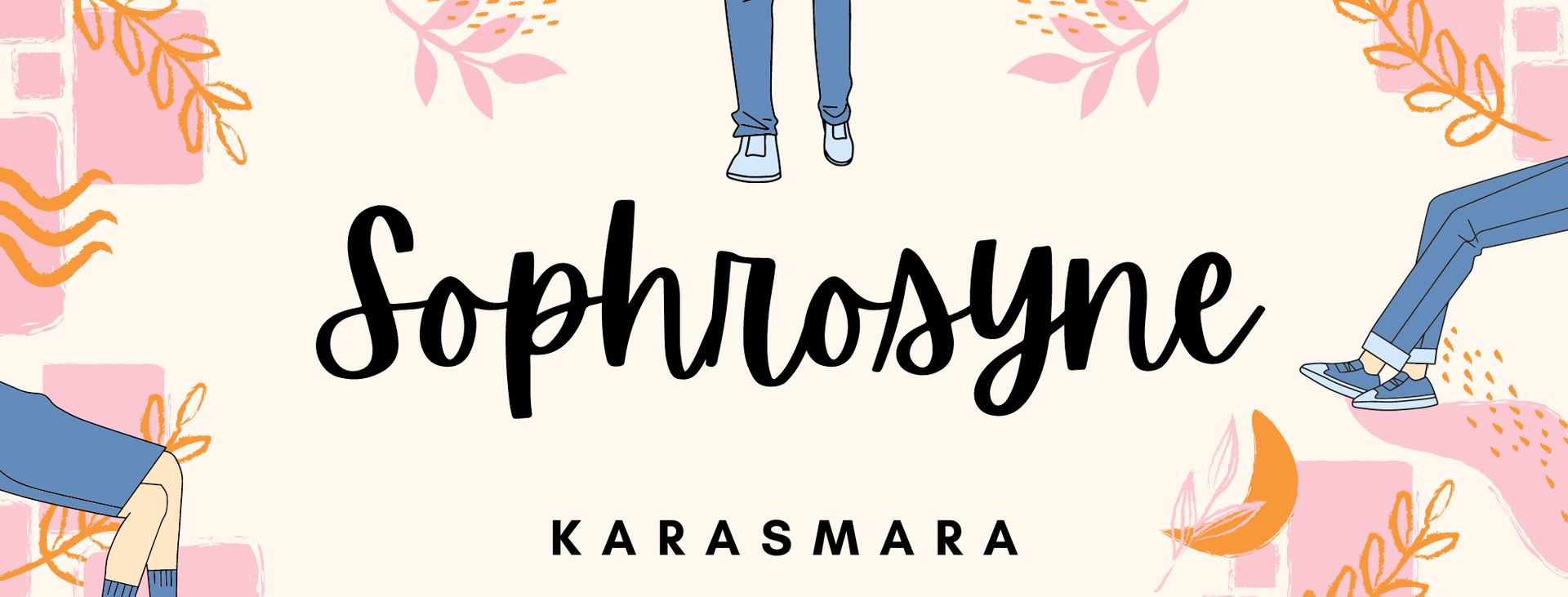
𝑨𝒑𝒂 𝒌𝒂𝒖 𝒃𝒆𝒓𝒑𝒊𝒌𝒊𝒓 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒊𝒕𝒖 𝒋𝒂𝒖𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒃𝒆𝒅𝒂 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒍𝒂𝒊𝒏?
𝑵𝒂𝒏𝒂: 𝒀𝒂 𝒊𝒚𝒂𝒍𝒂𝒉!
𝑴𝒊𝒍𝒐: 𝑨𝒑𝒂 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒓𝒃𝒆𝒅𝒂 𝒊𝒕𝒖...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top