Palsu Hingga ke Tulang

Rumah terasa lenggang. Hal yang biasa kurasakan setiap kali pulang sekolah. Hanya Mbak Rahma yang menyapa, itupun singkat saja. Pembantuku itu tidak begitu menyukaiku. Menurutnya aku ini diam-diam psikopat, dia pikir aku ini selalu bersandiwara setiap saat.
Ia tidak salah.
Ketika semua orang tertipu dengan senyuman manisku, tidak demikian Mbak Rahma. Ia selalu tidak membalas senyumanku. Mungkin menurutnya ada iblis di dalam diriku yang mengontrol segala tindak tandukku.
Itu juga tidak salah.
Terkadang aku merasa bukanlah dalang dari hidupku sendiri. Aku merasa aku hanya berenang dalam arus ekspektasi dan harapan orang lain terhadapku, bertingkah sesuai yang orang lain mau. Namun di balik itu semua, bila ada yang bertanya padaku, apa aku benar-benar ingin menjadi sosok Renald seperti ini...
Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
Aku baik-baik saja.
Lebih tepatnya, aku harus baik-baik saja. Dan ini adalah satu hal yang Mbak Rahma tidak dapat mengerti dan aku tidak dapat menjelaskan pada siapapun.
Setelah mandi sore aku biasanya mencoba tidur sebentar atau mengerjakan tugas sekolah. Namun hari itu aku hanya menatap langit-langit kamar dalam diam, seperti patung. Ponselku berdering terus-menerus setiap kali orang tuaku memberikan pesan demi pesan di Whatsapp. Mereka tentunya telah mendengar tentang hariku ini dari para guru, kemungkinan besar dari Pak Soni. Mereka juga telah mencoba menelponku berkali-kali tetapi aku belum mood untuk berbicara dengan mereka.
Aku belum siap memasang dinding dan topengku kembali.
Hanya sejenak... aku ingin melepas topeng ini sedikit lebih lama lagi... Aku ingin bernapas ringan sedikit lebih lama lagi.
Tak terasa tanganku mengepal begitu keras di sprei kasur. Aku baru sadar ketika suara ketukan pintu terdengar, membuyarkan lamunanku. Dengan cepat, aku terduduk dan mempersilakan siapapun di depan pintu.
Mbak Rahma membuka pintu sedikit dan memunculkan sebagian kepalanya. "Ren, itu Mami minta kamu angkat telpon. Dia khawatir."
Aku berkedip.
Dengan begitu gampangnya aku menampilkan senyuman manis nan sopan yang kupasang setiap harinya. Senyuman yang meluluhkan hati semua orang kecuali Mbak Rahma. Pembantuku itu malah sedikit mundur ketika aku tersenyum. Menurutnya, senyumanku ini mengerikan.
Ia tidak salah. Kadang-kadang aku merasa ngeri dengan diriku sendiri.
"Terima kasih aku sudah diingatkan ya, Mbak."
Mbak Rahma mengangguk dengan kikuk. Ia biasanya diam saja dan langsung cepat-cepat menjauhiku. Namun hari ini sepertinya hari spesial untukku.
"Ren, kalau kamu lagi sedih atau kesal tapi memaksakan senyum seperti itu," celetuk Mbak Rahma, "menyeramkan, tahu? Kayak ada yang mengendalikan kamu gitu. Kayak kamu bukan manusia."
Bukan manusia...
"Trus aku harusnya gimana Mbak?" tanyaku masih dengan senyuman yang sama. Yang Mbak Rahma tidak mengerti adalah, aku tidak mau melepas sosok di balik senyuman ini, 'Iblis' di balik keberadaanku. Bagian dari diriku yang selalu terbayang-bayang di setiap saat tanpa orang-orang ketahui.
"Kamu kan tidak harus selalu menjadi sempurna," jelas Mbak Rahma, "Jadi lebih manusia dikit lah."
Jadi lebih manusia?
"Tapi, aku kan manusia, Mbak?" Aku terkekeh kecil. Bagi orang lain, pastinya aku terlihat sedang mengajak mereka bercanda. Nada yang kugunakan pun tidak mencemooh dan ringan, sudah kupastikan itu.
Namun Mbak Rahma memang benar-benar anti diriku sepertinya. Menjengkelkan.
"Manusia ga selalu senyum kayak kamu," kata Mbak Rahma, "Udah, udah. Itu tolong ditelpon balik Bu Rina. Dia khawatir sekali dengar kamu tadi ditampar seorang guru."
Mbak Rahma sudah mengambil satu langkah mundur, tetapi kemudian berhenti dan berkata pelan. "Kamu boleh merasa sedih ataupun marah, tahu? Retak sedikit seperti kita semua."
Aku berkedip kembali. Senyumanku masih terpasang. Bila orang lain melihat percakapan kita, tentunya mereka akan berpikir Mbak Rahma lah yang sedikit aneh dan aku sedang meladeninya dengan senyuman. Hanya Mbak Rahma dan aku yang tahu kebenarannya bahwa...
Aku lah yang aneh.
Seperti kata Mbak Rahma, aku seperti bukan manusia.
Seketika Mbak Rahma menutup pintu, senyumku redup seperti seseorang telah begitu saja mematikan lampu. Entah mengapa, aku menoleh ke arah kaca besar di dinding. Dan aku melihat diriku yang sebenarnya.
Sejujurnya, aku lupa caranya menjadi manusia.
Siapa diriku tanpa senyuman palsu ini... tidaklah seperti manusia.
Identitas? Aku ingat tema proyek yang diusung Pak Soni. Aku tahu siapa diriku. Tapi aku menolak untuk menunjukkannya.
Menarik napas dalam-dalam, aku kembali memasang senyuman jagoanku itu dan mengangkat hape yang sudah kembali berdering. Suara desahan yang panjang terdengar dari balik sambungan telpon. Ibuku mengeluarkan napas lega segera setelah mendengar suaraku. Ia jelas sekali sangat khawatir.
"Ren, kau tidak apa-apa?" tanya ibuku, "Mami sudah di depan gerbang. Papi sedikit telat karena lagi mengajar, tapi kamu baik-baik saja, kan?"
Setelah Mami memastikan bahwa aku 'terdengar' baik-baik saja, ia menutup sambungan. Memang, untuk hal-hal seperti ini, orang tua tentunya harus melakukan percakapan tatap muka dengan sang anak. Jadi itulah yang dilakukan orang tuaku yang adalah seorang psikiater dan terapis. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di rumah setelah percakapan di hape.
Mami langsung memanggilku duduk di meja makan setelah memastikan aku tidak apa-apa secara fisik. Ia mendecak tidak suka pada bekas merah di pipiku. Matanya menggelap, tidak suka melihat anak semata wayangnya disakiti. Dengan setelan jas dan celana putih dan rambut yang dicepol ke atas, Mami terlihat menguarkan aura seorang bos besar. Dan memang dia adalah direktur dari sebuah institusi yang bergerak di bidang kesehatan mental remaja. Selain memberikan tes psikolog untuk sekolah-sekolah, ibuku ini juga membuka klinik yang memberikan terapi kognitif dan behavioral untuk anak-anak yang neurodiverse. Sekarang sudah tidak zaman mengelompokkan anak-anak dengan keterbatasan mental karena sebenarnya itu semua memang adalah kondisi dan bukannya penyakit. Kondisi mental kita bervariasi seperti kepribadian kita berwariasi. Mereka yang memiliki ADHD, disleksia, bahkan spektrum autisme sudah tidak zamannya dipandang sebagai manusia yang tidak sempurna.
Melihat muka ibu yang masam, aku berusaha meringankan suasana, "Ternyata bekas ditampar lumayan lama ya hilangnya."
Mami tidak menggubris usahaku untuk bercanda karena saat itu juga klakson mobil Papi terdengar. Dalam waktu hitungan menit, Papi bergegas masuk. Ia masih menggunakan pakaian scrub karena hari ini ia ada ronde di Rumah Sakit Nasional dan mengajar para PPDS psikiatri.
Sama seperti Mami, Papi langsung mendekatiku dan memeriksa keadaan fisikku selayaknya seorang lulusan kedokteran. Dari rambut hingga kaki, ia periksa. Ia bahkan memeriksa kondisi otot rahang dan leherku. Kemudian menyuruhku membuka mulut untuk memastikan tidak ada pendarahan gusi. Setelah itu ia membelai rambutku lembut dan mengeluarkan helaan napas lega.
Lihat? Kedua orang tuaku sangatlah mencintaiku dan begitu sukses.
Jadi kenapa... aku terus harus memasang senyuman palsu ini?
Papi duduk di seberang meja dariku, sementara Mami duduk di sampingku. Sekarang, sandiwara yang sebenarnya dimulai.
"Ren, kami telah dipanggil oleh Kepala Sekolah," kata Mami, "karena kamu ditemukan merokok di gedung sekolah. Apa itu benar?"
"Iya," aku menjawab dengan wajah netral. Tidak tersenyum kali ini, tapi aku menatap lurus Papi dan Mami. Karena aku tahu bila aku menatap ke arah lain, mereka pasti akan tahu aku sedikit berbohong. Mereka kan sehari-hari menangkap pasien berbohong pada mereka. Dalam tes psikologi manapun juga pastilah ada suatu standardisasi yang dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban pasien. Karena seorang psikopat seringkali sudah tahu jawaban apa yang dinginkan orang lain, tetapi bila ditanya dengan cara berbeda otak mereka dapat di-trick untuk memberikan jawaban yang sebenarnya.
Oh, kadang-kadang aku berpikir apakah diriku seorang psikopat? Mungkin saja...
"Kenapa, Ren?" tanya Papi, "Penasaran."
Aku mengangguk, masih menatap mereka lurus. "Tapi aku tidak begitu menyukainya," aku menambahkan, "Maaf Pi, Mi. Seharusnya aku tidak pernah melakukannya."
Papi dan Mami saling melirik satu sama lain sebelum kembali memandangku dan bertanya, "Kamu tahu kan dampak-dampak jelek dari merokok?"
Aku mengangguk. "Aku hanya penasaran tadi," jawabku, "Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya merokok tidak sepadan dengan efek-efek jeleknya pada kesehatan." Aku memasang wajah seperti jijik, seakan aku telah memakan sesuatu yang begitu pahit. "Ga enak banget merokok."
Papi tertawa kecil melihatku. "Sebenarnya tidak apa-apa bila kamu pingin mero–"
Kalimat Papi terpotong dengan senggolan tangan dari Mami. Satu lirikan tajam dari Mami membuat Papi membersihkan tenggorokkannya dan mengulang perkataannya, "Maksudku, kamu tidak boleh merokok. Titik."
Mami sedikit memutar bola matanya sebelum akhirnya bertanya, "Lalu, apa yang kamu lakukan sehingga Bu Neila menamparmu?" Tatapan Mami kembali menggelap. "Kamu tahu kan kamu bisa cerita apa aja ke kami. Kalau ada yang macam-macam sama kamu, bilang aja. Kita bisa juga menuntut Bu Neila dipecat–"
Aku menggelengkan kepalaku. Kemudian dengan suara lebih kecil, aku menceritakan kemalangan Bu Neila. "Aku bersimpati pada Bu Neila. Ia pasti merasa dikhianati. Jadi Mami Papi jangan adukan Bu Neila. Biarkan Kepala Sekolah yang menanganinya saja."
"Tapi Ren–"
Lagi-lagi aku memotong Mami. "Bukannya kalian yang mengajariku kalau kita harus selalu merelakan bila ada orang yang memproyeksikan kegundahan hati mereka pada kita. Kita justru harus bersimpati pada mereka."
Mami dan Papi saling memandang kembali.
"Tapi Ren," kata Papi, "Ini kan gurumu. Seharusnya dia bersikap profesional. Sebagai guru, dia seharusnya tahu batasan dan tidak akan pernah bermain tangan dengan muridnya. Apalagi ini sekolah yang sudah kita bayar mahal-mahal."
"Pi," kataku, "Aku beneran tidak apa-apa. Daripada memecat Bu Neila, mending Papi minta dia liburan aja. Sepertinya Bu Neila butuh liburan."
"Ren," Mami berkata dengan suara yang serius tapi lembut, "Kamu boleh lho marah. Kamu boleh lho nangis. Kamu boleh kok membenci orang. Ga perlu selalu memaafkan dan menjadi orang yang lebih besar. Kamu masih enam belas tahun, kamu berhak tidak bertingkah se-dewasa ini."
"Tapi...," aku memandang mereka bergantian, "...untuk apa? Aku beneran tidak apa-apa kok." Untuk melengkapi sandiwaraku, aku mengeluarkan tawa kecil, membuktikan pada mereka bahwa aku melihat ini semua lebih seperti hal yang patut ditertawakan daripada seperti sesuatu yang akan memberiku trauma batin.
"Syukurlah kalau kamu memandangnya seperti itu," kata Papi.
"Tapi, Ren, karena kamu kena detensi," kata Mami tegas, "Kamu harus menulis refleksi ya malam ini."
Klasik.
Mami memperlakukanku seperti pasiennya dengan memberiku tugas refleksi daripada menghukumku seperti orang tua lainnya. Begitu juga Papi yang sedari tadi sudah mengobservasi semua tingkah laku dan jawabanku. Mereka pikir aku tidak akan sadar, tetapi aku tahu.
"Siap, Mi," kataku mantap.
Begitu topik mengenai sekolah hari ini selesai, Mami dan Papi menjadi canggung ketika mencari topik lain.
Klasik juga.
Kita memang susah sekali mencari topik yang dapat dibicarakan ketiga. Pun bila ada topik, percakapan kita akan seperti tadi; dua ahli dan satu pasien. Bukan sepasang orang tua dan anak semata wayangnya. Kendati demikian, aku tahu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tahu mereka tidak sempurna.
Aku mengerti keadaan mereka.
"Ya sudah," kata Mami, "Kamu sudah makan malam?"
Meski belum, aku mengangguk. Aku benar-benar ingin ke kamar saja setelah ini. Seluruh tenagaku habis. "Aku mau naik, Pi, Mi. Mau lanjut PR proyek yang dikasih Pak Soni karena detensi. Kemudian mau tidur karena besok pagi-pagi ada kuis kecil dari Bu Tri."
Mami mengangguk. Melihat Mami, Papi pun mengangguk. Setelah mengucapkan selamat malam pada mereka berdua, aku pun naik dengan santai menuju kamarku.
Namun begitu pintu kamarku tertutup, dalam remangan cahaya kamar, mataku kembali menahan tatapan refleksi diriku sendiri di cermin. Tanpa senyuman, tanpa sandiwara, tanpa topeng.
Diriku yang sebenarnya.
Kemudian aku membuat tulisan refleksi. Dalam lima belas menit, aku sudah dapat menulis sepanjang satu setengah halaman dengan format detil kejadian, perasaanku, dan apa koreksi yang akan kulakukan di masa depan.
Begitu mudah untuk bersandiwara. Begitu mudah untuk menjadi palsu hingga ke tulang.
Sebelum alam tidur menjemput aku kembali memikirkan tema proyek yang diberikan Pak Soni.
Identitas.
Apa dunia siap melihat diriku yang sebenarnya?
–Bersambung–
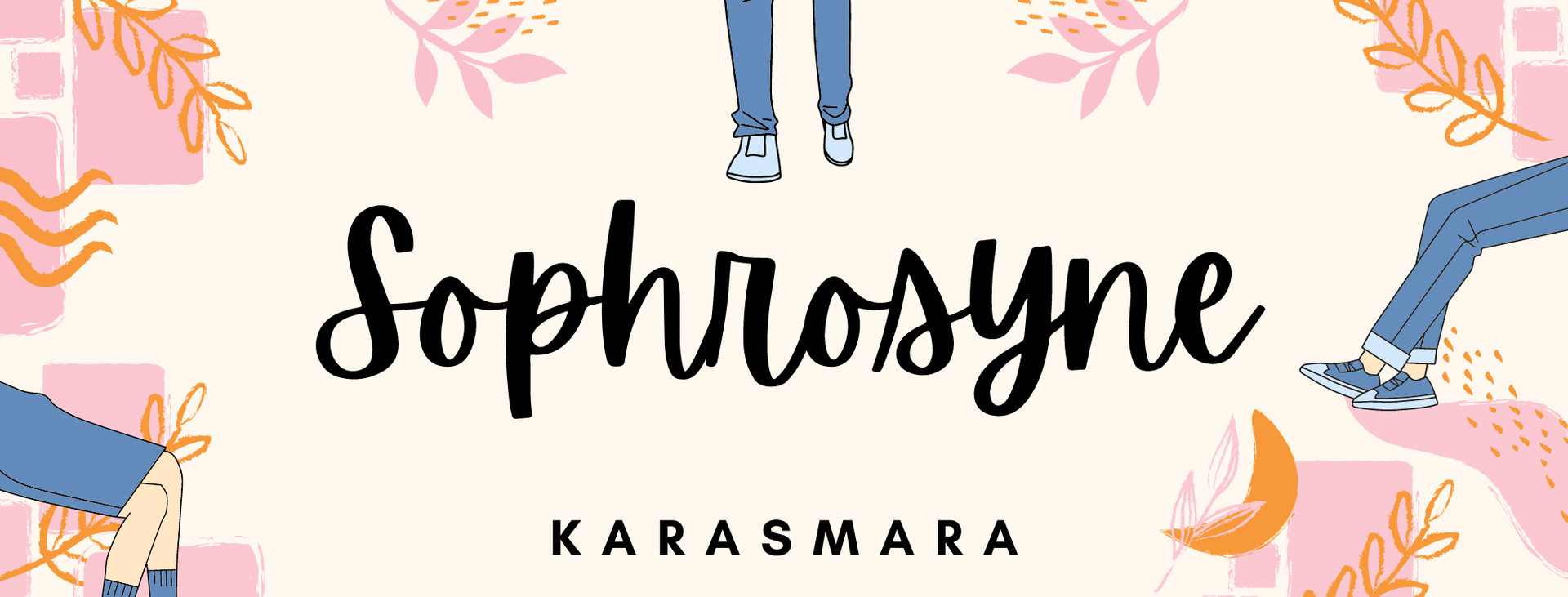
Apa kamu siap melihat Renald yang sebenarnya?
Nana: Tch. Dia tidak sesempurna yang orang bilang. Dia pun kena detensi kan.
Milo: Coba kalo aku lebih seperti Renald. Tidak ada yang berani merundungnya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top