Normal
Rekomendasi lagu: Exit Music (For a Film) oleh Radiohead

Setelah hari naas itu, aku mempelajari suatu hal yang baru: bila kau pintar, kau tidak akan ketahuan ketika berbohong. Begini, berbohong itu ternyata sangat mudah. Dan untungnya aku selalu menjadi murid dan anak dengan predikat baik. Aku terkenal jujur dan bertanggung jawab.
Bahkan ketika Fredie merokok di jam istirahat, aku lah yang memberitahukan pada guru piket mengenai kelakuannya. Lalu ketika Vanessa diam-diam mengatakan sahabatnya sendiri, Gina, memiliki rupa yang jelek. Kemudian ketika Adrian–
Kau mengerti lah maksudku. Kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Dan terkadang aku yang mengambil peran untuk membuka kebenaran. Ah, tidak perlu berterima kasih padaku. Kupikir itu adalah hal yang setidaknya setiap manusia dapat lakukan ... meski, aku tidak melihat semua manusia melakukan itu.
Anyway, aku dengan mudahnya mengatakan pada orang tuaku bahwa sedang ada proyek sekolah yang membutuhkanku untuk pulang lebih lama dari biasanya selama sebulan. Kubilang saja proyek itu adalah dari guru bahasa indonesia. Pertama, mereka tidak akan peduli dengan pelajaran itu. Kedua, guru bahasa indonesia, Pak Eko, adalah satu-satunya guru yang tidak pernah mereka temui. Ketiga, aku tidak ada niat untuk berbicara panjang lebar dengan orang tuaku ketika aku tahu aku telah mengecewakan mereka. Dengan menggunakan alasan itu, mereka tidak akan bertanya lebih dan aku tidak perlu menjelaskan apa yang membuatku dapat kelas detensi.
Alibi yang sempurna, bukan?
Jadilah aku duduk di dalam kelas X-1 yang selalu dijadikan tempat kelas detensi setiap pulang sekolah. Ruangan ini kosong kecuali aku dan satu murid laki-laki. Aku mengenal murid itu sebagai Milo. Dan melihatnya saja dari awal, aku sudah mendecakkan lidahku. Lelaki itu membungkuk di meja, menyatukan jidatnya dengan meja kayu di depannya. Dia sudah berada di posisi itu dari semenjak aku memasuki kelas.
Tsk. Sepatunya tidak serasi. Dia pikir keren apa menggunakan dua sepatu yang berbeda? Aneh, tahu. Kaos kakinya juga kendur, kemejanya ia keluarkan dari celana, dan rambutnya agak panjang untuk pria. Aku sudah mendengar bahwa Milo sangat sering kena detensi. Ya ... dengan penampilan seperti itu, tidak banyak yang bisa diharapkan.
Semenjak kejadian itu, semakin sering pikiran orang-orang dapat kudengar. Bahkan ketika aku berada di kamarku sendiri, aku masih dapat mendengar suara-suara itu. Aku sudah mulai terbiasa. Meski ... perkataan mereka yang tidak dikatakan di depan wajahku, menyakiti hatiku. Di sisi lain, ada pula pikiran Pak Soni yang mulai dapat kudengarkan.
'Mungkin kelas detensi akan baik adanya untukmu, Na.'
'Kamu spesial, Na.'
'Semua jawaban dapat kamu dapatkan di kelas detensi.'
Kalimat-kalimat itu adalah alasan mengapa aku repot-repot berbohong pada orang tuaku dan rela mengikuti kelas detensi. Bila bukan karena itu, aku pasti akan melawan Pak Soni yang menolak menoleransi alasan sakit perutku. Meski aku tidak benar-benar sakit perut ... tapi, masa seorang guru tidak akan menoleransi alasan sakit? Di mana empatinya bila begitu?
Karena kata-kata itu, aku duduk di kelas detensi dan siap menghadapi apa yang dunia akan berikan padaku.
Saat itu juga pintu kelas terbuka. Kulihat seorang murid lelaki lain memasuki ruangan. Berbeda dengan Milo, lelaki ini terlihat sangat rapi. Kemeja dan celananya terlihat mulus, rambutnya pun terpotong rapi, dan ia memakai sepatu yang sepasang. Parasnya juga lumayan, dengan aura misterius mengelilinginya.
Entah kenapa, aku teringat Tommy Shelby dari Peaky Blinders. Seorang berandal jalanan yang menaikan statusnya menjadi ketua gang di sebuah kota dan kemudian menjadi salah satu pebisnis terkaya. Tommy adalah seorang yang berbahaya namun membalut dirinya dengan pakaian mewah.
Aku menghapus pemikiran itu dari benakku. Aku tahu betul siapa laki-laki itu. Satu sekolah mengenalinya. Dan tidak mungkin dia adalah orang yang berbahaya.
Dia adalah Renald Aditya, anak dari pasangan psikiater dan terapis terkenal di DKI Jakarta. Orang tuanya memulai sebuah yayasan dan klinik terkenal berfokus pada kesehatan mental. Kampanye mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu mental bahkan dihargai oleh Presiden Indonesia sendiri. Selain memiliki jiwa sosial, mereka juga sangatlah pintar. Aku sering menemukan jurnal-jurnal mereka di internet. Pernah kubaca beberapa jurnal, kasus-kasus yang mereka tangani bervariasi dan lumayan membuka mata.
Sebagai anak dari pasangan sempurna seperti itu, ia dijuluki sebagai anak paling bahagia di Indonesia.
Jadi kenapa ... tatapannya begitu kosong?
Untuk pertama kalinya aku ingin dapat mendengar pemikiran seseorang. Namun suara-suara itu menjadi sunyi.

Aku menghela napas untuk kesekian kalinya. Kepalaku masih menempel pada meja kayu. Untuk beberapa saat aku menahan posisi itu. Bahkan ketika aku mendengar seorang memasuki kelas. Dari sudut mata, aku dapat melihat orang itu adalah perempuan.
Perempuan itu duduk dua bangku di sampingku. Aku dapat mendengar pergerakannya. Ia tidak bisa diam, terus saja melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menggaruk kepalanya dan menutup telinganya. Kakinya juga tidak bisa berhenti bergerak naik turun. Dan jemarinya terus saja menekan pulpen, membentuk sebuah irama yang monoton.
Sebenarnya, nada monoton itu ... menarik. Bila digabungkan dengan ketukan 3/4 lalu setiap setengah kali delapan hitungan diselingi bunyi dentingan ... kemudian sebuah senandung yang cocok adalah–
Aku baru sadar apa yang baru saja kulakukan ketika melihat pelangi mulai keluar dari jemariku. Meja yang tadinya berwarna hitam kini menjadi cokelat, tanganku yang tadinya putih kini menjadi krem.
Astaga! Aku hampir saja bernyanyi ....
Dengan panik aku menutup mulut dengan kedua tangan. Gerakan itu membuatku menegakkan tubuh. Warna-warna itu mulai memudar, kembali menjadi hitam dan putih. Warna yang sudah kupilih untuk melihat dunia ini.
Saat itu barulah aku sadar, terdapat satu orang lagi yang akan mengikuti kelas detensi. Orang itu bersama perempuan yang tidak bisa diam sedang menatapku kaget. Gerakanku yang mendadak sepertinya membuat mereka terkejut.
Mulutku terbuka lebar kembali ketika mengenali dua sosok itu.
"Lho? Nana ... dan Renald?!" seruku.
Sepengetahuanku, aku hanya menjadikan dunia imajinasiku hitam putih. Tidak sama sekali mengganggu alur dunia yang nyata. Namun tentu melihat dua sosok itu di kelas detensi ... bukankah itu tanda bahwa dunia sudah hancur? Bahwa matahari kini sudah terbit dari barat?
Keduanya adalah murid teladan di sekolah ini. Nana dengan kepintarannya dan Renald dengan sifatnya yang mudah bergaul serta disukai banyak orang. Aku, yang hampir selalu terkena detensi tidak pernah melihat mereka sebelumnya.
Apa dunia sedang mempermainkanku?
Apa aku akhirnya sudah menjadi gila?
Pikiranku harus dihentikan karena Bu Neila memasuki kelas –urgh, dia adalah yang terburuk. Delapan puluh persen dari kelas detensi dipimpin oleh Pak Soni –nah, beliau adalah sosok guru yang pengertian. Tapi terkadang ketika Pak Soni berhalangan, Bu Neila akan menggantikannya. Dan Bu Neila. Adalah. Yang. Terburuk.
Renald mengambil kursi di antara aku dan Nana. Sikapnya begitu tenang. Ia duduk dengan tegak dan posturnya santai, sangat kontras dengan Nana yang duduk tegak namun melakukan gerakan-gerakan repetitif. Bila mereka adalah warna, Nana memiliki warna amber yang menggambarkan kecemaasan. Dan Renald memiliki warna emerald yang menggambarkan ketenangan. Tetapi di dunia yang monokrom mereka hanyalah abu-abu.
Sedangkan Bu Neila adalah hitam.
Perempuan berusia setengah baya itu berjalan dengan dagu diangkat ke arah meja di tengah kelas. Ia berkacak pinggang dan menyoroti kami satu per satu di balik kacamata tebalnya.
"Kamu." Dia mengacungkan jari telunjuknya pada diriku. "Sudah berapa kali kamu kena detensi? Apalagi alasanmu sekarang, huh?" Suara Bu Neila meninggi. "Bolos pelajaran olahraga karena kehilangan sepatu. Tsk tsk tsk. Makanya kalau punya barang dijaga dong! Ga sayang apa kamu dengan uang orang tua?"
Bu Neila tidak menunggu jawaban sebelum mengacungkan jemarinya pada Nana. "Kamu." Tetapi sebelum Bu Neila mencerca Nana, aku angkat bicara. Entah apa yang merasukiku saat itu. Aku hanya ... ingin mengeluarkan sesuatu yang telah menjegal di hatiku. Aku lelah dinilai oleh orang lain tanpa mereka mengetahui cerita sepenuhnya. Lelah dipersalahkan ketika mereka belum mendengar penjelasanku.
"Bu, kenapa Ibu ga pernah tanya sama saya kenapa saya selalu kena detensi pas pelajaran olah raga? Atau kenapa kali ini sepatu saya bisa hilang? Itu sepatu lho Bu, bukan barang kecil yang gamp–"
"Kamu mau bilang kamu di–bully?"
Aku bergeming.
Nada Bu Neila seperti mengandung racun. "Tch. Dengan gayamu seperti itu, pantas aja kamu di-bully terus." Tatapan Bu Neila sama dengan tatapan Arya kemarin. Cuping hidung membesar, gurat bibir menurun, dan sorot mata seakan aku adalah orang ternista di dunia. "Gayamu kayak bencong sih. Mau gimana lagi?"
Sesuatu seperti berteriak di dalam pikiranku. Rasanya seperti tiba-tiba musik rock bermain dengan volume terbesar dekat sekali dengan gendang telingaku. Mataku mulai memanas. Jadi ... jadi ... selama ini para guru tahu aku sering di–bully tapi mereka tidak melakukan apa-apa?
Bu Neila menatapku dengan penuh kemenangan. Garis bibirnya sedikit terangkat. Pandanganku seketika menjadi buram sehingga aku tidak tahu apakah ia tersenyum atau tidak. Dengan cepat aku menundukkan kepalaku lagi, berusaha menghalau tangisan yang mengancam untuk keluar.
"Iihh, gitu aja nangis," lanjut Bu Neila, "Kayak cewek aja."
Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan menangis. Tidak akan. Aku tidak boleh menangis.
"Makanya jangan melawan kodrat deh. Kenapa sih kamu ga coba jadi laki-laki normal aja? Awalnya saya kira rumor belaka saja. Tapi saya perhatiin kamu memang gayanya lemah lembut. Ga kayak laki-laki yang seharusnya. Punya murid kayak kamu tuh malu-maluin sekolah kita, tahu."
Gawat. Gawat. Bila Bu Neila tahu ... dia bisa saja memberitahukan rumor ini pada orang tuaku. Aku merinding memikirkan bagaimana pendapat orang tuaku nanti. Aku harus menolak mentah-mentah pernyataan Bu Neila, aku harus meluruskan rumor itu. Namun lidahku terasa kelu. Seberapa keras pun aku mencoba, otakku juga tidak mau memberikan kalimat yang koheren.
"Menurut saya tidak ada masalahnya Milo bersekolah di sini," aku dengar Nana berkata, "Kalau soal imej sekolah, prestasi-prestasi saya sudah menjadi kebanggaan sekolah bahkan memasukkan sekolah ini di peringkat sepuluh teratas. Jadi, saya rasa tidak perlu ibu berkata seperti itu pada Milo."
Apa? Aku melongo menatap Nana. Mataku masih berair tapi keinginanku untuk menangis sudah tergantikan dengan rasa canggung. Dia ... apa dia baru saja berusaha menolongku? Atau dia hanya ingin mebanggakan dirinya sendiri?
"Tch. Ini lagi." Bu Neila terlihat tidak senang dengan perkataan Nana. Namun sedetik kemudian, ia tersenyum sinis kembali. "Kamu memang jenius, Na. Sangat jeniusnya sehingga kamu bertingkah seperti orang berhalusinasi di kelas, ey?"
Mataku membesar mendengar itu.
"Saya tidak berhalusinasi, Bu!" teriak Nana sambil berdiri. Kedua tangannya memukul meja dengan keras. Seketika ruangan menjadi sangat sunyi. Hanya deru napas Nana yang terdengar dan senyuman Bu Neila yang melebar. Senyuman penuh kemenangan.
"Ooh ... tapi saya dapat laporan dari teman-temanmu mengenai keanehanmu. Semakin lama semakin sering terjadi."
"Mungkin kamu terlalu pintarnya sehingga otakmu...," Bu Neila memutar jemarinya di dekat kepalanya, "...menjadi gila."
Aku merasa kasihan pada Nana. Kulihat ia mengepal kedua tangannya dengan keras. Kacamatanya bertengger di ujung hidungnya karena gerakannya tadi yang tiba-tiba.
Bu Neila telah menang atas kita berdua. Dan kita hanya dapat diam termangu.
–Bersambung–
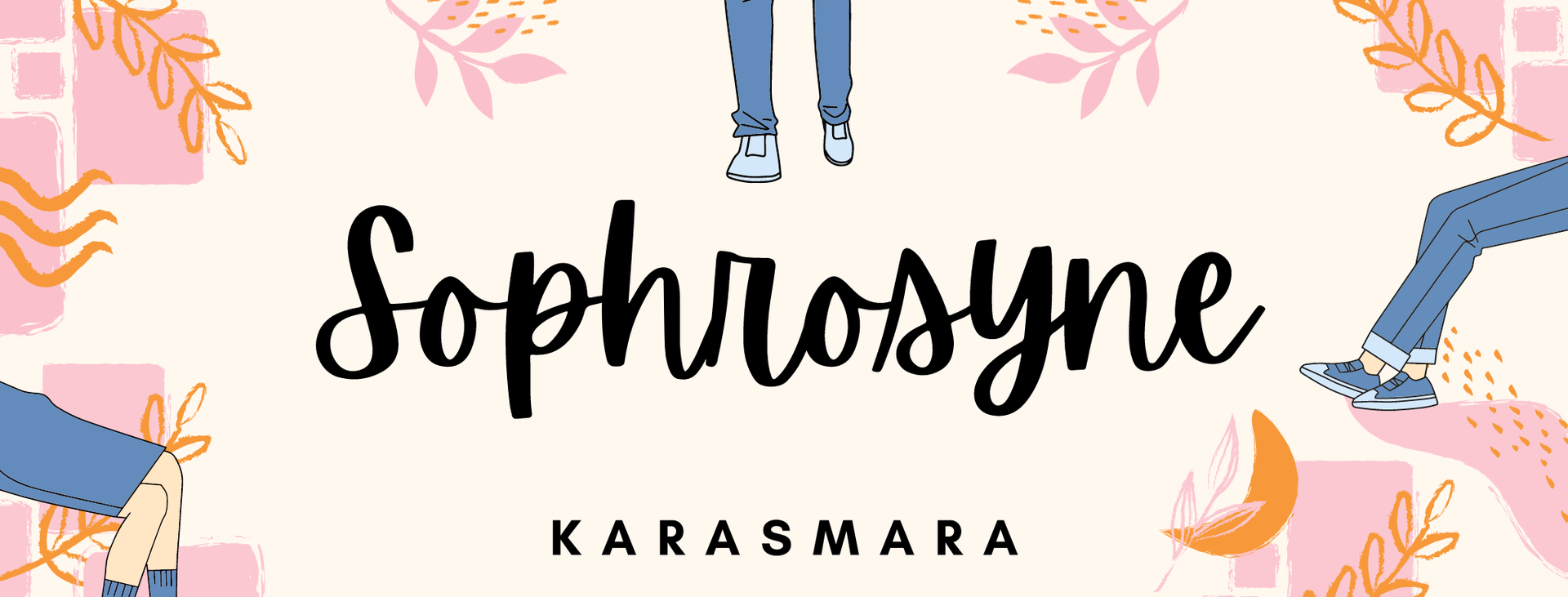
𝑯𝒂𝒍𝒐, 𝒏𝒂𝒎𝒂 𝒔𝒂𝒚𝒂 𝑹𝒆𝒏𝒂𝒍𝒅.
𝑲𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒌𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂, 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓𝒏𝒚𝒂 𝒊𝒏𝒊 𝒄𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒊𝒂𝒑𝒂 𝒔𝒊𝒉? 𝑰𝒏𝒊 𝒄𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂 𝑵𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒐.
𝑺𝒂𝒚𝒂 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒂𝒓𝒂𝒌𝒕𝒆𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒅𝒊𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒌𝒂𝒔𝒊𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒆𝒃𝒊𝒉 𝒍𝒐𝒈𝒊𝒔 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒌𝒆𝒂𝒅𝒂𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒅𝒖𝒂.
𝑱𝒂𝒅𝒊 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇 𝒔𝒂𝒚𝒂, 𝒃𝒊𝒔𝒂 𝒍𝒊𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒃 𝒔𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒖𝒕𝒏𝒚𝒂.
𝑺𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒉𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕,
𝑹𝒆𝒏𝒂𝒍𝒅.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top