20. Safe House for Liars
Happy reading ^^
****
Itu minggu yang gila.
Sejak aku mulai bekerja di restoran ayam, seluruh kehidupanku hanya berputar pada kampus, kerja, rumah. Kalau dikatakan tidak begitu sulit. Kutebak belasan persen penduduk dunia pernah bekerja sambil kuliah, bahkan ada juga para working mom yang bekerja, kuliah, dan mengurus anak (bila ada yang tahu cara masih hidup dalam lifestyle seperti ini, tolong hubungi aku). Namun bila dialami, tiap malam seluruh tubuh dan kepalaku seperti ingin rontok dan kuharap aku punya cara menggandakan badan.
Kerja di restoran ayam Chikkin ternyata mudah tidak mudah. Mudah, bila di jam-jam tertentu hanya datang satu-dua pengunjung. Tidak mudah bila di jam-jam sibuk terutama pada jam makan malam.
Bayangkan, pengunjung terus berdatangan tapi meja restoran hanya sedikit, pesanan antar belum dikerjakan, piring-piring kotor belum dicuci, teman kasirmu tidak datang hari itu jadi kamu harus melayani pembayaran juga, dan saat pembayaran belum selesai, seorang pengunjung me-request lagu.
Dan soal request lagu, aku punya pandangan unik soal itu. Dulunya kupikir, apa sih susahnya bersikap ramah pada pelanggan saat memesan lagu? Sekarang, tiap ada pelanggan yang me-request lagu Kpop kesukaannya, aku tidak bisa tidak membuang napas. Bagaimana tidak, belasan pesanan belum diantar, toilet mampet, semalaman begadang kerja tugas, dan saat aku masih sibuk aku harus melayani request lagu Korea yang sudah seharian itu aku dengar secara terus-menerus (sumpah, mereka tidak pernah pergi).
Satu hal yang membuatku tetap waras, pesan-pesan Dirga. Isinya tidak penting, tidak manis, tidak panjang karena kami berdua sibuk. Tapi cukup menyenangkan curi-curi waktu melirik ponsel di kantung celemekku dan melihat pesannya mengecek keadaanku, seperti "lagi apa?", "sudah makan? Mau makan bersama?", "ingat tempo hari aku bilang lagu Toni Braxton itu payah? Well, setelah mendengar 'Unbreak My Heart' tiga kali tanpa henti aku berubah pikiran. Ugh. I hate myself".
Layaknya dia ada bersamaku menghadapi kekacauan ini walau dia tidak ada di sisiku.
Shift terakhirku selesai lebih awal hari itu. Pukul delapan malam.
Itu artinya aku bisa mengambil bus terakhir menuju terminal dekat kampus. Itu artinya, aku punya waktu me time, selesai mandi air hangat, mengubur diriku dalam selimut sambil makan pizza sisa kemarin dan cola di atas tempat tidur dengan 5000 of Summer sebagai tontonan. Itu artinya aku bisa melakukan good night call lebih awal dan tidak tidur di tengah-tengah percakapan.
Membayangkan itu semua mengaliri kegembiraan dalam darahku. Langkahku ringan saat turun dari bus selayaknya tubuhku tidak diforsir kerja seharian. Kemudian, saat bus melintas dan menghilang, kulihat Raka berdiri di bawah lampu seberang jalan.
Kami jarang sekali bertemu di rumah karena jadwal kami bentrok, tapi itu bukan berarti aku jadi senang ketemu dengannya di tempat acak ini. Kami bukan jenis teman serumah yang seperti itu, terutama setelah percakapan terakhir kami di mobilnya.
"Kamu ngapain di sini?" Aku mendekatinya, agaknya tidak percaya apa yang kulihat.
"Pulang dari minimarket."
Di tangannya tidak ada tas atau kantungan. Dia bahkan memakai kaos longgar dan celana bahan nyaman. Aku mengernyitkan mata, menanyakan hasil pemindaianku pada penampilannya.
Raka mengerti maksudku. "Menjemputmu, tentu saja. Mau ngapain juga aku malam-malam ke terminal selain karena alasan itu?"
Setelah menggantungkan kalimat amat aneh itu, dia meninggalkanku untuk berjalan lebih dulu karena tidak tahan aku memandanginya dengan aneh. Kenapa juga dia melakukan ini? Mau menebus imagenya yang tercoreng di depan teman wanitanya?
Persetan dengan ini, kata akal sehatku saat ia kembali. Kupercepat langkah untuk menyalip Raka, menjadi dua langkah di depan Raka agar dia bisa melihat gaya jalan-tidak peduli kamu bersikap manis-ku. Kami berjalan seperti itu sampai apartemen.
****
Selesai mandi, aku berencana untuk memanaskan sisa pizza-ku yang kusimpan dalam kulkas. Namun, saat aku mengeringkan rambut, aku merasakan ada yang aneh pada perutku. Seperti perasaan perutku ditendang dari dalam dan diperas dalam satu kepalan tangan.
Ah, sial. Siang dan sore tadi aku tidak sempat makan karena jam kuliah dan kerja bersambungan.
Seingatku, kami menyimpan obat maag di kotak obat di laci atas konter dapur. Jadi setelah rambutku kering, aku keluar kamar untuk mengambilnya. Bunyi televisi yang riuh rendah terdengar dari ruang tamu waktu aku membuka pintu kamar. Raka sedang menonton pertandingan sepak bola di TV sambil minum bir dan menyantap satu box pizza sendirian.
Tidak biasanya dia ada di rumah. Orang seperti Raka selalu punya acara di malam hari, entah pergi bersama grup teman kuliahnya, grup basket, atau undangan teman ke pub atau klub. Lingkungan sosialnya jelas lebih luas dariku, jadi tidak aneh bila aku berharap pada hari biasa dia tidak ada di rumah.
Aku berencana untuk menghindari percakapan yang akan terjadi, namun saat aku mengambil obat di kotak obat, Raka melihatku.
"Mau pizza? Aku baru beli sekotak. Ini masih hangat." Dia menawari.
"Nggak, makasih."
Raka berjalan ke tempatku. "Ini domino's pizza. Beef pepperoni feast. Kamu selalu suka makanan. Yakin nggak mau?" Dia mengayunkan sepotong pizza-nya supaya baunya menguar ke tempatku.
Aku menutup hidungku. "Berhenti mengayunkannya. Kamu membuatku mau muntah." Baunya menggugah selera, namun badanku kurang enak, jadi penciumanku sedikit sensitif.
"Wow. Wow. Kamu baik-baik saja?" Raka memegang bahuku dan menggesernya agar bisa melihat mukaku lebih baik. "Mukamu pucat sekali."
Kukibaskan tangannya dari bahuku. Merasakan rasa mual lagi karena badanku yang baru saja diputar secara mendadak.
"Aku baik-baik saja. Aku cuma butuh obat maag, makan pizza sedikit, dan beristirahat. Bukan pizza-mu, ya. Aku punya pizza sendiri di kulkas." Aku melanjutkan pencarianku di kotak obat. Lanzoprazole. Lanzoprazole.
"Ini bukan persoalan pizza, Nola. Kamu sakit," sergah Raka. "Berbaringlah di kamar. Aku carikan kamu obat, ntar kuantar ke kamar."
"Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Lagipula, kamu nggak seharusnya mengurusi urusanku. Kita kan cuma teman serumah." Aku tidak ingin membangun tensi dalam kalimatku, tapi kendali diriku sedang tidak baik di bawah pengaruh mual ini.
Tanganku memilih plastik-plastik obat yang berhamburan di dalam kotak obat sampai ke dasar. Ada yang tinggal satu potong saja, ada juga beberapa papan jenis obat sama yang semuanya sisa setengah. Obatku belum kutemukan. Kami betul-betul tidak pandai menyimpan barang.
Raka menyadari nada ucapanku. "Kamu masih marah sama perkataanku itu? Itu sudah minggu lalu."
"Nggak. Kenapa aku harus marah? Itu kan urusanmu, bukan urusanku. Kamu jadi orang berengsek atau nggak juga bukan urusanku."
"Kamu benar-benar kekanak-kanakkan. Kalau kamu marah atau kesal, katakan saja. Jangan bicara baik-baik saja saat kamu bertingkah kebalikannya. Ini sudah seminggu kamu begini, berhentilah."
"Oh, maaf kalau aku sudah bersikap nggak sesuai yang kamu mau. Mungkin lain kali kamu bisa membuat tata cara gimana cara bersikap sebagai teman rumah yang baik supaya bisa kuikuti?"
"Kuharap kamu pingsan atau ambruk saja. Karena kalau kamu begitu, aku nggak akan peduli."
"Bagus, aturan pertama yang bagus. Aku mengerti kok badanku itu urusanku. Sakitku juga begitu. Jadi, aku pastikan nggak akan merepotkanmu dan jadi teman serumah yang baik."
Dapat!
Aku mengangkat satu papan obat maag dari laci, lalu mendadak gravitasi badanku goyah, kakiku tidak menapak di tanah, dan badanku terangkat. Raka menarikku dan mengayunkanku ke bahunya seperti cara orang angkat karung beras.
"Kakak! Turunkan aku!" Aku berteriak kencang sekali sambil memukul punggung dan menendang bahunya agar dia menurunkanku.
Raka membopongku melewati dapur dan membawaku ke kamar. Saat dia menurunkanku di kasur, perutku bergejolak dan aku hampir saja muntah di sana, tapi aku menahannya. Aku tidak akan tahan tidur di kasur bau muntahan. Aku bergeser ke kasur bagian dalam karena aku tidak tahu apa yang akan Raka lakukan padaku dan kenapa dia tiba-tiba bertingkah.
Raka keluar, lalu masuk kembali dalam kamar dengan segelas air.
"Baring di sini. Makan obatmu dan tunggu makananmu." Dia meletakkan gelas air di atas nakas.
"Kenapa aku harus mengikuti apa maumu? Kamu bukan siapa-siapaku."
"Karena aku ibumu." Raka mencibir. "Kamu berharap jawaban apa? Tentu saja, karena kamu temanku. Bukan teman serumah. Kita teman yang teman." Dia menekankan kalimatnya sambil menunjukku. "Tunggu di sini. Kubuatkan kamu bubur."
"Aku punya pizza."
"Orang sakit nggak makan pizza, mereka makan bubur," sergahnya. "Serius, Nola. Tidurlah. Kamu sudah sepucat zombie. Aku nggak mau jadi orang terakhir yang melihatmu hidup."
Meski aku punya beberapa kalimat penyanggah, akhirnya aku menuruti apa yang dia katakan. Setelah minum obat, aku berbaring.
Kubiarkan pintu kamarku sedikit terbuka agar aku bisa mendengar suara di luar. Entah ini perasaan yang tumbuh sejak merantau atau tidak, tapi tiap kali sakit aku merasa lebih kesepian. Biasanya aku akan memutar TV lalu tidur, tapi mendengar suara orang memotong di talenan atau suara orang memasak dan mengetahui ada orang bersamaku, itu lebih menenangkan.
Aku hampir saja tertidur ketika Raka datang mengetuk pintu untuk memanggilku makan.
Kami duduk berhadapan dengan bubur hangat dan sepiring pizza miliknya di meja makan. Dia menaburi bawang goreng dan helaian telur dadar di atas bubur. Kutaburi kecap asin sesuai selera, lalu mengaduk bubur ayamnya. Asap panas keluar waktu buburnya kuaduk.
"Enak?" Raka membaca mukaku di suapan pertamaku.
Aku mengangguk. Perutku terasa lebih hangat saat menelannya. Rasa mualnya pun tidak seburuk sebelum minum obat tadi. Lebih-lebih, keinginan makanku mulai muncul dan perutku aman akan bau makanan.
"Sorry," kata Raka merasa bersalah. "Soal perkataanku minggu lalu, itu nggak serius. Aku cuma bersikap picik karena nggak suka diatur macam-macam. Kamu cuma menyampaikan kekhawatiranmu, aku nggak seharusnya bereaksi begitu."
"Nggak. Ini salahku. Seharusnya aku nggak menyimpan di hati, toh benar, ini masalahmu. Aku yang harusnya minta maaf sudah bersikap keras kepala tadi."
"Iya, kamu keras kepala sekali. Aku hampir saja memukulmu pingsan agar kamu berhenti bicara."
"Syukurlah aku berhenti."
Kami tertawa selayaknya percakapan itu, saling minta maaf ini, tidak kami harapkan sepanjang seminggu. Hal lucu tentang membangun sebuah hubungan adalah kamu tidak sadar kalau kamu sudah membangun sebuah hubungan sampai saat kalian bertengkar dan merasa saling tidak bicara itu aneh. Aku senang kami bicara kembali.
Raka menghabiskan pizza-nya hampir satu kotak penuh. Dia membiarkanku mencicipinya sedikit sebelum mengeluh kalau aku seharusnya menghabiskan bubur buatannya kalau masih lapar. Bubur buatannya enak, tidak encer dan bumbunya pas, tapi aku suka sekali pizza.
"Kenapa kamu pulang sendiri? Pacarmu nggak mengantar?" Dia menjilat sisa remahan roti dan saus di ujung jarinya.
"Nggak. Aku nggak bilang ke dia kalau aku kerja sambilan."
Aku memberikannya tisu karena yang dilakukannya itu jorok, kemudian beberapa detik setelahnya aku menyadari yang barusan kubeberkan adalah hal yang ingin kusimpan sendiri.
"Eh, Dirga juga sibuk sama tugas kuliahnya. Kalian kan sejurusan, kok kamu kelihatan santai sekali, sih?" Aku mencoba mengubah jalur percakapan.
"Cuma di beberapa kelas. Aku mengulang beberapa kelas. Kenapa kamu nggak bilang kamu kerja?" Perhatian Raka sama sekali tidak teralihkan.
"Nanti kuberitahu. Kami terlalu sibuk jadi nggak ada kesempatan ketemu."
Aku tidak yakin 'nanti' itu kapan terjadinya. Mungkin saat utangku pada Raka lunas, Raka keluar dari apartemen, atau saat aku menemukan dan pindah ke tempat tinggal baruku. Atau saat semester depan. Atau bahkan tidak perlu sama sekali karena pada waktu mendatang itu, kejadian ini sudah lama lewat masanya. Tidak ada yang peduli dengan cerita sejarah yang tidak punya benda peninggalan. Bekas kehidupan Raka di apartemenku paling menghilang dalam beberapa bulan saja.
"Kalaupun kamu punya kesempatan ketemu, kamu nggak akan bilang. Kutebak, Dirga bahkan nggak tahu aku tinggal bareng kamu."
"Nanti bakal kuceritakan semuanya kok."
"Kata orang, belajarlah dari orang berpengalaman. Menyimpan kebohongan selalu merusak hubungan. Itu fakta. Aku sendiri sudah membuktikannya."
"Kata orang, jangan dengarkan orang yang mempermainkan cewek dan menyalahkan dia atas kesalahannya sendiri," cibirku.
"Orang yang banyak melakukan kesalahan biasanya berubah jadi orang bijak."
"Kalau jadi bijak harus melakukan banyak sekali kesalahan, mending aku nggak usah jadi bijak."
"Ooh. Pantesan," balas Raka, memaklumi.
Aku hampir saja memukul kepalanya karena itu. Coba saja dia bukan seniorku.
Raka membuka kaleng birnya, menyesapnya lamat-lamat sembari menonton TV melewati bahuku. Aku mendengar penonton bersorak di belakang, sepertinya bola masuk di gawang atau meleset masuk karena sorakan penonton berubah sumbang.
"Sebenarnya yang itu salah."
"Yang mana?" Kusuapi lagi satu suap bubur ke mulut.
"Cewek itu, aku nggak mempermainkannya dan menyalahkan dia. Sebenarnya, dia bahkan bukan pacarku." Raka mengambil jeda seolah sedang berpikir ulang. "Dia, pacar papaku."
Aku hampir meludah bubur dalam mulutku ke mangkuk saking kagetnya, untungnya berhasil kutelan. Aku jadinya tersedak dan terbatuk-batuk.
"HUH?" teriakku setelah menelan air.
"Cewek itu pacar papaku." Raka mengulanginya mengira aku tidak dengar. "Dia datang mencariku mengabari kalau mereka akan menikah dan meminta restuku. Tentu saja, aku menolaknya."
"Tapi bukannya dia terlihat sedikit agak ...." Tanganku bergerak melingkar menunjuk wajahnya.
"Muda?" tebak Raka dan dia tahu tebakannya benar. "Papaku bukan orang baik. Dia mengencani banyak wanita, yang tua dan muda. Sepertinya kalau ada cowok yang agak cantik dia akan mengencaninya juga. Nggak heran, mamaku pisah dari dia."
Candaan yang tidak lucu loh, omong-omong, sedikit miris malah. Ini rahasia yang amat sangat buruk untuk diketahui siapa pun, teman atau bukan teman. Kuharap aku punya stok kalimat simpati yang sesuai, tetapi tidak ada. Malahan hening mencekam mendadak terjadi hingga aku berharap kami ada di luar rumah supaya derik jangkrik bisa menggantikanku bicara.
"Kalau saja aku tahu ini ..., astaga, aku malah marah-marah karena itu. Maaf."
Raka menggeleng. "It's okay. Aku sedikit merasa inferior. Lebih mudah bilang dia pacarku dan kami bertengkar, daripada bilang cewek itu membujukku menjadikan dia ibu tiriku."
"Fair enough."
Jeda terjadi lagi. Kali ini agak panjang.
"Apa itu alasanmu kabur dari rumah? Karena kamu nggak tahan sama papamu?" Sedetik kemudian aku menutup mulut, tersadar sesuatu. "Ah. Kamu boleh kok nggak menjawab kalau kamu merasa pertanyaan itu terlalu personal."
"Terlalu personal," dia menekankan, "tapi jawabannya, ya dan nggak juga. Itu salah satu alasannya."
Raka sejenak termenung dengan sedih sampai aku rela sekali menarik pertanyaan itu, tapi dia tetap menjawab.
"Siapa juga yang betah tinggal dengan orang seperti dia? Papaku jarang sekali di rumah. Kalau pun dia di rumah, dia sering sembunyi-sembunyi membawa pacar-pacarnya. Aku lelah menghadapi itu semua jadi aku kabur. Toh, aku punya keluarga yang satu lagi. Keuntungan punya keluarga berantakan, keluargamu jadi ada dua."
"Kedengarannya itu bukan hal tepat untuk dibanggakan."
Raka mengangkat bahu. "Mamaku sudah menikah lagi. Suaminya orang biasa-biasa saja. Cukup baik malah. Dia menawariku periksa gigi gratis kalau aku ke kliniknya. Sore itu, aku datang ke rumah mereka. Kamu tahu apa yang kutemukan?"
"Apa?"
"'Pesta ulang tahun Oma yang ketujuh puluh satu', begitu bunyi papan gabus di panggung halaman belakang waktu aku mengintip. Ada pesta di halaman belakang dan sepertinya hampir bubar karena semua orang nggak lagi duduk makan tapi mereka berdansa. Salah satunya Mama dan dokter gigi itu. Waktu itu Mama tersenyum lebar sekali. Aku nggak pernah lihat dia begitu bahagia. Nggak saat bersama aku, nggak saat bersama Papa, atau dulu saat kami masih bertiga."
Raka adalah orang yang punya kepercayaan diri tinggi, tapi hari ini kulihat kepercayaan dirinya redup beberapa puluh persen. Dia menyembunyikan wajahnya.
"Karena itu menyebalkan, jadi aku kabur saja dan sampailah aku di rumah pantai ini."
Ketika kamu berusaha sedih kamu berusaha sekuat mungkin untuk tidak sedih. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana menyedihkannya mengharapkan sebuah rumah untuk pulang di kala sedih, hanya untuk mendapati bahwa semua tatanan kehidupan di sana telah berubah. Seolah kamu diseret keluar dari kehidupannya dan kamu hanya bagian dari masa lalu. Untuk mendapat masa mendatang yang berbunga, kamu harus melupakannya.
Mamanya Raka bahagia dengan keluarga barunya. Raka tentu tidak ingin merenggut kebahagiaan mamanya itu dengan kedatangannya.
Raka menutup percakapan itu dengan bercanda, "Aku nggak pernah cerita ini ke banyak orang, tapi malah cerita ke kamu yang sama-sama punya masalah. Kisahku sedikit menyedihkan, ya? Kurasa aku cocok jadi cowok pemeran utama yang punya kisah hidup sedih. Nggak heran, aku tampan."
Setelahnya, kami menghabiskan makanan dalam diam. Aku ingin sekali menghiburnya tapi sejujurnya aku tidak tahu harus bicara apa. Papanya berselingkuh, mamanya sudah punya keluarga baru, dan dia kabur dari di rumah ke sini. Kalau kulihat betapa cerianya dia, kukira kehidupannya jauh lebih baik dariku, tak ada yang tahu itu hanya cangkangnya saja.
Ada orang-orang yang pandai membungkus lukanya, ia terlihat seolah dia baik-baik saja ketika ia tidak merasa baik. Meski nampaknya dia sedang mengecoh pandangan orang lain, sebenarnya yang paling ia inginkan adalah agar orang lain membuatnya percaya bahwa dia baik-baik saja.
Raka berdiri di depan wastafel jadi aku menawarkan diri untuk mencuci piring. Dia sudah memasakkanku bubur, jadi tentunya aku yang kebagian tugas cuci piring. Raka malah mengusirku untuk kembali ke kamar. Jadi, kuambil bubuk teh chamomile di dapur punya Maya, lalu merebusnya di dua cangkir air panas. Aku menyodorkan satu cangkir pada Raka saat dia selesai mencuci piring.
Dia berterima kasih dan membawa cangkirnya ke kamar. Sebelum dia masuk ke kamarnya yang ada di seberang kamarku, aku menahannya.
"Makasih soal buburnya, juga soal obat tadi." Aku merujuk kepada sikap keras kepalaku, Raka tidak butuh rujukan lebih lanjut dia langsung mengerti.
"Tadi aku keren kan membawamu ke tempat tidur dan menyuruhmu minum obat?"
"Iya, keren, sampai kamu menyombongkannya."
"Nggak selamanya orang keren bisa selalu keren. Kadang-kadang, mereka harus bersikap seperti orang biasa supaya dianggap sebagai manusia."
Aku melihat kotak makanan di tanganku berisi satu potong pizza yang kata Raka 'untuk berjaga-jaga'. Rasa mual di perutku tidak seburuk tadi.
"Kamu bisa jadi Mama yang baik," kataku.
Dia tersenyum kecil. "Makanya, aku nggak butuh orang tua yang baik."
Senyum kecil yang secara tidak sadar disalurkan ke mukaku, memudar. Aku bisa merasakan bahwa dia sadar candaannya lebih terdengar getir setelah percakapan kami tadi. Bahunya menegang.
"Aku tahu kalau mementingkan kebahagiaan orang kamu sayang itu baik, tapi kurasa ada baiknya juga memberitahu mereka kalau kamu dalam kesulitan. Dia mamamu, dia pasti mengkhawatirkanmu."
Dia mengangkat bahu. "Ya, mungkin." Lalu melepas napas berat. "Kurasa kita masing-masing punya rahasia yang nggak bisa kita katakan dan kita berkumpul di sini. Ini seperti rumah persembunyian para pembohong." Dia menepuk punggungku pelan. "Tapi untunglah nggak ada yang lebih buruk dari ini."
Akibat tepukannya, perutku mendadak bergejolak. Sesuatu benda cair mendesak keluar dari tenggorokanku. Aku muntah di depan kamar Raka. Membuat rumah berbau pantai dan bau kebohongan itu ternodai dengan bau bubur ayam.
****
Gimana menurut kalian chapter ini?
Sudah oleng ke Raka atau masih tetap di kapal Dirga?
Maaf yang nunggu lama, aku lagi belajar buat rutin nulis lagi. Aku usahain nulis per hari biar cepat selesai ini cerita hehe 🙏
Dan untuk para pembaca yang punya akun Cabaca, yuk baca karyaku yang lain di sana
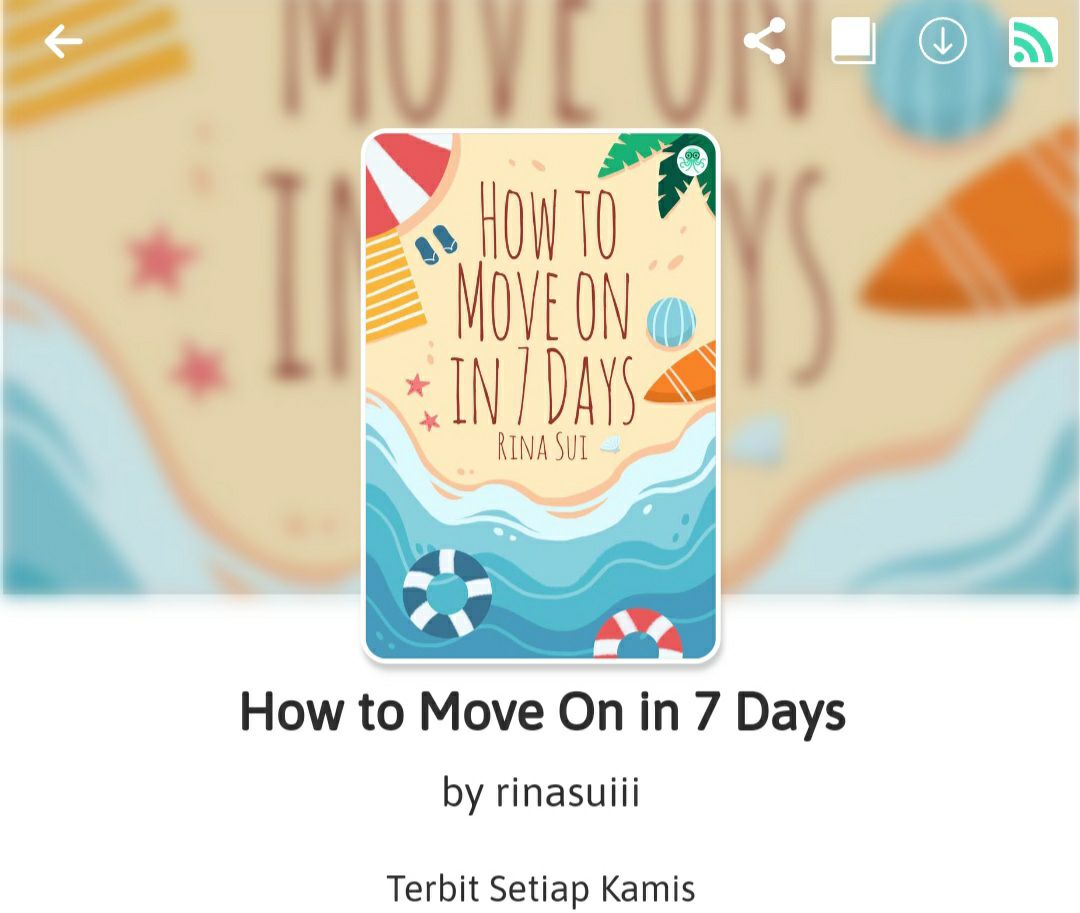
Nama : How to Move On in 7 Days
Terbit : Tiap Kamis
Blurb :
Pamela tidak pernah menyangka commited relationship-nya dengan Patrick akan berakhir di usia tiga tahun. Namun, cincin couple yang Patrick kembalikan di tangannya adalah bukti konkret bahwa semuanya telah berakhir.
Untuk mengobati luka hatinya, Pamela liburan di Bali selama tujuh hari. Di sana, ia bertemu Awan, mahasiswa hukum tampan, yang juga baru saja dilanda patah hati. Serangkaian peristiwa tidak terduga yang mereka alami mengantar keduanya lebih dekat, hingga menelurkan suatu ide unik, yaitu melakukan misi lepas dari patah hati.
Dua orang patah hati. Misi lepas dari patah hati. Tujuh hari. Di Bali.
Bukankah itu kedengaran romantis dan menyenangkan?
Memangnya, ada hal buruk apa lagi yang bisa terjadi di antara dua orang yang terjebak patah hati
Jatuh cinta season 2?
Ceritanya sedikit berbeda dan lebih dewasa dari yang biasa aku tulis.
Tapi aku usahain beri yang terbaik 💪
See you next chapter ! ❤
(2/11/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top