[4] Penjara
[Bagian 4 | 2165 words]

LEMBAP, adalah kata paling cocok untuk mendeskripsikan kondisi tempat ini bersama kata remang dan dingin.
Aku terduduk di kursi besi yang sudah berkarat. Adnan duduk di tempat yang sama, namun di seberangku. Sementara Kiara berdiri, tangannya menggenggam jeruji besi yang mengurung kami.
"Astaga, aku ke sini bukan untuk dipenjara!" serunya hingga membuat tahanan di jeruji seberang kami menatapnya aneh.
Aku menghela napas, bau tanah lembab dan jamur entah apa memasuki hidungku hingga aku mengerutkan wajah, tak suka dengan baunya.
Sekitarku berupa dinding, lantai dan langit-langit batu dengan sebuah obor yang menerangi di dinding. Ada tetesan air dari atas yang membuat lantai tampak berlubang serta menggenang dengan lumut di sudut ruangan. Hanya ada tiga buah bangku besi panjang yang sudah berkarat, sesekali mengalirkan hawa dingin. Aku juga yakin bahwa jeruji besi yang digenggam Kiara juga tak kalah dingin.
Tak ada penjaga di luar. Hanya pantulan cahaya obor yang menerangi lorong di luar. Hening. Hanya ada suara dari geraman salah satu tahanan yang entah mana, tetesan air, dan seruan kesal Kiara.
Di seberangku, Adnan duduk dengan tenangnya seolah kami sedang menunggu pesanan makan. Tanpa disengaja, mata coklatnya bertubrukan denganku. Aku bisa melihat banyak hal yang ingin ia tahu dari matanya itu.
"Tadi kamu ingin bicara apa?" tanyaku yang mendadak ingat dia ingin bicara sesuatu ketika kami ditangkap oleh para penjaga.
Adnan menatapku. "Kamu aneh."
"Apa?"
Seolah memiliki pendapat yang sama, Kiara berbalik. Rupanya ia mendengar percakapan sekilas kami. "Kamu bisa bicara bahasa mereka?"
Aku menatap Kiara yang beranjak duduk di salah satu bangku panjang berkarat, mereka ini bicara apa?
"Maksud kalian apa?"
"Kamu bicara bahasa mereka," ungkap Adnan.
Aku tak mengerti, namun aku mengangguk. "Tentu saja. Justru kalian yang aneh karena tidak mengerti. Mereka bicara begitu lantangnya, kalian tidak mendengar?"
Kiara dan Adnan menatapku tajam. Sebetulnya, apa yang salah dari ucapanku?
"Tentu saja kami tidak mengerti karena bahasanya berbeda." Kiara tampak kesal saat memberi tahuku. "Mereka berkata: Intrus! Le obține!—semacam itu, serta kata lain yang kami tidak mengerti."
"Lalu kamu, dengan anehnya juga ikut bicara bahasa mereka." Kiara memandangku tak percaya.
Aku diam, mencerna perkataan Kiara. Apa maksud mereka sebenarnya? Intrus itu artinya penyusup, le obține artinya tangkap mereka.
Lalu kemudian aku tersadar. Mendadak, wajahku berubah panik. Barusan itu bahasa apa? Aku bicara apa? Dan, mengapa aku mengerti?
"Viona, tenanglah."
"Kamu kenapa?" Kiara menatapku. "Kamu tidak kebelet buang air, kan?
Lalu Kiara mengaduh karena mendapat sebuah jitakan dari Adnan.
"Viona," panggil Adnan lagi.
Aku melamun sejenak, inikah bahasa kedua orang tuaku juga? Jadi apa secara otomatis tanpa mempelajarinya aku sudah bisa?
"Viona," kali ini Kiara memanggil.
Belum sempat aku menjawab, terdengar derap langkah kaki dan kencrengan kunci di kejauhan. Kiara dan Adnan berdiri tegak, aku masih tetap di posisi. Samar, aku mendengar apa yang mereka bicarakan.
"—orang asing. Dua perempuan dan seorang laki-laki. Kami meminta Anda untuk memeriksa bahwa tawanan tidak berbahaya."
"Mengapa kau tidak periksa sendiri saja?"
"Seperti yang saya bilang, Jendral. Mereka begitu asing. Tidak seperti berasal dari kota mana pun."
Aku mendengar percakapan itu semakin dekat bersamaan langkah kaki. Dari dialog, kusimpulkan bahwa ada dua orang. Dan dari suara, kusimpulkan mereka laki-laki.
"Ada yang datang," Adnan memberi tahu.
"Viona, mereka bicara apa?"
Aku mendongak hanya untuk mendapati kedua temanku menatap penuh ingin tahu. Dengan senyum kecil, aku tidak memberitahu dan membiarkan mereka menerka-nerka.
Sampai kedua sosok yang tak kuketahui siapa itu sudah berada di depan jeruji kami. Ada Si Pemimpin tadi, dan seorang pria yang mungkin baru berkepala tiga. Tanpa kuduga, manik hitamnya terpusat padaku.
"Mereka bicara dalam bahasa aneh, tapi salah satunya mengerti bahasa kami, Jen— Jendral? Anda tidak apa?"
Tahu bahwa Sang Jendral terpaku melihatku, Kiara dan Adnan langsung menatapku, lalu menatap Jendral lagi, dan padaku lagi, seolah memastikan. Aku memandang mereka dengan kerutan di dahi, memberitahu bahwa aku juga sama bingungnya.
"Jen—"
"Apa yang kau lakukan?!" seru Sang Jendral membuat kami berjengit. "Itu putri. Putri Viona!"
Aku terkejut karena Sang Jendral memanggilku putri, sedangkan Kiara dan Adnan ikut terkejut sebab Sang Jendral tahu namaku.
Lalu bisa kulihat mata Sang Jendral mulai berkaca saat ini, tapi aku tak yakin. Apa ia hendak menangis?
"Keluarkan mereka."
"Tapi, Jenderal—"
"Keluarkan mereka, ini permintaanku." Sang Jendral menatap Si Pemimpin. "Aku yang bertanggung jawab atas mereka."
Si Pemimpin hendak berkata, namun tertahan. Ia tidak berani membantah Sang Jendral.
"Bawa mereka ke rumahku dengan diam-diam. Aku akan menyusul. Dan yang paling penting," Jendral menatap Si Pemimpin lekat. "Jangan beritahu, Menteri. Paham?"
Si Pemimpin mengangguk.
"Kalian," kata Jendral ke arah kami. "Ikuti dia. Kita perlu bicara."
Setelah itu, Sang Jendral pergi. Meninggalkan kami dengan kening yang berkerut.
"Eh? Dia mengerti bahasa kita?" Kiara juga sama terkejutnya.
Setelah itu, Si Pemimpin yang masih di hadapan kami mulai membuka jeruji besi. Kiara lebih dulu keluar disusul aku dan Adnan. Wajahnya masih menyiratkan kekesalan pada kami.
"Ikuti aku."
Tanpa diminta dua kali, kami bertiga mengikutinya di belakang. Kiara dan Adnan menatapku yang kubalas dengan tatapan tidak tahu juga.
Setelah menaiki tangga, kami keluar dari penjara bawah tanah itu. Di luar, ada sepasang penjaga yang menatap kami dan Si Pemimpin penuh ingin tahu, tapi pemimpinnya itu tak bicara sedikitpun.
Kami terus berjalan di antara rumput semata kaki. Sinar matahari menyorot terik dari atas sana. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan. Untuk sejenak, aku lupa sedang berada di dimensi lain.
Di kejauhan, aku melihat sebuah bangunan yang cukup besar yang tampak seperti peternakan. Dengan pagar biru pendek yang mengelilingi bangunan. Halamannya berantakan karena tumpukan jerami yang tak beraturan. Saat kami masuk, bau kotoran kuda langsung memenuhi hidung.
"Siapkan aku sebuah kereta kuda," kata Si Pemimpin pada salah satu peternak yang sedang mengurusi kuda hitam.
Selagi menunggu, kami bertiga menatap takjub ke sekitar. Bahkan Kiara hingga membuka lebar mulutnya. Ini merupakan kandang kuda. Karena kami tinggal di perkotaan, baru kali ini kami lihat kuda secara langsung.
"Ada dari kalian yang bisa menaiki kuda?"
Aku terkejut ketika Si Pemimpin tahu-tahu bicara ke arah kami, padaku tepatnya. Mendengar ada yang bicara, Kiara dan Adnan menatapku.
"Apa katanya?"
"Ada yang bisa menaiki kuda?" ulangku pada mereka. "Adnan, kami bisa?"
"Ha, aku?" Adnan tersenyum kikuk. "Aku pernah mencobanya sekali. Tapi tidak berakhir bagus."
"Kalau begitu, jangan suruh Adnan," kata Kiara meledek. "Aku tidak mau kita berakhir ke dalam jurang."
"Aku tidak sepayah itu!"
Lalu mereka kembali bertengkar. Aku memutar kedua bola matanya dan kembali menghadap Si Pemimpin. "Tidak ada yang bisa."
Si Pemimpin memberikan pandangan malas dan seperti sudah menduganya. Aku sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan responnya karena tidak ingin memarahi orang itu.
Sebuah kereta kuda pun datang, mengakhiri perdebatan antara Kiara dan Adnan. Mereka menatap takjub, begitu pun denganku. Walau kereta kuda yang ini hanya terbuat dari kayu biasa dan sebuah kuda hitam, tetap saja kami takjub karena tidak pernah menaikinya.
Kiara dan Adnan lebih dulu naik, aku masih berdiri di luar sambil memandang kuda hitam yang (sepertinya) balas memandangku.
Si Pemimpin berdecih. "Apa kalian tidak pernah naik kuda?"
Aku menatapnya dengan senyuman sinis. "Tapi di duniaku kereta kuda sudah kuno."
Si Pemimpin tampak terkejut. "Lalu, apa yang kalian gunakan?"
"Motor, mobil, kereta, bahkan pesawat."
"Apa itu?"
Aku tak menjawab. Biarkan saja ia menerka-nerka.
Kupikir sudah tak ada lagi yang mau ia bicarakan. Maka, aku pun beranjak naik karena Kiara sudah memanggilku sejak tadi. Namun, sebuah suara mencegahku untuk naik.
"Tunggu," suara Si Pemimpin. "Apa kau benar putri? Maksudku, kau anak dari Raja Orthopera dan Ratu Kalyptra?"
Aku tersenyum kecil. "Entahlah. Tapi yang kutahu, itu nama kedua orang tuaku."
"Viona, ayo!"
Tak ingin bicara lebih banyak, aku meninggalkan Si Pemimpin yang tampak terkejut dengan pernyataanku barusan. Lantas menaiki kereta kuda dan duduk bersama kedua temanku.
"Lama sekali," protes Adnan. "Apa yang kamu bicarakan?"
"Hanya basa-basi."
Dari luar, aku mendengar Si Pemimpin berseru, "bawa mereka ke rumah Jendral Ryno," sebelum akhirnya kereta kuda ini berjalan.
Seolah mendapat petunjuk, aku tersenyum tak percaya.
Kami akan ke rumah Jendral Ryno?
※
Setelah setengah jam perjalanan (kurasa), kami sampai di pondok kayu yang berada di belakang bukit. Lingkungannya begitu asri dan menyatu dengan hutan di sekitarnya. Ada cerobong asap di atapnya dan dari sana keluar segumapalan asap.
Kami turun, dengan Kiara yang setengah tersadar —tadi ia tidur. Lantas berdiri di depan pintu pondok, menunggu sang empunya.
Seorang peternak yang membawa kami tadi, mengetuk pintu pondok. Tak lama kemudian, keluarlah seorang cowok yang kuperkirakan seumuran kami. Manik hitamnya agak terkejut melihat ada tamu yang datang ke rumahnya.
"Jendral menyuruh tamunya untuk menunggu di rumah," kata Si Peternak seolah menjelaskan.
Cowok itu mengangguk. Lalu pandangannya ke arah kami. "Silakan masuk."
Si Peternak memberi isyarat pada kami untuk masuk ke pondok. Ia sendiri menaiki kuda, dan berkata, "aku akan kembali jika Jendral menyuruh." Lantas, ia pergi bersama kereta kudanya.
Kami bertiga saling berpandangan, sebelum akhirnya masuk setelah anak Jendral menyuruh untuk kedua kalinya.
Pondok itu tidak terlalu besar, namun minimnya furnitur membuat ruangan tampak lebih luas. Semuanya serba kayu, dan untuk menghidari kemonontonan dari warna coklat, beberapa perabotan dicat dengan warna lain.
Cowok itu mempersilakan untuk duduk. Aku agak khawatir kursi kayu ini rubuh atau apa sebab menimbulkan bunyi deritan kecil saat kududuki. Namun anehnya, kursi kayu itu terasa empuk. Seperti sedang duduk di bantalan kapas.
Adnan berbisik, "kursinya ... empuk."
Dan disusul anggukan Kiara seolah menyetujui.
Si cowok tersenyum. "Kalian ingin minum apa?"
Sebelum ditanyakan oleh kedua temanku, aku lebih dulu mengulanginya, "kalian ingin minum apa?"
Mata Kiara berbinar seolah yang ia dengar barusan adalah kemenangannya dalam undian. "Aku mau kopi."
"Apa dia punya teh hijau?"
"Dan shortcake!" Kiara menambahkan. "Cepat katakan itu padanya, Viona!"
"Kamu pikir ini kafetaria kampus?" sindirku sebelum menghadap anak Jendral lagi. "Apa kau punya kopi dan teh hijau? Dan ... kue?"
Anak Jendral itu terlihat kebingungan, untuk sejenak aku merasa bersalah. Oh, tentu saja yang kupinta tidak ada di sini. Hanya ada di dunia kami.
"Maaf, aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Tapi aku punya air mineral dan sari bunga. Kamu mau?"
Aku mengulangi apa yang ia katakan pada kedua temanku. Dan respon mereka sudah bisa ditebak: mereka mendesah kecewa.
"Tapi sari bunga kedengarannya enak," kata Adnan yang diangguki Kiara.
Aku berdecak sebelum meminta dua sari bunga dan air mineral. Anak Jendral itu pun langsung bergegas pergi mengambil minuman untuk kami.
"Viona, kurasa kamu harus mengajari bahasa mereka."
Aku menoleh. Adnan tampak begitu ingin tahu, tentu saja, Kiara juga. Ah, kedua temanku selalu ingin tahu.
Tak ingin memperpanjang, aku mengangguk saja. "Akan kuajari nanti."
Di sela keheningan, Anak Jendral datang membawa talam berisi tiga minuman dan meletakkannya di meja. Ia tersenyum ramah lantas mempersilahkan untuk meminum.
Kiara dan Adnan berebut untuk mencoba sari bunga-nya. Sementara aku, belum tertarik sama sekali untuk minum. Aku memandang talam sekilas sebelum beralih pada Anak Jendral yang ikut duduk di seberang.
"Omong-omong, namaku Rylo," katanya memulai percakapan. "Kalau boleh tahu, siapa nama kalian?"
Aku agak ragu hanya untuk sekadar memberitahukan nama. Namun mengingat ia Anak Jendral, kurasa tak ada salahnya. Lagipula, ia orang yang sopan.
"Aku Viona, yang tak tahu malu itu namanya Kiara, dan yang selalu bertengkar dengannya namanya Adnan."
Rylo mengangguk-angguk. "Mereka ... pacaran?"
"Kami bertiga sahabat." Aku menoleh pada kedua temanku yang seperti anak kecil. "Mereka suka lupa umur."
"Ah, aku mengerti."
Aku menahan tawa. Bukan karena apa, tapi Rylo tampak serius sekali mendengarkan gurauanku. Masa dia tidak mengerti maksudku sih?
"Apa pendapatmu tentang mereka?" tanyaku ingin tahu.
"Kedua temanmu?" Rylo memastikan yang kutanggapi dengan anggukan. "Kiara cantik, namun begitu cerewet. Adnan ... hebat sekali ia tahan berdebat dengan cewek itu. Dan seperti yang kamu bilang: mereka terlihat lupa umur."
Aku tak sanggup lagi untuk menahan tawa. Maka, meledaklah tawaku yang disusul tawa kecil Rylo. Membuat Kiara dan Adnan terheran-heran melihat kami.
"Apa?" tanya Kiara tak suka. "Kalian menertawakan kami," katanya dengan nada menuduh.
Alih-alih memberitahu, aku lebih memilih untuk mengelak. "Tidak, hanya bertukar lelucon lama." Biarlah pendapat Rylo tentang mereka hanya aku dan ia sendiri yang tahu.
Setelah itu, Adnan berkata bahwa sari bunga-nya sangat enak, begitu manis. Membuatku ikut penasaran seperti apa rasanya dan menyesal tak ikut meminta sari bunga. Namun, Kiara menimpali bahwa rasanya seperti karet. Karet yang manis, lebih tepatnya.
Aku menyampaikan hal itu pada Rylo. Cowok itu tertawa kecil pada keteranganku. Lantas berkata bahwa Kiara jujur sekali. Rylo sendiri tak keberatan minuman buatannya dikritik. Malah, ia menceritakan tanaman apa yang ia gunakan untuk minuman itu.
Dari sana, kami mulai berbincang. Tidak, lebih tepatnya ketiga orang itu, dengan aku sebagai perantara bahasa mereka. Mereka seru sekali hingga aku kesulitan mana yang harus kuterjemahkan lebih dulu. Sebagai respon kewalahan, aku berdecak kesal. Namun, Adnan malah berkata bahwa memang seharusnya aku mengajari mereka.
Sejujurnya, aku sendiri tak kesal. Justru aku merasa senang karena kedua temanku mudah akrab, dan Rylo yang sifatnya ramah. Tak butuh waktu lama, kami terlihat seperti teman lama yang sedang reuni.
Hingga, aku mendengar suara derap langkah kaki kuda di kejauhan. Suara itu bertambah dekat, dan mulai memelan ketika aku yakin bahwa kuda itu ada di depan rumah. Disusul ringkikan kuda yang terdengar dekat sekali. Beberapa detik setelahnya, pintu kayu pondok diketuk dari luar.
Kami bertiga terdiam, sementara Rylo tersenyum. "Itu ayahku yang pulang."
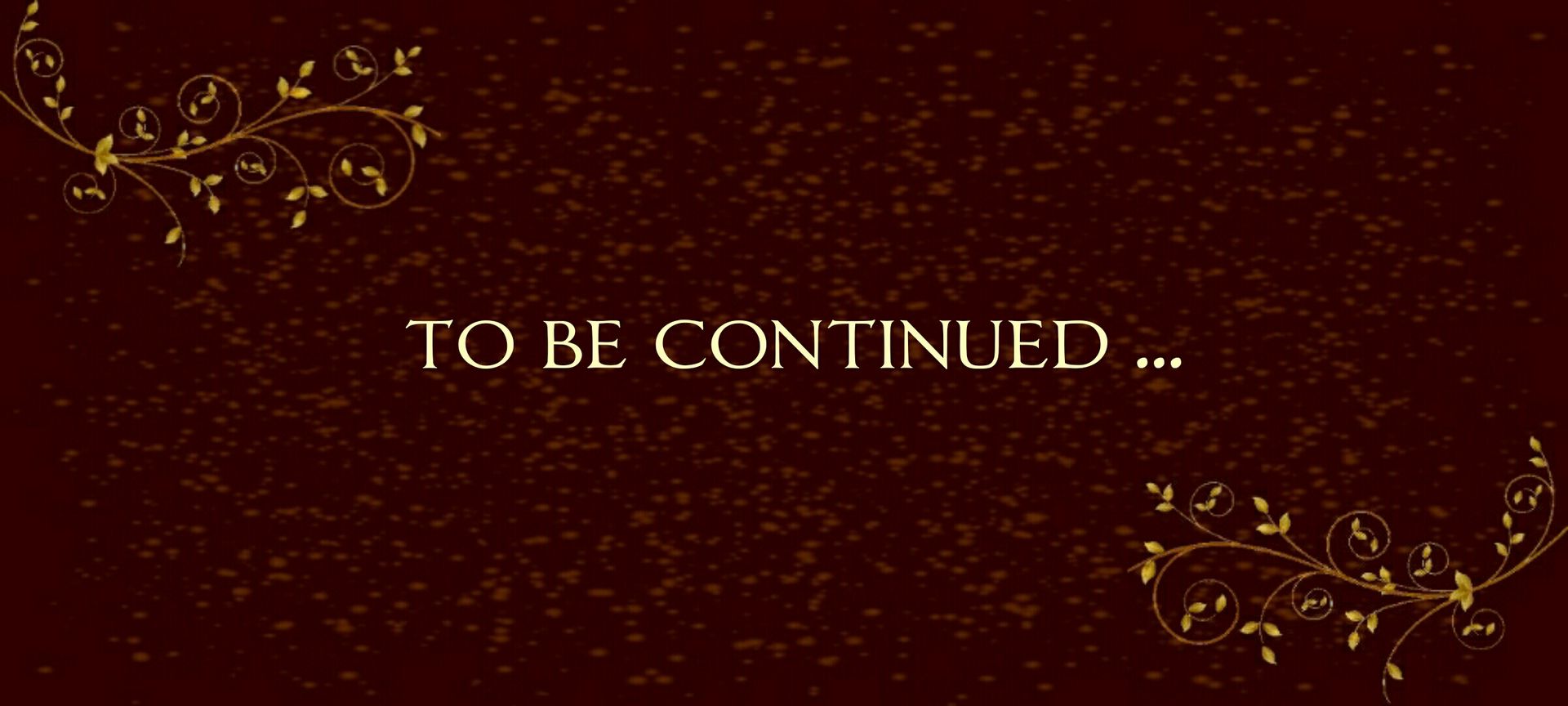
satu jejak kamu, berarti banyak buatku ^^
hai, sorry ya kalau kalian ngerasa bab awal ini kurang seru dan ngebosenin (?). aku tau kok. tapi sudah kuatur outline-nya sedemikian rupa. dan, cerita ini mulai menanjak di bab 6-9, lalu kita akan mulai bertualang di bab 10, tunggu ya!
oh ya karena ini pakai sudut pandang Viona, i want you to know kalau percakapannya aku-kamu itu berarti menggunakan bahasa kita, indonesia. dan kalau berubah jadi aku-kau itu berarti menggunakan bahasa dimensi ini, oke?
aku nggak saltik, tapi memang disengaja.
and last, keep supporting me!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top