[14] Pegunungan Putih
[Bagian 14 | 3157 words]

MELAMUNI telunjuk kini menjelma sebagai rutinitasku.
Aku sudah pasrah dengan eksistensi benang yang bahkan tidak kuketahui kegunaanya. Bodohnya lagi, sejak bangun tidur aku malah terbengong di depan bara api bekas api unggun tadi malam. Beberapa pengawal, Lilan, Kiara, dan Adnan hanya diam saja. Barangkali mereka hendak bertanya namun takut melukai perasaanku. Entahlah. Benang ini membuatku pusing.
Mari kita bicarakan hal lain saja.
Setelah kejadian tidak etis kemarin—yang sangat memalukan apabila Pulau Mov sedang ramai saat itu, aku meminta teman dan para pengawal untuk berkemah kembali dalam hutan. Tentunya setelah mendapat izin lebih jelas dari penjaga benteng yang melakukan pemeriksaan. Aku memutuskan untuk mengirim pesan pada Jendral Ryno sebagai tambahan saran selain ketiga temanku.
Rylo yang mengatur pengirimannya, entah dengan apa. Namun ia bilang, kita harus menunggu setidaknya dua puluh empat jam sebelum pesannya datang. Jadilah kami melanjutkan perkemahan di hutan ini.
Sadar aku sudah terlalu lama melamuni jari telunjuk, aku cepat berganti posisi. Tak ada yang harus kulakukan, kuraih ranting kayu dan menggoreskan ujungnya di tanah. Mendadak aku merasa ingin pulang hanya untuk menggambar menggunakan kertas dan pensil.
Gelondongan kayu di sebelah kiriku terisi, itu Kiara dan Adnan yang membawa sarapan di tangannya. Setelah menatap mereka sekilas, aku kembali pada kerjaan tak bermutuku.
"Kamu ini kenapa?" tanya Adnan sebelum menggigit roti isinya.
"Aku ingin pulang," kataku asal yang langsung dipercayai oleh mereka. "Aku ingin menggambar dengan kertas, bukan tanah dan ranting."
Kiara menggeleng pelan, tampak mengasihiku. "Ironi sekali."
"Pesannya datang."
Suara Rylo yang terdengar tepat di sebelah, berhasil membuat kami bertiga segera menoleh. Atensi aku, Kiara, dan Adnan seketika tertuju pada sebuah gulungan yang dibawanya. Rylo bergabung di gelondongan kayu sebelum memberikan benda itu padaku.
"Kamu saja yang membukanya."
Aku yang memang sudah menunggu benda ini cukup lama, memilih untuk membukanya tanpa berkomentar lebih jauh.
Kira-kira beginilah isi pesan dari Jendral Ryno:
"Kedengarannya sangat serius. Kalau begitu aku bisa apa? Keputusan ada di tanganmu, bukan padaku. Tapi jika kau ingin ke sana, kurasa aku tahu siapa orangnya. Ada kertas lain dalam gulungan, itu alamatnya."
Kening Kiara berkerut, ia menelan gigitan terakhirnya sebelum berkata, "sebentar. Ini berarti maksudnya ayahmu kenal dengan orang yang Fai maksud?" Kiara beralih pada Rylo.
Cowok itu malah mengangkat bahu. "Mungkin begitu. Nah, ini alamatnya."
Aku menerima sobekkan kertas itu yang berisi sebuah nama dan alamat. Bibirku terulas senyum kecil. Ada bibit-bibit keyakinan baru dalam hatiku. Baiklah kalau begitu. Perjalanan ini akan semakin panjang.
"Ayo bergegas," kataku mendadak.
"Apa?" Mereka bertiga mengucapkan hampir bersamaan, pasti terkejut karena aku langsung memutuskan begitu saja.
"Rapikan tenda-tenda," seruku sambil bangkit. "Kita akan melanjutkan perjalanan."
Pengawal yang mendengar perintahku pun bergegas menjalankan perintah. Keadaan yang tadi sempat tenang kini sedikit lebih ramai karena rupanya para pengawal juga sudah tak sabar ingin melanjutkan perjalanan.
Adnan dan Rylo saling berpandangan sejenak, seperti tampak ada yang ingin dikatakan. Namun kedua cowok itu akhirnya juga mengikuti apa yang dilakukan para pengawal lain dan mengemas barang mereka.
Bibirku mengulas senyum kecil, lantas ikut berbalik menuju tenda untuk mengemas barangku.
"Kamu serius ingin meneruskan perjalanan ke Pegunungan Putih?"
Kiara mengikutiku masuk dalam tenda dan bertanya disela kegiatan. Terselip nada keberatan dalam suaranya. Namun kudapati ia malah ikut mengemas barang. Lilan juga ikut membantu, tapi pelayan itu terlalu pendiam jadi lebih sering mendengar percakapan saja. Mungkin karena tak mengerti.
"Tampaknya harus begitu."
Kiara memandangku sejenak dengan bibir yang terlipat ke dalam. Setelah itu, kepalanya mengangguk pelan. Kusadari ada sesuatu yang hendak ia katakan namun hanya ditahannya.
Kegiatan mengemas barang usai tak lama setelahnya. Kami beralih menjadi menanggalkan tenda-tenda, membersihkan hutan bekas tempat kami serta menghapus jejak. Agar hutannya tidak tercemar.
"Bersiap, tujuan kita selanjutnya adalah Pegunungan Putih."
Salah satu pengawal yang sempat berkeliling bersama rekannya berkata bahwa ada dermaga lain di sekitar sini. Tentu itu kabar baik karena kami tidak perlu bersusah payah kembali ke pantai kemarin. Lagipula, dermaga di pantai kemarin terletak jauh dan belum tentu menyediakan banyak sampan. Jadi aku berharap bisa menyewa banyak sampan di sini.
Namun dugaanku salah. Sebab ketika kami semua sampai di sana, dermaga itu tampak sepi dengan kayu tua nan rapuh. Hanya ada empat sampan yang tertambat di dermaga, bahkan keempatnya tampak kurang meyakinkan. Belum lagi tidak cukup karena jika kuhitung dengan kemungkinan orang yang menaikinya, kami kekurangan.
Perhatian kami sontak teralih pada dua orang pengawal tak bersenjata yang datang dari arah lain. Mereka berdua bersedekap, menatap kami lamat-lamat.
"Kami ingin pergi ke Pegunungan Putih." Salah satu pengawal langsung mengutarakan tujuan kami.
Penjaga yang berdiri di sebelah kanan menatap malas lewat helm zirahnya yang terbuka. Aku kembali sadar bahwa ia adalah perempuan dari suaranya.
"Sebanyak ini? Maaf, tapi kami hanya menyewakan dua sampan."
Alisku menukik, dahiku berkerut. "Tapi itu ada empat—"
"Jika kalian ingin tenggelam sebelum sampai, silakan saja pakai. Gratis."
Penjaga yang di sebelah kiri tertawa sarkas. Kepalanya menggeleng dengan tangan terlipat di dada. "Satu sampan bisa berisi lima orang. Pulangkan saja sebagian pengawalmu, jangan seperti anak bayi."
Mendengar ketidaksopanan itu, sontak para pengawal mengacungkan senjata. Wajah mereka mengeras, tampak tak suka. Tapi aku dan Rylo berhasil menahan dan menenangkan mereka untuk tidak ditanggapi terlalu serius.
"Berpikir sebelum ingin menyerang, kalian kalah jumlah."
Ya, salah satu alasan tidak boleh gegabah di negeri orang adalah apa yang baru saja dikatakan oleh penjaga di hadapan kami.
Aku diam sejenak. Jika dipikir-pikir lagi, ucapan penjaga kiri tentang pengawalku memang benar. Ini terlalu banyak. Diriku mengeluhkan hal serupa yang sayangnya tidak berani kuungkapkan secara langsung. Setelah berbagai pertimbangan bersama Kiara, Rylo, serta Adnan, kurasa memang ada baiknya mengurangi jumlah pengawal.
Kuhela napas, akhirnya berbalik menghadap mereka semua. "Maaf, bukan aku tak suka pada kalian, tapi ini sangat mendesak. Aku akan memilih lima di antara kalian—oh, tidak. Rylo yang akan memilihnya," kataku cepat saat melihat mereka semua hendak mengajukan diri. "Sisanya, kalian boleh kembali ke kerajaan."
Riuh mulai terdengar. Mereka berusaha mengajukan diri tapi Rylo sudah memilih. Terlepas dari itu, aku sedikit terharu dengan mereka yang tampak begitu menghormatiku dan ingin menjaga pemimpin mereka.
Atau, mereka mendesak ikut karena belum pernah ke Pegunungan Putih?
Tapi ini bahkan bukan piknik.
"Maaf, Putri," protes salah satu dari mereka. "Tapi kami tidak—"
Aku mengangkat tangan, memutus perkataannya karena aku tahu ke mana ucapan itu tertuju. "Ini perintah, oke? Kalian kembali saja, kami tidak apa, sungguh. Lima pengawal sudah lebih dari cukup."
Sejujurnya kalau bisa, aku ingin memulangkan mereka semua termasuk Lilan. Jadi aku hanya pergi dengan ketiga temanku. Setidaknya aku tidak perlu mencoba 'anggun' setiap saat.
Mereka saling berpandangan, menukar isi kepala masing-masing. Sebelum pembicaraan bertambah panjang dan lama, aku kembali berkata. Keputusanku sudah mutlak. "Kembalilah. Bawa kereta kuda serta, ya? Jika ditanya oleh Jendral Ryno, jawab saja dengan jujur."
Semasih belum bergegas, aku baru teringat sesuatu. Lekas kulepas tas bekalku dan melempar pada mereka sambil berkata, "tangkap. Itu untuk bekal kalian di perjalanan."
Bekalku masih utuh, jika kalian ingin tahu. Lagipula kurasa mereka lebih membutuhkanya sebab perjalanan bukanlah waktu yang sebentar. Mereka tampak terharu membuatku tersenyum kecil.
"Putri ... kau sangat baik," ucap pengawal yang menangkap bekalku. "Kami akan berdoa untuk keselamatanmu."
Setelah acara berpamitan yang agak dramatis dan sosok mereka tak tampak begitu melenggang dalam hutan, aku kembali fokus pada tujuan kami. Kutatap kedua penjaga itu yang memandang kami sambil menguap, kentara sekali kalau mereka bermaksud menyindir.
"Sudah cukup bukan?" tanyaku merujuk pada jumlah kami.
"Ya. Harganya 100 keping emas."
"Apa?" Suara Kiara terdengar. "Kalian yang benar saja."
Penjaga di sebelah kiri menatap Kiara kesal. "Kaupikir membuat sampan bisa bermodalkan daun saja? Ini tidak mudah."
"Tapi itu terlalu mahal. Bahkan tidak sebanding dengan kondisi sampannya."
"Sudah biarkan saja." Aku menengahi sebelum bertambah lama. "Lilan, berikan uangnya."
Lilan mengangguk patuh, ia memberikan koin emas sesuai yang diminta.
Mata kedua penjaga itu tampak berbinar. Wajahnya puas, mereka tersenyum sumringah. "Silakan pakai saja. Mau kalian bawa pulang pun tak apa."
Sementara kedua penjaga itu melenggang dan berencana membagi-bagi koin emas, kami menaiki sampannya. Aku satu sampan dengan Kiara, Lilan, serta dua pengawal lainnya. Sisanya berada di sampan terpisah.
Perlahan sampan yang didayung oleh prajurit kerajaan mulai menjauh di dermaga dan sudah mengapung di lautan lepas tak lama kemudian.
Pagi ini cuaca cukup cerah dengan langit berawan yang menghalau sinar matahari langsung pada kami. Terasa terik, namun angin laut berhasil membuat sejuk. Ombak pun bergelombang pelan, menyebabkan sampan sedikit bergoyang.
Rupanya Pegunungan Putih tak sedekat yang kukira. Saat hari menjelang petang, barulah pulau itu tampak di kejahuan. Kedua mataku terfokus pada pulau dan pegunungan tinggi yang hanya tampak bayangan dari sini. Kurasakan antusias memenuhi diriku. Maka kupinta agar mereka mendayung lebih cepat.
Ketika kami berada dalam radius kira-kira satu kilometer dari dermaga pulau itu, kami mulai merasakan sedikit keanehan. Suhu terasa mulai menurun seiring kami mendekati pulau itu. Sampan menjadi sedikit lebih lamban. Saat kucek, air laut menjadi es tipis yang mulai retak karena kedatangan kami. Hal itu dikonfirmasi sampan Adnan dan Rylo di depan kami. Permukaan esnya semakin menebal, tapi masih bisa dilalui.
Kami tidak bisa mendekati dermaga lebih dekat. Esnya sudah membeku sehingga membuat permukaan air laut menjadi tampak mengkilap dan licin saat dipijak tentunya. Kami semua turun perlahan serta ekstra berhati-hati.
Dermaga yang kini sudah berhasil kami raih juga telah tertutupi salju. Kita sepakat untuk jalan teratur dan membuat jejak di salju yang cukup tinggi itu.
Aku tidak tahu pulau ini ada di angka suhu berapa. Yang jelas, kami mulai kedinginan dengan tingkat suhu di sini. Kulipat bibir ke dalam agar tidak pucat, kedua tanganku saling memeluk. Napasku menguap.
Apakah sebelumnya ada yang bilang kalau pulau ini bersalju? Kenapa aku tidak menyadarinya?
Di saat menyebalkan dengan dingin seperti ini, aku kembali teringat dengan benang emas di tangan.
Halo, Benang. Apa kamu bisa melakukan sesuatu untuk kami yang kedinginan?
Tentu tak terjadi apa-apa.
Daripada kesal lebih lanjut perhatianku tertuju pada Lilan yang tampak sangat kedinginan. Kulitnya memerah. Ia tampak menggigil.
"Apa kau baik-baik saja?"
Pertanyaan yang sangat bodoh, Viona.
Lilan menggeleng pelan. "A-aku punya pengalaman buruk dengan dingin. Maaf, Putri, aku merepotkan."
Aku dan Kiara bantu memapah gadis yang mungkin lebih muda dari kami. Ia gemetar, bibirnya bergerak pucat. Saat kuperhatikan, bukan hanya Lilan. Tapi kami semua.
Aku semakin merasa bodoh saat sadar kami malah menggunakan baju biasa ke sini. Harusnya kami menyiapkan baju hangat. Namun bagaimana harus menyiapkan jika aku saja tidak tahu sebelumnya?
Ketika kami berhasil menjauh dari dermaga, hari mulai gelap. Entah perasaanku atau apa, tapi suhu sepertinya kembali menurun. Belasan bintik-bintik putih perlahan jatuh dari langit. Oh, tidak. Aku punya firasat buruk untuk ini.
"Kita harus ke mana setelah ini, Viona?" Adnan bertanya.
"Kau punya peta?" timpal Rylo.
"Aku tidak tahu, dan aku tidak punya," kataku jujur. "Aku hanya berbekal kertas alamat dari ayahmu."
"Dan kita harus mencarinya ketika kini mulai gelap dan badai akan datang? Di sini tidak ada orang sama sekali. Bagaimana kita akan mencarinya?"
"Aku tidak tahu." Aku sedikit meninggi. " Oke, ini semua salahku. Tapi aku bahkan tidak tahu kalau kita akan menghadapi pulau seperti ini."
Kiara diam, dan kedua temanku yang lainnya. Mendadak aku merasa sesak sebab pasti mereka kecewa padaku yang tak memiliki persiapan apa pun.
Tiba-tiba di kejauhan, aku mendengar sebuah gerombolan langkah kaki yang sepertinya menuju pada kami. Kurasa bukan hanya aku yang mendengarnya, sebab yang lainnya juga ikut menoleh.
Aku tidak tahu harus menyebut ini anugrah atau kesialan. Anugrah sebab banyak orang yang datang, mungkin hendak menolong (?). Sial karena mereka membawa obor dan tombak beramai-ramai. Aku terpaku.
"Siapa kalian?"
Habis sudah.
Salah satu dari gerombolan yang membawa tombak maju. Ia bersiaga, tapi tidak mengacungkan senjatanya. "Dari mana asal kalian?"
Teman-temanku menoleh padaku. Aku meneguk ludah. Ayo, Viona. Sekarang bukan waktunya untuk takut.
"Tenang. Kami datang dari Kota Goldey."
"Kota Goldey? Kalian dari kerajaan?" Alis pria di hadapanku menukik tajam, disusul raut tak suka dari orang-orang di belakangnya.
Aku menjadk ragu sejenak, takut salah bicara. Kemudian kuputuskan untuk jujur saja. "Ya."
Dan yang terjadi di luar dugaanku. Alih-alih sambutan hangat, mereka justru berseru.
"Bawa mereka!"
Apa-apaan?!
Mereka yang tentunya jauh lebih sigap dari kami langsung bisa menangkap kami. Agak tidak adil sebab kami sedang dalam kondisi kedinginan dan tidak baik.
Gerimis salju yang mulai memutihkan rambutku mulai bertambah deras. Disusul hembusan angin yang sangat dingin. Sepertinya benar-benar akan ada badai.
Kami pasrah saja ketika dibawa walau sebetulnya aku bisa memberontak dan melawan, tapi kurasa itu hanya menghabiskan tenaga. Lagipula, jika kami ditahan bukankah tempatnya pasti jauh lebih hangat.
Orang-orang bertubuh besar yang membawa kami ini tampak santai saja saat menyeret begitu mudahnya. Sementara aku menjadi iri hanya karena ia menggunakan baju yang lebih tebal. Aku menghela napas kasar, menciptakan uap.
"Setidaknya beri kami kain atau apalah," kataku keras untuk menyaingi hembusan angin yang semakin ganas. "Kau tentu tidak mau tahanan-mu ini mati sebelum sampai di penjara bukan?"
Pria yang membawaku malah mendengkuskan tawa. Badannya besar dengan langkah lebar yang memijak salju dengan yakin. Sementara aku terseok berjalan di sampingnya, setengah terseret. Aku sempat berpikiran kalau orang ini kuat menggendongku bersama Kiara sampai ditujuan.
"Siapa yang mau memenjarakan kalian?"
Eh?
"Lantas apa? Membiarkan kami mati kedinginan sebelum sampai di tujuan?"
Satu sudut bibirnya terangkat. "Begitulah."
Aku mengumpat.
Setelah berjalan—tidak, lebih tepatnya terseret sepanjang perjalanan, kami sepertinya mulai memasuki pemukiman. Terbukti dari adanya rumah-rumah jerami yang atapnya tertutup salju dan mengepul asap dari cerobongnya. Lampu-lampu menyala menerangi jalan bersalju.
Yang kutahu langit lebih gelap dari sebelumnya beserta badai yang mungkin sebentar lagi akan terjadi. Aku memang kedinginan dan rasanya tubuhku seperti ada dalam lemari pembeku. Tapi hebatnya aku masih bertahan dan terjaga. Karena saat aku menoleh, hanya Rylo yang masih berusaha menjaga kesadarannya.
Melihat itu aku menjadi kesal. "Bisakan kalian percepat jalan kalian? Teman-temanku bisa mati kedinginan!" Padahal aku sendiri dalam kondisi yang sama.
"Kau kira mudah jalan di tumpukan salju?" tanyanya ketus. "Bangunan itu tujuan kita."
Aku menoleh ke depan, dan mendapati sebuah bangunan besar tampak seperti penginapan tua yang terbuat dari kayu. Hatiku seketika merasa lega. Hangat dari bangunan itu bahkan terasa sampai sini.
Kakiku yang terasa membeku mulai menghangat ketika kami masuk ke dalamnya. Koridor bangunan itu dipenuhi obor yang terang, baru seperti ini saja aku sudah bisa kembali bangkit dan berjalan pelan.
Kami diarahkan ke dalam sebuah ruangan besar dengan sofa, rak buku, dan sebuah perapian yang menyala. Aku tidak tahu harus berterimakasih atau kesal pada orang-orang yang telah membawa kami. Jadi aku diam saja.
"Kalian di sini dulu. Urusan kalian dengan kami belum selesai."
Pintu ditutup kasar setelahnya.
Aku tidak punya waktu untuk mengomentari hal tidak sopan itu. Karena selanjutnya kudapati diriku malah terduduk nikmat di depan perapian. Hangatnya benar-benar menghilangkan segala dingin di tubuhku.
Selepas menikmati hangat perapian, aku beralih pada Kiara yang terduduk lemas di lantai kayu. Matanya terpejam. Pipinya yang dingin mulai terasa menghangat. Kurasa pingsannya mulai beralih menjadi tidur.
"Kiara, bangun."
Aku menggoyangkan pelan bahunya hingga mata Kiara perlahan terbuka. Ia menguap sambil mengulet. Katanya, "sejak kapan kita ada di rumah?"
"Kita masih di Pegunungan Putih."
Sontak matanya membelalak. Kiara baru benar-benar memperhatikan sekitar dan agak terkejut berada di tempat ini dengan perapian.
"Orang-orang itu yang membawa kita."
"Benarkah?" Kiara sama terkejutnya denganku. "Tapi kenapa?"
Aku mengangkat bahu. "Kamu pingsan tadi. Mungkin mereka membawa kita ke sini karena wajah pingsan dan sekaratmu berhasil meluluhkan mereka."
"Viona!"
Aku tertawa kecil. "Aku bercanda. Entahlah, aku juga tidak tahu."
Di tengah kami yang mulai kembali sadar sepenuhnya dan sudah merasa lebih baik, pintu ruangan terbuka.
Seorang wanita tua yang rambutnya sudah memutih tampak bersama orang-orang tadi di belakangnya. Aku dan lainnya sontak langsung bangkit. Wanita itu duduk di sofa satu jok yang menghadap ke arahku. Wajahnya sedikit kurang ramah. Orang-orang yang berdiri di belakangnya memasang wajah datar.
"Mana pemimpin kalian? Duduk di sana," katanya tegas dan lantang.
Aku dan Kiara saling berpandangan sebelum duduk di sofa yang wanita itu maksud. Adnan dan Rylo berada di kursi terpisah.
"Untuk para prajurit dan pelayan, tolong tinggalkan kami sendiri."
Pria yang tadi membawaku menunduk sopan pada wanita tua itu. "Baik, Fe."
Kelima prajurit dan Lilan menoleh ke arahku, meminta persetujuan. Aku mengangguk kecil sebagai pertanda menyuruh mereka untuk melaksanakan apa kata Fe itu.
Ketika pintu ruangan itu tertutup dan tak ada orang lagi selain Fe dan kami berempat, suasanya hening sejenak. Di momen itu hanya terdengar retihan kayu yang terbakar di perapian dan hawa hangat yang mengalir di ruangan ini.
"Langsung saja, karena aku tidak suka berbasa-basi," kata Fe tiba-tiba yang hampir membuatku berjengit. "Apa tujuan kalian ke sini? Kalau boleh jujur, kami agak terganggu dengan kedatangan kaliam. Kami tidak menyukai tamu kerajaan."
Fakta itu membuatku serta ketiga temanku terkejut. Mengapa kau tidak menyukai tamu kerajaan? Aku bisa saja bertanya begitu, tapi aku pun sama halnya tidak ingin berbasa-basi.
"Kami mencari seseorang."
"Jelaskan lebih spesifik," balas Fe.
"Seorang perempuan. Dengan iris ungu."
Wajah wanita itu tampak terkejut untuk setengah detik sebelum kembali datar dan tegas. "Namanya?"
Aku mengambil kertas sobekan dari Jendral Ryno, membaca sebuah nama di sana. "El ... Elvalyn R. Candelaria."
"Darimana kalian tahu nama itu?"
"Dari seseorang yang kami kenal."
Fe menghela napas pelan dan diam sebentar. Menciptakan jeda hening yang cukup lama. Kami saling berpandangan.
"Jadi, di mana El—Elva-Eval ini?" tanya Adnan. Kentara sekali ia melupakan serta kesulitan melafalkan nama itu.
"Ada urusan apa kalian dengannya?"
"Ada sesuatu pribadi yang harus dibicarakan," jawabku. "Haruskah aku memberitahumu juga?"
Fe menggeleng. "Aku tidak tertarik dengan urusan kerajaanmu."
Selepas itu, Fe menepuk tangan tiga kali sambil memanggil sebuah nama. Pria yang tadi muncul dan tampaknya ia adalah seseorang kepercayaan Fe ini.
"Ada apa, Fe?"
"Panggil gadis ungu itu ke sini. Katakan ada yang menemuinya."
Pria itu menunduk sopan sebelum keluar dari ruangan.
"Kalian dari Kota Goldey?" tanyanya lagi.
"Ya."
"Apa kalian sama sekali tidak kenal siapa Elva?"
Kami saling berpandangan. Seingatku aku tidak mengenalnya, begitupun Rylo saat kutanya.
"Tidakkah kalian penasaran mengapa gadis ungu itu ada di sini alih-alih berada di Pulau Benteng itu?"
Maksudnya Pulau Mov?
Aku pun baru tersadar. Benar juga. Seharusnya ia berada di Pulau Ungu itu.
Kiara menggeleng. "Memangnya semua gadis beriris ungu harus tinggal di sana? Kalau iya, mengapa ia tidak?"
"Kalian benar-benar tidak tahu rupanya," gumam Fe sambil menggeleng pelan. "Biar kuceritakan sedikit. Semua gadis beriris ungu memang seharusnya tinggal di sana, tentu untuk melatih bakatnya. Sementara Eva—"
"Elva," koreksi Kiara.
"Ya, dia. Sementara gadis itu tidak karena—"
Ucapan Fe menjadi terpotong karena pintu ruangan kembali terbuka. Perhatian kami seketika terarah pada pria tadi yang kembali bersama seorang remaja sebaya kami.
Aku bisa merasakan kami berempat yang terpaku saat melihat gadis itu.
"Orang dari kerajaan mana yang ingin menemuiku?"
Ia memiliki kulit putih pucat yang hampir senada dengan rambutnya. Bagian bawah rambutnya sedikit bergelombang dengan warna merah jambu. Hidungnya mancung dengan bibir tipis yang bewarna cerah. Matanya yang sipit dan beriris ungu tearah pada kami. Ia hanya menatap kami biasa, namun jangankan Adnan dan Rylo, aku dan Kiara yang perempuan saja terpana menatapnya.
"Oh, kalian." Ia tersenyum tipis.
Ini hanya dugaanku saja, atau semua gadis beriris ungu memang secantik ini?
"Lama tak berjumpa, Marcia."
Aku mematung.
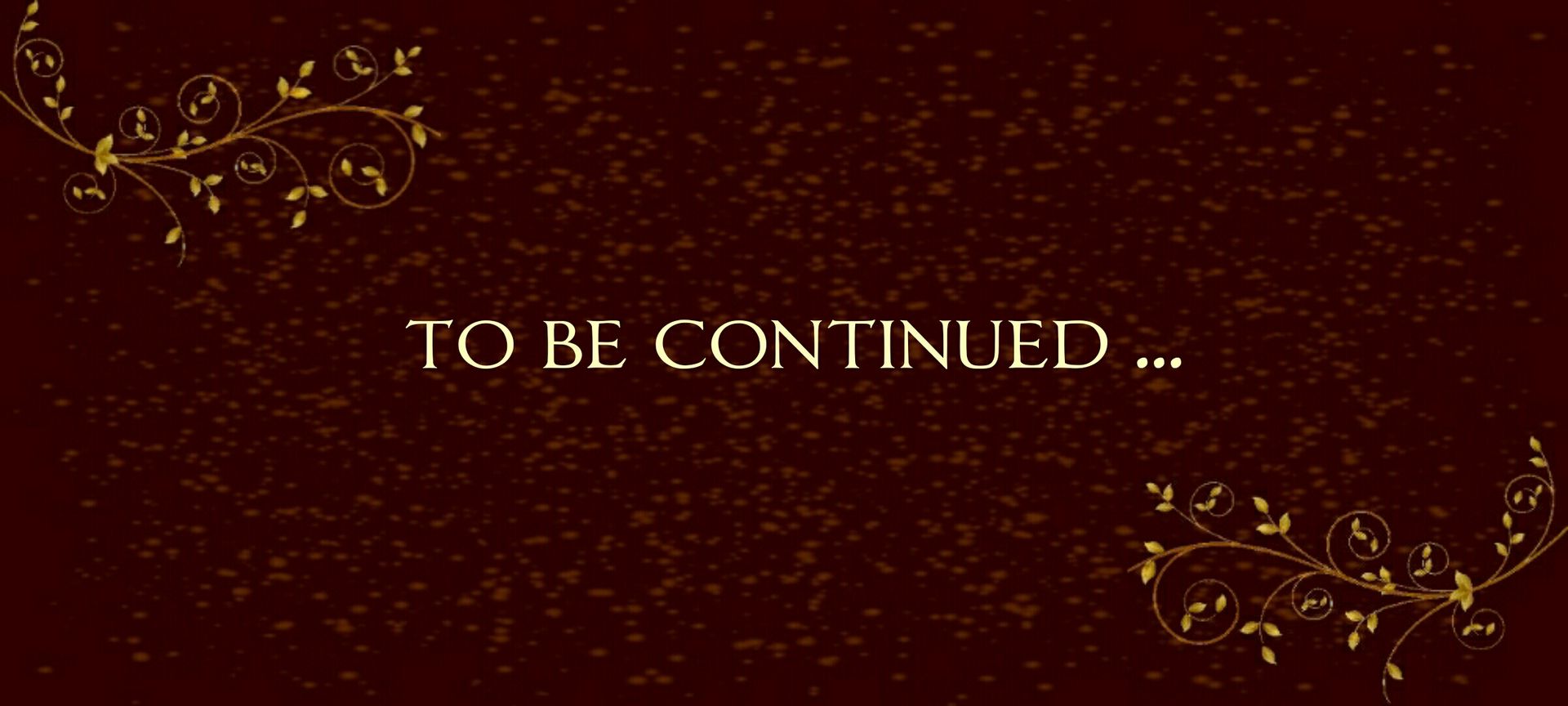
satu jejak kamu, berarti banyak buatku ^^
hah, gimana gimana? k-kok dia kenal Viona?
dan kenapa sejak kemarin Viona dipanggil dengan nama depannya; Marcia?
eh btw, aku kaget banget liat bab ini sampe 3000+ kata 😭
kirain chapter sebelumnya yang terbanyak, tapi ternyata bagian ini memecahkan rekor :')
jangan bosen dulu ya sama cerita ini, sebagian rahasianya bahkan belum terungkap 😭
masih ada di perpustakaan kalian kan? :')
vomentnya dong ★
keep supporting me!
- udah bisa apload pict deng, wkwk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top