27. Reuni Maya

Gadis muda itu berdiri sendirian di tengah padang bunga daisy putih. Angin sepoi-sepoi membuai ujung pakaiannya, sehelai gaun musim panas berenda yang tipis dan ringan. Warnanya putih, seputih bunga-bunga kecil di sekitar kakinya. Dengan mata birunya gadis itu memandang jauh. Sepanjang mata memandang, hanya rumpun daisy belaka yang membentang hingga pegunungan di kejauhan.
Beberapa puluh meter di hadapan Scarlet, sebuah pondok berdinding batu berdiri. Jemuran melambai-lambai di halamannya, asap keluar dari cerobongnya. Hati gadis itu menghangat. Dulu sekali, ketika ayahnya masih ada di dunia, pondok itu pernah menjadi rumahnya. Hanya, ia tak mengenali sekelilingnya. Ia pun tak ingat bagaimana ia sampai ke sana. Bila memorinya benar, pondok pertanian itu harusnya sudah terjual tak lama setelah ia dan ibunya pindah ke rumah kecil di pusat desa.
Di mana aku? batinnya.
Scarlet Dixon memejamkan mata, mencoba memutar ulang memorinya. Potongan-potongan adegan bermunculan, samar bagai mimpi yang sirna begitu insan terjaga. Sampai di titik ketika harum ganjil itu tercium, ingatan itu berhenti. Segalanya gelap, hingga ia tiba-tiba berada di padang bunga itu.
Apakah ini rasanya mati?
Tentu saja Scarlet tidak punya jawaban. Maka, tanpa suara, Scarlet melangkah mendatangi pondok itu. Sayup-sayup, suara cekikik garis kecil terdengar, ditingkahi tawa berat seorang pria.
“Lebih tinggi lagi, Pa! Lebih tinggi!”
Hati-hati Scarlet mengintip ke dalam. Interior rumah itu masih persis seperti yang ia ingat. Di ruang tengah, seorang pria dan seorang gadis kecil bercengkerama. Pria itu mengangkat si gadis kecil, menggendongnya berputar-putar. Seperti burung anak itu merentangkan tangan. Tiada hiasan cantik atau makanan mewah di rumah itu. Namun, tawa dan cinta para penghuninya penuh melimpah, memenuhi rumah itu dengan kehangatan.
“Scarlet, biarkan papamu istirahat! Ia pasti masih capek setelah seharian di ladang.” Sebuah suara lain terdengar. Amelia Dixon keluar dari dapur. Di tangannya ada pai daging cincang, makanan spesial kesukaan Scarlet.
Seketika, air mata Scarlet meremang. Betapa muda dan bahagianya ibunya dulu! Kini, bisa ia lihat mengapa ibunya selalu bilang bahwa ia mirip ayahnya. Rambut lurus berwarna cokelat, hidung mancung, dan mata laksana samudera yang tenang. Semua itu telah diwariskan padanya. Gadis kecil yang tertawa itu dirinya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Ah, Scarlet tak pernah menyadari betapa rindu dirinya pada masa-masa itu. Benar kata orang, ketidaktahuan sering kali bersinonim dengan kedamaian.
Sekonyong-konyong, ayahnya mendudukkan Scarlet kecil di kursi, lalu berjalan keluar. Gadis itu kelabakan. Tidak ada tempat sembunyi di sana. Selangkah, dua langkah, perlahan gadis itu mundur kembali ke padang daisy. Rindu, bingung, sedih, dan marah jadi satu dalam benak. Betapa pun separuh dirinya ingin memaki-maki sosok yang bertanggung jawab atas nasib kacaunya, separuh yang lain mengharap untuk memeluk pria itu, yang selalu memberinya kasih sayang apa adanya.
“Kau tidak seharusnya ada di sini, Scarlet.” Eustace Dixon berujar sedih. Pria itu hendak mendekat, tetapi Scarlet cepat-cepat melangkah mundur.
“Aku tahu,” ujar gadis itu kaku. “Aku juga tahu bahwa Papa pergi meninggalkan kami tanpa sepatah kata pun. Setidaknya Papa bisa meninggalkan suatu ucapan perpisahan, kan? Biar setidaknya aku tahu kalau Papa benar-benar menyayangi Mama dan aku.”
“Papa memang salah.” Lelaki itu mendekat, tangan kanannya terulur. "Tidak seharusnya makhluk seperti Papa berani berharap untuk memiliki sebuah keluarga dengan istri manusia. Dengan pongahnya Papa berpikir dapat lari dari jati diri Papa sebenarnya. Gara-gara itu, kaulah yang jadi korbannya. Maaf, tidak seharusnya Papa menikahi mamamu dan menyebabkanmu terlahir di dunia. Kau tak kuasa menolak jati dirimu, tetapi kau mengalami banyak kesulitan karenanya.”
“Bagaimana Papa tahu?” Scarlet mengangkat alis. Alih-alih penasaran, nada sinis terdengar dalam suaranya. Ada keheningan yang lama sebelum Eustace Dixon kembali menjawab. Seulas senyum merekah pada wajahnya yang sendu. Senyum yang selalu diberikannya setelah dongeng pengantar tidur dalam fragmen-fragmen yang tersisa dari ingatan masa kecil Scarlet.
“Papa selalu mengawasi kalian, Scarlet. Walau Papa tidak bisa lagi muncul di hadapan kalian, Papa tahu apa yang kaualami. Papa tahu kau terpaksa membunuh nenekmu, Papa tahu kau mengalami kesulitan di desa karena kau setengah werewolf.” Jarak antara Eustace dan Scarlet hanya beberapa puluh sentimeter sekarang. Tanpa sadar, Scarlet mematung. Napasnya tertahan. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya tulus, tanpa kepalsuan.
Tidak, hentikan. Jangan bersikap sayang padaku. Dada Scarlet rasanya akan meledak. Seharusnya aku membencimu.
Pedas mata Scarlet menahan tangis. Tangannya mencengkeram gaun kuat-kuat. Tak bisa ia menahan diri lebih lama lagi. Gadis itu menghambur, membenamkan kepalanya pada bahu lelaki itu. Ia lepaskan semua prasangka negative jauh-jauh. Perlahan, tangan Eustace merengkuh tubuh putrinya. Dalam senyap pasangan ayah dan anak itu berpelukan, melepas segala rindu yang terpendam.
Waktu Scarlet mengangkat muka, didapatinya rumah dan padang daisy telah sirna. Sebagai gantinya ada kekosongan, putih membentang.
“Tempat apa ini, Pa?” Scarlet melihat ke sekelilingnya.
“Alam pikiranmu, sama seperti tadi.” Ayahnya menjawab penuh arti. “Aku tahu kau merasa tidak berdaya mengontrol dirimu sendiri. Papa pun dulu begitu, hingga Papa mengetahui bahwa tidak ada teknik rahasia. Semuanya tergantung pada dirimu. Bila kau tidak membiarkan sisi werewolf dalam dirimu lepas dan liar, maka ia akan mendengarkanmu. Namun, untuk itu, kau harus terlebih dahulu menerimanya. Alih-alih sebuah kelainan, ia adalah senjata. Gunakan kemampuan itu dengan bertanggung jawab sebagaimana yang telah kaulakukan dengan kapakmu, dan kau akan baik-baik saja.”
Tentu itu bukan analogi yang sempurna, tetapi Scarlet mengerti maksud ayahnya. Mendadak, tak lagi ia merasa sendiri. Ayahnya benar. Apa yang ia alami sekarang telah lebih dulu dialami ayahnya, serta para pendahulunya sepanjang sejarah. Kemampuan yang ia miliki telah sekali menyelamatkan nyawanya, tetapi ia malah menganggapnya sebagai alasan untuk mengasihani diri. Bukannya menerima, ia malah berusaha meniadakan kemampuan itu, yang sebenarnya juga adalah bagian dari dirinya.
“Aku akan berusaha sebaik mungkin, Pa.” Scarlet mengangguk. Perlahan, suasana di sekeling mereka berubah. Angin sepoi-sepoi berembus dari belakang Scarlet, membawa serta suara-suara yang samar. Rupanya, hal itu juga disadari ayahnya. Lelaki itu melepaskan pelukan, lalu menggenggam kedua belah tangan putrinya.
“Sudah waktumu untuk kembali,” ujarnya. “Aku tahu kau pasti bisa melakukannya, Scarlet. Mungkin kau belum menyadarinya sekarang, tapi kau jauh lebih kuat daripada yang kausangka.”
“Tidak bisakah aku di sini sedikit lebih lama lagi?” Scarlet menoleh ke belakang. Lagi-lagi, hanya kekosongan yang ada sejauh mata memandang. Hanya, suara-suara itu makin kencang terdengar. Kini, gadis itu mulai dapat menangkap kata-katanya.
“Scar ... let ....”
“Scarlet ... bangun ....”
Gadis itu terkejut. Itu suara teman-temannya! Panggilan panik Sal yang pertama terdengar, disusul seruan Sean. Sesaat ia menunggu, tetapi suara Sawyer dan Seneca tak kunjung menyusul. Gadis itu ingat semuanya. Ia mengingat pertarungan yang sedang mereka jalani. Seketika, rasa khawatir menjalari benaknya. Apa Sawyer dan Seneca baik-baik saja? Apakah mereka bahkan masih hidup? Melihat perubahan ekspresi wajah putrinya, Eustace Dixon mengedikkan kepala.
“Mereka membutuhkanmu saat ini, Scarlet,” ujar pria itu. “Cepat, pergilah.”
“Apa aku bisa bertemu dengan Papa lagi?” tanya gadis itu lirih.
“Pasti.” Ayahnya mengangguk. “Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti Papa akan menemuimu.”
Scarlet menghela napas panjang. Meski masih berat hatinya untuk pergi, lagi-lagi ia mengakui perkataan ayahnya benar. Maka, ia lepaskan genggaman tangan ayahnya. Untuk terakhir kali, diusapnya sisa air mata dari wajah. Perlahan senyumnya merekah. Lalu, diiringi lambaian tangan, gadis itu berbalik.
Tak sedikit pun ia menoleh ke belakang. Makin lama, makin cepat langkahnya. Kembali pemandangan berubah. Kegelapan turun, dan pemandangan hutan yang sangat ia kenal pun nampaklah. Di ujung jalan, tampak cahaya putih. Gadis itu membulatkan tekad. Sambil berlari, ia ulurkan tangan kanannya. Sinar terang segera melingkupinya begitu jarinya bersentuhan dengan cahaya, menariknya kembali ke alam nyata.
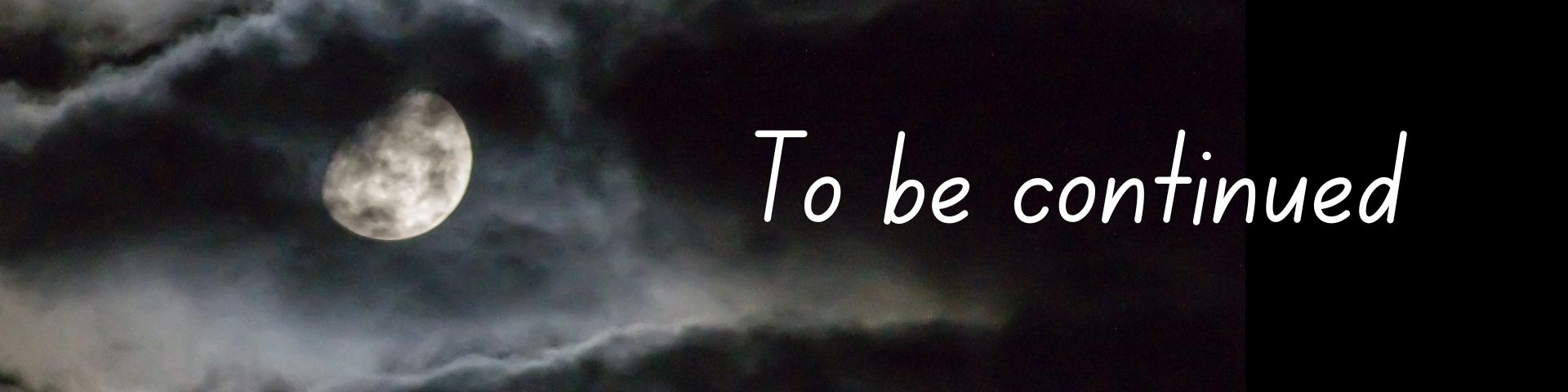
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top