12. Kunjungan
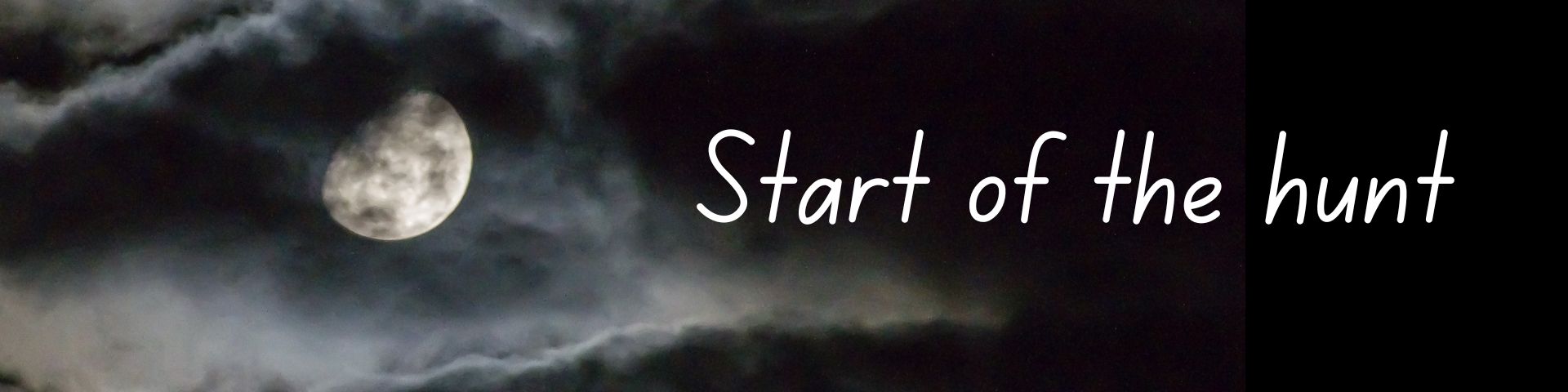
Sinar matahari lembut menembus tirai putih kamar di loteng klinik Desa Chartain, lalu jatuh menerangi figur seorang gadis muda yang sedang duduk membaca di atas sebuah sofa tunggal berlapis beludru merah. Sesekali ia mengangkat kepala, lalu menyibakkan tirai itu hingga menampakkan pemandangan di baliknya. Pagi itu, jalan utama Desa Chartain terlihat sama seperti biasanya. Orang dan kuda lalu-lalang, para pedagang berseru-seru di depan toko, para ibu membeli barang kebutuhan, serta anak-anak bermain-main.
Hanya satu hal yang berubah, yaitu jati dirinya.
Scarlet termenung. Kemarin malam, sudah ia dengar hasil keputusan rapat warga. Sejujurnya, ia tak keberatan seandainya mereka mengusirnya. Gadis itu yakin, andaikata ia adalah manusia biasa, dan orang lain dari kelompok pemburu yang ternyata adalah makhluk setengah werewolf, ia pasti akan ada di garda depan untuk mengusirnya. Ah, betapa Takdir memang sosok yang ironis! Sekarang, bagaimana ia harus menghadapi teman-temannya?
Agaknya semesta mendengar seruan hati Scarlet, dan memutuskan mengerjainya sekali lagi. Baru saja gadis itu kembali membuka buku, terdengar ketukan di pintu kamar. Gadis itu meletakkan bukunya, lalu bangkit dan pergi ke pintu.
“Scarlet, kau masih bangun? Seneca ingin bertemu denganmu.” Suara Sal terdengar dari balik pintu. Oh, hebat, keluh Scarlet dalam hati. Dari daftar orang-orang yang paling tidak ingin ia temui sekarang, pria itu bertengger di posisi teratas. Mengherankan memang, karena Seneca juga menempati posisi tertinggi pada daftar orang-orang yang dirindukannya. Masalahnya, setelah mendengar kesulitan yang dihadapi Seneca dalam pertemuan warga, Scarlet jadi merasa bersalah. Ia tak tahu harus berkata apa pada lelaki itu.
“Tunggu sebentar, aku akan merapikan diri,” ujar Scarlet pada akhirnya. Disisirnya rambutnya secepat yang ia bisa lakukan dengan satu tangan, lalu dirapikannya pakaiannya. Setelah puas dengan penampilannya, barulah ia buka pintu dari kayu pinus itu.
“Hei,” sapa Seneca canggung. Ia berdiri bersandar di dinding, kedua tangan dalam saku celana. Dengan gerakan kepala ia memberi isyarat pada Sal, yang langsung menyingkir seperti kucing yang diusir.
“Um, aku akan mengurus persediaan obat-obatanku di bawah.” Sal buru-buru menyelinap turun. Setelah pria itu hilang dari pandangan, Seneca berbalik menatap Scarlet.
“Jadi, boleh aku masuk?” Ia mengedikkan kepala. Tanpa suara Scarlet mengangguk, lalu menyingkir dari depan pintu. Ia biarkan Seneca masuk, lalu ditutupnya pintu kamar.
***
Seneca mulai melihat-lihat. Nyata benar kalau Sal telah mempersiapkan kamar itu sebaik dan senyaman mungkin. Lebih mirip kamar tamu daripada ruang perawatan, malah. Selain tempat tidur, meja berlaci, dan sofa tunggal, ada pula lemari baju dan sebuah rak buku berisi koleksi novel. Masih tak mengucapkan sepatah kata pun, Scarlet berjalan mendahuluinya dan memimpinnya ke arah sofa.
“Jadi, apa kau baik-baik saja?” Seneca duduk di sofa beludru itu.
“Sudah jauh lebih baik,” sahut Scarlet lesu. Hati-hati gadis itu duduk di tepian kasur, tangannya terlipat di atas paha. Kepalanya tertunduk, enggan menatap lawan bicaranya.
“Aku senang mendengarnya,” sahut Seneca. “Kurasa Dokter Fischer pasti sudah memberitahumu hasil pertemuan kemarin. Maaf, aku gagal mempertahankanmu.”
“Kalau kau khawatir aku marah, tidak, aku tidak marah.” Scarlet menggeleng, melempar senyum sendu. “Justru aku yang seharusnya minta maaf. Kau sudah membantuku begitu banyak dan aku ... aku hanya menyusahkanmu.”
“Hei, hei! Tatap aku.” Seneca mencondongkan badan ke depan. Ia raih kedua tangan Scarlet, lalu ia genggam. Lembut, tetapi mantap. Jenis yang biasa dilakukan orang untuk memberi keyakinan pada orang lain. Perlahan, gadis itu mengangkat kepala. Pandangan mereka bertemu. Tidak, gadis itu tidak menangis. Bahkan matanya tidak berkaca-kaca. Namun, Seneca tahu ada yang sirna dari tatapan itu. Mata biru itu tak lagi bersinar penuh energi. Sebagai gantinya adalah kehampaan mendalam, bagai palung laut tak berdasar.
Seneca menghela napas panjang. Tangan kanannya bergerak mengusap kepala gadis itu. Ia beri tepukan-tepukan lembut pada puncak kepalanya, ia belai rambut cokelatnya seolah-olah Scarlet masih seorang gadis kecil. Bagi pria itu, Scarlet adalah adik perempuan yang tak pernah ia miliki. Sejak pertama kali ia melihat antusiasme Scarlet saat gadis itu pertama kali bergabung dalam pasukan, ia tahu gadis itu akan menjadi seseorang yang istimewa.
“Dengar, Scarlet. Memang, aku akan berbohong bila kukatakan bahwa kau sama sekali tidak pernah menyusahkanku,” ujar Seneca hangat. “Bahkan, kasus ini adalah sakit kepala terparah yang pernah aku rasakan. Tapi, aku tidak menyesal merekrutmu sebagai pemburu. Kau adalah gangguan terbaik yang pernah aku peroleh, dan aku bersyukur memilikimu dalam skuad pemburu.”
Gadis itu tak menjawab dengan kata. Hanya jemarinya yang bergerak menggenggam tangan kiri Seneca. Lalu, tanpa permisi, mengalirlah air matanya. Scarlet sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya ia tangisi. Entah fakta bahwa ia dikeluarkan, fakta bahwa sebagian besar warga kini memandangnya curiga, atau ketidakpastian mendadak atas masa depannya. Atau, mungkin bahkan bukan semua itu. Barangkali, ia hanya lega setelah berbicara dengan seseorang yang familier.
Seneca pun memilih diam. Pria itu percaya, saat ini Scarlet hanya butuh ditemani. Ketika sesenggukan itu mulai berhenti, ia mengulurkan sapu tangannya sendiri, yang langsung diterima oleh Scarlet.
“Sudah enakan?” tanyanya.
“Sedikit.” Scarlet tersenyum tipis. Memang masih tersisa air mata di pelupuk gadis itu, tetapi bara asanya mulai timbul kembali. Ia tahu bahwa keadaannya belum berubah. Orang-orang desa pasti masih membencinya. Namun, ia tahu bahwa masih ada orang-orang di pihaknya. Orang-orang yang masih mengingat Scarlet Dixon sebagai seorang kawan yang setia, tanpa peduli jati dirinya.
Untuk sekarang, cukuplah itu baginya.
“Sebentar lagi aku harus pergi. Aku sudah berjanji pada para pemburu Desa Whittington untuk ikut menganalisis serangan Anomali barusan. Kalau, hm, kau menginginkanku datang lagi selama kau masih dirawat ...,” Seneca berpikir sebentar, “sampaikan saja pada Dokter Fischer, dan akan segera kulakukan begitu ada waktu.”
“Aku tidak apa-apa, sungguh. Bagaimanapun, tugas skuad pemburu harus diutamakan. Hanya saja, untuk Sawyer, Sean, dan teman-teman lain yang masih mendukungku, tolong sampaikan salamku, ya?”
“Baiklah, akan kulakukan,” balas Seneca. Rasanya tak perlu ia mengabarkan kalau lebih dari setengah anggota skuad pemburu mendukung keputusan rapat kemarin. Bahkan ia pun berhati-hati agar kunjungannya hari ini tidak diketahui mereka. Ketika gadis itu melepaskan genggaman tangannya, barulah ia beranjak. Meski Scarlet mengantarnya sampai ke pintu, kali ini ia membukanya sendiri.
“Oke, sampai ketemu lagi. Jaga dirimu,” pamitnya.
“Kau juga.” Scarlet melambai. Pandangannya mengikuti punggung pria itu, yang makin menjauh menuruni tangga. Begitu matanya tak mampu lagi melihat sosok lelaki itu, barulah gadis itu menutup pintu.
***
Saat Seneca hampir tiba di lantai bawah, dilihatnya Sal sudah berada di samping tangga. Begitu melihatnya, dokter itu terperanjat. Tatapan Sal bak maling tertangkap basah.
“Oh! Kau sudah selesai rupanya,” ucap Sal cepat-cepat. “Kebetulan klinik sedang sepi, jadi aku, eh, menunggu saja di sini. Aku tidak bermaksud menguping, sungguh!”
“Tetap saja kau mendengarkan, kan?” Seneca mengangkat sebelah alis. Suaranya sudah kembali pada nada ringannya yang biasa, tetapi matanya menyelidik.
“Yah, uh, aku hanya mau memastikan pasienku baik-baik saja.” Sal mengusap-usap tengkuk dengan gugup. “Tenang, aku hanya sempat mendengar sedikit. Kuharap kau berhasil membuat Scarlet tidak terlalu merasa bersalah pada, uh, hal-hal di luar kendalinya. Kasihan gadis itu, kau tahu.”
Seneca berjalan terus, melewati Sal dan berhenti di sudut ruangan. Di dinding kayu pinus ia bersandar, ditemani vas tembikar setinggi pinggang.
“Kenyataannya, justru aku yang merasa bersalah pada Scarlet. Maksudku, bahkan di saat nasibnya di ujung tanduk, hal yang pertama memenuhi kepalaku adalah bagaimana caranya mempertahankan posisiku sebagai komandan.” Seneca menyilangkan lengan. “Kalau itu tidak membuatku jadi orang paling brengsek di ruangan ini, aku tidak tahu sebab yang lain.”
“Tidak juga,” balas Sal kalem. “Aku memperhatikan pembelaanmu. Kata demi kata yang kauucapkan, serta gestur tubuh dan ekspresi wajahmu, semuanya tulus. Saat itulah aku tahu kau benar-benar ingin melindunginya.”
“Heh,” dengkus Seneca sinis. “Aku hanya melakukan yang seharusnya. Sedang kau sendiri, apa alasanmu membela Scarlet?”
“Er, tanggung jawab profesional, mungkin. Sudah jadi tanggung jawab seorang dokter untuk mengutamakan keselamatan pasiennya, kan?” Sal mengangkat bahu. “Lagipula ini fenomena yang sangat langka, jadi kurasa ini adalah kesempatan penelitian yang bagus. Para peneliti menghabiskan puluhan tahun meneliti hal ini di lembaga penelitian negara, sehingga setiap data sangat berharga. Belum tentu aku dapat menemukan manusia setengah werewolf lainnya seumur hidupku.”
“Bagus kalau kau tulus ingin menolong Scarlet.” Sekonyong-konyong, Seneca berjalan maju. Dengan tangan kanannya dicengkeramnya bahu kiri Sal erat-erat, hingga dokter itu mengernyit menahan sakit. Tatapannya tajam menusuk mata cokelat Sal. Saat itulah dokter itu sadar bahwa ia sedang mendapat peringatan serius.
“Camkan ini, Dokter. Bila kau hanya ingin menjadikan Scarlet subjek untuk percobaan-percobaanmu, aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah mendengar bagaimana peneliti-peneliti seperti kalian memperlakukan para werewolf yang tertangkap. Kalau kau berpikir hendak melakukannya pada Scarlet, ingat, gadis itu masih separuh manusia, dan aku ingin kau memperlakukannya sebagai manusia.” Suara Seneca sedingin es. Sal merinding dibuatnya. Ia yakin, inilah aura kebengisan yang dirasakan para werewolf ketika berhadapan dengan Seneca. Tak mampu berkata-kata, dokter itu cepat-cepat mengangguk. Dengan kasar, Seneca melepaskan cengkeraman.
“Sampai jumpa, Dokter Fischer.” Seneca berlalu, meninggalkan Sal yang masih menatap penuh ketakutan.
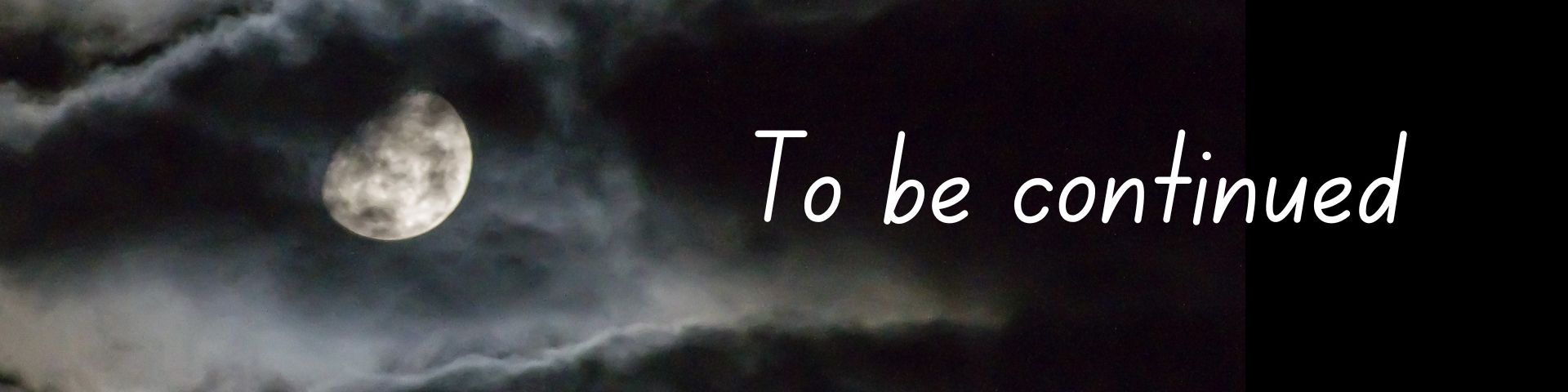
(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top