Episode Dua: Anak Idaman Orangtua
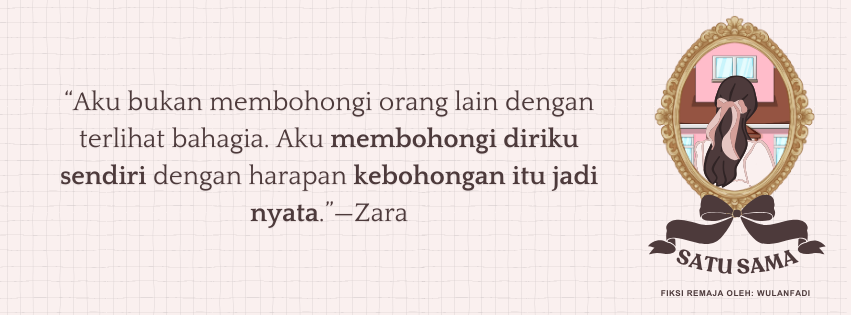
"Padahal aku nggak apa-apa kalo nggak pake helm."
Ucapan Zara itu bertepatan dengan Linggar menyerahkan helm padanya, hasil pinjam dari Ical. Teman Linggar itu masih di sekolah untuk gladi resik teaternya, sehingga Linggar bisa meminjam helm.
"Berkendara itu harus mementingkan keselamatan, mau itu jaraknya deket atau jauh."
Zara menerima helm tersebut dengan senyum tipis. Sudah satu setengah tahun Zara jadi teman sekelas Linggar, tapi sikap mengayomi Linggar tetap tak pernah luntur. Tak heran Linggar jadi ketua kelas dan Zara betah-betah saja jadi sekretaris mendampingi kepemimpinan lelaki satu ini. Tidak pernah Linggar mengambil keputusan berdasarkan kemauannya sendiri. Lelaki itu pasti mementingkan opini anak-anak di kelas.
"Maaf, ya, Linggar. Aku izin pegang bahu kamu pas naik," sahut Zara saat meng-klik tali pengaman helm.
Linggar melirik wajah Zara yang terlihat ... lucu karena memakai helm, berdeham pelan, kemudian menyalakan mesin motor. "Iya, nggak apa-apa. Pegang aja bahu gue."
Motor bebek Linggar memang tak sulit untuk dinaiki bahkan bila tanpa menjadikan bahu sebagai tumpuan, namun Zara tidak ingin kejadian dua minggu lalu saat hendak dibonceng Caca terulang kembali. Saat Zara mau naik motor, Caca tidak siap karena tidak sadar Zara mau naik, jadi motor oleng ke kiri. Untung saja parkiran motor tengah sepi saat itu.
Zara menarik sedikit roknya, kemudian memegang bahu Linggar sebagai tumpuan. Ia menaiki jok belakang dengan mulus, kemudian duduk anteng dengan tangan tetap di bahu Linggar.
"Aman?" tanya Linggar setelah Zara sudah tak bergerak-gerak lagi di jok belakang.
"Aman! Ayo, jalan, Kapteeen!"
Linggar nyengir kuda mendengar suara ceria Zara. Sudah barang tentu Bintang dan laki-laki korban ditolak Zara sampai jatuh hati. Semua yang ada di perempuan itu memang benar-benar memikat.
Motor bebek itu segera meninggalkan lahan parkir siap mengarungi jalan raya. Dari jok belakang, Zara mengarahkan Linggar bila ada belokan yang harus mereka lalui.
"Gue kira lo nggak akan hapal jalan, Zar."
Zara tertawa kecil. "Sering lewat masa nggak hapal, Linggar. Aku tuh suka merhatiin jalan, tau."
Linggar manggut-manggut.
Mereka sampai rumah Zara kurang dari lima belas menit. Zara segera turun untuk mengambil dokumen, sementara Linggar menunggu di depan rumah. Linggar bersyukur helm miliknya merupakan helm full face, karena kalau tidak, wajah syoknya pasti jelas ketara.
Bangunan yang disebut Zara sebagai rumah itu tidak pantas mendapat predikat demikian. Bangunan putih bertingkat empat dengan arsitektur gaya Eropa itu lebih cocok disebut istana. Linggar termangu. Bahkan dari arah luar gerbang, Linggar bisa melihat di depan rumahnya ada air mancur dengan patung yang mengucurkan air dari kendi. Tukang kebun mondar-mandir menggunting pucuk-pucuk daun di kebun agar tingginya merata.
Ketika Zara muncul dengan langkah anggunnya itu, Linggar menegakkan punggung lagi.
"Linggar, coba cek dokumennya sama kamu. Barangkali ada yang salah."
Linggar memandangi perempuan di hadapannya, perempuan dengan tatap yang begitu teduh dan tenang, juga senyum yang terus terpasang. Tutur kata baik dan tetap ber-aku-kamu di tengah gempuran gue-lo yang mendarah daging. Makhluk yang tahun lalu bahkan tak segan memasang tenda saat perkemahan Sabtu-Minggu di kegiatan Pramuka. Makhluk yang sama yang baru saja keluar dari singgasananya.
"Linggar?"
Linggar terkesiap. Pipi dan lehernya memanas. "Oke, gue cek."
Bagaimana ini? Linggar semakin menyukai Zara.
————— S A T U • S A M A —————
Badan Zara rasanya remuk saat akhirnya ia bisa merebahkan diri di kasur empuk. Jam bimbingan belajar tadi ditambah satu jam karena minggu ini akan banyak ulangan harian. Jam sudah menunjukkan pukul sembilan malam. Saatnya Zara menonton series kesukaannya di TV. Walau ini ketiga kalinya Zara menonton series yang sama, Zara tak menjumpai kata bosan. Zara merasa tenang saat menonton karena ia telah mengetahui alurnya. Ia menemukan kenyamanan di sana.
Kamar dingin itu kini hanya ramai dengan suara dari TV. Zara masih asyik menonton sampai akhirnya ia sadar air hangat di mug-nya kini mendingin. Bu Dyah, asisten rumah tangga yang mengurus keperluannya, sudah berkali-kali mengatakan bahwa perlu ada dispenser di kamar Zara agar remaja itu tidak bolak-balik dapur dan kamar. Namun, Zara selalu menolak. Baginya, semua harus berada di tempat yang semestinya.
Zara menghentikan tontonan sementara, kemudian turun dari tempat tidur menuju dapur. Gaun tidur satinnya bergerak seiring ia melangkah dengan sandal berbahan bulu hangat. Banyak lampu yang telah dipadamkan, tersisa lampu oranye redup di sekeliling lorong menuju tangga. Rumah Zara luas, sehingga untuk sampai ke tangga saja, Zara perlu jalan sekitar dua menit. Waktu kecil, Zara sering ketakutan karena tidur sendirian, namun seiring waktu, Zara tahu ada yang lebih menakutkan dari hantu.
Dan ketakutannya terpampang nyata ketika ia akhirnya mencapai dapur. Dari balik remang-remang dapur, Zara bisa melihat dua siluet tengah memadu kasih dekat dengan meja dapur. Zara pernah berharap kedua orang itu adalah orangtuanya. Mungkin dia hanya akan mengatakan, "Iiih, Ibu sama Ayah, mending ke kamar, deh!" Tapi, Zara tak pernah mengatakan itu, karena bukan kedua orangtuanya yang bermesraan.
Itu Ayah dengan wanita lain.
Zara memilih tetap berjalan ke arah dispenser. Pergerakannya rupanya disadari oleh kedua orang itu. Keduanya segera menjauh. Zara acuh tak acuh. Ia mengucurkan air panas pada mug, kemudian mencampurkannya dengan air biasa.
"Zara."
Panggilan dari Ayah. Suara bariton yang terdengar serak. Zara menoleh dan ia melihat dua kancing kemeja Ayah terbuka, lipstik yang berada di pinggir bibirnya, rambut yang berantakan seperti habis bangun dari tidur dan mata sayu. Zara sekilas melihat kondisi wanita di samping Ayah tak jauh beda.
"Iya, Ayah."
"Zara belum tidur?"
Zara menggeleng. "Sebentar lagi Zara bobo. Tadi Zara haus."
Mug di tangan Zara sudah menghangat. Zara kemudian berlalu begitu saja meninggalkan kedua orang tersebut. Meski terlihat kuat, sebenarnya tangan Zara gemetar hebat. Walau bukan sekali dua kali kejadian seperti itu terjadi, dunia Zara masih saja terguncang seolah baru pertama kali.
"Selamat tidur, Putri Ayah."
Suara Ayah menghentikan langkah Zara. Zara baru berada di ambang perbatasan antara dapur dan ruang tengah. Genggaman Zara pada mug semakin mengerat seiring senyumnya melengkung tepat. Zara sudah biasa memendam semua sendiri, bersikap dirinya baik-baik saja terhadap semua yang terjadi, itu makanan sehari-hari.
"Selamat tidur juga, Ayah ... dan wanita Ayah."
Zara berbalik, bergabung pada remang gelap ruang tengah. Isi kepalanya kosong. Tahu-tahu, Zara sudah di kamar, duduk di pinggir tempat tidur, dengan mata menyalang. Zara melihat jam. Sudah pukul sepuluh lewat lima menit. Sudah lewat dari jam tidur Zara. Tapi, Zara tidak mau tidur. Zara tidak bisa. Zara ingin pergi, ke mana saja asal tidak di sini.
Zara bangkit, berjalan ke arah walking closet dan mengambil jaket kulit cokelat, kaus, dan celana denim. Sesekali, Zara menoleh pada refleksinya di cermin saat berganti baju, hanya untuk dihadapi oleh wajah yang pucat.
Cantik, tapi mati.
————— S A T U • S A M A —————
Angin dingin menerpa wajah Zara saat motor besarnya melaju cepat membelah jalan raya yang lengang. Zara tidak pernah berkendara lebih dari 100 km/jam, tapi kali itu Zara melihat speedometer terus bergerak ke angka 100. Zara tidak melihat lagi. Ia hanya fokus pada jalan raya, pada hatinya yang remuk redam, dan pada dunia yang dengan kejam tetap berjalan.
Tempat favorit Zara adalah jembatan di Jalan Kenanga. Jembatan berwarna kuning pucat itu seperti lampu di malam hari yang menerangi. Zara lagi-lagi berhenti di sana. Ia mematikan mesin motor, turun, dan melepas helm. Rambut panjang bergelombangnya ia rapikan sesaat. Zara tahu sepuluh langkah di belakangnya, Pak Yusuf dan Pak Hanif mengikuti. Walau memberi jarak, Zara tahu semua gerak-geriknya tercatat.
Pada akhirnya Zara hanyalah burung yang berada di sangkar emas. Penderitaan yang tersembunyi dengan keindahan.
Zara berjalan lunglai ke arah jembatan. Deras air sungai terdengar dari bawah. Ia menumpukan tangan pada pagar pembatas. Melongok ke bawah. Gelap dan dingin. Bagaimana kalau Zara menghilang malam ini?
"Teh ...."
Suara Pak Yusuf terdengar, berjarak lima langkah.
"Kalau Zara menghilang, apa Ayah dan Ibu akan menangis?"
"Jangan bilang begitu atuh, Teteh ...."
Zara menoleh ke arah Pak Yusuf. Ia tersenyum menenangkan. "Bapak tenang aja. Zara nggak akan aneh-aneh. Kalau sampai Bapak diberhentikan, anak istri Bapak gimana?"
Kalau sampai ia berbuat aneh-aneh, banyak pekerja di rumah yang terkena imbasnya, termasuk Pak Yusuf, Pak Hanif, dan terutama Bu Dyah. Ketiga orang ini yang diamanatkan Ayah untuk menjaga dan melapor gerak-gerik Zara. Zara tidak ingin perbuatannya merugikan orang lain.
"Teteh jangan khawatirin soal saya ... Teteh khawatirin diri Teteh, atuh. Teteh udah sering banget ke sini."
"Iya, ini terakhir kalinya."
Pak Yusuf mengerucutkan bibirnya. "Kemarin juga Teteh bilang gitu."
Zara tidak menyahut, ia menoleh ke arah jembatan lagi. Pikiran berkelumit. Mencari jalan keluar, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
"Ibu masih sama mainannya, ya, Pak?" tanya Zara. "Zara lihat, kamarnya kosong. Mobilnya juga nggak ada."
"Teh ...."
"Mainan Ibu yang sekarang bukan orang kantoran yang itu lagi, Pak. Zara lihat kayaknya masih anak kuliahan. Mungkin beda empat atau lima tahun sama Zara."
Zara mundur dari pagar pembatas, kini menatap pekat malam. "Mungkin di dunia yang beda, Zara punya keluarga kecil yang bahagia."
Pak Yusuf menatap nyalang figur remaja di hadapannya. Ia sudah mengabdi di keluarga Zara sejak anak perempuan itu masih berumur lima tahun. Anak yang baik, penurut, dan tidak pernah macam-macam. Semua pekerja di rumah menyayangi Zara seperti anak sendiri. Zara juga tidak pernah menganggap semua pekerja di rumahnya sebagai bawahan, tetapi setara, sama. Bahkan ketika anak Pak Yusuf lahir, Zara membelikan banyak perlengkapan bayi dari tabungan uang saku bulanannya. Itu satu dari sekian kebaikan Zara.
Zara adalah idaman tiap orangtua, tetapi kenapa ...?
"Pulang yuk, Pak. Perasaan Zara udah lebih baik."
Melihat Zara malah tersenyum ringan, hati Pak Yusuf menjadi sesak.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top