Bujur Bumi 33 : Anyelir untuk Achala
Sudah hampir dua jam anak dan ayah itu berkutat dengan mainan bongkar pasang. Di atas karpet bulu, mainan Lego itu berserak. Kata si pria dewasa ia akan menyulapnya menjadi pesawat, sementara si kecil hanya membantu sang ayah membongkar dan kembali menyusun mainan warna-warni itu.
Atensi Achala teralihkan saat seruan dari anak laki-laki itu masuk ke rungunya. Ia menoleh, Juang mengangkat kedua tangannya tinggi kemudian bertepuk tangan dengan heboh, rona bangga tampak jelas karena pesawat dari susunan Lego yang mereka rancang sudah jadi.
"Macha, lihat pesawat buatan papaf sudah jadi. Bagus tidak, Macha?"
Juang beralih menghampiri Achala yang duduk di sofa. Wanita itu menelisik mainan yang disusun tinggi tersebut, di bagian kiri dan kanan agak melebar. Achala yang tak mengerti dengan mainan tersebut, atau imajinasinya yang tak sampai? Ia benar-benar tidak bisa melihat di mana bentuk pesawatnya.
Namun, tanpa mengecilkan hati suami dan anaknya, wanita itu tetap memuji, "Iya, bagus, Sayang. Hebat, ya, papaf, bisa bikin pesawat terbang dari Lego. Sebentar lagi bisa bikin pesawat beneran, kayak Prof. B.J Habibie."
Mendengar penuturan sang istri yang terkesan meledek, Affandra bangkit merangkul anak istrinya dalam satu dekapan. Dua manusia terkasihnya tak luput dari kecupan bertubi-tubi.
"Ngomong apa, coba ulangi lagi?"
"Papaf hebat bisa bikin pesawat dari Lego. Sebentar lagi bisa, nih, alih profesi dari ketua yayasan jadi ahli atom."
Affandra gemas saat istrinya kembali meledek. Ia mendekatkan wajahnya ke dada Achala, mengecup pipi Juang yang bersandar nyaman dalam pelukan sang mama. Kemudian bangkit meninggalkan Achala dan Juang di sofa.
"Macha, nanti papaf mau jadi profesor? Bikin pesawat dan mobil?"
Diulangi lagi. Kamu enggak tahu ini adalah bercandaan ala orang dewasa.
Achala tergelak mendengar pertanyaan polos dari putranya. Mendekap tubuh kecil itu lebih erat dan menciumi kepala anaknya dengan gemas. Achala menjelaskan, "It's a jokes, Pumpkin."
"Lelucon orang besar. Abang tidak mengerti."
Achala semakin tergelak mendengar ucapan sang anak yang tak kalah lucu, bahkan lebih lucu dari bentuk pesawat yang Affandra buat tadi.
"Pesawatnya belum mau disimpan?" tanya Achala pada balita itu.
"Lima menit lagi, Macha. Abang lelah habis bikin pesawat itu. Masih mau seperti ini."
Seperti ini yang anak itu maksud adalah meringkuk memeluk sang mama, bersandar nyaman dalam dekapan, menikmati usapan tangan wanita itu.
"Besok Senin. Ada tugas sekolah nggak?"
Menggeleng kuat anak itu menyahut, "Nggak ada, Macha. Cuma bernyanyi keluarga Nabi. Kata Miss Annisa dihapalkan."
"Abang, sudah hapal?" Achala bertanya di sela kegiatannya menepuk-nepuk bokong bocah itu.
"Sudah, Macha. Abang sudah hapal lagu anak-anak Nabi."
"Coba mama mau dengar Abang nyanyi."
Juang mendongak, mata kecilnya mengerjap beberapa kali, sementara Achala mengernyit, tidak paham tatapan anak itu. Juang tak kunjung bernyanyi.
"Awalnya gimana, Macha? Abang lupa."
Katanya udah hapal. Kok, tanya awalnya gimana, sih, Nak.
"Anak-anak nabi ...."
"Ah, iya. Abang ingat. Anak-anak Nabi. Ada tujuh orang." Juang menguraikan pelukan, duduk tegap di samping Achala dan mulai bernyanyi, mengangkat tangan kanannya dengan telunjuk dan ibu jari tegak, jari lainnya dilipat, gerakan angka tujuh.
"Tiga laki-laki, empat perempuan." Ia kembali memperagakan gerakan angka tiga dan empat. Anak itu sangat semangat dalam bernyanyi.
"Pertama ...." Achala mengangkat jari telunjuk ke atas.
"Qasim, Abdullah, Ibrahim ... Zainab, Ruqayah, Ummu Kultsum ... Fatimah."
Ibu dan anak itu larut dalam nyanyian mereka, terutama Juang yang sangat heboh bergerak, bertepuk tangan. Sampai-sampai kehadiran Affandra di belakang sofa tak mereka ketahui.
"Pantesan nggak dengar bel bunyi. Lagi asyik paduan suara ternyata," sindir Affandra kemudian berlalu ke pintu depan.
Meninggalkan ibu dan anak itu, Affandra berjalan membukakan pintu untuk tamu yang menekan bel berulang kali. Affandra berekspresi biasa saja saat netranya menangkap sosok pria berdiri di depan pintu dengan satu buket bunga berwarna merah muda di tangannya.
"Benar dengan rumah Ibu Achala Annandhita?" Laki-laki itu bertanya ragu pada Affandra.
"Iya, benar. Saya suaminya."
"Ada kiriman bunga untuk Ibu Acha. Mohon diterima, ya, Pak."
Affandra meraih rangkaian bunga itu, membuka kartu ucapan yang terselip di sana. Untuk Ibu Acha. Baru membaca tulisan itu, pria dengan seragam kurir dari toko bunga itu membuyarkan kegiatan Affandra, meminta paraf untuk tanda bukti terima barang. Affandra mengurungkan niatnya membaca pesan yang ditulis pada kartu ucapan.
"Mohon paraf di sini, ya, Pak."
Menggoreskan pulpen di atas kertas buram berwarna hijau, tak lupa nama jelas pun ia tulis di sana. Kemudian Affandra berucap, "Terima kasih."
Ia membawa bunga itu ke ruang tengah, tempat di mana istrinya terakhir kali ia lihat. Kaki jenjang Affandra sudah semakin mendekat ke arah Achala dan Juang yang sedang bersenda gurau.
"Sayang," panggil Affandra menyerahkan bunga itu.
Achala menatap bingung pada bunga di dalam gelas kaca berukuran cukup besar. Tangannya terulur meraih bunga Anyelir merah muda yang Affandra simpan di atas meja.
"Dari siapa, Mas?"
Affandra mengedikkan bahu. "Kurang tahu, tadi ada kurir yang nganter. Mungkin dari temen guru atau murid kamu, soalnya mas baca di kartu ucapan untuk Ibu Acha." Affandra berlalu, diikuti putra semata wayangnya.
Buru-buru Achala meraih kartu yang terselip di sana. Membuka kertas yang warnanya kombinasi merah dan keemasan.
Untuk Ibu Acha.
Katanya, Bunga Anyelir merah muda bermakna rasa syukur dan tak ingin melupakan seseorang. Seperti aku yang tidak ingin melupakan kamu, Ibu Acha.
J.L.D
Achala gugup, jemari lentiknya meremas kertas tersebut secara kasar saat netranya membaca inisial si pengirim bunga. Tentu saja pikirannya langsung ke seorang pria, siapa lagi kalau bukan Jibran Lintang Darmawan. Panggilan "Ibu Acha" yang terselip di sana, bukan Achala tak mengerti. Ia mengerti, sangat. Bukan sapaan karena ia adalah seorang guru atau karena ia seorang istri ketua yayasan. Melainkan, dulu sekali saat ia masih menjadi istri Lintang Darmawan, dari sekian panggilan dari anak ke ibunya, Achala ingin dipanggil "ibu" oleh anak-anaknya kelak.
Salah satu alasan Achala menjadi seorang guru adalah ... hanya karena ia ingin mendengar anak-anak memanggilnya dengan sebutan itu.
"M-mas, tadi ba-baca pesan di kartu ucapannya?" Achala sedikit berteriak, tetapi suaranya terbata.
Wanita itu takut jika Affandra membacanya dan mengetahui siapa pengirim bunga tersebut. Achala menggigit bibir bawahnya, jantungnya dua kali lipat berdegup ribut. Tindakan Lintang benar-benar nekat mengiriminya bunga seperti ini.
"Nggak, Sayang. Kenapa emang? Mas baru baca bagian untuk Ibu Acha, doang." Suara Affandra mendekat.
Achala memegang dadanya, ia benar-benar dalam situasi seperti hidup dan mati. Kertas yang diremas tak beraturan itu sudah ia singkirkan, sedikit lega jika suaminya belum sempat membaca. Achala menarik senyum getir saat Affandra menghidu bunga Anyelir dalam gelas kaca.

"Bunganya cantik. Pasti dari temen spesial kamu ini, ya, Sayang?"
"Hmm ... i-iya, Mas. Dari temen sekolah karena aku udah bantuin dia. Dia tahu aku suka bunga, makanya dikirimin Anyelir."
"Oh, jadi ini bunga Anyelir? Mas kira bunga kertas. Mas tahu cuma mawar, melati."
"Semuanya indah." Achala menyambung ucapan suaminya, berusaha mengusir rasa gugupnya.
Affandra tergelak mendengar kalimat yang Achala sambung seperti lirik lagu anak-anak. Jangan salahkan dia jika tidak tahu nama-nama bunga. Rasanya wajar saja jika seorang pria tidak banyak mengetahui perihal tumbuhan ini.
"Anyelir untuk Achala. Cantik!" tandas pria itu mengecup kening Achala singkat, sebelum akhirnya berlalu. Namun, tidak dengan gemuruh jantung Achala yang tidak bisa berkompromi. Belum lagi, ada seringai tersembunyi dari wajah suaminya. Seolah menyimpan sesuatu yang ia ketahui. Atau jangan-jangan Affandra tahu dari mana datangnya bunga itu?
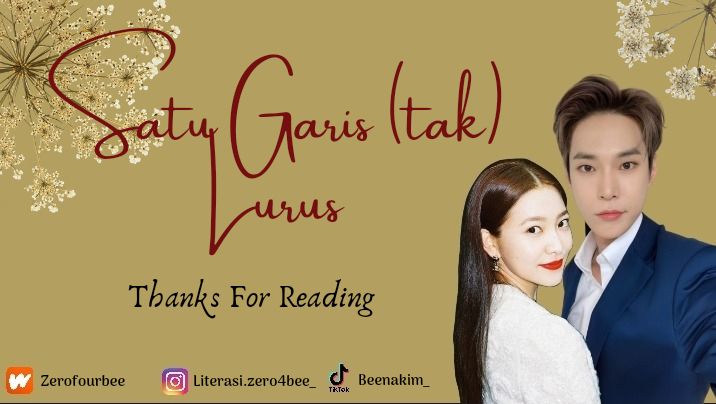
Tanjung Enim, 23 Oktober 2022
Republish, 24 April 2022
Rinbee 🐝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top