15. Nyala Api
"Lo oke?"
Aksa menghampiri Nakula yang tengah melangkah memasuki gerbang sekolah dengan wajah kaku.
Mendengar pertanyaan itu, Nakula mengangkat alisnya, melirik Aksa yang datang dengan wajah segar penuh semangat. Membuat lelaki itu tersenyum miring. "Abis ngapain kemaren?"
"Kepo lo," ucapnya sambil terkekeh sebelum menyadari maksud dari perkataan Nakula. Membuat dia mengumpat pelan. "Lo tau darimana?"
Nakula mengendikkan bahu. "Di samping Juna masih ada gue."
Aksa lantas tertawa. Kemampuan Nakula memang cukup baik dalam mengamati, lantaran lelaki itu sebelum seperti sekarang kerap mengisolasi diri. Memperhatikan dalam diam. Seperti predator yang mengawasi mangsa sebelum peristiwa yang menyebalkan itu terjadi, merubah segala sesuatunya.
Menuntun Nakula untuk berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka. Meski, terkadang, Aksa sendiri masih tidak dapat mengerti yang ada di pikiran Nakula. Terlampau rumit untuk dipecahkan.
Lelaki itu kemudian mengangkat wajah, melemparkan tatapan penuh tanda tanya begitu melihat Nakula yang kembali tersenyum miring, menunjuk dua sosok yang berdiri tidak jauh dari mereka.
"Sialan."
Nakula hanya terkekeh. "Pagi Re, pagi Ja."
Aksa menggigit bibir, mengabseni seluruh isi kebun binatang yang dia ketahui selagi langkahnya bergerak menyusul. Dia memperhatikan bagaimana Rea mendecak, menatap jengah lelaki itu akibat membuat mereka menjadi pusat perhatian, meski Nakula hanya tersenyum tipis melenyapkan ekspresi gusarnya, membuat Aksa sedikit berdecak kagum.
Maniknya kemudian bergulir pada Renja yang berjalan di sisi Rea, sedikit tersentak ketika Nakula menyapanya, meski gadis itu tetap mengukir senyum yang ganjil. Mereka sempat berpandangan beberapa saat, membuat Aksa yang berdiri tidak jauh dapat melihat ekspresi Nakula yang berubah. Menggelap. Hanya beberapa saat sebelum akhirnya senyum itu kembali.
Ketika dia menoleh, Renja sudah berada di sisi-sisinya. "Gimana?"
Aksa menelan saliva. Sedikit terkejut. Tidak. Dia sangat terkejut. "Lo gapapa?" Pandangannya bergerak menuju area depan sekolah yang masih cukup ramai. Selama ini gadis itu tidak pernah ingin berinteraksi secara langsung, meski Aksa sendiri tidak pernah mempersalahkan hal tersebut.
"Memangnya kenapa?"
Aksa terkekeh. "Penasaran ya?"
Renja mendecak. "Gue kan harus tanggung jawab sama apa yang gue bilang, kalo gagal dan berantakan karena gue kan bahaya."
Aksa tertawa pelan. "Makasih Ja."
Dia melirik gadis itu yang tiba-tiba terdiam sebelum satu senyum kecil perlahan terbit. Senyum penuh ketulusan.
"Bilang makasih ke diri lo aja karena udah berani."
Aksa tertawa pelan ketika melihat Renja tersipu. "Lo sendiri udah nyoba ngomong?"
Renja menipiskan bibir, memegang tali tas punggungnya sambil berucap gugup, "gue masih nyari waktu yang tepat."
"Take your time."
Renja terkekeh.
"Lo udah gak masalah keliatan kenal sama gue?" Akhirnya lelaki itu dapat menanyakan sesuatu yang sudah mengganggu pikirannya sejak lama.
Renja menggaruk tengkuknya. "Gue mencoba selangkah demi selangkah berubah, jadi lebih yakin dan percaya diri." Pandangannya kemudian terjatuh pada Rea. "Di dunia ini yang bisa nyelesain masalah gue cuman diri gue sendiri."
Dalam waktu yang singkat ini, Aksa merasa perubahan dalam diri Renja benar-benar luar biasa. Membuatnya ikut merasa senang.
Mereka kemudian berpisah di lantai dua, di mana kelas tiga berada satu lantai lebih tinggi. Begitu melangkah masuk, dia dapat melihat bibir Juna yang tertarik membentuk senyum miring kemudian pada Nakula yang tengah membaca buku, tampak acuh tidak acuh, dan Juna yang tengah tertidur.
Tidak biasanya.
"Lo kesurupan Jun?"
Lelaki itu mengumpat. "Lo punya cewek baru Sa?"
Aksa menaikkan alis. "Ngaco lo." Meski Aksa tahu tidak ada gunanya mengelak di hadapan Juna, lelaki itu memiliki kemampuan menerima informasi lebih cepat dari siapa pun di sekolah dan hanya perlu melihat wajah subjek dalam cerita sebelum mengkonfirmasi dalam diam.
"Ngomong-ngomong, Na, lo ditawarin buat gabung sama anak-anak teater."
"Gila," komentar Aksa. "Lo mau terima Na?" Dia masih mengingat bagaimana penampilan Nakula yang tidak berhenti dipuji oleh semua yang menyaksikannya pada saat itu.
Aksa menipiskan bibir selagi tatapan mereka sempat bersinggungan, dia masih tidak dapat menyingkirkan seluruh rentetan kejadian setelah acara kelulusan itu. Mimpi buruk yang dia harap tidak akan pernah terjadi untuk kali kedua.
Juna melirik Aksa, melemparinya tatapan penuh tanda tanya ketika merasakan dan melihat tatapan tidak setuju Aksa. "Kenapa?"
Aksa mengendikkan bahu, dengan cepat merubah eskpresinya.
"Nampilin apa?"
"Macbeth? Gue rada kurang yakin. Kalo lo mau entar gue pastiin lagi. Meski, kayaknya lo bisa ngomong langsung aja sih."
Nakula mengangkat wajahnya, menatap Aksa yang masih memperhatikannya. Dia hanya tersenyum, membuat lelaki itu mengumpat.
"Atau lo mau maen piano doang?"
Nakula menyandarkan tubuhnya, melirik keluar, memperhatikan langit yang tampak biru dan lapangan yang masih kosong. "Gue belom tau mau yang mana, tergantung," ucapnya.
Tergantung bagaimana keadaannya mendekati acara itu.
"Gue keluar sebentar," ucap Nakula ketika merasakan ponsel dalam saku bergetar. Bergegas menjauhi kelas, membuat Aksa dan Juna memandangi punggung lelaki itu dengan sedikit khawatir. Mengetahui apa yang biasa menyusul setelahnya.
Nakula menutup pintu kelas pelan, setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia memasukkan kedua tangan dalam saku selagi berjalan menuju ruang musik, kembali menelepon ayahnya.
Nakula meraih pemantik dari saku celana, membuka laci yang menyimpan kertas-kertas di mana dia menyembunyikan sekotak rokoknya, meletakkan benda itu di antara jemari selagi menunggu ayahnya menjawab.
"Halo."
"Halo, Pa. Gimana keadaan Om?"
Terdapat jeda beberapa saat, membuat lelaki itu membuka jendela dan mulai menghisap batang nikotin itu. Kegiatan yang selalu dilakukannya ketika seorang diri, jauh dari kebisingan. Terkadang Aksa akan turut menemani jika lelaki itu menginginkannya atau sekadar mengawasi.
Semenjak kejadian dua tahun lalu setelah kelulusan, Aksa menjadi lebih ekstra hati-hati ketika berinteraksi dengannya.
"Membaik. Habis sekolah kamu gak perlu datang ke sini, cukup di rumah dan baca dokumen yang kemarin ada di kamar kerja. Coba kamu evaluasi lagi dan perbaiki yang salah."
Nakula menghembuskan asap rokok.
"Tolong minta Pak Yon kirim ke apartemen aja, Pa."
Jeda itu kembali sebelum terdengar suara-suara yang membuatnya muak terdengar dari tempat Ayahnya menelepon. "Siapa? Nakula ya? Udah besar dia sekarang ya, bisa ikut bantu-bantu."
Dia dapat mendengar Ayahnya tertawa. Membalas pamannya itu. Bentuk ramah-tamah yang penuh kemunafikkan dengan seribu satu rencana untuk menyingkirkannya sekaligus merancang skenario baru untuk membuat cerita yang memukau media.
Nakula mengeraskan rahang. "Halo, Om Egar. Apa kabar?" sapanya, berusaha mengabaikan perasaannya. Seperti yang selama ini Ayahnya ajarkan.
"Bisnis adalah bisnis. Pisahin perasaan dengan pekerjaan. Tidak peduli seberapa kamu benci dengan orang di hadapanmu, kalau dia bisa menjadi alat yang berguna, sekalipun dia menodongmu dengan pistol, tetap kendalikan diri."
Sesuatu yang selalu menghantuinya, mengekorinya, memastikan dia tidak pernah melupakan kewajiban itu.
"Halo Nakula. Keliatannya kamu udah siap ambil alih ya?"
Kekehan itu seperti makanan yang menyimpan racun, terdapat makna tersirat yang membuat Nakula merasa mual.
Keliatannya kamu mau ambil alih dan jatuhin pamanmu ya.
Nakula memaksakan dirinya tertawa.
"Jangan gunakan perasaan."
Dia kembali mengisap rokok di tangan. "Waduh, saya masih harus belajar banyak Om. Lulus aja belum, mungkin Om Egar bisa bantu saya belajar."
Suara Egar yang berkomunikasi dengannya menggunakan ponsel Ayahnya terdengar berat seperti biasa. Pria itu kini tertawa, lalu dia kembali mendengar Ayahnya yang mengatakan akan menghubunginya lagi setelah ini lalu panggilan berakhir.
Nakula menghebuskan asap putih dari mulut, mematikan rokoknya dan membuang benda itu di tempat sampah setelah membungkusnya dengan kertas.
Jika semula dia merasa lelah setelah semua panggung sandiwara itu, tetapi kini dia tidak lagi merasakan apa-apa setelah sekian lama rutinitas ini berjalan. Perlahan terbiasa. Mulai beradaptasi.
Kakinya bergerak menuju grand piano hitam yang diberikan oleh Mamanya untuk dia gunakan di tempat ini. Sumbangan untuk ruang musik sekolah dengan tujuan dia dapat berlatih saat senggang. Nakula menghela napas, pandangannya kemudian bergulir pada jam di dinding. Masih tersisa beberapa belas menit sebelum bel berdentang.
Dia kemudian menjatuhkan tubuhnya, membuka tutup piano itu sebelum mulai bermain.
Symphony No. 5
Musik yang ditulis oleh Beethoven selama empat tahun ketika dia perlahan kehilangan pendengarannya. Kehilangan sesuatu yang krusial dalam hidupnya, alat yang membantunya mewujudkan ambisi dan tujuan dari hidupnya.
Lelaki itu selalu mencintai musik klasik. Merasakan ikatan, merasakan bagaimana musik itu berkomunikasi dengan dirinya, seperti suatu bahasa. Jika Aksa pernah menyebutkan bahwa angka adalah bahasa bagi para fisikawan, maka musik adalah bahasanya. Membantu dia memahami dunia.
Sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan seni akting, teater membantunya mempelajari apa yang tidak dapat dia mengerti. Mengkomunikasikan apa yang tidak dapat dia lakukan dengan baik. Terjebak dalam dirinya sendiri.
Kedua matanya tertutup perlahan, dia sudah sering memainkan ini, berulang kali berlatih ketika dia merasa sesak. Di antara ratusan komposer yang dikenalnya, milik Beethoven selalu terasa lebih personal.
Bagaimana pria itu bekerja di bawah tekanan Ayahnya semenjak kecil ketika lelaki itu menemukan bakat Beethoven, rasa frustasi yang muncul ketika apa yang dilakukannya tidak cukup baik, mengulang hingga ratusan kali, bergelut selama bertahun-tahun, musik ini seolah mencerminkan hal tersebut.
Menjelaskan perasaannya.
Dia hendak mencapai bagian akhir, berada pada bagian perpindahan dari tangga nada C Minor menuju C Mayor ketika mendengar suara langkah kaki. Membuat permainannya terhenti, menoleh untuk mendapati Renja berdiri di sana, pandangan mereka sempat bertabrakkan selama beberapa saat.
Mata cokelat itu seperti refleksi. Jika dia mencoba terjun lebih dalam, menggali lebih jauh, mungkin dia dapat menemukan dirinya sendiri di dalam sana. Tatapan penuh luka yang sama, persis seperti ketika mereka pertama kali bertukar pandang di ruang kesehatan, pada pagi tadi, lalu kini.
Nakula ingin membuka suara, ingin memecah kesunyian, dan merubah atmosfir di tempat ini, tetapi sesuatu dalam tatapan itu mengunci pergerakannya. Berhadap-hadapan seperti ini membuat luka mereka tampak seperti buku terbuka. Saling berlomba untuk menaklukkan.
Tidak ada dari mereka yang hendak mengalah, seolah membaca pikiran lawan adalah suatu kompetisi yang mempertaruhkan nyawa. Sama-sama keras kepala. Penuh tekad. Sebelum suara Mala menginterupsi, memanggil Renja membuat gadis itu akhirnya menoleh dan beranjak dari sana.
***
"Lo ada latihan 'kan abis ini Sen?"
Pertanyaan Aksa itu membuat lelaki berambut ikal itu menekuk wajahnya, menggaruk tengkuknya selagi berjalan. "Gue masih bimbang, antara berenti atau lanjut."
"Lo serius mau berenti?"
Sena menghela napas panjang. "Gue cuman lagi dilema. Gue takut gak punya waktu."
"Lo pikiran baik-baik aja, jangan langsung berenti," ucap Nakula, melirik Sena yang lebih tinggi darinya.
Sena hanya mengangguk. Mengulas senyum tipis. "Gue balik duluan ya," ujarnya.
"Gue nebeng lo dong Sen, sekalian ikutan jenguk."
"Gue ngikut dong."
Hal itu menyisakan Nakula, membuat ketiga sahabatnya menoleh. Menanti jawabannya. "Sorry, kayaknya gue gak bisa abis ini."
"Santai aja Na, good luck," ucap Sena menuju mobil miliknya yang di parkir tidak jauh dari gedung sekolah, sudah dipersiapkan oleh lelaki itu sementara Nakula merapatkan jaketnya, memilih berjalan kaki hingga dia merasa lelah.
Perjalanan menuju tempat tinggalnya memakan waktu kurang lebih dua puluh menit menggunakan kendaraan yang berarti akan membutuhkan waktu satu jam jika berjalan kaki. Satu-satunya orang yang cukup gila mau melakukan hal ini selain dirinya adalah Aksa. Sena yang merupakan seorang atlet sekalipun akan memilih berenang seribu meter ketimbang berjalan kaki satu kilometer dan jelas Juna tidak akan memasukkan hal ini sebagai opsinya.
Dia menghela napas panjang. Dia harus dapat mengendalikan dirinya jika ingin bertahan.
"Kendalikan dirimu, kendalikan orang lain."
Kata-kata yang dipegangnya dengan teguh untuk menjalani kehidupan. Sekalipun Ayahnya adalah sosok yang paling banyak menyumbang kehancurannya, tidak dapat dipungkiri bahwa pria itu pula yang membawanya sampai pada titik ini. Membuatnya bertahan sekalipun terseok-seok.
Nakula merogoh saku celana, hendak mengeluarkan kartu akses apartemen miliknya sebelum mendengar sebuah suara dari dalam. Keningnya lantas mengerut ketika menyaksikan siapa yang berada di dalam sana.
"Pa. Kenapa gak kasih kabar?"
Pria dalam balutan jas itu tidak banyak berbicara. Duduk dengan tegak di sofa dengan satu amplop cokelat di hadapannya.
"Na, Mama udah taruh makanan di dalem kulkas ya." Wanita berpenampilan anggun itu tersenyum, sekalipun telah memasuki kepala lima, Helena masih memiliki wajah segar dan tampak muda tanpa kerutan. "Tinggal kamu panasin aja, di dalem sana kosong begitu. Udah diisi juga bahan makanan yang lain."
"Makasih, Ma," ucapnya pelan sambil membuka sepatu.
"Kamu harus bisa jaga diri atau semuanya sia-sia." Pria itu akhirnya membuka suara. "Diri sendiri adalah nomor satu, gimana caranya kamu mau kerja kalau sakit? Siapa yang bakal percaya dengan orang yang bahkan gak bisa merawat dirinya sendiri?"
Nakula menelan saliva. Mengangguk. "Iya, Pa."
Pria itu menghela napas panjang, bangkit berdiri selagi bersiap-siap kembali. "Jangan lupa sama pesta ulang tahunmu. Balik sebelum itu."
Nakula kembali mengangguk patuh, mengantar orang tuanya keluar.
"Gimana di sekolah? Udah punya temen?" Helena memandangi anak semata wayangnya yang kini telah bertumbuh menjadi dewasa dengan cepat. Dia menepuk pelan pipi Nakula. "Rasanya gimana?"
Nakula menarik bibir, mengukir senyum kaku. "Baik."
Helena terlihat lega. Mengangguk. "Nanti kamu undang mereka ya, bawa pacarmu juga kalo ada." Wanita itu kemudian terkekeh pelan sambil mengangguk, melambaikan tangan pada Nakula sebelum akhirnya mengikuti Ayahnya yang sudah lebih dahulu memasuki lift.
Setelah itu pintu tertutup, meninggalkan Nakula seorang diri. Dia menarik napas panjang. Menjatuhkan tubuh di balik pintu.
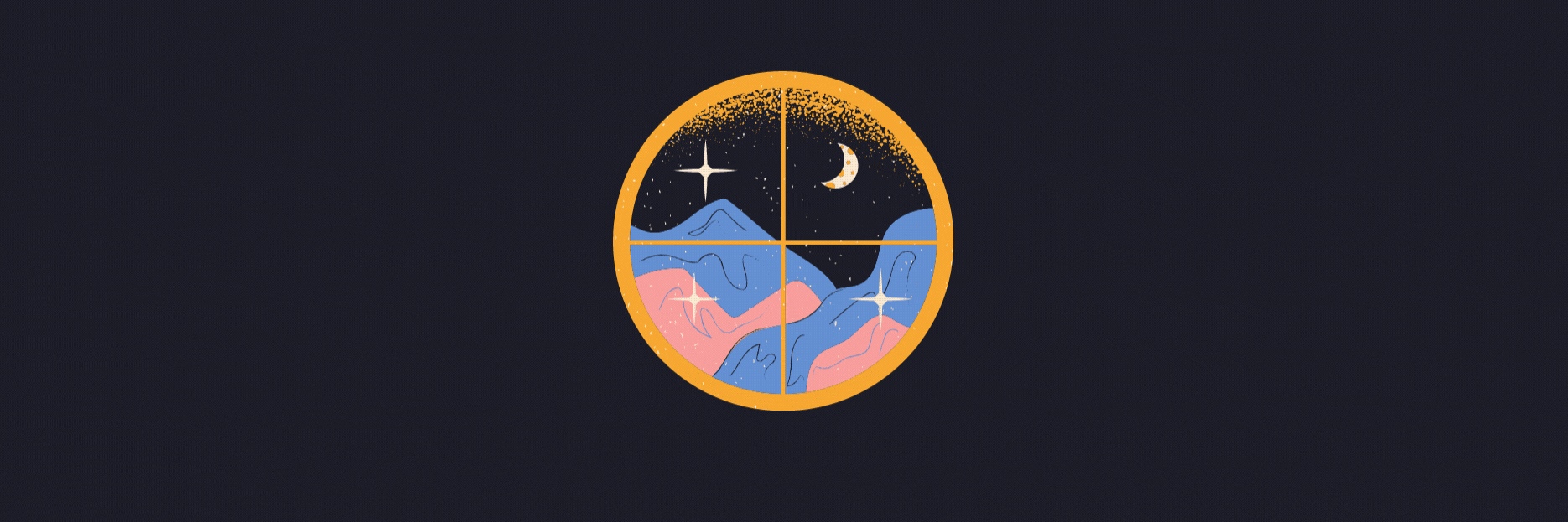
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top