13. Riak Air
"Hah?"
Mala mendecak, menarik Renja pelan menuju perpustakaan. "Lo penasaran kan sama gimana pertunjukkan Nakula?"
Gadis dengan rambut berwarna merah samar di ujung-ujungnya menarik bibir, selagi melanjutkan perkataannya, "yang kemaren sempet gue bilang waktu dia tampilin Macbeth, gue dapet dokumentasinya dari Regan yang anak dokumentasi dulu."
Tubuhnya bergerak menuju lantai dasar dengan penuh semangat. "Buat pertunjukkan nanti, kalo lo yang jadi volunteer kelas mau Ja?"
"Hah?"
Mala terkekeh ketika melihat Renja terkejut untuk kedua kalinya siang ini. "Lo kayaknya cocok buat main Macbeth."
Renja mengerjap. "Macbeth supposed to be a guy dan bukannya lo udah pernah nampilin itu?"
Mala mengendikkan bahu. "Dua tahun lalu dan Nakula udah pernah mainin itu, gue pikir satu-satunya orang yang cocok selain dia kayaknya bakal lo. He could be Lady Macbeth, changing roles."
Renja mengerucutkan bibir. "Bukannya yang keren dari Macbeth adalah posisi Lady Macbeth yang kuat? Shakespeare nulis itu di abad ke tujuh belas di saat perempuan posisinya selalu di bawah laki-laki?"
Mala langsung terkekeh. "Lo baca Macbeth?"
Renja menelan saliva, merutuki dirinya yang terkadang kelepasan berbicara jika menyangkut hal-hal semacam ini.
Absennya suara membuat Mala kembali tertawa. "Bagus deh, jadi gue punya temen yang bisa diajak ngobrol. Tentang Hamlet, King Lear, Othello, or even Little Mermaid."
Renja menghela napas, sepertinya kekhawatiran itu sia-sia. Dia melirik Mala, padahal selama ini gadis itu tidak pernah terlihat bersemangat membicarakan apa pun, berbaur menjadi satu seperti dirinya dahulu.
Mengikuti arus.
"Meski gue sempet kepikiran ini, Nakula as Macbeth and Rea as Lady Macbeth." Mala terkekeh ketika melihat reaksi ragu Renja. "Cuman gue takut dibunuh Rea jadi gue tawarin lo aja."
Renja mendengus, jadi dia tidak sebanding dengan Rea? Kemudian, memikirkan bagaimana seandainya hal itu dapat menjadi kenyataan. Nakula dan Rea di atas panggung yang sama, seperti sebuah lelucon. Setidaknya hingga dia menyaksikan sendiri Nakula di atas panggung dalam layar lebar di hadapannya.
Macbeth yang didorong oleh ambisi membunuh sang Raja setelah mendengar ramalan penyihir.
Dia menelan saliva, merasakan sekujur tubuhnya merinding ketika melihat tatapan mata itu. Ketika mereka bertatapan melalui layar di ruang audio visual perpustakaan, ketika Nakula meyakinkan sang pembunuh untuk membunuh Duncan, sosok yang selama ini menjadi rekannya ketika dipenuhi oleh rasa takut. Dibutakan oleh ambisi dan diselimuti rasa takut sebelum akhirnya meninggal.
Nakula seolah menjadi satu dengan peran itu, bagaimana tatapannya yang menajam selagi meyakinkan mereka bagaimana rasanya setelah menyingkirkan orang yang menjadi ancaman, menggunakan kalimat berulang untuk memastikan mereka mendengar, menuang lebih banyak api.
Permainan yang rapih dan sempurna, seolah lelaki itu pernah berada di posisi yang sama. Melakukan hal serupa.
Memukau.
Renja tahu seharusnya dia tidak mengagumi karakter Macbeth tetapi cara Nakula memainkan dan membuatnya hidup benar-benar luar biasa. Membuat karakter itu seperti diciptakan untuknya. Menghisap seluruh perhatian.
"Gimana?" Mala terkekeh. Merenggangkan tubuh setelah menyaksikan pertunjukkan itu, berapa kali pun dia melihatnya, penampilan Nakula saat itu memang luar biasa.
"Sempurna."
Mala menyisipkan anak rambut, tersenyum puas melihat ekspresi Renja. Menurutnya, Renja dapat memainkan peran seperti itu sama baik meski tertahan dengan ketidakpercayaan dirinya. Dia penasaran bagaimana Renja akan menunjukkan Macbeth versi dirinya.
Apakah akan terlihat kuat dan menyeramkan seperti Nakula?
Atau terlihat lembut dan rapuh?
"Ini pertama kali lo nonton teater?"
Renja menggeleng. "Gue pernah nonton di tv bareng Papa gue sekali. Dikenalin, meski gue lebih prefer baca langsung bukunya."
Mala mengangguk sebagai respon. "Pertama kalinya gue suka sama teater itu sewaktu SMP, gue dulu punya banyak buku dongeng tentang pahlawan. Dari sana, gue ngerasa pahlawan itu keren." Dia menjatuhkan tubuh di atas karpet, memandangi langit-langit ruangan.
Setiap kali Ayahnya pulang dari bekerja, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu pulang dengan membawakannya buku fiksi. Ketika kecil, buku-buku itu biasanya bersampul warna-warni tentang seorang putri lalu ketika dia beranjak dewasa buku itu berubah menjadi novel klasik.
"Mereka mau mengorbankan diri untuk dunia, tetap berpegang teguh dengan kebaikan hati sekalipun dunia itu kejam, dingin." Mala teringat dengan salah seorang tokoh di buku yang di dapatnya beberapa tahun silam. "Itu alasan novel klasik favorit gue Oliver Twist. Pada akhirnya dia berhasil dapetin sesuatu yang sepadan di akhir."
"Stay sane and good in this world is actually harder than committing your first crime."
Mala tertawa ringan mendengar komentar datar Renja. "Itu tantangannya 'kan? Tetap baik sekalipun dunia jahat sama lo. Tetep teguh dengan pendirian lo."
Semakin lama menghabiskan waktu dengan Mala, Renja merasa gadis itu lebih dari sekadar si populer yang selalu menjadi pusat perhatian, lebih dari titel gadis cantik yang selalu disematkan setiap menyebutkan namanya.
Mala luar biasa dengan caranya sendiri, mungkin itulah yang membuatnya menjadi matahari, menjadi pusat dari planet-planet.
"Apa itu alasan lo seneng main di atas panggung?"
Mala mengulum bibir.
"Itu alasan yang berbeda lagi," kekehnya. "Gue merasa panggung seperti dunia lain, di saat gue naik, gue gak mikir apa pun lagi selain berada di sana, fokus sama diri sendiri." Dia tersenyum. Dia masih menikmati seluruh perhatian yang tertuju padanya, tetapi, ketika kakinya melangkah naik. Mala melupakan semua itu dan menemukan kebahagiaan yang terasa lebih nyata.
"Rebeca berulang kali nyuruh gue untuk masuk ke cheers, kata dia kalo gue nyari perhatian, di sana akan lebih banyak lagi ketimbang teater yang gak seberapa menarik perhatian orang. Awalnya gue mau nurutin itu, tapi gue ngerasa gak cocok. Rasanya aneh." Dia menghela napas panjang. "Apa gue salah Ja? Dengan begitu gue rasanya mengkhianati prinsip sendiri."
Renja bergumam pelan.
"Gue gak terlalu suka konsep benar salah," kekehnya. "Soalnya hal itu yang bikin gue nelangsa sampe sekarang. Tapi Mal, gue pikir konsep kebaikkan itu juga harus berlaku untuk diri kita sendiri." Renja melirik Mala yang masih berbaring di atas karpet. "Perlakukan diri lo dengan baik dulu sebelum akhirnya baik ke orang sekitar lo, tanpa pandang buluh. Seimbang, I guess?"
Renja mengulum bibir, sedikit menertawakan dirinya dalam diam. Lebih mudah untuk berbicara dan membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka ketimbang miliknya. Solomon's Paradox.
"Makasih Ja."
Mala melompat bangkit. Tertawa ringan. Sedikit kagum dengan kontras antara Renja yang jauh lebih lembut ketika memilih kata-kata dibandingkan dengan Rea dan keduanya berhasil menjaga hubungan itu dengan baik.
"Gue harap lo bisa nemuin jalan keluar untuk semua itu."
Renja mengangguk, perlahan ikut bangkit dan berjalan keluar dari dalam ruangan. Menyapa singkat Kenanga yang seperti biasa duduk di balik meja.
"Lo udah tanya Arjuna soal teater?"
"Belom. Gue beberapa hari ini lagi sibuk ngurus properti," jawab Mala. "Gue pengen tanya langsung sama Nakula kalo ada kesempatan. Rea hari ini ada ekskul kan?"
Renja terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. "Kenapa? Lo mau nyamperin dia sekarang?"
Mala langsung tertawa ringan, merangkul Renja selagi mereka keluar dari perpustakaan. "Gue pengen nanya dia. Eh, Ja, mau nemenin gue ke ruang seni?"
"Jadi sekarang lo mau ke ruang seni apa ke ruang tari?"
Mala menggaruk tengkuk. Sedikit bimbang. "Ruang seni deh, sekalian gue mau nanya sama Arjuna soal poster yang gue minta."
"Oke."
Lagipula, setelah ini, gadis itu tidak memiliki kegiatan lain, tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah kembali, masih merasa bimbang dengan nasehat yang diberikan oleh Aksa kemarin serta Rea tadi pagi.
Ruang seni terletak di lantai dua, berada di sayap kiri gedung SMA yang berlawanan dengan area perpustakaan serta kelas mereka. Renja jarang mengunjungi bagian sekolah yang satu ini lantaran seluruh keperluannya berada di sayap kanan.
Jika dibandingkan, atmosfir tempat ini sedikit lebih ceria dan bebas lantaran sebagian besar ekskul dilakukan di sini.
Mala menghentikan langkahnya ketika membaca tulisan ruang seni, ruangan itu sedikit lebih mencolok dibandingkan yang lainnya dengan poster-poster tertempel di dinding. Begitu melangkah masuk, aroma cat minyak langsung menyapa indra penciuman membuat Mala mengernyit.
"Selamat datang di dunia lain," kekeh Mala, melirik Renja yang kini mengamati ruangan itu lekat-lekat. Tampang menikmati beragam lukisan sekaligus benda-benda yang ada di dalamnya.
Renja mengenali beberapa lukisan yang terletak di dinding, di pigura, sebelum jatuh pada dinding yang memajang karya-karya anggota ekskul sekaligus penghargaan yang berhasil didapat.
Dia menelan saliva.
Warna-warna cerah itu sangat kontras dengan adegan yang terlukis, dengan sesuatu yang mencoba disampaikan. Sekalipun terdapat ragam warna di atas kanvas, kompleksitasnya membuat lukisan serta objeknya semakin menonjol.
Keindahan yang menakutkan.
"Gimana menurut lo?"
Suara ceria itu menyapa indra pendengarannya, membuat Renja menoleh. Mendapati seorang lelaki dengan kulit sedikit kecokelatan, wajahnya yang sedikit bulat dipenuhi oleh bermacam warna cat.
Dia tersenyum lebar, hanya dalam sesaat, Renja tahu dia Arjuna. Sekarang dia mengerti mengapa beberapa murid menyebutnya sebagai matahari.
"Bagus ya?" Juna tersenyum bangga selagi memperhatikan hasil karyanya. "Karya kebanggan gue ini," kekehnya. "Lo tau Vincent van Gogh?"
Renja mengangguk. "Pelukis post-impressionist?"
Juna langsung tampak bersemangat. "Gue terinspirasi dari dia, lo tau lukisannya Night Caffe? Yang disebut sebagai lukisan paling jeleknya?"
"Yang pake warna hijau merah yang ninggalin kesan anxiety?"
Juna mengangguk, senyum lebar itu tidak meninggalkan wajah. "Gue selalu suka karya-karya dia dan cara dia mainin warna. Terutama di lukisan itu, lukisan yang beda dari Caffe Terrace yang cerah. Lo suka ngelukis juga?"
Renja menggigit bibir. "Gue cuman tau aja," cicitnya pelan. Apakah dia menyukai hal tersebut? Entahlah, hanya saja menurut James tidak ada salahnya mempelajari semua hal. Maka, di sinilah Renja. "Dan, kebetulan tau beberapa pelukis."
Juna mendecak. Sedikit kecewa dengan fakta itu. Mengekori Renja yang bergerak menuju lukisan lain.
"Giuseppe Arcimboldo?"
"Dari Nakula. Lo suka karya dia?"
"Gue kagum sama cara dia menggabungkan seni dengan tanaman dan hewan."
Renja memperhatikan lukisan four seasons itu yang melambangkan empat musim berbeda dengan buah ceri sebagai penanda musim panas yang membentuk bagian telinga, buah prem di belakang kepala, keriputnya batang yang melambangkan musim dingin, dan membentuk kepala serta dada.
"Unik, kreatif," komentarnya.
"Memang terobosan baru, gue dapet dari Nakula," kekeh Juna.
"Ehm." Terdengar suara dehaman dari belakang, membuat keduanya segera berbalik. "Udah?" kekeh Mala.
Juna mendecak. Meledek perempuan yang jauh lebih pendek dan mungil darinya itu. "Lo marah-marah sih kalo gue bahas tentang lukisan."
"Ya gue gak paham?" balas Mala sedikit emosi. "Lo juga gak mau denger kalo gue bahas tentang teater."
"Gue gak suka teater."
"Gue juga gak suka lukisan," balas Mala tidak mau kalah.
Renja hanya terkekeh melihat perdebatan tidak penting itu, memilih menikmati beragam lukisan yang dipajang di dalam sana. Sepertinya dia akan betah berada di tempat ini. Setiap lukisan penuh dengan ciri khas para pelukisnya.
"Entar lo kabarin gue aja Jun, awas lo kabur lagi," decak Mala, menatap tajam lelaki itu sebelum melangkah keluar dan menarik Renja di belakangnya.
"Iya, iya, bawel lo."
Kemudian pintu ditutup.
"Lo deket sama Arjuna ya?"
Mala langsung melotot. "Ngaco lo Ja. Gue kan memang deket sama semua orang," ucapnya, mengerucutkan bibir. "Mantan gue yang sebelum ini kan temen sekelas sekaligus sohib dia di kelas."
Mala mendesah. "Sialan, karena mantan gue yang itu jadi muncul gosip, makanya Rebeca ngamuk." Gadis itu merangkul Renja sambil berjalan menyusuri lorong yang sudah sepi. "Dia pikir gue mau ngincer gebetannya."
Meski akibat itu, Mala akhirnya memiliki kesempatan untuk lebih leluasa berfokus pada hal yang disukainya.
"Terus dia udah tau yang sebenernya?"
Mala mengendikkan bahu. "Paling itu dijadiin alasan biar gue bisa dia singkirin. Udah bosen kali." Gadis itu tampak sedih hanya beberapa saat sebelum senyum di bibir kembali merekah. "Gue udah ngomong sama Juna dan dia bilang dia bakal coba bantu meski akhirnya dia saranin gue ngomong langsung."
"Lo gak mau coba?"
"Gue mau cuman Nakula itu susah dibujuk. Keras. Gue salut kalo ada yang bisa bujuk dia." Mala menatap sekilas langit dari jendela besar di samping. "Di antara mereka berempat yang paling bisa ngebujuk Nakula cuman Aksa."
Renja menelan saliva.
"Kenapa?"
"Lo baru masuk pas SMP kan ya?"
"Iya. Bukannya mereka baru deket pas SMP?"
Renja tahu itu karena sempat menjadi berita yang menghebohkan ketika empat serangkai terbentuk meski dia tidak tahu siapa saja mereka, hanya tahu sekelebat sebelum Mala menceritakan lebih jauh beberapa hari lalu.
"Lo tau rumor di sekolah?"
"Tentang?"
Setiap sekolah memiliki lebih dari selusin rumor yang jelas tidak mungkin dipedulikannya. Rea sendiri bukan informan sekolah yang baik.
"Nakula itu sinting?"
Renja terdiam. Sepertinya dia tidak akan menyukai bagaimana cerita ini berjalan.
"Semua dimulai dari saat mereka sekelas, Nakula pas itu belom gabung sama klub teater dan Aksa baru temenan sama Juna, Nakula jadi ketua kelas dan Aksa jadi wakilnya." Mala melirk Renja. "Lo kalo kenal Aksa yang sekarang pasti gak akan percaya gimana dia dulu."
Apakah ini berkaitan dengan keluarganya? Renja mencoba menyatukan seluruh kepingan itu.
"Dia lulus dengan nilai hampir sempurna, tepat di bawah Nakula sebelum akhirnya di SMP nilai dia hancur sehancur-hancurnya. Banyak yang berasumsi karena itu Nakula hampir bunuh Aksa."
Mala menatap Renja, sedikit ragu melanjutkan ketika melihat tatapan terkejut Renja.
"Nakula selalu sendirian meski begitu gak ada yang berani deketin dia karena gosipnya Nakula pernah masukkin satu anak ke rumah sakit selama dua bulan meski besoknya Nakula masuk dengan santai seolah gak terjadi apa pun, lo tau apa yang bikin hal ini jadi topik perbincangan?"
Renja tidak tahu harus bereaksi seperti apa ketika mendengar kisah itu perlahan dituturkan.
"Dia masuk karena ulangan dan dapet nilai sempurna, seolah apa pun yang terjadi gak lebih penting dari ulangan itu walau perlahan Nakula berubah semenjak dia masuk ekskul teater, gue gak tau apa yang terjadi di sana, tapi dia yang sekarang berubah setelah itu." Mala menggigit bibir. "Lo tau kenapa empat serangkai itu terkenal tapi keliatannya gak tersentuh?"
Renja menggeleng.
"Mereka kadang disebut gila Ja. Kalo lo pernah denger the four temperament karya Carl Nielsen, mungkin itu cocok untuk sedikit ngedeskripsiin."
Tentu saja Renja tahu apa itu four elements, simfoni nomor dua dari seorang komposer Denmark yang mendapat ide untuk membuatnya ketika dia berada di Zealand, hal yang sama dengan teori psikologi di mana kepribadian manusia terbagi menjadi empat tipe; melankolis, apatis, optimis, dan mudah tersinggung.
Dia tidak tahu reaksi yang tepat untuk semua ini.
***
"Iya, gue disuruh balik," ucapnya selagi memakai kembali sepatu miliknya.
"Buset, tumben disuruh balik," komentar Juna lalu melirik kaca besar apartemen milik Nakula yang menampakkan langit yang bersemburat oranye. Matahari masih berada di atas. "Masih pagi."
"Udah sore itu mah," decak Sena yang baru selesai mencuci piring makannya. "Gue nebeng dong Sa," kekehnya.
"Lo mau ke rumah sakit Sen?"
Sena langsung melirik sumber suara. Nakula yang tengah duduk di sofa, membaca buku dengan kacamata membingkai wajah.
"Lo mau ngikut Na?"
Nakula menutup bukunya perlahan, meletakkan buku tersebut di atas meja lalu mengangguk. "Sekalian aja naik taksi bareng gue." Lelaki itu kemudian menatap Aksa. "Lo juga Sa."
"Sialan, gue ditinggal sendirian nih?"
Nakula hanya tertawa pelan sementara Sena mencibir lelaki itu. "Lo seneng kan dibiarin tinggal sama Nakula di sini."
Juna mengumpat pelan. "Sialan, lo juga yang paling semangat kalo ke apartemen Nakula."
"Gue cuman pengen numpang berenang aja."
"Lo harus ke rumah Aksa," ujar Juna, tersenyum miring selagi menatap Aksa. "Kolam renangnya gila. Belom katanya kemaren direnovasi kan ya Sa?"
Aksa menggaruk tengkuk. Mengangguk. "Lo disuruh dateng Sen, kapan-kapan. Katanya sayang jarang dipake. Lo kan seneng sama air tuh."
Sena tersenyum lebar, tidak peduli dengan hinaan yang terpampang nyata di hadapannya. Baginya, kesempatan untuk menggunakan kolam renang dan berenang adalah yang nomor satu, mengingat rumahnya tidak memiliki satu. Meski sejauh ini, kolam renang yang paling luar biasa terletak di rumah utama Nakula.
"Lo bawa aja kartunya Jun kalo mau balik," ucap Nakula selagi meraih ponselnya di atas meja. "Entar kabarin aja."
Juna yang tengah bermain mengacungkan ibu jari. "Oke. Kalo males gue nginep sini aja."
"Asal lo kabarin Karna aja."
Juna mendesah, mengangguk. "Iye, gue tau."
Setelah mendengar balasan itu, ketiganya melangkah keluar dan bergerak turun menggunakan lift kemudian menunggu beberapa saat hingga taksi yang sudah dipesan oleh Nakula tiba.
"Gue jalan atau ntar pesen ojek aja."
"Ribet, lagian searah kan."
Aksa mendesah, pasrah ketika Nakula yang keras kepala memaksanya masuk. Ketika lelaki itu berbicara dengan tegas, tidak ada gunanya mendebat.
Melihat hal itu Sena yang sudah duduk tenang di depan terkekeh.
"Tumben lo ke rumah sakit Na," komentar Sena.
Nakula memadangi gedung demi gedung yang terlewat dengan cepat. "Om gue keadaannya kritis jadi disuruh nemenin sama bokap."
Sena mengangguk, mengerti bahwa lelaki itu tidak ingin ditanya lebih jauh ketika melihat responnya, memilih memperhatikan jalanan yang mulai ramai.
Kendaraan beroda empat itu kemudian berhenti di dekat kompleks perumahan Aksa sebelum melanjutkan perjalannya menuju salah satu rumah sakit terkenal.
Lelaki itu menatap langit yang mulai gelap, merogoh saku celana ketika merasakan getaran dan nama Renja terpampang di layar, membuatnya kembali teringat dengan ucapan Juna sore tadi sewaktu lelaki itu datang. Tentang bagaimana pertemuan pertama mereka meninggalkan kesan yang menyenangkan untuk Juna.
"Renja unik. Gue perdana ngobrol sama dia, tapi gue paham kenapa orang pada ngincer dia sekaligus kenapa mereka mundur."
Jika menyangkut masalah menilai orang lain, Aksa perlu akui Juna akan menduduki peringkat pertama di antara mereka.
Alasan dibalik tingkah lelaki itu senang mendengarkan dan membawa cerita yang kebenarannya sedang divalidasi-Juna memilih kata tersebut ketimbang gosip karena menurutnya, gosip bisa menjadi benar maupun tidak, hanya menunggu waktu dan pembuktian sama seperti hipotesis dalam praktikum.
Juna senang menganalisa manusia, memperhatikan, menilai, dan menjadikan sebuah cerita.
Mungkin itu alasan sebenarnya lelaki berwajah bulat itu sengaja memilih IPS, mengabaikan peringatan ibunya.
"Sekilas Na, dia ngingetin gue sama lo. Keliatan kaku, dingin, dan isi otaknya luar biasa."
Aksa mengulum bibir, bukan hanga dirinya yang menganggap hal seperti itu, lelaki itu lalu mengetikkan balasan dan satu pertanyaan tentang apakah dia boleh menelepon malam-malam.
Balasan yang dinantikannya datang lebih cepat dari yang dia harapkan, Aksa segera menekan gagang telepon selagi melangkah menuju kursi taman. Merasakan jantungnya yang berdetak cepat, gugup.
Entah mengapa.
"Halo?"
"Halo Kak."
Suara Renja yang ragu-ragu membuatnya mengulum bibir. Gemas.
Terdengar dehaman dari seberang sana. "Gue jarang teleponan, hampir gak pernah. Jadi jangan ketawain gue, oke?"
Aksa terkekeh. "Lo lucu."
"Smooth, Kak. Jangan ngehina atau ngegombalin gue."
"Gue ngomong serius. Gimana perkembangan lo?"
Kali ini balasan itu datang lebih lama. "Gue masih takut."
Aksa menyandarkan tubuhnya pada kaca di belakang. "Itu wajar. Take it slow aja, lo harus coba untuk komunikasiin itu baik-baik atau lo bakal terjebak di lingkaran setan yang sama." Aksa memandangi langit yang mulai menggelap. Teringat dengan dirinya sendiri, berada di posisi ini beberapa tahun lalu. "Lo pasti bisa Ja."
"Kalo..., hasilnya gak sesuai?"
"Setidaknya lo udah mencoba kasih tau, gue bakal ada di sana kalo lo butuh nanti."
Terdengar tawa renyah. "Lo memang jago ngegombal."
Aksa mendecak meski bibirnya tetap tertarik. "Lo orang pertama yang ngomong gitu."
"See, Kak?"
Aksa langsung tertawa. Sejauh ini tidak banyak orang yang dekat dengannya hingga ke lingkup ini, sehingga dia tidak pernah merasa hebat, terlebih mengingat terbatasnya pengalaman asmaranya. "Lo lagi ngapain?"
"Belajar?"
"Gue ganggu dong?"
"Kagak, gue lagi stress bacain momentum dan impuls." Lalu terdengar suara kursi bergesekkan dengan lantai. "Gue lebih milih disuruh bahas suatu teori, kayak topik tentang waktu, di mana berkat teori relativitasnya Einstein yang bilang kalo waktu itu berbeda bagi situasi tertentu, kayak sewaktu lo terbang dengan kecepatan cahaya dan akhirnya muncullah spacetime."
Renja terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan.
"Sehingga kita tahu, kalau kenyataannya kita hidup di dunia empat dimensi dengan waktu sebagai dimensi yang keempat, meski terbatas. Kita gak bisa kembali ke masa lalu...." Renja berdeahm, menyadari sesuatu. "Maaf, gue kebawa suasana," cicit Renja.
Aksa langsung terkekeh, membuat Renja berdecak. Malu.
"Gue seneng kok ngedengerin lo semangat sama sesuatu." Aksa berdeham. "Padahal fisika asik loh, angka-angka itu malah ngebantu. Lo bayanginnya mereka sebagai bahasa aja, cara untuk berkomunikasi. Para fisikawan make angka buat mahamin fisika itu sendiri. Kalo lo mau gue bisa ngajarin fisika."
"Serius?"
"Ngapain gue bohong? Lo coba baca bukunya Richard Feynman yang six easy pieces, gue rasa lo bakal suka."
"Richard Feynman, maksud lo yang ngejelasin soal elektrodinamika kuantum?"
"Iya, isi bukunya tentang kuliah dia waktu itu. Asik dan tipis, ntar gue pinjemin kalo lo mau-"
"-woi, Sa."
Perkataan Aksa terhenti begitu mendengar suara yang tidak asing. Suara yang sudah lama tidak terdengar di rumah ini, membuat tubuhnya menegang.
"Kak? Lo gak papa?"
Lelaki itu tersentak ketika mendengar suara Renja sebelum berucap pelan, "sorry Ja. Gue..., matiin dulu ya." Setelah mendengar balasan dari gadis itu, dia mematikan panggilannya. Perlahan bangkit berdiri, berbalik.
Pandangannya kemudian bertabrakkan dengan sosok yang kerap dilihatnya di sekolah. Rahangnya mengeras.
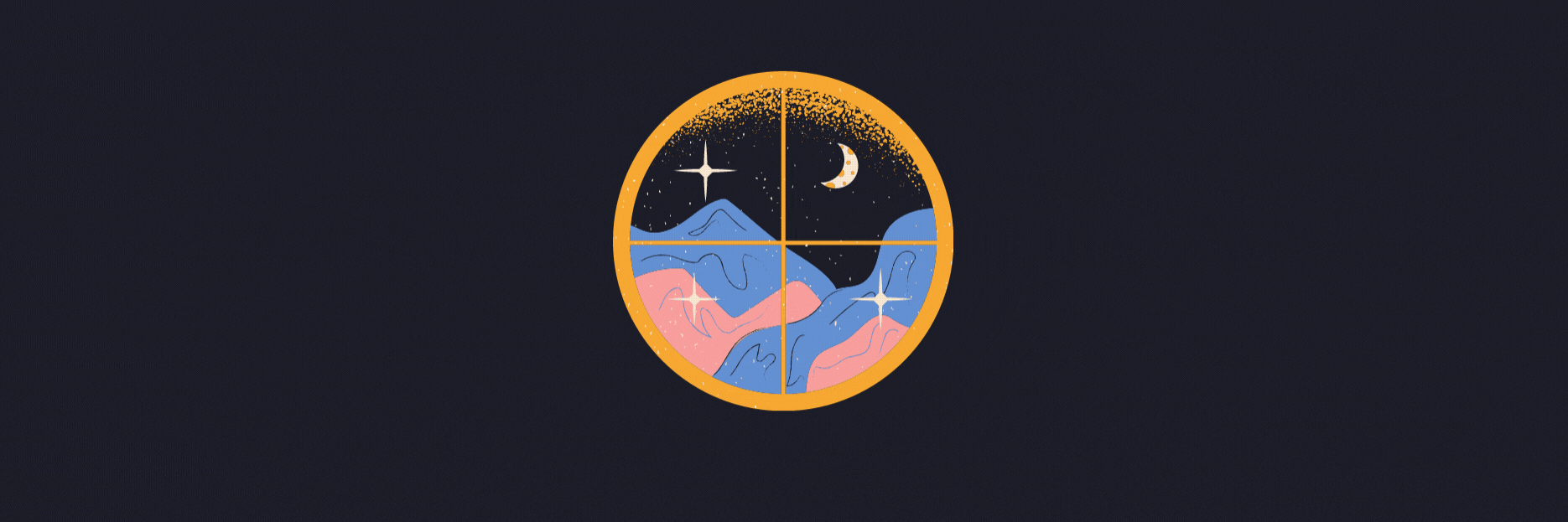
NOTE:
Buat yang gak suka baca fisika coba baca buku six easy pieces-nya richard feynman, setelah baca buku itu, aku yang awalnya paling anti sama fisika jadi bucin setengah mati wkwk. Meski, kayaknya untuk sekarang cuman ada versi bahasa inggris.
Balik ke topik, semoga kalian suka sama chapter kali ini, awalnya ada 5000 kata cuman dibagi dua sama yang sebelumnya, maaf kalo masih kepanjangan T-T.
Ini salah satu chapter yang rada sulit ditulis juga wkwk.
Kira-kira ada yang bisa nebak siapa adiknya Aksa? Udah sempet dikodein kayaknya di chapter sebelum-belumnya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top