12. Merah Hitam
"Ja, gue buat semua ini. Kata Rea lo suka opera, fraisier, dan macaroon kan?"
Renja menelan saliva ketika melihat beberapa dus yang diikat pita dengan rapih diletakkan di atas meja. Dia melirik Rea di belakang Mala yang memberikannya senyuman jahil.
Tahu Renja akan kebingungan dengan semua ini.
"Katanya makanan manis bisa bikin perasaan membaik." Mala mengukir senyum lebar. Membuat Renja semakin gugup, dia tidak pernah pandai memberikan reaksi. Tidak terbiasa.
"Makasih banyak Mal," cicit Renja. "Sumpah, makasih banyak."
Mala terkekeh. "Lo gak perlu ngerasa terbebani gitu," ucapnya, menjatuhkan tubuh di depan Renja. "Gue seneng kalo bisa ngasih sesuatu yang berguna ke orang lain, apalagi berhasil bikin mereka kembali semangat."
Perkataan itu membuat Rea ingin menyumpahi dirinya di masa lalu.
"Lo makan aja semuanya pelan-pelan," ucap Mala, hendak bangkit berdiri sebelum Rea menahan lengan gadis itu. Membuat dia menoleh dengan bingung.
"Lo mau ke mana?"
"Balik?" Dia menggaruk tengkuk.
"Ngapain, duduk aja bareng sini," ucap Rea yang ditimpali Renja. "Lo harus bantuin gue makan semua ini," kekehnya sambil membuka ikatan pada dus perlahan. Gadis itu tersenyum lebar. "Lagian, lo udah buat susah-susah."
Mala terenyuh, selama ini dia terbiasa memberikan sesuatu cuma-cuma dan teman-temannya tidak menganggap semua itu sebagai sesuatu yang spesial.
"Gue jarang nerima hadiah," ungkap Renja selagi memasukkan potongan matcha opera ke dalam mulut. "Dan, sebelum pindah ke sini gue selalu sendirian jadi gue memang gak terbiasa bergaul sama orang."
Mala mengangkat alisnya. Sedikit terkejut mendengar pengakuan yang keluar dari mulut Renja. Padahal, gadis itu dapat bergaul dengan baik di kelas walau memang sedikit kaku dan dingin ketika ada yang mendekatinya.
"Gue dulu ngehindarin perhatian, jujur gue takut," kekeh Renja. Setelah kejadian yang menimpanya, dia memilih berdiri di bawah panggung. Mencoba meminimalisir kemunculannya dalam keramaian. "Jadi terkadang hal itu membebani gue. Tapi, gue mencoba untuk jadi lebih berani."
"Makanya lo nyamperin gue?"
Rea menimpali, terkekeh selagi meraih macaroon yang disodorkan untuknya.
Renja menganguk. "Gue pikir saat itu lo yang paling keren dan berani."
Renja masih mengingat bagaimana Rea membela dirinya sendiri di hadapan banyak orang.
"Gue pengen bisa jadi berani," ungkap Renja. Dia tidak pernah memiliki keberanian untuk memulai, untuk memperbaiki sehingga selalu terjebak di neraka yang sama. Memilih memendamnya dan menutup diri.
Mala mengangguk. "Gue setuju, despite kata-kata lo yang nyebelin Re. Gue akuin lo adalah orang paling keren yang gue liat." Mala menyandarkan tubuhnya di kursi. "Bagi gue sendirian adalah hal paling menakutkan, tapi lo selalu tampak percaya diri dan puas."
Ketika melihat Rea yang tidak peduli bagaimana orang lain mencercanya, bagaimana mereka membicarakannya, ketika dunia seolah memusuhi Rea, gadis itu tetap melangkah dengan tegap.
Tidak goyah.
"Gue kadang iri sama lo," aku Mala.
Hal itu membuat Rea terkekeh. "Gue cuman terbiasa untuk bertahan hidup."
***
"Gue balik duluan ya, mau ada rapat festival dua minggu lagi." Rea menyampirkan tas di punggungnya, menatap Renja yang masih merapihkan barang-barang miliknya. "Lo harus lebih jujur Ja."
Perkataan itu membuat aktivitas Renja terhenti sesaat. Dia balas menatap Rea.
"Jujur sama diri lo sendiri dan hadapi kenyataan dengan berani." Rea menarik bibirnya. "Lo sahabat gue yang paling berharga dan gue gak mau kehilangan itu, lo harus tau kalo lo itu keren." Tatapannya menajam, meyakinkan Renja dengan ketegasan dalam nada bicaranya. "Bahkan dengan diri lo yang biasa. Lo cukup jadi Renja. Lakuin hal yang lo pengen dan ungkapin itu dengan jujur tanpa rasa takut."
Setelah mengatakan itu, Rea meninggalkan kelas, membiarkan Renja mencerna kalimatnya.
Gadis berambut cokelat gelombang itu menghembuskan napas, sedikit berharap kali ini kalimat yang tegas itu cukup membuat Renja sadar dan berhenti membohongi dirinya dengan harapan-harapan palsu. Berani untuk mengambil langkah keluar.
Kaki jenjangnya kemudian berhenti di depan pintu ruang OSIS, mengeraskan rahang dan menarik napas panjang sebelum membuka pintu itu.
Hanya ada Nakula di dalam sana. Duduk di kursi tengah sambil menulis.
Mungkinkah dia terlalu pagi, gadis itu melirik jam di dinding. Tidak. Dia benar.
Tangannya terkepal. "Lo batalin rapat?" Rea berjengit, ekspresinya sedikit melunak ketika pandangan mereka terkunci satu sama lain. Dia menipiskan bibir. "Lo butuh sesuatu?"
Rea melangkah masuk dan menutup pintu. Menjatuhkan tubuh pada kursi di dekat pintu, posisi paling jauh dari tempat Nakula duduk.
"Lo gak berniat maki-maki gue lagi?"
Wah.
Rea ingin melayangkan umpatan kasar sebelum kembali menutup mulut. Benar. Biar bagaimana pun mereka berada di dalam ruang OSIS dan Nakula memiliki posisi yang lebih tinggi saat ini.
Meski, persetan.
"Sial, lo mancing biar kita ribut?"
Dia sudah mencoba sedikit berdamai dengan Nakula. Tetapi, lelaki itu sepertinya senang dengan keributan.
Nakula menghela napas panjang setelah diam selama beberapa saat. Dia menyandarkan tubuhnya. Menyodorkan kertas laporan dari bendahara yang segera diterima Rea, gadis itu membacanya dengan cepat.
Tidak ada yang salah.
Bahkan, mereka mendapat beberapa sponsor tambahan untuk menyelenggarakan acara ini. Nakula bekerja dengan sangat baik sebagai ketua OSIS tahun ini, memastikan seluruh anggota bekerja dengan benar dan sempurna.
Tidak sungkan mengoreksi, tidak segan memberikan bantuan, dan berani bertanggung jawab. Kesempurnaan yang membuat Rea terkadang merinding.
Jika dilihat semakin dekat, Nakula benar-benar tidak memiliki celah maupun kekurangan setitik pun. Usaha lelaki itu untuk memperbaiki reputasi dan mengubur rumor buruk yang beredar di sekolah tentangnya patut diacungi jempol.
Tidak akan ada yang cukup waras untuk membicarakan keburukan dan mengungkit kembali kejadian Nakula di masa lalu.
"Udah selesai analisa gue?"
Rea tersenyum sinis. "So?"
Nakula bangkit berdiri, memandangi lukisan Mark Rothko yang berwarna dasar merah dengan dua garis hitam yang hanya terpisah oleh jarak sebesar garis.
"Gue penasaran." Nakula berbicara dengan nada yang lebih pelan, jatuh beberapa oktaf di bawah kebiasaannya, lebih berhati-hati, dan lebih terkendali. Seolah takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah. "Menurut lo, apa kategori manusia?"
Rea terperanjat. Pertanyaan itu membuatnya terkejut, sangat. Dia ikut menyandarkan tubuh, memandangi kaca yang tertutup di hadapannya, memperhatikan bayangan dirinya sebelum angkat bicara, "entah ya, gue gak terlalu peduli atau nyoba untuk tau. Selama ini gue hidup tanpa perlu mikiran hal semacam itu."
Rea memandangi punggung Nakula yang tegak, tidak bergerak seolah menjadi benda mati.
Tetapi, lelaki itu memang sudah mati bukan?
Gadis itu mengetuk meja beberapa kali, menerka akan ke mana tujuan dari pembicaraan ini sebelum akhirnya kembali membuka suara, "gue gak peduli dengan apa itu konsep manusia atau pandangan orang lain, selama gue bisa menjalani hidup gue dengan baik tanpa mengganggu orang, kenapa gue harus peduli dengan mereka yang gak memberi kontribusi di hidup gue."
Rea kembali mengangkat wajahnya, kali ini Nakula bergerak, cukup untuk memberi tahu bahwa jiwa dan raganya masih di tempat ini. Gadis itu menipiskan bibir, jawaban terakhir bukan yang sebenarnya ingin dicari tahu oleh Nakula? Meski, egonya terlalu tinggi untuk menyederhanakan pertanyaan. Memberitahukan sesuatu, isi kepalanya secara gamblang. Lebih senang bermain teka-teki dan Rea sudah cukup terlatih untuk permainan membosankan ini.
"Hidup gue lebih dari sekadar ocehan mereka."
Nakula tersenyum. Menatap Rea dari balik pundaknya. "Hidup bebas itu berbahaya." Nakula menyandarkan tubuh di dinding, kepalanya mengarah pada gadis itu meski pandangannya, pikirannya jauh berada di tempat yang lain.
Menuju rumahnya.
Menuju hidupnya.
Rea menaikkan alis. Meski memilih menutup mulut, menunggu Nakula menyelesaikan kalimatnya.
"Pada akhirnya, prinsip dan konsep itu akan berbalik dan berkhianat," ucapnya datar, sesuatu dalam dadanya terasa bergemuruh.
"So what?"
Nakula mengerjap.
"Di dunia ini gak ada yang selalu pasti, bahkan segala yang kita pelajari di buku saat ini bisa berubah." Rea bangkit berdiri. "Lo bilang gue takut sama hubungan baru?" Rea tersenyum, melipat kedua tangan di dada. "Kenapa enggak? Gue gak tau apa yang ada di pikiran mereka terkait gue yang merupakan anak haram ini."
Sekali ini Nakula menatap Rea, gadis itu tidak terlihat terpengaruh dengan segala sesuatunya. Pijakannya yang kuat seolah mampu menerjang badai. Dia tidak peduli dengan kelemahannya, menggunakan hal itu sebagai alat untuk menyerang.
"Mungkin mereka mikir kalo gue akan ngikutin langkah nyokap gue, mungkin mereka mikir kalo gue bakal jadi sampah masyarakat, mungkin mereka mikir kalo gue akan mudah dipermainkan, but fuck it." Rea tidak goyah ketika Nakula menatap maniknya tajam, seakan jika dia dapat menghancurkan Rea dia akan melakukannya saat itu juga.
"Di dunia ini gue cuman punya diri sendiri, so why would I destroy myself for them?"
Rea tahu ada yang salah dengannya ketika mengatakan semua ini secara gamblang di hadapan wajah Nakula yang tampak ingin membunuhnya, terlebih mengingat apa yang pernah dilakukan lelaki itu di masa lalu. Tetapi, segala tindak tinduk lelaki itu membuatnya muak.
Dia mengeraskan rahang. Ketakutan itu hal yang wajar, sifat dasar manusia, yang tidak wajar adalah tenggelam di dalamnya dan Rea tidak akan tunduk pada hal itu. Dan, jika dia merasa ragu, Renja dan Mala sudah berada di ujung jalan itu. Menunjukkan padanya bahwa terkadang, keberanian untuk menghadapi kenyataan dibutuhkan.
Dan, Nakula yang ada di hadapannya menyadarkan fakta itu. Baik secara sadar maupun tidak, meski menurut Rea, tidak ada yang lolos dari perhitungan dalam otak jeniusnya.
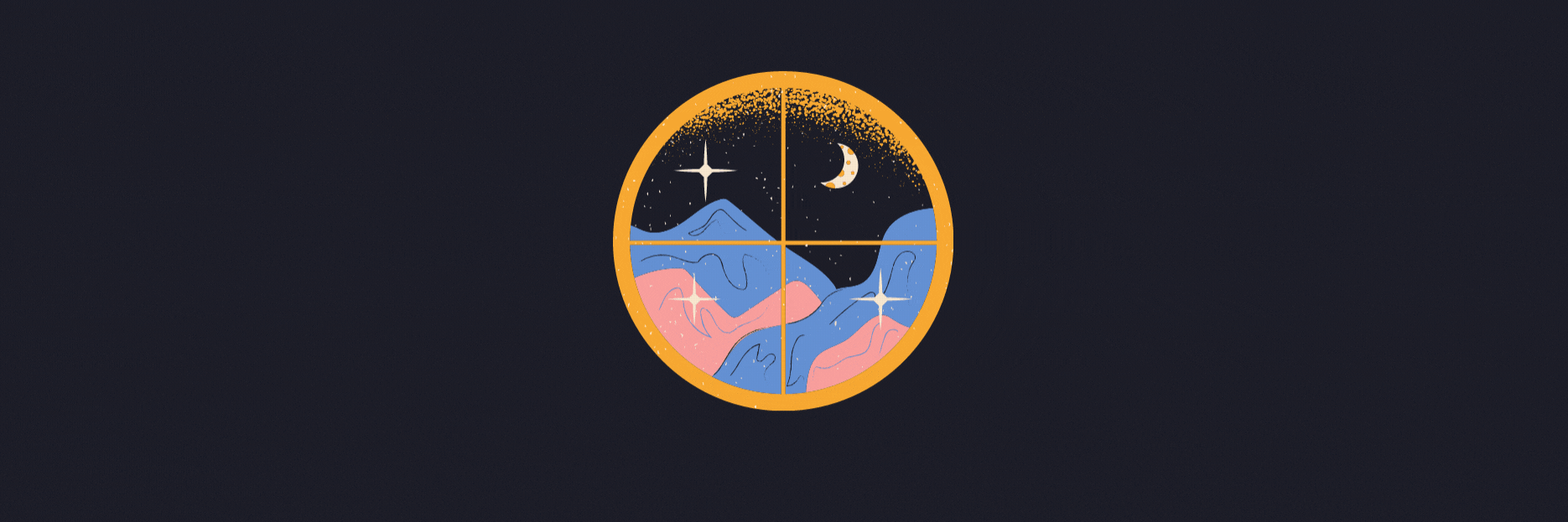
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top