08. Lorong Kosong
"Ja, mau balik?"
Aksa mengangkat wajah, memperhatikan langit yang mulai menggelap. Membuatnya menatap awan yang mulai menghalangi cahaya dengan perasaan gamang.
"Ayo," ucap Renja yang ikut mengangkat wajahnya, menyaksikan matahari yang perlahan menghilang di balik awan. Meski dirinya sendiri tidak keberatan dengan hujan, menikmati air yang membasahi tubuh, memberikannya sensasi dingin yang menyegarkan.
Gadis itu menyaksikan Aksa menyimpan kembali bolanya, kemudian ikut membuang sampah minuman mereka sebelum beranjak dan meninggalkan lapangan.
"Lo balik aja, Kak." Renja kembali menatap langit yang semakin gelap, menurut perhitungannya hujan dapat turun dalam kurun waktu lima menit. Lelaki itu akan sempat kembali, setidaknya, tanpa basah kuyup.
Aksa menggeleng. "Gak papa, gue anter lo sampe deket rumah aja."
Dalam beberapa hal, Aksa sama keras kepalanya.
Renja menggigit bibir, dia dapat melihat belokan yang mengarah pada rumahnya bersama tetesan air yang turun rintik-rintik. Membuat dia mengangkat tangan sambil menoleh. "Rumah gue di jalan belokan ketiga, mending lo ngikut gue Kak," ucapannya itu membuat Aksa melebarkan mata.
Terkejut.
Dia hendak membalas, tetapi Renja lebih cepat, menarik pelan lelaki itu sebelum akhirnya berlari ketika hujan turun semakin deras. Renja mengumpat pelan ketika menyadari pagar yang terkunci. Membuatnya merogoh saku celana cepat.
Elegi tentu saja menguncinya. Saat ini gadis itu hanya seorang diri di rumah.
Setelah bergelut selama beberapa saat, akhirnya Renja mampu membuka pagar, mendorong Aksa masuk ke dalam rumah, dia kembali mengunci pagar. "Masuk aja Kak," ucapnya ketika menyadari Aksa yang masih menunggunya di bawah hujan.
Aksa mengulum bibir, sedikit mendecak. "Masa gue masuk duluan dari pemilik rumahnya."
Kini, giliran Renja yang mendecak. "Masuk aja, di rumah gue gak ada orang." Dia menipiskan bibir tatkala menyadari perkataannya sendiri lalu dengan cepat meralatnya. "Cuman ada Elegi. Dia gak bakal ambil pusing."
Aksa tidak membalas, mengekori Renja membuka pintu, membuka sepatunya dan perlahan masuk ke dalam rumah yang cukup besar itu. Pandangannya langsung terjatuh pada sebuah lukisan berukuran sedang abstrak yang didominasi warna abu dan hitam. Dia dapat mencium aroma segar, mengingatkannya dengan buah lemon begitu melangkah masuk.
Lukisan itu tampak sempurna dengan seluruh rumah yang berwarna abu-abu dan putih dengan lantai kayu, meski beberapa peralatan dalam rumah memiliki sentuhan cokelat senada dengan lantai, memberinya nuansa hangat yang ganjil.
Di atas rak dan meja, dia dapat melihat beberapa foto dalam pigura, seluruhnya adalah foto perjalanan keluarga Renja baik di dalam kota maupun luar. Beriringan dengan benda yang merepresentasikan tempat itu. Replika batu Candi Borobudur dan Candi Prambanan di sisi figura yang menampakkan pemandangan Jawa, menara Eiffel di sisi figura kota Paris, dan patung Liberty di ujung lain.
"Handuk?" tanya Renja dengan tubuh yang masih basah sambil menyodorkan satu handuk putih yang masih baru. "Lo mau mandi, Kak? Gue ambilin baju sebentar."
Aksa menahan tangan Renja lalu menggeleng. "Mending lo yang keringin badan dulu," ujarnya, hendak meletakkan handuk di tangan pada kepala Renja sebelum tangan Renja yang lebih cepat—seolah sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan menahannya.
"Pake aja, gue mandi abis ini." Renja melirik rumahnya. Bersyukur bahwa situasi dan keadaan rumah mereka dalam kondisi baik. "Lo boleh duduk," Renja menggigit bibir, "atau nonton tv juga gak masalah, terserah sih."
Aksa terkekeh. Mengangguk. "Gue bakal duduk tenang aja sampe lo kelar."
Setelah kepergian Renja, Aksa menjatuhkan tubuh pada sofa di ruang tamu. Melihat rak-rak yang memajang piala demi piala sekaligus piagam. Membuatnya menelan saliva. Hanya dengan duduk di sini, dia merasa terintimidasi.
Manik hitam itu kemudian jatuh pada tanaman lemon meyer yang berukuran sedang di samping rak kayu, dia menelan saliva. Tanaman itu tidak mudah ditanam dalam ruangan, dibutuhkan sedikit perhatian dan keahlian. Lalu, pandangannya mengarah pada meja kaca kecil di samping sofa, terdapat satu pot tanaman croton yang sedikit rontok.
"Itu semua punya Papa gue."
Suara pelan Renja membuat Aksa nyaris melompat dari tempatnya. Dia menoleh, melihat gadis itu yang tengah mengeringkan rambut panjangnya.
"Walau jadi kurang terawat pas dia sibuk," tambahnya. Semenjak intensitas pertengkaran di rumah meningkat, James tidak lagi memperhatikan tanaman miliknya, terlampau lelah. "Gue juga gak terlalu paham."
Aksa kembali melirik tanaman itu. "Croton harus kena cahaya biar warnanya gak memudar karena dia tanaman outdoor, meski tipe yang ini cahaya sedang juga udah oke. Daunnya rontok karena dia gak suka dipindah-pindah, itu normal kok."
Renja mengulum bibir. Beberapa saat lalu Alana sempat memindahkan tanaman itu karena sedikit menganggu ketika James tidak lagi merawatnya, hanya meninggalkan pesan untuknya dan Elegi agar membantu merawat selagi pria itu sibuk.
"Tapi, diliat dari kondisinya, ini dirawat baik."
Renja perlahan menarik sudut bibirnya. Merasa sedikit puas.
"Lo mau minum apa, Kak?"
Aksa menggeleng. Tersenyum kecil. "Gak usah, gue gak ngerasa haus."
"Kak, lo mau liat yang seru?"
Melihat binar semangat dalam manik adik kelasnya membuat Aksa mengangguk, mengekori Renja melewati ruang tamu dan membuka pintu kayu, memasuki sebuah ruangan yang cukup luas.
Dari interior tempat ini, Aksa dapat mengetahui bahwa ini adalah ruangan di mana gadis itu menghabiskan waktunya. Rak demi rak menjulang tinggi hingga ke atas yang dipenuhi buku, dinding sisanya terdapat beberapa lukisan, dan sisanya didominasi oleh poster film.
Shawshank Redemption. The Martian. 2001: A Space Odyssey.
Lalu, bergeser ke dinding sebelah kanan terdapat empat poster lain yang membuatnya terdiam.
Black Swan. Whiplash. First Man. Birdman.
Aksa bukanlah sosok yang hobi menonton film, walau begitu, setidaknya, dia mengenal dua poster awal tadi. Meski, keseluruhan ruangan ini tampak memukau, posisi-posisi benda disesuaikan dengan baik.
"Kak, duduk aja dulu. Gue ambil minum sebentar."
Setelah pintu tertutup, kakinya bergerak menuju rak di dekat meja yang menarik perhatiannya. Rak yang dipenuhi oleh buku sejarah pada bagian teratas, sains dalam dua bagian, dan tiga bagian ke bawah dipenuhi buku psikologi maupun tentang otak.
Sebelum dia menjatuhkan tubuhnya di atas kursi, tangannya bergerak meraih beberapa gambar sekaligus desain poster dari buku fiksi.
Jika karya-karya milik Juna memiliki warna yang didominasi oleh warna cerah sehingga memberikan nuansa ceria serta semangat, maka milik Renja terkesan dingin dan kuat dengan warna gelap.
Seluruh ruangan ini tampak seperti mendeskripsikan gadis itu.
"Kak, mau teh atau air?"
Aksa mengangkat wajahnya, melihat Renja yang membawa satu nampan berisi teko, dua cangkir, dan satu kotak kecil. Lelaki itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Membuatnya merasa tidak enak telah membuat gadis itu repot.
"Gue yang gak enak, kalo enggak," kekehnya.
Aksa memperhatikan Renja yang merapihkan kertas-kertas di atas meja, menjadikannya satu sebelum duduk di kursi kayu di hadapan meja dengan jendela yang menghadap pekarangan rumah.
Hujan masih turun deras di luar sana.
Gadis itu menggumamkan terima kasih atas teh yang disodorkan, dia dapat mencium aroma melati yang menenangkan. Membuat tubuhnya lebih rileks bersama kehangatan yang menyentuh epidermis kulit.
Kepalanya bergerak ke samping, menatap Aksa dari pundaknya ketika lelaki itu mulai membuka suara.
"Walau klise, gue benci hujan."
Nada itu terkesan datar, tidak peduli walau getarannya berbeda. Seperti ketika Rea salah melewatkan satu petikan pada gitarnya. Membuat Renja tidak dapat mengalihkan perhatiannya pada potret samping Aksa, lelaki itu selalu tersenyum.
"Semua orang punya hal yang dibenci," ungkap Renja, perlahan. Meragukan kalimat yang lolos dari mulutnya. Dia hendak berhenti, tetapi ketika melihat tatapan Aksa, otaknya kembali memberi perintah untuk tetap menyuarakan isi pikirannya. Aksa, entah bagaimana, seperti refleksi dirinya sekaligus tiruan dari Rea.
Penuh dengan dirinya sendiri, membuat mereka yang kosong tertarik untuk mendekat. Ingin mendapatkan hal serupa. Atau setidaknya, ingin mengisi kekosongan dalam relung dada. Mencari sesuatu yang hilang dan tidak jarang kecewa pada akhirnya. Sama seperti elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lain ketika terjadi ketidakseimbangan.
"Gak suka dengan sesuatu biasanya berkaitan dengan memori tertentu, dengan pengalaman tidak menyenangkan." Renja kini kembali memusatkan perhatian pada jalan lengang yang berada di antara dinding penyangga. "Gue sempet benci taman bermain." Dia terkekeh di akhir.
Aksa ikut terkekeh, menyandarkan tubuh selagi memandangi lukisan pantai. "Hidup gue berakhir saat itu." Dia mengerjap, berusaha mengusir bayang-bayang itu. Meski dia sudah mencoba menerima, melupakannya adalah persoalan lain. "Apa ada alasan khusus lo suka film-film ini?"
Renja mengikuti arah pandang Aksa, mengabseni judul-judul itu dalam benak.
"Sejak kecil, gue selalu suka hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan, mimpi, dan ambisi." Dia tersenyum kecil. "Mungkin karena gue anak pertama, jadi orang tua gue selalu memastikan gue dapat yang terbaik dan untuk itu, gue dididik agar jadi sukses."
Maniknya menggelap seiring hippocampusnya memutar memori masa kecil. Dia menelan saliva, mengingat betapa mengerikannya dia dahulu.
"Gue dan adik gue sebelum ini, jauh lebih buruk. Bahkan, setiap kali ketemu bisa berantem."
Saat itu, orang tuanya kerap membandingkan mereka berdua. Membuat hubungan yang semula baik-baik saja merenggang. "Meski karena keadaan kita akhirnya saling ngandalin satu sama lain."
Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan, mereka berusaha bertahan dengan saling mendukung.
"Lo kenapa?"
"Gue tinggalnya pisah. Terkadang cuman butuh satu alasan untuk merusak hubungan yang dekat dan ratusan alasan untuk memperbaikinya."
Absennya suara membuat Aksa melirik Renja, walau melalui gestur tubuhnya, lelaki itu tahu dia mendengarkan dengan baik. Membuat bibirnya tertarik, melawan gravitasi. Apa ini alasan Juna selalu mencari teman di luar sana dan meneriakkan dirinya untuk melakukan hal serupa. Mencari sosok yang tepat bukan hanya sekadar kamuflase.
Hanya dengan berbincang seperti ini, perlahan bongkahan batu itu mulai retak. Tidak, bukannya lenyap. Bertemu dengan seseorang yang cocok tidak serta merta akan menyembuhkannya, lebih lagi merubah dirinya. Tetapi, setidaknya, dia tidak perlu terseret semakin jauh dan berakhir tenggelam dalam dasar gelap itu.
Duduk bersisian dengan Renja membuat benang rumit yang menjadi tumpukan sampah dalam benak, sesuatu yang berusaha disingkirkan Aksa tanpa disentuhnya perlahan terurai.
Membuatnya bertanya-tanya, apakah ini alasan gadis itu senantiasa menjadi topik perbincangan dalam diam?
Menjadi sosok yang diperhatikan, menjadi mekanisme yang menarik untuk diketahui dan diuraikan. Ketika bertemu pertama kalinya, ketika malam penuh kegilaan itu terjadi, Aksa berpikir Renja adalah sosok yang bebas, seperti burung yang terbang tinggi di udara. Lalu, pada pertemuan kedua, dia seperti melihat jiwa berbeda. Persona lain. Seolah setiap tindakan, perkataan, dan dirinya diperintahkan untuk mengikuti aturan tak kasat mata.
Gadis itu mengingatkannya dengan mitologi Pandora dan kotak terkutuk, menarik rasa penasaran untuk dibuka tanpa dapat mengetahui apa yang menanti. Membuatmu terjebak di antara berani dan pasif.
Dia melihat sisi Renja yang sekalipun tidak banyak bergerak, tidak banyak bersuara, tetapi penuh kehidupan, seolah api terbakar di balik manik cokelat itu. Menyerupai biji kopi yang senantiasa dibakarnya untuk nenek dan kakeknya setiap pagi. Menguarkan aroma kopi menenangkan sekaligus memberi semangat.
"Manusia itu rumit, meski rasanya itu yang menjadi daya tarik mereka. Kita terkadang membenci kejadian tertentu, merenunginya, bahkan berharap untuk mengulangi kejadian tersebut dan merubahnya."
Suara Renja yang tenang, hampir menyatu dengan hujan di luar sana. Mengalir begitu saja.
"Walau pada akhirnya melakukan nol proses, tidak bergerak, terlalu takut untuk melakukannya." Dia menautkan jari-jemarinya, merasakan tiupan angin menyapu wajah, mengantarkan rasa dingin. Seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah memiliki keberanian untuk merubahnya. Terlanjur terjebak dengan keadaan. Berlarut dalam kebenciannya.
***
"Tumben balik telat."
Suara ramah kakeknya yang penuh semangat itu membuat Aksa tertawa pelan, memasuki rumah bergaya Belanda itu. Meski sudah direnovasi, kakeknya tetap mempertahankan beberapa ciri khas rumah mereka.
"Udah makan, Sa?"
Kali ini, suara omanya yang menyambut, wanita paruh baya itu masih tampak segar. Dia membawa satu nampan berisi buah-buahan yang sudah dipotong, meletakkannya di atas meja ruang tamu.
"Sini Sa, nonton match ulang kemaren."
Aksa melangkah mendekat dan menjatuhkan tubuh di sisi kakeknya yang tampak berseri-seri. "Duh, kamu telat nontonnya," cercanya sambil menusuk apel dalam mangkuk. "Dunk-nya tadi mantep banget."
Aksa ikut menusuk buah dalam mangkuk, memandangi omanya yang kini tengah membaca artikel dari iPad putihnya yang dia tebak merupakan artikel tanaman seperti biasa. Membuat Aksa sedikit bergidik.
Semenarik apa pun, artikel-artikel itu membuatnya bosan. Lebih senang jika Natasha berbicara langsung padanya untuk menjelaskan.
"Aku mau belajar, Kek."
Pria tua itu mendecak, mengibaskan tangan di udara. "Nanti aja itu, kamu udah pinter ini."
Natasha langsung terkekeh. Hal itu sukses membuat Aksa mendengus. Merasa terhina. "Aku beneran naik nilainya."
"Ya, ya. Terserah kamu."
Aksa melemparkan tatapan jengah. "Kek, liat Oma."
Kakeknya, Pratama, tertawa pelan. "Kamu abis apain bunga Anggreknya?"
Sial.
Aksa menggigit bibir, nyaris berlutut jika Natasha tidak mengangkat wajah dan tertawa pelan, berucap santai, "abis ini kamu tinggal bantu tanam yang baru. Sendirian."
"Maaf, Oma."
Pratama tertawa puas menyaksikan pertunjukan singkat itu. "Harusnya jangan dimaafin, dia mah lupa mulu."
Aksa mendengus, mempertanyakan mengapa kakeknya yang satu ini senang mengusilinya.
"Gak usah kamu bikinin kopi aja Sa," ujar Natasha yang sudah kembali pada aktivitasnya, seolah dapat membaca pikiran Aksa. Perkataan itu membuat Pratama menggumam kesal.
"Impas ya, Kek," kekeh Aksa lalu menaiki tangga. Menuju kamarnya cepat sebelum mendapat balasan lain dari Pratama.
Dia menyalakan lampu, merogoh saku celana untuk mengeluarkan ponsel. Tangannya berhenti ketika menyentuh satu kotak rokok, Aksa mengeraskan rahang.
Sudah lama dia tidak mengisap nikotin itu.
Lelaki itu kemudian merogah lebih dalam dan mengeluarkan satu botol kaca berukuran kecil dengan tutup gabus, menyimpan bunga matahari di dalamnya.
"Kemaren gue coba buat ini, biasanya di dalemnya pasir tapi tiba-tiba gue kepikiran bakal cantik kalo diisi bunga."
Tawa renyah Renja kembali berputar dalam benaknya, ketika manik gadis itu berubah selagi memandangi hasil kerjanya.
"So, bunga matahari. Gue coba cari-cari artinya, gue pikir this will suit you."
Aksa ikut tersenyum, menggenggam botol kecil itu selagi mendekati kasur, menjatuhkan tubuh di atasnya selagi memandangi langit-langit kamar.
Untuk pertama kali, ketika hanya tersisa dirinya sendiri di ruang ini, Aksa dapat memikirkan sesuatu yang lain. Membuat darahnya berdesir.
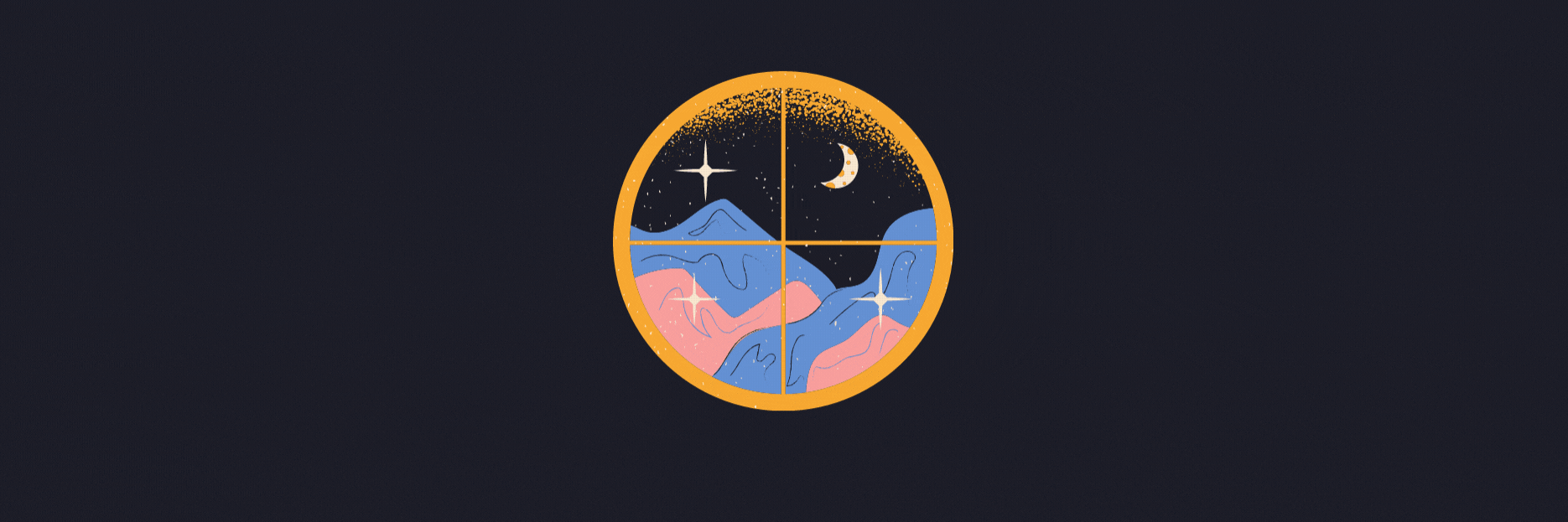
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top