06. Potret Rupa
"Buset, lo mau sekalian jaga sekolah?"
Juna menggeleng pelan, melihat pukul berapa lelaki itu tiba. "Abis nge-date?" godanya sambil terkekeh begitu melihat penampilan Aksa yang jauh lebih rapih. Padahal, biasanya lelaki itu tidak pernah langsung mengganti pakaiannya selepas olahraga.
Aksa hanya tertawa, bergerak masuk tanpa memedulikan celotehan Juna yang sebagian besar berisi kalimat-kalimat godaan dan pertanyaan.
"Om, Tante," sapanya begitu melihat kedua orang tua Juna di ruang makan, hendak bergerak menuju lantai atas, tempat di mana kamar Juna dan kedua kakaknya terletak sebelum suara Intan menginterupsi. Menghentikan langkahnya.
"Eh, Aksa, udah lama kamu gak mampir," ucap Intan. "Mau makan dulu?"
Juna menipiskan bibir, memilih naik terlebih dahulu. Membiarkan sahabatnya yang satu itu mengurusi masalahnya sendiri.
"Enggak, Tante. Aku udah makan sebelum ke sini," balas Aksa sopan. Lelaki itu sempat bertukar kata lagi selama beberapa waktu hingga dapat terbebas dan menyusul Juna yang sudah berada di kamarnya.
"Lo latian sampe malem lagi?"
Kali ini, suara Sena yang dalam yang pertama kali menyambutnya. Membuat Aksa mendecak.
"Dia udah punya cewek baru sekarang," cemooh Juna sambil menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Membuka ponselnya dan kembali melanjutkan permainannya yang terhenti. "Siapa Sa? Anak sekolah lain?"
Sena tertawa pelan, melirik Juna. "Biasanya lo yang paling cepet kalo soal gosip."
Juna mendecak. Tidak menerima tuduhan yang diberikan oleh Sena. Selama ini, dia hanya menyebarkan informasi yang ada. "Gue cuman kasih berita."
"Berita yang belom tentu bener ya gosip, payah lo."
Aksa terkekeh, menjatuhkan tasnya di dekat milik Sena lalu meraih stik play station yang terletak di meja dan duduk bersama Sena. "Nakula mana?"
"Lagi telponan sama bokapnya di balkon luar," jawab Juna lalu meletakkan ponselnya di atas kasur. Memandangi kedua temannya yang mulai bermain. Sena dan Aksa kerap kali berkunjung ke rumahnya ketika ingin bermain game lantaran Juna yang tidak pernah absen membeli apa yang baru saja keluar.
Maniak.
Juna sendiri tidak keberatan dengan sebutan itu, baginya game adalah realita dalam bentuk yang lain, ketika hanya keahlian yang dibutuhkan untuk bertahan. Dunia yang tidak akan menghakiminya hanya dari pilihan-pilihan yang dia sukai.
Bebas menentukan hidupnya.
"Kenapa La?"
Seluruh perhatian langsung tertuju pada Nakula begitu Juna membuka suara. Lelaki itu mengendikkan bahu lalu tersenyum. Senyuman yang sama setiap kali dia selesai menelepon.
Senyuman yang pernah menghantui Aksa. Membuat lelaki itu mengeraskan rahang. "Mau balik La?"
Nakula melirik jam kotak yang berada di atas meja Juna, lalu mengangguk. "Besok deh gue mampir lagi," kekehnya dengan raut bersalah. Padahal mereka berencana untuk tidur larut malam ini dan bermain hingga pagi.
Sena yang pertama menggeleng. "Itu mah gampang, ntar lo chat aja."
"Lo balik sendiri La?"
"Bareng gue aja," tambah Aksa. Fokusnya kini sudah berubah, jatuh pada punggung Nakula yang sibuk merapihkan barangnya. Meski, sejak awal barang lelaki itu sudah rapih. Hidupnya selalu seperti itu. Begitu tertata dan terstruktur.
Terkekeh, Nakula menyampirkan tas hitamnya. "Gue gak pulang buat mati," ujarnya ringan, seolah mengerti apa yang berada di pikiran Aksa. "Mending lo pada latian biar gak kalah mulu sama gue."
Ucapan tadi sukses membuat Sena merengut kesal, sudah berapa kali dia kalah ketika melawan Nakula? Padahal penampilan lelaki bersurai hitam itu seperti anak teladan yang senantiasa belajar, tidak, Nakula memang selalu belajar di sekolah.
Buku-buku tidak pernah lepas dari tangan hingga dia perlahan menjabat sebagai ketua OSIS. Sehingga ketika Aksa pertama kali mengenalkannya dan Nakula perlahan bergabung, Sena sedikit meragukan tindakan lelaki itu. Bukankah mereka hanya akan menjadi penghambat bagi lelaki itu?
Meski perlahan dia mulai menyadarinya. Dalam bidang apa pun lelaki itu turun, dia tidak pernah gagal. Membuat Sena menelan saliva gugup, kemampuan seperti itu dapat berubah menjadi pedang bermata dua.
"Gue dijemput sama sopir buat ketemu sama temen bisnis bokap gue." Setelahnya, lelaki itu menghilang dari pintu yang diikuti Juna. Perlahan menuruni tangga dari kayu itu.
"Kamu udah mau balik?"
Juna dan Nakula menoleh, mendapati seorang wanita dengan rambut hitam tergerai rapih. Meletakkan buku medis yang dibacanya. Juna lantas melirik Nakula yang berada di hadapannya. Sedikit penasaran bagaimana percakapan ini akan berakhir.
Apakah akan kembali seperti yang sudah-sudah?
"Iya, Tante. Saya diminta temenin Papa."
Alis Intan terangkat dengan bibir tertarik. "Wah, hebat ya kamu," ucapnya. "Kemarin katanya kamu bakal masuk sekolah bisnis 'kan?"
Nakula menggaruk tengkuknya. "Iya, Tante."
"Baguslah, memang seharusnya begitu biar bisa banggain keluarga."
Nakula mengulas senyum, mengangguk pelan selagi dia melirik jendela yang terbuka begitu mendengar suara mobil. "Tapi saya kadang juga berharap bisa banggain keluarga dengan sesuatu yang beda," ucapnya sambil tertawa dengan ekspresi bersahabat yang jarang dikeluarkannya kecuali dalam waktu tertentu. Situasi tertentu.
"Oh ya, maksud kamu?"
Nakula mengulum bibirnya. Berucap dengan pelan sambil menggaruk tengkuk. "Hal yang jadi keahlian saya dan hal yang saya suka, saya pikir bakal jadi sesuatu yang keren kalo bisa menonjol dengan ciri khas sendiri?" Nakula kembali melirik ke luar. "Eh iya, maaf Tante, saya permisi dulu. Pamit pulang."
Intan memandangi Nakula selama beberapa saat lalu, pada akhirnya melirik Juna. "Hati-hati di jalan."
Dan, pandangannya tidak lepas dari Juna yang hanya berdiri diam.
***
"Ja."
Gadis itu membasahi bibirnya, menoleh pada papanya yang berdiri di dekat pintu ruang belajar miliknya. "Kenapa, Pa?"
Pria setengah baya itu mengendikkan bahu. "Pengen liat aja, gak boleh?" kekehnya, membuat Renja ikut tertawa pelan.
"Tumben aja."
Manik cokelat itu mengekori papanya yang bergerak memasuki kamar yang dipenuhi lukisan, belasan rak buku, alat musik, dan tumpukan kertas serta poster di dinding. Meski sudah memasuki usia yang cukup tua, pria yang turut membesarkannya itu masih tampak sehat walau kerutan pada wajahnya samar-samar terlihat di bawah cahaya.
Lelah dengan segala yang terjadi belakangan ini.
Renja menghela napas, dia hendak membuka mulut, mempertanyakan keadaan pria yang selalu memberikannya nasehat sebelum kembali tertutup. Dia mengepalkan tangan, hubungan mereka tidak pernah seperti itu.
Sepanjang ingatan Renja, dirinya dan Elegi tumbuh dalam keluarga dimana mereka tidak pernah membahasa masalah pribadi maupun perasaan. Memilih diam. Sehingga ketika berada pada situasi ini dia hanya mampu berharap dalam hati.
"Gimana latihan kamu?"
Renja mengerjap, kedua obsidian itu bertabrakkan dengan mata yang serupa.
"Gitar, ngelukis atau belajar bahasa?"
Renja membasahi bibir. "Lumayan," ucapnya, berjalan mendekati meja miliknya. Gadis itu mencoba menyingkirkan kertas lain yang berada di atas gambar miliknya meski papanya bergerak lebih cepat, membuat dia merutuk dalam hati.
"Kamu masih suka nulis?"
"Masih," ujarnya ragu, lalu dengan cepat menambahkan, "tapi kadang-kadang doang, waktu aku lagi nganggur."
James mengangguk selagi memegang kertas itu, membacanya singkat sebelum menjatuhkan tubuh di atas kursi bulu milik Renja, tempat di mana gadis itu biasanya berbaring jika ingin beristirahat. "Bakal lebih bagus dan bermanfaat kalau kamu nulis berbasis riset atau essai. Bisa kamu kirim untuk lomba."
Renja menarik sudut bibir. Ikut menjatuhkan tubuh di kursi yang berseberangan. "Aku baru kemarin coba pelajarin soal sejarah Mesopotamia, gimana salah satu faktor penting dari perkembangan kebudayaannya di pengaruhi alam." Gadis itu memutar kursinya sehingga mata mereka kembali bertatapan. "Hingga mereka bisa jadi tempat lahirnya peradaban. Mencipatakan sistem menulis, meski saat ini masih banyak perdebatan. Kemudian, rajanya Hammurabi yang punya kebijakan-kebijakan luar biasa sekaligus kemampuan politiknya."
Renja melirik sticky notes yang tertempel di dinding.
"Benar, padahal sebelum itu, Ayahnya Hammurabi sempat dikalahkan oleh Raja Rim Sin 1 di tahun 1792 sewaktu dia naik takhta dan Babylonia masih kalah jauh jika dibandingkan Larsa. Sistem menulis sendiri dikatakan berkembang secara independen di empat tempat berbeda." James kemudian memandangi lukisan langit milik Renja yang tertempel di dinding. "Gambarmu cukup berkembang, cuman bakal lebih menarik kalau kamu mikirin suatu konsep sewaktu gambar, apa yang mau kamu sampaikan, apa yang ada di balik lukisan ini dan coba kuatin basic-basic-nya. Jangan takut buat mainin warna."
Hubungan mereka selalu seperti ini.
Meski, Renja tidak pernah mengharapkan lebih daripada ini, cukup puas dengan keberadaan James yang selalu menjadi teman diskusi yang baik.
James menatap putrinya. "Kamu gak perlu jadi sehebat Mozart dan Papa gak akan perlakuin kamu kayak Johann ke Beethoven, tapi gak ada salahnya kamu berusaha sekuat tenaga dan pelajarin semuanya selagi bisa."
Renja kembali tersenyum. Tertawa pelan. "Tenang aja Pa, aku gak akan berenti belajar." Dan, percakapan hari itu berakhir begitu saja, papanya yang kembali ke ruang kerjanya sementara Renja memutuskan untuk berbaring di atas sofa. Memperhatikan langit-langit ruangan yang dihiasi dengan peta bintang.
Hanya dengan memperhatikan bintang-bintang itu dia merasa hidup sekaligus merasa kecil di antara ribuan benda angkasa di atas sana.
"Renja."
Dia menipiskan bibir, perlahan bangkit dan menatap mamanya yang berdiri di ambang pintu. "Kenapa, Ma?" Melihat absennya senyum di bibir, Renja mulai memperkirakan bagaimana kisah ini akan berlanjut.
"Nilai kamu berapa?"
"Nilai... apa?"
Alana bersedekap, perlahan menutup pintu di belakang membuat Renja menelan saliva.
Sial.
Dia lupa bahwa kertas ulangannya berada dalam kantung.
Renja perlahan mengambil langkah mundur, dia mengeraskan rahang begitu melihat tangan yang semula berada di samping tubuh Alana perlahan terangkat. Berusaha keras untuk tidak bereaksi.
Kedua matanya secara spontan terpejam begitu tangan Alana terayun.
Satu detik.
Dua detik.
Tidak ada yang terjadi. Tamparan di pipi tidak diterimanya seperti yang sudah-sudah, membuat dada yang bergemuruh perlahan kembali pada ritme normal. Dia mengerjap, memandangi obsidian Alana.
Wanita bersurai pendek itu perlahan menghela napas. Mengepalkan tangannya. "Pramadita berapa?"
Renja menipiskan bibir. Dia membenci bagaimana situasi ini berubah, membuatnya tertawa sinis dalam hati. Bukankah lebih baik Alana menamparnya ketimbang menekannya seperti ini.
"Seratus."
"Kamu?"
Renja kembali mengeraskan rahang, hal itu hanya membuat Alana semakin murka. "Jawab, Renja!"
"Sembilan lima."
"Kenapa?" Alana bersedekap. "Kamu salah di mana?" Dia kemudian menyandarkan tubuh pada rak yang berjejer di belakang. Melirik sebentar buku-buku itu. "Mama kan udah bilang kalo kamu harus berusaha semaksimal mungkin, kita gak akan tahu ke depannya gimana Ja. Nilai-nilaimu itu penting. Jangan karena kamu selama tiga tahun di atas menganggap sepele semuanya."
Renja menundukkan kepala. Berusaha keras menutup rapat mulutnya agar situasi ini tidak berubah menjadi pertengkaran. Renja masih mengingat setiap detail kejadian beberapa waktu lalu ketika dia mencoba membela diri. Ketika satu vas bunga melayang, pecah begitu menyentuh tanah.
Menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
"Mama gak pernah maksa kamu untuk kerja atau bantu dalam hal lain, cukup belajar Ja." Wanita itu mendesah, kerutan di wajahnya terlihat semakin jelas. Kehidupan mereka, rumah ini, dan hubungannya mulai mempengaruhi Alana padahal sebelum ini, wanita itu tampak gemilang. Sempurna. Baik penampilan, akademis, dan dalam bersosialisasi.
"I try," gumam Renja, pelan, seringan desau angin.
"What? Mama mau kamu buktikan, bukan cuma ngomong."
"I try, Ma." Renja mengangkat kepala, dia mengeraskan rahang, mencoba mengabaikan teriakan dalam benak yang memintanya untuk berhenti.
Berhenti sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk.
Berhenti sebelum dirinya terluka lebih banyak lagi.
Sebelum luka yang mulai sembuh itu kembali menganga.
Tetapi, gadis itu sudah lelah hidup seperti ini selama empat tahun. Dia mengerti posisi Alana, mencoba memahami mamanya yang berusaha bertahan dalam kegilaan ini, tetapi, apakah wanita itu harus memproyeksikan rasa sakitnya pada dirinya?
Renja mengepalkan tangan. "I do my best." Suaranya meninggi. "TAPI APA YANG BISA AKU LAKUIN? DI SAAT APA PUN YANG AKU LAKUKAN GAK PERNAH CUKUP. I barely sleep, aku bahkan gak bisa—"
"—cukup."
Satu tamparan melayang.
Perih, tetapi gadis itu sudah terbiasa. Dia tersenyum kecil, satu tetes liquid jatuh, menyusuri lekuk wajahnya.
Dia mengerjap, berusaha menahan sisanya yang menunggu untuk keluar. Dia tidak boleh tumbang dan goyah.
"Mama lahirin dan besarin kamu susah payah bukan untuk dikurang ajarin," ucapnya, menatap tajam Renja sebelum berbalik, melangkah pergi dari ruangan itu. Meninggalkan Renja yang perlahan jatuh ke atas lantai kayu.
Dia tertawa pelan. Rasanya seluruh pijakannya benar-benar hancur saat itu. Dadanya terasa sesak selagi berusaha menutupi wajah dengan tangan, meredam suara tawa yang semakin kencang seiring tangisan yang pecah.
Dia tidak mampu menahannya lagi.
Mengapa semesta selalu bekerja melawan dirinya?
Mengapa dia tidak pernah menjadi cukup baik? Bukankah dia sudah bekerja keras, menyerahkan seluruh waktunya, bahkan rela menjual jiwanya demi dapat menjadi lebih baik. Tetapi, mengapa? Mengapa dia tidak pernah cukup baik.
Selalu tenggelam dalam kegagalan yang sama dan berulang.
Renja memejamkan mata. Mencoba mengatur napasnya sebelum perlahan bangkit berdiri dan menghapus seluruh jejak air mata. Keributan tadi dapat menarik perhatian dan Renja tidak ingin siapa pun melihatnya tampak berantakan seperti ini.
Dia meraih satu kaca yang terletak dalam laci, menuangkan air dari dalam botol selagi membasuh muka.
Menangis hanya menunjukkan kelemahannya.
Renja memandangi dirinya pada pantulan kaca. Memejamkan mata, merasakan sensasi air dingin pada kulit. Dia menelan saliva, berusaha menyingkirkan imajinasinya yang memikirkan rencana untuk meraih benda tajam, benda yang dia simpan rapih di dalam laci seandainya hal seperti ini terjadi.
Setidaknya, hal itu memberi waktu baginya untuk berpikir jernih.
Dia menggigit bibir.
"You're amazing, Ja."
Renja meraih tissue di atas meja, mengeringkan wajahnya. Entah mengapa, hippocampus miliknya malah memutar perkataan Aksa.
"Gue berharap, lo bisa sadar dan tau itu."
Renja hanya tertawa hambar selagi perlahan keluar, mengendap-endap naik.
Bagaimana bisa dia menelan hal itu, jika wanita yang melahirkannya saja menganggap dia tidak berguna.
"Kenapa, Kak?"
Elegi yang tengah berbaring dan memainkan ponsel mengangkat wajah, memandangi wajah kakaknya itu.
Renja terkekeh pelan selagi berucap, "kenapa, kangen ya?" Menarik bibirnya selebar mungkin, dia mengangkat alis, menggoda adiknya.
Elegi mendecih, kembali fokus pada layar ponsel. "Amit-amit, Kak."
"Gak perlu malu gitu," candanya sambil menjatuhkan tubuh di atas kasur. Perlahan memejamkan mata, mencoba menelan bulat-bulat rasa yang mencekiknya. Jika, sekali lagi dia mengabaikannya, tidak akan menjadi masalah bukan?
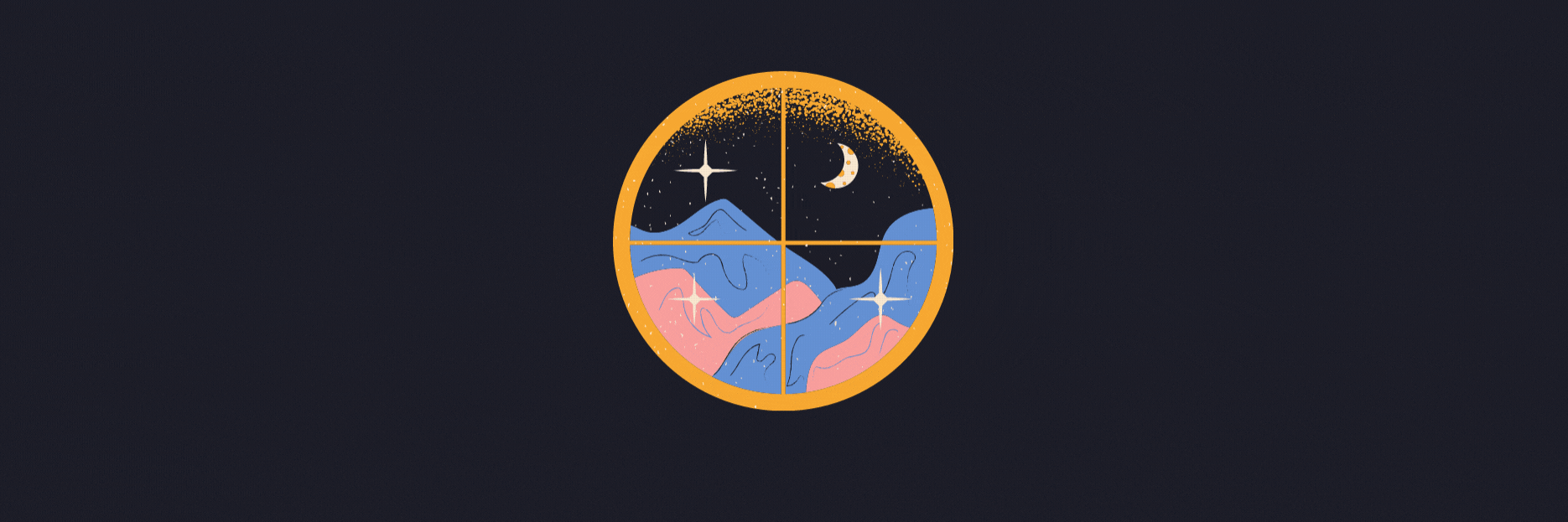
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top