01. Luar biasa
"Udah bener belajarnya?"
Renja yang tengah merapihkan rambutnya melirik wanita yang kini duduk di belakang kemudi, menatap pantulan wajahnya dari kaca membuat Renja terpaksa mengulas senyum. Memasang topeng lain. "Udah, Ma."
"Kamu harus usahain supaya peringkatmu naik lagi. Jangan kebanyakkan main dan ngegampangin, mentang-mentang kamu selalu ada di atas."
Renja hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak memberikan balasan. Menutup mulut rapat-rapat dan mendengarkan seperti yang selama ini dituntut darinya.
Bersikap pasif.
Lagipula, tidak ada gunanya membela diri. Reaksi yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan aksinya, jauh berbeda dari hukum aksi reaksi milik Newton yang dia pelajari.
Satu-satunya yang dapat gadis bersurai cokelat itu lakukan hanya mengepalkan tangan di bawah kertas catatan miliknya. Memperkirakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai sementara adiknya sibuk memainkan ponsel diam-diam dengan telinga tersumpal. Memutuskan untuk tidak terlibat dalam ritual pagi ini.
"Jangan terlalu baik juga," tambah Alana selagi memutar kemudi. "Jangan mau dimanfaatin orang lain.
"Tenang aja, Ma."
Rutinitas memasuki musim ujian akan selalu dihiasi oleh omelan dengan tameng nasehat yang tidak berhenti, tidak sampai mobil hitam yang dikemudikan Alana berhenti di depan gerbang sekolah dan Renja turun dari mobil.
Gadis itu langsung menyambut Rea yang tengah bersandar selagi memainkan ponselnya, sedikit tersembunyi di dekat dinding.
"Tumben rada telat Ja," ujar Rea selagi merangkul dan menarik Renja yang lebih tinggi darinya memasuki gerbang sekolah. Merapihkan rambut panjangnya ke belakang, dia melirik Renja. Memicingkan mata. "Tidur sampe pagi lagi lo?"
Renja hanya tertawa. "Udah belajar?"
Rea merotasikan mata, mengetahui niat Renja untuk mengganti topik percakapan mereka. Tidak ada satu pun dari nasehat dan peringatannya yang didengar. Keras kepala. "Lo rajin gitu gak mau sekalian ngikut lomba? Ditolak mulu perasaan."
"Kaga ah, gue," ucapannya terhenti, membuat Rea melirik Renja dengan tatapan menyelidik. "Gue sibuk."
Rea hanya mengangguk. Tidak mudah untuk membujuk Renja ketika gadis itu sudah memutuskan sesuatu, kecuali segala sesuatu yang berkaitan dengan nilainya.
Begitu keduanya memasuki ruang kelas tiga, seolah menjadi bagian dari pertunjukkan, tatapan seluruh murid di dalam menghujami mereka terutama Rea yang berjalan lebih dahulu, membuat Renja menelan saliva. Seolah gadis itu adalah tersangka.
Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang dapat dilakukannya. Renja mengepalkan tangan, seandainya saja dia memiliki keberanian lebih untuk berbicara selain menyumpah serapahi mereka semua.
"Lo duduk mana, Ja?"
Suara tinggi itu mengalihkan perhatiannya sementara tatapan menusuk seluruh penghuni kelas masih terarah pada Rea, memperhatikan dengan rasa lapar apa yang akan dilakukannya. Renja ingin tertawa, mereka seperti hewan buas yang tidak memiliki akal.
"Deket jendela, kursi ketiga dari belakang," ucapnya selagi menunjuk tempat duduknya dengan dagunya.
Rea mengangguk, mengekori Renja dan menjatuhkan tubuhnya di atas meja di depan gadis bersurai cokelat itu. Dia melempar senyum miring, mengangkat satu alisnya pada salah satu kakak kelas yang duduk tidak jauh dari sana. "Kenapa?"
Gadis itu mengerutkan wajahnya kesal, hendak membalas sebelum seruan demi seruan mengalihkan perhatiannya.
"Mal! Telat mulu lo!"
"Cie yang kemaren abis jalan, mana nih traktirannya? Tinggal masuk cheers aja bareng gue."
Pemilik nama tertawa pelan, perlahan tenggelam dalam perhatian yang diterimanya. Mala, bahkan di tahun pertamanya di bangku SMA, gadis itu sudah menarik puluhan perhatian kakak kelas mereka. Sosok yang hampir selalu ditemukan di setiap sekolah. Ramah, cantik, dan populer.
Tubuh rampingnya dengan wajah yang mungil serta mata bulat membuat gadis itu semakin sempurna.
Rea memperhatikan semua itu untuk beberapa saat, mengulas senyum sebelum beralih pada Renja yang sibuk mengeluarkan catatannya.
"Manusia memang aneh. Mereka selalu ngerasa inferior, walau kata Alfred Adler itu udah bawaan semenjak lahir," ujar Renja.
Rea hendak membuka mulut sebelum menutupnya kembali ketika Renja melanjutkan, "nih, lo baca Re." Renja mengangkat satu jilid kertas yang penuh warna.
Rea terkadang takjub dengan cara kerja otak sahabatnya. "Lo memang unik," ungkapnya, menggeleng pelan. Selama mereka berteman selama tiga tahun, Renja hampir tidak pernah menghibur dengan kata-kata biasa. Seolah gadis itu tidak mengerti caranya.
Pandangannya kembali terarah pada kertas di tangan. "Gila, ini kayak udah kayak pelangi," komentarnya terus terang, mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa beban lalu terkekeh pelan, membuat Renja mendengus. "Makasih banyak Ja. Siang gue traktir lo deh."
"Mending lo belajar dulu sana, pahamin aja yang udah gue lingkarin, itu poin-poinnya."
Rea mengangguk. "Gue harus nemuin Nakula dulu, mau serahin proposal sama data yang dia minta," ucapnya setengah merasa bersalah.
"Bukannya Kak Nakula juga ujian?"
"Dia kan rada sinting," decak Rea, teringat kembali dengan kejadian kemarin yang membuatnya terjebak dalam situasi ini. "Ntar gue ceritain ke lo pas pulang, gue pinjem yang ini ya." Setelahnya, tanpa mengatakan apa pun lagi Rea menghilang dengan cepat dari dalam kelas, meninggalkan Renja seorang diri, berusaha memahami rumus demi rumus Hukum Newton dan mengetahui konsepnya seperti yang pernah diajarkan oleh Papanya sewaktu dia duduk di sekolah dasar. Ketika segala sesuatunya masih berjalan sempurna dan pondasi itu masih kokoh.
Kepalanya berkedut pelan, dia hanya tertidur selama kurang lebih dua jam sebelum terpaksa bangun dan berangkat ke sekolah. Berharap cemas tidak tertidur dan mengacaukan segala usahanya.
"Gila, lo suram banget."
Renja mengangkat wajah untuk mendapati Pramadita tersenyum kecut dengan kantung mata yang sama. Gadis berkulit kecokelatan dengan rambut sebahu itu adalah sosok yang menjadi subjek favorit Alana. Orang yang memegang peringkat ke dua selama tiga tahun berturut-turut sekaligus mimpi buruknya.
Pramadita tertawa pelan. "Sampe jam berapa lo? Gue hari ini tidur lebih pagi kayaknya, jam tiga udah gak kuat, kebablasan main game juga," celotehnya sambil membaca deretan kata yang bercampur angka di atas kertas catatan miliknya.
Renja bergumam pelan, "lumayan. Kemaren gua abisin banyak kopi." Lalu dia tertawa, kembali teringat berapa banyak kopi yang dihabiskannya hingga memancing amarah dari mulut Mamanya. Mengancam akan menyita seluruh minuman berkafein di dalam rumah.
Pramadita ikut tertawa. "Eh, ujiannya cuman sampe materi hukum Newton 'kan ya?"
Renja dengan cepat memindai seluruh catatannya, menipiskan bibir ketika menyadari satu materi tambahan yang diberikan oleh gurunya di akhir kelas. Wajar saja jika tidak semuanya mendengar, terlebih ketika mereka sudah mulai sibuk dengan euforia sesaat akan selesainya pelajaran menyesakkan tersebut.
Dia mengepalkan tangan bersama rahang yang mengeras, Renja terkekeh sinis dalam kesunyian, mengapa semesta seolah bekerja untuk mengejeknya dengan semua yang terus terjadi. Tidak membiarkan dirinya bernapas dengan tenang, membuat pikiran yang sudah dipenuhi hujan kini kembali berkecamuk menjadi badai besar. Membuat tubuhnya menggigil tidak nyaman di tempat.
"Ja, lo oke?"
Suara itu terdengar samar-samar dengan pikiran yang semakin kalut, nada tinggi seperti bunyi piano itu mengabur bersama pikiran yang terbagi menjadi dua hal berbeda. Menjadi sisi yang berlawanan di atas koin yang sama.
Haruskah dia memberitahunya? Atau menutup mulut dan memanfaatkan keadaan, lagipula, bukan salahnya sehingga gadis itu tidak mendengar dan sibuk bercengkrama.
Dia menggigit bibir, mencoba menyingkirkan tatapan tajam wanita yang melahirkannya dan mengangkat wajah. Tersenyum kecut. Menarik napas panjang. "Kayaknya cuman sampe situ doang," ucapnya sedikit tersendat. "Gue rada kurang yakin juga."
Pramadita mengangguk. Gadis itu mengukir senyum, berucap pelan selagi melangkah keluar. "Makasih Ja."
Renja mengacak rambutnya pelan, dia membenci dirinya yang tidak dapat melepaskan obsesi sekaligus harapan orang tuanya. Pada akhirnya, menjadi sama seperti mereka yang hidup dengan topeng. Berpura-pura, memanfaatkan keadaan demi meraih keuntungannya sendiri.
Ambisi, dia teringat dengan lelaki berlesung pipi dengan presensinya yang menenangkan dan topik percakapan mereka pagi ini. Sepertinya, kali ini dia yang kalah.
Berusaha mengabaikan teriakan lain dalam benak, dia mengembalikan pandangan pada kertas di atas meja. Kembali bergelut pada kewajibannya.
Rea baru kembali setelah bel berbunyi bersama wajahnya yang kusut, guru yang sudah hadir di depan kelas membuat Renja mengurungkan niat untuk bertanya. Membereskan peralatannya dan duduk dengan tenang sesuai instruksi.
***
"Kantin Re?"
Rea menggeleng, setengah merasa bersalah. "Gue cuman bisa kerjain pilihan gandanya," ucapnya pucat. "Lo bayangin, gue bahkan bisa kerjain itu karena lo sempet kasih ke gue catatan tadi. Kalo enggak gue bakal dapet nol."
Renja terkekeh pelan, membuat Rea mengerut semakin kesal. "Fisika yang tadi memang susah sih. Gapapa Re, setidaknya gak lo kosongin."
Rea menipiskan bibir selagi menggumam. Menjatuhkan wajahnya di atas meja. Benar, setidaknya dia menuliskan angka-angka dalam soal. "Nakula sialan."
"Gak ke kantin?" Renja menyodorkan roti miliknya yang diterima Rea setengah ragu.
"Gak makan? Gue tadi udah sarapan," ucap Rea, setidaknya dia harus belajar untuk pelajaran berikutnya.
Renja mengendikkan bahu. "Gue masih kenyang, mau belajar di perpustakaan. Mau ngikut?"
"Kagak deh."
Balasan itu datang terlalu cepat, membuat Renja terkekeh. Entah mengapa, Rea bermusuhan dengan segala hal yang berbau buku berbanding terbalik dengan dirinya. Jika diibaratkan, mereka seperti kutub yang berlawanan tetapi saling menarik ketika berdekatan.
Kaki jenjangnya bergerak cepat membelah jalan, menuruni tangga menuju lantai satu. Perpustakaan terletak di dekat pintu menuju kantin, membuat Renja harus memutari lapangan untuk tiba di tempat itu.
Selama masa ujian, akibat bergabungnya tiga angkatan dalam satu kelas membuat banyak dari mereka yang beristirahat di selasar sekolah sehingga Renja berusaha keras untuk tidak bersilangan jalan dengan mereka. Berjalan cepat.
"Ja!"
Tubuhnya menegang ketika mendengar suara itu mendekat, kakinya seolah terpaku pada lantai, menghalangi usahanya untuk bergerak. Dia menelan saliva.
"Gila, lo jalan cepet banget," ucapnya sambil berusaha mengatur napasnya yang tersengal-sengal. "Makasih banyak ya," ucap Pramadita, gadis itu menarik bibirnya membentuk kurva lebar membuat rambut pendek yang berpotongan oval itu ikut bergerak. "Kalo lo gak ngejar gue tadi kayaknya bakalan dapet nilai nol."
Renja berusaha membalas senyum itu, mengangguk kaku. "Lo tanpa belajar juga pasti bisa seratus," kekehnya. Berusaha bercanda. Pramadita selama ini dianggap jenius di sekolah, kerap dipanggil sebagai Einstein dan sebutan itu tidak salah menurut Renja.
Pramadita adalah segala hal yang tidak dimilikinya.
Segala yang jauh di atasnya.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hasilnya akan selalu dan selalu sama. Dia tidak lebih hebat dari gadis itu sekalipun peringkat mereka berbeda. Pramadita tidak perlu menghabiskan waktu yang sama untuk mendapat nilai sempurna, dia tidak perlu berjuang habis-habisan hanya demi memahami satu soal, dia tidak perlu terbangun di tengah pagi buta untuk memikirkan kemungkinan soal yang dapat keluar.
Pramadita mendecak. "Ah, padahal lo juara satu pararelnya."
Renja hanya tersenyum lemah. Benar, tetapi mengapa dia tetap merasa hal tersebut tidak pernah cukup. Berusaha mengenyahkan pikiran negatif dan kembali pada kewajibannya. "Kantin?"
Pramadita menggeleng, mengendikkan kepala menuju Regan, teman sekelas mereka yang berdiri tidak jauh, sibuk bergelut dengan kameranya, mengangguk, mereka kemudian berpisah.
Perasaan gamang yang menggantung dalam dada setelah percakapan singkat itu perlahan terangkat ketika aroma segar melati memasuki indra penciumannya, diproses melalui sistem olfaktori yang kemudian meneruskannya pada otak untuk diterjemahkan. Aroma melati yang menyapa ketika pintu terbuka itu selalu berhasil membuat suasana hatinya membaik.
"Apa kabar, Ja?"
Berikutnya, pasti suara merdu Kenangan yang menyambut. Diiringi senyum manis puan itu.
Renja melempar senyum serupa, mendekati meja perpustakaan yang digunakan oleh Kenanga untuk mendata buku demi buku yang masuk dan keluar. Puan itu mulai bekerja satu tahun yang lalu dengan alasan mencari pekerjaan tambahan di sela kuliahnya selagi memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Jika tidak salah mengingat, kuliah Kenanga sendiri berkaitan dengan buku.
Perpustakaan di Danudara sendiri terbilang lengkap dengan buku baru yang selalu mengisi rak setiap satu hingga dua bulan. Baik buku berbahasa inggris maupun indonesia.
"Lumayan," balas Renja pelan, memperhatikan Kenanga yang sibuk memilah buku sehingga mudah dikembalikan. Rambut panjangnya dijedai hingga menyisakan anak rambut yang menggantung. Tampak pas dengan tulang pipinya yang tinggi.
Melihat tumpukan buku di sisinya, membuat Renja ingin mengulurkan tangan, memberikan bantuan meski Kenanga dengan tegas menolak. Menatap Renja tajam. "Udah belajar sana, entar nilai kamu malah jelek," ujarnya, mengusir halus menggunakan kibasan tangan. Mengabaikan protes Renja yang keras kepala, puan itu memukul pelan kepala Renja menggunakan salah satu buku tebal. "Buku yang kamu cari udah ada di rak dalem."
Mendesah, Renja mengangguk. Setengah pasrah. Toh, dia tidak dapat banyak mengelak ketika nilai yang menjadi topik perbincangan mereka. Satu-satunya kelemahan yang selalu dipakai Kenanga.
Gadis itu menggerakkan tungkai menyusuri rak demi rak, melangkah menuju tempat favoritnya selagi menghirup aroma buku yang membangkitkan semangat. Sudah cukup lama semenjak terakhir kali dia menghabiskan waktu di tempat ini.
Langkahnya terhenti sesaat ketika melihat lanskap taman belakang sekolah, menyaksikan langit yang menggelap dengan gumpalan awan kelabu menggantung di langit. Diiringi daun-daun yang beterbangan, seluruh pemandangan itu menorehkan senyum di bibir.
Dia menyukai bagaimana kaca yang besar itu mampu menangkap seluruh peristiwa di depan sana, membuatmu seolah terjebak dalam waktu yang tidak pasti. Salah satu alasan lokasi belakang perpustakaan menjadi titik berat, lokasi favoritnya. Belum lagi ketenangan yang dijanjikan. Tidak banyak dari murid Danudara mendatangi tempat ini.
Tangannya kemudian bergerak untuk meraih satu buku bersampul kuning sebelum suara yang tidak asing menginterupsi membuat Renja menoleh. Kedua alis terangkat ketika menyaksikan siapa yang berada di sana dengan senyuman, seolah sudah menanti kehadirannya.
Dia menelan saliva.
Ini sungguh luar biasa.
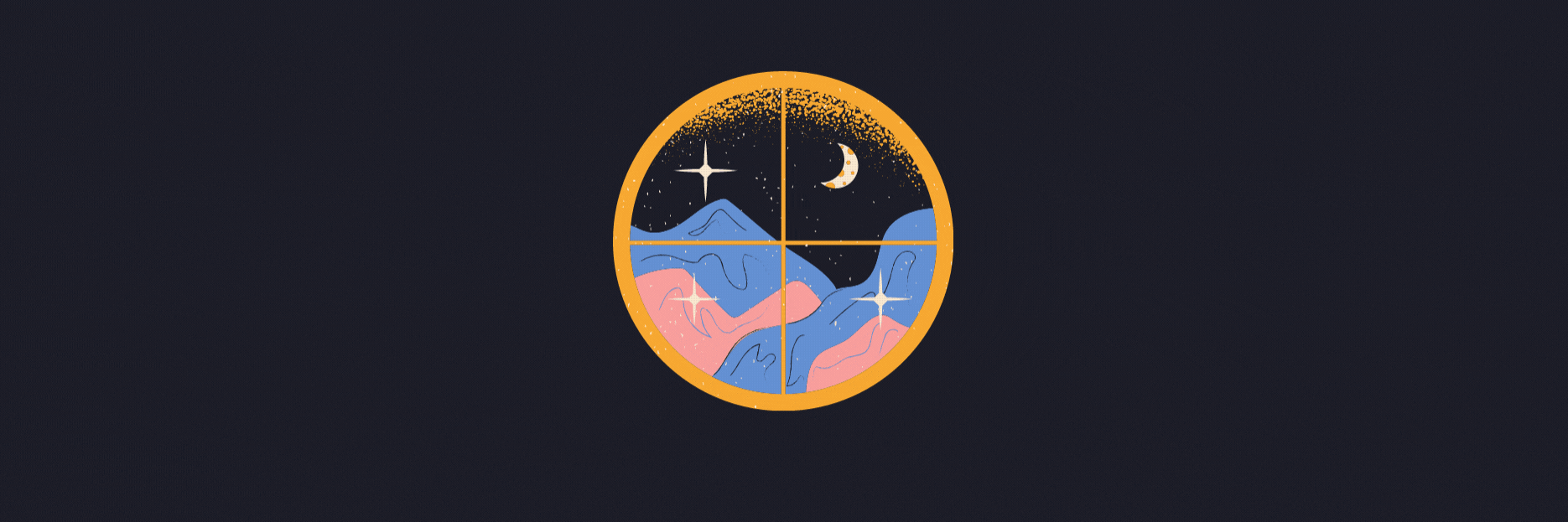
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top