April - 11
Acid
Kalian tau Rama kan? Raden Pramadipta Atmojo, temen kosan gue yang juga seumuran gue tapi jauh, jauh lebih dewasa dari gue yang udah kodratnya infantil ini? Rasanya gue bisa denger teriakan tertahan kalian 'Kyaaaa Mas Rama!!!!' gitu kan? Ya, ya, harap tenang, Rama gak ke mana-mana kok, masih di Komet, belom pergi ke Natuna.
Gue cuma ngasih dia honorable mention di sini buat dia. Kalo bukan karena Rama, gue mungkin gak bakal ngekos di Komet. Komet tuh termasuk ke dalam daftar hal yang paling gue syukuri dalam hidup. Meskipun di dalemnya ada kutu-kutu busuk macem Wawan, Bangsat (bangsat tuh artinya kutu lho), tapi di sana gue nemuin keluarga. Asik, keluargaaaaa.
Komet bukan sekadar tempat ngekos anak SMA sampe anak kuliahan, yang sering rame sama suara nyanyi-nyanyi ngegitar, atau nonton bola, atau maen karambol (sampe sekarang gue gak tau tu dari mana asalnya papan karambol bisa ada di Komet). Komet juga tempat seorang Rasyid Ananta pulang, selain ke rumah sendiri, dan ke pelukan pacar.
Becanda.
Komet tempat gue belajar, 'Oh, jadi gini kalo tinggal bareng orang lain dengan karakter masing-masing', udah gitu karakter mereka ajaib-ajaib, kalo gue sih charming, bukan ajaib.
Ditambah lagi ada Krucils yang bikin gue belajar kalo suatu hari nanti gue punya anak cowok gimana. Sok tua ya. Tapi beneran Krucils Komet tuh bocah-bocah banget dan bikin gue sering ngulang masa-masa gue waktu seumur mereka gimana. Terus gue jadi suka gatel ngajarin mereka cara menjalani hidup lebih seru dan bermakna, because... Carpe Diem, man.
Balik ke topik, Rama adalah orang yang membawa gue ke Komet. Jadi sebelumnya gue tuh gak ngekos, rumah gue emang di daerah luar kampus dan lumayan jauh, tapi gue belom kepikiran buat ngekos, jadi gue pulang pergi naik motor. Oh ya, tapi bukan si Dongker, si Dongker dulu lebih sering di garasi dan predikatnya adalah kendaraan weekend gue. Kendaraan weekdays gue mobil yang pakenya ganti-gantian sama kakak gue.
Jadi ceritanya waktu itu, di penghujung semester satu akhir, gue udah bersiap-siap menyambut liburan pertama gue sebagai mahasiswa yang konon panjang banget itu. Sebenernya gak panjang sih karena gue masih ada satu tugas akhir yang deadlinenya rada telat, harusnya udah libur, akhirnya masih tetep ke kampus karena tugas sialan itu.
Waktu itu gue inget banget lagi motokopi buat kepentingan tugas gue di deket fakultas terus si abang fotokopi yang udah kenal gue nanya,
"Kok lo masih ngampus aja sih, Cid?"
"Tinggal ngelarin tugas ini doang gue."
"Oh, kirain sengaja ke kampus cuma buat ngeceng."
"Ya kali." gue ketawa. "Eh tapi yang gokil kapan hari itu anak mana, Bang?"
"Yang mana nih? Yang gokil banyak."
"Itu lho, yang pas gue ngejilid sambil beli teh botol itu."
Si Abang keliatan nginget-nginget. "Oh! Itu anak manajemen kayaknya, kalo diliat dari buku yang dia copy sih."
Gue ketawa, canggih kan intel level abang fotokopian?
"Emang dia gak ngerpint tugasnya gitu? Kan kalo ngeprint tugas kita bisa tau nama, NIM sampe jurusan dia dari cover."
Si Abang cuma geleng-geleng, "Belom beruntung lo."
Sekadar mengingatkan ya, ini terjadi ketika gue semester satu, gue belum kenal Adisa. Jadi gitu deh, masih suka meleng-meleng dikit.
Di tengah suara kertas yang lagi diperbanyak di tempat fotokopian yang sempit itu, tau-tau....
"Bang, ini bisa diulang gak ya fotokopinya? Soalnya miring."
Gue melirik sumber suara di sebelah gue, seorang laki-laki yang sedari tadi sibuk dengan berkas-berkasnya, dahinya mengerut sambil mengangkat secarik kertas, dengan jarinya ia mencoba mengukur sudut kemiringan tulisan di kertas itu. Gue yang penasaran ikut melirik kertas yang ia permasalahkan lalu ikut mengerutkan dahi.
Miring dari mananya sih anjir? Perasaan gak miring ah.
Apa guenya aja yang otaknya udah miring?
"Iya, ini miring. Saya fotokopi ulang aja." Ujarnya lugas. Cara dia berbicara mengingatkan gue sama cara berbicara dosen. Jangan-jangan dia emang dosen? Tapi masa dosen pake celana jeans?
"Bentar ya, Cid. Punya lo gue pending dulu. Ni punya dia selembar doang." Kata si Abang fotokopian ke gue.
Gue sih ngangguk-ngangguk aja, sementara orang di sebelah gue itu ngelirik juga nggak. Dia kembali sibuk merapikan berkas-berkasnya, gue tebak dia lagi nyiapin berkas buat beasiswa, tuh kan fotokopi KTP sama KTM segala, sama ada surat-surat resmi, dan gue kagum sama cara dia mengorganisir semua itu. Btw dia kayaknya bukan anak Teknik deh? Tapi kenapa motokopinya di sini ya? Ah tapi cewek anak manajemen aja motokopi ke sini kan.
Gue berhenti kepo sama berkas dia ketika hp gue bergetar, nama 'Rarara' muncul di layar.
"Hallo."
"Dek, masih lama gak? Gue mau pake mobil."
"Masih di kampus gueee. Lo mau ke mana sih?"
"Mau ketemu temen. Cepet pulang dong. Bukannya lo udah libur ya?"
"Yeee naik umum aja gih. Atau minta jemput cowok lo?"
Hening.
"Eh iya ya, udah jadi mantan ya. Sorry, Ra."
"Gue makan ya chitato yang lo stok di kolong kasur."
"EH EH IYA JANGAN. Buset dendaman banget. Iya, sorry, sorry, kan namanya juga baru seminggu putusnya, masih anget, wajar dong kalo gue lupa. Pasti masih berasa juga kan sayangnya?"
"Rasyid, lo pulang nanti semua stok jajanan lo udah tinggal ampas."
"Nooooooooooo, my loooooveeeeeeeee." Gue menggigit bibir, tersadar kalo gue baru aja berteriak norak, lelaki di sebelah gue bahkan mengerling gue sekilas. Gue langsung memelankan volume. "Iya iya ini gue lagi motokopi, abis motokopi gue ngumpulin tugas, abis gue kumpulin, gue langsung pulang."
"Bener ya."
"Iya, sayang."
"Sayang, sayang. Tumben lo nurut."
"Kenapa sih??? Gak nurut salah, nurut juga salah."
Rara terdiam sejenak di ujung sana, lalu seperti biasa insting tajamnya mengendus sesuatu yang tidak beres. "Lo abis ngelakuin kesalahan ya?"
"Ra, curigaan amat sih, pantes lo putus."
"Heh."
"Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma tadi kayaknya bensin mobil mau abis."
"Ya udah ntar lo sekalian pulang lo isi fulltank lah."
"Gak ada duit. Bye, Ra. See you at home."
Sebelum gue diceramahi sepanjang tiga puluh paragraf sama Rara. Gue langsung memutuskan sambungan dan mengabaikan teleponnya selanjutnya. Ya jadi, Rara itu kakak gue satu-satunya, namanya Raisa Andita. Dia bukan yang nyanyi 'SEKARANG AKU TERSADAR, CINTA YANG KUTUNGGU TAK KUNJUNG APALAH ARTI AKU MENUNGGU BILA KAMU TAK CINTAAA LAGIIII.', bukan, itu Raisa Andriana alias Yaya. Kalo Raisa kakak gue dipanggilnya Rara. Btw, kenapa Raisa yang penyanyi itu dipanggilnya Yaya ya? Dari mana Yayanya?
Kakak gue cantik, dari dulu gue sering banget nolakin satu-satu temen gue yang gigih usaha di kolom komen foto gue dan kakak gue.
'Cid, kenalin dong.'
'Wih boleh kakak lo. Bisa kali Cid.'
'Temen keparat, punya kakak bidadari gak pernah dikenalin'
'Cid. Ceki-ceki lah.'
Dan gue yakin 100 persen, temen-temen kakak gue juga suka memuji ketampanan gue dengan komen:
'Ih Ra, adek lo....'
'Ganteeeng. Ini Rasyid ya, Ra? Salamin bisa nih hehehehhehe'
'Ra, ini Rasyid yang kata lo dulunya pernah keselek gundu itu ya? Udah gede ya sekaraang.'
Anjir... Kakak gue tuh cerita apaan aja coba. Jangan-jangan temen-temen dia juga tau kalo gue waktu kecil dulu pernah hampir diculik ondel-ondel?
Rara tuh kakak yang baik, cool, bisa diajak kerjasama (waktu SMA gue pernah pura-pura ngaku kalo dia pacar gue), gak ngaduin gue ke nyokap waktu gue mecahin teko beling dapet doorprize (walaupun ujung-ujungnya ketauan juga), terus dari kecil gue udah ngintilin dia mulu. Soalnya bokap nyokap gue jarang di rumah, dua-duanya kerja. Jadi ya di rumah cuma ada gue sama dia doang, sama si Mbak sih, tapi si Mbak cuma di rumah sampe sore.
Gimana ya, gue deket banget sama Rara sampe kadang gue posesif, kalo ada yang ngapelin dia, gue harus tau dan harus lapor ke gue dulu. Kalo ada cowok yang nelepon ke rumah nyariin dia, terus gue yang angkat, pasti gue tanya-tanya dulu ala operator. 'Ya? Ada keperluan apa ya dengan Saudari Rara? Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir anda? Saya harus tau dulu zodiak Anda apa dan apakah Anda cocok kerja di air. Oh ya, apakah Anda tahu tanggal berapa adiknya Saudari Rara lahir? Apa?? Anda tidak tau?? Kalau begitu, Anda tidak bisa mendekati Saudari Rara, terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan.' Begitu kata gue dengan meniru suara robot.
Abis itu gue dijitak sama Rara karena gak terhitung berapa banyak laki-laki yang mundur gak jadi deketin dia gara-gara gue. Kemaren ada tuh yang sreg, namanya Ian. Setelah gue cek, bukan kok, bukan Ian Kasela. Ian asik banget, kalo jemput Rara sering ngobrol sama gue, ngobrolnya nyambung gitu lho. DAN DIA SUKA MUFC, DIA JUGA SUKA NAIF. Oh My God, pas gue tau soal itu, gue nyaris nyuruh dia ngelamar kakak gue saat itu juga.
Sayang, mereka baru putus kemaren.
Kasian, Rara.
Lebih kasian lagi sekarang dia harus menghadapi kenyataan kalo adeknya yang tampan rupawan ini bakal pulang dengan mobil hampir abis bensin.
Tadinya dia kemana-mana bareng Ian, sekarang jadi sendiri. Siapa yang kena imbasnya? Guelah. Selain suka diseret minta anter sana-sini, mobil barengan jadi sering dipake dia, padahal tadinya gue bebas-bebas aja makenya, sekarang berasa banget, gak bisa pergi lama-lama, lagi di mana gitu tau-tau ditelepon disuruh balik karena dia mau pake mobil. Hhhh.
Gara-gara itu juga akhir-akhir ini gue kepikiran buat ngekos aja. Apa pas liburan ntar gue cari-cari kosan enak di sekitaran kampus ya? Gak deket banget juga gak apa-apa. Kan ada si Dongker.
"Nih, udah." Abang fotokopian meletakkan tugas gue di atas etalase kaca, membuyarkan lamunan gue. Gue juga baru sadar kalo lelaki di sebelah gue udah pergi.
"Berapa, Bang?" gue menarik dompet dari saku celana.
"Goceng."
Gue menyerahkan selembar lima ribuan, lalu mengempit tugas gue di lengan dan bersiap pergi, "Tengs, Bang."
"Eh? Itu bukan punya lo?"
"Hah?" gue nengok.
"Itu." Abang fotokopi menuding ke lipatan kertas di atas etalase.
"Bukan, bukan punya gue. LAH ADA KTPNYA JUGA?" Gue bengong ketika mendapati KTP di balik lipatan kertas itu. Gue menyipitkan mata dan tersentak. "Ini mas yang tadi bukan sih?"
"Mana?" Abang fotokopi memajukan badannya melewati etalase untuk ikut melihat. "Kayaknya belom jauh, Cid orangnya, kejar deh. Kasian. Repot ntar gak ada KTP."
"Dih? Dia seumuran gue ternyata, Bang??" gue memekik gak penting melihat keterangan lahirnya di KTP.
Sejurus kemudian, gue membawa lipatan kertas dan KTP masnya itu keluar fotokopian, kalo kata si abang tadi, dia baru lima menitan pergi, harusnya belom jauh. Gue setengah berlari menyusuri jalan mencoba mengandalkan intuisi gue kalo dia melewati jalan ini ke arah gedung fakultas ekonomi karena sepertinya dia memang anak ekon.
Intuisi gue ternyata benar, gue mendapati sosok bersweater abu-abu itu berjalan sambil menunduk di sisi barisan pepohonan, rambutnya tertiup angin. Anjis, ini udah kayak film-film romantis, membuat gue menyesal, KENAPA YANG GUE TEMUIN TUH KTP COWOK???
Gue mempercepat lari gue dan begitu sampai di jarak yang dekat dengan dia, cukup dekat untuk menepuk bahunya, gue berdeham. Dia menoleh mendengar dehaman tidak natural gue yang sekilas terdengar seperti katak kejepit itu. Matanya menyiratkan pertanyaan.
"Lo...." Gue memastikan lagi nama yang tertera pada KTP di tangan gue, "Raden Pramadipta Atmojo kan?"
Lelaki itu menghentikan langkahnya sepenuhnya sekarang, "Ya?"
"Nih, KTP lo ketinggalan. Untung lo belom jauh."
Garis wajahnya menunjukkan kekagetan singkat sebelum ia mengambil KTP-nya dari tangan gue. Gila, gila, kalo aja yang di depan gue tuh cewek, udah dari tadi ada BGM lagu Bila Aku Jatuh Cinta-nya Nidji di kepala gue terus ntar daun-daun di pohon sisi jalan menggugurkan daunnya. Najis.
"Sama ini juga nih, ketinggalan. Gak tau kertas apa." Gue mengangsurkan kertas yang dilipat dua itu.
"Aduh, makasih banget." Ujarnya, kelihatan sangat berterima kasih. "Syukur gue belom sampe kosan. Kalo udah sampe, repot."
"Nama lo beneran Raden?" tanya gue polos, menghentikan gerakannya membuka map untuk memasukkan kertas yang tadi gue berikan ke dalam isi berkasnya.
"Ya?"
"Nama lo beneran Raden? Lo.... Pak Raden? Yang di Si Unyil itu? Kok gak berkumis?"
Mata tajam lelaki itu sedikit menyipit mendengar pertanyaan gue, apalagi karena gue menanyakannya dengan intonasi dan raut serius, tapi kemudian dia tersenyum sopan, mungkin karena gue udah berjasa buat dia, kalo nggak, kayaknya dia udah jutekin gue dengan tatapan 'Apaan sih ni orang.'
"Iya, emang ada Radennya. Tapi panggilan gue Rama."
Gue bersiul, jangan-jangan gue sebenarnya lagi ngomong sama Pangeran Ningrat. Gue harus behave, siapa tau ini adalah awal dari takdir gue dikenalin sama Putri Keraton yang cantik. "Gue Rasyid."
Rama mengangguk singkat, "Makasih, sekali lagi."
"Eh iya, tadi lo bilang kosan ya? Lo ngekos? Kosan lo di deket sini?" gue menahan sebelum Rama berbalik.
"Kenapa emangnya? Lo lagi nyari kosan?" tanyanya to the point. Kayaknya emang dia ini tipe orang yang mengedepankan prinsip ringkas dan waktu adalah uang. Calon-calon CEO di masa depan.
"Nah!" Gue menembak dengan jari gue karena jawabannya tepat. "Ada yang kosong gak?"
*
Dan sekarang, setahun lebih setelahnya, Raden Pramadipta Atmojo, orang yang membuat gue tinggal di rumah besar bernama Komet ini baru saja keluar dari kamar mandi sambil mengacak-acak rambut basahnya dengan handuk. Gila si Rama kok bisa cakep banget gitu ya? Ayo coba semuanya bayangin Rama baru keluar kamar mandi, wangi sabun disinfektannya masih kecium, rambutnya basah nitikin air. Bayangin!!
Hahaha mampus.
"Lho? Udah dateng pizzanya?" ia menghampiri sebagian anak-anak Komet yang membentuk lingkaran di karpet ruang tengah.
Hari ini Satrio bilang dia lagi banyak rejeki dan dia dengan murah hati mentraktir anak-anak Komet tiga loyang besar pizza yang sekarang sudah dikerubuti anak-anak Komet dengan sangat berisik, terutama Wawan yang rebutan saos sama Krucils.
"Makan, Ram. Sebelom disikat Wawan semuanya." Ujar Satrio yang sengaja pesan pizza satu loyang ukuran sedang untuk diri dia sendiri dan dengan anteng mengunyahnya di sisi luar lingkaran.
"Iya. Eh, Wan. Udah mandi belom lo?" tegur Rama pada Wawan yang kini sudah mengevolusikan jurus melindungi saosnya menjadi jurus silat. Fariz, lawannya langsung kewalahan. "Mandi, Wan." ulang Rama lagi, kali ini sambil meraih tisu untuk membersihkan noda saos yang ditinggalkan Wawan di karpet.
"Ntar aja ah, Ram. Elah. Kalo gue mandi nanti gue disisain remahan doang!"
"Emang." timpal Opang datar.
"TUH KAN! Heh!!! Ciat!!! Hah! Untung gue gak lengah! Muahahaha." Wawan baru saja berkelit dari jurus burung merak Fariz.
"Nih, Riz, nih." Biru mengoper saos pada Fariz, sudah muak dengan pertengkaran atas dasar saos yang sudah berlangsung bermenit-menit itu. Tapi Fariz tidak peduli, dia tetap ngambis mengambil saos Bang Wawan. Wawan sampai kayang untuk melindungi saosnya. Heran, ini maincoursenya pizza apa saos sih?
"Heh, heh, Wan, awas ntar lo sama Fariz kejedot meja." Rama memperingatkan lagi.
"Jadi lo belom mandi, Wan??? Jorok banget lo." Jime menggeleng-geleng prihatin.
"Gue juga belom, Wan." Satrio nimbrung dengan mulut penuh pizza, padahal gak ada yang nanya.
"Sip, nanti kita mandi bareng aja, Sat."
"Gak mao ah." Sahut Satrio, kembali bercengkerama dengan pizzanya.
Seolah merasakan tatapan gue, Rama menoleh dan mendapati gue yang senyum-senyum di ambang pintu.
"Ngapain, Cid?" tanya Rama heran. Mungkin dikiranya gue kesurupan.
"Gak apa-apa. Tadi baru kepikiran."
"Kepikiran apa?"
"Kepikiran kalo gue bersyukur banget dipertemukan sama kalian semua."
Seperti sudah gue duga, anak-anak Komet perlahan menghentikan aktivitasnya-bahkan Wawan dan Fariz mempending pertarungan mereka-untuk menatap gue. Tatapan ganjil.
"Apaan sih? Kesambet apaan lo?" Satrio paling sewot.
Gue tertawa sementara Rama yang mengerjap-ngerjap heran. "Kenapa sih, gue kan sayang sama lo, Ram. Makasih ya udah kayak bapak di sini barengan sama Jime juga."
Gue bersumpah melihat mata Rama melebar mendengar kata 'sayang'.
"Lo makan apaan tadi? Nasi Padang basi ya?" tuduh Wawan tanpa tedeng aling-aling.
"Nyet, lo masih suka sama cewek kan?" Satrio memastikan.
Gelak tawa keluar dari mulut gue, apalagi melihat muka horror Rama. "YA MASIHLAH. GUE PUNYA DICA. KENAPA DEH LO SEMUA?"
"Ya lagian ujug-ujug bilang sayang ke Rama."
"Gue sayang kalian semua.." Gue senyum-senyum sambil duduk nyempil di antara Wawan dan Galang. "Pizzaaaaaaaaa." Gue bersorak seraya mengambil sepotong yang paling dekat.
Rama yang tadinya kelihatan masih bingung akhirnya ikut bergabung. Tahu-tahu Iqbal yang duduk di seberang gue berkata, "Aku juga, Bang Acid. Aku juga sayang Bang Rama."
"INI KENAPA SIH PADA SAYANG-SAYANGAN?" Wawan misuh. "TERUS KENAPA GAK ADA YANG BILANG SAYANG GUE?"
"YA MENURUT LOOOO?" seloroh gue sambil menyumpal Wawan pake pinggiran pizza.
"Sat, tadi lo beli pizzanya sama Ayu?" tanya gue kepo.
"Yoi."
"Oh. Terus Ayu lo beliin juga?"
"Iyalah. Emang kenapa sih?"
"Biasanya kan orang pacaran tuh gak suka pizza, Sat."
"Hah? Kenapa tuh?"
"Kalo pizza jauh-jauh ntar kangen. HAHAHAHAHAHAH."
"Anjeng." suara Satrio.
"Bangsat." Suara Wawan.
"Heh, tolong bahasa kalian, ada krucils nih." Suara Rama.
"Jadi kalo suami istri cerai namanya pizza ranjang?" suara Opang.
Ini lagi anak satu. Rama makin pusing, ia memijat pelipisnya.
Gue ngakak.
Tapi ada yang janggal, biasanya ada yang responsif terhadap jokes gue, kok sekarang sepi ya? ketika gue melirik Galang-orang responsif yang gue maksud-di sebelah gue, ia terlihat melahap pizzanya pelan dan tanpa semangat. "Kenapa, Dek?" gue menyenggol lengannya.
"Lang, udah napa, Lang jangan dipikirin mulu." Kata Wawan.
"Kenapa dia?" tanya gue penasaran.
"Ituuu lho mikirin siapa tuh, kakak kelasnya yang dia suka."
"Oooh, yang di pensi kemaren. Kenapa dipikirin, Lang? Kan lo udah sukses ngajak dia?" Gue merangkul Galang, ia menghela napas.
"Gak tau deh, Bang."
"Lho kok gak tau?"
"Aku takut."
"Takut??? Lang, kita lagi ngomongin cinta, bukan film horror. Kok takut sih???"
"Tau tuh dia, padahal udah gue bilang, ikutin saran gue, jangan takut mencintai." Wawan menimpali.
"Iya kalo lo mah jangan takut mencintai, karena yang harusnya takut tuh orang yang lo cintai, Wan."
Tawa Satrio langsung menyembur mendengarnya, sedangkan Wawan mencelat bangun, emosi.
"Bajingan. AYO GELUT SAMA GUE CID!"
"Gak ah, sibuk." gue ketawa.
"Makanya mandi." Komentar Rama gak nyambung.
Galang dengan lesu membalas tatapan gue, "Bang Acid masih baik-baik aja kan sama Kak Dica?"
"Ya masihlah." Gue sontak tersenyum, reaksi tetap gue setiap mendengar nama Dica disebut. "Ayo Lang, jangan kebanyakan mikir-mikir. Kan mau kayak Bang Acid sama Kak Dica katanya?"
"Alah sombong lu." Gerutu Wawan, dahinya terlipat, sepertinya sedang memikirkan pembalasan buat gue. Gak gue nyangka, selang lima detik kemudian dia udah menemukan idenya. "Cid, lo sama Dica kan teknisnya sepupu jauh ya? Lo sepupunya Ikal, Dica sepupu istrinya Ikal."
"Ya... terus?"
"Sepupu jauh gitu gak boleh nikah tau, Cid."
Gue yang sedang mengunyah pizza, kontan melotot mendengarnya, tidak percaya.
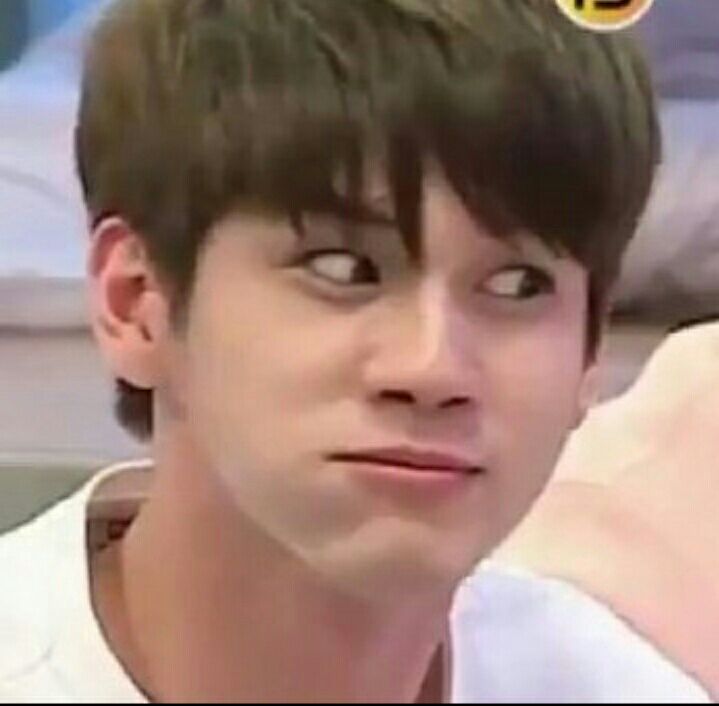
"Yang bener lo? Ngibul ya?"
"Yeee gak percaya." ada senyuman setan terselip di cengiran Wawan, "Coba aja lo cari di internet."
"AH NGGAK AH KATA SIAPA???? KAN SEPUPU JAUH. JAUH. JAUH." Gue menekankan kata 'jauh' dengan panik.
Gue gak mendengar sahutan Wawan karena layar hp gue yang gue letakkan di karpet seketika menyala.
'Adisa Mutiara Dewi is calling'
"TSAELAAAH." Ledek Wawan ketika matanya menangkap nama itu di layar hp gue.
"Sssst, sorry, kita pause dulu berantemnya, Wan." Kata gue dengan mata berbinar menggeser tanda hijau di hp sambil bangkit berdiri.
Bagaimanapun, teleponan sama Dica di tengah-tengah anak Komet-di samping Wawan terutama-sama sekali bukan ide yang bagus, jadi gue memutuskan melipir ke teras.
"Hallo, Ca?" gue mendekatkan layar hp ke kuping sambil cengengesan.
"Cid, Cid, rokoknya matiin dulu, Cid, rokok." Wawan dengan sengaja berteriak.
"Aduh Cid. Itu kaleng birnya buang dong, oi, Cid." Satrio ikut-ikutan, dasar pengkhianat.
"Cewek gue gak bakal percaya kebohongan klasik begitu." ujar gue, meleletkan lidah sebelum kabur ke teras, diiringi teriakan Wawan, "CID ROKOKNYA BAWA CID!!!"
"Nah, udah aman. Hallo, Ca." Gue duduk berselonjor di kursi teras.
"Lagi ngumpul-ngumpul ya?" tanya suara kalem di ujung sana.
"Iya, itu si Satrio nraktir pizza."
"Oooh."
"Ca, kamu tau kan tadi mereka iseng doang? Aku gak ngerokok."
"Iya, tau koook."
"Aku cuma minum doang..."
"Hm?"
"Minum air putih maksudnya. Hehe."
"Kamu udah makan?"
Aduh, diperhatiin cewek emang selalu menyenangkan. Hehe.
"Udah, kan tadi pizza."
"Jangan makan pizza doang. Paling kamu cuma makan sepotong kan?"
"Ya udah, sepotong lagi pizzanya pake nasi ya?"
"Pizza.... pake nasi? Rasyid..."
"Becandaaaa. Iya nanti aku makan."
"Jangan mie instan tapi."
"Iyaaa."
"Ya udah."
"Ya udah apa?"
"Ya udah, aku cuma mau ngingetin kamu makan aja kok. Aku tutup ya."
Gue tertawa, Adisa, Adisa.
"Kamunya sendiri makan apa?"
"Makan soto ayam tadi. Eh iya, Cid. Lusa aku gak jadi minta anter kamu."
"Kenapa?"
"Aku dijemput ayah."
Oh. Lusa emang Dica bilang mau pulang ke rumah, jadwal dia pulang biasanya sebulan sekali tapi emang udah dua bulan ini dia belum pulang, terus lusa rencananya dia mau pulang, tadinya mau gue anter, tapi kalo ayahnya mau jemput...
"Ayah kamu jemputnya ke kampus apa ke kosan?"
"Ke kosan kayaknya, kenapa?"
"Mau salim terus aku kan belom bilang sesuatu sama beliau."
"Bilang apa?"
"Bilang aku mau terus jagain anaknya."
Gue rasanya bisa melihat Dica tersenyum malu di sana. Senyum favorit gue, yang bahkan walaupun gue gak melihatnya sekarang, tapi bayangannya jelas banget di kepala gue.
"Yakin mau ngomong gitu sama Ayah?"
"Benerlah. Aku nih pasti klop banget sama Ayah kamu."
"Oh gitu?"
"Iya, soalnya sama-sama sayang kamu. Makanya pasti langsung klop."
Dica terdiam tapi gue yakin seyakin-yakinnya dia lagi senyum.
"Ya udah ah, aku tidur dulu. Kamu jangan tidur malem-malem."
"Tidur mah malem-malem, cantik, kalo siang-siang aku kuliah."
"Ih, Rasyid."
"Hehe. Ya udah, good night?"
"Good night."
"Hpnya jangan taro deket bantal ya, Ca."
"Iya."
"Yang taro deket bantal foto aku aja, biar mimpiin aku."
"Sssst. Good night, Rasyid."
Gue tekekeh telepon pun terputus.
Ketika gue kembali ke ruang tengah Komet sambil mesem-mesem, pizzanya sudah ludes, hanya sisa sepotong kecil, satu persatu juga sudah bubar, tinggal Rama, Wawan, dan Satrio yang tersisa di ruang tengah, dan Wawan masih belom mandi juga. Satrio malah sudah pulas ketiduran di sofa.
Gue menggeser paha Wawan yang terdampar begitu saja di karpet sambil main hp, "Ini sisa segini buat gue nih?" cetus gue, melirik Rama yang fokus menonton televisi.
"Ya udah, makan aja, Cid." Jawabnya tanpa mengalihkan pandangan.
Gue baru saja mau ngeloyor ke dapur untuk makan, manut pada instruksi pacar untuk makan dengan benar ketika sesuatu menghentikan langkah gue. Suara presenter berita malam yang tayang di tengah iklan.
"Dugaan korupsi Rektor Universitas X semakin menguat dengan adanya bukti dari seorang saksi. Saksi yang menghimpun keterangan disebut-sebut sebagai Dekan Universitas X, Fakultas Teknik."
Sesuatu menyentak gue dan sesuatu itu seolah membekukan sekujur tubuh dengan es. Gue menatap lekat layar TV, mencerna apa yang diberitakan di dalamnya seraya berharap gue cuma bermimpi.
*
Gue melangkah setengah tersaruk memasuki gedung yang sebelumnya sering gue datangi sewaktu kecil. Kapan terakhir kali gue ke sini? Mungkin kelas 5 SD. Ingatan gue samar, dan yang paling gue ingat, yang langsung mengalirkan déjà vu ke dalam diri gue ketika gue menjejak lantainya adalah gue berkali-kali datang ke sini dengan ayah.
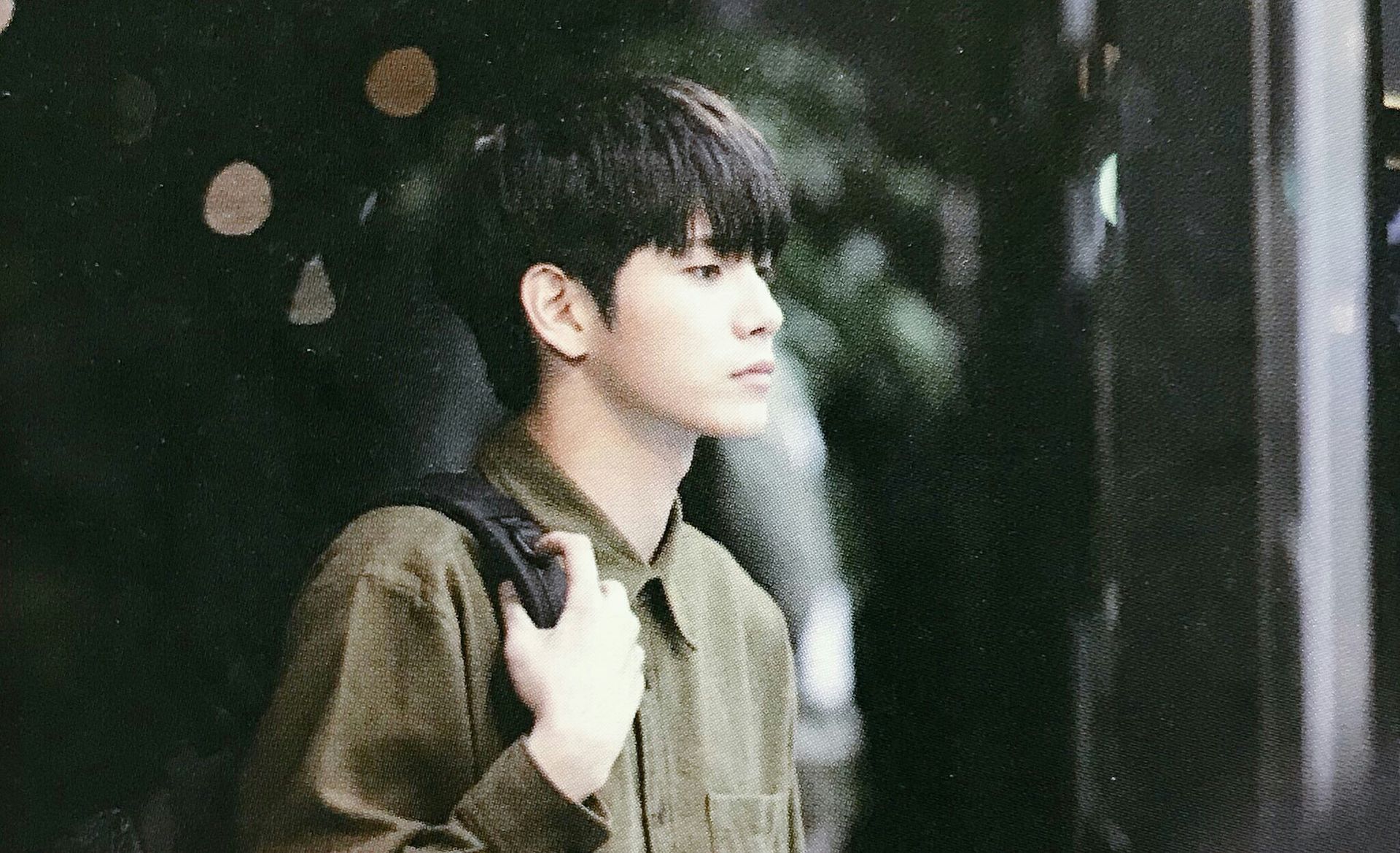
Tarikan napas gue semakin berat dan anehnya menyesaki gue di setiap anak tangga yang gue injak. Apalagi ketika gue melihat seramai apa situasi di luar kantor dekan fakultas. Orang-orang dengan tanda pengenal 'PRESS' dikalungkan di leher mereka mondar-mandir dan sibuk berkomunikasi satu sama lain.
Gue menduga sejak kapan mereka semua berada di sini? Sejak pagi? Ataukah sejak kemarin?
Dengan muram, gue menatap pintu ruang dekan yang tertutup rapat, menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan mata lalu berbalik, menuruni tangga kembali. Memutuskan menunggu di bawah.
Di bawah untungnya tidak seramai di atas, sehingga gue dengan leluasa duduk di salah satu kursi di dekat papan pengumuman, menyandarkan punggung gue ke dinding yang terasa dingin. Memejamkan mata lagi.
Gue pengen tidur banget. Kayaknya semalem gue cuma bisa tidur satu jam tapi anehnya, meskipun gue ngantuk dan pengen banget pulang ke Komet, bolos kuliah lalu tidur sampe siang, gue ngerasa gue gak bakal bisa tidur.
Mata gue yang sedari tadi memejam mendadak terbuka begitu gue mendengar derap langkah yang semakin dekat dan menghampiri gue. Gue memicing dan hal pertama yang gue lihat adalah seorang perempuan dengan jaket kebesaran, rambut acak-acakan yang tidak lagi tertolong oleh jepit, dan menggenggam coffee cup yang menguarkan uap, matanya menatap gue, menyorotkan pertanyaan.
"Lo nunggu juga? Dari media apa?"
Gue mengerutkan kening, apakah dia menyangka gue wartawan? Emangnya tampilan gue yang keliatan kayak wartawan? Oh, atau mungkin justru karena mata kurang tidurnya kali ya, gue jadi keliatan kayak wartawan yang lembur ngeliput.
Seingat gue, gue belum menjawab, tapi sepertinya dia sudah yakin dengan dugaannya kalo gue wartawan. Dia duduk di sebelah gue sambil meletakkan kopinya di tengah-tengah, sementara dia mengikat tali sepatunya yang terlepas.
"Gue udah di sini dari pagi. Belom sempet tidur. Ngantuk banget."
Gue jadi penasaran, apakah semua wartawan memang terbiasa mengajak ngobrol orang seperti ini?
Bola mata gue bergulir, mencoba membaca tulisan di ID cardnya yang alih-alih ia kenakan, malah ia letakkan di begitu saja di samping kopi.
'Shilla Kinanti' namanya, dilihat dari logo yang ada di ID cardnya, ia dari salah satu media online cukup terkenal yang sepertinya beritanya sering dibaca Rama.
"Jadi... lo dari media apa?" tanyanya setelah mengikat tali sepatunya, jemarinya mencoba merapikan rambutnya yang sebenarnya sudah sangat berantakan dan mencuat ke sana kemari.
Alis gue menyatu di tengah, memikirkan apa sebaiknya gue berbohong atau jujur. Toh, di gak kenal gue dan gue juga gak bakal ketemu dia lagi. Tapi ternyata sebelum gue menjawab, cewek itu lagi-lagi buka suara duluan.
"Kayaknya sebentar lagi Pak Adi keluar sih, soalnya dari pagi sejak beliau dateng ngantor kayak biasa sampe sekarang belum keluar-keluar."
"Hm." Gue mengangguk-angguk, membiarkan dia mengambil alih percakapan sepenuhnya.
"Kalo dipikir-pikir, kasian ya Pak Adi," katanya sambil ikut menyandarkan punggungnya ke dinding, ie melipat tangannya di depan dada sambil menatap lurus ke arah tangga.
"Kasian kenapa?"
Cewek itu mengembuskan napas keras-keras, "Kasian, padahal maksudnya ngasih bukti tuh biar rektornya ditangkep dan gak ada korupsi-korupsi lagi, apalagi ini tuh di kampus lho, kampus, tempat nuntut ilmu. Tapi beliau malah dituntut balik karena mencemarkan nama baik, terus malah dia yang dituduh korupsi. What a terrible world we live in, kan?"
Gue menelan ludah, sementara cewek itu melanjutkan dengan berapi-api.
"Kalo Pak Adi gak punya bukti yang kuat banget, gue khawatir semua kasus ini malah bakal jadi kerugian besar buat dia. Tau sendiri hukum negara ini tuh gimana. Bukan gak mungkin malah beliau yang jadi tersangka."
Helaan napas gue makin berat, rasanya setiap kata, bahkan sampai jeda-jedanya juga, yang lolos dari mulut cewek itu menambah kilogram demi kilogram di beban invisible yang bermukim di bahu gue.
Telinga gue seketika menangkap keriuhan yang bersumber dari lantai atas, keriuhan itu juga yang membuat cewek itu menegakkan tubuhnya, menatap ke tangga dengan waspada. "Kayaknya Pak Adi udah keluar ya?"
Gue ikut menatap tangga, dan rasanya ada yang meremat jantung gue ketika melihat sesosok laki-laki menuruni tangga itu pelan-pelan, di tengah orang-orang yang menembakkan pertanyaan-pertanyaan seperti peluru dan mengajukan mikrofon dan handphone ke depan wajahnya.
Cewek di sebelah gue terburu-buru mengalungkan tanda PRESS-nya lalu bangkit, ia tersadar lalu menoleh, "Lo gak ngeliput?"
Mata gue lekat pada lelaki yang sudah memijak anak tangga terakhir, dan ia akhirnya menyadari kehadiran gue, berada dalam radius beberapa meter darinya, duduk diam. Bibirnya perlahan membentuk senyum, mengabaikan semua pertanyaan yang sedang menyerangnya tanpa ampun.
Lagi-lagi jantung gue kayak ada yang nonjokin begitu melihat senyum itu.
"Gue bukan wartawan," kata gue pada cewek itu dengan suara mirip bisikan, "Gue anaknya Pak Adi, Dekan Fakultas Teknik yang dari tadi lo omongin."
Gue tidak melihat seperti apa reaksi cewek itu, karena tahu-tahu bokap gue udah berdiri di depan gue, bersikap seolah di tengah-tengah kami sekarang gak ada wartawan.
"Rasyid, setirin ayah pulang ya? Bisa?"
*
Sudah hampir tiga puluh menit gue dan ayah duduk di dalam mobil dengan gue di jok pengemudi, diam di balik setir, dan ayah di sebelah gue, memandangi sisi jalanan dengan sama bungkamnya.
Ayah gue, seperti yang pernah gue ceritain, sama kayak gue, sama-sama kuliah Teknik Mesin. Sekarang ayah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik di salah satu universitas, tapi bukan kampus gue.
Ada banyak alasan kenapa gue gak masuk universitas tempat ayah jadi dekan, pertama, karena ayah membebaskan gue memilih, dan dia sama sekali gak keberatan ketika gue memilih universitas lain yang menurut gue lebih bagus. Dia bilang gak apa-apa. Ya gak apa-apanya juga karena dia lulusan kampus gue sih sebenernya.
Gue tau banget ayah, dari gue kecil. Sebelum dia jadi terlalu sibuk dan hampir gak ada waktu buat gue maupun Rara, ayah yang ngajarin gue drum pertama kalinya, yang ngajarin gue naik sepeda pertama kalinya, yang memperdengarkan lagu-lagu The Beatles ke gue adalah ayah yang idealismenya sangat tinggi, ayah yang selalu nasihatin gue buat selalu jujur.
Jangankan korupsi, sama janji aja ayah gak pernah lupa nepatin. Gue inget dia pernah tau-tau jemput gue di sekolah karena katanya dia pernah janji nemenin gue nonton Spiderman, padahal guenya aja udah lupa kalo dia pernah janji itu.
Karena itu, gue juga gak kaget kalo rekan-rekan kerja ayah bilang dia idealis dan semacamnya, karena emang dia begitu. Jadilah dia kadang gak disukai sama beberapa orang yang jadi susah ngeraup untung gara-gara dia. Keluarga gue pernah dikirimin kotak isinya kotoran ayam, tanda kalo ada orang yang benci banget sama ayah. Padahal ayah sering bilang, dia bukan siapa-siapa, cuma pendidik yang kebetulan diangkat jadi punya jabatan tinggi aja.
Dulu mungkin gue bisa menyikapi kiriman kotoran itu dengan santai, tapi sekarang, sekarang beda, gue udah cukup dewasa buat tau kalo yang gue dan keluarga gue hadapi bukan lagi ancaman kiriman kotoran. Sekarang jauh, jauh lebih menakutkan daripada itu. Gue melirik ayah di sebelah gue, menahan diri untuk mengeluarkan semua yang memadati pikiran gue. Semuanya, termasuk ketakutan gue atas kemungkinan buruk.
"Kamu udah jago ya nyetirnya, Dek." gumam Ayah, ia tertawa, tawa khasnya yang rasanya udah lama banget gak gue denger.
"Kan ayah yang ngajarin dulu." jawab gue, kaget sama suara gue sendiri yang terdengar lirih.
"Oh iya, hahaha. Ayah lupa, kan kamu juga sering bawa mobil ke kampus ya sebelum ngekos, sebelum kakak kamu lanjutin kuliah ke luar."
Gue diam.
"Tapi mobilnya gak dibawa ke kosan, Dek? Naik si Dongker terus kamu di sana?"
"Iya, Yah." Gue tertawa hambar. Tawa yang dipaksakan.
"Pelan-pelan, depan lampu merah tuh." Ayah menggumam lagi.
Gue mengembuskan napas keras ketika menginjak rem dan mobil berhenti, mata gue memandangi merahnya lampu lalu lintas itu dengan sorot kosong.
"Terus kalo ngajak pacar kamu pergi, ke mana-mana naik si Dongker, Dek?" tanya ayah, sepertinya berusaha menciptakan percakapan, tapi usahanya itu malah membuat hati gue makin ancur. "Nama pacar kamu Adisa kan? Kapan mau kamu ajak ke rumah? Ayah mau ketemu pacar kamu yang kata kamu cantik itu. Tapi pas ngajak, pastiin ayah lagi di rumah ya."
Sumpah, Yah.
Gue juga udah lama pengen banget kayak begini, ngobrol berdua, gue nyetirin ayah, ayah duduk di sebelah, ngomongin apa aja, ngomongin musik, ngomongin lagu baru, ngomongin mesin, atau ayah cerita kerjaannya, gue cerita kuliah gue, ayah cerita ibu, gue cerita pacar gue dan betapa gue sayang dia. Semuanya.
Ini tuh momen yang pengen banget gue punya.
Tapi kenapa?
Kenapa harus sekarang?
Harus sekarang ketika gue menyetir dengan mata seperti mata zombie dan dengan semua ketakutan ini. Ketakutan kalau kejujuran ayah kali malah akan menjadi ketidakadilan.
Lampu merah berkedip menjadi kuning, lalu hijau. Gue menjalankan mobil kembali, tanpa sadar tangan gue mencengkam setir.
"Dek," panggil Ayah. "Ayah minta jangan kasih tau Rara dulu ya soal ini. Ayah gak mau bikin dia kepikiran. Kasian kakak kamu jauh dari rumah."
Gue menggigit bibir, kembali menahan semua protes.
"Kamu juga," ia melanjutkan, membuat gue tambah mencengkram setir. "Nanti di rumah, tidur dulu Dek sebelum balik ke kosan. Kamu kayak anak teknik aja deh begadang terus. Hahaha."
Untuk pertama kalinya dalam hidup gue, gue gak tertawa menanggapi lelucon ayah. Lalu kalimat berikutnya yang keluar dari mulut ayah untuk memecah sunyi, ikut memecah pertahanan gue.
"Gak apa-apa, Dek. Sebagaimana kita bisa gak suka sama orang lain, orang lain juga bisa gak suka sama kita. Gak apa-apa."
*
Dica
"Ca, lo disuruh ke ruang dosen sama Bu Lili." pemberitahuan dari Dea menghentikan gue yang tengah menjejalkan buku-buku gue ke dalam tas setelah kelas berakhir.
"Hah? Ada apa Bu Lili nyari gue?"
"Gak tau deh." Dea mengangkat bahu. "Udah sana, gue tunggu di selasar ya."
Gue mengangguk, masih dengan wajah heran, gue mencangklong ransel dan melangkah cepat menuju ruang dosen, nyaris menabrak seseorang yang baru saja membuka pintu ruangan.
"Sorry." ujar gue pelan, dan langsung mengerjap-ngerjap melihat siapa yang hampir bertabrakan dengan gue.
Lelaki itu hanya memandang gue selama beberapa detik dengan mata dinginnya kemudian melengos dan berjalan melewati gue. Gue memutar bola mata, kenapa sih dia?
Memutuskan untuk gak terlalu memikirkan orang itu, gue mendorong pintu ruang dosen dan langsun berjalan lurus ke meja Bu Lili.
"Permisi Bu, maaf, ibu panggil saya?"
Bu Lili mengangkat wajahnya dari kertas yang sedang ia telaah dengan saksama, ia langsung tersenyum dan mempersilakan gue duduk di kursi di depan mejanya.
"Langsung aja ya, Adisa, pengajuan berkas kamu buat program Student Exchange University to University sudah disetujui. Kamu berangkat bulan depan."
Sebentar,
Sebentar...
Gue gak salah denger kan?
Kalo ada Dea di sebelah gue, pasti gue udah minta tolong dia buat nyubit tangan gue. Masa sekarang gue minta Bu Lili nyubitin tangan gue?
"Adisa?" Bu Lili terlihat cemas melihat gue blank. "Jangan bilang kamu lupa kalo kamu pernah apply?"
Butuh waktu kira-kira setengah menit untuk gue memproses semuanya, dan kalimat yang keluar adalah, "Bu Lili... serius?"
"Kalo nggak serius ngapain saya manggil kamu ke sini?" Bu Lili menarik senyum tipis dan dari sorot matanya, pasti gue terlihat lucu. Ia menyodorkan berlembar-lembar kertas. "Ini, kamu baca ya. Pelajari baik-baik. Yang jelas, akomodasi sudah ditanggung semuanya, di sana kamu tinggal di dorm."
Rasanya waktu itu kaki gue sudah tidak memijak di lantai ruang dosen, tangan gue langsung terasa dingin karena excitement dan setengah tidak percaya. Gue? Ke Jepang? Buat kuliah? Mimpi gue selama ini? Gue gak yakin bisa keluar dari ruangan ini tanpa langkah gontai.
"Oh ya, tapi gak kayak taun-taun sebelumnya ya, taun ini yang berangkat dua mahasiswa." ujar Bu Lili sambil membetulkan letak kacamatanya.
"Eh? Saya sama siapa lagi, Bu?"
"Tadi orangnya baru saya kasih tau juga. Irham, Irham Prakasa, seangkatan kamu tapi kayaknya gak sekelas ya? Kamu kenal?"
Mendengar itu rasanya kegembiraan gue yang sudah meroket ke angkasa, menabrak langit-langit ruang dosen, tahu-tahu menyusut kembali, mendarat dan teronggok di lantai di sebelah sepatu gue. Gue menatap Bu Lili dengan tatapan penuh harap, berharap ia salah menyebutkan nama, ia salah orang atau apapun.
"Kenapa, Adisa?" Kening Bu Lili mengerut melihat tatapan gue.
"Eh, ng, maaf, Bu."
"Ya udah, pelajari dulu ya, oh ya, ada yang harus ditandatangani orang tua juga. Selamat belajar setahun di Jepang."
Gue mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih sambil membungkuk dua kali pada Bu Lili sebelum keluar ruang dosen.
Jadi itu alasan Irham tadi ke ruang dosen juga.
Kenapa di tengah antusiasme dan euforia ini ada duri berbentuk Irham? Ya sebenarnya sekarang gue udah gak ada masalah apa-apa sama Irham Prakasa tapi dulu, awal kuliah dulu gue pernah ada masalah sama dia, yang juga menyebabkan sampe sekarang gue dan dia bersikap seperti orang gak saling kenal. Gue menghela napas berat sambil menuruni tangga, menuju selasar tempat Dea menunggu gue dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja diberitahu bahwa salah satu mimpinya tercapai.
Ke Jepang..
Tapi bareng Irham?
Benak gue juga langsung dipenuhi seseorang.
Rasyid.
Gimana kata dia soal ini. Gue kan bakal pergi setaun.
Waktu itu gue sempet cerita gue apply program itu sih dan dia iya iya aja.
Tapi gue gak yakin dia bakal iya iya aja sekarang kalo tau gue gak pergi sendirian.
Kepala gue serasa mau pecah sekarang. Excitement yang tadi memompa darah gue udah hilang sama sekali.
Gue segera memberitahu Dea dan seperti yang gue prediksi, reaksi Dea lebih heboh dari gue.
"SUMPAH CA!!!! GILA. AH TAU GITU GUE APPLY JUGA!!! SIAPA TAU YA KAN?? KYAAAAA DICA KE JEPANG!!!!!" Dea mengguncang-guncang bahu gue.
Gue memaksakan diri tersenyum, sengaja tidak memberitahu Dea dulu soal Irham.
Tahu-tahu hp gue bergetar, ada whasapp dari bunda di grup keluarga yang terdiri dari gue, ayah dan bunda.
"Bentar, De." gue membuka grupchat, sedikit tidak sabar ingin memberitahu mereka berdua soal Jepang, sebelum gue melihat screenshoot yang dikirim bunda. Artikel dari portal berita online tentang kasus dugaan korupsi di Universitas X.
Gue menelan ludah, perasaan gue mendadak semakin tidak enak.
[Bunda]
Ca, ini dekannya ayahnya Rasyid bukan?
Kamu kan waktu itu cerita ayahnya Rasyid dekan fakultas univ itu?
Mata gue benar-benar membelalak sekarang. Semua informasi seakan bercampur jadi satu di otak gue.
"Kenapa, Ca?" tegur Dea, ia berkedip heran, apalagi ketika gue menatapnya dengan tatapan panik. "Kenapa ih???"
"Bentar, bentar." Dengan cepat gue menelepon Rasyid. Nomornya tidak aktif.
Rasyid, kamu di mana.....
Gue menelepon sekali lagi. Tetap tidak aktif. Gue nyaris berjalan menuju gedung jurusan Rasyid tapi kemudian gue teringat seseorang.
Dengan putus asa, gue menelepon nomor Satrio yang memang gue simpan di phonebook saking seringnya Rasyid numpang sms ke dia dulu.
Diangkat di nada sambung pertama.
"Hallo, Satrio?" gue berkata cepat, "Rasyid ada di Komet gak?"
Hening sejenak di seberang sana.
"Ca," katanya dengan nada yang aneh, "mending lo ke Komet deh sekarang. Acid ada di sini, tapi...."
*
Hujan turun di luar ketika gue sampai di Komet, membuat rambut dan cardigan yang gue kenakan sedikit basah.
"Masuk, Ca." Satrio menyambut gue ramah di pintu depan, dan ketika gue masuk ada beberapa orang lain yang sedang duduk di ruang tengah, gue tidak kenal semuanya, yang gue kenal selain Satrio hanya Wawan, Galang, Biru, Fariz, dan... oh, gue juga tahu yang mana Rama, Rasyid sering cerita tentang dia. Meski beberapa yang lainnya tidak gue kenal, tapi tatapan beberapa di antara mereka seakan berkata, 'Jadi ini...'
Mungkin Rasyid sudah sering bercerita tentang gue sebelumnya, tapi tatapan-tatapan itu membuat gue gugup, meski gue tetap mengangguk sopan pada mereka satu persatu.
"Acid di kamar," kata Satrio, dengan gesturenya mengajak gue mendekat ke salah satu kamar yang pintunya tertutup. "lagi tidur, tapi.... gitu. Lo udah baca berita kan?"
Gue menelan ludah, pahit.
"Udah."
Satrio mengangguk-angguk, "Acid pulang masih siang tadi, tapi langsung tidur kayak orang mati, bangun cuma ke toilet doang, kayaknya dia juga belom makan dari pagi." Satrio menarik napas, "Semuanya khawatir sama dia, ini pertama kalinya juga liat dia begini. Mungkin kalo sama lo dia mau bangun terus makan, Ca."
Cerita Satrio ibarat jarum yang menusuki hati gue, mata gue melirik pintu yang tertutup itu dengan hati tidak keruan. "Ngg, ya udah, gue... masuk ya?"
Satrio mengangguk mempersilakan gue lalu melipir ke ruang tengah,
Gue menarik napas, dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu itu pelan-pelan.
Sesuatu di dalam diri gue seperti pecah, luruh, dan hancur melihat Rasyid meringkuk di tempat tidurnya. Posisinya benar-benar meringkuk. Gue tahu kalau posisi dia tidur kadang memang seperti itu tapi kali ini, melihatnya seperti memantik sesuatu bernama kepedihan di hati gue. Terlebih karena gue tahu, Rasyid sedang hancur. Rasyid sedang membutuhkan seseorang yang bisa meyakinkannya kalau dia baik-baik saja.
Gue perlahan mendekatinya, duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap wajah lelaki itu, lelaki yang selalu berusaha terlihat bahagia dan membahagiakan semua orang yang dia sayang. Selalu percaya bahwa membuat orang lain senang adalah kapabiltasnya sepenuhnya, tanpa memperhitungkan dirinya sendiri.
Kini dia terlihat sangat kesepian, dengan posisi tidur menyamping tanpa memeluk guling, kedua tangannya terkulai di dekat kepalanya, dan wajahnya terlihat sangat lelah, seakan baru saja melalui hari yang amat berat sekalipun hari ini bahkan belum berakhir.
Tangan gue terulur, menyentuh lembut rambut bagian depannya yang menjuntai, sudah mulai panjang dan menusuk mata.
Rasyid Ananta terlalu sering menyimpan rapat semua kecemasan, kekhawatiran, dan masalahnya sendiri, menutupi semuanya dengan sangat rapi di balik semua tingkah lakunya, lelucon yang dia keluarkan dan cara-caranya dalam membuat orang lain tertawa dan senang berada di sekitarnya.
Ia tidak pernah ragu menunjukkan rasa sayangnya pada orang-orang di sekitarnya, tapi ia tidak pernah menunjukkan kekalutannya, apa saja yang mengganggu pikirannya seperti dia menunjukkan rasa sayangnya. Dia selalu berpikir bahwa perasaan bahagialah yang harus dibagi, urusan sedih, sakit hati, adalah urusannya sendiri.
Orang lain gak perlu ikut sedih, kalau ikut bahagia boleh. Karena kalo kamu sedih, kamu bakal ngerasa kayak kamu nangis sendirian, seberapa banyak pun orang yang ikut nangis buat kamu, tapi kalo kamu bahagia, kamu akan tambah bahagia karena rasanya semua orang di dunia ikut seneng bareng kamu. Begitu katanya.
Dan ia selalu berhasil mengecoh orang lain sehingga orang lain tidak perlu tahu semua ketakutannya. Meski kadang, ia tidak cukup mampu menyembunyikan itu dari sorot matanya yang tidak pernah bisa berbohong.
Gue tahu dari pendar matanya ketika ia bilang ia mau membelikan jam tangannya, kalau sebenarnya ia merindukan ayahnya, ayahnya yang dulu, yang belum terlalu sibuk seperti sekarang, yang masih bisa diajak main drum.
Gue tahu dari binar mata dia ketika memakan sestoples kue nastar buatan bunda buat dia, kalau sebenarnya dia ingin kembali pada masa saat ibunya punya waktu untuk membuat kue-kue manis itu, dengan dirinya menonton dan iseng mencolek adonan seperti waktu masa kecil dulu.
Gue tahu dari cara dia menunjukkan foto-foto dia waktu dia pergi ke New York menjenguk kakaknya, dan berkata kalau kadang dia sering hanya duduk di depan laptop hanya untuk membuka-buka folder foto NY ini, kalau sebenarnya dia sedih karena kakaknya berada bermil-mil jauhnya, dipisahkan jarak berjam-jam perjalanan pesawat, dan gue bisa merasakan betapa dia menyayangi dan merindukan kakaknya.
Apalagi sekarang, gue gak bisa membayangkan seperti apa perasaan dia hari ini, setelah membaca semua berita itu.
Pandangan gue mulai mengabur karena air mata. Kenapa sih, Rasyid? Kenapa harus berusaha keras buat menutupi itu semua? Kamu bukan manusia super, bahkan superhero sekalipun punya hak buat bersedih. Kenapa kamu berangggapan kalau kamu gak punya?
It hurts people who care about you as much as it hurts you.
Tangan gue yang mengusap-usap rambutnya berhenti ketika Rasyid bereaksi seperti seseorang yang sedang tidur lalu tiba-tiba bermimpi buruk, seperti seseorang yang baru saja jatuh dalam mimpinya.
Matanya setengah terbuka, melihat ke sekeliling, lalu tatapannya tertumbuk pada gue yang duduk di tepi tempat tidurnya, mengusap rambutnya dengan harapan bisa membuatnya sedikit lebih nyaman.
"Ca? Kamu di sini?" suaranya terdengar parau.
"Iya." jawab gue dengan suara yang sama-sama bergetar.
Rasyid kelihatan masih setengah sadar, gue sempat merasa sebenarnya dia sedang mengigau. Serta merta, tangannya menggenggam tangan gue. Tangannya dingin.
"Jangan tinggalin aku lagi ya, Ca." bisiknya lemah, berada di tengah tidur dan sadar, namun gue sudah tercekat sejadi-jadinya mendengarnya.
'Jangan tinggalin aku lagi' katanya.
Air mata mulai menitik di pipi gue, menyadari kalau gue juga pernah membuatnya seperti ini, gue pernah meninggalkannya. Dan lagi-lagi penyesalan menghantam gue seperti seseorang baru saja menimpuk gue dengan ensiklopedia tertebal sedunia.
Gue mengeratkan genggaman tangan gue. Kalau begini, rasanya gue tidak akan menyangkal kalau Rasyid meminta gue jangan pergi ke Jepang.
Atau mungkin gue tidak akan pernah bilang dan tidak jadi pergi. Tidak kalau Rasyid Ananta sedang seperti ini.
"Aku gak ke mana-mana kok."
Rasyid tersenyum dengan mata setengah terpejam lalu ia kembali tidur.
"Rasyid, makan dulu, kamu belum makan dari pagi ya?"
Tidak ada jawaban, tapi gue yakin dia tidak benar-benar tidur.
"Rasyid..."
"Kamu kenapa lupa lagi bawa payung? Kenapa ke sini hujan-hujanan? Hm?"
Bahkan di saat seperti ini dia masih mengkhawatirkan gue.
Hari itu, tidak semua air hujan turun ke bumi, ada yang tertahan dalam diri Rasyid Ananta yang bukannya ia deraskan, malah kembali ia endapkan di dasar hatinya, tersulam jadi ombak yang kemudian berdebur jadi nyanyian kesedihan. Tidak semua bisa mendengarnya.
a/n:
haiii, nih nih yang kangen acidica nih hehehe.
aduh lama banget nyelesaiin ini soalnya ngetiknya sambil nangis. semoga nyampe juga ke kalian ya ini perasaanku.
oh ya, universitas di sini maupun di komet semuanya fiktif ya :)
terima kasih sudah membaca!! ditunggu vote dan commentnya hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top