another July
Acid
"Tuhan pasti punya rencana kenapa kita diketemuin lagi kayak sekarang. Mungkin karena apa yang kita anggap udah selesai ternyata belum."
Omongan gue di rooftop menyisakan keheningan panjang yang gak berusaha gue pecahkan. Gue bisa aja menjelaskan semuanya sekarang, gue bisa aja jujur soal alasan gue ninggalin dia sekarang, tapi sesuatu menahan gue.
Muka ayah berganti-ganti sama muka Irham saling berebut berkelebat di benak gue. Apakah kalo gue bilang ke Dica sekarang, gue ngelanggar kesepakatan gue sama Irham dan bikin dia melakukan manuver lainnya yang gue terlalu ngeri untuk bayangin?
Setan banget emang, gara-gara si dickhead urusan perasaan yang seharusnya simple, harus campur baur sama masalah pelik. Tanpa sadar rahang gue mengeras karena memendam marah.
"Mungkin.." Jawab Dica akhirnya dan gue yakin gue bisa menangkap ada tanya dalam satu kata yang dia suarakan itu.
Gue menangkap kesan, Dica lagi nunggu gue ngelanjutin ucapan gue. Walaupun dia lagi menatap lurus ke gedung-gedung beton yang kelihatan dekat tapi juga jauh dari jarak pandang kita. Kayak gue sama dia sekarang, deket tapi jauh.
Seketika dia menoleh, menatap gue lama sampe bikin gue gak kuat mau natap balik lama-lama.
"Jangan ngerokok lagi ya, Rasyid." katanya pelan sebelum beranjak pergi dari sisi rooftop, ninggalin gue yang cuma bisa ngeliatin dia pergi dari belakang. Rasanya pengen banget gue meluk dia. Peluk yang bisa mengurai semua pelik.
Ingetin aku terus, Ca, kasih aku permen mint lagi kayak biasa, tanyain lagi aku udah tidur atau belum. Aku kangen. Bisik gue dalam hati.
Saat pintu yang menuju tangga tertutup dan sekeliling gue kembali sunyi, gue menarik napas dalam-dalam, menunduk memandangi puntung rokok dan sisa abunya yang gue injak.
Mungkin bukan hari ini, belum. Gue masih harus berusaha lagi.
*
Sebulan sekantor sama Dica, bisa dibilang usaha seorang Rasyid Ananta belum bener-bener maksimal. Buat ukuran gue, seorang Rasyid, deketin perempuan kayak Adisa harusnya bisa lebih effort. Gue kayak jalan pelan-pelan, sambil dikit-dikit lemah setiap ngelirik Dica di mejanya. Sejak kapan ya ngeliat orang lagi ngetik aja bisa lebih menarik daripada curi-curi nonton youtube? Belum lagi kalo pas gue ngelirik, Dica lagi ngiket rambutnya pake iket rambut yang ngelingker di lengannya. Selemah-lemahnya gue jadi manusia deh kayaknya pas liat.
Gue sampe hafal kalo kerjaan lagi numpuk dan Dica harus ngurusin banyak kontrak, dia pasti langsung ngiket rambutnya tinggi-tinggi atau langsung nyeduh teh tanpa gula pagi-pagi, terus sambil celupin pelan-pelan kantong tehnya ke dalem mug dia jalan ngelewatin meja gue ke meja dia sendiri. Sejauh ini sih dia belum nyeduh ovaltine, padahal gue udah diem-diem request ke Mas Didit buat banyakin persediaan ovaltine di pantry. Baru nyadar, gue tuh sebenar-benarnya bucin ya?
Dica juga kayaknya nyadar kalo gue sering merhatiin dia, dia sering senyum-walaupun tipis dan cuma bentar-kalo liat meja gue. Tapi kadang itu cukup bikin gue semangat kerja sampe si Fadhil sempet komen, 'Berkobar bener kayaknya, Pak?'
Gak tau aja si Fadhil kalo berkobarnya karena api asmara. Anjis, dangdut banget.
Selama sebulan terakhir, hampir setiap hari Dica selalu pulang lebih dulu dari gue dan ada beberapa hari, gue sepik-sepik nyari alasan ke bawah cuma buat liat dia pulang sama siapa. Sejauh ini sih aman, gue gak pernah liat dia dijemput si dickhead.
Bentar ya, Ca. Kalo aku udah bisa pulang tenggo aku anterin kamu pulang. Beneran.
Oh iya, ada kejadian lucu Jumat kemaren.
Jadi kan di kantor gue tuh semuanya kepisah kubikel-kubikel gitu dan di beberapa kubikel ada pesawat telepon yang biasa dipake dengan tujuan efisiensi. Jadi kalo Mbak Sandra yang kubikelnya jauh mau ngomong panjang lebar sama anak planning bisa langsung lewat telepon. Nah, gue satu telepon barengan sama Mas Aryo.
Terus kemaren abis Jumatan, kantor masih sepi. Sejak ada Dica di kantor, gue emang memisahkan diri dari geng mas-mas-makan-gorengan-dulu-abis-dari-masjid. Gue nyampe kantor dengan lengan kemeja masih digulung, dasi longgar, dan rambut kesibak.
Bener dugaan gue, gue cowok pertama yang balik. Cewek-ceweknya juga cuma ada Dica sama Kinar, yang lainnya pasti masih pada makan siang. Ini Dica gak makan apa ya?
Dica sendiri gak nyadar gue balik dengan setelan abis Jumatan, kayaknya dia lagi mumet sama sesuatu karena matanya fokus banget ke layar komputer.
Pas gue lagi muter-muter di kursi sambil ngemil nutrition bar yang dikasih Mbak Sandra, telepon di kubikel Mas Aryo bunyi. Gue celingukan, siape yang nelepon? Masa gak nyadar kalo Mas Aryo belom balik dari masjid.
Gue memundurkan kursi sampai ke kubikel Mas Aryo terus gue angkat teleponnya.
"Hallo, Mas."
Gue hampir aja keselek, itu suaranya Dica. Tubuh gue yang tadinya nyender selow ke punggung kursi langsung tegak. Untung gerakan mendadak itu gak bikin gue kejengkang. Lagian siapa suruh tiba-tiba manggil 'Mas'?? Bikin gue grogi aja. Walaupun bukan gue yang dipanggil sih. Hehehe.
"Ini... mas, saya tadi udah ngehubungin sekretaris perusahaan X, draft agreementnya udah saya kirim ke email. Tolong dicek ya, soalnya-"
"Ca," Gue gigit bibir nahan ketawa gemes.
Dica di seberang sana langsung diem denger suara gue.
"Ca, Mas Aryonya belum balik kantor. Bentar lagi paling. Hehe."
"... Aduh maaf, aku gak ngeh."
Ya ampun, seseorang tahan gue buat gak ngangkat kepala terus nengok ke kubikel dia di ujung sana.
"Gak apa-apa, nanti aku sampein. Cek draft agreement kan?"
"I..ya."
"Ok."
"Ok, makasih ya, Rasyid."
"Eh, bentar, bentar, Ca."
"Hm?"
"Tadi kamu manggil apa?"
"Manggil apa?"
"Tadi... begitu telepon kesambung." Gue nyengir.
"Mas...? Kan iya, maksud aku Mas Aryo."
"Kok Mas Aryo doang yang dipanggil Mas?"
Gue rasanya bisa ngeliat Dica senyum sambil geleng-geleng kepala.
"Ya udah makasih ya, Mas.. Rasyid." Ujarnya menyerah.
"Sama-samaaaa. Jangan pusing-pusing, Ca. Makan dulu gih." Terus telepon ditutup, dengan cengiran masih menghiasi wajah gue.
Untung belum ada si Fadhil atau Gery, kalo ada, bisa dihujat gue pake telepon kantor udah kayak nelpon dari wartel.
Nutrition bar yang gue makan langsung jadi manis abis itu, abis denger gue dipanggil 'Mas'. Hahahaha.
"Lo gila ya?" Pertanyaan Rama lengkap dengan tautan alisnya menarik gue dari lamunan tentang Jumat kemaren. Mengembalikan gue ke realita kalo dari Sabtu siang sampe Sabtu sore gini lagi bantuin dia nyiapin pernikahannya yang bakal berlangsung beberapa bulan lagi.
"Sorry sorry tadi sampe mana Ram?" Gue cengengesan minta maaf sebelum nyetekin lagi pulpen di tangan gue, siap menulis.
Pernikahan aristokrat ini sebenernya masih ntar bulan Desember tapi ya namanya juga Raden Pramadipta, persiapan lamaran waktu itu aja beberapa bulan sebelumnya, apalagi pernikahan ya kan?? Ini aja udah hampir 50%, formasi panitia udah dirumuskan.
Rama memutar bola matanya, "Live musicnya, Cid. Plan B kalo misalnya band yang direkomen Mala udah penuh bookingnya. Lo ada rekomen lain gak?"
"Playlistnya gue yang nentuin juga kan?" Gue menatap Rama dengan sorot mata penuh harap kayak anjing minta dikasih makan.
Rama menghela napas, "Tapi jangan yang aneh-aneh. Inget, ini nikahan bukan konser."
"Siap, Ram, siaaap." Gue memejamkan mata sambil menjentikkan jari seolah tugas gue cetek banget, "gue tau kok selera musik lo."
"Siapin dulu, kasih ke gue, ntar gue acc."
"Buset lo mau nikah apa mau jadi dosen pembimbing sih, Ram?"
"Dan jangan sampe ada intro-intro apalah itu yang diusulin Satrio."
Rama lalu langsung ke poin perencanaan berikutnya. Begitulah Rama, terlalu terstruktur.
"Ram,"
"Apaaa?"
"Kan Mala manggil lo kakak ya, abis nikah ntar manggil lo 'mas' gak?"
Mata Rama memicing, "Ngapain lo tiba-tiba nanya gitu?"
"Hehe enak tau Ram, dipanggil 'Mas'. Mas Raamaaaaaa." Gue sengaja membuat Rama bergidik.
"Cid. Lo salah minum obat?"
Tahu-tahu Wawan berguling dari sisi karpet ruang tengah, mendekat ke meja tempat gue dan Rama diskusi. "Ram, yang bener aja." Mulutnya monyong-monyong sambil memperhatikan tulisan di kertas yang ada di genggamannya.
"Masa gue jadi seksi undangan doang?"
"Pffffffft." Gue meledek dengan mengeluarkan bunyi-bunyian kentut.
"Tugas gue cuma ngurusin undangan doang, Ram?? Gak adil banget! Ini si krucils pada jadi pager bagus!"
"Ya lo mau jadi pager bagus emang?"
"Nama gue aja Bagas, Ram! Udah cocok!"
Cocoklogi, Wan, Wan.
"Udahlah, Wan, emang udah tugas lo nyari alamat." Celetuk gue.
"Setan."
"Wan, jangan salah lho, susah ngurusin undangan. Lo harus mastiin semua yang di daftar udah pada dapet."
"Ya tapi masa gitu doang tugas gueee???"
Gue berdecak, "Lo maunya apa lagi? Ngangkat soundsystem?"
"Bangke."
"Ya udah, ya udah, lo gue masukin ke perlengkapan ya, koordinatornya Dzaki nih." Rama menuding.
"Nah gitu kek kerenan dikit. Lah tadi, tukang nyebar undangan."
Gue ketawa, padahal bisa aja di perlengkapan ntar dia disuruh ngangkat soundsystem.
Setelah Wawan berhenti ngambek, Rama kembali fokus mengetik di laptopnya, mencoret atau menambahkan beberapa bagian di kertas catatannya sambil sesekali membetulkan letak kacamatanya.
Gue yang tadinya mikirin lagu-lagu buat playlist nikahan Rama selaku penata musik, malah jadi diem-diem merhatiin Rama. Dia seumuran sama gue, kita sama-sama udah kerja dan udah punya penghasilan sendiri, tapi dari dulu, dari pertama kali gue kenal dia gara-gara KTPnya ketinggalan di fotokopian terus jadi satu kos-kosan sama dia, gue selalu merasa dia jauh, jauh lebih dewasa dari gue.
Walaupun seumur, entah kenapa gue sering ngeliat dia sebagai figur kakak-plis jangan laporin Iqbal-yang bijaksana, yang bisa nenangin gue, bisa bantuin gue. Bikin gue kayak punya dua kakak, satu Rara, dan satu lagi Rama.
Sekarang gue ngerti kenapa Iqbal seposesif itu sama abangnya. Rama emang sebaik dan sepantes itu jadi abang.
Penghujung tahun dan itu berarti kurang dari enam bulan lagi, Rama bakal nikah. Secara gue seumuran sama dia, gak mungkin gue gak mikirin diri gue sendiri. Kayak... ada satu pikiran yang 'mukul' pala gue kayak palu, 'Anjrit ya, Rama Desember ntar beneran nikah lho, beneran bakal jadi kepala rumah tangga. Gue? Gimana gue? Ntar gue bakal bisa kayak Rama gak sih??'
Tapi tiap kepikiran itu, gue langsung inget kata-kata Ramanya sendiri, pas di mobil malem-malem, perjalanan pulang dari kampung halaman Awang:
'Semua orang punya standar waktunya masing-masing kok.'
"Wawan jadi ngingetin gue, gue belum perbarui daftar undangan di laptop." Rama tahu-tahu ngegumam, bikin gue tersentak.
"Udah berapa ratus yang lo undang, Ram?" Tanya gue iseng.
Bukannya menjawab, Rama membalik halaman catatannya, tempat ia menulis nama-nama tambahan untuk dimasukkan ke daftar undangan.
Mendadak gue kepikiran suatu gagasan.
"Ram,"
"Apa?" Rama menyahut sambil mengetik.
"Anu... Adisa lo undang gak?"
Gerakan jemari Rama di atas keyboard terhenti, matanya langsung tertuju ke gue.
"Adisa mana?" Tanyanya seolah ada banyak Adisa yang gue kenal.
"Dica. Yts."
Mendengar itu, Wawan yang tadinya melanjutkan tidur-tidurannya di karpet langsung berguling tengkurap buat memperhatikan gue dan Rama. Membuat gue sadar kalo ini adalah pertama kalinya gue menyebut nama itu lagi di Komet.
Rama kelihatan tertegun dulu sebentar sebelum kembali serius, "Iya, gue undang kok."
Jawabannya langsung bikin gue ternganga tiga detik.
"Seriusan, Ram?"
"Iya, udah ada namanya di daftar."
"Seriusan????"
"Iya, Cid." Jawab Rama sabar.
Gue langsung noleh, "Wan! Gue aja yang jadi tukang sebar undangan kalo gitu!"
"Lah?"
Rama tersenyum miring sambil menggeleng-geleng ngeliat kelakuan gue.
Terus gue langsung nulis satu judul di daftar lagu buat pernikahan Rama: No. 1 Party Anthem - Arctic Monkeys.
"Hoi hoi, ini nikahan gue, bukan nikahan lo." Rama memprotes setengah bercanda melihat judul yang gue tulis.
So you're on the prowl wondering whether
She left already or not
Leather jacket, collar popped like antenna
Never knowing when to stop
Call off the seach for your souls
Or put it on hold again
Sipping a drink and laughing at imaginary jokes
As all the signals are sent, her eyes invite you to approach
And it seems as though those lumps in your throat
That you just swallowed have got you going
Come on, come on, come on
Come on, come on, come on
Number one party anthem

*

Takdir jelas-jelas lagi memanjakan gue karena hari Senin, setelah hari Jumatnya gue dipanggil 'Mas' di telepon, pagi ini, pas baru dateng, gue satu lift sama Dica.
Gue langsung gak kenal sama kalimat 'I hate Monday', mata gue langsung berbinar begitu gue baru aja mencet tombol lantai 5, terus Dica masuk ke dalam lift dengan langkah terburu-buru.
Bentar, mampus gue. Kok dia pake kacamata?
Sejak kapan dia pake kacamata? Kok gak pernah bilang?? Yaelah siapa elu, Cid.
Tapi... jadi makin cantik. Berkah Senin pagi bener ini namanya. Kalo gue wibu kayak si Ariq nih ya, pasti gue udah berseru heboh dalam hati: 'MEGANEEE? KAWAIIII!'
Dica senyum sekilas ke gue sebelum berdiri di sisi kanan lift, sebelahan sama gue, dan doa gue terkabul, gak ada lagi yang naik lift sampe pintunya menutup di tengah. Gue ngelirik pantulan diri gue sendiri di dinding lift, meyakinkan kalo dasi gue terpasang dengan benar dan rambut gue gak kusut kayak abis tidur di landasan udara.
"Pake kacamata sekarang, Ca?" Tanya gue setelah berdeham. Lift bergerak melewati lantai 2.
Dica mengangkat wajahnya, "Iya, sebenernya minusnya baru dikit, tapi biar tahan aja lama-lama di depan komputer, gak perih."
Masalahnya gue yang jadi gak tahan lama-lama di depan dia. Gak tahan mau muji cantik terus.
Duh ini lift bisa gak sih sampe langit aja.
Mendekati lantai 2, gue yang biasanya lancar ngomong, jadi ilang kata-kata. Apa gue harus ngeluarin headphone terus dengerin lagu There is A Light That Never Goes Out-nya The Smiths kayak Tom Hansen biar ditanya, 'The Smiths? I love the Smiths. You have a good taste in music.', HAH?? HAH??
Ok, mungkin ini saat yang tepat buat-
"Rasyid, kerah kemeja kamu..."
Gue tersentak, KENAPA KERAH KEMEJA GUE? ADA CICAKNYA???
Begitu gue noleh ke dinding lift. Monyeeeeeeet, kerah kemeja gue bagian belakangnya nyelip ke tengkuk. Kenapa gue baru nyadar???? Kenapa lo malu-maluin geneeee, Cid, Cid.
Alih-alih langsung membetulkannya, gue melirik Dica lagi.
"Ngg, benerin dong, Ca,"
Tolong dicatat, itu refleks keluar gitu aja dari mulut gue ok. Kayaknya beneran udah gak kebendung ini aliran kebucinan yang mendarah daging.
Dica sempat berkedip beberapa kali begitu mendengarnya.
Selama beberapa detik gue pikir dia bakal pura-pura gak denger tapi gue merasa bisa melihat dia tersenyum kecil sebelum agak berjinjit dan mengulurkan tangannya ke tengkuk gue. Membetulkan kerah kemeja gue yang nyelip.
"Udah." Katanya tepat ketika lift berdenting dan pintu menggeser terbuka.
Persamaan gue dan Tom Hansen di 500 Days of Summer pas elevator scene itu adalah... begitu sang perempuan keluar dari lift, dia dan gue sama-sama menggumam, "Holy shit."
*
Dica
Rasyid Ananta dengan mudah membuat kehadirannya dalam kehidupanku lagi menjadi sesuatu yang sangat wajar. Meski aku masih merasa dia masih punya banyak hal untuk dikatakan, aku membiarkan semuanya berjalan tanpa memaksakan atau menuntut.
Aku tahu aku bisa saja menanyakannya langsung waktu di rooftop, atau membalas kata-katanya tentang 'Ada yang belum selesai' dengan 'Kalau gitu selesein?' tapi aku masih diliputi keraguan. Jadi aku menunggu, kalau memang akan ada waktunya dia menjelaskan, maka aku akan mendengarkan.
Mengenai perempuan berambut pendek yang kulihat di lobby, yang sempat melirik dan seperti mengenaliku. Aku mulai meyakini dugaanku sendiri kalau dia pacar baru Rasyid.
Ya kan? Mana mungkin setengah tahun lebih ini dilalui Rasyid tanpa pacar? Kalau mengikuti julukan Mbak Sandra yang disematkan padanya, dia itu Hot Engineer. Seorang hot engineer rasanya mustahil belum punya pacar. Lagipula aku sudah mempersiapkan diri menghadapi kenyataan itu jauh sebelumnya.
Tapi itu tidak serta merta membuatku berhenti memperhatikan Rasyid.
Seringkali aku masih dengan tanpa sadar mengamati matanya ketika ia baru datang, karena itu aku dengan mudah tahu kalau dasinya terpasang miring dan lainnya, aku bisa tahu kapan dia kurang tidur, aku juga tahu kalau dia sering mengenakan dasi yang sama setiap hari Senin seperti sebuah repetisi. Aku juga tahu berapa sendok gula yang ia masukkan ke cangkir kopi ataupun tehnya, bagaimana candaannya bersama Mas Didit di pantry, bagaimana sepatunya selalu ada di rak di depan musala setiap sore-ini membuat hatiku menghangat-bagaimana ia saling mencela dengan Fadhil sampai mereka disebut sebagai Komeng dan Adul. Semua itu menempel di kepalaku seperti sticky notes bertuliskan fakta-fakta tentang Rasyid meski aku tidak pernah merasa menulisnya.
Dan terakhir, aku juga tahu bahwa ia sering sengaja makan diam-diam kalau ia dikirimi bekal oleh.... orang yang kuduga pacarnya. Dia bersikap seolah aku tidak boleh tahu apa yang sedang ia makan, padahal aku tahu itu dari siapa.
Sore itu, tidak seperti hari-hari tengah pekan pada umumnya di kantor yang serba sibuk, pekerjaan cukup longgar karena kami sudah 'mati-matian' pada hari sebelumnya, kemudian timbul gagasan dari Mbak Sandra: "GUYS! Hari ini kita pulang tenggo, karaokean dulu yuk???!!!"
Ajakan itu tentu saja disambut meriah oleh para cowok.
"Mbak Sandra tau aja deh kita-kita udah lama gak dangdutan."
"Mbak Sandra nih mentang-mentang mendekati hari H jadi manten yess, mau puas-puasin maen sama para bujangan dulu."
"Eh, aku ni udah gak bujangan lho, masih boleh ikut gak nih?" Mas Aryo menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa.
"Bolehlaaah Mas Aryooo, asal bilang dulu tuh sama istriii, tenang sebelum jam 10 kita pulaaang."
"Ini Mbak Sandra yang bayarin kan?" Tanya Rasyid riang.
"Enak ajeee, heh hot engineer masa udah kere sih baru tanggal segini?"
"Duh lagi nabung nih, Mbak, buat modaaal."
Aku hampir tersedak permen susu di mejaku mendengar jawaban Rasyid, sejurus kemudian aku tersadar dia sedang bergurau seperti biasa.
"Yuk kalo gitu berangcut." Kata Fadhil paling semangat, ia mengenakan tas selempang kulitnya lalu berdiri dari kursi.
Tahu-tahu Mbak Sandra sudah berdiri di samping mejaku.
"Dis, ikut yuk? Karaokean bareng-bareng? Gak jauh kok dari kantor."
"Eh?" Aku tidak tahu apakah sebelum masuk ke kantor ini, mereka memang sudah biasa karaoke bareng dan aku selaku orang baru harus ikut. Sejujurnya aku tidak suka karaoke, kalaupun aku ikut, dapat dipastikan aku tidak akan menyanyikan satu lagu pun.
"Yuk? Gak sampe malem banget kok. Tuh, Kinar juga ikut." Bujuk Mbak Sandra.
"Ayo Dis, ikut aja. Kalo kemaleman, bisa gue anter pulang." Cetus Fadhil dan aku bisa melihat Rasyid meliriknya dengan lirikan aneh.
Sepertinya aku tidak punya pilihan, jadi akhirnya aku mengiyakan.
*
Benar kan.
Aku di tempat karaoke adalah aku yang duduk diam di sudut sofa, mengerjap sesekali saat lampu kerlap-kerlip menyorot mataku karena setelah tidak di kantor, aku melepas kacamataku.
Baru tiga puluh menit berlalu dan baru beberapa yang menyanyikan lagu pilihan mereka tapi kehebohan sudah terjadi. Gery dan Fadhil naik-naik ke sofa, Mbak Sandra menyanyikan lagu-lagu lawas-yang anehnya semua hafal-Rasyid sepertinya berhasil mempengaruhi Mas Aryo untuk melepas dan mengikat dasinya melingkar di kepala seperti waktu itu, seperti bapak-bapak kantoran Jepang yang sedang mabuk.
"Dis? Gak mau pilih lagu???" Mbak Sandra bertanya padaku di antara kebisingan lagu Counting Stras yang dipilih Gery seperti sedang curhat, "LATELY I'VE BEEN, I'VE BEEN LOSING SLEEP!!!"
Aku menggeleng sambil tersenyum lalu menolak halus, "Nggak usah, Mbak."
"Ih masa dateng ke sini gak nyanyi? Ayooooo."
Sebelum aku sempat menjawab, Rasyid menghampiri aku dan Mbak Sandra, menatapku sejenak dan mengambil alat penginput lagu dari tangan Mbak Sandra, "Acid aja yang ngewakilin Dica nyanyi." Gaya bicaranya seperti anak kecil sedang bicara pada ibunya, membuatku sedikit gugup. Kata-katanya seperti menunjukkan bahwa dia mengenalku sebelum satupun orang di kantor mengenalku, dan memang itu kenyataannya. "Dia gak bakal mau soalnya, Mbak."
Seperti yang kuprediksi, Mbak Sandra langsung mengangat sebelah alisnya curiga, ia menatapku dan Acid berganti-ganti sebelum tertawa seolah paham. "Ya udah deh, nih lo pilih nih."
Rasyid menatapku lagi lalu menyambar jaket yang tersampir di tasnya di sofa, tidak jauh dari tempatku duduk lalu menyerahkannya padaku.
Sesuatu dalam diriku seperti bereaksi, menyusul jantungku yang berdebar keras. Jaket denim. Bukan jaket denim kesayanannya, tentu saja, karena jaket itu masih ada padaku. Tapi ini adalah kali pertama dia membawa jaket denim ke kantor, biasanya ia pulang mengenakan hoodie.
"Aku tau kamu gak nyaman dari tadi, tutupin pake jaket aku aja." Katanya dengan volume yang aku yakin tidak akan didengar yang lain, apalagi dia sedikit membungkukkan tubuhnya. "Sebelum dilirik Fadhil." Tambahnya lagi, sedikit posesif.
Aku tahu yang dia maksud adalah rok hitam yang sedang kukenakan. Rok-ku memang sedikit pendek dan berkali-kali sejak duduk di sofa tempat karaoke ini aku membetulkan posisi dudukku, tidak menyangka kalau Rasyid menyadarinya.
Kuturuti sarannya, dengan jantung yang masih berdebar kencang, kulebarkan jaketnya di atas pangkuanku. Seketika aku merasa aman meski yang kulakukan hanya membentangkan jaket.
Rasyid lalu kembali sibuk menekan-nekan alat penginput lagu di tangannya.
"Nih, nih, gue tiga lagu ya. Lagu wajib karaoke gue nih." Katanya semangat.
"Anjis, The Script, Naif, Sheila on 7 yang Dan, galau amat coyyy?"
"HAHAHAHA. HOT ENGINEER APA EMO ENGINEER NIH?"
Rasyid mengabaikan ledekan-ledekan yang dilayangkan padanya
"Dibilangin ini lagu wajib karaoke gue." Katanya cuek lalu mulai menyanyikan intro lagu Six Degrees of Separation.
"You've read the books, you've watched the shows, whats the best no one knows, YEAH."
Aku diam menatap Rasyid, seakan lagu yang dia nyanyikan sedang menceritakan sesuatu padaku.
Setelah dia menyanyikan tiga lagu berturut-turut tanpa jeda, ia menghempaskan tubuhnya ke sofa tepat di sampingku, dasinya sudah tidak lagi ia ikat ke kepala. Dalam keremangan pencahayaan ruangan karaoke, matanya seperti punya sinar sendiri, menatap lurus ke mataku.
"Pulangnya aku anterin," ujarnya padaku setelah mengambil napas.
Sementara aku menahan napas.
*
Seharusnya sesuatu yang sudah diberi judul dan konsep masa lalu tidak akan terasa melekat pada realitas. Seharusnya hubungan antara aku dan Rasyid yang sudah mewujud jadi masa lalu itu terlihat seperti awan padat yang ketika disentuh hanya berupa setetes embun yang rapuh.
Tapi duduk kembali di boncengan vespa biru dongkernya, mau tidak mau menggenggam ujung jaketnya karena aku duduk menyamping-karena rok-dan mengikuti arus jalanan malam menuju rumahku membuatku merasa konsep itu tidak pernah ada.
Dia hanya mengantarku pulang tapi rasanya seakan kami kembali berjalan bersama-sama lagi di satu jalur, tidak lagi tersesat dengan arah kompas yang berbeda. Semua jarak seperti tergerus seiring roda vespa biru tua itu menggilas aspal. Aku juga tidak tahu kenapa.
"Eh bersiiin." Celetuk Rasyid lucu saat aku bersin, refleks mengencangkan genggamanku di jaketnya. Dengan cepat ia menyambung, "Harusnya tadi kamu pake aja jaket aku. Bandel sih."
Dan membiarkan kamu masuk angin? Nggak, Cid.
Awalnya, aku takut aku sedang menyakiti seseorang dengan menyetujui tawaran Rasyid mengantarku pulang, maksudku.. kalau Rasyid sudah punya pacar, ia pasti tidak akan senang mengetahui cowoknya mengantar mantannya pulang.
Tapi setelah beberapa menit dalam perjalanan bersama Rasyid, semua pikiran-pikiran itu seperti menguap. Aku hanya bisa berharap dugaanku tentang pacar Rasyid itu salah.
Rasyid masih Rasyid yang sama, yang suka bersenandung sambil mengendarai motornya sekalipun ia sebenarnya baru saja bernyanyi di karaoke, yang melirikku sesekali lewat spion depan.
Kalau saja aku bisa memilih satu momen yang bisa kuabadikan di tengah kehidupan yang terus berevolusi ini, momen yang bisa kubiarkan stagnan dan memfosil tidak peduli bahwa semesta terus bergerak, maka akan kupilih momen ini. Saat setiap detiknya seperti berpusat pada kami berdua, dan bukan pada segenap hal lain pada detik berikutnya.
Saat aku merasa seperti memiliki Rasyid kembali.
"Udah sampeee." Kata Rasyid saat si Dongker berhenti tepat di depan pagar rumahku.
Aku turun dari boncengan dan langsung merasakan tatapannya yang mengalahkan cahaya lampu teras.
"Makasih ya, Rasyid." Ujarku pelan.
Rasyid tersenyum kotak, senyuman yang rasanya sudah lama aku tidak melihatnya.
"Kenapa Ca? Kerah kemejaku nyelip lagi ya?" Tanyanya pura-pura panik.
"Nggak kok." Aku tersenyum mengingat saat ia memintaku membetulkan kerah kemejanya di lift hari Senin lalu.
"Kirain.. baru mau minta benerin lagi." Rasyid nyengir. "Udah sana masuk. Salam buat ayah bunda kamu ya."
Aku mengangguk, berbisik "Ati-ati, jangan ngebut" dengan cepat sebelum berbalik pelan untuk membuka pagar.
"Ca?"
Apakah Rasyid kembali pada kebiasaan lamanya? Sampai jumpa yang berjilid-jilid sebelum benar-benar pulang?
Aku menoleh.
"Besok pake kacamata lagi gak?"
Aku tertegun mendengar pertanyaannya, "Pake... emang kenapa?"
"Gak apa-apa biar aku bisa siapin ini." Dia menunjuk jantungnya. "Deg-degan soalnya tiap liat kamu kacamataan."
Rasyid, Rasyid. Aku bisa merasakan panas menjalari wajahku.
"Besok juga jangan lupa bawa jaket, Ca!" Akhir dari rangkaian sampai jumpanya sebelum aku benar-benar masuk ke rumah dan dia melaju pulang.
*
"Lho ternyata masih di sini.. kirain udah pulang." Fadhil menghentikan suapan cokelatku ketika dia menghampiriku yang duduk sendirian di meja kantin. Hari ini kami pulang tepat waktu lagi dan sebelum pulang, aku menyempatkan diri makan cokelat sebelum menghadapi jam pulang naik kereta.
Ternyata Fadhil tidak berbasa-basi, ia duduk di depanku sambil mengetik sesuatu di hpnya.
"Gak pulang?" tanyaku ramah.
"Mau kok, bentar lagi. Nunggu anak finance dulu nih, ada yang mau diomongin."
"Oh." Aku mengangguk-angguk lalu kembali ke duniaku sendiri, makan cokelat. Sebelum pertanyaan Fadhil menyeruak.
"Kemaren jadinya dianter pulang Acid kan?"
Untung aku tidak sedang menelan cokelat.
"Ng, iya."
Fadhil manggut-manggut, sesaat ia tidak berkata apa-apa, kemudian tahu-tahu ia menopang dagu memperhatikanku, "Dis, gue boleh nanya gak?"
"Nanya apa?"
"Lo... tuh pernah ada sesuatu ya sama Acid?"
Lagi-lagi, untung aku tidak sedang menelan cokelat.
Fadhil masih memandangku penasaran, aku tidak tahu kalau dia bisa sekepo ini, dan kenapa dia tidak bertanya pada temannya langsung?
"Lo mantannya ya?" Tebak Fadhil lagi. Tebakan yang tepat sasaran. "Mantan yang masih sayang?" Untuk tebakannya yang satu ini aku tidak tahu apakah tepat sasaran.
Aku berusaha kelihatan tenang sebelum menjawab, namun sebelum mulutku melontarkan jawaban, mata Fadhil tertumbuk pada dua orang laki-laki, anak finance yang sedang berjalan menghampirinya.
"Eh, Ca, sorry. Ntar lagi ya dilanjutin." Kata Fadhil langsung lupa pada penasarannya.
Sejurus kemudian aku kembali memakan cokelatku sendirian.
Sampai terdengar derap langkah seseorang dari meja di belakangku, tahu-tahu sudah ada orang lain yang menggantikan Fadhil duduk di depanku dan kali ini cokelatku benar-benar tersangkut di tenggorokan begitu melihatnya. Aku langsung menggapi botol air minum di meja.
"Hai!" Perempuan berambut pendek itu menyapa riang.
Kenapa dia ada di sini saat jam pulang? Kan tidak mungkin ia baru mengantarkan makan siang untuk Acid?
Aku tersenyum kaku. Apakah dia mendengar pertanyaan Fadhil barusan? Sudah berapa lama ia duduk di belakangku?
"Sedivisi sama Acid ya?" Tanyanya membuatku yakin ia mendengar pertanyaan Fadhil tadi. Perasaanku mendadak tidak enak.
Aku mengangguk samar lalu ia mengulurkan tangannya.
"Kenalin gue Shilla."
"Adisa." Aku membalas uluran tangannya.
"Kok Acid belum turun-turun ya? Udah bubaran belum sih? Gue nelponin gak diangkat-angkat."
Aku tidak tahu kalau cokelat yang tadi kumakan menyisakan rasa pahit yang aneh.
"Mungkin... lagi bahas sesuatu dulu bentar sama yang lain, atau.. lagi di lift."
"Oooh." Mulut Shilla membulat, kemudian ia melirik jam tangannya gelisah, "Duh lama gak ya.. soalnya gue sama dia mesti buru-buru pulang."
"Pulang?" Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengerutkan kening.
"Iya, pulang ke rumahnya. Gue ada janji sama nyokapnya hehe makanya bela-belain gojekan dari kantor gue ke sini, biar bareng. Ck. Malah lama lagi dia."
Semenit mengenal Shilla aku bisa menyimpulkan kalau dia tipe orang yang bisa menceritakan apa saja pada orang yang baru dikenalnya, termasuk informasi yang membuat sesuatu yang asing menghentakku.
"Sebentar lagi juga turun mungkin." Ujarku lalu berdiri, "Duluan ya."
Aku menghindari tatapannya saat mengangguk sopan dan pergi keluar kantin.
*
Aku urung pulang naik kereta. Sebaliknya kubiarkan diriku duduk lama di bangku halte dekat kantor, menatap kendaraan yang lalu lalang di depanku. Meski enggan mengakuinya, hatiku berdenyut sakit menyadari kalau dugaanku besar kemungkinannya benar. Tentang Rasyid dan Shilla. Seharusnya kemarin aku menolak diantar pulang Rasyid.
Lamunanku sudah semakin menjauh saat sebuah motor berhenti tepat di depan halte. Pengendaranya membuka kaca helm dan menatapku.
"Dis?"
Aku menghela napas, "Maaf ya, Am. Tiba-tiba minta jemput." Kataku saat menghampirinya.
*
Irham menatap gadis di depannya yang kelihatan murung. Mereka berhadapan di satu meja di McDonalds yang mereka lewati sebelum pulang. Irham kira kentang goreng ukuran large bisa membantu memperbaiki mood Dica, tapi sepertinya sesuatu yang mengganggu pikiran Dica masih lebih dominan dibanding setumpuk kentang goreng.
"Dis, kenapa?" Irham mencondongkan badan dan memiringkan kepalanya, mengamati air muka Dica, "Ada masalah di kantor?"
Sejenak Dica terpaku menatap Irham sebelum menyunggingkan senyum geli. "Ada saos di bibir lo." Kata Dica sambil menahan tawa, ia mengulurkan tisu pada Irham.
Irham tampak malu selama beberapa detik sebelum mengelap noda saus itu dengan tisu. Mengutuki dirinya sendiri yang seperti anak kecil. Tapi kemudian ia melihat senyuman Dica dan merasa lega, setidaknya kemuramannya tidak bertahan terlalu lama.
"Gue ke toilet dulu deh." Irham makin terlihat gugup.
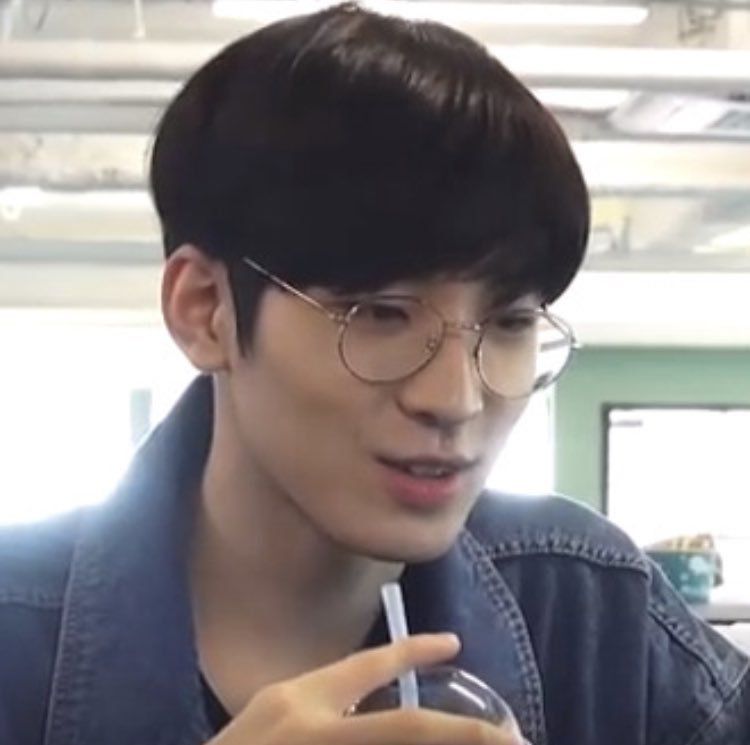
"Eh, gak usah. Kenapa mesti ke toilet?"
"Bersihin saosnya."
"Am, udah ilang kok, tadi cuma dikit doang." Dica menenangkan, masih sambil menahan senyum. Irham kalau sudah gugup jadi lucu.
"Jadi... gak mau cerita nih kenapa?" Tanya Irham setelah mendeham, mengenyahkan rasa malunya.
"Gak apa-apa, ntar aja ceritanya. Lo gimana di kantor?"
Pertanyaan Dica seperti memantik antusiasme Irham, "Gue butuh referensi yang romantis-romantis lagi. Kenapa ya klien-klien pada maunya yang romantis-romantis?"
"Padahal lo kan anti-romantic ya?"
Irham membetulkan letak kacamatanya, "Tapi gue bisa romantis kayak tokoh-tokoh drama yang terpaksa gue tonton itu kok."
"Contohnya ngapain?"
"Gambar satu perempuan yang sama bertahun-tahun."
Dica mengerjap-ngerjap mendengarnya.
Tapi Irham dengan segera mengganti topik, "Dis, menurut lo apa perbedaan Mcd di sini sama Mcd di Jepang?"
Tanpa mereka ketahui ada dua pasang mata yang mengenali mereka, berjarak beberapa meja.
"Itu.. beneran adek kamu kan, Yan? Irham, Irham itu?" Rara sampai mengabaikan burgernya, matanya menajam, memastikan ia tidak salah lihat. "Kok... dia sama Dica sih? Dica, Yan. Mantannya Acid itu."
Ian menghela napas, melihat Ian tidak ikut bingung dan heboh seperti Rara, Rara melayangkan pandangan curiga.
Pikirannya sibuk menyatukan fakta-fakta seperti menyusun puzzle, Irham, Jepang, pembeberan bukti yang bikin ayah bebas, Acid putus.... sampai akhirnya Rara menggumam.
"Kok aneh ya?"
*to be continued*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top