Chapter 32²

Jika kau mendengar laung kepedihan itu, maka kau berada di jalan kematian.
Ren tersentak dan terbangun. Ia membuka matanya lebar-lebar. Dada gadis itu naik turun. Napasnya terengah-engah dan jantungnya berpacu seolah tengah berlomba, menggebrak-gebrak kerangka di dada sampai sesak rasanya. Ia lantas menarik napasnya dalam, mencoba bernapas senormal yang ia bisa. Matanya bergerak-gerak, berusaha mengenali tempatnya berada.
Putih. Rasanya seperti berada di alam bawah sadar yang hampa. Tanpa ada sebuah ilusi setitik pun yang mampu sedikit mewarnai pandangan. Ren beranjak dan memutar pandangan. Apa ia berada di alam bawah sadar, tapi mengapa terasa begitu asing? Seolah dirinya sudah tidak berada di dalam tubuhnya sendiri. Apa karena Ellea tak bersama dirinya lagi? Ren memegangi kepalanya, berusaha untuk kembali mengingat. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang telah terjadi bukanlah sebuah mimpi. Semua kekacauan dan mimpi buruk itu. Ini tidak betul, 'kan, Elle. Ia tersenyum getir saat tak mendapatkan jawaban apa pun.
Dengan ragu, Ren mulai melangkahkan kakinya. Ia merasakan kakinya tanpa alas di bawah sana dan tubuhnya hanya terbalut sebuah piama krem berenda. Rambutnya digerai dan dibiarkan jatuh begitu saja di punggung. Ia tidak pikun atau amnesia lagi. Dirinya ingat betul sebelum jatuh ke jurang mengerikan itu, ia masih memakai pakaiannya yang telah koyak dan ternoda darah, rambut kepang yang telah awut-awutan, dan keadaan dirinya yang terluka. Namun, apa yang sekarang dirinya dapati? Tak ada luka segores pun, lagi rasa sakit. Seolah yang sebelum itu hanyalah khayalan belaka.
"Nak, kurasa kau tersesat."
Ren memutar pandangan dan menemukan sesosok pria. Dia pria dengan kaki jenjang dan tubuh bagus yang dibalut pakaian berjubah yang tampak elit. Rambutnya pirang, menjuntai sampai punggung dan memiliki ujung tajam--sepintas terlihat seperti lidah api. Maniknya kuning keemasan yang memiliki tatapan tajam dan kewibawaan. Ren pernah lihat dia. Rasanya sering dan menjadi sebuah kefamiliaran dalam ingatannya. "Ravish Wolfheart?"
Pria itu tersenyum. "Hebat. Kau langsung mengenaliku ya," katanya sambil terkekeh.
Bagaimana mungkin? Ren terperangah. Bagaimana mungkin sosok yang jelas telah tiada ratusan tahun silam berdiri di hadapannya? Kecuali ... Aku sudah mati?!
"Kenapa wajahmu masam begitu?"
Ren merasakan jemari Ravish yang besar menegakkan dagunya, membuatnya menengadah. Ia bisa lihat dengan jelas wajah Ravish. Dia masih sangat muda, sebagaimana ia tiada sebagai sun yang jarang memiliki umur panjang. Wajahnya putih bersih, tanpa kerutan. Seolah keramik yang dipahat tanpa cela. Di dahinya, terukir sebuah simbol matahari yang mempertegas kedudukannya sebagai sun pertama yang mencipta barrier. Sangat jelas dan mutlak. Ren terpaku. Tak hentinya mengagumi wajah yang begitu elok di hadapannya.
"Hei, kau tak apa?"
Ren tersadar dari lamunannya dan lekas-lekas melengos. Berhenti menatap dengan tatapan kurang ajar pada orang yang harusnya begitu ia hormati. Jika kedudukan sun-nya kini adalah seorang junior, maka orang di hadapannya itu adalah guru besar, guru dari segala guru.
"A-aku baik-baik saja." Ren menggaruk tengkuk dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain sibuk meremas ujung piamanya.
"Kau pasti bingung saat tiba di sini, benar?" Ravish merangkul Ren dan mengajaknya melangkah. Menjejaki lantai asing yang dingin. "Mari kujawab pertanyaanmu."
Ren mendengar suara langkahnya berderap, bergema, dan mengisi pendengarannya. Tempat itu sungguh senyap. Tak ada yang bisa didengar kecuali langkah dan napasnya sendiri. Sangat tenang dan hampa. Ren melirik Ravish. Pria itu masih merangkul bahunya, seolah enggan melepasnya. "Tempat apa ini?" Akhirnya gadis itu mulai bertanya.
Ravish menatapnya dengan tatapan teduh. Bibirnya terangkat, mengulas senyum. "Ini tempat yang damai, bukan?" katanya, "semua sun yang pernah mengabdi pada barrier ada di sini."
"Maksudnya tempat orang mati?" Dahi Ren mengkerut. Nyenyatnya tempat itu terlalu ganjil. Lebih terlihat seperti tempat yang membosankan daripada damai.
Ravish tertawa. "Secara kasarnya." Ia menepuk-nepuk bahu Ren dan melanjutkan, "Nak, kau menyebut tempat ini dengan nama yang menakutkan, tapi percayalah! Tempat ini lebih baik dari apa pun."
Ren mengedikkan bahu. "Entahlah," katanya, "tapi tempat ini terasa ganjil. Terlalu nyenyat dan hampa."
Ravish menengadah dan mengatupkan kelopak matanya. "Tak banyak yang diinginkan orang mati. Kau hanya akan menginginkan kedamaian," katanya. Ia lantas menatap Ren. "Bukankah kau juga menginginkan hal yang sama?"
Ren menghentikan langkahnya yang juga menghentikan Ravish. Gadis itu menegakkan dagunya lantas menatap Ravish. "Tidak," sanggahnya sembari menggeleng. "Aku tak menginginkannya." Ren merasakan cairan air mata mulai berkerumun di pelupuk dan mulai rebas.
"Lalu?" Ravish meletakkan telapak tangannya pada pucuk kepala Ren. Ia berkata dengan lembut.
"Aku tak layak." Ren menggeleng sekali lagi. Ia berkata dengan suara serak. "Aku tak pernah berjasa pada barrier. Aku membuatnya rusak. Aku menghancurkannya." Bahu Ren bergetar dalam isakan. Ada perasaan sesal yang tetap mengendap di palung hatinya. Padahal, ia kira selepas meniadakan Rise dan mencegah kehancuran yang lebih cukup menghilangkan sesal dan rasa bersalahnya. Mengapa hatinya terasa karut-marut seolah hutangnya belum berkurang sama sekali?
"Kau lahir di masa-masa sulit ya." Ren merasakan usapan di pucuk kepalanya. Ia merasa ditenangkan. "Ini bukan salahmu," bisik Ravish kemudian.
"Bagaimana kau tahu?" Ren mengusap air matanya. Namun, rebasannya tak kunjung berhenti.
"Walaupun kami sudah mati, tapi kami masih mengamati kehidupan, Nak."
Saat Ren menengadah, Ravish tersenyum ke arahnya. Ada binar kehangatan yang terpancar dari kedua maniknya yang terang. Seperti sebuah kehidupan yang menuai berbagai harapan. Dengan melihatnya, ada sebuah rasa yang timbul di hati Ren dan membuat otaknya bereaksi untuk berpikir. "Aku tak boleh di sini sekarang." Ia menegakkan dagunya dan menatap Ravish dengan percaya diri. "Belum saatnya."
Dahi Ravish berkedut, tapi sebuah senyuman menghapus reaksi kebingungan itu. "Kau punya semangat yang bagus. Apa yang akan kulakukan jika kau hidup?"
Ren melebarkan senyumnya dan menjawab dengan mantap. "Aku memang tak bisa berjasa untuk barrier, tapi aku masih bisa berusaha menjadi orang yang berguna untuk Shappire. Aku ingin membuat diriku layak untuk bertempat bersama kalian, para sun."
"Ya," kata Ravish. Ia menegakkan tubuhnya dan bercekak pinggang. "Kupikir ini belum waktunya untuk mengajakmu bergabung."
"Nah, Tuan Ravish Wolfheart, apa kau bisa memberitahuku jalan untuk pulang?"
Ravish menepuk bahu Ren. "Berbaliklah," ungkapnya masih dengan senyuman yang ramah. Ren menuruti perintah pria itu dan berbalik, menghadap kekosongan yang terhampar. "Berlarilah lurus ke depan. Jangan pernah menoleh. Karena menoleh adalah sebuah keraguan."
"Terima kasih," kata Ren sembari menatap lekat wajah Ravish. Ini pertemuan singkat yang mengagumkan bagi gadis itu. "Ngomong-ngomong, aku penggemar beratmu, Tuan." Ren mulai melangkahkan kakinya, semakin lama semakin cepat. Ia mulai menjauh dari Ravish dan melepaskan kedamaian abadi yang belum saatnya ia gapai. Tak ada keraguan dalam langkahnya. Ia terus berlari menempus kehampaan yang membawanya pada cahaya yang begitu terang.
"Nak, kau lulus dari ujian kesabaran yang sejak dulu berusaha kau tolak. Kau tak boleh menolak jati dirimu lagi."
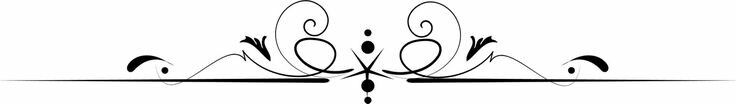
16 hari berlalu sejak hancurnya kubah barrier Shappire. Selama itu pula, musim dingin masih sibuk menghamparkan dirinya. Merisak orang-orang yang sibuk mengurusi kemelut hatinya masing-masing. Menata kembali keberanian untuk melanjutkan hidup yang berbeda dari sebelumnya di Shappire. Benua itu telah berubah.
Bencana yang berhasil meratakan Kota Hillaria, Cornelium itu tak akan pernah dilupa. Lebih lagi bagaimana banyaknya laung masygul kehilangan akan harta dan orang terkasih. Luka itu tak akan hilang dengan mudah. Sebagaimana karat yang telah menggerogoti besi. Perbaikan masih terus dilakukan dan bantuan masih datang berbondong-bondong kepada Hillaria. Namun, satu kenyataan yang tak lagi bisa disangkal dan ditutupi adalah masa barrier telah berakhir. Masa di mana orang-orang shappire tinggal di balik tempurung tak kasat mata yang membatasi. Walaupun kuil barrier masih kukuh berdiri dan lotus biru masih terus tumbuh, upaya pembangunan barrier kembali tak dapat dilakukan. Anak-anak di bawah umur--yang mereka sebut para pemilik elemen dewa itu--masih dalam keadaan kacau. Bahkan, tampaknya tak mampu sekadar membangun barrier untuk sebuah kota kecil.
Seminggu sebelumnya, tepat satu minggu setelah bencana, kapal-kapal dari benua terdekat Shappire singgah di pelabuhan-pelabuhan yang menghadap langsung ke benua luar. Dan kapal-kapal besar tampak datang semakin dekat mendekat dari jauh. Hal itu cukup menggetarkah hati penghuni Shappire yang masih dicokoli resah. Walaupun Shappire adalah benua terluas, ia tak memiliki armada laut yang kuat. Keamanan laut tak begitu diperhatikan saat barrier masih kukuh melingkupi. Bayang-bayang perang lama yang timbul dari musnahnya barrier menghantui semua orang. Namun, pada akhirnya anggapan itu terpatahkan. Benua-benua di luar, seperti Ametyst, Topaz, dan Ruby menyambut baik atas Shappire yang membuka dirinya kembali. Menanggalkan kubah yang membuatnya terkurung dan terpisah dari peradaban yang lebih luas. Mereka bahkan menawarkan bantuan untuk memperbaiki Hillaria dan menawarkan kerja sama di berbagai bidang. Seperti di masa lalu.
Benua-benua di luar juga bersedia melakukan pertukaran ilmu pengetahuan. Shappire adalah benua primitif yang tertinggal. Ia masih bertumpu pada penggunaan elemen dan membuat perkembangan teknologi terhambat. Di luar sana, benua-benua tumbuh dalam modernisasi. Teknologi dan elemen bertumbuh bersama dalam harmoni. Tanpa ketimpangan yang berarti. Jauh lebih maju dari benua kuno Shappire.
Dalam waktu beberapa hari ini, segalanya sudah banyak berubah. Ya, berubah secara harfiah. Bahkan, dalam waktu sesingkat seminggu itu, Aliansi Internasional telah dibentuk untuk menyambut Shappire kembali dalam perputaran aktivitas internasional. Hilangnya barrier bukan mimpi buruk. Sebaliknya, barrier adalah pengekang yang mengurung mereka dalam keterbelakangan. Tempurung yang mengurung dalam lakuna mimpi buruk mereka sendiri.
Kini, semuanya berakhir. Pemerintah telah menutup bencana runtuhnya barrier dan menetapkannya sebagai peristiwa cataclysum biasa. Tak ada yang namanya sun yang berkhianat atau apa pun yang berhubungan dengan Rise Carmerose dan dark. Semuanya dilupakan seolah penghapusan perempuan itu mencakup ingatan orang-orang. Tak ada yang akan mencarinya sekali pun ia tak pernah terlihat lagi.
Salju masih sibuk menghambur di luar jendela. Ini ketiga kalinya dalam minggu ini. Bulan ketiga bukan akhir musim dingin untuk Annelosia. Ia mengawali juga mengakhiri musim dingin. Tanah yang dingin dan beku. Manik biru yang mengamati turunnya salju dari balik jendela berkilat. Terkena pantulan cahaya matahari yang menyorot salju di luar sana. Laki-laki pemilik manik itu mengatupkan pelupuknya, lantas menghela napas panjang. Sebelum akhirnya sebuah suara terdengar di belakangnya, "Berhentilah berdiri di depan jendela. Kau menghalangi cahaya."
Laki-laki itu, Vier, berbalik dan menengadahkan kepalanya. Menengok lampu di langit-langit masih benderang dan cukup untuk sekadar menerangi satu ruangan. "Kurasa retinamu tak dapat menerima cahaya lagi, Excel," tukasnya kemudian.
Excel mendecih, lantas berkata, "Ah, selesaikan saja berkas-berkas ini! Aku muak melihatnya." Laki-laki itu melempar penanya asal di atas meja dan menjatuhkan punggungnya pada sandaran kursi.
Vier menggelengkan kepalanya. Dua minggu berlalu sejak peristiwa itu dan entah kenapa hubungannya dengan Excel sedikit membaik. Seolah ada yang salah dengan kepala laki-laki bersurai kelam itu. Yah, ini lebih baik daripada bermain kucing dan tikus lagi.
Hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, Raja Annelosia pergi dalam rapat Asosiasi Internasional. Dengan itu, beberapa tugas untuk menangani dokumen dilemparkan kepada pewaris takhtanya, Vier. Selepas hilangnya barrier dan statusnya sebagai sky tak lagi berlaku, kedudukannya sebagai pewaris takhta semakin kuat. Karena sudah pasti ia tak akan mengabdi pada kuil barrier sepanjang hidupnya. Dan Excel, laki-laki itu mungkin akan jadi asisten selama tangan kanannya cedera. Kerjanya bagus, tapi terlalu banyak mengeluh.
"Bagaimana bisa kau muak? Padahal itu pekerjaan seorang raja. Bukannya kau berniat mengambil takhta?" Vier berkata sembari menaikkan bibirnya.
"Kalau begitu, tak jadi," jawab Excel dengan mudahnya sebelum menutup mata dan melemaskan bahu.
Pintu di sisi ruangan terbuka tanpa ketukan. Sosok Rezel muncul dan membawa beberapa tumpuk buku dan berkas. "Pekerjaan," katanya dengan nada tukang pos.
"Hei, Rezel, ada kabar dari Castelesia?" Vier bertanya sembari menggapai beberapa lembar kertas dan pena. Excel pun tampak memperhatikan, menajamkan pendengarannya untuk mendengarkan kabar.
Rezel menatap Vier sejanak, lantas menglihkan pandangan pada buku di tangannya. "Belum," katanya, "tenang saja. Dia akan segera bangun."
Vier menghela napasnya. "Kuharap begitu, ini sudah lebih dari dua minggu."
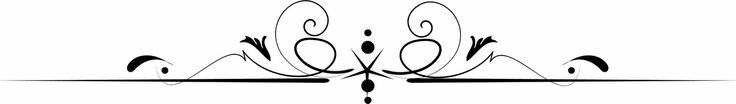
Saat Ren mendapatkan kesadarannya kembali, ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia tak melihat cahaya merasuk ke dalam retina matanya. Gelap. Seperti berada dalam kegelapan tanpa setitik cahaya. Napas gadis itu mendadak sesak, seolah tak lagi tersisa oksigen buatnya. Ia takut kegelapan. Dalam kebingungannya itu, pecahan-pecahan ingatan datang padanya. Memberikan gambaran tentang dirinya sebelum kembali pada kegelapan yang pekat. Ia bertemu Ravish. Dan itu artinya, ia hampir mati.
Dalam kegelapan, jemari Ren meraba-raba. Mengenali tempatnya terbaring. Alasnya betul-betul lembut dan empuk. Ia juga merasakan bagaimana selimut yang tebal dan hangat melingkupi tubuhnya. Seolah mereka ditenun dari benang wol terbaik. Yang sebagaimana mampu menangkal hawa dingin. Selepas sibuk mengenali tempatnya sebagai ranjang king size--yang kedua tepiannya tak dapat ia gapai dengan rentangan tangan--Ren berusaha bangun dan duduk. Namun, baru saja berhasil menegakkan perut, gadis itu meringis kesakitan. Perutnya berdenyut-denyut nyeri seperti ditusuki ujung-ujung yang tajam. Namun, dirinya sadar bagaimana perban melilit pinggangnya erat, sampai sesak. Seolah berusaha mencegah luka di baliknya untuk kembali terbuka.
Sambil mengelus perutnya yang berdenyut, Ren mencoba kembali untuk melihat. Namun, tak ada setitik cahaya yang mampu merangsang retinya. Apa sebegitu gelapnya ruangan tempatnya sekarang? Namun, sekoyong-konyong gadis itu menyadari sesuatu memutari kepalanya, tepat menutup kedua matanya. Jemari Ren gemetar merasakan tekstur kasar perban yang menghalang matanya untuk melihat. Aku buta? Tanyanya berulang-ulang pada dirinya sendiri. Gadis itu terdiam cukup lama. Mengulas kembali segala kemungkinan buruk yang berbondong-bondong mengisi kepalanya. Ia merasakan air mata menyusup lewat celah perban dan turun ke pipinya. Apa ini hasil karena memaksakan mata hoffan-nya untuk terus bekerja. Atau sebuah karma karena tak menggunakan kemampuannya dengan bijak? Bagaimanapun juga, ia telah membunuh Rise. Parahnya lagi, ia memusnahkannya. Mengoyak raga dan jiwanya. Menjadikannya sebuah hal yang tiada seolah tak pernah tercipta.
Dengan jantung yang berdebar tak karuan, Ren menggapai-gapai tepi ranjang. Gadis itu lantas menurunkan kakinya ke atas lantai pualam yang dingin. Saat hendak berdiri, kakinya terasa lemas dan kehilangan daya untuk menahan berat tubuhnya. Saat hampir jatuh, ia berusaha menggapai benda-benda yang dekat darinya. Namun, dirinya malah menubruk nakas dan membuat dirinya terjatuh bersama barang-barang yang mengeluarkan suara berdebap. Ren rasa dirinya menjatuhkan serta sebuah vas dan membuatnya bersepai. Napas Ren terdengih-dengih. Jantungnya berpacu kian cepat. Kegelapan membuatnya ketakutan. Di tengah kegamangan hatinya, pintu berderit di sisi ruangan. Mengiring suara yang menyeru ke arahnya. "Stella!"
Tubuh Ren seperti tersengat saat seseorang yang datang itu menyentuh lengannya. Gadis itu sontak menepisnya dan berkata, "Siapa?!" Namun, sosok itu tiba-tiba memeluknya erat. Membenamkan tubuhnya dalam rengkuhan dada yang lebar. Ada perasaan akrab yang kontan dirasa Ren. Aroma tubuh yang ia kenal dan rengkuhan yang tak terasa asing. "Kak Zeon?"
"Ya," jawab sosok itu seperti bisikan. Laki-laki itu masih mengeratkan pelukannya pada Ren, tampak tak berminat untuk melepaskannya dalam waktu dekat.
"Aku...." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ren terisak. Isakannya itu berhasil membuat Zeon kontan melepas pelukannya. Laki-laki itu mengelus pucuk kepala Ren.
"Ada apa?"
"Aku takut," jawab Ren sembari mencengkeram lengan Zeon yang mengelus kepalanya. "Apa aku buta? Apa aku lumpuh?"
Ada jeda di mana Zeon tak segera menjawab. Kebungkamannya itu berhasil membuat hati Ren mengkerut. Ia malah berharap Zeon tak menjawabnya karena ia takut akan hal yang akan keluar dari mulut laki-laki itu. Namun, pada akhirnya jawaban Zeon malah membuat Ren tersentak. "Tidak." Laki-laki itu menjawab tenang. Ia mengangkat tubuh Ren dan membaringkan gadis itu kembali ke ranjangnya.
"Apa maksudmu tidak?"
Ren dengar Zeon berdeham sebelum menjawab, "Kau tidak buta. Matamu hanya butuh istirahat karena kau terlalu memaksakannya." Ia menjeda dan melanjutkan, "dan kau tak lumpuh. Kau hanya terlalu lama berbaring."
"Terlalu lama?" Ren mengerutkan dahinya. "Berapa lama aku tak sadarkan diri?"
"Lima belas hari." Zeon menarik selimut dan kembali melingkupkannya pada Ren. "Kau tak terkena pecahan vas, 'kan?" Gadis yang ditanyainya hanya menggeleng tanpa membuka mulut. Namun, malah bereaksi saat Zeon hendak berbalik.
"Jangan pergi!" Ren menggapai lengan Zeon kuat-kuat.
Zeon menatap Ren sejenak sebelum mengulas senyum. "Sebentar saja. Aku akan panggilkan dokter kerajaan dan memanggil pelayan untuk bersihkan ini. Jangan turun dari ranjang, okay?"
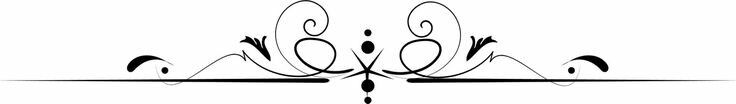
Selepas dokter selesai memeriksanya, Ren mendengar suara ribut di luar pintu. Suara itu lebih ia kenal dari suara ribut mana pun. Zuan. Kiranya laki-laki itu tengah adu mulut dengan saudara kembarnya. Entahlah, Ren tak mengerti persis apa yang ada di pikiran anak kembar. Kadang mereka terasa amat dekat dengan keserupaan perupaan mereka, kadang kala terasa jauh sebab perbedaan yang muncul sebagai sekat di antara mereka. Mereka sulit ditebak.
Tak lama, pintu kembali berderit dan Ren kembali mendengar suara langkah datang kepadanya. Langkahnya terdengar ringan dan tenang. "Ren, ah, maksudku Estella, bagaimana peraaaanmu?"
Mendengar suara perempuan yang familier itu, Ren menegakkan wajah ke arahnya. Dalam kebutaannya ia berseru, "Musa!"
"Hai!" Musa duduk di samping Ren dan menggapai kedua tangan Ren. "Senang mendapatimu sebagai sepupuku," katanya kemudian diselingi tawa.
Genggaman tangan Musa terasa sangat hangat. Dan Ren bisa merasakan seberapa halusnya sepasang telapak tangannya. Ia pikir, dirinya tak akan pernah berjumpa dengan Musa lagi selepas ini semua berlalu. Namun, takdir memberinya kesempatan. Sama halnya kesempatan hidup yang diberikan untuknya.
"Ya, kupikir kita memiliki ikatan batin sejak awal." Ren ikut tertawa.
Tak lama suara pintu yang digebrak memutus obrolan mereka. Di sana Ren dengar suara Zuan dengan nada merengek. "Oh, Estelle, kau harus memberi kakakmu pelukan!" Laki-laki itu menghambur ke arah Ren dan memeluknya. "Aku sangat bersyukur kau kembali," bisiknya kemudian.
Ren tersenyum dan membalas pelukan Zuan. Ia tak pernah merasa didebarkan oleh rasa senang macam ini sebelumnya. Rasanya asing, tapi ia begitu menyukainya. Untuk pertama kalinya, Ren merasa dirinya telah pulang. Menemukan kembali pecahan-pecahan dari dirinya yang hilang. Ia punya ingatan dan keluarga. Ini seperti mimpi. Seperti bayang semu yang hampir tak mungkin ia dapatkan. Ren mengeratkan pelukannya. Kalaupun ini mimpi, setidaknya ia akan memuaskan pelukannya pada orang-orang ini dulu.
"Zuan, jangan memeluknya terlalu erat. Kau bisa membuat luka Stella terbuka."
Zuan melepas pelukannya mendengar omelan Zeon. Laki-laki itu mendecak sebelum mencebik, "Oh, ayolah, kakak posesif! Kau sudah dapat giliran."
"Apa kau bilang? Posesif?" Zeon menggeram dan menatap Zuan tajam. Gelagatnya seperti hendak menerkam saudara kembarnya.
"Berhenti bertengkar, kalian berdua." Musa bersuara dari tempatnya duduk. Membuat sepasang saudara itu saling melengos dan mendengkus.
Ren terkikik, membayangkan mereka bertiga dari kegelapan pandangannya. Walaupun tak melihat mereka secara langsung saat ini, tapi ia hafal betul bagaimana Zeon dan Zuan bertengkar seperti anak kecil. Dan ia juga ingat sedikit-sedikit tentang Musa yang kerap menjadi penengah, namun bisa jadi lebih ganas kalau ia kesal.
"Ngomong-ngomong." Ren menjeda untuk menyusun kalimatnya. "Bagaimana kalian tahu ini aku. Maksudku, Estella?"
"Oh, kau mau dengar cerita?" Perkataan Zuan tampak menyaru Zeon yang hendak membuka mulutnya. Ia melirik ke arah saudaranya itu sambil menjereng gigi.
"Cerita?"
Zuan mengambil napasnya dan mulai bercerita. Ia memulainya dengan kabar dari Vier. Laki-laki itu yang menyalurkan cerita dari Precious tentang Ren kepada si kembar. Seolah tengah kebakaran jenggot, mereka bertindak cepat--lebih nampak terburu-buru menurut Musa. Si kembar--yang tengah menjalankan tugas sebagai relawan--langsung menghubungi Castelesia dan menyampaikan kabar tentang Estella yang telah ditemukan. Ren dijemput ke Castelesia hari itu juga. Sebelum betul-betul diakui sebagai Castelia secara resmi, gadis itu harus menjalani beberapa tes. Tes medis bukanlah masalah. Yang menjadi masalah kala itu adalah pengujian adat dari hoffan. "Mereka primitif," desis Zeon. Keadaan Ren yang masih terluka membuat pengujian itu terlalu beresiko. Kalau dia bukan hoffan, maka presentase keselamatannya adalah tipis. Klan hoffan tidak akan mengampuni dengan mudah orang-orang yang mengakui dirinya hoffan tanpa bukti. Hal itu dianggap tindakan merendahkan martabat hoffan dan melanggar kode etik.
Dalam masalah itulah Zuan menyebut Zeon seperti orang kesetanan. Ia bahkan mendatangi Vier dalam masa pemulihan dan berteriak padanya. Menuntut kebenaran bahwa Ren benar-benar adiknya dan seorang hoffan. Atau jika anggapan itu adalah sebuah kesalahan, maka tak dapat dijamin gadis itu akan selamat dari pengujian. Tak masalah jika Ren bukanlah Estella, Zeon hanya tak mau gadis itu mati sia-sia. Karena hatinya yang terus merasa gamang, laki-laki itu sempat menentang pengujuan secara adat. Dengan bukti pengujian medis, ia berpendapat semuanya sudah jelas dan tak perlu melakukan pengujian secara adat. Dengan sikap tenangnya yang berubah total itu, ia sampai perlu ditenangkan, bahkan sang raja juga harus turun tangan.
"Begitulah drama Zeon! Kau tak akan percaya itu benar-benar Zeon!"
Zeon menabuk punggung Zuan keras hingga laki-laki itu meringis kesakitan. "Kita sudah sepakat tak membahas ini, okay?"
"Aku hanya bercerita. Apa salahnya?"
Ren terkikik. "Bagaimana kau bisa sepanik itu?"
Zeon mendecih. "Kau hanya tak tahu sisi lain primitif yang aneh dari klan hoffan itu."
"Kau hanya paranoid, Zeon." Musa menyahut. "Itu terjadi karena sejak awal kau punya rasa untuk melindungi Estella yang tinggi."
"Aku tahu. Aku hanya merasa kurang sehat."
Ren meringis. Merinding membayangkan pengunjian macam apa yang membuat nyawanya terancam. Yah, dirinya tak tumbuh di lingkungan hoffan. Masih banyak hal yang patut dipertanyakan.
"Oh, ngomong-ngomong, Ella. Kami menerima banyak e-mail yang ditujukan untukmu." Musa membuka tablet yang sejat tadi ditentengnya. "Coba kita lihat. E-mail dari para pemilik elemen dewa. Oh, ya, mereka meminta maaf karena telah memperlakukanmu kurang baik. Mereka juga berharap kau mengundang mereka untuk minum teh, atau apa pun agar bisa herkumpul."
"Pesta minum teh?"
"Yah, itu bisa diagendakan." Zeon bersuara dari sisi lain. "Mungkin bisa dilakukan beberapa hari setelah dokter melepas perbannya."
"Boleh juga," sahut Musa setuju.
Ren hanya tersenyum. Sepertinya malah para saudaranya ini yang akan mengurusi segala masalahnya. Rasanya sudah lama sekali segala hal terasa begitu mudah.
"Lalu, e-mail tidak resmi dari Luca Annello. Oh, ini pesan darinya secara pribadi." Musa melanjutkan sembari mengutik tabletnya.
"Apa itu surat cinta?" Zuan menyahut sembari tertawa.
"Surat cinta apanya?" Zeon memperhatikan e-mail dalam tablet Musa. "Dia terlalu sering menulis surat resmi ya? Ini tak kelihatan seperti surat pribadi."
Ren tertawa. "Oh, ayolah. Mana ada surat cinta." Ia mengedikkan bahu. Ia tak yakin Vier bisa menulis surat macam itu. Terlebih mustahil lagi kalau ia mengirimnya pada Ren. "Hanya itu?"
Musa berdeham. "Ada surat-surat yang ditulis secara manual juga. Ah, liat amplop-amplop ini. Tertulis di sini 9 Heroes?"
"Masih ada yang menulis surat manual begitu. Nama pengirimnya juga." Zuan mengambil alih amplop dari tangan Musa.
"Dari sembilan pahlawan? Musa bisa kau tolong bacakan untukku?"
"Tentu saja."
Ren menghela napasnya lega. Ia duduk dan menyandarkan punggungnya sembari mendengarkan Musa. Ia bersyukur, tak ada hal buruk yang menimpa mereka, para sembilan pahlawan. Mereka sudah cukup membantu. Yah, walaupun dengan anggapan memanfaatkan Ren untuk membantu mereka keluar dari kastil kedengaran agak salah. Gadis itu tak ambil pusing, toh semua temannya selamat. Setidaknya semuanya jadi lebih baik dari sebelumnya.
Tak ada lagi ketakutan akan peperangan lagi di ranah Shappire. Lagi, para pemilik elemen dewa dapat menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Kedua sisi zona di Shappire pun saling mengikat perdamaian lagi. Banyak perubahan yang terjadi di Shappire. Namun sama halnya dua sisi mata koin, banyak yang harus dikorbankan untuk sebuah perubahan. Bencana yang sempat menimpa Hillaria akan dikenang semua orang. Karena kejadian itu adalah tonggak sejarah kembali Shappire pada dunia.
Mengingat sesuatu, ren kembali bertanya. "Bagaimana dengan keluarga lamaku?"
"Kami sudah mengirim pesan pada mereka," sahut Musa. "Castelesia juga akan jadi donatur tetap."
"Kau ingin mengunjungi mereka?" Zeon bersuara di sisi Musa. "Kau bisa berkunjung saat sudah benar-benar sembuh."
Ren tersenyum. "Ya, terima kasih."
Bukankah ini sebuah akhir dan awal yang baik?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top