16. Janji yang Tak Terpenuhi

♬ Lost in longing,
I’m standing still ... ♬
⇆ㅤ ||◁ㅤ❚❚ㅤ▷||ㅤ ↻
"Aku cuma mau kebebasan, Pa!"
Pria berusia kepala empat itu menghela napas panjang. Percakapan ini lagi. Sepanjang sejarah kehidupan keluarganya, topik semacam ini memang paling efektif untuk menghancurkan suasana. Telanjur. "Dengar. Papa enggak mau kondisi Langit makin parah, oke? Papa enggak akan pernah membatasi apa yang Langit mau, selama itu enggak bikin Langit kenapa-napa."
Napas Langit memburu. Bahu ringkih itu bergetar, naik-turun, bersesuaian dengan ledakan emosi yang tak terkendalikan di dalam sana. Tangan Langit terkepal kuat. "Aku cuma pengin merasa hidup, Pa. Tanpa beban, tanpa ketergantungan, tanpa ketakutan-ketakutan yang selalu gentayangan selama ini."
Dengan raut cemas, Aksa mengusap-usap puncak kepala Langit perlahan. Sorot mata sayunya terus menjelajahi setiap senti wajah Langit yang pucat sekaligus tampak menahan amarah. "Iya. Papa paham."
"Enggak. Papa enggak tahu dan enggak akan pernah paham. Aku yang merasakan sakitnya, aku yang terus dilarang ini-itu, aku yang lagi-lagi hidupnya cuma berorientasi di antara terapi dan ceramah basi dokter-dokter," serobot Langit. Cairan bening akhirnya menetes dari pelupuk mata hitam legam itu. Tidak. Kenapa ia malah menyakiti papanya begini?
Rasa sesak sekaligus penyesalan mulai menyeruak makin banyak. Langit menunduk dalam, berusaha menetralkan buncahan emosinya. Tenang ... tarik napas dalam-dalam. Setelah hanya terdengar deru napas tak beraturan dalam belasan detik lamanya, Langit pun memejamkan mata, lantas menghambur pada pelukan papanya.
Kaget dengan aksi dadakan itu, Aksa mematung, lantas mengulas senyuman getir. Tangan kokoh pria menjelang usia kepala empat itu balas mendekap punggung Langit erat-erat. Detik berikutnya, terdengar suara lirih Langit. "Maaf. Maafin Langit."
"Enggak apa. Pelan-pelan, ya. Semesta pasti punya rencananya sendiri. Bukan salah Langit, kok. Papa malah kagum sama Langit." Masih dengan dekap yang bertautan, Aksa mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah. Tak sengaja, netra Aksa malah bertabrakan dengan tatapan cemas istrinya yang menyaksikan mereka dari balik dinding pembatas dapur dan ruang tamu. Lagi, Aksa tersenyum menenangkan. "Langit anak Papa yang kuat. Papa aja belum tentu bisa sekuat Langit."
Langit hanya anak-anak ....
Entah bagaimana mengatakannya, tetapi semenjak mendapat diagnosis dokter pada lima tahun silam, Langit seolah tak mengenal lagi yang namanya kehidupan. Remaja? Dewasa? Rasanya, sampai saat ini pun, Langit merasa dirinya terjebak dalam masa kanak-kanak. Langit belum beranjak dari masa di mana dirinya hanya belajar dan terus bermain, tidak memedulikan apa pun.
Mungkin itu mekanisme pertahanan dirinya untuk mengelak dari kenyataan mengenai hitungan mundur kehidupan ... mungkin saja.
Langit makin membenamkan kepalanya di dada bidang Aksa. Selama ini, Langit tak mampu kembali naik ke permukaan ... Langit sudah kesulitan bernapas sejak awal, kenapa tidak sekalian tenggelamkan saja dari sekarang?
"Papa enggak mau Langit kenapa-napa. Papa mau Langit tetap di sini." Aksa menggeliatkan bola matanya ke sana kemari, berusaha menahan air mata yang tak tahan untuk jatuh. Pria itu mengeratkan dekapan, tak mau anak lelakinya menyadari seberapa lemahnya ia untuk terus menghadapi semua ini tanpa pernah berniat menyerah. "Maaf kalau Papa egois."
Di antara tangan papanya yang melingkari erat, Langit menggelengkan kepala dengan bergetar. Kaus di bagian dada Aksa sudah terasa dibasahi cairan hangat. Langit menangis. "Aku, Pa. Langit yang egois. Langit pengin membebaskan diri dari renggutan kehidupan. Langit sok kuat menaklukkan semesta. Langit ... Langit ngotot pengin hidup seolah Langit emang mampu memegang tuas kendalinya."
Rambut hitam tipis Langit diusap Aksa dengan lembut. Lagi. Lagi-lagi, malam ke sekian kali yang diisi keluhan keduanya dalam kelam. Bukan sekali dua kali Langit dan Aksa melakukan perbincangan senyap begini. Namun, seringnya terjadi setelah Aksa meminta Langit untuk beristirahat cukup dan jangan terlalu aktif di sekolah. Selalu saja begitu.
Ya ... Langit senang melakukannya. Setidaknya, dengan menjadikan punggung kokoh papanya tempat untuk pulang, Langit bisa menyalurkan apa yang ingin ia sampaikan. Begitulah cara Langit mempertahankan mental yang stabil setiap kali di luar rumah. Langit bisa tampak begitu terkendali ketika bersama orang lain, karena semua rasa sakit yang tersemai di setiap penjuru jiwanya sudah dikeluarkan ketika bersama Aksa.
Begitu saja seterusnya. Isi ulang rasa sakit, lantas ditumpahkannya di rumah.
Setelah emosinya sudah cukup tuntas tertangani, Langit menjauhkan kepalanya dari pelukan Aksa. Lelaki itu merekahkan senyuman lebar. Mata bulatnya yang sewarna hitam legam itu bahkan menghadirkan binar-binar keceriaan. Tak ada sama sekali bekas menangis yang tersisa di bingkai wajahnya.
"Papa enggak usah khawatir, ya. Ini cuma memar biasa, kok. Sekali-kali." Dengan cengiran dan nada bicara santainya, Langit menunjuk rahang kirinya sendiri. Ah, Aksa memang menyadari itu sedari awal. Akan tetapi, menanyai anaknya lebih lanjut soal memar itu pasti tidak akan berujung baik. Aksa mengangguk seraya menahan segala kehawatirannya dalam dada.
Dengan muka paling cerah yang pernah Aksa lihat seharian ini, Langit pamit undur diri untuk naik ke kamarnya. Lihatlah betapa cepat anak itu berubah ... seolah tak pernah terjadi apa-apa. Langit memang selalu mampu berkamuflase dengan lihai.
Di lantai dua, Langit langsung memasuki kamar dan duduk di atas kursi belajarnya. Tangan itu menjelajahi setiap sudut meja. Tidak ada. Oh, masih di tas, mungkin. Langit menggeledah isi tas demi mengeluarkan earphone putih miliknya. Ketemu.
Baru saja jari Langit menggulirkan layar ponsel untuk memutar lagu GFriend - Crossroads favoritnya, keseluruhan atensi lelaki itu tersedot oleh pop-up notifikasi yang masuk. Tiga chat dari Tala. Kepala Langit berdenyut nyeri. Gejala anemia itu ... oh, jangan dulu. Ayolah. Langit menyugar rambut hitam legamnya ke belakang, lantas membuka chatroom dengan Tala.
Ikan Bental Ta(Mak)Lampir
Langit Bau Hangit! xixixi
Besok tetep berangkat bareng, 'kan?
Ajak Mega, yuk!:3
Langit menyimpan senyuman tipis di sudut bibir. Setelah mengembuskan napas berat, lelaki itu menengadahkan kepala di sandaran kursi belajar, berusaha menetralisir rasa pusing yang masih menggerogoti, belum beradaptasi dengan pergantian posisi dari berdiri ke posisi duduk. Menyebalkan, memang. Setelah segalanya terasa membaik, barulah jari Langit mengetikkan pesan balasan di atas keyboard.
Iyalah! Bareng aja, biasa.
Kalau Mega-nya mau, tapi.
Enggak janji bisa bertiga, ya.
Tidak perlu waktu lama untuk Langit menunggu balasan Tala, mengingat anak perempuan itu masih online dan langsung membaca pesannya. Detik berikutnya, Langit menerima pesan baru, masih dari kontak yang sama.
Yeay! Fix, ya.
Besok aku samper dari pagi.
Jangan kesiangan, lho!
Oh ... Lang, Lang!
Masih dengan alis terangkat begitu dibombardir oleh spam chat dari Tala, ponsel Langit berdering panjang. Panggilan masuk. Tanpa perlu menunggu apa pun lagi, Langit mengangkat video call tersebut.
Hal yang pertama kali Langit lihat dari layar ponselnya adalah sosok Tala yang sedang rebahan. Tidak salah lagi. Kaum rebahan sejati. Tak sengaja, netra hitam legam Langit menangkap eksistensi tumpukan buku dan alat tulis yang berserakan di atas kasur, persis di dekat kepala Tala. Anak itu pasti sedang istirahat setelah belajar keras sejak pulang sekolah tadi. Langit menahan senyuman geli.
"Lang, Lang! Kita belum ulangan matematika peminatan, lho. Di masa UTS kemarin, Pak Prana malah terus ngebahas kedudukan lingkaran, 'kan? Gradien ... titik potong?" Suara cempreng yang heboh tersebut menerpa indra pendengaran Langit dengan tidak estetik. "Nih, ya, kata aku ...."
Belum sempat Langit mendengar Tala menuntaskan kalimatnya, kamera di seberang sana malah terlihat tidak stabil dan berubah hitam, bersamaan dengan seruan sebal Tala yang mengaduh heboh. Tak perlu bertanya lebih dulu, Langit sudah tahu kalau anak itu menjatuhkan ponselnya hingga menghantam muka. Langit terbahak. Beberapa saat kemudian, barulah kamera Tala kembali ke posisi seharusnya, memperlihatkan alis Tala yang mengerut kesal.
"Hape nyebelin! Enggak sopan banget, orang lagi ngomong." Begitulah gerutu Tala sembari mengusap-usap bibirnya yang terasa lebih monyong. Meski begitu, Tala tak kehilangan semangat untuk meneruskan kalimatnya yang sempat terjeda barusan. "Nih, ya! Lang! Kata aku, besok masih ulangan, enggak, sih? Harusnya, ya ... biasalah. Pak Prana, kan, suka ngasih kejutan. Kita belum ulangan MTKP sama sekali, selama semester dua, 'kan?"
Oh, ayolah. Tala melakukan panggilan video dengannya hanya untuk membicarakan hal begini? Tala banget, ya. Langit mengangkat bahu. "Kemungkinannya, sih, gitu."
"Oke, fix. Mau belajar! Aku pasti bisa ngalahin nilai Langit di ulangan besok!"
Tanpa memberikan kesempatan bagi Langit menanggapinya, Tala sudah langsung mematikan panggilan. Ah. Terbayang sekali bagaimana rempongnya Tala yang belajar mati-matian semalaman, di benak Langit. Kebiasaan ....
Langit juga bersiap untuk membuka buku. Akan tetapi, tangannya tremor habis-habisan. Tunggu. Apa? Kenapa sistem tubuhnya aneh sekali, malam ini? Sangat menjengkelkan ....
Bahu Langit bergetar. Lelaki itu menggertakkan gigi, tampak tak tahan lagi. Sebenarnya, apa yang ia miliki di dunia ini? Kenapa tubuhnya sendiri saja selalu memberontak begini?
Sebenarnya ... milik siapa raganya ini? Langit sudah lelah.

Selama masih bersangkutan dengan 'belajar', Tala tak pernah sekali pun bermain-main. Benar saja. Pagi-pagi sekali, Tala sudah bersiap dengan seragam dan ransel abu di punggung. Dengan langkah mantap, anak perempuan itu berpamitan pada ibunya, lantas menghampiri rumah di seberang jalan.
Burung-burung dan ayam katai milik Pak Haji Amir yang selalu berkokok setiap pagi saja sampai insecure dibuatnya. Tala mendekap buku binder khusus untuk menuliskan poin penting materi, rumus, dan catatan jembatan keledai yang dibuatnya. "Rumus diskriminan, D sama dengan b kuadrat dikurangi empat kali a kali c. Kedudukan garis ... Langit! Mega! Berangkat, yuk!"
Detik demi detik berlalu. Tidak ada sahutan sama sekali. Yang Tala dapati hanyalah tatapan penasaran dari anak-anak SD yang baru pulang mengaji subuh. Satu-dua berbisik menggunjingkan Tala yang memang populer sebagai kakak kelas paling tidak ada adabnya di antara warga sekampung.
Menyadari apa yang bocah-bocah itu pikirkan, Tala langsung melotot galak. "Apa lihat-lihat! Sana, mandi! Sekolah yang rajin, biar pintar kayak Kak Tala." Setelah sekumpulan anak itu berlalu dari hadapannya, Tala kembali menggerutu sembari berkacak pinggang. "Dasar, bocil enggak tahu diri. Dia kira siapa yang suka nemanin pas main kejar-kejaran dulu, ha? Main congklak, bola bekel, Kak Tala yang ajarkan, hei!"
Setelah puas mengeluh, Tala mendengkus, kembali teralihkan pada kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Langit. Padahal di luar sini sudah cukup ribut, deh. Sedang tidak ada orang di rumah, kah? Masa iya?
"Langit!" Tak kunjung ada sahutan. Tala menghela napas kecewa. Sekali lagi, dipandanginya bingkai pintu rumah Langit yang tertutup rapat. Apa Tala berangkat lebih dulu saja?
Akan tetapi ... Langit sudah berjanji padanya, 'kan?

Ya. Hingga penghujung hari, Tala tak menemukan satu pun alasan tepat di balik janji yang tak terpenuhi kala itu.
⇆ㅤ ||◁ㅤ❚❚ㅤ▷||ㅤ ↻
♬ Going back and forth
Lingering on ... ♬
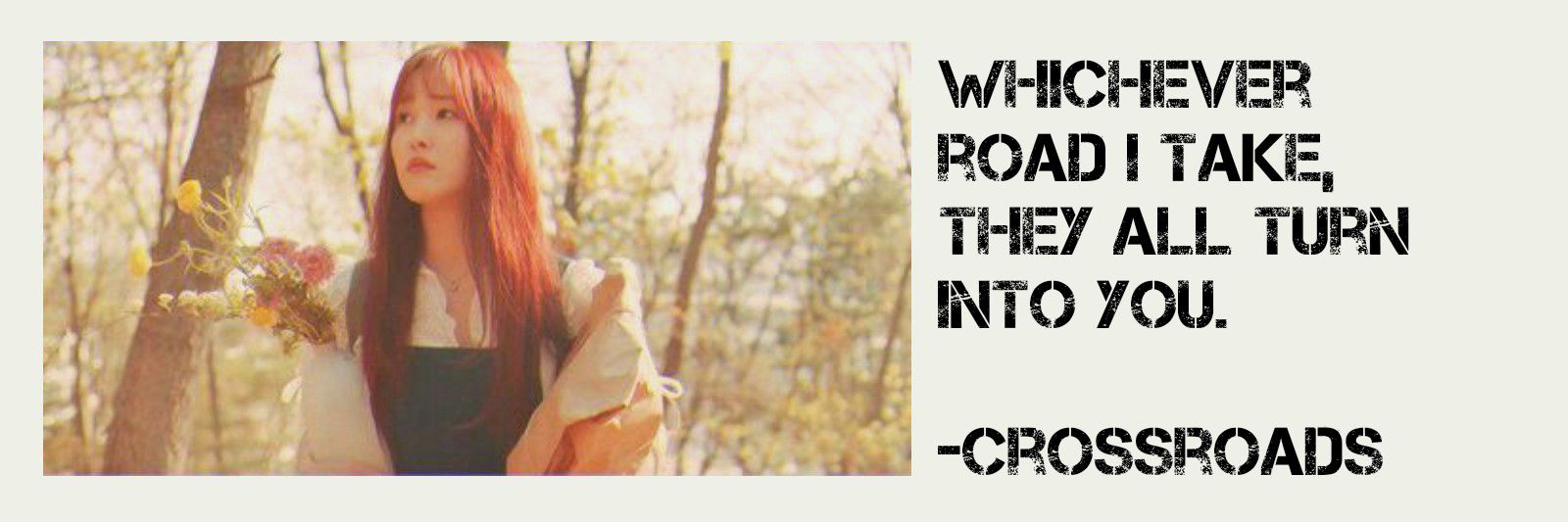
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top