52. Rahasia dan Jawaban
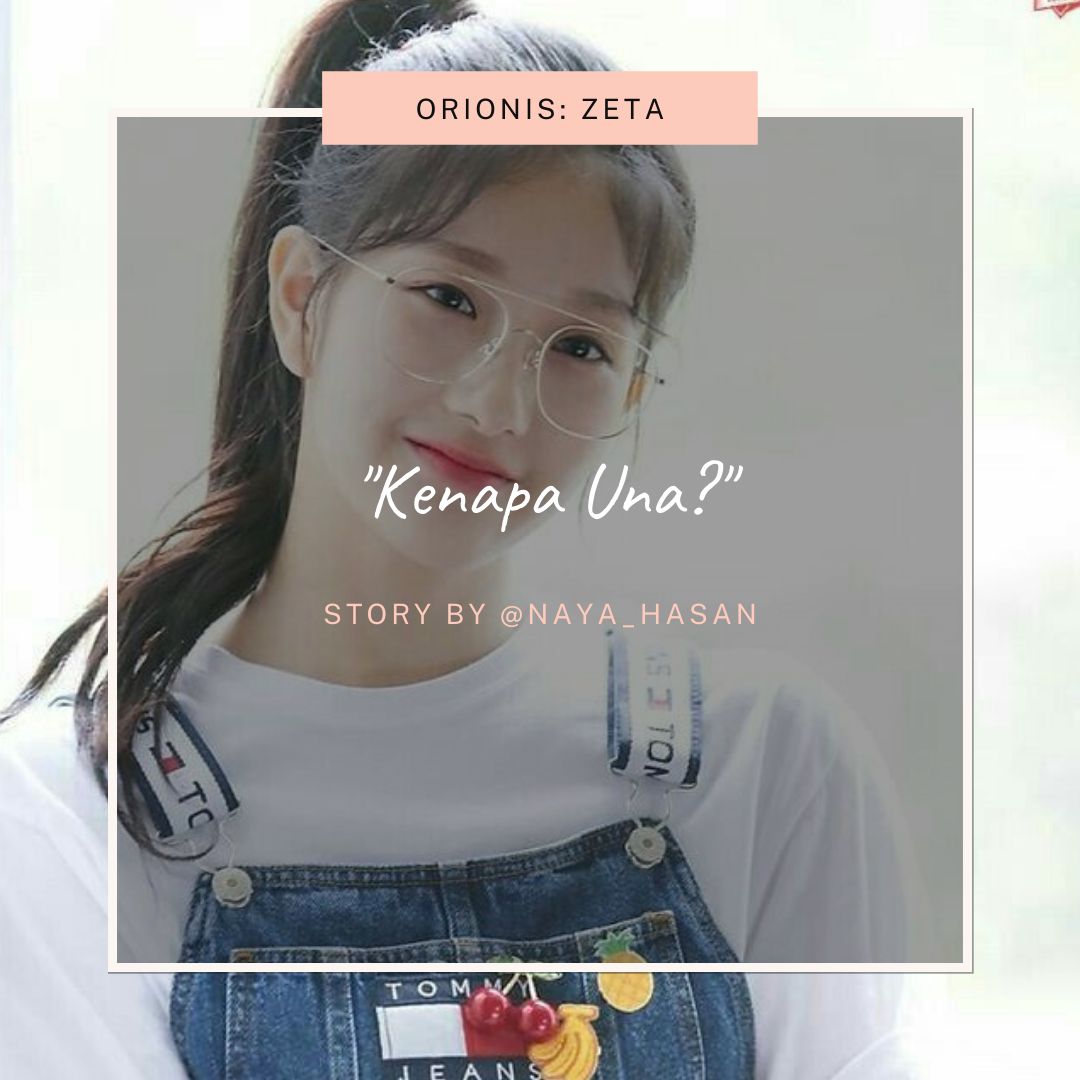
Kangen Anin? *digampar*
Btw ini yang digaris miring itu momen flashback Riam sebelum menemui Aksal, ya. Selamat membaca~
***
Mama telah menceritakan semuanya. Masih di meja makan yang sama, dengan tangan Mama di atas punggung tangannya dan Riam yang menaruh kembali sendok di mangkuknya yang telah kosong. Ia telah menghabiskan sup bikinan Mama.
"Aku siap sekarang."
Ada jeda kira-kira setengah jam sebelumnya. Sejak Mama mengatakan bahwa ia akan menceritakan semua tentang Papa ketika Riam siap. Dan setengah jam itu, sembari menyantap sup panas yang baru matang pelan-pelan, Riam menyiapkan diri.
Mama menatapnya sesaat seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada bantahan. Ia hanya meneguk ludah dan mengangguk tak begitu kentara.
"Kami bertemu di rumah sakit. Waktu itu Mama masih magang dan Papamu kecelakaan motor, lengannya harus dijahit, luka lainnya nggak cukup berat, hanya mengharuskannya menginap dua malam sebelum boleh pulang. Dia minta nomor telpon Mama dan dari situlah awalnya."
Sampai situ, seringaian kecil terbentuk di bibir Riam. Ia melepaskan dengkus pelan, sebelum berkomentar, "Kayak FTV."
Mama terkekeh. "Iya. Iya. Ledek aja sesuka kamu. Toh, itu kenyataannya." Wanita itu tersenyum sebentar sebelum kembali fokus pada ceritanya. "Singkatnya, kami pacaran. Cuma empat bulan sebelum Papa kamu dengan mantap ingin menikahi Mama. Sayangnya, hubungan kami nggak mendapat restu dari orangtua Papa. Seharusnya, Mama tahu, seharusnya saat itu Mama menyerah...
"Tapi Papa nggak bersedia menyerah. Jadi kami menikah, secara diam-diam hanya mengandalkan restu nenek kamu, tanpa kakek kamu tahu. Waktu itu kamu masih di perut Mama waktu kakek kamu tahu dan menyeret Papa pulang. Rupanya, Papa udah dijodohin."
Riam terdiam. Ia ingin tertawa karena cerita yang keluar dari mulut Mama terdengar seperti drama murahan. Tapi ... ia tahu ia juga menjadi salah satu tokoh di dalamnya.
"Kakek kamu nyuruh Papa menceraikan Mama, tapi diam-diam, Papa nggak melakukannya. Sampai umur kamu enam tahun. Papa nggak pernah bilang alasannya, dia pergi begitu aja. Tapi Mama tahu.. Mama tahu kenapa ...."
"Kenapa?"
"Ada beberapa ... dan alasan-alasan itu nggak bisa disalahkan."
Jemari Riam sekarang bergeser sedikit. Cowok itu mencondongkan tubuh lebih dekat pada mamanya, menunjukkan ketertarikan akan kelanjutan kalimat dari wanita itu. Sekaligus, meyakinkan bahwa ... ia di sini, ia mendengarkan dan ia tidak akan menghakimi.
"Kakekmu sakit keras sampai harus dirawat di Singapura. Ingat rumah kita yang lama? Itu adalah apa yang Mama dan Papa kumpulkan selama bertahun-tahun, hanya sebuah rumah sederhana. Mama hanya seorang perawat, Mama nggak bisa bantu apa-apa. Tapi wanita itu ... istri resmi Papa kamu ... dia orang berada, dia membiayai semuanya. Dia jauh lebih berguna daripada Mama. Dia berhasil membantu Kakek kamu bertahan beberapa tahun lebih lama ..."
Rasanya ... ada beban yang memberatkan di udara. Bersanding dengan detak jam dinding ketika mengisi keheningan di ruangan itu.
Mama menghela napas sejenak. Pandangan kosongnya jatuh ke atas meja. Dan ada kesedihan yang kental terpancar dari sorot matanya, dari getar suaranya, dari bagaimana telapak tangannya berkeringat. Riam dapat merasakan semuanya.
"Lalu anaknya, Aksal,sakit, sampai dirawat di rumah sakit. Mama melihat Papa terpukul. Suatu hari dia pergi menemani anak itu, berhari-hari. Ketika dia pulang, dia pulang hanya sekali, untuk membereskan barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal."
Riam masih mengingatnya dengan jelas. Senja itu, ketika Papa pergi menggeret koper dan Riam menangis memohonnya untuk tidak pergi. Dia rindu Papa, dia ingin ikut bersama Papa. Sekarang dia tahu ... Papa lebih merindukan anaknya yang lain.
"Dia nggak pernah kembali setelah itu. Hanya memenuhi janjinya untuk mencukupi segala kebutuhan kamu. Uang itu terkumpul di rekening, begitu banyak kalau kamu ingin mengambilnya."
Riam menggeleng pelan. Persetan dengan uang. Ia justru menatap Mama.
"Kenapa Mama nggak pernah bilang?"
Jeda. Mama menatap jam dinding bisu di sudut ruangan, semangkuk sup yang sudah mendingin, lalu Riam. Pandangannya jatuh pada Riam untuk waktu yang lama.
"Kamu begitu mencintai dan mengagumi Papa. Mama ... nggak ingin merusaknya. Papa adalah panutanmu, motivasi kamu. Mama enggak akan merusaknya hanya demi ego Mama sendiri. Enggak setidaknya sampai kamu cukup dewasa untuk bisa memahami ini."
...
"Jangan benci Papa ...," ucapnya lagi beberapa saat kemudian. "Jika ada di posisinya, semua ornag mungkin akan melakukan hal yang sama. Wanita itu ... jauh lebih baik."
Riam menarik tangannya dari kungkungan tangan sang ibu, sebelum berbalik meletakkannya di atas tangan Mama. Ia meremasnya pelan, menyalurkan hangat.
"Aku nggak setuju."
Karena jauh di lubuk hatinya, Riam tahu, Mama sudah melakukan yang terbaik. Tidak, Mama adalah yang terbaik. Hanya saja, masih sulit bagi lidah kelunya untuk mengatakan itu semua.
Beruntungnya, dering telepon dari ponsel yang tergeletak di atas meja menjadi penengah kesunyian itu. Riam mengintip nama kontak si pemanggil. Pacarnya Mama. Mama meliriknya, tetapi membiarkan benda itu terus bergetar hingga akhirnya berhenti dengan sendirinya.
"Kenapa nggak diangkat?" Riam bertanya.
Mama justru menatapnya. "Apa Om Banu pernah bilang sesuatu ke kamu?"
"Soal?" Riam mengangkat alis.
"Keinginan dia...," terlihat, Mama menggigit bibir selama sesaat sebelum melanjutkan. "... untuk serius. Sebenarnya sudah dari cukup lama."
Ya, pria itu pernah mengatakannya, tidak peduli dengan rentang usia mereka yang terpaut beberapa tahun. Dan beberapa hal lain yang membuat mereka bukanlah pasangan paling ideal di dunia.
Mama masih menatapnya.
"Mama bisa mengerti kalau kamu nggak setuju ... Om Banu itu lebih muda dari Mama, dan masih lajang. Pasti memalukan, ya? Mama tahu kamu sudah menderita selama ini karena Mama. Karena gosip-gosip itu."
"Orang-orang itu ... kita nggak berhutang apapun sama mereka," Riam balas menatap. "Nggak perlu dengerin mereka."
Lidya mengangguk, tersenyum. "Bener. Tapi serius, kalau kamu nggak suka dan sekeberatan itu sama Om Banu... Mama akan lebih memilih kamu. Mama mencintai kamu lebih dari apapun di dunia ini. Jadi klau kamu benar-benar nggak suka dengan kehadirannya, Mama akan meninggalkan dia. Mama serius."
Kalimat itu diucapkan dengan hangat. Dengan mata Mama yang menemukan tatapannya dan tangan mereka yang masih saling genggam. Riam membuang pandang. Harus, atau pelupuk matanya yang terasa panas tidak bisa menahan diri. Ia hanya mengangguk, masih menolak memandang Mama.
"Tadinya nggak suka," ujarnya seraya berdiri, bersiap pergi. Tetapi tidak sebelum ia mengatakan, "Sekarang ... aku hanya ingin Mama bahagia."
***
Bisa kita bicara? Ini penting.
Pesan itu datang lagi semalam, seperti malam-malam sesudahnya. Dan di antara dera lelah yang Riam tidak yakin penyebabnya, ia melakukan hal yang sebelumnya tidak ia lakukan. Kali ini, Riam mengetik balasan.
Oke, kita ketemu besok.
Percakapan singkat itulah yang membawa mereka berdua ke sini sekarang. Riam membiarkan pelayan kafe meletakkan Iced Americano pesanannya di atas meja, dan jus alpukat di seberangnya, tepat di hadapan seseorang yang semalam mengajaknya bertemu.
Dan yang sekarang duduk di depannya adalah temannya Una, Riam ingat pernah melihatnya. Cewek itu memperkenalkan diri sebagai Anin. Selanjutnya, dia juga mengingatkan Riam pasal penolakan cowok itu di lapangan sekolah. Yang akhirnya bisa Riam ingat setelah menggeledah otak.
Sesuai percakapan tadi malam, mereka bertemu di sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari sekolah. Riam yang hari ini masih enggak kembali ke sekolah sekarang mengenakan tshirt abu-abu dengan tulisan kalimat kecil di bagian dada, sementara Anin masih mengenakan seragam sekolahnya siang itu. Begitu pesanan mereka diantar dan sang pelayan pergi, cowok itu tidak menunda untuk menyambung obrolan. Bertanya langsung pada tujuan mereka di sini.
"Jadi, ada apa?"
"Gue juga ... adalah orang yang sama yang menulis surat pernyataan cinta di loker lo. Apel dan Jeruk."
Samar, Riam mengingatnya. Ia membuang surat itu. "Gue nggak tertarik."
Anin mengangguk. "Tahu, kok. Gue ke sini bukan untuk itu."
"Lalu?"
"Maaf kalau waktunya kurang tepat. Gue tahu lo masih berkabung. Tapi gue pikir ... gue juga nggak bisa menunggu. Gue ingin semuanya jelas ... Gue punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan."
"Soal?"
"Soal kita."
Riam menaikkan alis. "Ada apa dengan kita?"
Ada kegugupan pada cewek di depannya yang bisa Riam baca dengan mudah. Dari caranya meremas tangan, atau pandangannya yang liar menatap sekitar saat mencoba bicara.
"Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan terdengar aneh. Tapi gue memerlukannya. Agar merasa lebih baik."
Riam masih menatapnya datar. "Ngomong aja."
"Kenapa lo mau pacaran sama Una? Gue tahu lo nggak mungkin pacaran hanya karena dia mengejar lo. Ada banyak orang yang mengejar lo. Tapi kenapa Una?"
"Kenapa enggak? Gue udah tahu rencana kalian sejak awal. Atau seenggaknya, gue menebak-nebak. Dan gue pikir... hal itu nggak akan merugikan gue. Dia mungkin punya motif sendiri mendekati gue, dan gue ... melakukan hal yang sama. Gue hanya penasaran. Sampai hal-hal yang nggak gue duga terjadi..."
"Seperti?"
Seperti jatuh cinta.
Tetapi, Riam tidak menyuarakannya. Ia hanya menatap embun di gelas Americano dinginnya, tanpa menyentuh.
"Lo suka sama Una?"
Pertanyaan itu menyentak Riam kembali. Ia mengangkat pandang, memertemukan matanya dengan Anin yang tengah menatapnya serius.
Lalu, seperti mendesak, cewek itu mengulang pertanyaan.
"Lo ... jatuh cinta, sama sahabat gue, Una?"
Tidak ada jawaban. Anin meraih gelas Americano Riam, menyandingkan dengan gelas jus alpukat miliknya. Tidak apel dan jeruk kali ini.
"Jus ini untuk yes, Americano untuk no."
Masih tidak ada jawaban. Hingga Anin harus menatap ke dalam mata Riam dalam-dalam.
"Yes .... or no? Ini penting."
Ketika Riam pada akhirnya meraih gelas alpukat itu, Anin tersenyum. Ia tidak tampak terkejut. Ia tersenyum, kemudian terkekeh, dan cepat-cepat menyeka airmata di sudut mata.
"Melegakan."
Sebentar ... melegakan? Kerutan di kening Riam telah mewakili pertanyaan itu. Sehingga Anin, dengan senyum kecil di bibirnya, menjelaskan.
"Ternyata, ini adalah jawaban yang selama ini gue inginkan. Gue terus bertanya-tanya, kenapa gue nggak bisa move on. Gue juga pengin move on dan berhenti berharap pada orang yang nggak memiliki perasaan yang sama. Sekarang gue tahu jawabannya."
...
"Gue ... pengin lo berakhir sama orang yang baik. Yang sayang sama lo dengan tulus. Dan gue berharap hal yang sama terjadi pada sahabat gue, Una. Sekarang, gue udah tahu jawabannya ... secara aneh gue udah move on. Begitu aja."
Riam masih menatapnya, melihat kelegaan yang ditunjukkan cewek itu.
"Gue nggak mau jadi penghalang di antara kalian."
"You're not."
"Terus, kenapa lo nggak balikan sama Una?"
"Gue ...," Riam terdiam. Ada banyak alasan, sebenarnya. Seperti, ia baru saja kehilangan Mitha. Seperti, ia baru saja kehilangan sosok Papa yang menjadi panutannya. Seperti, kesadaran bahwa ia telah membenci Mama tanpa alasan, atau Aksal meski anak itu tidak bersalah. Tetapi di atas semuanya, ada alasan besar yang membuat jemarinya berhenti dari mengusap tombol panggil di samping nama Una di ponselnya. Atau mencegahnya berlari menghampiri cewek itu dan memeluknya tiap mereka berpapasan di koridor. Atau yang membuat jemarinya menghapus kembali ungkapan kerinduan yang ia tulis hampir setiap malam, menjadikannya pesan-pesan tak terkirim.
"Gue ... nggak tahu caranya."
***
Apakah kamu melihat hilal balikan? Apakah kamu melihatnya? DImana?
Masih benci Anin?
Hehe, ada lagi yang mau disampaikan?
Besok update NAVY, yay! Udah dimasukin library belum? Kalo belum, ayo! Cek aja di work aku. Di sana, kamu bisa ketemu Aksal, adik seayahnya Riam dan temen-temennya. Di sana, aku juga bakal bikin fiksi remaja yang ringan kayak arum manis.
Jangan lupa juga mampir baca Saga oleh okkyarista
Dan follow Instagram aku, hehe @specialnay.Dah gitu aja. Sampai jumpa lagi dengan hati yang lebih ringan dan badai yang telah berlalu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top