28| I Admitted to Myself
Shin Runa to Jeon K. Kalinsky;
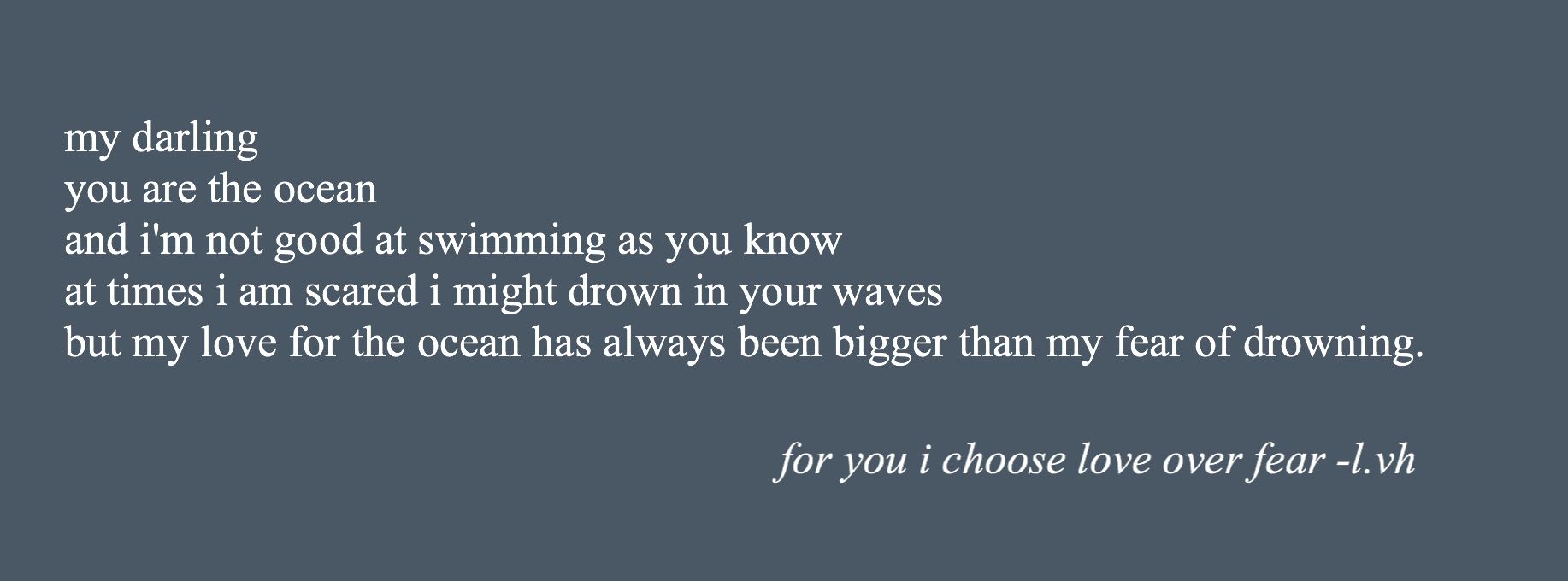
"Aku suka yang satu ini."
Aku mengangkat tangan kiriku ke udara dan memperhatikan lamat-lamat model cincin yang tersangkut di jari manisku.
Taejoon ikut tersenyum semringah. Dia telah bekerja keras membantuku mencari model cincin sejak setengah jam lalu. "Ada beberapa desain lainnya. Jika kau mau kau bisa mencobanya satu persatu."
"Sepertinya aku akan mengambil yang ini." Cincinya terbuat dari platinum dengan pilinan bunga melingkar berhiaskan safir biru. Aku mengambil ponsel dan memotret jariku, lalu mengirim hasilnya pada Danna.
Kau suka?|
Danna membalas tanpa membuatku menunggu.
|Suka. Belikan satu.
Sengaja kupilih untukmu|
|Bagus. Tapi jangan warna itu. Ganti permatanya dengan ungu.
Oke|
Aku melepas cincinnya dan mengembalikan pada Taejoon. "Aku pilih yang itu."
"Ada beberapa pilihan warna, tapi mungkin kau harus menunggu beberapa hari untuk menyesuaikan bentuknya."
Aku menggeleng. "Aku ambil yang itu saja." Masa bodohlah dengan ungu.
Taejoon memasukkan kembali perhiasannya ke kotak penyimpanan.
Sambil terus memperhatikannya, kusangga sebagian pipiku. "Han Taejoon-ssi, boleh aku bertanya padamu beberapa hal?"
Senyum simpul merekah di wajah Taejoon. "Tanyakan saja jika aku bisa menjawabnya."
"Apa semua pria dekat dengan kebohongan? Atau mungkin kau pernah dengar idiom men who lie and the women who suffer?"
"Pria yang berbohong dan wanita yang menderita." Dengan cepat dia menerjamahkan kalimatku tadi.
Aku memuji kagum. "Oooh, Han Taejoon-ssi, kau cakap dalam bahasa Inggris."
Taejoon hanya tersenyum manis menunjukkan lesung pipinya. "Tidak semua laki-laki dekat dengan kebohongan, hanya saja mereka memang pernah berbohong," ujarnya. "Dan bukan hanya sekali," selorohnya.
Aku mengerutkan kening sembari meringis. "Apa pria lebih banyak berbohong ketimbang wanita?"
Taejoon merenung sebentar. "Entahlah. Mungkin saja. Banyak pria terbiasa 'sedikit' berbohong terutama ketika menjalin hubungan."
"Seperti?"
"Kau pernah dengar nama penulis Caldwell?"
"Taylor Caldwell?" tanyaku menyebutkan salah satu penulis Amerika.
Taejoon menggeleng. "Novelist Amerika, Erskine Preston Caldwell. Dalam salah satu bukunya* dia pernah menjelaskan pria bisa berbohong banyak dalam pendidikan, latar belakang militer, status perkawinan, pekerjaan, atau bahkan seperti sanjungan kecil untuk pasangan ketika dia malas mengatakannya. Dan juga satu kebohongan lainnya ketika pria ditanya bagaimana kepribadiannya. Untuk yang satu itu pria tidak sepenuhnya berbohong, karena biasanya pria sulit mengartikan secara mendalam siapa dirinya dan bagaimana karakternya."
(*buku Men and Women)
"Benarkah? Bagaimana bisa?"
"Umumnya para pria memiliki sistem limbik* yang lebih kecil dari wanita, membuat kami lebih sulit memahami emosi dan selalu mengedepankan pikiran rasional daripada mengandalkan perasaan. Sehingga terkadang, kami hanya mengerti sifat umum laki-laki."
(sistem limbik : bagian otak yang berhubungan dengan
emosi, perilaku, kenangan, dan gairah)
Aku berusaha memadatkan semua informasi itu dalam kepalaku. "Jadi bagaimana kau melihat pria yang bersikap tulus namun berbohong?"
"Menurutmu seperti apa mereka di matamu?" tanyanya balik.
"Pria baik yang jahat?" Aku mengangkat alisku.
"Pria baik yang jahat, aku suka penyebutan itu."
"Atau pria baik yang jahat tapi merasa tersakiti."
Taejoon tidak membalas perkataanku melainkan tertawa sambil menggeleng-geleng seperti sedang menanggapi sosok gadis kecil cerewet yang mengganggunya ketika bekerja.
"Pria seperti itu pasti ada disekitarku," gumamku tidak bermaksud mengatakannya pada Taejoon.
Ketika tawa Taejoon surut, dan ketika kami sama-sama terdiam, Taejoon membuka mulut seperti hendak mengatakan sesuatu yang penting. Tetapi sedetik kemudian dia mengurungkan niatnya.
Sebagai gantinya dia bekata, "Aku akan mengemas pesananmu."
Aku mengamati punggungnya yang meninggalkanku. Sejauh ini aku bisa melihat kebiasaan-kebiasaan kecil Han Taejoon yang terasa lucu. Misalnya, ketika dia mendadak kikuk di depanku atau memandangku dengan tatapan yang seolah mempelajariku.
Dan ada sesuatu dalam senyumnya yang membuatku selalu merasa nyaman.
Pesan dari Jaemin muncul saat aku sedang menunggu;
Aku baru keluar kelas. Siang ini aku tak punya jadwal. Noona pasti rindu setengah mati kan? Hehe. Jangan rindu dong, nanti aku malu.
Usai membaca pesannya, aku segera menekan panggilan telepon.
Sebelum Jaemin bicara aku buru-buru menyela, "Datanglah ke kantorku. Ada sesuatu yang ingin kuberikan."
[Oke. Kurang dari dua puluh menit aku pasti sampai]
"Dan Jaemin," panggilku sesaat, lalu menghembuskan napas, "bisa kau pulang ke rumah sebentar?"
[Untuk apa?]
Aku sempat terdiam lalu berdeham. "Aku lupa membawa hasil pemeriksaan medis waktu itu. Dokumennya ada di lemariku. Kau pasti ingat."
Jaemin tidak segera menjawab, aku tahu dia sedang berpikir keras mengapa tiba-tiba aku menginginkan laporan medis yang sudah kusimpan sangat lama. Yang kusembunyikan rapat-rapat delapan tahun lalu.
[Kenapa mendadak memintanya?] Seperti dugaanku, suara Jaemin agak berbeda dari sebelumnya.
"Hanya ingin memeriksa ulang."
Jaemin tidak bersuara.
"Kau dengar permintaanku tadi? Bawakan itu segera."
[Noona... baik-baik saja?] tanya Jaemin pelan dan kurang yakin.
Aku kembali berdeham gelagapan. "Ya, aku aman." Aku membuat suaraku terdengar mantap, tetapi aku baru saja merasa tenggorokanku kering dan bergetar. "Bawakan saja dokumennya. Aku tidak menerima protes."
Secara sepihak kuakhiri sambungan kami. Aku menarik napas sangat panjang untuk meredakan kegelisahan serta rasa mual yang datang sekejap.
Kemudian menunggu sebentar sampai Taejoon selesai mengemas pesananku.
"Kau ingin membayarnya tunai atau..."
"Debit," aku buru-buru mengeluarkan kartu pembayaran dan memberikannya pada Taejoon. "Aku harus pergi sekarang," kataku setelah menyelesaikan transaksi.
Taejoon mengangguk mempersilakan.
Setengah perjalanan manjauh, rasa sakit melanda perutku. Sakit. Perih. Napasku sempat berhenti. Lalu sakit itu mereda hanya dalam hitungan detik. Dan aku kembali melangkah masih menanggung sedikit rasa tak nyaman dalam perutku.
Di depanku, seorang pria berjas baru saja masuk dengan langkah lebar. Ketika mata kami bersitatap pria itu menyunggingkan senyum aneh yang terlihat mengerikan pada pertemuan pertama.
Aku berkedip, lalu cepat-cepat menyasarkan pandanganku ke pintu. Meskipun begitu aku masih bisa merasakan tatapan pria itu seakan mendorong paksa punggungku keluar.
***
"Chakkanim*." Asistenku mengetuk pintu dan membukanya perlahan sewaktu aku duduk di ruangan sambil merenung.
(*Author/penulis)
Aku sedikit tersentak lantaran sejak pagi otakku sangat sibuk memikirkan semua tentang Jeon. Apakah Jeon ada kantornya? Apakah dia bekerja seperti biasanya? Siapa orang yang dia temui hari ini? Atau siapa yang bertukar pesannya saat dia tidak ada di rumah?
Tak pelak ketegangan kami pagi ini membuatku menjadi gelisah dan murung.
"Aku mengganggumu, Chakkanim?" Asistenku menyembulkan kepala dari celah pintu.
Aku menggeleng dan tertawa merajuk. "Eonni! Kan sudah kubilang jangan panggil aku begitu."
"Memangnya kau tidak suka kalau kupanggil penulis? Itu kan profesimu." Dia ikut tertawa, kemudian duduk di sofa kecil yang dulu sering menjadi tempat tidurku jika tidak pulang ke rumah.
Wanita itu telah membantuku selama satu tahun terakhir menggantikan asisten sebelumnya. Sutradara Bong yang memperkenalkannya padaku saat makan malam sebelum menjalin kerja sama. Alasan lainnya, karena asistenku saat ini adalah keponakan sutradara Bong.
Sekarang aku tahu asistenku sudah harus pergi seperti asisten sebelumnya. Dan meskipun hanya bertemu dua atau tiga kali dalam seminggu, aku begitu menyayangi wanita yang lebih tua empat tahun dariku ini seperti kakak kandung.
Aku membiarkannya memandang berkeliling ruangan. Padahal semuanya tidak berubah sejak dia datang. Jujur saja, aku kurang tertarik pada kegiatan ornamental. Melelahkan. Jadi kubiarkan apa adanya dengan catatan membersihkannya setiap Selasa dan Sabtu. Lagi pula sejak menikah aku jarang sekali ada di kantor mungilku. Dulu, aku bahkan hampir tidak keluar selama sepekan.
"Eonni benar-benar harus pergi sekarang, ya?" tanyaku memastikan dengan harapan dia berkata tidak walau mustahil.
Dia mengangguk dan menunjukkan ekspresi yang berusaha membujukku bersemangat.
"Aku bahkan belum mencari asisten pengganti," keluhku. "Bagaimana ini?"
"Maafkan aku," katanya dengan raut menyesal. Ia mengelus perutnya. Aku melihat caranya mengusap perut yang nyaris sebesar bola basket. "Suamiku ingin aku berhenti bekerja."
"Baiklah," kataku muram. "Kalau keputusannya sudah bulat, aku bisa apa."
Masih segar diingatan, bahwa suaminya adalah koreografer tari di salah satu agensi besar Korea. Atas dasar permintaan sang suami, asistenku membuat keputusan ini satu bulan sebelumnya.
"Sepertinya suami Eonni sangat sayang padamu dan memperhatikan segala kondisimu."
Dia menggeleng diiringi senyum tipis. "Dia masih cukup sibuk. Katanya ada grup yang akan comeback dan dia bekerja keras dari pagi hingga malam di studio. Tapi dua bulan sebelum persalinanku dia berencana mengambil cuti panjang."
"Pasti dia bahagia sekali saat tahu Eonni hamil." Entah mengapa harus kalimat itu yang keluar dari mulutku.
"Itulah masalahnya. Aku menyesal tidak merekam ekspresinya. Dia memelukku hampir sepanjang hari dan mengeluh karena kelahirannya masih lama. Suamimu mungkin akan melakukannya juga."
Suamiku tidak begitu. Aku iri.
Aku juga ingin Jeon melakukan itu padaku. Tetapi aku hanya berusaha membayangkan Jeon yang seperti itu. Jeon yang tiba-tiba menerjangku dengan pelukan dan memberi ucapan selamat dengan wajah berseri-seri.
Namun tidak bisa. Terlalu sulit. Pada akhirnya semua ilusiku hanya seperti gambaran delusif cacat.
"Apa semua pria akan reaktif seperti suamimu saat tahu istri mereka hamil?" tanyaku dengan perasaan takut yang entah dari mana asalnya.
Asistenku memikirkan jawabannya sebentar. "Temanku tidak bereaksi saat tahu istrinya hamil. Dia bilang rasanya seperti ada campuran berbagai emosi jadi dia hanya bisa terdiam."
Aku menghela napas panjang. Penjelasan itu sudah cukup membuatku tenang.
Mungkin... mungkin saja Jeon sebetulnya amat bahagia sampai tidak sanggup menunjukkan reaksinya.
Beberapa saat berlalu asistenku telah meninggalkan studio, sementara aku masih menunggu kedatangan Jaemin.
Ponselku berdenting tanda pesan masuk. Pesan dari nomor yang tidak kukenal.
Si pengirim melampirkan dua foto Jaemin. Dilihat dari pakaian yang dikenakan Jaemin, aku bisa menyimpulkan kedua foto itu diambil di hari yang berbeda. Anehnya semua foto itu tampak dibidik diam-diam dari jarak aman.
Dengan pikiran positif aku bermaksud mengirim pesan balasan. Siapa tahu saja teman Jaemin salah mengirimnya. Tetapi satu foto baru Jaemin muncul disusul sebaris keterangan; Foto hari ini.
Apa maksudnya?
Aku membalasnya. [Siapa ini?]
Tidak ada balasan dalam waktu lama. Pikiran positifku goyah dan berubah menjadi keraguan. Aku mencoba menghubungi nomornya. Secara ganjil nomor itu mendadak tak aktif.
Kucermati ulang isi pesannya sampai sebuah panggilan masuk mengejutkanku. Aku menarik napas terkesirap dan memegang dadaku saat membaca nama Jaemin di layar.
"Noona aku datang!" seruan keras Jaemin terdengar dari arah pintu.
Dengan langkah terburu-buru aku mendatangi pintu. Jaemin kembali membuatku naik pitam.
"Noona di dalam? Kenapa kode pintunya diganti? Belnya tidak mau bunyi."
Begitu membuka pintu hal yang pertama kulakukan adalah memukul kuat-kuat otot lengannya.
Jaemin berusaha menghindari pukulan kedua dan ketiga tapi gagal. "Kenapa?" Jaemin mengusap lengannya terkejut. "Kenapa aku dipukul? Padahal kubawakan Noona cheesecake."
"Kau berulah lagi, kan?"
"Seminggu ini aku bahkan tidak ke mana-mana selain kuliah," amuknya.
"Lihat ini!" Aku menunjukkan ponselku tak kalah garang. "Ada orang yang baru mengirim ini padaku! Kau pasti membuat orang lain kesal, kan?"
Jaemin melongo tidak percaya. "Jadi karena ini Noona memukulku." Dia menghembuskan napas dari mulutnya. "Abaikan saja. Bisa jadi itu salah satu penggemar isengku."
"Kau yakin tidak dalam masalah?"
Dia mengangkat dua jarinya membetuk huruf V di samping kepala. "Jika aku berbohong, aku akan kerasukan arwah lagi," lalu ia menggeleng-geleng, "Tidak, tidak. Kalau aku bohong aku tidak akan mengganggu Noona dan kakak ipar sampai lulus. Sampai aku jadi pengusaha, sampai aku memiliki rumah dan bisnisku sendiri. Sekarang ayo masuk. Makan kue bersama."
Aku menghembuskan napas dan menatap wajahnya sekedar meyakinkan diri.
"Aku bersumpah aku sedang bebas dari masalah," tegasnya.
"Baiklah. Kali ini aku percaya, tapi jika...."
"Jika aku melakukan kesalahan, aku bersedia telanjang di depan kampusku. Demi Noona. Demi Shin Runa noona."
Tanpa mengindahkan tatapanku, Jaemin masuk lebih dulu.
Aku mengiringi langkahnya dari belakang. "Kuenya untukmu saja. Aku mau muntah mencium bau keju."
"Ada apa? Aku beli di toko kue biasanya."
"Aku sedang mual makan keju." Aku pun baru menyadari setelah mencium aroma pembakaran keju di etalase kafe di seberang kantorku saat aku membeli teh tadi.
"Kenapa? Noona sakit?"
Dengan malu-malu aku menggigit ujung jempolku. "Aku hamil," bisikku.
"Hah?"
"Aku hamil," ujarku lebih tegas.
"Hamil?" Jaemin memekik. Matanya membelo. "Hamil? Noona hamil? Sungguh? Benarkah? Bayi sungguhan? Noona hamil? Di dalam perutmu sekarang ada bayi? Aku bakal punya keponakan?" tanyanya berlipat ganda sambil menunjuk perutku.
Aku melipat bibir dan mengangguk tersipu.
"Bayinya laki-laki atau perempuan?"
"Usia kandungannya masih terlalu dini."
"Ah padahal aku tidak sabar bayinya keluar. Tapi selamat ya Noona. Nanti aku akan membelikanmu hadiah atau bila perlu aku sendiri yang akan merancang studiomu ini sebagai hadiah." Jaemin menunjukkan gembira kemudian ngeluarkan sesuatu dari ranselnya. "Ini hasil permeriksaan yang Noona minta."
Jaemin menyodorkan dokumen itu padaku. Sebelum aku menggapai mapnya, ia menarik kembali lengannya. "Tapi aku harus memastikan dulu kalau Noona baik-baik saja."
"Hidupku sudah bahagia. Berikan itu padaku."
Jaemin menyelidiki wajahku dan memberikannya setengah yakin. "Noona tahu hal itu cuma masa lalu kan. Jangan terlalu banyak mencemaskan apa pun."
Dengan suara kecil aku menjawab, "Aku tahu."
"Kau sudah berjuang sejauh ini untuk tetap hidup. Jangan kembali seperti dulu. Jangan menjadi Shin Runa yang dulu." Tutur kata Jaemin terdengar seperti peringatan telak.
Aku menghela dan mengangguk. "Aku janji." Kemudian aku menarik napas dan mengambil undangan untuknya dari balik meja kerjaku. "Kuberikan satu kursi premier untukmu."
Jaemin hanya mematung di tempat, menatap undanganku tanpa melakukan sesuatu. Lalu ia menggaruk pelipisnya. "Begini. Sebetulnya..." mimiknya dibungkus kebimbangan, "Aku tidak tahu harus cerita dari mana. Tapi aku sudah punya satu tiket filmmu."
"Se Jin Ah?"
"Bagaimana Noona tahu?" Jaemin tercengang.
"Memangnya siapa lagi yang akan memberikan tiket perdana padamu?"
"Tolong jangan salah paham. Rabu itu aku datang ke lokasi yang Noona katakan. Awalnya dia memang mengabaikanku. Tapi beberapa hari kemudian gadis itu terus-terusan menghubungiku dan mengungkit-ungkit masalah itu seolah aku harus selalu minta maaf dan menyetor wajahku di lokasi syuting setiap hari."
"Hanya sebatas itu?" Aku melipat tanganku. Kepalaku meneleng beberapa derajat, mengintimidasi.
"Sebenarnya..." Jaemin menggaruk belakang telinganya dengan gelisah. "Kami pernah menghabiskan malam bersama."
Aku tercengang. "Hah?!"
"Bukan malam yang itu!" Jaemin gelagapan. "Cuma duduk di taman. Dia yang membuatku begini. Dia menghubungiku seperti tak kenal waktu."
"Jadi kau suka Jin Ah?"
"Suka. Bukan! Maksudku, saat bersamaku dia seperti gadis biasa yang butuh perlindungan. Aku lumayan suka menjadi pendengarnya. Jin Ah terlalu banyak memendam semua sendirian. Jadi aku ada untuk mendengarkan kisah hidupnya. Hanya sebatas itu."
Aku memejamkan mata kemudian menarik napas relaks. "Terserahlah. Noona tidak akan ikut campur urusan pribadimu. Tapi ada risiko jika kau jatuh hati padanya."
"Aku tahu. Sekarang balikkan badan Noona."
Apa lagi yang mau dia perbuat?
Aku menurutinya begitu saja.
Tiba-tiba Jaemin memelukku dari belakang. Dari posisi tanpa jarak ini, aku bisa langsung mengetahui perbedaan postur badan kami. Jaemin tumbuh tinggi menyerupai ayahku. Tentunya sedikit lebih tinggi dari Jeon.
"Jangan sakit," bisiknya di pundakku. Seketika itu aku merasa lebih tenang. "Jangan sakit lagi."
Belum sempat kuberikan Jaemin respons, dia menarik diri dariku dan lari membuka pintu. Aku melihat pintu yang menutup perlahan.
Tingkah konyolnya membuatku tertawa lepas. "Jaemin-ah! Kau bisa memeluk Noona dari depan."
"Aku pulang!" teriaknya dari kejauhan.
Aku menyibak tirai jendela, dan tersenyum saat melihatnya berlari turun ke jalan hingga ia hilang dari pandangan.
Langit di luar sudah agak gelap. Hari ini aku memutuskan pulang terlambat.
Tiga puluh menit kemudian aku kembali duduk tanpa melakukan apa-apa selain memandangi bingkai foto pernikahanku di samping komputer. Terkadang foto itu memberikan aspirasi jika mulai kehilangan ide menulis. Dari cara Jeon menatap dan tersenyum padaku seolah menunjukkan akulah satu-satunya wanita penting dalam dunianya. Membuatku sontak menertawakan ketololanku.
Jeon sungguh sangat profesional dalam segala hal. Profesional dalam pekerjaan, dan profesional dalam menyembunyikan perasaan. Dan sekarang foto ini sedang tak berdampak apa-apa.
Setelah cukup lama kutarik napas dalam-dalam, kemudian meraih figura itu dan membuangnya ke laci sebelum beranjak pulang.
Semuanya mulai masuk akal bagiku. Kenapa Jeon menikahiku, kenapa Jeon mau bersanding denganku. Jeon melakukannya hanya karena takut sendirian.
Seperti yang pernah dia katakan, dia ingin memiliki keluarganya sendiri. Maka aku hanyalah alasan baginya agar dia tidak sendirian. Agar dia memiliki keluarga kecilnya. Aku hanyalah orang yang menjaganya dari rasa sepi.
Nilaiku di matanya tidak lebih dari cintanya pada Go Ae Jin.
Kuakui kenyataan itu pada diriku sendiri.
***
Aku mengunci pintu studio dan ketika berbalik sosok Jeon yang berdiri ditempa sinar malam mengejutkanku. Tangannya memegang sebuket bunga. Ia tersenyum mengamatiku selagi aku mendekat.

Wajah Jeon malam ini tampak segar dan bersih berbeda dari yang kuingat pagi ini. "Siang tadi aku mencoba menghubungimu dan mengirim beberapa pesan. Aku khawatir kau tidak membaca lokasi restoran yang kukirim."
"Aku membacanya." Aku membaca semua pesannya, pesan makan siang, dan pesan lainnya. Namun aku mengabaikan semua itu.
"Kau sibuk seharian ini?" tanyanya.
Aku menggeleng. Dadaku sesak. Terlalu tidak sanggup menatap wajahnya. "Aku memang tidak berniat datang. Badanku letih. Makan di rumah saja."
Jeon tidak menjawab dan dia mendesah dengan ekspresi pasrah. Dari sikapnya tadi artinya Jeon benar-benar paham aku marah.
Aku memang masih sangat marah padanya. Sejak kemarin hatiku meradang. Seandainya saja semua bukan sebuah kebohongan.
"Kalau begitu sebaiknya kita pesan makanan sebelum pulang," usulnya dengan nada lembut.
"Tidak," kataku dingin. "Aku yang akan memasak. Apakah bunga itu untukku?"
Jeon berdeham mengendurkan kekalutan di wajahnya. Dia menarik napas dengan suara berat dan senyumnya merekah saat menyerahkan bunganya padaku. "Untuk calon ibu dan calon bayi kita."
Aku menerima bunga itu dan berseru, "Ah, sayang sekali. Aku tidak suka bunga peony tapi terima kasih."
Aku masuk ke mobilnya lebih dulu dan meletakkan buket itu di kursi belakang. Aku serius tidak menyukai peony. Seandainya saja semua bukan kebohongan, andai saja Go Ae Jin tak tinggal di hatinya, maka senyum Jeon saja sudah cukup segalanya bagiku dibanding setangkai bunga.
Jeon sudah duduk belakang kemudi. Dia menarik sabuk kursinya, lalu tiba-tiba kusadari pergerakannya terhenti. Ia menghela napas dan membiarkan sabuknya ditelan kembali oleh mesin kursi.
Pandanganku teralih ke jendela. Selama beberapa menit ke depan kami terus berdiam diri satu sama lain.
"Aku akan menjelaskan semuanya padamu malam ini," ucapnya memulai.
Aku berusaha menjaga pikiranku tetap jernih meskipun kini kedua pundakku terasa lemas.
"Pernikahan itu sulit, kan?" tanyaku tidak ingin kehilangan keberanian.
Di jendela napasku tampak seperti uap putih. Tanganku gemetar dan bukan karena kedinginan. Aku cemas. Dulu aku sering mengalami kecemasan yang lebih parah dari kecemasan pada umumnya.
Aku tersenyum sedih sebentar. Saat ini terlalu banyak yang muncul di kepalaku tentang Jeon sehingga aku tak tahu apa yang harusnya kusampaikan.
"Kejadian pagi ini bukan sesuatu yang besar bagiku." Aku mencoba menguatkan diri dan mengatakannya dengan lancar. "Bagaimanapun aku bersyukur masih memilikimu dan akan sulit melepaskanmu yang sudah begitu baik padaku." Aku menarik napas dengan mulut terbuka lalu menoleh padanya.
"Karena ketika aku sudah memiliki sesuatu yang baik, aku tidak harus pergi mencari sesuatu yang lebih baik. Begitulah aku hidup."
Jantungku berdebar di luar kendali ketika Jeon berhati-hati mengamatiku. Ada kesengsaraan yang terkubur di bawah tatapannya.
"Aku hanya tidak mau pernikahanku gagal. Aku tidak mau pernikahanku berakhir seperti pernikahan kalian. Jadi mohon bekerja samalah untuk tidak menyakitiku lebih jauh dari ini." Aku membalas tatapan Jeon lurus-lurus. Belum pernah aku setakut ini menatapnya. "Kumohon hargai apa yang kaumiliki saat ini, Jeon. Karena aku juga sedang belajar menghargai apa yang kupunya sekarang. Dan malam ini aku ingin kau tahu, bahwa aku masih mencintaimu. Masih."
Jeon berkedip dan segera mengangguk. "Aku berjanji. Aku tidak akan meninggalkan maupun melepaskanmu asal kau memberiku waktu sedikit lebih lama."
Namun sayang sekali ucapannya belum bisa meringakan kengerianku. Karena aku hampir saja kehilangan harapan pada pria ini.
"Aku mencintaimu, Runa. Aku akan belajar mencintaimu secara penuh."
Jeon menjangkau belakang leherku dan mendekatkan kepalanya padaku. Dia mencium ubun-ubunku sangat lama sebelum akhirnya aku mendorong pelan bahunya. "Sudahlah. Aku mau istirahat. Bangunkan kalau sudah sampai rumah."
***
Aku berhati-hati membawa sup bulgogi ke sunroom yang letaknya terpisah dari rumah utama. Biasanya aku berada di sini saat mengalami kesulitan tidur atau saat aku jenuh apabila Jeon tak ada di rumah.
Sebelum aku menikah dengannya, Jeon bilang sering menghabiskan waktu di sunroom sekedar bersantai atau membaca. Sekarang dia menyerahkan kuasa tempat ini untukku seorang.
Di tempat ini terdapat satu sofabed , kursi baca, meja panjang dengan beberapa kursi kayu, seperangkat meja kerja, dan yang paling membuatku terkesima adalah rak buku, terbuat dari kayu bubinga* putih. Tingginya sekitar empat kali tinggi badanku. Menjulang dan membutuhkan tangga mengambil salah satu buku di rak teratas.
(*kayu dari benua Afrika)
Tetapi aku tak pernah ingin mengambil semua buku yang diletakkan paling tinggi. Sebab itu semua adalah milik Jeon. Buku-buku lama yang kemungkinan takkan dia baca ulang.
Aku meletakkan dolsot* bergabung dengan nasi dan makgeolli* di ketel yang sudah dibawa Jeon sebelumnya. Ibuku selalu mengelukan makan bulgogi ditemani makgeolli akan terasa jauh lebih nikmat.
(*mangkuk batu)
(*arak putih susu dari beras)
Sekarang Jeon kembali masuk ke rumah dan kembali membawa lilin dekoratif.
"Kau mau menyalakan lilin?" Suaraku tidak sedingin beberapa jam lalu. Saat mandi aku telah memikirkannya. Aku sadar tidak ada gunanya memperlakukan Jeon dengan ketus.
"Sebagai hiasan," katanya, lalu menyalakan lilinnya dan menempatkan di meja. Lilinnya meniupkan wangi karamel.
Aku menuangkan sup bulgogi ke mangkuk kosong Jeon dan setelahnya kami makan dengan tenang.
Ketika akan menuang makgeolli ke gelasku, Jeon buru-buru menjauhkan ketelnya. "Ibu hamil dilarang minum alkohol."
"Sedikit saja," rayuku memelas.
Jeon menggeleng kukuh. "Tetap saja ada alkoholnya."
"Tapi kandungan alkohol makgeolli tidak sebesar soju. Biarkan aku minum satu gelas."
"No."
Sebagai gantinya Jeon menuangkan air putih ke gelasku.
"Sedikit," kataku belum menyerah. "Sedikit saja. Dua sendok."
Tanpa suara Jeon menatapku galak.
"Aku mengerti," ucapku putus asa sambil menyuap sesendok nasi ke mulut. "Lain kali jangan menatapku begitu. Tidak boleh ketus atau marah pada ibu hamil. Bayinya bisa sedih."
"Iya. Ayahnya ikut sedih karena ibunya tidak mau mendengar nasihat baik."
Aku mengalah, membiarkan dia yang menang. Lalu kuraih sesuatu di kursi sebelah, amplop berisikan tiket premier dan mendorong ke arah mejanya. "Aku ingin kau datang lebih awal."
Jeon tersenyum hangat. "Aku pasti datang."
"Sekarang aku ingin dengar ceritamu." Aku memasukkan sesuap lagi nasi.
"Tidak sekarang," sahutnya pelan.
Aku menelan makanan di mulutku dan menggertak. "Aku ingin sekarang."
"Kita sedang makan, Runa." Nada suaranya meninggi.
"Apa salahnya membahas hubunganmu dan Go Ae Jin saat kita makan."
Matanya memancarkan pergulatan emosi. "Kau mulai lagi?"
"Mulai lagi?" Sedikit demi sedikit emosiku melonjak naik. Kewarasanku bagai menguap di udara. Kata-kata mulai lagi terdengar seperti dia menuding jika akulah pemicu pertengkaran kami. "Mulai lagi yang seperti apa maksudmu?" Aku membentaknya tidak terima. "Pikirmu semua perkara ini muncul dariku? Begitukah?"
Sejak tiba di rumah aku berusaha mati-matian menahan segenap amarah, namun ini adalah emosi yang sama sekali baru, yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku sangat marah dengan pria di depanku sampai-sampai tidak tahu mesti berbuat apa.
Tensi di antara kami meningkat. Melihat Jeon sekarang benar-benar membuat selera makanku hilang. Kenapa dia bisa jadi sebodoh ini?
"Kumohon," pintanya melemah. "Aku hanya ingin kau memahami keadaanku."
Aku mulai kehabisan napasku. "Kau sadar betapa menyebalkannya dirimu sepagian ini?"
Jeon mengetatkan rahanganya seolah sedang mencekal seluruh binatang buas yang ada dalam tubuhnya supaya tidak menyerangku. "Aku pasti mengatakannya. Semuanya. Tapi aku butuh waktu, Shin Runa. Aku akan mengatakannya dengan jujur."
"Dengan jujur?" Aku mencela. "Kau berharap aku percaya setelah semua yang kau lakukan padaku? Setelah semua kebohonganmu, dan setelah mengatahui semua kejahatanmu padaku?" Aku berteriak lantang hilang kendali dan memukul meja. "Sekarang bagaimana caranya aku percaya? Beritahu aku. Jelaskan padaku bagaimana caranya kau membuatku percaya setelah semua kebohongan yang kau tunjukkan padaku?"
Seolah kesadaranku baru saja dikembalikan, aku segera mencengkeram bagian atas kepalaku dengan dua tangan, lalu mengusap pipi dan menutup mulutku dalam gerakan cepat. Aku mencari napas dengan rakus. Detik demi detik amarahku bergulir kembali menjadi ketenangan.
Orang disekitarku bilang aku pandai mengelola emosi. Padahal tidak begitu jika aku tidak mempelajarinya selama yang tidak pernah kuperkirakan.
Aku telah banyak belajar cara mengendalikan kemarahanku melalui rasa sakitku sendiri. Dan hanya Jeon yang bisa membuatku berteriak seperti itu.
Aku meraih benda lainnya di sampingku. Map yang diberikan Jaemin siang ini. Kuberikan ini pada Jeon dengan semua akal warasku.
Jeon menarik napasnya. Terlihat masih sedikit marah ketika membuka dokumennya.
"Hasil medis kejiwaanku beberapa tahun lalu." Aku memberitahunya dengan kaku.
Matanya menatapku antisipatif. Seperti baru pertama kali melihatku.
"Aku melakukan farmakemoterapi selama bertahun-tahun karena mengalami gangguan kecemasan yang tidak biasa daripada kecemasan pada umumnya," ucapku dengan suara yang begitu tenang. "Aku selalu membutuhkan seseorang untuk mengatakan kalau keadaanku akan baik-baik saja. Dulu, semua itu nyaris membuat gila dan sering terpikir akan lebih baik jika aku mengakhiri hidupku. Untungnya aku punya Jaemin, Danna, dan orang-orang terdekat untuk membantuku mengatasi kecemasan, dan sekarang aku hanya memilikimu. Lalu apa jadinya bila kau sendiri tidak bisa menjamin aku akan baik-baik saja?"
Jeon menarik napas panjang hingga kulihat dadanya naik dan turun. Ia keluar dari kursinya dan mengambil tempat di sebelahku. Ketika Jeon menangkup wajahku dan ketika dia memandangku cemas dengan cara seolah dia ingin menyerap rasa sakitku, aku baru bisa merasakan udara memenuhi paru-paruku.
"Di dunia ini bukan hanya kau satu-satunya yang menderita, Jeon. Bukan hanya kau satu-satunya orang yang boleh sakit. Sadarlah."
Tatapan Jeon melembut. Dalam lubuk hatiku pun yakin Jeon pasti tidak ingin aku mengalami kejadian semacam itu.
"Maaf." Jeon menggerakan jarinya di pipiku. "Bukan tujuan membuatmu terluka. Maafkan aku."
"Ini bukan tentang sikapmu, Jeon. Tapi seluruh perasaanmu," ungkapku. "Aku kecewa pada diriku sendiri karena tidak bisa menjadi satu-satunya untukmu. Aku kecewa karena masih banyak yang belum kutahu tentangmu. Aku hanya tahu jam berapa kau bangun, aku hanya tahu pola hidupmu teratur atau aku tahu kau selalu sulit tidur lagi jika terbangun. Aku tahu jabatan dan pekerjaan. Aku tahu semua yang orang-orang katakan tentangmu, tapi ternyata semua itu tidaklah cukup."
Aku mengakui—Akhirnya aku mengakui apa yang kupendam selama ini sambil menahan isak tangis.
"Aku tidak tahu masa lalumu—Han Taejoon, perasaanmu, dan mungkin masih ada banyak hal yang kau sembunyikan karena kau tidak pernah berterus terang padaku. Aku hanya sedih karena aku tidak berarti apa-apa untukmu."
"Tidak, tidak. Tolong jangan bicara seperti itu." Jeon menggeleng-geleng panik. Dia semakin mendekatkan wajahnya padaku. "Jika ini bisa membuatmu sedikit lebih tenang, baiklah, aku benar-benar akan mengatakan kejujurannya sekarang dan kau tak harus mempercayaiku."
Jeon menarik napasnya sebelum memulai. "Aku memang masih mencintainya. Aku masih mencintai Go Ae Jin tapi rasa cintaku tidak sebesar itu bahkan hampir sepenuhnya hilang. Aku tidak bisa melupakannya karena dia sempat ada dalam hidupku. Sekarang aku lebih bahagia kau ada di sini. Aku bahagia kau bisa bertahan dengan pria lemah sepertiku, pria yang selalu sulit mengatakan sesuatu.
Aku merasa tenang setiap kali kau berada di sekitarku, setiap kali mendengar suaramu, atau setiap kali menatapmu, dan aku selalu tak sabar pulang untuk bertemu denganmu karena aku benar-benar merindukanmu setiap hari. Aku merasakannya. Aku merasakan seluruh kebahagiaanku terletak padamu.
Go Ae Jin tidak bisa memenuhi pikiranku sebesar kau melakukannya, Shin Runa. Dan hari ini aku tidak bekerja dengan benar karena di sini," sebelah tangannya turun ke perutku namun tatapannya menetap di mataku, "ada sesuatu yang membuatku bahagia dan tidak fokus bekerja. Aku terlalu bahagia sampai tak tahu bagaimana caranya aku menunjuk sikapku padamu."
Aku memandangi bola matanya lekat-lekat. "Kau bersungguh-sungguh?" tanyaku tersendat menahan tangis.
Jeon menekan pipiku dan tersenyum. "Aku bersumpah. Aku jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada Shin Runa. Aku bersumpah tidak akan meninggalkan ataupun melepaskanmu."
Ada jeda waktu cukup lama sampai kemudian bibir Jeon menyentuh bibirku. Aku tidak bisa bernapas dengan benar karena seluruh tubuhku rasanya bergetar.
Jeon menunggu bibirku menyambut ciumannya dengan sabar. Lalu dengan perlahan aku menutup mata sambil menggerakan bibirku di atas bibirnya. Kedua lenganku mengalung di lehernya.
Ciuman ini membuatku sadar jika aku merindukan pria ini. Sebab sesuatu yang lebih buruk ketimbang kemarahanku adalah aku yang berpura-pura tidak merindukannya seharian ini.
Aku melepas ciuman kami dan bangkit dari kursi. Menarik tangannya menuju sofa dan mendorong halus badannya ke sana.
"Runa?" Jeon terkejut saat aku menaiki pahanya dan dia memandangku dengan cemas.
Kemeja kuning miliknya yang malam ini kupinjam sempat menjarah perhatiannya. Aku tahu Jeon sudah menyadari penampilanku sejak awal. Aku tidak ingin bertanya, tapi aku tahu dia akan menyukai bagaimana kemeja kuning dan celana dalam putih melekat di tubuhku.
Namun aku memilih tidak memberinya jawaban selain mencumbu kembali bibirnya. Kemudian menarik bajunya melewati leher. Kubiarkan bajunya teronggok di lantai lalu membuka kancing celananya.
"Runa, biar aku yang melakukannya," pintanya sedikit memohon di antara celah bibir kami.
Tetapi aku mengabaikan Jeon dan menurunkan ritsleting celananya. Malam ini aku tidak ingin memperlakukan Jeon seperti orang yang pantas dikasihani.
"Runa, kumohon." Dia menahan pinggulku. "Aku belum ingin di bawah."
"Tidak mau, Jeon," sentakku
Kali ini aku tidak ingin berada di bawah kendalinya. Aku ingin menjadi dominan dan bersumpah bisa melakukannya dengan benar.
"Anggap saja hukuman," timpalku menuntut.
Semua yang akan kulakukan malam ini tak boleh mendapat penolakan.
Jeon harus mengerti itu.
[]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top