04| Who's Lying Between Us?
Ternyata belum seminggu update 4 bab. Yaudahlah. Anggep new year gift. Semoga kalian masih betah dan bisa bantu aku build up semangat untuk update. Kalau rame, malem sabtu/malming akan publish part baru.
Kalau kalian suka jangan lupa vote,
komen, dan share yaaa.
— — —
Setelah menikah, setiap harinya aku merasa semakin muda dan bukannya bertambah tua.
Kemungkinan besar karena hubungan kami yang tumbuh seperti remaja malu-malu saat berpacaran.
Ah, ya— tadi kami sarapan bersama tanpa mengulas masalah semalam. Berbincang singkat terkait pekerjaan. Selebihnya tenggelam pada pikiran masing-masing.
Tetapi saat aku menggosok gigi di depan wastafel, kutemukan tanda kecil lucu pada leher. Perbuatan liar Jeon semalam.
Refleks aku tersenyum dan tidak tahan untuk tidak merabanya. Kilas balik tindakan sensual kami di meja makan membuat perutku kegelian.
Lucu, tentu saja. Aku menganggap cap bibirnya adalah hadiah.
Terdengar konyol. Tetapi bagiku yang sulit berkencan setelah sibuk menjadi penulis naskah, hal ini termasuk unik dan menggemaskan. Sekarang aku baru mengerti kenapa banyak manusia menjadi bodoh saat menyukai seseorang.
Tidak ingin membuang waktu bercermin, aku bergegas kembali pada seluruh aktivitasku.
Jadwal harianku hanya bertemu dengan salah satu reporter berita untuk mengatur pertemuan dengan penggemar dan sesama komunitas menulis, barulah pukul dua nanti menemui adikku di kafe dekat kampusnya. Sedangkan Jeon sudah berangkat sekitar sembilan menit lalu.
Begitu pertemuan dengan reporter TV swasta perihal wawancara film selesai, aku pergi menuju kafe. Kupesan segelas kopi hangat bersama sepotong kue matcha.
Setelah minumanku habis setengah gelas, wajah adikku muncul di muka pintu sambil melambai tinggi-tinggi. "Noona!"
Shin Jaemin tersenyum lebar.
Aku hanya menyuguhkan Jaemin ekspresi datar saat mendekat. Segala tindak tanduknya tidak lepas dari pengamatanku. Kemudian dia duduk di hadapanku dan menenggak kopiku tanpa izin hingga tandas. Sangat normal.
Dia membesut bibirnya dengan lengan baju. "Noona, apakah kakak ipar sibuk?"
Mataku melotot karena sudah ahli menebak jalan pikirannya. "Jangan coba-coba mengusiknya."
"Ah, padahal mau minta tolong sebentar. Ada tugas sketsa yang belum rampung."
"Mengapa sejak aku menikah kau jadi lebih manja pada suamiku?" Aku mencibir dengan tampang dongkol.
"Itu-karena-kakak-ipar-lebih-manusiawi-daripada-kakak-kandungku," Jaemin menjelaskan dengan wajah malas-malasan.
Aku nyaris mengangkat tangan ingin memukul ubun-ubunnya. "Augh! Anak ini. Pokoknya jangan sampai kau mengganggu suamiku. Dia itu orang sibuk, mengerti."
"Aku kan cuma mau minta sedikit bantuan kakak ipar. Tugasku sangat mendesak."
Mengingat Jaemin merupakan mahasiswa jurusan seni kreatif dan desain, Jaemin sering sekali meminta bantuan pada Jeon, bahkan sejak sebelum kami menikah. Sehubung Jeon mahir dalam beberapa teknik fineart, hal itu membuka kesempatan Jaemin untuk minta bantuan kecil-kecilan tanpa perlu bayar. Aku sudah tahu visi misi Jaemin setelah mendengar suamiku menciptakan desain produknya sendiri.
Tidak tanggung-tanggung, Jaemin juga pernah bertandang jam dua pagi ke rumah kami karena besoknya harus mengumpulkan sketsa yang belum diarsir. Akhirnya sepanjang malam Jeon yang bekerja ekstra membantu Jaemin merampungkan tugas.
Sementara Jaemin?
Jangan ditanya. Anak itu malah tidur pulas di sofa. Dan dengan baik hatinya, Jeon malah menyelimuti anak nakal itu.
Mataku mendelik. "Awas kalau kau berani meneleponnya."
"Kenapa? Kenapa?" Jaemin mengangkat dagunya menantang. "Apa kakak ipar sedang sibuk?"
"Selalu sibuk," tukasku. "Pokoknya jangan diganggu. Nanti dia sulit fokus."
"Iya, iya. Tidak akan. Sekarang berikan aku uang." Jaemin mengulurkan tangannya.
"Lagi?" Hanya anak ini yang sanggup membuat tekanan darahku naik.
"Uang saku yang Noona berikan sudah habis."
"Bagaimana bisa habis? Minggu lalu aku sudah memberikan dua kali lipat, Bocah!"
"Bolak-balik kampus butuh uang. Aku sering lapar karena terlalu banyak berpikir. Biasanya makan enam kali. Apalagi cuaca dingin."
Merengek-rengek adalah kudapan yang Jaemin berikan pada orang rumah setiap hari. Aku justru curiga jika anak itu mendadak diam. Karena pernah ada kejadian setelah pulang berkemah Jaemin menjadi pemurung dan tidak banyak bicara, setelah dibawa ke dukun setempat ternyata anak ini kerasukan arwah kuil Buddha. Maka dari itu, aku lebih lega mendengar Jaemin masih bisa menggonggong seperti anjing liar.
"Tidak bisa. Jangan minta juga pada ayah dan ibu. Kau harus tahu cara berhemat."
"Baiklah. Kalau Noona menolak, tidak ada cara lain."
"Apa maksudmu?"
"Apa lagi. Terpaksa aku harus minta pada kakak ipar." Jaemin bersiap-siap mengeluarkan ponselnya dari kantong.
"Kau! Jangan coba-coba."
Mendengar suaraku meninggi, Jaemin merosot di kursinya kehilangan semangat. "Harta kakak ipar pun takkan habis kalau kupalak beberapa kali."
"Hei, Shin Jaemin, memangnya kau menyimpan uang padanya?" ucapku ketus masih dengan cara seorang kakak. "Nanti akan kuberitahu suamiku agar tidak terlalu memanjakanmu."
"Ah, Noona! Habisnya Noona juga tidak mau memberiku uang. Padahal jumlah digit di rekening Noona sanggup membeli dua rumah dan empat sport car."
"Kali ini uangnya untuk apa?" Bola mataku seolah bisa copot dari poros jika terlalu lama menghadapi Jaemin.
Sambil menunggu, aku terus menatapnya dalam-dalam. Sebetulnya aku bisa saja mengalirkan dana ke rekening Jaemin cuma-cuma. Tetapi kalau terus begitu, Jaemin akan mudah bermalas-malasan meskipun kemampuan otaknya sangat cemerlang. Aku khawatir anak ini mengabaikan fokusnya dari tugas-tugas kampus.
Tetapi seperti yang lalu-lalu, baik aku maupun ayah akan luluh ketika mengingat Jaemin masuk ke universitas negeri terkemuka Seoul dengan biaya kecil karena mendapat beasiswa jalur prestasi.
"Untuk apa?" ulangku semakin mendesak.
Jaemin masih kelihatan berpikir mencari alasan. "Keperluan anak muda."
Aku tidak langsung menjawab. Sebelumnya kuberikan Jaemin tatapan menusuk.
"Ayolah, Noona."
Aku mendesis. "Alasan spesifik. Aku butuh itu."
"Dijelaskan sampai lidah bengkak pun Noona takkan percaya. Pokoknya untuk keperluan anak muda." Saking semangatnya ludah Jaemin sampai muncrat dan terjun bebas di sampul noteku.
"Katakan lebih rinci." Aku melipat tangan.
Jaemin mulai merengek dan menendang-nendang kakinya di kolong meja. "Ayolah, Noona. Kali ini akan kugunakan lebih bijak. Kalau bisa aku makan satu kali. Bila perlu aku jalan kaki ke mana-mana. Bila perlu lagi aku tidak akan membeli baju dan sepatu selama satu tahun."
Astaga, anak ini... aku berusaha menahan luapan emosi.
Sembari mengeluarkan lembaran uang yang jumlahnya tidak sedikit, aku berpesan, "Berhematlah. Kau akan merasakannya saat bekerja nanti."
Wajah Jaemin kembali ceria seperti anak-anak yang sedang berwisata. "Terima kasih, Noona. Noonaku memang Orang Kaya Dermawan."
"Ingat. Jangan gunakan uang yang kukirim ke rekeningmu untuk sesuatu yang tidak berguna. Aku mengawasi penggunaan kartu debitmu."
Jaemin mengangguk patuh.
Aku menghembuskan napas pasrah. Tatapanku kali ini tidak segarang beberapa detik lalu. Bagaimana bisa aku marah lama-lama dengan Jaemin. Dulu, akulah yang membersihkan kencing dan kotorannya, atau sekedar menemaninya ke kamar mandi tiap jam satu pagi. Sekarang tinggi badan Jaemin bahkan melebihi tinggi badanku. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu masih membuatku tidak menyangka. Namun bagi kami sekeluarga, Jaemin masih tetaplah sosok anak laki-laki yang manis hingga terkadang membuatku tidak tega kalau ingin membentak atau memukulnya.
Karena di mata kami, Jaemin kami masihlah seorang balita.
Akhirnya aku hanya bisa menghembuskan napas kalau mengalah. "Yang perlu kau ingat, jangan menyusahkan kakak iparmu sementara kau tidak bisa membalas kebaikannya."
Jaemin mencebikkan bibir. "Membalas kebaikan kakak ipar bukankah sudah diwakili oleh Noona?"
"Apa maksudmu?"
"Body Service setiap malam. Apa itu namanya kalau bukan kebaikan," sahut Jaemin ceplas-ceplos.
Aku mendesis. "Shin Jaemin, bicaralah yang sopan."
"Oppa!"
Suara itu menyabotase pembicaraanku. Aku sedikit memutar tubuh di kursi dan melihat sesosok gadis cantik dengan kulit putih bersinar. Lalu, kembali menghadap Jaemin, menuntut penjelasan.
Air wajah Jaemin menjadi sangat sumringah. "Oh! Chagiya." (Sayang)
Oh, apa ini? Aku merinding mendengar suara Jaemin barusan.
Kemudian aku memicing pada Jaemin penuh selidik. "Apa-apaan ini? Dia pacarmu?"
Jaemin mengulurkan lehernya lebih dekat ke arahku lalu berbisik dengan maksud tertentu, "Noona kumohon bersikaplah waras. Berpura-pura tidak ada yang terjadi."
"Kau membohongiku? Uang tadi mau kau pakai untuk membelanjakan pacarmu barang, kan? Lalu bagaimana dengan pacarmu minggu lalu? Hei, Player. Jelaskan padaku."
"Sstt. Dia mendekat. Kumohon sekali ini saja Noona."
Gadis itu berlari kecil mendekat. Jaemin lantas berdiri dari kursi dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dalam hitungan detik gadis itu telah jatuh ke pelukan Jaemin.
Mode imut Jaemin saat memohon padaku tadi tergantikan oleh mode sok kerennya.
"Perkenalkan," Jaemin membebaskan pelukannya. "kakakku, Shin Runa."
Gadis cantik itu langsung membenahi rambutnya yang bahkan tidak berantakan dengan gerakan terburu-buru sebelum membungkuk sederhana ke arahku. Senyum lugunya sempat membuatku ragu jika itu merupakan kamuflase sesaat. Masalahnya aku sudah sering bertemu gadis seperti ini.
Pandanganku tertuju ke rok putihnya dengan cara menilai. Orang macam apa yang memaksakan diri mengenakan pakaian minim di musim dingin.
Sejurus kemudian tatapan laser kuberikan kepada Jaemin.
Mata Jaemin mengedip untuk memberi kode agar aku tidak membongkar rahasia apa pun di depan pacar-barunya-yang-malang, kalau boleh kubilang.
Aku menarik napas sembari mengendik. "Masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan." Kubenahi buku catatanku dan memasukkannya ke tas.
Saat berdiri dari kursi, Jaemin sontak memegangi tanganku. "Noona! Noona takkan bilang pada ibu kan?"
Aku menyeringai ke arah Jaemin. "Kita lihat nanti," lalu berpaling pada gadis yang menjadi mangsa Jaemin selanjutnya.
Aku membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu namun kembali mengatupkan bibir secepat yang kubisa, dan memilih keluar kafe.
Di belakang sana, samar-samar kutangkap suara Jaemin yang mencoba menenangkan gadisnya, berkata bahwa aku hanya sibuk dan memang sudah ditakdirkan berwajah seperti nenek sihir, bukannya langsung pergi lantaran tidak menyukai gadis itu.
Aku tersenyum geli sambil menggeleng-geleng kecil.
But sorry Jaemin, she is cancelled. You failed again.
Gadis pilihannya tadi lagi-lagi tidak termasuk kriteria calon adik iparku.
Di depan pintu kafe aku mengaduk tas mencari remot mobil. Setelah ketemu kutekan tombol nyalakan mesin mobil yang sudah ditanami semacam microchip, membuat semua serba efisien.
Sebelum masuk, dari kejauhan aku melihat tipe mobil dan nomor plat yang tidak asing. Mobil itu terparkir di tepi jalan, di seberangku, tepat di depan pelataran toko bunga.
Tidak salah lagi, itu benar mobil Jeon. Alisku berkerut.
Sedang apa Jeon di area ini?
Lokasi ini jauh dari kantornya. Sekitar dua menit menunggu, si pemilik mobil keluar. Dan benar saja, Jeon keluar dari dalam toko membawa sebuket bunga, memasuki mobilnya, dan melaju pergi meninggalkan kawasan.
Anehnya kecepatan mobil Jeon berpacu di atas rata-rata untuk jalanan lengang. Mobil itu terlihat memburu waktu dan baru saja melewatiku tanpa pengemudinya menyadari sosokku.
Aku buru-buru masuk ke mobil dan entah mengapa rasa penasaran itu mendadak timbul, membuatku berniat melakukan pengejaran.
*****
Aku menghela lagi.
Dalam lima belas menit sekurangnya sudah memeriksa arloji sebanyak dua puluh kali. Penasaran apa yang Jeon lakukan di kawasan perumahaan elite ini.
Satu jam menunggu dan memantau dari kejauhan di dalam mobil, tidak juga terdapat tanda-tanda Jeon akan keluar dari rumah berpagar kayu besar yang rindang.
Namun ketika pikiran seperti; ahh, mungkin saja Jeon bertemu kerabat atau siapalah itu muncul, akhirnya aku berniat meninggalkan tempat itu, tetapi pintu gerbang tadi segera terbuka. Jadi aku menggagalkan rencana pergi.
Jeon keluar pertama kali, disusul seorang wanita di belakangnya. Buket bunga dalam genggamannya juga sudah tak lagi ada di sana. Dia pasti sudah menyerahkan buket itu pada si pemilik rumah.
Penasaranku membuncah. Aku menjulurkan kepala menuju bagian atas stir sambil menyipitkan mata. Mempertegas pengelihatanku terhadap sang wanita untuk menemukan kunci dari spekulasiku yang bertambah parah.
Wanita itu memakai busana rumahan dan sedang tersenyum mengusap lengan kiri Jeon. Mataku terus mengawasi setiap pergerakan mereka, terutama tiada henti menyelidiki wajah wanita itu.
Apakah wanita itu pernah datang ke acara pernikahan kami?
Aku mencoba mengingat-ingat.
Tidak. Aku menggeleng tak sadar.
Wanita itu jelas tidak ada dalam pesta pernikahan kami.
Berdasarkan adat Korea, di mana mempelai pria dan wanita harus mengunjungi meja-meja tamu undangan untuk menyapa, jadi sedikitnya aku masih ingat wajah-wajah mereka.
Di depan sana mereka membicarakan sesuatu yang tak dapat kutangkap gerakan bibirnya dengan jelas. Aku menyipit berkali-kali sekedar bisa memahami dan membaca gerak bibir mereka untuk mendapat satu dua patah kata kunci.
Lalu, sesuatu yang membuatku terkejut adalah bagaimana cara wanita itu membuka tangannya dan merengkuh tubuh Jeon dalam hitungan singkat.
Dan apa-apaan itu? Jeon juga membalas pelukannya, menyandarkan dagunya ke bahu wanita itu dengan mata terpejam. Kenyamanan di wajahnya tergambar jelas.
Sekonyong-konyong aku teringat perkataan Jeongmin, Direktur berangkat lebih pagi dan akan pulang paling akhir. Di rumah masih harus memikirkan gagasan proyek baru.
Ini bahkan belum tiba waktunya jam pulang kantor.
Detik ini kepalaku memberat. Agak pening, kuberi sedikit pijatan pada ujung pelipis kiri.
Lantas apa selama Jeon membohongiku?
Secepat itu pula aku menggeleng. Tidak, Runa. Tidak mungkin.
Tentu saja tidak mungkin suamiku tega melakukan itu. Kenapa aku bisa berpikiran konyol.
Namun timbul keyakinan lain dalam benakku. Menepis prasangka tidak semudah kedengarannya, apalagi aku melihatnya langsung. Maka dari itu aku segera meraih telepon genggam di jok sebelah dengan tangan agak gemetar.
Tidak butuh waktu lama Jeon melepaskan pelukan mereka—sorry. Bukannya ingin menginterupsi momen kalian— tetapi saat ini seperti ada yang menyulut api di dasar tubuhku. Tidak bisa kujelaskan detailnya, tapi... ya, aku kesal.
Kulihat di depan sana Jeon mengambil ponsel di sakunya. Jeon tidak buru-buru menjawab panggilanku. Dia menatap wanita itu seolah meminta persetujuan. Anggukan kepala wanita itu membuat Jeon yakin mengangkat panggilannya. Dalam sambungan kami kudengar Jeon berdeham.
"Aku mengganggumu?" tanyaku sebelum dia membuka suara dan sepertinya dia memang takkan memulai.
Kembali Jeon menatap wanita itu, lalu menjawab dengan suara bimbang. "Tidak."
"Apakah kau masih di kantor?"
Dua detik Jeon baru menjawab. "Ya. Aku masih di kantor."
Hancur.
Nyeri.
Bagai ada beban besar menghimpit dada. Sebelah tanganku yang mencengkeram stir langsung terkulai di paha, tidak menyangka Jeon baru saja berbohong.
Pernikahan kami bahkan masih jauh dari hitungan bulan. Mendadak aku diliputi perasaan tak enak.
Mataku berbayang, namun mencoba tak menangis dalam situasi ini. Kemudian kuteguk ludahku mencoba tenang. "Begitukah?"
"Ya."
"Baiklah. Kalau begitu kukatakan saat kau tiba di rumah. Selamat bekerja."
Jeon berdeham lagi, menjawab 'Ya. Terima kasih' dengan suara yang agak aneh, sebab aku bisa menangkap suaranya lebih mudah ketimbang suaraku sendiri.
*****
Obrolan kami untuk penutup hari lebih singkat. Makan malam monoton. Nyaris tak punya tajuk.
Aku mencuci perlatan makan yang tidak terlalu banyak, karena hanya memasak sup miso dan nasi goreng.
Segalanya berjalan lebih lambat. Namun tetap seperti biasa: makan tanpa keributan.
Makin lama aku sadar situasi ini membuatku kurang nyaman. Di rumah selalu ada Jaemin yang melontarkan jokes saat makan. Ada ibu yang selalu marah jika ayah makan tidak rapih atau terlalu banyak. Tetapi di sini—bahkan aku tak bisa tertawa lepas ketika sedang makan. Sungkan. Takut mengusik atau membuat suamiku hilang selera.
"Jeon," Aku menyebut namanya ketika membilas gelas, "berhenti mengirim Jaemin uang."
Dia berjalan mendekat, mengambil posisi di sebelahku setelah membuang sampah. "Kenapa?"
"Jangan. Nanti dia tambah manja."
Jeon memasang sarung tangan karet kuning, turut membantu menyabuni piring bekas kimchi. "Jaemin anak yang pantang menyerah," ucapnya sambil memberikan piring berbusa padaku. "Sebanyak apa pun yang kita bagi dia akan tetap berusaha."
Aku kesal mendengar jawabannya. Aku kesal pada Jeon karena seolah dia mengerti Jaemin lebih baik daripada kakak kandungnya. Kakak yang hidup bersamanya lebih dari 20 tahun. Bukan 20 hari.
Malam ini aku kesal pada Jeon. Tapi tidak benar-benar bisa menumpahkannya seperti seember air beku yang meski dibalik tidak akan mengalir.
Ada beragam perasaan jengkel. Entah aku marah karena dia masih memberi Jaemin uang atau kesal karena kejadian siang ini.
Enggan berkomentar banyak akhirnya aku bersikeras, "Hanya kali ini. Biarkan dia memulainya sendiri. Aku hanya ingin kau hargai keputusanku."
"Tapi—"
"Aku kakaknya!" Sontak aku menghadapnya lepas kendali. Inilah teriakan pertamaku setelah menikah. "Aku lebih mengerti segala sesuatu tentangnya. Tolong jangan memulai keributan." Dadaku naik turun tidak karuan. Marah lantaran Jeon menjadi sangat menyebalkan.
Awalnya Jeon masih terlihat tidak menyetujui gagasanku, tetapi pada akhirnya dia bisa menghormati keinginanku.
"Maaf membentakmu." Aku mengakui dengan suara pelan sambil menarik napas.
Jeon memaklumi responsku.
Hal berikutnya yang kami lakukan pergi ke kamar masing-masing. Lambat laun, sejak kejadian siang tadi aku mulai menyalahkan keadaan.
Kenapa kami tidur terpisah?
Aku menekan kepalaku ke belakang pintu kamar berpelitur putih gading. Mataku mengawang pada ranjang. Bukankah masih ada banyak ruang di kasurnya? Kami bisa berbagi setengah tempat.
Tapi mengapa dia harus begini? Mengapa dia memperlakukanku seperti penghuni asing?
Pertanyaan seputar Jeon tidak pernah putus mengelilingi kepalaku.
Sebagai wanita yang tidak berpengalaman dengan percintaan, hubungan asmara, apalagi pernikahan, masalah ini jelas membuatku resah.
Aku tidak bisa menghalau keresahaan yang seakan bisa membeludak kapan pun. Aku tidak tahu seputar hubungan masa pra-nikah. Namun sedari tadi alam bawah sadarku menuntun pada satu kata sialan itu.
Perselingkuhan.
Selagi merenungi segala kejanggalan yang Jeon tampilkan, tahu-tahu ponselku berdering. Aku berjalan tanpa semangat mengambil benda itu di atas selimut dan betapa terkejutnya bahwa itu adalah panggilan video call dari Jeon.
Apalagi sekarang?
Sejujurnya aku menjadi lelah. Aku menarik napas dan menggeser tombol terima, namun jempolku lebih dulu menutupi mata lensa.
Jeon tertawa renyah. "Kau menutupi kameranya."
"Itu...," mataku berkelana mencari pengalihan. "... aku belum pakai bedak."
Sepertinya alibiku gagal, karena saat makan malam tadi wajahku pun luput dari riasan.
Dia mengulangi tawanya. "Tapi aku rindu wajahmu."
Terdengar aneh. Kami baru bertemu di ruang makan beberapa menit lalu, dan dia sudah merindukan wajahku.
Aku tidak percaya ini.
Lebih dari itu aku mulai meragukan hubungan kami yang tidak ada perkembangan.
Aku menggigit bibir karena bimbang dan menjawab agak tercekat, "Tadi kan sudah bertemu."
"Rindu lagi." Jeon membasahi bibirnya.
Bila rindu kenapa tidak datang langsung dan tidur bersamaku? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Rahasia apa yang sebetulnya kau sembunyikan?
Itu semua yang sejujurnya ingin kutanyakan setiap kali kami sarapan dan makan malam bersama, tetapi aku tidak bisa menyampaikan dan belum menemukan situasi serta momen yang pas.
Semuanya mulai menjadi tidak benar untuk diriku sendiri. Pernikahan yang sebelumnya kudambakan mulai terasa palsu.
Kupikir menerima Jeon adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Jika ternyata salah, entah bagaimana hancurnya aku nanti.
Aku tidak bisa berpikir.
Semuanya salah.
Jeon tidak ingin kusentuh, tetapi dia memeluk dan disentuh wanita lain.
"Runa?"
Aku tersentak. "Ya?"
"Kau masih di sana?"
"Tentu saja. Aku masih melihatmu." Dengan cara berbeda.
"Biarkan aku dengar suaramu. Lima menit."
Kenapa tidak langsung mendatangi kamarku, Jeon?
Aku bisa berceloteh hingga suamiku tidur jika ingin. Aku bisa menyanyi dan memiliki suara bagus jika dia berharap mendengarku bernyanyi sebagai lullaby, atau aku bisa bermain piano dan membiarkan dia bersandar di bahuku hingga pulas.
Tetapi mengapa kami berjarak?
Lagi-lagi pertanyaan itu membuatku ingin marah. Batas kamar kami bahkan kurang dari dua puluh langkah. Kenapa dia harus menghubungiku seperti ini sementara dia bisa dengan gampangnya memeluk wanita lain?
Merasa sikapku agak kekanakan, akhirnya, pelan-pelan kujauhkan ibu jariku yang menutupi lensa kamera.
Aku memasang senyum lebar seakan tidak terjadi apa-apa. "Bagaimana harimu?"
"Seperti biasa."
"Berada di kantor seharian?" pancingku ingin tahu, mungkinkan dia berkelit atau jujur.
Dia terdiam dalam hitungan lima jariku dan tersenyum. "Ya."
Bohong.
"Jadi kau benar-benar tidak beranjak dari perusahaanmu untuk menghirup udara segar?"
Jeon kelihatan memaksakan bibirnya tersenyum dan mengangguk pasif. "Ya."
Bohong. Semua jawabannya hanyalah dusta. Kenapa kau tega berbohong padaku, Jeon?
Tetapi aku tidak ingin bertingkah menjadi wanita melankolis yang bisa merusak suasana. Jadi aku menetralkan suara serak demi menghindari ketegangan. "Apa yang ingin kau dengar dariku?"
"Ceritakan pekerjaanmu hari ini." Wajahnya saat ini jauh dari kesan orang yang memang sengaja berbohong.
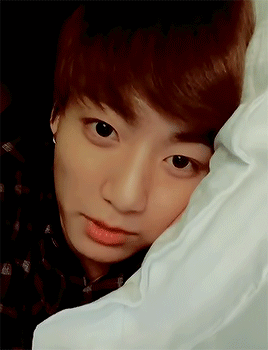
"Lancar." Jauh di lubuk hatiku ingin sekali membalas ucapannya dengan kepalsuan. Dusta dibalas dusta. Adil. Tetapi aku tidak sepicik itu. Aku tidak bisa berbohong pada suamiku sendiri.
"Tadi ada yang mau kau katakan?"
Bersyukur aku punya alasan mengubah negosiasi topik lain. "Sesuai janjiku, aku membelikanmu kemeja baru."
"Aku pasti suka." Jeon tersenyum.
Aku mulai berjalan ke meja kerja dan menempatkan ponselku di depan layar laptop. "Kalau begitu besok kusiapkan untukmu," ujarku terdengar lebih ceria sambil duduk.
"Bisa dipakai besok?"
"Tentu. Sudah kucuci dan setrika halus. Aku berusaha menghilangkan bau toko dan membuatmu tidak malu ketika memakainya."
"Terima kasih," ucapnya lembut. Seperti biasa. Tapi perih kali ini.
Aku terdiam beberapa saat. "Tapi aku beli kemeja dari brand lain. Bukan brandmu." Dan aku malah membelinya dari label lain yang mungkin saingannya.
"Kedengarannya bukan masalah."
Inilah yang paling menariknya darinya. Jeon tidak mempermasalahkan itu. Dia senang memakai baju dari berbagai merek.
"Bagaimana denganmu? Ada yang mau kau katakan?" tanyaku.
Setelah bimbang sesaat, Jeon segera berkata, "Itu... bisa kupanjangkan sedikit rambut dan membuat agak wavy?"
Tanpa pikir panjang aku menjawab dengan apa yang tidak sesuai isi hatiku. "Kau bisa jika perusahaanmu memberi izin."
"Boleh?"
Aku mengangguk layaknya orang hipokrit; bermuka dua.
Namun sesungguhnya, jauh di lubuk hati, aku tidak suka penampilan Jeon yang berantakan ketika di luar rumah—ketika dia berada jauh dari jangkauan mataku. Karena artinya dia membagikan pesonanya pada setiap orang secara gratis. Membagikan ketampanan yang memuat aura seksualitas kepada wanita-wanita yang mengaguminya secara visual. Seperti celana ketat dan ukuran kelamin yang dibicarakan Yeon Sun dan staf produksi tempo lalu.
"Sudah mau tidur?" tanya Jeon.
"Belum. Masih ada yang harus kukerjakan."
"Terkait naskah?"
Aku mengangguk. Entah mengapa kali ini semangatku berbicara dengannya menjadi sangat kacau.
"Jangan terlalu larut." Jeon memperingati dengan suara merdu seperti biasa.
"Kau juga, jangan tidur malam-malam," kataku. "Tapi kau terlihat seperti mau pergi tidur. Aku iri."
Jeon langsung tertawa dan mengganti posisinya menjadi duduk. "Begini? Kau mau ditemani?"
Sangat ingin.
Setidaknya aku berharap dia menemaniku di sini. Bukan dari kamarnya, atau dari balik layar ponsel.
"Memangnya malam ini tidak ada yang kau kerjakan?" tanyaku sepelan mungkin.
"Ada."
"Lembur lagi?"
Dia menghirup udara dari celah giginya. Kepalanya menoleh sedikit menghindari layar. Sepertinya memandangi meja kerja, bahkan sialnya aku tidak tahu apakah di kamarnya terdapat meja kerja.
"Beberapa pekerjaan lain," jawabnya.
Cukup lama bagiku untuk angkat bicara. "Rasa rindumu sudah lebih baik, Jeon? Jika kerinduanmu sudah terobati, maka sebaiknya aku kembali menulis naskah."
Jeon menghembuskan napas dan mengangguk. "Berjuanglah, Runa. Mimpi indah."
Sekali lagi, di tengah kedustaannya, lelaki ini menemukan cara membuatku tersenyum.
Sebelum panggilan kami selesai, aku menelisik wajahnya dalam layar.
Apakah ini yang dinamakan pernikahan? Apakah kami harus saling tertutup satu sama lain?
Sebenarnya... siapa yang sedang kami bohongi?
Dia yang tidak ingin kusentuh?
Atau aku yang tidak bisa bicara lugas?
[]
Kalau kalian Runa, apa yang akan kalian lakukan?
Pernah gak sih, kalian ngetes orang bohong padahal udah tau kebenarannya?
Kalian bakal mikir apa ke orang kayak gitu?
Terakhir masih gak nyangka kalo ini bisa dapet antusias banyak dari pembacaku 😭
Aku janji akan berusaha yang terbaik buat Océanor. Sayang banget sama pembacaku ❤️🥺
Makasih kalian. Makasih banyak.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top