Chapter 20. Tanpamu
Spam-spam komen, yaaaa
***
Gisele jenis perempuan yang tak mudah diintimidasi. Saat membukakan pintu yang kutekan bel-nya, dia sama sekali tidak terkejut melihatku tiba-tiba muncul di depan rumahnya seakan-akan dia sudah menanti kehadiranku.
Aku agak mempersiapkan diri kalau-kalau dia bersikap sama buruknya denganku malam itu, tapi dia malah tersenyum seolah ingin mengatakan bahwa kehadiranku di sana tak akan banyak berpengaruh. Selain itu, dia seolah terlahir dengan riasan wajah, warna-warna cantik nan memesona itu bagaikan menyatu dengan kulitnya dan tak bisa dihapus, membaur sempurna menyokong kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Bibirnya bagaikan benar-benar semerah buah delima, aku harus meyakinkan diriku bahwa warna itu didapat dari pewarna bibir yang sangat bagus.
Secara otomatis, aku membandingkan diriku dengannya. Mungkin sekali kami seumuran, tapi Gisele bagai datang dari kalangan yang jauh berbeda denganku. Dia mengendarai mobil mewah, wanginya mahal, mungkin dia punya karir cemerlang sehingga pria-pria sebayanya tak mampu mengimbangi dan membuatnya senang bermain-main dengan anak muda seperti Adam.
Terus terang, aku merasa rendah diri. Hari Seninku buruk, aku tidak berdandan karena tak ada janji bertemu dengan nasabah, nyaris tidak makan apa-apa karena banyak pikiran, serta kurang tidur. Terakhir kali kucek di spion tengah sebelum keluar mobil tadi, penampilanku hampir tak ada bedanya dengan tadi pagi sebelum mandi. Sementara Gisele mengenakan busana terbuka yang menurutku akan manis jika dikenakan Katya (masih cukup manis dikenakannya), aku mengenakan setelan katun membosankan yang—seperti kata Adam—paling pantas dikenakan pegawai kantoran pada hari Senin. Terlebih Senin yang buruk.
Aku beruntung ini memang hari Senin.
"Ya?" Gisele bersikap seperti tidak mengenaliku.
Atau mungkin memang dia tak mengenaliku?
"Aku ingin bertemu dengan Adam," ucapku—lebih seperti memberi tahu daripada meminta izin—sambil menutup bagian depan blazerku, entah mengapa.
"Adam nggak mau ketemu," katanya, tersenyum lebar. Rupanya dia bukan tidak mengenaliku, tapi sengaja memperlakukanku sebagai seseorang yang tak berhak berada di sini.
"Jadi dia ada di sini?" tanyaku, melongok ke balik bahunya.
"Tentu dia di sini, tapi dia nggak mau aku bilang ke kamu bahwa dia ada di sini, India—itu namamu, kan?"
Kupingku memerah, mungkin begini juga yang ia rasakan saat aku menyindirnya dengan pertanyaan apa-kamu-teman-Adam malam itu. "Gisele," aku harus bersabar. "Dia adikku, aku berhak tahu keadaannya."
Gisele menatapku, mulai ada keraguan terbersit di wajahnya.
"Apa dia tidak bilang bahwa aku kakaknya?"
Apa Adam tidak memberitahunya?
"Dia sudah dewasa," katanya, meyakinkan dirinya sendiri. "Kamu kakaknya atau bukan, dia sudah boleh menentukan sikapnya sendiri. Sekarang pulanglah, dia ingin di sini bersamaku, kalau ternyata dia berubah pikiran, aku akan mengantarnya pulang."
"Ke mana kamu akan pergi?" seketika aku meradang, tak pernah dalam hidupku seseorang mengklaim Adam seolah ia lebih berhak dariku. Seumur hidup setelah ayahnya meninggal bersama ibuku, semua orang menolaknya, hanya aku yang bersedia merawatnya. Seharusnya dia tidak bicara seperti itu padaku. "Kamu mengangkut semua barang-barangmu, mau kamu bawa ke mana dia?"
"Aku nggak mau bawa dia ke mana-mana," katanya. "Dia yang mau ikut denganku."
Rahangku mengetat, "Jangan main-main," kecamku.
Sekarang dia tahu aku serius, matanya membulat sempurna seakan dia baru tahu apa arti ucapannya. Dia pikir mudah membawa pergi anggota keluarga seseorang seolah dia barang yang akan dianggap hilang begitu saja?
Suaraku menggeram mengerikan setelah beberapa saat mulutnya tetap bungkam, "Suruh dia ke sini atau aku akan masuk. Apa kamu tahu berapa usianya?"—dia sudah sembilan belas tahun—"Tapi dia belum lulus sekolah"—aku meralat sendiri—"Apa yang kamu lakukan padanya? Suruh dia keluar. Sekarang."
Gisele bergerak, bahasa tubuhnya defensif. Bahunya yang tadinya lemas dan santai menghadapiku menegak, ia berdiri di tengah seakan menghadang pintu. Aku yang sudah kewalahan menahan emosi mendorongnya agak kasar supaya bisa melewatinya. Sesudah berada di dalam, aku baru sadar ia sama sekali tak bermaksud menghadang karena dengan mudah doronganku menabrakkannya ke pintu, tapi aku terlalu gusar untuk peduli.
"Adam!" seruku lantang.
Tak ada sahutan, Gisele juga diam saja.
Tiba-tiba, aku merasa sudah melakukan kesalahan yang memalukan. Mengingat pernyataan Dimas yang diminta Adam merahasiakan keberadaannya, bisa saja Gisele juga menahanku hanya karena Adam memintanya.
Aku berbalik menatap perempuan itu. "Apa dia benar-benar akan pergi denganmu?" tanyaku padanya dengan suara lebih lembut.
Gisele hanya mendesah sambil memandangi bagian dalam rumahnya.
"Oke," ucapku paham. "Kalau kamu nggak mau keluar, aku anggap kamu menyudahi hubungan kita sampai di sini"—suaraku masih lantang, aku yakin Adam bisa mendengarnya—"Aku masih berusaha mencarimu karena aku yakin kamu tahu kenapa, Dam, tapi kalau ini maumu ... aku akan pulang. Begitu aku pulang, aku hanya akan menunggumu di rumah buat mengemasi barang-barangmu."
Sambil mengakhiri kalimatku, aku menatap Gisele yang menempel di pintu dengan muka mengerut. Ya Tuhan, aku benar-benar sudah dikerjai. Dia hanya menggertak, pasti Adam yang menyuruhnya. Entah apa rencana anak bodoh itu setelah Gisele pindah, jangan-jangan Dimas dan Katya juga terlibat dengan semua ini.
"Aku pulang sekarang," kataku, berjudi, tapi dengan kemungkinan menang jauh lebih tinggi daripada kalah. Adam tak akan mungkin menerima keputusanku, dia pasti keluar menemuiku. Dia begini karena dia sedang mengancam supaya aku memenuhi keinginannya, dia tidak akan membiarkanku pergi tanpa mendapat apa yang ia mau.
Belum sampai hitungan ke tiga, pemuda itu muncul dari balik sebuah lorong yang menghubungkan ruang depan dengan bagian lain rumah. Aku lega melihatnya, tapi juga kesal. Aku memikirkannya sampai tak bisa makan dan tidur untuk mendapatinya mempermainkanku dengan cara murahan seperti ini.
Adam tampak bugar, mukanya memang merengut persis kalau kemauannya tak kuturuti, tapi penampilannya jauh lebih baik dari yang kucemaskan. Kupikir dia sama menderitanya denganku setelah mengungkap perasaan yang dipendamnya. Aku sudah jatuh iba, berpikir yang bukan-bukan, dan sempat akan menyerah asal dia mau pulang bersamaku. Nyatanya dia tinggal di rumah mewah, segala kebutuhannya terpenuhi, dan diam-diam menyusun skenario buruk sementara aku berdiri di sini kekurangan gizi dan hampir pingsan karena mengantuk. Oh Tuhan, aku memang menyayanginya, tapi aku tetap berharap dia pulang bersamaku tanpa aku harus menyerah pada kekanak-kanakannya supaya kami bisa membicarakannya baik-baik.
"Ayo pulang," ajakku tegas, daguku terangkat.
Adam bergeming, jarak di antara alisnya berkerut dalam seolah aku tak berhak bicara padanya seperti itu. Kami adu tatapan siapa yang akan menuruti siapa, dan sama-sama tak mau kalah. Walaupun tak berniat berlama-lama di sini, tapi aku juga tak sudi membiarkannya menang.
"Oke," aku meregangkan otot sebab Adam terlihat nyaman bersikap menjengkelkan. "Kamu nggak mau pulang? Terserah, aku sudah muak terpaksa memenuhi semua tuntutanmu."
"Aku nggak mau pulang kalau di rumah tak ada yang berubah!" Adam baru angkat bicara setelah aku berbalik cepat memunggunginya hingga rambutku berayun.
"Aku sudah muak bersandiwara," imbuhnya.
Tubuhku memutar secepat sebelumnya (dan membuatku sedikit pusing), agak tersinggung, tapi sungguh, daripada perasaanku yang lain-lain, saat ini aku lebih merasa malu membicarakannya di depan orang asing seperti Gisele, makanya aku ingin kami cepat-cepat pulang. "Nggak ada yang nyuruh kamu bersandiwara."
Sayangnya, Adam terlalu keras kepala untuk memahami makna yang kusiratkan, "Pura-pura jadi adikmu itu apa namanya kalau bukan sandiwara?"
Pipiku memanas, aku bahkan sempat-sempatnya melirik Gisele dan mencoba menerka apa yang dipikirkannya tentang kami, tapi sepertinya dia terlalu tegang untuk menganggap adegan ini sesuatu yang memalukan. Mungkin dia pikir kami akan saling bunuh, atau menimbulkan huru-hara di kompleks perumahannya yang tenang saat semua bayi dan anak-anak tidur siang.
"Adam ...," kataku lembut, nyaris habis kesabaran. "Aku nggak akan merespons ancaman."
Adam mengernyit, "Ancaman?" tanyanya tak paham (dia bahkan tak paham bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah pemaksaan). "Aku hanya menuntutmu supaya jujur, mengakui perasaanmu, kamu berputar-putar dan menolak semua pria karena kamu mencintaiku—"
"Adam!" aku menjerit mencegahnya mengatakan hal-hal yang lebih memalukan lagi.
"Kamu malu," ia menuduh.
"Nggak!" sangkalku.
"Di depan Gisele yang bukan siapa-siapa kita saja kamu malu, apalagi di depan tante Lydia, atau saudara-saudaramu yang lain. Kamu malu karena kamu lebih mencintai anak ingusan daripada Bastian yang sudah mapan, atau Satrio yang—"
"Satrio yang kamu racuni supaya menjauh dariku, kan?"
"Oh sekarang kamu juga mau menipu semua orang, seolah kamu nggak berterima kasih sama usahaku menjauhkanmu dari lelaki pengecut itu?"
"Dia bukan pengecut!"
"Kamu lebih membelanya?"
"Aku enggak membelanya, demi Tuhan, Dam, TERSERAH!"—oh, aku tak tahan lagi, tubuhku gemetaran, air mataku menetes dan aku kaget sendiri—"Terserah kamu mau pulang atau enggak. Aku mau pulang, kamu sudah dewasa, kan? Ini maumu, kan?"
Adam mengatupkan bibir.
"Kalau ini maumu." Suaraku bergetar.
Bola mata Adam bergerak kasar seperti akan menangis, tapi berhasil ditahannya dengan sekuat tenaga.
"Kamu nggak mau pulang bersamaku? Mau tinggal bersamanya?" aku memalingkan wajah ke Gisele tanpa melihatnya.
Kedua tangan Adam mengepalkan tinju, saat ini pasti sekujur tubuhnya berusaha meredam darahnya yang bergolak karena emosi. Lapisan kaca di matanya semakin tebal, air matanya membendung di pelupuk.
Aku tidak akan kehilangannya. Dia akan pulang bersamaku.
"Sebelas tahun aku merawatnya, Gisele," kataku. "Sejak usianya delapan tahun, saat itu dia manis dan penurut, bukan pembangkang, apalagi tukang ancam. Percayalah ... it's not getting easier each day. Semoga kamu beruntung."
Kaki kananku perlahan mengayun mundur, tubuhku tidak memutar, sengaja tak ingin melepas kontak mata darinya. Aku menanti sesuatu hal terjadi untuk mengetahui kapan aku berbalik dan membiarkannya menyaksikan punggungku menjauh.
Saat air mata pertama Adam menetes jatuh ke lantai tanpa membasahi pipinya, saat itulah aku benar-benar meninggalkan rumah Gisele. Aku menang, dia akan pulang bersamaku. Mungkin aku harus menunggu selama beberapa saat di mobil, tapi dia akan menyusul ke tempatku memarkir mobil. Jika tidak, aku tak tahu harus bagaimana lagi.
Tidak. Aku yakin dia akan menyusul.
Ya Tuhan, biarkan dia berpikir aku sungguh-sungguh sudah tak peduli lagi terhadapnya. Aku akan menjelaskannya nanti, tidak di hadapan Gisele. Aku tidak menyukai wanita itu, apa saja yang dilakukannya dengan wanita itu selama ia tak pulang? Aku cemburu. Ya ampun India, kamu cemburu pada wanita lain yang dekat dengan Adam seperti dia cemburu pada Bastian sampai melibatkan orang asing ke tengah-tengah kami.
Dia muncul.
Gemuruh di dadaku perlahan mereda, Adam berjalan pelan dan lunglai dengan ransel tersampir di pundak kanannya. Untunglah dia berjalan lambat, aku punya beberapa detik untuk membuang napas kencang lewat mulut tanpa diketahuinya. Kunci sentral di sampingku kubuka, Adam masuk dan duduk di sampingku, membuang ransel begitu saja di sela kakinya yang terbuka.
Jalanan kompleks ini sebenarnya cukup besar untuk berbalik arah seandainya aku tidak sangat payah. Beberapa kali memutar-mutar kemudi serta bergantian menginjak gas dan rem, bagian belakang atau depan mobilku tak juga pas sehingga kami berdua maju mundur di tempat yang sama seperti orang tolol. Aku mengumpat lebih karena kesal gara-gara Adam tak berniat membantu. Daripada nekat dan menabrak pagar rumah orang, aku menginjak gas masuk gang melintasi rumah Gisele.
"Apa?" tanyaku, Adam tidak bicara apa-apa, dia hanya memandangiku seolah bertanya apa yang kulakukan.
Ternyata jalan buntu.
"Kenapa kamu diam aja aku kesusahan begini?" aku menjerit, memukul kemudi di depanku sebanyak tiga kali. Kepalaku pusing, badanku lemas, aku bertingkah seperti orang gila.
"Mundurkan saja mobilnya," kata Adam enteng.
"Kenapa nggak kamu suruh terbang aja sekalian, kamu pikir mundur itu gampang?"
Adam menggeleng samar seperti sedang menanggapi nenek tua penggerutu yang nggak bisa apa-apa, "Masukin R," katanya. "Di belakang bebas, lihat ke depan aja seperti menyetir lurus, banting kanan sedikit sebelum sampai mulut gang. Jangan terlalu mepet—"
"Aku nggak bisa."
"Bisa, nanti kuarahin."
"Nggak bisa, aku pasti nabrak."
"Nabrak juga nggak apa-apa, paling kena sedikit. Jalannya lebar, jangan jadi penakut. Ini cuma mobil!" bentak Adam nyaring, aku terperangah. "Kenapa kamu selalu bersikeras mempersoalkan sesuatu yang belum terjadi, mencemaskan hal-hal buruk, dan menghindar dalam hal apapun, India? Kenapa kamu nggak mencoba menghadapinya? Masukin R, mundurkan pelan-pelan, nanti aku arahkan saat sudah waktunya memutar di mulut gang!"
"Kenapa nggak kamu aja yang nyetir?!" aku balas menyalak.
Adam menggertakkan rahang, udara terasa panas menahan amarah kami berdua. Napasnya tersengal, napasku tertahan.
"Please, aku nggak bisa," kataku lemah.
Dia mencibir, "Gimana kalau kamu tadi sendirian?"
Aku menggenggam erat roda kemudi, menelan bulat-bulat harga diriku yang terbanting bukan hanya karena nggak bisa memutar arah, atau mengemudi mundur. Ucapan Adam barusan jelas bukan semata-mata soal memundurkan dan mengeluarkan mobil dari gang, dia sedang mengkritikku. Dia masih marah, sama denganku, aku juga masih marah.
"Kamu cuma menggertak, kan?" tuduhnya, yang sebenarnya memang benar.
Aku menoleh menatapnya.
"Kamu nggak sungguh-sungguh akan melepaskanku, kan?"
"Ini cuma mobil, katamu? Ini lebih daripada itu, ini keegoisanmu, ini salah satu caramu buat memenangkan perlombaan—"
Adam menjengit, "Perlombaan?"
"Kamu tersinggung karena aku memperlakukanmu buruk di hadapan Gisele—"
"Ini nggak ada hubungannya dengan Gisel, bodoh."
"Adam!"
"Apa? Tampar!" serunya lantang sekali sambil menghadap kepadaku. Aku seperti dihempas. "Jangan cuma meneriakiku 'Adam, Adam', kalau kamu nggak suka, tampar, pukul, lampiaskan kekesalanmu, aku muak kamu teriaki 'Adam, Adam' karena kamu nggak mau mukul adikmu sendiri! Aku bukan adikmu, sialan, aku orang lain! Ngapain coba tadi aku masuk ke mobil ini, kalau kamu memang bisa ngelakuin semuanya sendiri, benar-benar membiarkanku pergi sama orang lain, paling enggak buktiin kalau kamu bisa hidup tanpa aku, India! Jangan jadi pembohong, pengecut, yang bisanya cuma menuduh orang lain karena kamu nggak mau ngakuin apa yang sebenarnya kamu rasain!"
"Astaga, Adam ... ini cuma soal mobil katamu...," kataku lebih seperti rintihan, dengan suara mirip orang tercekik.
Adam mendengkus-dengkus. "Ini bukan perkara mobil, jangan menganggapku sepele. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kuinginkan."
"Keluar dari situ," perintahku sambil melepas sabuk pengaman.
Adam tak berani menatapku.
"Keluar dari situ dan pindah ke sini," aku mengulang. "Aku memang tidak bisa hidup tanpamu."

Belum ada part baru dari POV Adam
Kamu udah baca yang mana aja? Baru satu, apa dua2nya udah baca?
1. POV ADAM 1: Bu Lestari
2. POV ADAM 2: Gisele
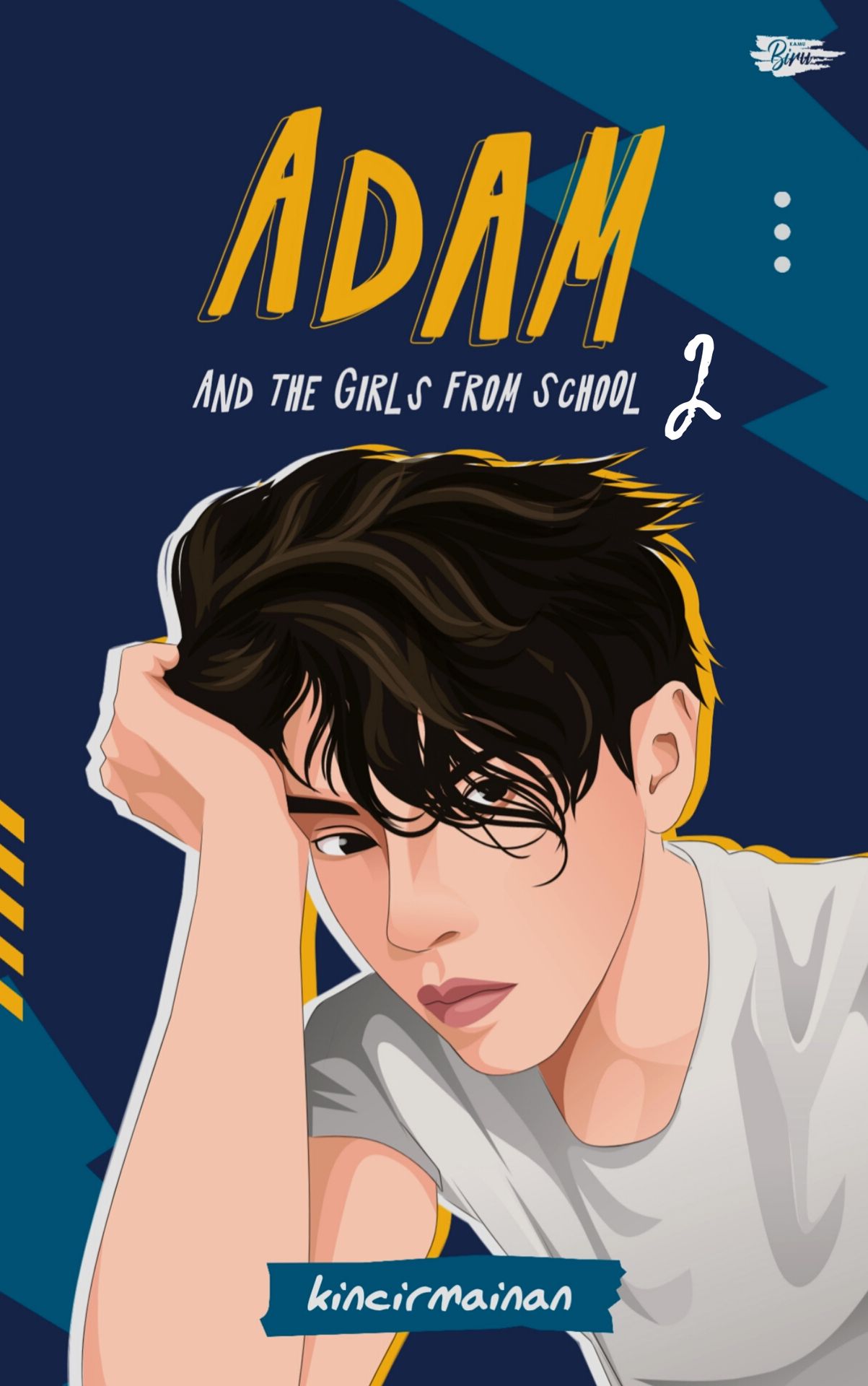
POV ADAM 3 nanti sama Kincirmainan aja, lah. Dia kan kayaknya selalu tertarik oleh pesona tante2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top