Chapter 10. Topeng
Kalau kutahu Adam akan bersikap biasa saja seolah semalam tak terjadi apa-apa, aku nggak perlu tinggal di dalam kamar keesokan harinya sampai waktu berangkat ke acara keluarga tiba. Dengan santainya dia mengetuk pintu kamarku dan bertanya, "Kirain belum bangun, kalau kita nggak jadi pergi aku mau keluar sama Dimas."
Pipiku yang malah memerah dengan sendirinya begitu dia kembali menutup pintu.
Aku langsung mengecek laci meja kecilku, siapa tahu aku hanya salah sangka. Mungkin saja semalam dia hanya meminjam gunting kuku, selotip, atau apa. Tapi, tak ada yang tak berada di tempatnya. Namun akhirnya, aku berhasil mengalihkan perhatian dan bersiap-siap.
Kami berpapasan di dapur saat ia muncul dari pintu belakang yang menghubungkan dengan garasi. Aku bertanya singkat apa ia habis memanasi mesin mobil dan ia menjawab hanya dengan anggukan kepala. Sewaktu ia muncul lagi, aku mengernyit menyadari Adam mengenakan kemeja biru tua.
"Hari ini dresscode-nya merah, Dam," kataku.
"Hm," gumamnya.
"Udah kusiapin di dekat meja setrika," ujarku lagi. "Kemeja merah yang minggu lalu kubeliin. Aku udah minta kamu cobain dulu sebelum dimasukin ke mesin cuci. Udah kamu cobain belum waktu itu?"
Adamnya ngeloyor aja tanpa jawab apa-apa.
"Kekecilan," keluhnya saat kembali ke tempatku menunggu sambil menghabiskan setangkup roti.
Aku tak memberi tanggapan dan segera menghabiskan sarapanku yang kesiangan.
"Bisa nggak sih next time kalau beliin baju bilang-bilang? Ukuran badanku udah lama berubah," protesnya lagi.
Aku menggeleng dalam diam sambil meletakkan piring kotor ke kitchen sink. Sebaliknya, kurasa kemeja merah yang senada dengan dress semi resmiku pagi ini tampak sangat sempurna melekat di tubuhnya. Warna merahnya juga membuat wajahnya tampak lebih bercahaya.
Seolah tahu aku meragukan keluhannya, remaja bongsor itu berbalik menunjukkan punggungnya. Memang sedikit ketat kalau dilihat dari belakang, pikirku dalam hati. Seharusnya dia tidak tumbuh secepat itu, aku semakin merasa was-was tanpa sebab. Semakin ia dewasa, acara bulanan ini semakin menyekik leherku sedemikian rupa. Terlebih jika Adam bersikap tak kooperatif seperti ini.
Tak ingin meributkan baju dan memperkeruh suasana, sambil mengucurkan air dari keran kubilang, "Tahan aja sebentar."
"Aku nggak bisa napas!"
"Kalau kamu nggak bisa napas, dari tadi kamu udah pingsan," kataku pelan. "Bajunya kelihatan bagus dan pas, kok."
"Aku mau pakai kemeja yang tadi aja, ah."
Aku diam, pikiranku belum reda dari kecamuknya sejak semalam. Pikirku, terserah lah kalau dia mau pake apa aja. Niat awalku yang cuma mau menaruh piring di tempat cucian jadi benar-benar mencucinya buat melampiaskan kekesalan.
Untung Adam tak sungguh-sungguh. Melihatku malah mencuci piring setelah dia menyembur nekat, pemuda itu melintas lagi dengan kemeja merah yang sama setelah menghilang sebentar ke dalam. Wajahnya tentu saja ditekuk dan tak enak dipandang, aku ingin mengkritik tatanan rambutnya yang nggak serapi biasa kalau kami pergi ke acara keluarga, tapi tak sampai hati kusampaikan.
Di dalam perjalanan, kami nggak banyak bicara. Dia menyetir, membisu, tapi sesekali menunjukkan emosi kalau ada hambatan di jalan. Puncaknya, saat dia menurunkan kaca jendela mobil untuk memaki seorang pengendara motor yang nyelonong seenaknya. Aku marah dan memintanya menepikan mobil ke bahu jalan.
"Ya udah, kalau kamu nggak mau nemenin ke acara keluarga, sana pulang aja," sengalku tak tertahan. "Biar aku ke sana sendiri!"
"Yang bilang nggak mau tuh siapa?" balasnya tak mau kalah. "Kamu nggak lihat sedikit aja tadi motor itu hampir nabrak spion mobil kita?"
"Ya tapi kamu nggak usah sampai maki-maki orang sembarangan kayak gitu memangnya nggak bisa? Kalau orangnya nggak terima, terus dia ngajak ribut, gimana?" semburku. "Apa kamu malah senang, dengan begitu kita punya alasan buat nggak nyampe tepat waktu, atau nggak muncul sekalian ke rumah Budhe Krisna?"
"Aku cuma nggak suka pakai baju ini!" Adam nyaris memekik.
"Tadi katanya mau pakai baju yang tadi, kenapa nggak jadi?"
"Karena kalau aku pakai baju yang tadi, pasti ujungnya kita ribut-ribut!"
"Kamu tetep pakai baju itu juga akhirnya kita ribut-ribut, apa bedanya?"
Mulutnya bungkam.
"Nggak bisa apa kamu ngehargain aku? Udah kubeliin baju susah-susah juga ... ya kalau sedikit kesempitan tuh aku minta maaf. Siapa sangka kamu tambah besar dalam hitungan hari sejak aku beli baju itu!"
"Aku udah tambah besar dari kemarin-kemarin, kamu aja yang nggak nanya ukuranku berapa sebelum beliin baju baru."
Seketika, emosiku langsung naik ke kepala. "Minggu lalu waktu kubelikan, aku nyuruh kamu nyoba, memangnya nggak kamu cobain?"
"Nggak!" katanya ketus.
"Salah siapa kalau gitu?"
"Memangnya kalau waktu itu kucoba dan nggak pas, baju ini jadi muat?"
"Kalau kamu bilangnya kemarin-kemarin masih bisa ditukar!" Aku menggeram, mencoba menahan amarah. "Ya ampun, Dam, kamu tuh bukan anak kecil lagi. Kenapa sih hal-hal kayak gini selaluuu jadi masalah tiap kali kita mau pergi ke acara keluarga?"
Dia diam seribu bahasa, membuang tatapannya ke luar jendela.
"Udah sana kalau kamu nggak mau nemenin, kamu pulang aja naik taksi ke rumah," suruhku sambil melepaskan sabuk pengaman, berniat berpindah ke kursi kemudi kalau dia sungguh-sungguh nggak mau ikut. "Daripada kamu bersikap buruk, dan jadinya aku lagi, aku lagi yang dimarahin karena dianggap nggak bisa didik kamu dengan baik!"
Adam bergeming.
"Daaam ...," panggilku lelah. "Kamu tuh maunya apa? Kalau baju itu nggak kekecilan, kamu juga akan nyari alasan lain buat melampiaskan kekesalanmu karena kupaksa datang, kan? Kamu masih marah soal obrolan kita semalam?"
Kedua tangan Adam memegang kemudi kuat-kuat. Rahangnya bergerak-gerak tanda ia sedang mencoba meredam emosinya. "Bajuku kekecilan!" geramnya tertahan.
"Benar hanya karena itu?"
Dia mendengkus berat. "Sampai kapan aku harus datang ke acara keluarga kayak begini?"
"Adam—"
"Mereka nggak suka aku ada di sana, memangnya kamu nggak bisa ngelihat itu?" sambarnya duluan. "Jangan bilang itu cuma perasaanku. Jujur, aku benar-benar mau tahu, kenapa kamu bertahan datang ke acara keluarga yang ujung-ujungnya selalu hanya ingin tahu bagaimana kehidupan pribadimu, menanyaimu apa kamu baik-baik aja dan nggak bisa menyembunyikan kekecewaan saat kamu bilang kamu benar-benar baik-baik aja, nanyain kapan kamu nikah, kapan kamu ini, kapan kamu itu, yang sebenarnya mereka cuma mau tahu kapan kamu menyerah mempertahankanku."
Aku baru membuka mulut.
"Aku muak dan lelah." Tapi Adam lagi-lagi mendahului. "Kapan aku boleh berhenti pura-pura aku adalah bagian dari kalian padahal aku tahu kalian nggak pernah menganggapku demikian?"
"Kalian?" sergahku.
"Kecuali kamu." Dia buru-buru meralat. "Apa aku harus benar-benar pergi dari rumahmu dulu supaya punya alasan nggak bisa datang setiap bulannya?"
"Adam, tunggu dulu," tahanku. "Pertama, aku mulai merasa nggak nyaman kamu terus menerus manggil aku dengan kamu, kamu, kamu. Kamu yang bikin aku merasa aku bukan bagian darimu, kamu yang akhir-akhir ini bikin aku ngerasa asing!"
Adam memperlihatkan mimik bingung seolah komplainku terhadap sikapnya mengada-ngada..
"Apa yang kulakukan sampai aku nggak berhak lagi dapat panggilan yang sedikit lebih menghargaiku seperti sebelumnya?"
"Kalau aku manggil kamu kakak, kamu lebih merasa dihargai?"
"Selama ini, aku selalu nganggep kamu adikku, Dam—"
"Tapi aku enggak," kata Adam dingin.
Sekonyong-konyong, aku kehilangan kata-kata. Mataku langsung terasa panas, air menggenang di pelupuk mata, menebal hingga pandanganku kabur. Kudengar kait sabuk pengaman Adam dilepas saat air mataku jatuh dan tanganku meraup wajah untuk menutupinya. Aku mendorongnya menjauh saat ia berusaha menyentuhku.
Karena Adam terus kutepis saat mendekat, akhirnya ia menyerah dan menunggu tangisku reda.
Sakit sekali rasanya. Seumur hidup aku berjuang, kepalaku jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi bisa menghidupinya, aku hampir saja melakukan segala cara. Demi meyakinkan semua orang bahwa aku bisa bertanggung jawab tanpa menghancurkan masa depanku sendiri, aku menuruti anjuran dan nasihat semua orang. Supaya kami tak dipisahkan, supaya aku bisa menyaksikannya tumbuh layak bersamaku yang menerimanya seutuhnya, aku mengesampingkan segalanya. Demi menebus rasa bersalah karena pernah menolak cinta ayahnya untuk mamaku dulu, aku menjadi kakak dan ibunya sekaligus.
Untuk apa semua itu? Untuk mendengarnya mengatakan bahwa dia tak menganggapku kakak?
"Keluar dari sini," kataku.
Embus napas berat Adam terdengar.
"Kamu sudah besar, kan?" tanyaku getir. "Kamu sudah ngerasa besar, ngerasa bisa ngurus hidupmu sendiri, lalu dengan seenaknya kamu ngomong begitu?"
"Aku hanya berusaha jujur," katanya dengan nada membujuk.
"Jujur?" pekikku naik pitam. "Kamu benar-benar nggak punya perasaan ya, Dam!"
"Justru aku punya perasaan, makanya aku ngomong gitu!" Nada bicaranya setinggi nada bicaraku. "Makanya dengerin dulu!"
"Kamu boleh ngerasa semua orang di acara keluarga itu nggak bisa menerimamu, tapi kenapa jadi aku juga yang kena sasaran? Apa yang kurang dariku selama ini, Dam? Apa pernah aku nganggap kamu bukan bagian dari keluargaku sejak orang tua kita nggak ada?"
"Nggak ada yang kurang," jawabnya tenang. "Kamu nggak pernah membuatku merasa bukan bagian dari keluarga, oke? Kamu sempurna, tapi justru karena itu aku ngerasa aku capek, muak, lelah! Aku nggak bisa lagi pura-pura di depan semua orang yang ingin melihatku menunjukkan kemauan untuk menjadi bagian dari mereka, padahal aku nggak ingin!"
Napasku tersengal.
"Dulu memang aku pernah ingin menjadi bagian dari keluargamu," imbuh Adam. "Tapi sekarang enggak lagi."
"Adam... aku tahu kamu putus asa—"
"Aku nggak putus asa, aku memang nggak ingin lagi dianggap bagian dari keluargamu. Aku sudah lama melupakan keinginan itu dan sampai tadi malam aku pikir aku bisa menahan diri untuk nggak memberontak."
"Tadi malam?" Aku menggumam.
"Obrolan kita," terangnya seperti memberi petunjuk.
Tapi, percuma. Yang bisa kuingat malam itu hanya perdebatan kami tentang Bastian. Seharusnya itu nggak ada hubungannya dengan Adam, kan? Apa dia berpikir setelah dewasa dia juga akan dituntut mengikuti saran-saran bude dan tante yang dia sebut 'mendikte' itu?
"Setelah obrolan semalam, aku makin nggak ingin pergi ke acara keluarga, atau bersikap seolah aku memang diterima di sana. Tersenyum, meski diasingkan. Maklum, meski dianggap seperti benalu. Sekuat apapun kamu membuktikan diri, itu nggak pernah cukup buat mereka. Masalahnya bukan di kamu, tapi aku. Tapi memang benar, aku berani bilang begini karena aku sudah merasa cukup dewasa untuk bisa berdiri sendiri."
"Dam, kamu tahu cepat atau lambat, mereka akan nyuruh kita tinggal terpisah, kan?" tanyaku terus terang.
"Aku tahu."
"Seperti yang kita bicarakan, entah kamu kuliah di luar kota, atau kita beli dua rumah ... yang jelas mereka nggak akan mengizinkan dua orang dewasa seperti kita tinggal bersama lebih lama lagi. Kamu tahu, kan?"
"Aku tahu."
Aku menarik napas dalam dan melepasnya lewat mulut. "Tak bisakah kamu menunggu sampai saatnya tiba tanpa bikin kerusuhan? Kuanggap keenggananmu datang ke acara adalah bentuk kerusuhan. Kamu bisa melakukannya tanpa mengambil risiko apa-apa. Yang perlu kamu lakukan adalah memakai topeng yang sama dengan yang biasa kamu pakai bertahun-tahun..."
"Nggak bisa," katanya sambil menggeleng.
"Dam, honestly, aku juga pakai topeng yang sama denganmu. Kalau kamu pikir hanya kamu yang di alienasi, aku juga, Dam!"
"Tapi aku udah nggak punya lagi kelonggaran seperti itu buat menyenangkan orang lain."
"Bahkan buatku?" sambarku, berharap Adam meralat kalimatnya lagi seperti sebelumnya.
Akan tetapi, kali ini ia bungkam. Ia menghela napas sambil meraup wajahnya dengan tangan kanan, kemudian memandang lurus ke depan dan perlahan menoleh sewaktu aku memanggil namanya. Mengingatkannya untuk menjawab pertanyaanku.
Secara mengejutkan, Adam mengangguk. "Bahkan buatmu," dia bilang. "Mungkin ... justru terutama buatmu."
Jantungku berhenti bedetak.
"Aku nggak bisa memakai topeng lagi," imbuhnya kejam. Dia menatap langsung pada inti mataku yang memandang takjub padanya. "Terutama demi kamu, aku nggak mau lagi. Sudah cukup rasanya aku pura-pura jadi adik yang baik karena aku memang bukan adik yang baik ... setidaknya beberapa waktu belakangan ini."
Sebutir air mataku menetes ke pangkuan.
Adam menyambung. "Kalau aku terus melanjutkan sandiwara ini ... aku bisa gila."
"Apa maksudmu?"
Adam terdiam, pandangannya lurus ke depan. Ia menggenggam kemudi erat-erat, seperti sedang meneguhkan pendiriannya sementara tanpa sadar ia sudah membuatku demikian terluka. Aku terus memperhatikannya, beberapa kali kulihat ia berusaha mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Apa sebenarnya yang berkecamuk dalam kepalanya? Apa yang begitu sulit ia ungkapkan padaku? Apa Adam sadar, jika ia masih punya sekutu di dunia ini, orang itu adalah aku?
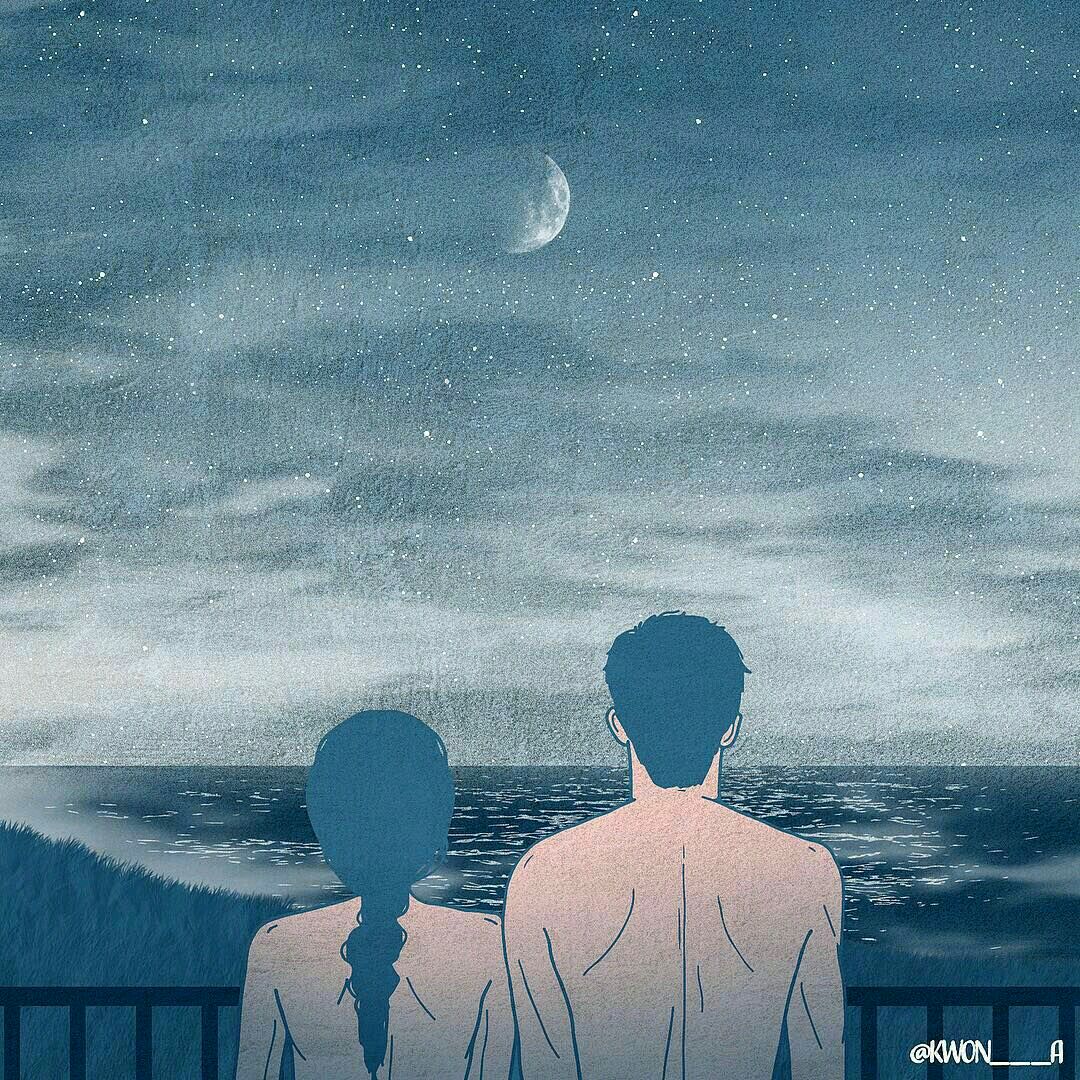
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top