[sebelas] - Tidak Semua Orang Siap Dicintai
Tidak pernah aku merasa suasana secanggung ini di dalam mobil, dalam perjalanan ke tempat favoritku—seharusnya—, bahkan ada Ibu juga di sini. Anehnya, justru menurutku, kehadiran Ibu lah yang membuat suasana semakin aneh. Kalau hanya aku dan Gyan, aku yakin aku mampu menghadapi, sudah berkali-kali.
Tapi, alasan Ibu di dalam mobil ini sejak awal yang membuatku tertekan, kan?
Karena ... ini terasa sungguhan.
Coba-coba pendekatan yang dilakukan Gyan sepertinya justru salah jalan.
Tidak tercium aroma ini pura-pura.
Aku malah merasa mereka seakan siap menjadi ibu mertua-menantu idaman di masa depan.
Atau ... ini cuma dari kacamataku yang memang sangat ketakutan? Apakah Gyan tidak merasakan ini? Apakah Gyan baik-baik saja dan masih yakin kalau semua ini akan berjalan sesuai rencana kami? Kalau sungguh hanya aku yang ketakutan di sini, pertanyaannya adalah ... kenapa? Kenapa aku takut? Benar kata Gyan, aku kenapa takut banget rencana berubah dan berakhir tak ada jalan lain untuk kami selain menikah? Apa karena aku setidaksuka itu menjadikan Gyan pasangan? Karena ... tapi ada rasa kasihan karena aku merasa dia bisa berubah untuk ke arah lebih baik versiku.
Aku sepertinya nggak bisa melakukan apa pun tanpa melibatkan perasaan.
Ah kepalaku pusing, dan aku semakin ciut melihat obrolan dan kedekatan Ibu dan Gyan di dalam mobil ini. Padahal, aku yang duduk di depan, pura-pura sibuk dengan handphone—padahal aku hanya scroll media sosial tidak jelas apa yang kulihat—sementara Ibu duduk di belakang.
"Nini, udahan dong main hapenya."
Aku patuh, meletakkan benda itu ke atas pangkuan, menoleh ke belakang dan memberi Ibu cengiran minta maaf. Kutoleh Gyan, dia hanya tertawa kecil di sebelahku.
"Kalau cowok suka taneman boleh nggak sih, Bu?"
Pertanyaan apa itu, Gyaaaan??? Aku refleks menoleh dan menatapnya terbengong-bengong, saking herannya dengan pertanyaan yang dia lontarkan. Semua manusia boleh suka tanaman! Mau jenis kelaminnya apa, mau gender yang dia pilih apa. Bahkan hewan aja boleh suka tanaman. Kambing juga suka sekali tanaman, masa manusia dilarang-larang.
Ternyata bukan cuma aku yang punya jawaban demikian, Ibu pun sama. Bedanya, Ibu menjawab dengan suara karena memang dia yang diajak ngobrol. Katanya, "Boleh dong! Ayahnya Nini juga dulu suka taneman banget, Ibu malah ketularan dia. Dia rajin banget rawatnya."
"Ohya? Nggak diejekin temen-temen atau saudaranya dulu, Bu? Atau ortunya mungkin? Cowok kok suka urus taneman."
Please, Ibu ....
Semoga dia paham bahwa Gyan agak berbeda, semoga Ibu bisa memperlakukan Gyan jauh lebih lembut dari yang kumampu. Jangan langsung dibantai seperti cara kerja orang-orang di media sosial, ya Bu?
Aku mengelus dada dan curi-curi membuang napas lega saat mendengar jawaban Ibu dengan nada tenang dan adem.
"Yang suka ngejekin hobi orang lain itu biasanya belum bisa happy sama hidupnya, Nak Gyan. Kalau diturutin ya gila kita." Good job, Ibu! Ibu memang terbaik. Orang yang paling paham perasaanku atas kepergian Ayah di saat orang lain sibuk memintaku jangan menangis dan Ibu yang selalu mempersilakanku untuk menangis bersama, walau kadang aku yang menahannya setiap di hadapannya. Maunya pura-pura kuat. "Ayahnya Nini suka sama taneman, bahkan bunga dan nggak bikin dia kehilangan kelaminnya tuh."
"Ibu?" Aku benar-benar terkejut, menoleh dan seketika ikut tertawa saat melihatnya tertawa sendirian di belakang. "Sorry, Yan—" Ucapanku gagal karena melihat Gyan malah terbahak. Akhirnya kami sama-sama tertawa kencang.
"Bener juga ya," lirih Gyan. "Gyan berarti bodoh banget, Bu, kayak takut banget berubah jadi cewek kalau suka hal-hal kayak gitu. Padahal nggak ada yang berubah nih." Dia terkekeh geli. "Kenapa Mama nggak ngenalin Ibu sama Nini dari waktu Gyan kecil, ya? Kan hidup Gyan bisa jadi sebahagia kalian."
Tawaku seketika terhenti.
Bibirku terkatup rapat, dan entah kenapa ucapannya dengan nada bercanda dan diiringi tawa itu tetap berhasil membuat dadaku nyeri. Dia mau bilang kalau dia tidak bahagia, kah? Dia ... iya aku tahu kehidupannya agak—bukan agak, tapi rumit sekali. Tapi mau sesering apa pun kami berbicara tentang itu, anehnya respons spontanku masih tidak bisa sesantai dia. Sekarang aku ketar-ketir menunggu jawaban Ibu yang memang aku belum membahas tentang keseluruhan Gyan ini dengannya. Aku cuma bisa berharap, semoga Ibu—
"Berarti hidup Gyan selama ini proses pembentukannya. Dikasih semua itu buat sudut pandang yang beda, dan sekarang waktunya ketemu Ibu sama Nini. Ibu doain semoga mulai sekarang dan ke depannya, semoga kehadiran Nini di hidup Gyan bisa nambah bahagianya Gyan. Ya, Nak, ya?"
Ini normal nggak kalau malah aku yang berkaca-kaca mendengar doa itu? Kulirik Gyan sedang mengedip-ngedipkan matanya cepat, kemudian dia tertawa kencang, dan menjawab 'aamiin' sebelum menoleh membuang muka ke kanan dan aku melihatnya mengusap mata. Dia ... tidak mungkin menunjukkan emosinya di depanku dan Ibu. Untuk orang seperti Gyan, merasa terharu atau menangis mungkin adalah kesalahan. Jadi, aku mau menunjukkan padanya, bahwa kita ini ... sebagai manusia biasa boleh merasakan segala macam emosi, termasuk meneteskan air mata terharu. Aku menoleh ke belakang dan bilang, "Ih Ibuuuuuu, doanya bikin terharu deh. Malah mau mewek nih Nini."
Ibu tertawa. "Nini, kan, memang dikit-dikit terharu."
Aku menemukan tatapan Gyan dan dia menatapku beberapa detik tanpa bilang apa-apa, kemudian dia tersenyum. "Kamu terharu Ibu doain aku gitu tadi, Rha?"
"Iya lah. Emang lo—kamu enggak?"
Dia tak menjawab, kemudian tersenyum dan mengangguk. "Terharu banget."
Mobil kami terhenti di pinggir jalan, di belakang mobil lain yang sepertinya punya tujuan yang sama dengan kami. Apalagi parkir di sini kalau bukan mau beli—benar, kan. Mereka sedang memasukkan tanaman ke dalam bagasi. Aku baru mau membuka pintu mobil, tetapi terhenti saat melihat Gyan terburu-buru dan berlari mengitari mobil, kemudian membukakan pintu Ibu. Aku dengar Ibu bilang kalau dia bisa sendiri. Saat dia akan membukakan pintuku, aku sudah melakukannya sendiri lebih dulu.
Kami sama-sama tertawa.
Seperti anak itik, aku dan Gyan berjalan di belakang Ibu yang mulai memilah-milah tanamannya. Dulu, selain belanja bulanan, belanja tanaman juga salah satu hal yang paling kusuka bersama keluarga. Yang bete biasanya selalu Abang, karena dia harus berhenti main game dan menurutnya beli tanaman bukan hobinya. Dia tak suka dan dia tak mau. Tapi, Abang tetap kalah dengan Ibu.
Abang selalu kalah dengan Ibu.
Sampai hari ini.
Dan aku salut, karena mungkin, kalau aku jadi dia, aku akan kabur entah ke mana bersama Kak Mel dan menikah tanpa memberitahu keluargaku. Hidup berdua bahagia. Abang tidak, dia bertahan di rumah bersama kami, dengan peraturan dan syarat dari Ibu. Dia terima dan dia tidak terlihat tertekan—atau mungkin berusaha untuk tidak terlihat.
"Lho, kalian berdua jangan ngintil di belakang Ibu dong. Cari sebelah sana, siapa tau nemu yang bagus. Gih, sana."
Aku meringis.
Aku tahu betul tujuan Ibu bukan supaya kami menemukan tanaman yang lebih bagus dari temuannya, tetapi supaya aku dan Gyan berduaan, lebih lama. Terbaca gerak-gerik perjodohan, mau apalagi. Aku menurut, memilah-milah tanaman asal-asalan.
"Rha."
Aku menoleh.
"Tanaman favorit bokap lo apa?" Belum sempat aku menjawab, dia sudah buru-buru menambahkan. "Eh sori sori, kalau lo masih—"
"Santai, dong, Yan .... Gue nggak pa-pa. Ini baru mau mangap, lho, buat jawab."
Dia tertawa pelan.
"Dia suka banget sama ... banyak deh, tapi kayaknya yang jadi fav-nya Aglaonema. Tuh, tuh ituuuu, Gy!" Aku jadi heboh sendiri dan berlari menjemput tanaman ini. Kupeluk erat sambil memamerkan pada Gyan. "Kenalin, tanaman favoritnya cowok favorit gue."
"Bukannya Angkasa?" tanyanya jail.
Aku memutar bola mata. "Diem nggak lo?"
"Kalau enggak, apakah tuh pot akan melayang ke kepala gue?"
"Bisa jadi."
Dia tertawa kencang sampai memegangi perutnya. Padahal, menurutku tidak selucu itu, tapi tak apa, aku hargai selera humornya atas dasar Hak Asasi Manusia. "Pinjem dong, Ni. Mau megang," pintanya. Kemudian kembali melanjutkan setelah aku menyerahkan pot ke tangannya. "Siapa tau bisa ketularan jadi orang favorit lo juga."
"Gyan, please?"
Dia terbahak-bahak, sementara aku mulai ketar-ketir. Aku harus ikutan tertawa atau khawatir dengan semua jokes-nya itu? Aku takut menjadi kenyataan dan semua omongan Emma menjadi fakta, begitupun ketakutan dan kegeeranku.
Tidak lucu.
"Udah nemu belum, Anak-anak?"
Pertanyaan itu membuat kami kembali sadar. Gyan tertawa mendengar panggilan Ibu untuk kami, kalau aku memang sudah terbiasa, aku dan Abang juga dipanggil begitu. "Ini tanaman favorit almarhum Ayah kata Nini, Bu."
"Oh bener." Ibu menatap haru dan mengelus daunnya. "Kita beli ini juga, ya."
Gyan mengangguk. "Mau mana lagi, Bu?"
"Kalian ada lagi yang mau dipilih nggak? Ibu udah dapet beberapa di sana. Tinggal bayar, yuk?"
"Nini udah," jawabku.
"Gyan nggak paham, jadi ikutan Nini udah."
Ibu tertawa, membawa tanaman tadi untuk dibayar.
"Berapa, Mas?" Ini Gyan yang ngomong.
"Lho, Nak Gyan nggak usah. Heiiii, biar Ibu aja."
"Ibu, nggak pa-pa. Masa Ibu yang—"
"Memangnya kenapa kalau Ibu yang bayar? Kan Ibu yang ajak."
"Tapi, kan, Gyan la—"
"Memangnya kalau perempuan nggak punya uang?"
Di saat perdebatan itu terjadi, abang penjualnya bengong menatap Ibu dan Gyan bergantian, kemudian dia menemukan tatapanku. Aku hanya memberinya senyuman penuh arti, seolah bilang selamat menikmati tontonan menyenangkan ini.
Pada akhirnya Gyan tertawa, mengangguk, dan mempersilakan Ibu maju untuk membayar. Dia memilih untuk mengangkat tanamannya dan memindahkannya ke dalam mobil. Giliran tanaman terakhir, kami berjalan berbarengan dan Ibu sempat-sempatnya menggoda, "Masih nggak berubah kan, kelaminnya habis biarin perempuan yang bayar?"
Dengan satu pot di pelukannya, Gyan terbahak.
Aku pun jadi ikutan nimbrung tertawa.
Ibu ... kenapa sih random-nya harus keluar secepat ini dan di hadapan Gyan pula! Bukan di hadapan calon menantu sungguhannya. Aku jadi sedih.
Aku melihat Gyan membukakan pintu untuk Ibu, mendapatkan ucapan terima kasih dan senyuman manis dari Ibu. Lalu Ibu menoleh ke belakang, sibuk membenarkan posisi tanamannya. Saat giliranku, dia sudah telat karena aku membuka pintuku sendiri, dan berhasil duduk dengan cantik.
Gyan masih berdiri di sebelah pintu, menatapku, kemudian menunduk untuk berbisik, "Sori."
"Buat?"
"Telat bukain pintu lagi."
Aku memegang pipinya dan tersenyum lebar. "Lo nggak dibayar buat itu. Nggak ada kewajiban bukain pintu. Gue bukan Ratu kelesss." Aku berusaha ngomong sepelan mungkin di saat Ibu sedang fokus dengan tanamannya.
Dia tak menjawab, malah bengong.
"Gy?"
Lalu dia tertawa. "Lo random banget sih, Ra. Manggil Gy, Yan, macem-macem."
Aku nyengir. "Elo juga sekarang punya panggilan dua, kan? Nini dan Dhara."
"Jangan suruh gue buat berhenti manggil Nini, ya. Gue mulai nyaman."
"Nggak boleh tau. Itu buat keluarga doang."
"Ya, kan, nanti kita keluarga."
Aku menatap wajahnya serius. Gyan terlihat kebingungan, tapi di sini harusnya aku yang kebingungan setelah mendengar kalimatnya barusan. Dia tidak boleh bilang kalau dia tidak sadar mengucapkan kalimat itu karena aku tidak menerima alasan semacam itu. Dia harus—
"Gue salah ngomong, ya?"
"Hm," gumamku mulai tak suka.
"Sori, gue—"
"Gyan."
"Ya?"
"Jujur sama gue," bisikku pelan, memastikan Ibu masih fokus dengan dunianya, kemudian aku kembali berbisik. "Lo mulai puter balik, ya?"
"Maksudnya?"
"Perasaan lo ke gue masih sama kayak tujuan awal atau berubah?"
Matanya sempat membulat sebelum dia ternyata berani menjawab dengan kalimat mengerikan. "I guess ... I'm in love with you, Rha."
Aku tidak salah.
Itu terdengar mengerikan.
---
aduh Gyan, kumahaaa iyeeee? huhu
btw gaessss, aku berusaha update di KK lebih cepet dari di wattpad HAHA. yang punya recehan lebih, bisa baca di sana cuma 2k per part. tapi yang gapunya recehan, gapapa menanti di sini ngoheeeyy? muach bazah.
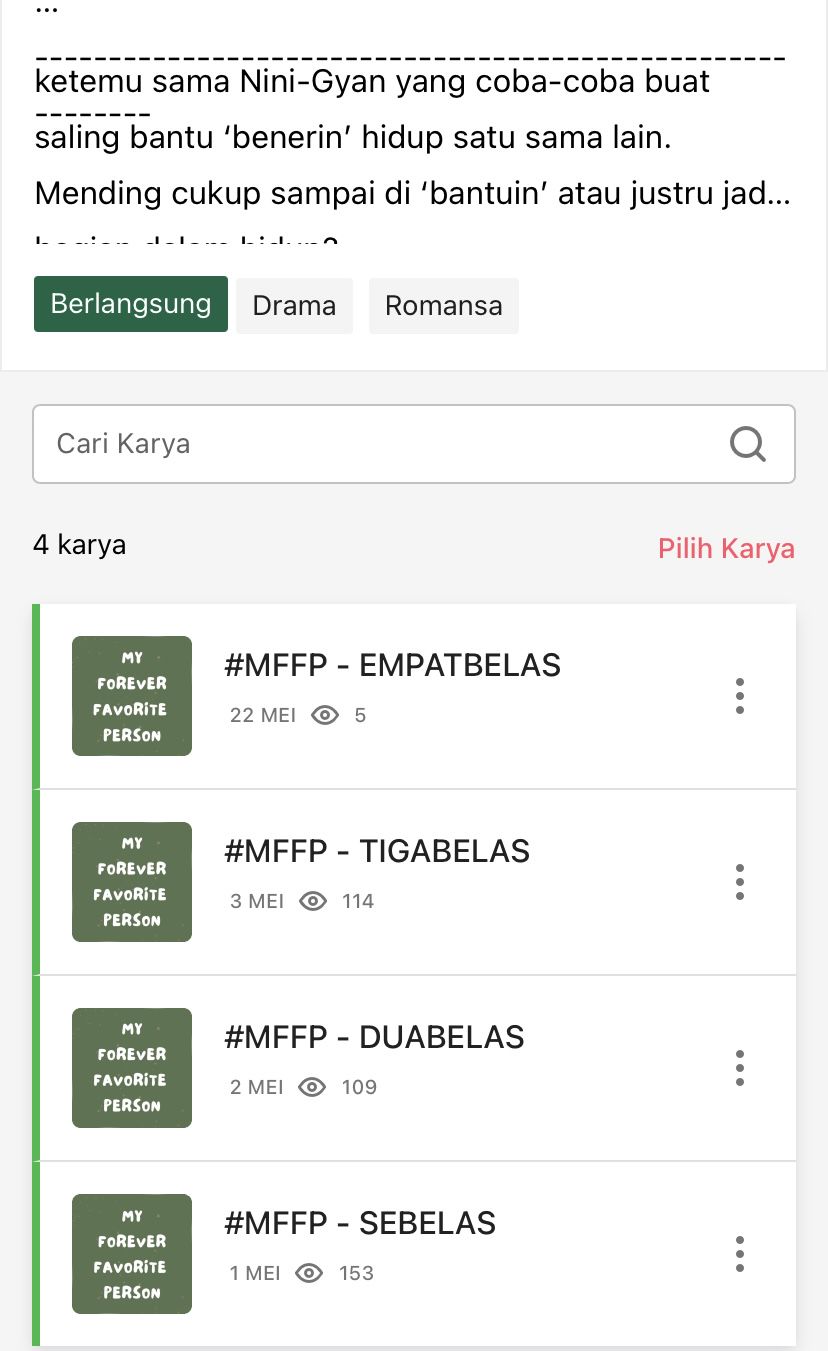
cari akunku: Aku-UMI atau katan atau search judulnyaa🙂💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top