Chapter 29 [Jayden Wilder]
Selamat datang di chapter 29
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do love Jayden and Melody
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Manusia diajari setiap hari untuk memberi dan menerima. Tapi sayangnya manusia selalu lupa untuk belajar menghargai.”
—Tanpa Nama
____________________________________________________

Musim gugur
Bisley, 23 Oktober
Pukul 14.50
“Bajingan! Keparat! Tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diuntung! Berani-beraninya dia mengajak istriku pergi!” Aku berapi-api sampai aksen British-ku jadi aneh.
Nicolo—yang untungnya tidak ikut eksekusi balas dendam sehingga masih bisa bebas berkeliaran—berjingkat dan kembali menunduk. Melalui ekor mata, bidang pandangku bisa melihat polisi yang bertugas menjaga kami sedikit terhenyak, tetapi tidak berkomentar atau melakukan tindakan lain. Ketika refleks menoleh ke samping, aku mendapati beberapa tahanan lain yang mengobrol dengan tamu mereka masing-masing menatapku kesal sambil memaki kasar. Sebagian kecil hanya mengembuskan napas sambil mencebik malas.
Mana aku peduli?
Otakku sekarang bagai disiram air mendidih karena dipenuhi oleh istriku dan Umar Al-Khareem. Seandainya aku sedang tidak menjadi tahanan sementara sampai kejaksaan menggelar persidangan kasusku dan aku dibebaskan, kupastikan mantan tunangan istriku itu lenyap dari muka bumi dengan tanganku sendiri.
Seandainya Dahlia berhasil membujuk salah seorang aparat untuk memberiku waktu menemui Melody, pasti aku sudah akan membawa Melody pulang. Akan kuajak istriku pergi jauh. Kuyakinkan padanya kalau semua akan baik-baik saja. Bahwa semua hanya tipu daya media massa. Dengan bukti aku bersamanya. Sayangnya tidak demikian, bukan?
Terkutuklah si penyidik keparat yang dendam padaku itu, yang terus memperhatikan gerak-gerikku bagai kamera pengawas. Hingga secara tak terduga Umar datang menemui Melody dan mengajak istriku pergi.
Padahal beberapa bulan lalu, aku berbaik hati mewujudkan cita-cita si pecundang itu menjadi dokter bedah dengan menawarinya beasiswa penuh di universitas Harvard. Selain sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah mengobatiku di insiden Hotel Four Season London, sebenarnya itu juga rencanaku untuk menyingkirkannya dari hadapanku dan Melody. Aku muak mengetahui pria itu masih berada di sekitar kami kendatipun ia bekerja di London yang jaraknya lumayan jauh dari Summertown.
Bagiku, Umar laksana kuman yang harus dibasmi agar tidak menimbulkan penyakit. Terutama di rumah tanggaku dan Melody. Well, dengan benci aku mengakui tampangnya memang sangat menjual alias di atas rata-rata. Ditambah dengan profesi mulia bin mentereng seperti itu, aku ragu para wanita tidak kepincut dalam sekejap mata. Mengingat istriku pernah menjalin hubungan dengan pria itu, aku pun menjadi ketar-ketir.
Sekarang, setelah mimpi pria itu sedang berjalan menuju kesuksesan—tentunya bila ia dapat menyelesaikan dengan baik dalam beberapa tahun ke depan, apa yang telah dilakukanya padaku sebagai balasan? Pergi ke rumah sakit menemui istriku dan membawakan bubur kepiting. Lalu mencuci otak Melody dengan membeberkan fakta tentang semua kebusukanku sebelum membujuk istriku agar mau pergi bersamanya?
Apa-apaan? Apa pria itu sungguh cari mati? Apa pria itu benar-benar ingin melawanku?
Ditambah lagi, kini aku mendengar dari mulut Nicolo bahwa Melody menyetujui ajakan Umar pergi jelas membuatku benar-benar gila.
Apakah Melody sudah lupa bahwa aku masih menjadi suaminya meski belum bisa ada di sampingnya? Apakah akibat kejadian mahakacau belakang ini Melody telah melenyapkan rasa cintanya padaku?
“Kenapa kalian membiarkannya masuk dan berduaan di kamar inap istriku? Siapa yang bertugas jaga di sana? Dasar tidak becus!”
“Maafkan kami, Bos. Kami kecolongan. Kami sungguh tidak menduganya karena pria itu mengenakan pakaian dokter. Kami kira—”
“Kami kira?” potongku. “Kalian seharusnya tahu pegawai rumah sakit istriku semua orang Italia kecuali Meggy dan Diana! Apa kalian tak lihat tampang Umar? Pria itu jelas-jelas bukan keturunan Italia!”
Nicolo tidak menjawab, hanya menunduk.
“Lalu ke mana mereka pergi?” tanyaku tak sabaran. Kedua tanganku yang diborgol mengepal erat. Aku bisa melihat urat-uratku menonjol di permukaan kulit gelap punggung tanganku yang kapalan.
“Kami belum tahu, Bos. Belum ada laporan dari Dahlia yang mencari-cari keberadaan mereka lewat CCTV rumah sakit sebelum mencegat merek. Tapi aku lekas-lekas kemari untuk menyampaikannya pada Anda lebih dulu,” bisik Nicolo yang masih tidak ingin mengangkat pandangannya untuk menatapku secara maksimal. Mungkin ia takut kedua mataku mengeluarkan laser yang dapat membuatnya buta.
Aku menoleh ke samping sambil menjambak rambutku lantaran frustrasi. Tidak menyangka. Padahal beberapa menit lalu sebelum kebakaran jenggot karena hal ini, aku baru mendapat kepuasan dari laporan Nicolo mengenai karangan bunga superbesar yang kupesan khusus untuk pemakaman Cavez.
Pemakaman bedebah itu yang digelar secara besar-besaran menarik minat awak media bagai burung kondor yang menemukan bangkai dan tak sabar menyantap makanan tersebut. Banyak dari media yang mengait-ngaitkan karangan bunga tanpa nama—dariku—denganku dan dengan kasusku yang masih hangat.
Kemudian kepuasan itu berubah menjadi kemurungan karena mendengar kabar bahwa klan Davidde belum bisa seratus persen menangani para pemburu berita tersebut. Dan entah kenapa Tito lama sekali tak sampai-sampai kemari. Media-media yang kami suap pun belum mampu menyaingi media arogan di luar sana.
Ditambah kabar Salvatore Luciano yang menolak menjadi pengacaraku di waktu aku tidak punya banyak waktu. Nicolo berkata polisi makin gesit menelusuri rekam jejak kriminalku di Danau Bouldish dan Hotel Four Season London. Aku lantas memintanya mencari pengacara andal lain. Sebab bila tidak ada yang mau menjadi pengacaraku, negara ini akan memberiku pengacara. Namun, bukan itu yang kuinginkan.
Dalam kemurungan itu, aku berandai-andai ada Alfred. Seandainya pria itu masih hidup, pasti aku tidak akan kebingungan dan kebakaran jenggot setiap waktu seperti ini. Alfred pasti memiliki segudang rencana dan nasihat brilian untukku dan untuk klan kami. Seandainya ada Alfred, aku pasti tidak akan berakhir di sini.
Setelah Alfred tidak ada, semuanya jadi tidak terkendali. Tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum terpaksa ditunda lantaran tidak ada satu pun dari kami yang memiliki lisensi hukum resmi atau lulusan sarjana hukum yang menguasai bidang tersebut. Beberapa tugas Alfred yang tidak berkaitan dengan hukum kulimpahkan pada Nicolo, Liam, dan Spencter, termasuk mengatur keuangan bisnis. Pada insiden Danau Bouldish, Liam dan Spencter terpaksa bersembunyi lagi. Tugas-tugas mereka pun harus dilimpahkan ke Nicolo dan caporegime-capoergime lain.
Kematian Alfred dan insiden ini telah menggeser seluruh sistem klan Davidde yang stabil.
“Tapi kita bisa mengambil kabar baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bos. Dahlia menemukan sebuah mangkok kosong dengan sisa makanan. Ada bungkus berlogo restoran dan daftar harganya, ada juga bungkus obat yang terbuka, Bos. Itu berarti istri Anda sudah mau makan, minum obat, dan istirahat. Kalau istri Anda sudah bisa ikut Umar, berarti kondisinya membaik.” Lagi-lagi Nicolo berbisik sambil memandangku takut-takut.
“Jadi, maksudmu, istriku bisa sembuh gara-gara dia?” tanyaku sedikit membentak dan mendelik. “Istriku itu kuat, Nic. Tanpa si keparat itu, istriku akan tetap bisa sembuh! Masih ada Dokter Sofia dan dokter lain yang bisa menanganinya! Jadi, jangan sok memberi komentar seperti itu! Aku muak mendengarnya! Kau mengerti?”
“M-maafkan aku, Bos. Omong-omong, Tito rupanya masih ragu kemari karena mengkhawatirkan kakak Anda.”
“Apa kakakku sudah tahu seperti apa kondisiku?”
“Tito bilang belum, Bos. Dia berusaha menutupi berita ini dari kakak Anda.”
“Kalau begitu katakan pada Tito, tak perlu mengisi posisiku yang kosong. Aku masih mampu menjalankan semuanya dari sini. Tolong beritahu dia juga untuk menjaga kakakku. Tak perlu memikirkan keadaan di sini.”
Karena hanya Jameka-lah satu-satunya saudara yang sedarah denganku. Meski aku teringat Papa pernah mengatakan kalau Jameka akan senantia membelaku, tetapi aku ragu dengan yang satu ini.
Nicolo mengangguk, bertepatan dengan petugas polisi yang mendekati kami untuk memberi informasi bahwa waktu besukku telah usai. Aku terpaksa beranjak. Sebelum benar-benar pergi, aku mengatakan, “Besok, aku ingin kau datang lagi ke sini dengan laporkan lengkap, Nic. Tidak hanya laporan tentang istriku dan si pecundang itu, tapi juga tentang pencarian pengacara, perkembangan kasus ini, lalu kakakku, Tito, Lih, dan basecamp Jakarta.”
Nicolo yang sudah ikut berdiri pun mengangguk. “Baik, Bos. Besok aku akan ke sini lagi dengan laporan lengkap.”
“Coba hubungi Ralph Brachii teman Horizon Devoss. Mungkin saja pengacara itu mau membantuku.”
“Akan kuhubungi dia secepat mungkin.”
“Terima kasih.”
Nicolo menggaruk pelipis menggunakan telunjuk. “Eh, lalu bagaimana dengan Dokter Umar Al-Khareem? Apa ada permintaan khusus?” bisiknya sambil melirik petugas polisi yang berdiri di belakangku.
Berkat pertanyaan Nicolo yang satu ini, emosiku surut berganti dengan kesenangan. Seringai tipis pun terakit di bibirku begitu saja. Aku sedikit menoleh untuk memastikan polisi di belakangku menguping obrolan kami. Kemudian, aku menjawab dengan lantang. “Oh, hanya permainan kecil. Aku akan sangat senang kalau kau bisa mencabut beasiswanya di Harvard.”
Nicolo mengangguk. Aku menelengkan kepala ke petugas polisi tanpa menindah pandangan darinya. Pria itu mengerti kodeku. Dengan cekatan ia menjabat tangan polisi tersebut sembari menyelipkan sekotak rokok.
Aku kembali ke sel tahanan tunggal sementara. Kata mereka, aku berbahaya. Jadi, harus diamankan di sel khusus. Yaitu sebuah ruangan mirip kamar yang dikelilingi dinding beton. Ada jendela kecil yang dibingkai dan berteralis baja di pintunya. Luas sel itu sendiri sekitar dua meter kali dua meter. Berisi kasur tunggal dengan ranjang besi, kabinet bersusun tanpa pintu terbuat dari playwood yang dapat menampung TV layar datar 14 inci. Ada wastafel, toilet dengan shower, dan meja kecil yang di atasnya ada botol air mineral.
Meski ada hiburan berupa TV dan tahanan diizinkan ke ruang gym atau mengakses microwave untuk menghangatkan sandwich yang didapat dari waktu makan, tetapi aku nyaris tidak tergoda dengan semua itu. Aku mondar-mandir dalam selku seperti hewan buas dikandangkan. Menanti hari esok agar cepat-cepat mendapat laporan mengenai hal-hal tadi dari Nicolo.
Ketika jam makan malam, para tahanan dikeluarkan dari sel. Khusus sel tunggal, tahanan bisa mengambil makanan dan kembali ke selnya untuk makan di sana.
Sementara para tahanan keluar dari sel, petugas-petugas polisi biasanya melakukan pemeriksaan sel. Aku teringat rokok pemberian Nicolo yang tergeletak di meja. Namun, terlalu malas mengurusinya. Biarlah petugas-petugas itu menemukannya dan menceramahiku soal aturan larangan merokok yang tertulis dan tertempel di setiap pintu sel tahanan.
Ditahan di sini dapat memperburuk mental. Banyak tahanan di sel kanan, kiri, dan depanku yang meneriaki petugas keamanan. Mereka mengoceh tentang hal-hal jorok dan betapa bosannya mereka di sini. Banyak juga dari mereka yang menggedor-gedor pintu baja sel. Ada yang membanting cermin dan tindakan arogan lain.
Oleh sebab itu petugas-petugas polisi di sini berbaik hati menyediakan guru spiritual dan psikiater untuk mengajak mereka mengobrol—bila mereka dapat diajak mengobrol dan bukannya malah menjadi arogan dengan menyerang petugas.
Bagian paling menarik, dari pengelompokan tahanan berdasarkan kasus masing-masing, ada aturan penjara tidak tertulis yang dibuat para tahanan. Mereka membenci tahanan pelaku pelecehan seksual. Bila ada tahanan dengan kasus itu dan ditahan bukan di sel tahanan khusus, penghuni-penghuni lain yang satu sel dengannya akan menghakimi pelaku pelecehan seksual itu. Penjahat kelamin itu pun dilecehkan ramai-ramai sampai tak kuat mental dan akhirnya banyak yang mencoba bunuh diri dengan menelan sabun.
Beberapa dari penjahat kelamin itu tidak berhasil mati. Maka, setelah menjalani pengobatan di penjara, orang itu dikembalikan lagi ke sel tahanannya. Jika beruntung, petugas akan memindahkannya ke sel khusus.
Aku memang baru di sini. Namun, cukup paham dengan aturan tertulis ataupun yang tidak tertulis itu.
Malam harinya aku tidak bisa tidur karena pikiranku lari-larian. Plus perasaan haru biru lantaran mengingat Melody keguguran. Mungkin jika tidak, aku akan menjadi ayah. Keluarga kecilku akan lengkap.
Oh Tuhan …. Aku sangat merindukan Melody.

Musim gugur
Bisley, 24 Oktober
Pukul 07.30
“Yah, aku lebih suka di sini. Hidup di luar sana begitu keras. Jadi, aku tidak keberatan sama sekali menjadi tumbal. Orang-orang penting itu menawarkan jaminan hidup layak untuk keluargaku. Siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Iya, kan?” cerita salah seorang tahanan di sebelahku duduk. Namanya Curtis. Ia merupakan tahanan dengan dakwaan kasus pembunuhan. Padahal, ia hanya tumbal—seperti yang baru saja ia ceritakan.
Pagi ini aku memutuskan sarapan bersama tahanan lain di meja panjang yang bisa menampung sepuluh tahanan. Hitung-hitung untuk mengurangi tekanan mentalku. Dengan bekal menjadi pendengar yang baik, kurasa tekanan yang kualami sedikit berkurang.
“Kau benar. Hidup di jalanan memang keras. Tapi, lebih enak di sini,“ tanggap tahanan bernama Brice yang duduk di seberangku.
Bagiku sama saja. Jalanan dan penjara sama-sama keras. Aku bisa menyimpulkan seperti itu sebab sudah merasakan keduanya.
Setelah makan dan kembali ke sel tahananku, tidak lama kemudian petugas memberitahuku kalau ada tamu untukku. Itu pasti Nicolo, pikirku senang. Namun, betapa terkejutnya ketika aku melihat orang yang ingin menemuiku itu bukan Nicolo. Melainkan Melody.
Jantungku mulai memukuli dadaku begitu kencang. Perasaanku pun kian memburuk. Aku mendadak berhenti dan merasa ketakutan. Berbagai pikiran negatif kontan berjejalan masuk ke otakku sampai rasanya aku mual.
Ketika pandanganku turun ke borgol di kedua tanganku, perasaanku hancur. Ada seorang tahanan yang melintasiku dan bersiul saat melihat Melody. Namun, aku seperti tidak bisa melakukan apa pun.
Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan padanya soal ini? Kenapa otakku buntu sekali? Padahal kemarin aku bisa berpikir untuk menjelaskan bahwa ini hanya tipu daya media massa, dengan syarat bersamanya di luar penjara. Namun, kenyataannya tidak demikian. Jadi, aku harus bagaimana menghadapinya?
“Hai,” sapaku dengan suara serak karena menahan gumpalan pahit dalam tenggorokanku. Aku menyemangati diri bahwa semua akan baik-baik saja. Melody akan mengerti keadaanku bila aku menjelaskan alasannya. Namun, aku kesusahan menyusun kata-kata lagi.
Yang kulakukan sekarang adalah mengamati istriku. Ia mengenakan sweter marun tebal yang lengannya sampai menutupi seluruh tangannya. Jins hitam yang pas melekat di kedua kakinya. Ia mengenakan bot. Tas selempang melingkar di sebelah bahunya. Lehernya dilingkari syal yang terlihat hangat dan rambutnya digerai anggun. Riasannya agak tebal hari ini. Biasanya, aku akan protes. Kali ini, aku tidak bisa melakukannya.
Singkat kata, penampilan Melody jauh lebih manusiawi, tidak seperti orang yang baru saja sakit. Setidaknya itu pertanda bagus, bukan? Maksudku, istriku baik-baik saja. Namun, kenapa aku masih tidak rela Umar-lah yang berperan dalam kesembuhan Melody?
Aku maju selangkah lebih dekat dengannya, berusaha berlagak baik-baik saja agar dapat memeluknya. Namun, Melody menjauh.
“Kenapa kamu pikir aku bakal bales pelukanmu?”
Pertanyaan itu menghantam harapanku.
“Why not?” Sungguh, aku ingin memukul mulutku karena berkata impulsif. Tidak disaring dulu oleh otak; apakah dampak yang akan ditimbulkannya.
“Setelah apa yang kamu lakuin ke aku? Kenapa kamu masih bisa mikir aku bakal meluk kamu?”
Kali ini aku benar-benar bingung. “Aku ngelakuin apa ke kamu?”
“Love booming.”
“Love boombing?” Kurasa aku benar-benar tolol karena hanya mengulang-ulang jawaban Melody. “Aku cinta kamu, itu bukan bohong. Kok, bisa aku love boombing?”
“Terus kenapa kami nipu aku habis-habisan.?
“Aku? Nipu kamu?” Lagi-lagi aku terkejut dengan apa kata Melody. “Aku nggak nipu kamu.”
“Nyembunyiin semua fakta ini. Apa namanya kalau bukan nipu aku?”
“Ini nggak kayak yang kamu pikir.”
“Nggak kayak yang aku pikir?” Gantian Melody yang mengulangnya dengan nada sedikit lebih tinggi. “Emang kamu tahu aku lagi mikir apa? Kamu nggak tahu apa-apa soal pikiranku.”
Awal yang tidak baik. Seharusnya aku sudah menduga itu, bukan? Seharusnya aku tak perlu coba-coba memeluknya. Seharusnya aku menggeret kursi untuknya dan mempersilakannya duduk lebih dulu. Lalu kamu akan mengobrol dari hati ke hati. Obrolan dalam. Saling mengerti. Saling menguatkan. Namun, aku terlalu gugup, takut, dan naif. Sehingga pikiranku tak sejalan dengan perilakuku.
Mungkin karena merasa aku tidak menanggapi, Melody kembali berkata, “Udah cukup basa-basinya.”
Ketakutan makin menyergapku, sehingga aku hanya bisa diam. Menunggunya bicara.
“Can I ask you some questions?”
“Jangan khawatir. Ini cuma sementara. Kamu tenang aja,” jawabku tak sesuai pertanyaannya. Karena berpikir ia pasti akan menanyakan itu. Jadi, aku potong lintasan.
“Aku nggak tanya alasan gimana kamu bisa ada di sini sekarang. Jadi, nggak usah intervensi.”
Kenapa Melody tidak butuh penjelasan bagaimana aku bisa berada di sini? Meski tentu saja, tolol namanya bila aku agak marah, tetapi bukankah sudah jelas alasanku berada di sini? Aku hanya tak ingin Melody melihatku seperti ini. Aku hanya ingin Melody bertanya padaku apa yang terjadi sebenarnya, dengan versiku. Lalu ia akan membantuku melewati ini. Namun aku tahu itu benar-benar naif.
“Aku inget waktu kita di basecamp Jakarta, aku pernah denger obrolamu sama Kak Jame. Katanya kamu yang bikin alibi kecelakaannya Kak Jordan. Padahal kamu, Tito, dan Lih yang bikin Kak Jordan babak belur. Apa itu benar?”
“Kamu denger obrolanku sama Jameka?” Lagi dan lagi, aku sama sekali tidak pernah menduga kalau Melody akan mendengar obrolanku dengan Jameka dan menanyakan hal itu yang sudah terjadi bertahun-tahun silam.
“Jawab aja! Bener atau enggak?”
Aku harus menjawab apa? Mampukah aku berpikir lebih baik? Lebih bijak? Tak salah menjawab sehingga tidak menimbulkan kebencian lebih?
Tak tahu harus bagaimana lagi, aku pasrah dan mengangguk.
“Aku juga denger suara tembakan di ruangan Gamelita di Heratl setelah punggungmu ketembak waktu itu. Waktu kamu meluk aku. Seolah-olah kamu halangin pandanganku dari itu. Aku emang nggak pernah nanya soal itu. Tapi karena kamu—” Melody menghentikan kalimatnya untuk melihat tanganku yang diborgol lalu menatapku lagi. “Apa bener kamu yang nembak Gamelita dan Kak Jordan?“
Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain memohon, “Baby ....”
“Apa itu bener?” tuntut Melody dengan suara agak keras. “Jawab aja! Apa itu bener?”
Kepalaku menggeleng lemah dengan sendirinya. “Nggak sepenuhnya bener.”
Melody mengangguk. “Pantes aja waktu itu aku lihat ada orang-orang pakai baju kayak astronot, APD lengkap. Mendiang Alfred di situ lagi nyuruh mereka bersihin darah yang nyiprat di dinding, di lantai, dan di perabotan. Aku paham sekarang. Mestinya aku juga nggak kaget kamu nyembunyiin pistol di kabinet dapur. Dan sekarang ini.”
Jujur saja, emosiku terasa diaduk-aduk. “I’m sorry,” bisikku lemah.
“Don’t say sorry. Emang kayak gitu, kan, kamu? Pantes aja, tiap kali aku tanya soal pekerjaanmu, kamu selalu ngelak dengan cuma jawab bisnis tongkronganlah, urusan cowoklah! That’s fucking bullshit! Kamu bos mafia! Kamu pemeras kayak tiran!” makinya sambil menggeleng dan wajah kacau. Benar-benar menghancurkan hatiku.
“Nggak kayak gitu, Baby.”
“Nggak kayak gitu gimana? Kamu manipulatif! Kamu nekan orang-orang di sekelilingku buat ngawasin aku! Biar aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya! I’m your fucking wife! But, I don’t fucking know you! Dan aku juga ngerti sekarang, kenapa sampai ada orang-orang yang ngobrak-abrik rumah kita! Sampai nodongin pistol ke pelipisku!”
“Baby ....”
“It makes sense kenapa kamu ngelarang aku telepon polisi waktu itu. Karena kamu mau bikin perhitungan sama mereka. Iya, kan?”
“Baby ....”
Aku merasa duniaku runtuh saat ia berkata, “Tapi aku sekarang tahu siapa kamu, juga apa yang sebenarnya udah kamu lakuin. Jadi, aku mau pulang ke Jakarta.”
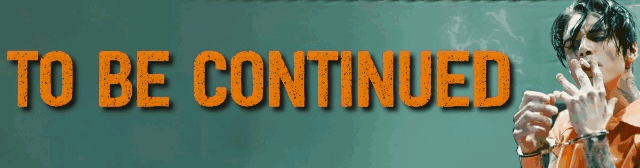
____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote, komen, atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto suami zeye

Bonus foto Maggy Force

Jangan lupa follow sosmed saya lainnya ygy

Well, you next chapter teman-temin
With Love
©® Chacha Nobili
👻👻👻
Minggu, 28 Agustus 2022
Remake and repost: Jumat, 29 September 2023
Repost: Selasa, 22 Oktober 2024
Btw, jangan lupa nabung ya timin-timin
Stay tune pantengin Instagram teorikata.publishing dan chachaprima03 ya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top